Novel Jejak Terakhir
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Novel Jejak Terakhir as PDF for free.
More details
- Words: 19,961
- Pages: 160
Loading documents preview...
viii
Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Penulis Zulfikkar PN
i
Persembahan Telah 3 tahun, cukup lama. Ku tulis berlembar-lembar cerita. Bukan kisah cinta remaja nan syahdu. Melainkan kisah anak tak beribu. Ialah anak penuh haru biru. Sumber inspirasi sanubariku. Ia yang datang dari kampung seberang. Kampung diantara lautan yang garang. Semangat pantang menyerah berkobar. Dalam tubuh kecil terdapat jiwa yang tegar. Apalah dia dibanding mereka si kaya raya. Namun lihat, ia lebih hebat dimata Tuhannya. Persembahan inilah jadi awal pembuka. Dimana dan darimana kisah ini bermula. Kisah suka duka si anak nelayan. Hatinya tulus lewati halang rintangan. Tak berlebihan jika dijadikan suatu teladan. Walau penuh cobaan percayalah pada Tuhan. Karena Dia-lah yang akan berikan jalan. Sebuah hikmah beserta tuntunan. Ku persembahkan kisah ini. Pada mereka yang masih miliki hati. Untuk melihat ke beberapa sisi. Bahwasanya hidup perlu disyukuri.
Cilacap, 11 Agustus 2013 Zulfikkar PN
ii
Daftar Isi Halaman Judul Persembahan Daftar Isi Kesan & Pesan Monolog Garis Hidup Nyonya Surati Kuburan Raibnya Si Doreng Ampun, Ayah Paman Salim & Saudara Baru Teman Masalah Baru Jejak Terakhir
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
i ii iii iv 1 8 21 37 49 59 73 90 107 122
iii
Kesan & Pesan
Tak ada yang lebih berarti daripada kesan dan pesan darimu kawan. Bantulah aku untuk menulis lebih baik lagi. Pastinya apa yang kau sampaikan melalui salah satu kolom dibawah ini akan menjadi inspirasi, motivasi sekaligus kenangan yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaan dan perhatian yang kau berikan melalui kolom kesan dan pesan yang sengaja ku lampirkan dalam buku ini.
Zulfikkar PN
iv
MONOLOG
Petang ini aku hanya duduk di bangku bambu yang menua di depan rumahku. Ku lihat lalu lalang orang-orang seakan tak memperdulikan keberadaanku. Mungkin aku tak ubahnya seonggok batu. Wajahku kuyu, ku sandarkan punggung pada dinding kayu rumahku. Pandanganku mulai menuju ke arah pantai, arah dimana ayah biasa muncul setelah pulang melaut. Namun, hanya kegelapan yang ku temukan. Terkejut aku dibuatnya, saat seekor nyamuk menggigit siku kiriku. Tak dapat ku lihat bentuknya, hanya suaranya saja yang mendengung kekenyangan. “Nguingg nguiinggg”. Ku garuk bentol-bentol di siku kiriku seraya beranjak mengambil sarung sebagai perlindungan seadanya. Ku pikir nyamuk-nyamuk itu tak pernah kenyang, masih saja berusaha menggigit kulitku melalu celah sarung yang mereka temukan.
1 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Jengkel dibuatnya, ku ambil sandal japit kemudian ku pukulkan ke udara, berharap membuat nyamuk-nyamuk itu pontang panting ketakutan. Namun sia-sia, mereka pandai menghindar. Aku heran apa enaknya darahku ini, padahal hanya makanan ala kadarnya yang masuk ke dalam tubuhku. Tak lama, suara adzan dari surau dekat rumah terdengar. Inilah hal yang paling aku suka untuk mengisi waktuku, sembahyang. Bergegas aku menuju surau, tak lupa rantai kecil pada pintu ku kaitkan agar pintu tetap tertutup rapat. Selesai sholat aku berdoa agar hasil melaut ayah melimpah dan ia kembali dengan selamat, tak lupa ku doakan ibu agar ia tetap damai di akhirat sana. Selesai sholat Isya, ku lihat beberapa anak bermain petak umpat. Aku tak ikut, malas, tak tertarik. Aku lebih memilih pulang dan merebahkan tubuhku di atas dipan dalam kamarku. Lampu bohlam yang menerangi kamarku mulai meredup, tanda usianya tak lama lagi. Aku menghela nafas, merasa bosan, aku berpikir mencari sesuatu untuk ku kerjakan.
2 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku melihat ke arah rak kecil di sisi kananku. Ku tarik sebuah kertas kosong yang mencuat diantara tumpukan buku-buku usang semasa aku sekolah dulu. Sesaat kemudian mulai ku bangun rasa rinduku pada ibu melalui sebuah puisi. Sejak umur 10 tahun aku memang sudah suka menulis. Belum jelas menulis apa, yang aku tulis hanya khayalan-khayalanku waktu itu. Mulai dari cita-citaku menjadi seorang guru sampai keinginanku memberangkatkan haji ayah dan ibu. Beberapa gambar yang mewakili cita-citaku juga sering ku buat. Aku rasa cita-cita itu kini hanya isapan jempol belaka, ah sudahlah, aku sedang rindu pada ibu, lebih baik ku tulis puisi untuknya. Sebelum ku tulis puisi untuk ibu, ku tulis dulu namaku di sudut kanan atas kertas itu. Bono Sugiarto, itulah nama yang ayah berikan padaku. Kata ayah nama itu diambil dari kalimat Rebo Dino Sugih Arto. Menurut ayah, waktu aku lahir tepatnya hari Rabu, hasil melaut ayah sedang bagus-bagusnya. Karena itu ayah menamaiku seperti itu. Ayah berharap aku jadi orang
3 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berhasil suatu saat nanti. Sayangnya, nama itu dinodai oleh beberapa tetangga dan teman sebayaku. Mereka lebih sering memanggilku Boncel. Mungkin lantaran tubuhku kurus dan pendek untuk ukuran anak usia 12 tahun. Tak apa, anggap saja mereka sedang khilaf. Seketika aku mulai khusyu menulis puisi untuk ibu. Ku mulai dengan menulis judulnya dan kemudian bait-baitnya. Sesekali ku gosok-gosokkan ujung pensil ke pelipisku, tanda aku sedang berpikir keras. Tiba-tiba suara hujan terdengar deras, membawa suasana syahdu menenangkanku. Udara dingin mulai menembus diantara sela-sela dinding kayu kamarku. Ku lihat bulir-bulir air saling berdesakkan membasahi jendela kamarku. Ku lanjutkan menulis puisiku untuk ibu. Ku coba menggambar wajah ibu dalam benakku agar dapat ku curahkan melalui selembar puisi. Bagaimana senyum manisnya, bagaimana sentuhan lembutnya, bagaimana suara merdunya. Imajinasiku mulai meloncat-loncat dari ingatan yang satu ke ingatan yang
4 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
lain. Ku sambung satu demi satu kata yang mungkin saja membuat ibu tersenyum senang. Ku lihat jam dinding yang menggantung, jarum pendekknya berada pada angka 9 dan jarum panjangnya berada pada angka 12. Pantas saja mataku mulai berat ku buka. Sesekali kepalaku terguncang karena rasa kantuk yang mulai mengganggu. Namun, aku masih bersemangat menuliskan beberapa bait puisi untuk ibu. Hanya ini yang dapat ku lakukan untuk menyambung rasa rinduku pada ibu. Segala daya upaya ku kerahkan untuk melawan rasa kantukku. Terjadi perkelahian yang sangat hebat karena aku masih ingin menulis puisi disaat mata mulai mengantuk. Rasanya kantuk ini mulai menghapus sedikit demi sedikit ingatanku. Kesal, ku buka lebar-lebar mata ini dan menampar setengah keras pipi kananku. Aku katakan pada diriku sendiri, “Ayo, jangan menyerah. Harus selesai.” Ku tarik nafas dalam-dalam dan bersiap menyelesaikan puisi yang ku buat. Aku sangat gigih menulis puisi itu, aku ingin
5 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
mempersembahkan itu untuk ibu. Kegigihanku tak sia-sia. Sepuluh menit kemudian, akhirnya puisi untuk ibu dapat ku selesaikan. Ku baca lagi bait-baitnya, meneliti jikalau ada kata yang kurang pantas dalam puisi itu. Aku rasa sudah bagus. Dengan senyum puas, ku lipat kertas puisi itu dan ku selipkan di bawah bantal tidurku. Aku berharap ibu akan menemuiku dalam mimpi dan membaca puisi yang telah ku buat untuknya. Aku mulai merebahkan tubuhku yang sudah tak tahan lagi karena kantuk. Tak butuh waktu lama, aku tertidur pulas. Ku lepaskan lelah dan kantukku bersama selembar puisi yang ku buat. Sebuah puisi rindu untukmu ibu.
6 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bono Sugiarto Rindu Untuk Ibu
Di malam penuh kesendirian. Anakmu rindu pada belaian. Terlintas sosok cantikmu ibu. Yang kini berada jauh dariku.
Hujan mengguyur basah rumah kita. Bawa ketenangan dari suara derasnya. Antarkan anakmu terlelap tidur, bu. Dengan nyanyian suara merdumu.
Anakmu rindu akan pelukmu. Ibu pasti mengetahui hal itu. Temui anakmu dalam mimpinya. Karena anakmu ingin bertegur sapa.
7 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
GARIS HIDUP
Kriiiinngg kriinggg kriiinggg…. Bunyi sepeda bersahutan menyambut mentari pagi. Aku meloncat dari tempat tidurku dan berlari menuju depan rumahku. Ku lihat anak-anak seusiaku sedang bergembira berangkat ke sekolah. “Senangnya mereka.” kataku dalam hati. Ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah musim libur sekolah usai. Tidak semua anak di kampung ini bisa bersekolah, hanya anak-anak yang beruntung bisa bersekolah. Dulu aku seperti mereka bisa pergi ke sekolah, sekarang tidak lagi. Penghasilan ayahku hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ibu masih ada, ia dan ayah berbagi tanggung jawab. Ayah yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, ibu yang bekerja serabutan untuk membiayai sekolahku.
8 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Sebenarnya aku ingin sekali bekerja membantu ayah, tapi ayah melarangnya karena aku belum cukup umur menurut ayah. Tiba-tiba aku rindu datang ke sekolah. Ku putuskan untuk pergi menuju bekas sekolahku, walau hanya sekedar melihat bagaimana bentuk gedungnya sekarang. Sebenarnya jarak rumah ke sekolah cukup jauh, namun aku tak perduli. Dalam perjalanan aku tak mengerti mengapa orang-orang yang ku temui terlihat aneh, seakan-akan mereka ingin menertawaiku. Sejurus kemudian aku mengerti. Ternyata saking rindunya, aku tak sadar pergi dengan muka yang dekil, tanpa alas kaki dan dengan baju yang berwarna coklat pudar yang seakan membusuk. Tapi biarlah, mereka berhak menilai tampilanku. Aku hentikan langkahku tak jauh dari gerbang sekolah. Aku berdiri di sana memperhatikan anak-anak yang lain berlarian masuk ke dalam sekolah. Anak-anak itu datang dengan beragam kendaraan. Kebanyakan dari mereka bahkan datang diantar oleh ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sedang yang lain datang
9 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
bergerombol tanpa diantar keluarga atau sanak familinya, mereka berjalan kaki. Tentu mereka lebih beruntung daripada aku yang kini hanya bisa berdiri di tepi jalan ini. Aku belum beranjak dari tempatku. Rasanya kakiku seperti terpaku. Sampai suasana di depan sekolah menjadi sunyi aku baru bergerak mendekat, ingin sekali menuju ke dalam tapi aku malu dengan keadaanku yang antah berantah seperti ini. “Bono, apa kabar?” teriak Pak Rimbo penjaga sekolah dari kejauhan seraya melambaikan tangannya. “Sini!” tambahnya, aku mendekatinya. “Baik-baik saja pak. Bagaimana dengan bapak?” tanyaku. “Ya, Alhamdulillah. Sehat segar bugar. Tuh lihat kumis bapak semakin lebat!” kata Pak Rimbo kemudian tertawa hingga kumisnya menutupi lubang hidung. “Jauh-jauh kesini, sedang apa di sini?” tambahnya. “Tidak pak. Hanya rindu dengan sekolah ini.” kataku.
10 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Rindu bapak juga tidak?” goda Pak Rimbo seraya menyolek ketiakku. “Ah, buat apa merindukan Pak Rimbo. Dulu Pak Rimbo kan sering menghukum saya.” kataku mengingat saat sekolah dulu. “Hahaha..siapa suruh datang terlambat?” kata Pak Rimbo. “Pak Rimbo seperti tidak tahu saja, jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh. Bayangkan pak, saya harus berangkat pukul 6 pagi, sementara untuk mandi saja saya butuh waktu 30 menit menimba air di sumur Pak. Itu juga kalau ada air bersih pak.” “Ya ya, tapi tugas bapak kan memang menghukum siswa yang terlambat. Jangan-jangan kamu kesini karena rindu bapak hukum ya?” kata Pak Rimbo tersenyum seraya mengambil cangkir kopinya. Aku tersenyum kecut. “Tidak pak, terima kasih!” “Oh ya Bono, kenapa dulu kamu keluar sekolah? Dengardengar masalah biaya?” tanya Pak Rimbo setelah meneguk kopi hangatnya. “Iya pak, tak ada uang buat sekolah.” kataku sedikit malu.
11 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kamu kan cukup pintar, terakhir dapat peringkat berapa?” tanya Pak Rimbo seraya melinting ujung kumisnya. “Dapat peringkat 7 pak.” jawabku. “Nah itu dia, sayang kan?” kata Pak Rimbo keras seraya menepuk punggungku, hampir saja mataku copot dibuatnya. Aku menelan ludah sejenak, “Iya pak, padahal Bono punya cita-cita jadi guru. Tapi kepergian ibu seakan-akan membuyarkan itu pak. Terkadang Bono pikir Tuhan tak adil.” kataku. “Hushh..jangan berkata seperti itu! Dosa! Tidak adil bagaimana maksudmu?” tanya Pak Rimbo. “Teman-teman Bono bisa bersekolah walau prestasi mereka tak sebagus Bono, bahkan suka membolos. Sementara Bono yang sangat semangat bersekolah, sekarang hanya bisa melihat mereka bersekolah. Ini karena Tuhan mengambil ibu, pak!” kataku mulai larut dalam kesedihan.
12 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, selalu ada hikmah dari cobaan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi bersabarlah, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya.” nasehat Pak Rimbo. “Ayah juga bilang seperti itu, tapi apa pak? Bono tak bisa melakukan apapun, ingin membantu ayah melaut saja tidak boleh!” kataku ketus. “Bono, pasti ayahmu punya alasan untuk melarangmu melaut. Mungkin karena usiamu belum pantas untuk melaut, atau bisa jadi ayahmu masih trauma dengan kejadian ibumu yang tenggelam saat ikut ayahmu melaut.” kata Pak Rimbo. “Pak Rimbo benar, Bono jadi rindu ibu.” kataku. Pak Rimbo sedikit terbata-bata, “Aahh..maaf Bono, bapak turut berduka cita. Ya sudahlah, jangan dibahas lagi. Kamu rindu guru-gurumu tidak?” Pak Rimbo mengalihkan pembicaraan. “Iya pak. Pasti mereka sedang sibuk mengajar ya pak?” kataku sambil mengernyitkan dahi mencoba melihat kegiatan di dalam kelas.
13 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Coba tengok saja sana, tapi jangan mengganggu ya?” kata Pak Rimbo mempersilahkan. “Siap pak jendral!” kataku seraya mengambil sikap hormat pada Pak Rimbo. Pak Rimbo hanya tertawa terkekeh. Aku pergi meninggalkan Pak Rimbo dan singgah di teras ruang kelas V, kelas terakhir aku bersekolah. Di sana aku mengintip proses belajar dari jendela dan sesekali ikut menghitung di atas tanah soal matematika yang diberikan oleh guru yang mengajar. Kalau saja aku masih sekolah mungkin saat ini aku sudah jadi siswa SMP. Dulu aku sangat suka sekali pelajaran matematika. Pelajaran yang sekarang sedang diajarkan. Ku rasa aku lebih cepat menghitung daripada murid di dalam. Tentu saja, aku hanya mengulang dan coba mengingat-ingat apa yang pernah aku pelajari dulu. Saat sedang asyik menghitung, aku dikagetkan oleh suara lembut dari arah belakang. “Bono?”
14 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku menoleh dan ku lihat Bu Astuti berdiri melihatku. Ia adalah guru kelas V, guru yang sama saat aku masih bersekolah. Dulu ia sangat baik padaku, bisa dikatakan ia adalah ibuku di sekolah. Ia datang dari luar desa, kemudian mengabdi di desaku. “Ehh Bu Astuti, maaf bu jadi mengganggu.” kataku tersipu malu. “Ahh tidak. Sudah lama ibu tidak melihatmu. Tapi badanmu sepertinya tidak jauh beda dengan terakhir kali ibu lihat.” kata Bu Astuti, pandangannya menggerayangi tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku hanya menunduk malu. Kemudian Bu Astuti mendekat dan melihat coretanku di atas tanah. Dia tersenyum dan berkata, “Apa cita-citamu nak?” “Guru seperti Bu Astuti. Tapi rasanya itu tak mungkin bu.” jawabku putus asa. “Kenapa tak mungkin?” tanya Bu Astuti.
15 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kata ayah, harus kuliah dulu kalau mau jadi guru seperti Bu Astuti. Sekolah saja Bono tidak selesai, apalagi kuliah?” kataku menahan diri tidak bersedih. “Andai saja ibu bisa membantumu nak. Tapi tunggu sebentar!” kata Bu Astuti seperti mengingat sesuatu kemudian ia masuk ke dalam kelas. “Ini untukmu.” kata Bu Astuti kembali seraya menyodorkan buku matematika kepadaku. Aku sangat senang. Ku terima dan ku peluk buku itu. “Terima kasih bu.” kataku girang. “Iya belajarlah dari buku itu.” kata Bu Astuti lembut. “Baik bu, tapi bagaimana dengan Bu Astuti?” kataku sungkan. “Oh ya, tak usah khawatir. Ibu punya dua buah buku yang sama. Bawa saja tak apa. Ibu sangat senang melihat semangat belajarmu. Dan sebagai hadiahnya, buku ini untukmu.”
16 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Terima kasih, bu. Terima kasih.” ku peluk Bu Astuti, erat sekali. Aku sangat senang, sama seperti aku sekolah dulu. Bu Astuti mengusap rambutku, seakan tak jijik dengan badan dan pakaianku yang kotor. “Bono, tetap rajin belajar ya? Walau sekarang kamu tak bersekolah lagi, tapi bukan berarti kamu juga harus berhenti belajar.” Bu Astuti menasehatiku. “Baik bu, apalagi Bu Astuti memberikan buku ini. Pasti Bono tambah semangat dalam belajar, bu.” kataku. “Bagus kalau begitu. Ya, sudah Bu Astuti mau melanjutkan mengajar ya? Jaga dan pelajari buku itu.” Bu Astuti tersenyum lembut padaku. “Baik, bu. Bono pamit pulang ya, bu? Assalamualaikum.” Tak sabar aku berpamitan pulang. “Wa’alaikumusalam.” Bu Astuti mempersilahkan, tak lupa ku cium tangannya. Di gerbang sekolah ku ambil sikap hormat pada Pak Rimbo dan berpamitan pulang juga padanya.
17 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Pak Rimbo, Bono pamit pulang!” kataku setengah keras. “Iya iya, hati-hati nak! eh bawa apa itu?” tanya Pak Rimbo. “Buku matematika pak, diberi Bu Astuti.” kataku sambil berlari kegirangan. “Owalah Bono..Bono.” kata Pak Rimbo menggelengkan kepala kemudian tersenyum. Aku
berlari
seraya
mengangkat
tinggi-tinggi
buku
matematika yang diberikan Bu Astuti. Sesampai di rumah, ku cari lagi buku-buku usangku. Ku buka lembar yang masih kosong dan ku kerjakan beberapa soal dari buku matematika itu. Aku sangat bersemangat. Walau mungkin cita-citaku menjadi guru jauh dari kenyataan, aku tidak mau menjadi orang yang bodoh. Aku ingin pintar seperti mereka yang masih bersekolah. Siapa tahu ada kesempatan suatu saat nanti. Kata kebanyakan orang hidup adalah sebuah pilihan. Setiap orang berhak memilih hidupnya masing-masing. Aku juga punya pilihan. Aku sudah terbiasa ditemani pantai, lautan, perahu dan
18 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
ikan-ikan. Tak salah jika kemudian pilihan hidupku sementara ini menjadi seorang nelayan seperti ayah. Hanya pekerjaan itu yang mungkin aku lakukan, sambil menunggu keajaiban dari Allah yang mampu mewujudkan cita-citaku menjadi seorang guru. Aku bahagia. Bukankah pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang bahagia mambuat segala pekerjaan menjadi mudah. Aku percaya bahwa inilah garis hidup yang Allah berikan padaku. Aku selalu bersyukur dengan semua itu. Aku yakin nelayan pun punya peranan penting dalam kehidupan, tak kalah dengan peran pentingnya seorang guru. Kalau tidak ada nelayan, bagaimana bisa kita semua menikmati lezatnya ikan dan makanan-makanan laut lainnya. Ibu yang tak pernah putus asa semasa hidupnya dan ayah yang tak lelah bekerja adalah penyemangat hidupku. Aku tahu pekerjaan menjadi seorang nelayan bukanlah pekerjaan yang hina. Aku ingin suatu saat kelak bisa hidup lebih baik dari orangtuaku kini. Aku sepakat dengan batinku untuk
19 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
terus berusaha menjadi anak yang patuh dan cinta pada orangtua. Agar di masa yang akan datang aku tidak hanya dapat berguna bagi orangtua melainkan juga untuk orang lain, agama, bangsa dan negara. Aku yakin orangtuaku tak mungkin menyesatkanku karena mereka sangat menyayangiku. Akan ku patuhi semua yang orangtuaku nasehatkan. Semua orangtua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kalau memang ini adalah garis hidupku. Aku yakin garis hidupku tidaklah buruk. Aku tinggal dengan orangtua yang sangat menyayangiku. Walau sekarang tinggal tersisa ayah, namun ku rasa ibu masih saja memantauku dari surga. Bukan karena
ayah
tak
ingin
aku
pandai
sehingga
ia
tak
menyekolahkanku. Namun karena tuntutan ekonomi yang memaksaku berhenti sekolah. Andai ayah mampu pasti ayah bisa menyekolahkanku hingga aku sarjana seperti yang pernah ku lihat di televisi Balai Desa. Tak apa aku ikhlas menerima semua ini. Buku yang di berikan Bu Astuti ini tidak akan aku
20 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
terlantarkan. Buku ini jadi suatu tanda bahwa masih ada orang yang percaya bahwa aku masih bisa mewujudkan cita-citaku. Kalau orang lain saja percaya, kenapa aku tidak? Kuncinya hanya rajin belajar walau dengan segala keterbatasan yang ada. Mungkin saja dari buku ini aku memiliki kesempatan menjadi guru seperti Bu Astuti. Insya Allah.
21 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
NYONYA SURATI
“Ipung, ayo lihat sabung ayam di lapangan!” ajakku. “Ah kamu bercanda Bon, kamu kan sudah tahu aku takut pada hewan itu!” kata Ipung cemberut. “Ciyee yang takut sama ayam, bibirnya manyun mau saingan sama ayam ya?” canda Ara. Kemudian aku dan Ara menertawai wajah Ipung yang terlihat lucu. Ipung hanya menatap polos kami berdua. Ara dan Ipung adalah teman bermainku, mereka sama sepertiku. Putus sekolah. Namun, dari segi umur aku lebih tua 2 tahun dari mereka. “Ya sudah, ya sudah, jangan cemberut lagi. Kita main kucing dan tikus saja yuk?” ajak Ara. “Ya aku setuju, lebih setuju lagi kalau Ipung yang jadi tikusnya. Lihat saja bibirnya, dari tadi manyun terus seperti bibir
22 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
tikus.” kataku kemudian tertawa. Tak mau dijadikan bulanbulanan, Ipung membalas, “Biar saja bibirku seperti bibir tikus, daripada bibirmu seperti bibir kuda!” Tawaku semakin keras seraya menepuk lengan kanan Ipung. Ara pun ikut tertawa, lagi-lagi Ipung hanya terbengongbengong. “Sudah, sudah. Ayo kita mulai hompimpa saja.” kata Ara. Kami
bertiga
mendekat
dan
mengambil
posisi
untuk
menentukan siapa yang jadi kucing, siapa yang jadi tikus. “Hompimpa alaiyum gambreng.” teriak kami bersamaan. “Ipung jadi kucing!” teriakku dan Ara. Kemudian aku dan Ara berlari menjauhi Ipung. Entah karena kesal atau apa, Ipung langsung mengejarku. “Bono, lari, cepat lari!” teriak Ara. Aku berlari secepat mungkin mencoba meloloskan diri dari kejaran Ipung. Na’as aku tersandung dan jatuh, Ipung menangkapku.
23 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kena!! Bono jadi kucing!” kata Ipung kemudian berlari menjauh dariku. Tiba-tiba dari arah berlawanan terdengar seseorang berteriak. “Woyy Boncel, enggak sekolah? Dasar miskin! hahahaha” begitulah ejekan usil Aceng teman satu kampungku. Hal itu yang membuat aku benci padanya. Sebenarnya, aku malu, aku selalu diejek olehnya hanya karena ia sekolah dan aku tidak. Masa bodoh, cuek saja. Kalau aku tak diajarkan sabar oleh ayah, sudah ku hantamkan mulutnya pada karang-karang laut. Mungkin lebih baik aku menjauhinya. Ara dan Ipung menarikku menjauhi Aceng yang baru saja pulang sekolah. “Sudah, ayo pergi saja!” kata Ara. “Iya Bono, kita bermain saja di karang besar itu!” imbuh Ipung. Aku hanya menuruti mereka. Dalam kegundahan aku berdiri dan berjalan menuju karang yang paling besar. Ku lepas alas kakiku dan bersila di puncaknya kemudian berlagak seperti nahkoda kapal menghibur diri.
24 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ombaknya sangat besar, penumpang diharap berhatihati!” teriakku dari atas karang berlagak mengemudikan kapal besar. Sementara Ipung dan Ara duduk di atas karang yang lebih rendah dari karang yang ku duduki. “Awas kapten, ada gunung raksasa!” teriak Ipung. “Baiklah, penumpang harap berhati-hati, kapal akan menikung tajam ke kanan.” kataku seraya menyondongkan badan ke kanan. Ipung dan Ara mengikuti gerakkanku. Saat sedang asyik berkhayal jadi nahkoda, dari kejauhan ku lihat Mbah Menir. Siang itu, ia sedang mencari sisa-sisa kerang laut yang menempel di antara karang-karang yang mencuat saat air laut surut dan menyisakan sedikit air dalam cekungan karang. “Ipung, Ara kalian main berdua dulu ya? Aku mau menemui Mbah Menir!” kataku. “Terus siapa yang jadi nahkodanya?” tanya Ipung. “Sini berdiri!” kataku menarik lengan Ipung.
25 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Sekarang ku lantik kamu jadi asisten nahkoda. Antarkan tuan putri Ara ke pulau Bali!” kataku kemudian menepuk bahu kanan dan kiri Ipung. “Siap!! Akan aku laksanakan kapten!” kata Ipung dengan posisi siap. Ara tersenyum melihat tingkah kami kemudian berteriak “Dasar gila!” kami bertiga tertawa. “Ah sudah. Aku mau bantu Mbah Menir dulu. Besok kita main lagi.” kataku. “Biar kami ikut bantu saja, bagaimana?” tawar Ara. “Ah jangan, kalian main saja berdua.” aku menolak. “Kenapa?” tanya Ara. “Kalian tidak tahu, di antara karang itu banyak cacingnya. Kalian tidak takut kalau cacing itu masuk ke dalam kaki kalian?” aku menakut-nakuti mereka. “Halah, bilang saja kamu takut upahnya dibagi tiga.” kata Ipung menyindir.
26 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hahaha...kalau sudah tahu ya sudah, kalian main saja berdua. Ayo sana!” aku mendorong mereka berdua agar pergi. “Ipung, ayo kita main lompat tali saja!” ajak Ara. “Dasar pelit kamu Bon. Ayo Ra!” Ipung melompat dari atas karang dan pergi dengan Ara. Ku lihat Mbah Menir semakin sibuk. Aku mendekatinya dan bertanya, “Mbah, Bono bantu ya?” “Ah, kamu le. Boleh. Nanti simbah masakan kerang laut.” Mendengar simbah menawariku makanan seenak itu, tentu aku tak menolak dan semakin bersemangat membantu Mbah Menir. Ku masukan satu per satu kerang yang ku cabut dari karang ke dalam kain jarit yang terikat kuat di badan Mbah Menir. Mbah Menir adalah bidan yang membantu persalinanku dulu. Ia sangat mengenal ibuku, karena Mbah Menir adalah teman karib nenekku yang juga sudah meninggal belasan tahun lalu. Jadi, ia banyak tahu tentang keluargaku. “Ayo le, sudah cukup banyak yang kita kumpulkan.” ajak Mbah Menir.
27 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku menurut dan mengikuti langkah Mbah Menir menuju rumahnya. “Nanti sesampainya di rumah, kamu bantu simbah mencuci kerangnya ya?” pinta Mbah Menir. “Baik mbah. Kalau buat Mbah Menir apapun Bono lakukan.” candaku. “Kalau begitu, sekalian saja nyapu, ngepel dan cuci baju simbah ya le?” Mbah Menir membalas candaku. “Ah kalau itu Bono menyerah mbah. Rumah simbah kan luasnya seperti lapangan sepak bola. Belum lagi baju-baju simbah kan mahal-mahal, kalau rusak bagaimana?” kataku. “Kamu bisa saja, le.” Mbah Menir mencubit gemas pipiku. Akhirnya kami sampai di rumah Mbah Menir. Rumahnya jauh lebih besar dari rumahku, dindingnya sudah berupa susunan batu bata dan semen. Beberapa perabotan rumahnya juga sudah lebih baik. Rimbun rindangnya pepohonan di halaman rumahnya
28 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
yang luas membuat suasana rumahnya sangat sejuk untuk cuaca pesisir pantai yang cenderung panas. “Duduk dulu, simbah mau mempersiapkan alat-alat memasaknya. Nanti jangan lupa bantu simbah mencuci kerangnya ya, le?” kata Mbah Menir. “Baik mbah.” Aku duduk di halaman rumahnya, Mbah Menir masuk ke dalam rumah. Ku rebahkan tubuhku pada lincak tua yang berderit menahan bobot tubuhku. “Ah, nyamannya.” pikirku. Mbah Menir terlihat sibuk mempersiapkan alat dan bahan memasak di
dapurnya. Merasa
sungkan, aku
beranjak
membantunya. “Mbah, mana? Katanya Bono yang mencuci kerang.“ kataku seraya mencari kerang yang akan ku cuci. “Owalah iya le, itu di belakang dekat sumur. Tinggal di cuci saja, sudah simbah siapkan tempatnya le.” kata Mbah Menir.
29 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Rumah simbah bagus ya? Baru kali ini Bono masuk rumah simbah yang baru.” kataku seraya mencuci kerang. “Ah, tidak jauh beda dengan rumahmu. Rumah simbah jelek.” Mbah Menir merendah. “Kamu terakhir kesini waktu ibumu meninggal. Jadi mungkin kamu pangling.” Aku tertegun. Aku ingat ibuku, Nyonya Surati. Ibu adalah sosok yang lembut dan penyayang. Ibu tak pernah sedikitpun marah kepadaku. Aku ingat, setiap aku menangis, ibu selalu mengusap rambutku dan memberiku segelas air hangat. Ya, Nyonya Surati, nama ibuku, sosok yang penuh perhatian. Tetangganya juga sangat segan padanya, tidak pernah sedikitpun dia meminta-minta untuk mencukupi hidupnya. Dia pekerja keras, pekerjaan halal apapun akan dia lakoni demi mendapat sedikit rizki untuk kebutuhan hidup. Bahkan ditengah kekurangannya, ibu tak ragu untuk membantu tetangganya walau harus mengeluarkan uang sekalipun. Aku bangga memiliki ibu seperti Nyonya Surati.
30 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Sayang, semua itu cepat berlalu. Terakhir aku melihat ibu saat umurku masih 10 tahun. Saat itu aku masih bersekolah walau dengan keterbatasan. Tas saja tak punya, alhasil kantung kresek aku jadikan alat untuk membawa buku-buku sekolahku. Sepatuku kumal, warisan ayah semasa sekolah dulu. Baju dan bukuku adalah hasil sumbangan dari sekolah untuk anak tak mampu. Saat itu aku sedang bersekolah, menerima pelajaran dari guruku. Tiba-tiba salah seorang tetanggaku berteriak histeris, “Bonooooo, Bonoooo, ibumu, ibumu...” Aku beranjak dari bangkuku dan bertanya, “Ibu kenapa?” “Ibumu tenggelam, meninggal!” Aku terhentak dan segera berlari menuju rumah. Disana ku dapati tetangga telah berkerumun. Ku lihat mayat ibu berada di tengah kerumunan bersama ayah yang menangisinya. Aku berlutut dan memeluk tubuh ibu yang basah dan dingin. Aku menangis, pahit menerima kenyataan.
31 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ibuuuuuuuuuu....” teriakku memekikan telinga. Rasanya aku tak rela melepaskan pelukkan ini. Aku ingin selalu bersama ibu. Ibulah pengobat hatiku kala aku sedih. Tapi kini, ibu telah tiada. Siapa yang sanggup mengobati kesedihanku ditinggal pergi ibu? Sampai tubuh ibu dimakamkan, aku masih mengingat senyumnya dengan jelas. “Hei..jangan melamun..” tiba-tiba suara Mbah Menir menyadarkanku. “Sudah bersih belum? Mau simbah masak kerangnya.” kata Mbah Menir mengagetkanku. “Oh iya mbah. Sudah, cangkangnya juga sudah Bono buang mbah.” kataku terkaget-kaget. “Kamu sedang melamunkan apa le?” tanya Mbah Menir. “Emmm..ibu, mbah. Sudah 2 tahun berlalu tapi Bono tetap ingat kejadian itu. Seringkali Bono rindu pada ibu.” kataku. “Ibumu itu memang luar biasa, le. Sama seperti kamu, santun, suka menolong, rajin ibadahnya. Dulu waktu ibumu
32 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
masih kecil, setiap sore ibumu sering membantu simbah memasak. Seperti kamu sekarang ini.” Mbah Menir bercerita. “Begitu mbah? Pantas saja ibu pintar memasak, ternyata simbah ya gurunya?” kataku buat Mbah Menir tersipu. Ku lihat Mbah Menir sangat cekatan memasukan bumbu dan mengolah kerang-kerang itu. Bau sedap mulai tercium. Air liurku mulai mengencer, lambungku seakan-akan meronta tak sabar ingin merasakan sedapnya masakan Mbah Menir. “Masakannya sudah jadi, ayo makan!” ajak Mbah Menir. Mbah Menir menyiapkan piring berisi nasi hangat untukku. Kemudian Mbah Menir menuangkan lauknya, Mbah Menir baik sekali sama seperti ibuku dulu. Seketika sosok ibu muncul dalam diri Mbah Menir, aku meneteskan air mata. Mbah Menir heran dan bertanya, “Kenapa menangis?” “Bono ingat ibu.” kataku lirih. Mbah Menir tersenyum, “Sudah, makan dahulu selagi nasimu masih hangat.”
33 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Senyum
Mbah
Menir
hampir
sama
seperti
ibu,
mendamaikan. Aku sangat nyaman berada di dekat Mbah Menir. Walau perawakannya jauh berbeda, tapi rasa sayang Mbah Menir kepadaku hampir sama seperti ibu. Aku rindu ibu. Tiba-tiba Mbah Menir beranjak dari bangkunya. “Tunggu sebentar le, ada yang ingin simbah tunjukan padamu!” Mbah Menir masuk ke kamarnya dan segera keluar dengan membawa sebuah radio yang kelihatannya sudah tua. Mbah Menir tersenyum dan memasukkan sebuah kaset ke dalam radio tua itu. Baru kali ini aku mengerti, ternyata radio tua itu juga bisa dijadikan pemutar kaset. Mbah Menir memutar sebuah lagu keroncong. Aku tak mengerti isi lagu itu. Tapi iramanya mendayu-dayu mengungkap kejayaan tempo dulu. Ku pegang radio itu dan menilik gerakan memutar di dalamnya. Penasaran aku dibuatnya. Mbah Menir berkata padaku, “Ini adalah lagu kenangan ibumu le, dahulu ibumu suka sekali memutar lagu ini.”
34 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kenapa ibu suka lagu ini mbah?” tanyaku penasaran. “Ini lagu masa muda ibumu dahulu, saat ibumu jatuh cinta pada ayahmu.” jelas Mbah Menir seraya tersenyum. “Jatuh cinta mbah? Apa itu mbah?” “Jatuh cinta itu, apa ya? Emmm kata anak muda jaman sekarang, jatuh cinta itu lope-lope.” jawabnya bercanda. “Lope-lope itu apa mbah?” tanyaku semakin penasaran. “Lope-lope itu ya orang yang suka pada lawan jenisnya.” Mbah Menir menjelaskan. Aku semakin tak mengerti. “Bono suka bermain dengan Ara, berarti Bono juga lopelope pada Ara ya mbah?” kataku dengan mata berbinar. Seketika Mbah Menir terdiam, menghentikan kunyahan nasi di mulutnya, sadar kalau aku belum mengerti betul tentang jatuh cinta. “Sudah, selesaikan makanmu dulu!” perintah Mbah Menir gugup menghindari pertanyaan lainnya yang lebih jauh. “Tapi simbah belum menjawab pertanyaan Bono.” kataku bersikeras.
35 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya nanti simbah jawab, habiskan nasimu dulu!” katanya. Aku makan dengan lahapnya, sangat jarang aku menikmati makanan selezat ini. Selain Mbah Menir, tidak ada tetangga yang sebaik dia. “Sudah selesai mbah. Biar Bono cuci piringnya.” “Ehhh, sudah tidak usah. Biar simbah saja! Hari sudah mulai petang, sebaiknya kamu pulang dan bawa kerang ini untuk lauk makan di rumah.” kata Mbah Menir seraya menyodorkan rantang berisi masakan kerang laut. “Terima kasih mbah.” kataku senang. “Tapi simbah tadi sudah janji, selesai makan simbah mau memberitahu apa Bono sudah lope-lope?” imbuhku masih penasaran. “Bono, lihat matahari sudah mau hilang dari langit. Kamu mau saat pulang nanti bertemu wewe gombel?” Mbah Menir menakutiku. “Ahhh tidak mbah.” aku merinding ketakutan.
36 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya sudah, cepatlah pulang. Bawa rantang itu untuk makan malam dengan ayahmu!” perintah Mbah Menir. Aku pun bergegas pulang sebelum matahari terbenam. “Iya mbah, Bono pulang dulu ya mbah? Assalamualaikum.“ “Wa’alaikumsalam putu lanang.” jawab Mbah Menir seraya tersenyum dan melambaikan tangan. Sesekali ku lihat isi rantang itu selama perjalanan pulang. Ku pikir ayah pasti akan senang. Karena malam ini tidak lagi makan makanan dengan bumbu garam saja. Dalam perasaan senang itu aku masih penasaran, jatuh cinta itu seperti apa? Suatu saat nanti Mbah Menir harus bertanggung jawab menghapus rasa penasaranku. Tak mungkin ia tak tahu, hanya Mbah Menir yang bisa memberiku jawaban karena aku tak berani bertanya pada ayah tentang jatuh cinta atau “lope-lope”.
37 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
DOA UNTUK IBU
“Allahu akbar..Allahu akbar...” Suara adzan memecah keheningan malam diiringi sinar mentari yang sayup-sayup kemerahan muncul dari arah timur. Aku terbangun dari mimpiku, ku seka mata yang masih enggan untuk ku buka. “Ah lagi-lagi ayah belum pulang.” Ku lihat sayur kerang yang ku sisakan untuk ayah semalam masih saja utuh. Aku bergegas mengambil air wudhu dan sarung usangku yang ku gantung pada paku yang menancap di tiang kayu rumahku. Aku berjalan terhuyung menuju surau kecil di kampungku. Aku mulai sholat berjamaah dengan khusyuk, sedikit menguap mungkin masih wajar untuk anak seusiaku. Seperti biasa aku berdoa untuk ayah dan ibu. Selepas sholat shubuh aku duduk di dekat pantai menunggu ayah pulang.
38 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Boncel! Mana kucing sialanmu itu!” suara menggelegar mengalahkan deru ombak. Tiba-tiba ku lihat dari arah belakang Mak Nasib mengacungkan gagang sapunya ke arahku, ia terlihat murka. “Aku tak tahu mak. Ada apa?” aku ketakutan. “Lagi-lagi ia mencuri ikan asinku. Dasar kucing kudisan!” “Awas kalau aku lihat dia, ku patahkan tulang punggungnya dengan sapu ini!” Mak Nasib terengah-engah. Aku hanya bergeming tak berani membantah. “Hei, mau kemana kau bocah?” Tanpa
perduli
aku
berlari
mencari
Doreng
dan
meninggalkan Mak Nasib yang masih jengkel. Berjam-jam ku telusuri sudut-sudut kampung namun aku tak menemukannya. Aku menuju rumah dan ku dapati Doreng terbujur di dekat kaki meja dengan memar di kepala. Aku berjongkok di dekat Doreng yang terkulai lemah dan merintih. Ku elus tengkuknya penuh
39 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
kasih sayang, ia pun membalasnya dengan menjilati tanganku seakan mengerti siapa empunya. “Kasihan sekali kau Reng, tunggu biar ku ambilkan air dan kain untuk menyeka memarmu.” kataku sedih. Ku petal kepalanya dengan kain basah. Lagi-lagi ia hanya merintih. Aku menatapnya iba. “Kamu jangan nakal lagi ya Reng? Sungguh biadab yang melukaimu. Biar saja, kita doakan saja tangannya pengkor sebelah.” gerutuku kesal. “Jangan sembarangan kalau bicara!” Tiba-tiba bulu kudukku meruap, sosok tinggi besar berdiri di belakangku. Perlahan ku palingkan wajah, “Ayah.” “Doreng kenapa le?” kata ayah dengan peluh yang mengucur bagai hujan barat. “Bono tak tahu yah, mungkin dipukul Mak Nasib. Tadi Bono bertemu Mak Nasib yang jengkel karena ikan asinnya dicuri Doreng lagi.” jelasku.
40 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Lain kali, jaga dan beri makan kucingmu dengan baik. Jadi, ia tidak mencuri ikan asin lagi.” kata ayah bijak. Aku hanya mengangguk. “Le, goreng beberapa ikan yang ayah dapat, sisakan sirip ekornya untuk Doreng!” perintah ayah seraya menyodorkan keranjang bambu berisi ikan. Aku segera mengambil dua ikan yang masih segar dan menggorengnya dengan bumbu garam. Ku sajikan ikan yang sudah matang ke hadapan ayah yang masih mengibas handuknya untuk menghilangkan panas tubuh. “Ini sayur dari siapa le?” tanya ayah seraya mencium rantang di atas meja. “Oh itu dari Mbah Menir, yah. Kemarin Bono membantu Mbah Menir mencari kerang, lalu Mbah Menir memberikan itu untuk kita. Tapi semalam ayah tidak pulang, jadi tidak habis, yah.” jelasku.
41 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Oh begitu, iya semalam ayah menginap di gubuk dekat pantai dengan Mas Ikin membetulkan jaring. Sepertinya belum bau, ayo kita makan saja le!” kata ayah. “Iya, yah. Kita habiskan saja, nanti mubazir.” kataku seraya menyendokkan nasi dari Mbah Menir sisa tadi malam untuk ayah. Ayah menahan tanganku, “Nasi itu buat kamu saja, ayah makan dengan singkong rebus sudah cukup.” Aku menurut. “Ayah, besok Bono ikut mencari ikan ya?”pintaku. “Meh ngopo?” kata ayah seraya mencuil ikan dan memakannya dengan singkong rebus. “Bono ingin membantu ayah bekerja. Bono bosan di rumah.” pintaku semakin menggebu. “Ndak usah Bono, kamu masih 12 tahun. Tunggu hingga kamu berumur 17 atau 19 tahun.” larang ayah. “Tapi Bono sudah cukup berani melawan ganasnya ombak laut, yah. Bono selalu jadi kapten nahkoda saat bermain dengan Ipung dan Ara.” kataku bersikeras.
42 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kamu pikir melaut itu seperti bermain, le?” kata ayah. “Kenapa sih, ayah selalu saja melarang Bono ikut ayah melaut!” kataku ketus. “Sudah diam! Makan saja ikannya, ra usah nglawan!” kata ayah meradang. Aku tersentak, kecewa dan masuk kamarku. Ku kunci pintu rapat-rapat dengan gerendel paku. Aku tahu ayah lelah, jadi emosinya cepat naik. Tapi tidak perlu membentakku seperti itu. Aku ingin membantu ayah bekerja. Aku kasihan pada ayah, meski kondisi fisiknya sudah mulai sakit-sakitan namun ia paksakan untuk bekerja. Aku duduk di lantai menghadap jendela. Ku lihat foto Ir. Soekarno idola ayahku tertempel di dinding kayu dekat jendela. Foto itu sudah memudar, namun ayah tetap menyimpannya. Ialah sosok yang jadi panutan ayah mendidik anaknya. Keras namun penyayang. Ayah memang sudah tak mampu menyekolahkanku. Namun, ia bisa memberi pelajaran hidup yang berharga.
43 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bagaimana dapat bertahan hidup dengan tidak menyusahkan orang lain. Ayah juga sangat telaten mengajariku membaca dan menulis huruf Arab. Kini aku bisa khatam Al-Qur’an juga karena jasa ayah. Tinggal di kampung yang tertutup kokohnya Pulau Nusakambangan memang tak mudah. Harus benar-benar berjuang mencari sesuap nasi. Wajar saja, jarak kampung ke kota sangat jauh. Apalagi jika harus melewati jalan darat, belum sampai di kota uang kami sudah habis untuk menumpang kendaraan umum. Hanya singkong yang mampu menjadi pengganti nasi. Tapi aku tetap bersyukur, karena bukan nasi kering yang ku telan dan menyumbat rasa lapar di perutku. Kampungku berada di balik Pulau Nusakambangan. Pulau penjara tempat penjahat kelas kakap pernah mendekam. Pulau dengan berbagai keseraman yang didengungkan, padahal kenyataannya bertolak belakang. Pulau Nusakambangan sangat eksotis. Aku sering menghabiskan akhir pekan di pasir putihnya
44 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
yang berkilauan bak pecahan permata. Kata ayah, dahulu kampungku adalah lautan. Kemudian tanah yang mengendap berubah jadi daratan. Daratan itu sering disinggahi nelayan untuk
beristirahat,
hingga
akhirnya
nelayan-nelayan
itu
membangun sebuah rumah dan jadilah kampungku sekarang. “Tok tok tok” Ayah mengetuk pintu dan memanggilku. “Bono. Keluar, le! Ayah ingin bicara denganmu.” Aku diam, tak menyahut sebagai protes atas sikap ayah tadi. “Le, ayah mau bicara. Cepat keluar!” kata ayah dengan nada meninggi. Dengan wajah masygul aku keluar dan duduk di bangku kayu bersama ayah. Ayah menatapku tajam. Aku takut membalas tatapannya. Aku hanya menunduk. “Kamu tahu kenapa ayah melarangmu melaut saat ini?” tanya ayah menggenggam pundakku. Aku hanya menggelengkan kepala.
45 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ingat peristiwa saat ibumu meninggal?” tanya ayah, binar matanya mulai meredup. Aku palingkan pandangan ke arah ayah dan aku tertegun memandang mata ayah. “Saat itu ibumu tenggelam karena perahu ayah tersapu ombak. Untungnya saat itu ayah berhasil meraih sebilah kayu yang melintas. Sementara ibumu....” ayah terdiam, bibirnya bergetar hebat dan air matanya mulai menetes. Untuk kedua kalinya setelah pemakaman ibu, ku lihat ayah menangis. Sosok keras dengan tubuh tinggi besar menangis di hadapanku. Rasa cintanya pada ibu sangat luar biasa. Aku memeluk ayah dan menahan air mataku dengan handuk yang tergantung di pundaknya. “Bono, kamu..kangen ibumu le?” tanya ayah lirih dengan nada terputus-putus. Aku mengangguk menahan tangis dengan bibirku. “Ayah juga kangen ibumu.” tambah ayah. “Kita ke kuburan ibu saja, yah.” ajakku.
46 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kamu mau ayah ajak ke sana, le?”tanya ayah seraya menyeka air mataku. Aku mengangguk tak sabar. Rasa rindu membuat ayah membawaku ke kuburan tak berpagar dekat rawa tempat ibu dimakamkan. Sore, hari itu juga. Batu nisannya hanya terlihat seujung kuku didesak bergumpal-gumpal ilalang. Aku melihatnya miris, apakah ibu nyaman dengan tempat peristirahatan terakhir yang buruk seperti ini? Aku saja gerah melihatnya. Ku ayunkan clurit menebas ilalang kurang ajar yang mengotori kuburan ibuku. Seandainya aku bisa kesini setiap hari, pasti kuburan ibu akan terlihat layak. Sayangnya, terlalu jauh dari rumah. Harus menggunakan perahu untuk menyeberang ke area makam. Sementara aku pun tak bisa menunggangi sepeda onthel milik ayah untuk menuju dermaga. Ayah mengusap nama ibu dengan kain basah. Pandangannya nanar seakan-akan ayah ingin memeluk ibu. Aku melihatnya dan mendekati ayah. Ayah tersadar, melihatku dan mengusap rambutku.
47 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, sudah. Sekarang doakan ibumu!” perintah ayah seraya memeluk pundakku. Hatiku berdebar, inikah rasa cinta ayah sebenarnya? Merinding. Sesaat aku seperti merasakan kehadiran ibu di sisi kananku sementara ayah memeluk pundak dari sisi kiriku. “Apa yang kamu tunggu? Ndang doakan ibumu!” perintah ayah mengagetkanku. “I..iya, yah” “Jangan lupa baca basmallah, nanti ayah amin-kan.” kata ayah mengingatkan. Aku bersiap mengambil sikap berdoa. Sebelumnya ku sentuh terlebih dahulu nisan ibu tepat pada namanya dengan tangan kananku. Dalam hati aku berkata, “ibu aku rindu.” Kemudian aku menengadahkan kedua tangan dan segera berdoa. “Ya Allah. Tempatkan ibuku dalam Surga ‘Adn-Mu. Dia adalah mujahid. Mati demi mencukupi kehidupan anaknya. Berjuang
di
jalan-Mu
menyehatkan
anaknya.
mendapatkan Entah
upah
dengan
apa
halal aku
untuk bisa
48 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
membalasnya, selain memberinya lantunan doa yang dapat membangunkannya dalam keadaan suci di hari akhir nanti. Sungguh aku tak marah pada-Mu yang telah menjemput ibuku saat aku masih sangat membutuhkannya. Justru dengan demikian aku dapat selalu mendoakannya. Mungkin aku akan jadi anak yang lalai jika aku masih dimanja lembut telapak tangan ibuku. Seperti teman-teman yang berani menentang ibunya, membuatnya menangis dan sakit hati. Sungguh aku tak ingin seperti mereka. Aku lebih baik mencium kaki ibuku yang berlumpur daripada harus membuatnya menangis dan sakit hati. Muliakanlah ibuku Ya Allah, agar aku dapat bertemu dengannya dan ia menyambutku dengan wangi minyak kasturi dari Surga. Amiin”
49 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
RAIBNYA SI DORENG
Suatu sore, saat aku sedang asyik melipat kertas yang ku sobek dari sebuah buku menjadi pesawat terbang mainan, ku lihat Doreng melintas beberapa kali di depan pintu kamarku. Heran, aku keluarkan kepalaku dari balik tiang pintu kamarku. Doreng melihatku dan menatapku tak biasa. Ku dekati ia, berjongkok dan menyuruhnya tidur berkali-kali, ku elus kepala hingga tengkuknya agar ia tenang. Namun, ketika aku berhenti mengelus, ia kembali beranjak dan memandangku seakan ada yang ingin ia sampaikan. “Kamu mau makan?” tanyaku sedikit bingung. Sesaat sebelum berdiri mengambil makanan untuk Doreng, ku lihat makanannya masih utuh hanya saja sedikit berantakan tidak pada posisi saat aku menaruhnya. Tak mengerti apa yang Doreng mau, ku tinggalkan saja ia. Aku kembali ke kamarku dan
50 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
memainkan pesawat terbang kertas yang baru ku buat. Sejenak ku lupakan si Doreng, bersenang-senang memainkan pesawat dari kertas yang terbang tinggi dan jatuh menukik tajam. Ku terbangkan berulang-ulang pesawat mainanku dan terbang
keluar
melalui
pintu
kamar.
Aku
berlari
menghampirinya, saat akan ku ambil, aku teringat pada Doreng. Dia sudah tidak ada. Aku pun melupakan pesawat mainanku, ku cari doreng di bawah kursi dan meja, di dapur, kemudian di sekitar rumah tapi hasilnya nihil, ia tak terlihat bahkan gerak geriknya. Ku panggil namanya, “Doreng..Reng..Pus..Pus..Pus..Pus.” Ia pun tak menyahut. Hatiku mulai hancur dibuatnya. Aku coba mencarinya di jalanan desa namun Doreng tetap tidak ada. Aku putuskan untuk mengajak Ipung dan Ara ikut mencarinya. Aku datangi rumah Ipung dan memanggilnya, “Ipung..Ipung.” “Iya Bon, ada apa?” katanya dari dalam rumah.
51 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kau sedang apa? Bantu aku mencari Doreng yuk!” kataku terlihat panik. “Hanya membantu ibu menata ikan asin. Doreng kemana?” katanya heran. “Ahhh mana ku tahu, dia pergi tapi ini tidak seperti biasanya. Ayo kamu bisa bantu tidak?” kataku tergesa-gesa. “Sebentar, aku pamit dulu pada ibu.” katanya seraya berlari menuju dapur kemudian ia kembali dengan menenteng sandal japitnya. “Ayo kita cari!” katanya. “Kita ke rumah Ara dulu, lebih banyak yang mencari lebih baik.” kataku dengan langkah cepat. Ipung mengikuti langkahku. Tak lama kami sampai di rumah Ara, ku lihat ia sedang menyirami tanaman di depan rumahnya. “Araa...” teriakku dari kejauhan, ia menoleh ke arahku. “Kamu bisa bantu aku?” kataku. “Bantu apa Bon? Aku sedang menyirami tanaman ini.” katanya seraya menuangkan air dari gayungnya.
52 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bantu aku cari Doreng, kalau sudah ketemu nanti kami bantu menyirami tanamanmu.” kataku seraya menarik gayung yang digenggam Ara. “Ada apa sih?” kata Ara penasaran. “Sudah nanti ku jelaskan, ayo bantu cari dulu!” kataku seraya menarik tangan Ara, ia terlihat sempoyongan. “Aduhh sabar dong.” wajahnya cemberut. Kami bertiga pergi mencari Doreng hingga ke arah pantai. Di pantai aku bertemu Mas Ikin, teman ayahku melaut. Ia lebih muda dari ayahku. “Mas, lihat Doreng?” tanyaku. “Enggak Bon, Doreng hilang?” tanyanya. “Iya mas, enggak tahu pergi kemana.” jawabku panik. “Nanti
juga
pulang
sendiri
Bon.”
kata
Mas
Ikin
menenangkan. “Kali ini Bono rasa berbeda mas, dia tak pernah jauh dari rumah, kalau pun jauh, Bono panggil pasti dia mendekat.”
53 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
bibirku mulai melengkung sedih, khawatir pada Doreng. Melihatku yang sedang tak baik, ayah mendekat. “Ono opo le?” tanya ayah. Aku berlari memeluk pinggul ayah, “Doreng hilang yah.” Ayah menghela nafas, “Sudah, tunggu saja di rumah. Kalau belum juga kembali, besok kita cari bersama.” kata ayah ikut menenangkan. “Ayo pulang, hari sudah semakin petang. Ipung dan Ara juga pulang ya?” ajak ayah. Mereka mengangguk. Ayah mengantar Ipung dan Ara terlebih dahulu. Kemudian aku pun pulang bersama ayah, sesekali pandanganku fokus melihat ke arah celah-celah semak belukar yang ku lewati, berharap Doreng terlihat. Sore berganti malam, biasanya aku tengah asyik bercanda dengan Doreng. Tapi malam ini berbeda, hanya suara jangkrik yang bergiliran menggelitik telingaku. Ah, aku tak sabar menanti
54 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
esok pagi, aku ingin matahari segera terbit. Kesepian, ku dekati ayah yang sedang membetulkan jaring. “Yah, besok mau cari Doreng kemana?” tanyaku. “Di sekitar kampung saja, kalau tidak ketemu ya di kampung sebelah.” kata ayah yakin. “Kalau tidak ketemu juga yah?” tanyaku memastikan. “Ya doakan saja ia masih hidup.” jawab ayah seraya memandangku. “Kalau Doreng sudah mati yah?” tanyaku lugu. “Ya doakan saja masuk surga.” jawab ayah setengah tersenyum. “Iya yah, tapi kalo masuk neraka bagaimana yah?” aku semakin mempersulit. Ayah mulai menggaruk kepalanya, “Emmm, kalau masuk neraka ya berarti sekarang Doreng sudah gosong.” canda ayah kemudian tertawa. “Sudah sana, masuk! Di luar dingin.” perintah ayah.
55 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku masuk ke dalam dengan sedikit menggerutu, ayah tak serius menjawab pertanyaan terakhirku. Ku raih pesawat mainanku yang tergeletak di atas dipan kemudian ku terbangkan sesekali. Pandanganku tertuju pada langit-langit rumah yang dipenuhi sarang laba-laba. Berkali-kali ku pahami lagi, ada apa dengan Doreng hingga ia tak ku temukan lagi. Otakku mulai dipenuhi dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana dan mengapa. Pertanyaan yang berjejal di otakku menguras energi dan seketika aku tertidur. Pagi-pagi sekali setelah selesai sholat shubuh, aku menarik tangan ayah untuk menepati janjinya mencari Doreng. “Ayah, ayo kita cari Doreng!” aku tak sabar. “Iya ayo, sabar to le.” kata ayah seraya meraih topinya dari atas meja. Aku dan ayah mulai mencarinya, menelusuri sudut-sudut desa hingga kami lelah. Aku hampir putus asa karena tak ada tanda-tanda Doreng akan ku temukan.
56 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Sudah kita pulang saja, le. Tunggu saja dia pulang sendiri. Doreng itu kan kucing yang pintar.” hibur ayah. Aku hanya mengangguk. Sesampainya di rumah aku duduk di kursi kayu dekat meja makan. Wajahku terlihat muram, mengetahui perihal yang sedang dialami anaknya Ayah berkata, “Sudahlah, pasrahkan saja.” Namun, aku tetap saja tak rela. Hampir tiga tahun bersama tak bisa dianggap sebentar untuk begitu saja melupakannya. Seakan aku sudah terikat secara batin dengan Doreng. Ibu yang menemukannya di pinggir jalan kemudian memberikannya padaku. Ku namai ia Doreng karena bulunya memiliki campuran warna pirang, hitam dan putih. Dulu ibu dan aku senang bercanda dengannya. Ia sangat suka memainkan bola dan bertingkah lucu. Doreng adalah kucing betina yang penurut, tidak seperti kebanyakan kucing kampung yang cenderung bertindak agresif. Kalau pun ia mencuri ikan asin yang sedang dijemur, itu karena aku lupa memberinya makan.
57 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Setelah ibu meninggal, Doreng satu-satunya teman bermainku di rumah. Saat aku bermain dengannya, seakan-akan ibu turut hadir menemaniku. Kini semua tinggal kenangan, Doreng tidak juga ku temukan. Aku sedih. Setiap memikirkan Doreng aku selalu mengingat betapa manjanya dia dulu. Betapa cerdasnya dan betapa khas dengkurannya saat ia tidur. Aku masih ingat suaranya ketika ku panggil untuk makan, "meonngg meoonggg", begitu juga setiap kali aku mengelus kepalanya. Belum lagi tingkah lucunya saat menarik-narik tali jaring yang terkadang membuat ayah marah besar. Aku mengingatnya dengan baik. Ia sudah seperti keluarga di rumah ini. Kini aku harus percaya Doreng ada di tempat yang baik sekarang. Kucing manis itu pasti sedang bahagia entah dimana. Sedikit ada penyesalan yang terlintas, berharap bisa memutar waktu. Andai saja waktu itu aku tak sibuk dengan pesawat
mainanku
dan
menggendong
Doreng
untuk
58 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
menenangkannya. Mungkin saat ini Doreng masih ada dan bermain bersamaku. Aku merindukan Doreng, mungkin Doreng juga merindukanku kalau ia masih hidup. Perasaan seperti ini terulang kembali, sama seperti saat aku kehilangan ibu. Aku sangat sedih, menangis dan tak bisa ku katakan bahwa aku baikbaik saja. Setiap hal yang terjadi pasti ada dampaknya dalam hidupku selanjutnya. Ku pastikan setelah kejadian ini, aku akan benar-benar sendiri tanpa Doreng. Aku coba menerima ini sebagai serentetan ujian yang Allah berikan padaku. Allah sudah mengatur semua ini, bukan untuk melemahkanku tapi untuk menguatkanku. La haula wala quwwata illa billah.
59 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
AMPUN, AYAH
Sebulan setelah Doreng menghilang, hatiku masih saja gundah dibuatnya. Beruntung aku masih memiliki teman seperti Ipung dan Ara. Aku hanya mampu bermain-main dengan mereka di tepian pantai. Di sudut yang lain, ayah bersama nelayan lainnya sedang sibuk membetulkan jaring. Ku ambil ranting kering tak jauh dariku. Kemudian ku gambar ayah, ibu, aku dan tak lupa Doreng dengan ikan asin kesukaannya. Ipung dan Ara berjongkok mengamati gambarku. Agar tak tersapu ombak, ku beri batu-batu mengitari gambar yang ku buat. Ternyata batu yang ku temukan tak cukup kuat menahan ombak. Ku putuskan mencari batu yang lebih besar sedikit lebih jauh dari tempat aku menggambar. “Ara tolong jaga gambarku dulu ya! Aku dan Ipung mau cari batu yang lebih besar!” kataku.
60 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya, aku jaga. Tapi jangan lama-lama ombaknya cukup besar.” kata Ara khawatir. “Ayo Pung. Kamu cari di sebelah sana, aku di sana! Cari yang seukuran kepalan tangan!” perintahku. Ipung mengangguk tanda ia telah mengerti. Ku ambil satu persatu dan ku kumpulkan ke dalam bagian depan kausku yang ku bentuk menjadi semacam wadah. Cukup lama aku mencari batu-batu itu, setelah ku pikir cukup aku kembali ke tempat dimana aku menggambar. “Ipung, sudah belum?” aku berteriak. “Ya sudah cukup, ini aku dapat banyak.” kata Ipung sambil menunjukkan kantung kresek berisi batu-batu yang cukup besar. “Dapat kantung kresek darimana Pung?” “Itu ada yang hanyut, ku lihat masih bagus jadi aku ambil.” “Cerdas kamu Pung!” pujiku buat Ipung tertawa bangga. “Siapa dulu? I.P.U.N.G gitu lho.” katanya sombong.
61 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Haduh. Baru dipuji sedikit, sudah lebar hidungmu, Pung. Ayo cepat kita kembali ke tempat kita menggambar tadi.” kataku. “Pasti wajah Ara sudah tak berbentuk karena bosan menunggu kita.” tambah Ipung. Kami tertawa. Kami segera kembali ke tempat kami menggambar. Dari kejauhan aku melihat ada yang aneh dengan gambar yang ku buat tadi. Aku mendekat dan berdiri tepat dimana aku menggambar. Alangkah terkejutnya ketika ku lihat gambarku sudah hancur porak poranda. Bukan karena ombak, ku lihat ada bekas sapuan kaki. Ara juga terduduk menangis. “Ara, siapa yang melakukan ini?” kataku kesal. Ara menunjuk ke suatu arah. Mataku mulai mencari pelakunya searah telunjuk Ara mengarah. Tak jauh ku lihat Aceng dan Munir membawa ranting yang ku gunakan untuk menggambar tadi. Sepertinya aku tahu siapa pelakunya. “Pung, kamu di sini saja. Jaga Ara!” kataku dongkol.
62 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya Bon. Kamu mau kemana?” katanya seraya membantu Ara berdiri. “Sudah diam saja di sini!” teriakku spontan. Aku berlari ke arah Aceng dan Munir kemudian berteriak, “woooooy!”. Mereka tersentak dan melihatku datang dengan wajah dongkol. Aku bertanya pada mereka, “Kalian yang menghancurkan gambar yang ku buat di sebelah sana?” “Kalau
iya
memang
kenapa?”
kata
Aceng
seraya
mematahkan ranting yang ku gunakan menggambar tadi. Aku hanya terdiam menahan kesal, tanganku mulai mengepal. Melihat reaksiku, Aceng menantang, “Berani? Ayo pukul!”. Aceng mendorongku hingga aku jatuh terduduk. Aku pikir walau badan Aceng lebih besar aku tidaklah takut, yang jadi masalah adalah ia bersama Munir, aku kalah jumlah. Mengajak Ipung membantuku berkelahi tak mungkin, ia penakut. Dengan ayam saja ia tak berani, apalagi harus menghadapi dua orang ini.
63 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kenapa diam saja? Takut?” bentak Aceng sok jagoan. Ingin sekali aku menghantam mulutnya, namun lagi-lagi nasehat ayah menahanku untuk bertindak brutal. “Ibumu sudah mati! Doreng juga sudah hilang mungkin dia juga mati sama seperti ibumu! Buat apa kamu gambar?” Aceng semakin menjadi-jadi. Kali ini sepertinya ia tak bisa ku biarkan, ku genggam pasir dan melemparkannya ke arah Aceng. “Ahhhh…Boncel sialan!!” Tak terima Aceng mencoba memukulku. Bogemnya tepat mengenai pelipisku. Segera aku membalasnya, ku hantamkan bogemku ke arah dagunya. Mantap, ia terhuyung. Akhirnya berkelahilah kami, Aceng tertinju beberapa kali kemudian meminta bantuan Munir. “Nir, bantu! Jangan diam saja! Kampret!” kata Aceng. Munir hendak menangkapku dari belakang tapi terkena tendanganku. Tendanganku tepat masuk ke bagian dadanya. Munir menahan nafas kesakitan. Ku lakukan tendangan yang
64 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
sama pada Aceng, namun nahas usahaku gagal. Aceng berhasil menangkap kaki kananku dan menariknya hingga aku jatuh tersungkur. Seketika Munir menggenggam kaki kiriku. Bersamasama mereka mengarakku hingga siku tanganku terluka terkena pecahan cangkang kerang. Mas Ikin yang kebetulan melintas melihat kejadian itu. Ia segera memberitahu ayahku, ”Mas, anakmu berkelahi dengan Aceng dan Munir.” “Owalah, dimana mereka?” tanya ayah naik pitam. “Di sudut pantai sebelah sana, mas.” kata Mas Ikin seraya menunjuk ke suatu arah. “Ayo kita ke sana, Kin.” ajak ayah. Ayah dan Mas Ikin mendekat. “Wooy, bubar!” teriak Mas Ikin dari kejauhan. Melihat ayahku datang, Aceng dan Munir lari ketakutan.
65 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Awas kalau ketemu, aku hajar kamu Cel!” kata Aceng masih bernapsu untuk berkelahi. Aku pun lari ketakutan, aku takut ayah akan memarahiku. “Ipung, Ara cepat kalian pulang saja!” teriakku seraya berlari menjauhi ayah dan Mas Ikin. Aku menuju rumah Mbah Menir, berharap perlindungan di sana. Sesampainya di rumah Mbah Menir, “Mbah..Mbah Menir, ini Bono mbah. Assalamualaikum.” kataku memanggil Mbah Menir dari luar rumah. Tak lama Mbah Menir keluar dengan muka terkaget-kaget, “Wa’alaikumsalam. Ealah putu lanang. Kamu kenapa kotor seperti itu? Tanganmu juga terluka?” “Tadi Bono berkelahi dengan Aceng dan Munir mbah. Mereka mengejek Bono mbah. Bono tak tahan lagi.” jelasku. “Owalah Bono..Bono..kamu ini rajin sholat, rajin ngaji. Koq yo sampai berkelahi seperti itu?” tanya Mbah Menir iba melihatku. “Nanti ayahmu bisa marah.” tambahnya.
66 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya mbah, Bono khilaf. Bono takut ayah marah.” kataku dengan suara lirih. “Ya sudah, lepas bajumu. Biar simbah mandikan, lalu mbah obati lukamu.” kata Mbah Menir seraya membuka kausku. Mbah Menir memandikanku. Setelah mandi aku tidak boleh pergi dulu oleh Mbah Menir. Aku hanya bermain sendirian di rumah Mbah Menir, meski pintu pagar terbuka aku tidak berani keluar takut durhaka kepada orang yang lebih tua. Aku duduk dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, walau sebenarnya aku berpikir kalau bertemu Aceng lagi, aku ingin sekali memukul perutnya sampai ia terjatuh dan muntah darah. “Sini le, mana sikunya?” kata Mbah Menir dari arah belakang. Mbah Menir mengobatiku dengan obat merah, pedih sekali rasanya. “Sakit le?” tanya Mbah Menir. Aku hanya mengangguk dengan mata terpejam. Disuruhnya aku duduk di beranda rumahnya agar obat merahnya cepat kering oleh angin. Aku
67 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
meniup-niup lukaku menghilangkan rasa pedih yang masih menggelayut di sikuku. Sesaat kemudian aku terpekur menyesali perbuatanku tadi. “Andai saja aku bisa menahan emosiku, pasti tidak begini kejadiannya. Tapi mereka pantas mendapatkannya, paling tidak mereka tahu bahwa aku bukanlah pengecut.” Ku lihat Mbah Menir sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya, jadi aku tak mau mengganggunya. Aku hanya memandang ke sekeliling rumah Mbah Menir, berharap ayah tidak menyusulku ke sini. Namun tiba-tiba dari kejauhan ku dengar suara yang ku kenal memanggilku, “Bono..Bono..” itu suara ayah. Bergegas aku menghampiri Mbah Menir, ketakutan. “Mbah, ayah datang. Bono takut.” kataku bersembunyi di balik punggung Mbah Menir yang sedang berjongkok mencuci piring. “Sudah, kamu di sini saja dulu. Jangan takut, biar simbah yang temui ayahmu.” kata Mbah Menir.
68 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mbah Menir menuju ke teras rumah dan mempersilahkan ayah masuk. “Bono di sini mbah?” tanya ayahku. “Iya, tapi..” belum selesai Mbah Menir bicara ayah hendak menuju dapur, dengan cepat Mbah Menir menahannya. “Ehhh tunggu dulu, duduk dulu!” kata Mbah Menir lembut. Aku tak berani keluar, aku hanya mengintip dari balik tirai yang menggantung di pintu dapur Mbah Menir. “Sudah, istigfar saja dulu. Tenangkan dirimu, baru aku perbolehkan kamu bertemu anakmu.” nasehat Mbah Menir kepada ayah. “Dasar anak nakal mbah, sudah diberi tahu jangan berkelahi. Wani-wanine nglanggar perintahku mbah.” kata ayah marah. “Ehhh namanya juga anak-anak. Lagi pula Bono seperti itu karena temannya yang mendahului. Dia sakit hati karena ejekan temannya. Tapi ra usah kuatir, tadi simbah sudah memberi tahu
69 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bono, mana yang benar, mana yang salah.” kata Mbah Menir bijak. “Sudah, simbah tak perlu ikut campur. Itu sudah kewajiban dan tanggung jawabku sebagai ayahnya.” kata ayah seraya berdiri dan menerobos masuk ke dalam dapur. Ayah mendapatiku tersudut diantara rak dan meja makan. “Heh
bocah
sontoloyo.
Ayo
pulang!”
suara
ayah
menggelegar. Ayah menarik tanganku. “Sabar Wan, dia masih kecil. Dia anakmu. Eling..eling.” Mbah Menir berusaha menahan, namun tubuh rentanya tak kuat menahan ayah yang berbadan kekar. Mbah Menir hanya menangisiku. Ayah semakin kesal karena aku coba menahan tarikan ayah. “Heh wani koe? Meh dadi preman? Iyo? Hah?” kata ayah semakin murka. Ayah yang sudah kehilangan kesabaran mengambil sebatang ranting dari pohon di depan rumah Mbah
70 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Menir dan terus dipukulkannya berkali-kali ke punggungku. Aku hanya bisa menangis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. “Ampun yah..ampun ayah..” kataku kesakitan, namun ayah tak menghiraukannya dan terus memukulku berkali-kali. Tetangga yang melihat kegaduhan itu hanya terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah cukup lama memukul-mukul punggungku dengan ranting. Sakit sekali. Ku rasakan darah mulai menetes dari kulitku yang terkelupas. “Sudah Wan, sudah! Kasihan Bono.” kata Mbah Menir menangis. Ayah pun menghentikan pukulannya, merasa puas telah menghukumku dengan sadis. “Putuku lanang. Kasihan sekali kamu le.” Mbah Menir segera menggendongku masuk ke dalam rumah, sementara ayah hanya terdiam mulai menyadari ia keliru. “Aduhhh, sakit mbah. Punggungku.” aku mengeluh. Mbah Menir membuka bajuku dan terperanjat melihat luka-luka di punggungku. Aku menangis kesakitan. Sambil menyiram lukaku
71 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dengan air, Mbah Menir ikut menangis. Aku menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukaku terkena air. “Mbah sudah mbah. Sakit. Pedih.” Belum sembuh luka di sikuku, muncul lagi luka-luka di punggungku. Rasanya hari itu aku benar-benar sedang celaka. Mbah Menir mengobati luka di punggungku dengan obat merah dan membalutnya dengan kain kasa. “Auw mbah. Sakit sekali. Rasanya seperti ayah masih saja memukuli Bono mbah.” kataku. “Sudah, malam ini kamu tidur di sini saja.” pinta Mbah Menir. Aku melihat ke arah ayah, yang terduduk seakan-akan menyesali perbuatannya. Mbah Menir melihat gerak gerikku yang meminta persetujuan ayah. “Malam ini Bono tidur di rumahku saja.” kata Mbah Menir pada ayah. Ayah melihat Mbah Menir dan mengangguk. Ayah sengaja membiarkanku tidur di rumah Mbah Menir. Mungkin
72 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dalam hatinya muncul perasaan tak tega melihat luka-luka yang aku alami karena perbuatannya. Tak lama ayah berpamitan pulang, ia terlihat lesu hingga kata maaf lupa ia utarakan. Langkahnya sangat berat, aku khawatir pada ayah. “Bono, istirahat saja di kamar simbah ya?” ajak Mbah Menir. Aku hanya mengangguk, menurut. Aku tidur tengkurap dan berharap ayah baik-baik saja. Dalam hati aku berkata, “Ayah maafkan Bono. Bono berjanji tidak akan nakal lagi. Tidak akan melanggar perintah dan nasehat ayah lagi. Bono tidak ingin di cambuk ayah lagi dengan ranting-ranting itu. Maafkan Bono ayah...” Mbah Menir setia menemaniku, mengusap keningku seraya menyanyikan tembang jawa. Aku tak mengerti apa judulnya, tapi terdengar sangat lembut, sejuk di hati. Hanya kalimat ”Lir ilir lir ilir ...” yang ku ingat. Tak terasa, air mata berlinang mengantarku terlelap tidur.
73 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
PAMAN SALIM & SAUDARA BARU
Sudah dua hari ini aku tinggal di rumah Mbah Menir. Bukan karena aku tak ingin pulang melainkan Mbah Menir menahanku. Menurutnya, tunggulah beberapa hari sampai ayah datang menjemput. Mbah Menir sudah menganggapku seperti cucunya sendiri, jadi aku pun tak sungkan dengannya. Terkadang aku mencuri waktu untuk pulang ke rumah sekedar menengok keadaan rumahku dari kejauhan. Terlihat sepi, mungkin ayah sedang melaut. Aku pun bergegas kembali ke rumah Mbah Menir, aku tak mau mengecewakannya. Aku turuti saja apa yang Mbah Menir katakan, pastinya Mbah Menir lebih tahu mana yang baik untukku. Seperti biasa, selesai membantu Mbah Menir mengerjakan pekerjaan rumah aku bermain di halamannya. Terkadang Ipung dan Ara menemaniku bermain di rumah Mbah Menir. Tapi kali
74 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
ini tidak, mungkin mereka sedang sibuk membantu orang tua masing-masing. Ku mainkan beberapa permainan sederhana hanya untuk menghibur diriku sendiri. Mbah Menir turut serta hanya untuk menemaniku bermain. Walaupun Mbah Menir sudah berumur 74 tahun, namun ia masih sangat fasih memainkan beberapa permainan tradisional. Aku lebih sering dikalahkan olehnya dalam memainkan beberapa permainan. Sore itu kami sedang asyik bermain suramanda. Di beberapa kesempatan, aku pernah memainkannya bersama teman-teman. Tetapi selalu ada saja yang mengejekku, terkadang aku ingin sekali menjadi orang lain. Menjadi Aceng yang berasal dari keluarga berada, ayahnya adalah pemilik kapalkapal untuk melaut. Ayahku pun bekerja kepada ayahnya. Hidupnya serba dicukupi oleh ayahnya, bahkan di beberapa acara, ayahnya mampu mengadakan panggung hiburan yang megah.
Tak
dipungkiri
lagi,
hidupnya
terjamin
apalagi
sekolahnya. Sungguh senang menjadi dirinya. Tapi kata ayah
75 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berdosa jika aku tak mensyukuri apa yang telah Allah berikan untukku. Ayah sangat melarangku untuk mengeluh. Ayah pernah berujar, “Jangan pernah mengeluh sedikit pun, karena kalau kamu mengeluh 1 detik saja, Allah juga akan menunda rezekimu 1 detik.” Kini hubunganku dengan ayah sedikit merenggang karena peristiwa yang lalu. Aku ingin sekali bertemu ayah, tapi aku masih takut padanya. Entahlah, esok atau lusa aku harus bertemu ayah, tentu saja jika Mbah Menir sudah mengijinkan. Aku duduk di salah satu batu besar di halaman rumah Mbah Menir, melihat Mbah Menir memainkan gilirannya bermain. Tiba-tiba seorang anak datang mendekati dan memanggil Mbah Menir. “Mbah…” dia menyapa kemudian mencium tangan Mbah Menir.
Mbah
Menir
menghentikan
permainannya
dan
mengamati anak itu. “Siapa ya?” “Ihsan mbah.” katanya.
76 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Owalah Ihsan? Cucu simbah.” kata Mbah Menir kemudian menggendongnya. Tak berapa lama orang tua anak itu datang dan mencium tangan Mbah Menir. “Apa kabar bu?” tanya ayah anak itu. “Baik, Alhamdulillah. Ada apa gerangan kamu pulang kampung, Lim?” tanya Mbah Menir. “Iya bu, rencananya kami sekeluarga akan tinggal disini. Karena saya dipindahtugaskan di kantor cabang Cilacap.” “Oh, yo syukur. Ibu jadi ada teman di rumah.” “Ini siapa, bu?” ayah anak itu melihat ke arahku. “Oh iya ini Bono. Anak Surati teman SD-mu.” “Owalah, sudah gede kamu jang?” kata ayah anak itu kemudian mengusap rambutku. Aku menatap Mbah Menir, meminta penjelasannya. Mbah Menir menatapku dan mengerti maksudku.
77 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, ini anak simbah. Salim namanya. Dulu Salim ini teman ibumu waktu SD. Waktu Salim berangkat ke Jakarta, kamu masih kecil. Jadi mungkin kamu lupa.” jelas Mbah Menir. “Ayo cium tangan dulu!” lanjutnya. Aku mencium tangan Paman Salim dan memperkenalkan diri, “ Saya Bono, paman.” “Ya ya, ini istri paman dan ini anak paman, Ihsan namanya.” kata Paman Salim memperkenalkan istri dan anaknya. Aku mencium tangan istrinya dan menjabat tangan Ihsan, anak Paman Salim. “Kelas berapa kamu jang?” tanya Paman Salim. Aku menggelengkan kepala. Kemudian Mbah Menir coba menjelaskan, “Begini Salim, Bono ini putus sekolah. Terakhir kali ia duduk di kelas V.” “Kenapa putus sekolah, bu?” tanya Paman Salim.
78 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya setelah ibunya meninggal. Ia putus sekolah karena masalah biaya.” jelas Mbah Menir. “Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Jadi Surati sudah meninggal bu?” tanya Paman Salim terguncang. Mbah Menir hanya mengangguk. “Tujuh tahun sudah saya meninggalkan kampung ini. Bekerja dan tinggal di Jakarta. Tak tahu kabar di sini.” kata Paman Salim. “Kasihan anak ini. Tak ada yang mengurusnya.” kata Mbah Menir memelukku. “Kemana Kang Ridwan, ayahnya?” tanya Paman Salim. “Ridwan seperti biasa, melaut. Ia bertemu ayahnya seminggu mungkin hanya tiga kali karena ayahnya sibuk di laut. Kalaupun di rumah, ayahnya sibuk membetulkan jaring.” jelas Mbah Menir. “Kasihan kamu jang. Paman ada sesuatu, ini terima.” Paman Salim menyodorkan selembar lima puluh ribu rupiah.
79 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Untuk apa paman?” “Untukmu Bono, anggap saja hadiah dari paman.” Paman Salim tersenyum. Aku bingung, aku tak ingin menolak namun ayah pernah berpesan jangan menerima hadiah apapun dari orang lain. Aku pun menggelengkan kepala. “Kenapa?” “Ayah melarang Bono menerima hadiah dari orang lain paman.” kataku tak enak hati. “Paman bukan orang lain, paman ini anak Mbah Menir, kalau kamu menganggap Mbah Menir sebagai nenekmu, tak ada salahnya kan kalau kamu menganggap Paman Salim sebagai pamanmu?” kata Paman Salim ramah. “Lagipula, paman kan teman karib ibumu Bono. Sudahlah terima saja.” tambahnya. “Tidak paman. Terima kasih.” Aku bertahan pada keputusanku. Paman Salim menatap dalam mataku kemudian ia
80 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berkata, “Apa yang harus paman lakukan agar kamu mau menerima uang ini?” Aku berpikir sejenak. “Bagaimana kalau Bono bekerja untuk paman? Pekerjaan apapun asal halal akan Bono lakukan paman.” Paman Salim tersenyum. “Ya ya, baiklah. Boleh paman lihat nilai-nilai saat kamu sekolah dulu?” “Untuk apa paman?” kataku heran. “Katanya
kamu
mau
bekerja,
paman
tidak
bisa
mempekerjakanmu kalau nilai-nilaimu di sekolah tidak baik.” jelas Paman Salim. “Ada di rumah, paman. Tapi Bono belum berani ke rumah.” “Lho, kenapa?” Aku melihat Mbah Menir, berharap ia mau membantuku menjelaskannya pada Paman Salim.
81 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ohh begini Lim, beberapa hari yang lalu Bono dihukum oleh ayahnya. Karenanya, ia masih takut untuk bertemu ayahnya.” jelas Mbah Menir. “Begitu? Mau paman antar?” Sekali lagi aku melihat Mbah Menir. Ia mengangguk, pertanda ia mengijinkanku pulang ke rumah. “Ayo jang!” ajak Paman Salim. Aku dan Paman Salim pergi menuju rumahku. Sementara Mbah Menir menemani istri dan anak Paman Salim di rumahnya. Sesampainya di rumah. Aku mengetuk pintu rumahku namun tak ada yang membukanya. Coba ku raih kait rantai yang menahan pintu dan ku buka. Ternyata tak ada seorang pun. Dengan hati bingung, aku mempersilahkan Paman Salim duduk. “Silahkan duduk paman.” “Oh ya, Terima kasih.” “Sebentar Bono cari rapor Bono dulu, paman.” “Ya silahkan, cari saja dulu tak perlu terburu-buru.”
82 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Ku acak-acak tumpukan buku di salah satu rak mejaku. Beberapa menit kemudian aku menemukan buku raporku. Ku serahkan buku rapor itu kepada Paman Salim. “Ini paman rapor Bono, sudah rusak tapi masih terlihat jelas tulisannya.” kataku malu menunjukan rapor itu. Paman Salim terlihat mengamatinya dengan seksama kemudian ia tersenyum. “Nilai rapormu bagus Bono?” “Terima kasih paman, tapi Bono paling suka pelajaran matematika.” “Kenapa kamu tidak melanjutkan Kejar Paket A saja?” “Kejar Paket A itu apa paman?” aku bingung baru mendengar. “Kamu belum tahu? Kejar Paket A itu ya sama dengan sekolah SD, hanya saja Kejar Paket A dikhususkan untuk orang yang putus sekolah seperti kamu, Bono.” “Tapi apa ayah Bono sanggup membiayainya, paman?”
83 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Begini saja, kamu tidak perlu khawatir. Kamu paman bantu ikut Kejar Paket A, tapi kamu harus bantu Ihsan selama ia bersekolah disini. Kebetulan sekarang ia naik kelas V. Kamu masih ingat pelajaranmu waktu kelas V?” “Masih, paman. Walau sudah tidak bersekolah, Bono masih sering baca buku-buku sekolah Bono.” “Nah, kalau begitu bantu dia belajar dan temani bermain, bagaimana?” “Paman, Bono tanya ayah dulu ya?” “Iya Bono tak perlu buru-buru. Nah, sekarang simpan saja buku rapormu. Lagipula kamu belum cukup dewasa untuk bekerja seperti paman.” “Baik paman!” kataku kemudian menyimpan buku raporku kembali. Tiba-tiba dari arah pintu ayah muncul. Ku lihat tubuhnya lunglai, mukanya pun pucat. “Bono, ini siapa?” kata ayah.
84 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ini Paman Salim yah, anak Mbah Menir, katanya teman ibu juga dulu.” kataku menjelaskan. Paman Salim menoleh ke arah ayah kemudian tersenyum. “Oh, Salim? Piye kabare?” kata ayah seraya tertawa lebar dan memeluk Paman Salim. “Ya ya, aku baik- baik saja. Bagaimana denganmu, kang?” tanya Paman Salim. “Ya, cukup sehat. Hanya saja pandanganku mulai kabur jadi dari pintu tadi aku kurang jelas melihatmu.” kata ayah menepuk bahu Paman Salim. “Silahkan duduk!” lanjut ayah. “Dapat apa hari ini, kang?” tanya Paman Salim. Kakang (kakak) adalah sebutan akrab Paman Salim kepada ayah. Mereka berdua terlihat sangat akrab, seperti dua sahabat yang lama tak jumpa. “Yahh, cuma dapat ikan layur. Itu pun tak sebanyak biasanya Lim. Kamu bagaimana di Kalimantan? Wah wis dadi wong penak saiki yo? Hahaha.” kata ayah.
85 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hahaha. Kang Ridwan bisa saja. Ya, Alhamdulillah, kang. Rejeki saya di luar kota, tapi sebentar lagi rejeki saya tak jauh dari sini.” kata Paman Salim. “Maksudmu?” tanya ayah heran. “Iya, tak lama lagi saya dipindahtugaskan di Cilacap, kang. Jadi lebih bisa dekat dengan ibu. Sebenarnya di kota sudah disediakan rumah. Tapi tidak saya ambil. Saya lebih memilih tinggal di sini, kasihan ibu sudah tua, kang.” jelas Paman Salim. “Malah bagus to? Kuwi jenenge anak eling wong tuo, ora elok ngorbanke wong tuo mung nggo urusan dunyo. Toh nanti kita juga bakal tua Lim, kalau bukan anak, siapa yang mau peduli tur ngopeni kita.” kata ayah menasehati seraya menyalakan rokok 234 kesukaannya. “Bukannya sekarang kita sudah tua, kang?” canda Paman Salim seraya menepuk siku kanan ayah. “Wah, iya ya? Gara-gara ketemu kamu, aku jadi merasa masih muda, Lim.” balas ayah.
86 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hahaha. Kang Ridwan bisa saja.” Paman Salim sungkan. Sekitar 45 menit mereka asyik berbincang-bincang. Sementara itu, aku hanya duduk di dekat meja makan memperhatikan mereka. “Oh ya, begini kang. Saya mau minta ijin, berhubung Ihsan mau sekolah disini, kebetulan juga naik kelas V. Saya meminta Bono untuk mengajari dan menemani Ihsan selama disini. Nantinya, Bono saya bantu sekolah kejar Paket A. Bagaimana kang?” kata Paman Salim meminta izin. “Sssttt. Ora usah repot-repot. Kalau mengajari dan menemani
anakmu
boleh-boleh
saja
Lim.
Tapi
harus
membebanimu untuk menyekolahkannya, ndak usah.” kata ayah seraya menggoyangkan telapak tangannya. “Tapi kang, Bono anak yang pintar. Dia ingin melanjutkan sekolahnya. Saya pun tak keberatan kang.” kata Paman Salim berusaha meyakinkan ayah.
87 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Begini ya lim. Kamu itu kan harus menyekolahkan anakmu juga, belum lagi harus mencukupi kebutuhan rumah tangga. Iya sekarang kamu masih sanggup, lha nanti kalau kamu mulai kesulitan. Apa ndak yang repot aku juga? Bono juga kasihan harus putus sekolah lagi. Wis ben, anakku dadi nelayan wis apik koq.” jelas ayah menolak permintaan Paman Salim. “Iya memang benar kita tidak tahu bagaimana nanti. Tapi rezeki Allah yang mengatur kang. Insya Allah saya sanggup menyekolahkan Bono sampai lulus tingkat SD, bahkan kuliah bersama Ihsan.” Paman Salim sedikit memaksa. “Ya sudah, terserah kamu saja lim. Tapi aku cuma minta, jangan pernah menyesal sudah menyekolahkan Bono.” kata ayah. Tiba-tiba ayah batuk hebat. Tangan kirinya memegang kencang lehernya menahan batuk di tenggorokannya. Ayah terlihat membungkuk-bungkuk karena batuk itu.
88 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, ambilkan air minum untuk ayahmu!” Paman Salim segera menyuruhku mengambilkan air minum. Aku berlari menuju dapur dan ku ambilkan air minum untuk ayah. “Ya, sudah-sudah. Aku sudah tidak apa-apa.” kata ayah. “Bono, bilang terima kasih pada Paman Salim.” perintah ayah. Aku segera menjabat tangan Paman Salim dan menciumnya. “Terima kasih paman.” kataku. “Iya Bono. Jangan kecewakan paman ya? Buat paman bangga dengan prestasimu nanti.” kata Paman Salim. Aku hanya mengangguk. “Wah anakku sekolah meneh. Sing rajin yo le. Ayah cuma bisa kasih doa semoga kamu jadi anak yang sukses. Ndak seperti ayahmu.” kata ayah setengah tersenyum, ku lihat matanya berkaca-kaca. “Iya yah.” ku peluk tubuh ayah, ia membalasnya erat sekali. Paman Salim mengusap-usap punggungku. Seketika Paman Salim sudah seperti orang tuaku saja.
89 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Akhirnya keinginanku melanjutkan sekolah terkabul. Tak henti-hentinya ku ucapkan hamdallah sebagai tanda syukurku pada Allah yang telah mendatangkan Paman Salim untuk membantuku. Disisi lain, kini aku punya saudara baru. Ya, dialah Ihsan anak Paman Salim. Saudara dari kota dan yang pasti dia tidak jahat padaku seperti teman-teman kebanyakan. Aku sudah tak sabar ingin mengenalkan Ihsan kepada dua teman baikku, Ipung dan Ara. Kini aku memiliki saudara baru, Ihsan saudara dari ibu kota.
90 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
TEMAN
Pagi ini aku sangat senang. Karena hari ini aku mulai melanjutkan sekolahku. Walau hanya masuk kejar paket A di sebuah sanggar belajar, namun aku sudah sangat bersyukur. Paling tidak cita-citaku menjadi guru kembali terbuka. Aku berangkat bersama Paman Salim dan Ihsan. Kami berboncengan mengendarai motor Paman Salim. Seperti halnya aku, hari ini adalah hari baru untuk Ihsan. Ini hari pertamanya masuk sekolah baru setelah pindah ke kampung ini. Kebetulan jarak sekolahnya dan sanggar belajarku hanya berjarak 200 meter, karena itu kami berangkat bersama. Walau bukan sekolah formal, tapi sanggar belajar ini benarbenar hebat. Paman Salim tidak salah memilihkanku tempat ini, ia juga membelikanku tas, sepatu, baju sampai buku-buku baru untukku. Aku menyukai semua yang Paman Salim belikan.
91 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Begitu juga teman-teman baruku, aku suka bergaul dengan mereka, mereka sangat baik padaku. Tak terasa aku sudah begitu akrab dengan beberapa teman baru. Bel tanda pulang dibunyikan, aku pulang bersama 2 orang teman baruku Widi dan Dani. Sebelumnya, aku dan Ihsan dijanjikan akan dijemput oleh Bibi Salim, istri Paman Salim. Ku lihat Bibi sudah menunggu di depan sekolah Ihsan. Aku sengaja meminta ijin padanya untuk pulang bersama teman baruku karena ia harus menunggu Ihsan pulang, baru kami bisa pulang bersama. Ku pikir daripada menunggu, lebih baik aku pulang lebih dahulu sekaligus agar lebih dekat dengan teman baruku, Widi dan Dani. Ya, sekolah formal dan sanggar belajar memang memiliki waktu belajar yang berbeda. Aku pulang lebih dulu daripada Ihsan. Ketika pulang sekolah aku, Widi dan Dani melewati sebuah kebun milik sanggar. Saat itu kami melihat buah mangga yang ranum menguning bergelantungan.
92 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hai, lihat mangganya banyak yang sudah matang!” kata Widi sambil menunjuk ke salah satu pohon mangga. “Kita ambil saja yuk!“ ajak Dani. “Enggak ah, aku takut! “ sahutku. ”Nanti kalau ketahuan orang bagaimana?” “Ah, dasar kamu. Nyalinya kecil.“ sahut si Widi. Mendengar ucapan Widi, akhirnya aku terhasut. Aku menyetujui ajakan mereka, tentunya jantungku berdegub kencang. Dengan hati-hati, kami memanjat pagar bambu yang mengelilingi kebun. “Hati-hati, ada pakunya.” bisik Widi. “Tolong pegang tas-ku, Dan.” perintahku pada Dani. Kemudian aku memanjat dinding bambu itu. “Sini, lempar tas-ku.” perintahku lagi pada Dani. Dani melempar tas milik kami bertiga ke dalam kebun kemudian ia masuk ke dalam kebun diikuti Widi.
93 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Kemudian kami memanjat pohon mangga itu bersamaan. “Hai hati-hati memanjatnya!” Widi memperingatkan kami. Ketika sampai di atas, kami menemukan pemandangan yang menakjubkan. Betapa tidak? Di dalam kebun, kami tidak hanya menemukan mangga yang membuat air liur mengalir, tetapi kami juga melihat kolam ikan yang cukup luas. Ketika kami asyik mengamati, tiba-tiba muncul seseorang yang meneriaki kami untuk turun. “Hai, turun!” Dengan segera kami turun dari pohon itu dan mengambil langkah seribu. “Lari......” teriak Widi mengomandoi kami. Dalam perjalanan pulang kami membahas kejadian tadi. “Untung saja tadi tidak ditangkap oleh orang itu, kalo tertangkap bisa habis kita. Belum lagi kalau ayahku tahu.” kataku terengah-engah ketakutan. “Baru segitu saja sudah takut, itu belum apa-apa. Besok kita ambil mangganya.” kata Widi.
94 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya aku setuju, bagaimana denganmu Bon?” kata Dani seraya menyikut lenganku. “Ah
kalau
sampai
tertangkap
bagaimana?”
kataku
khawatir. “Bukan apa-apa, ayahku galak.” tambahku. “Kali ini tidak akan ketahuan, kita cepat-cepat ambil mangganya sebelum ada orang yang melihat kita.” kata Widi. “Tapi..” belum selesai aku bicara, Dani memotong. “Alah bilang saja kamu tak punya nyali Bon.” Untuk kedua kalinya aku terhasut, tak mau diremehkan. Karena belum sempat mengambil sebiji pun buah mangga, kami sepakat untuk menyelinap masuk ke dalam kebun esok harinya. Esok harinya, seperti biasa kami belajar dalam kelas. Setelah menghabiskan waktu 6 jam. Guru kami sedang bersiapsiap untuk mengakhiri pelajaran hari itu. ”Anak-anak, tugas latihan yang hari Senin kemarin sudah bapak periksa. Ada yang bagus ada yang kurang bagus nilainya. Bagi anak-anak yang kurang bagus, bapak memberi kesempatan
95 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
untuk memperbaiki nilai. Kalian kerjakan soal di halaman 14 buku cetak matematika. Mengerti?” “Mengerti pak!” kami menjawab serentak. “Baik. Ini bapak bagikan hasil tugas latihan kemarin.” kata pak guru kemudian memanggil nama siswanya satu per satu. “Semua sudah mendapat hasilnya ya?” kata pak guru. “Sudah pak!” sekali lagi kami kompak menjawab. “Ya sudah, kalau begitu ketua kelas memimpin doa pulang!” perintah pak guru. Setelah berdoa kami semua pulang dan tak lupa mencium tangan pak guru sebelum meninggalkan kelas. Sesuai kesepakatan kemarin, aku, Widi dan Dani kembali memasuki kebun mangga milik sanggar. “Hei Bono, tugasmu berjaga saja disini. Beri tahu kami jika ada orang yang datang. Sementara aku yang memanjat dan memetik buah mangga lalu Dani yang menangkapnya dari bawah. Bagaimana?” kata Widi menjelaskan rencananya.
96 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kita pilih dulu saja pohon yang akan kita panjat.” usul Dani. “Kamu disini saja, aku dan Widi mau mencari-cari pohon yang akan kita panjat.” tambahnya. Aku hanya mengangguk. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisku, terus terang aku takut. Tapi aku tak mau diremehkan oleh mereka. Saat sedang berjaga tak jauh dari pagar bambu, Widi mengagetkanku dengan suaranya. “Bono, kemari!” kata Widi setengah berteriak. “Ada apa?” kataku mendekat. “Lihat ada sarang burung di atas sana.” kata Widi seraya menunjuk segumpal sarang burung di ujung salah satu pohon. “Kamu berani ambil sarang burung itu, Wid?” tanyaku. “Aku berani tidak sepertimu yang penakut.” katanya. “Ahh siapa takut, aku berani memanjat pohon ini hingga ke ujung.” kataku tak terima disepelekan. “Baik. Bagaimana kalau kita taruhan, siapa yang lebih dulu mendapatkan sarang burung itu, dia yang menang. Dan yang
97 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
kalah, harus memberikan semua uang sakunya hari ini pada yang menang.” kata Widi menantangku. “Siapa takut, tapi biar adil, kita titipkan uang saku kita pada Dani dahulu. Bagaimana?” saranku. “Baik. Dan, ini pegang uang saku kami. Awas kalau sampai hilang 100 rupiah saja, uang sakumu yang akan kami ambil.” kata Widi mengancam. “I..iya Wid, aku jaga.” kata Dani seraya memasukkan uang saku kami ke dalam saku bajunya. Kami bersiap. Aku melepas sepatuku dan menekuk celana panjangku ke atas. Dani memberi aba-aba. “Siap? Tiga Dua Satu Mulai!” Seketika aku dan Widi melompat menaiki pohon itu. Widi terlihat cepat sekali meraih dahan dan melangkahkan kakinya naik ke atas pohon. Aku tak mau kalah, ku percepat gerakanku layaknya Tarzan. Kami berdua sangat cepat mendekat pada sarang burung itu. Aku hampir berhasil meraih sarang burung itu
98 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
tapi tangan Widi lebih cepat. Spontan ku tarik lengannya dan meraih sarang burung itu. Tiba-tiba “Ahhh” Widi berteriak dan jatuh ke tanah. Tubuhnya keras menghantam tanah, aku panik. Aku bersegera turun dan mendekati Widi yang sudah menggelinjang kesakitan. “Wid, maaf aku tak sengaja.” kataku cemas. Widi tak menjawab hanya mengerang kesakitan. Ku peluk tubuhnya dan menangis, ku ucapkan maaf berkali-kali. Aku menyesal. “Toloonggg..toloongg..”
Dani
berteriak
meminta
pertolongan pada orang yang berlalu lalang di dekat kebun. Tak lama pembina sanggar datang. Ia dan beberapa orang menggendong Widi dan membawanya ke Puskesmas terdekat. Aku terdiam penuh penyesalan. “Bono, kenapa kamu buat Widi jatuh?” kata Dani menghakimi. Kerumunan manusia tanpa komando juga mulai bising membicarakanku.
99 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Aku tak sengaja, sungguh. Aku tak tahu kalau tindakanku membuatnya jatuh.” kataku sedih. Dani yang harusnya menenangkanku justru memasang wajah ketus dan pergi meninggalkanku. Aku berlari mendahului Dani, menuju orang-orang yang menggendong tubuh Widi. Sesampainya di Puskesmas, Widi mendapat perawatan intensif. Beberapa jam menunggu, dokter yang menangani Widi keluar dan menjelaskan bahwasanya Widi baik-baik saja. Hanya tangannya retak, perlu istirahat. “Sudah kalian pulang saja! Orang tua Widi sudah datang.” perintah pembina sanggar. “Baik, bu.” Widi pergi meninggalkanku. Sementara itu, Paman Salim menemui ayahku di rumah. “Kang, kang sudah dengar belum kejadian tadi di sanggar?” kata Paman Salim panik. “Ono opo to?” kata ayah kebingungan.
100 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Anakmu tadi bermain di kebun mangga milik sanggar. Dan yang aku dengar, dia membuat temannya jatuh dari pohon mangga. Sekarang temannya ada di Puskesmas kampung.” kata Paman Salim panik. “Aku bilang apa Lim? Anak itu tidak perlu sekolah lagi, cuma bikin repot kamu to?” kata ayah dengan wajah menahan marah. “Bukan kang. Bukan itu yang aku khawatirkan, namanya musibah, siapa yang tahu? Maksudku, apa benar kabar tersebut? Mungkin Kang Ridwan lebih tahu.” jelas Paman Salim. “Ah mbuh. Ra sah dipikir Lim.” kata ayah ketus. Paman Salim mendekat, merangkul pundak ayah. Ia tahu bahwa sebenarnya ayahku sangat mengkhawatirkanku, hanya saja ia tak mau terlihat lemah dengan memanjakanku. Saat mereka sedang berbincang-bincang di rumah, aku sedang dalam perjalanan pulang. Dengan langkah gontai aku pulang menuju rumah. Bajuku kusut, basah dimana-mana karena
101 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
peluh yang menetes deras dari sekujur tubuh. Sesekali aku menengok ke kiri dan ke kanan, tetapi kepalaku lebih sering menunduk, menghitung jumlah kerikil di jalan yang sedang ku lewati. Rasa bersalah terus menghantuiku. Belum lagi kalau ayah atau Paman Salim tahu, aku panik. Benar saja, belum sampai rumah ku lihat dua sosok bertubuh tegap berdiri di depan rumah, mereka adalah ayah dan Paman Salim. Tak sadar tanganku meremas-remas ujung baju hingga tak berbentuk lagi, aku takut. “Bono, sini jang!” Paman Salim memanggilku seraya mengayunkan tangannya. Ayah hanya diam terpaku. Aku mendekat. “Ada apa Paman?” tanyaku gemetar. “Ganti bajumu dulu, setelah itu makan. Paman sudah belikan ayam goreng untukmu.” kata Paman Salim ramah menyambutku. Ku lihat ayah masih saja berdiri, kali ini ia menyalakan rokok di mulutnya.
102 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Sikap Paman Salim melunturkan dugaanku. Ku ganti bajuku yang sudah lengket berkeringat, kemudian makan dengan lahapnya.
Paman
Salim
memperhatikanku
kemudian
ia
tersenyum. Sementara ayah masih diluar menghabiskan rokoknya. “Sudah makannya?” tanya Paman Salim. “Sudah Paman.” kataku puas kekenyangan. “Cuci piringmu, lalu temui paman di sini ya? Ada yang ingin paman berikan padamu.” kata Paman Salim dengan gaya ramahnya yang khas. Setelah mencuci piring, aku menemui Paman Salim. “Ada apa paman?” “Ini tolong berikan pada temanmu yang jatuh dari pohon tadi. Paman sudah dengar ceritanya dari Ihsan.” katanya. Paman Salim menyodorkan amplop berisi uang yang tak ku tahu berapa jumlahnya. Lagi-lagi Paman Salim membuatku terharu.
103 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Terima kasih paman, maaf Bono selalu merepotkan.” kataku sungkan. “Mbok yo sadar to le! Kamu itu sudah disekolahkan sama pamanmu. Jangan buat yang macem-macem. Sekarang sudah begini, pamanmu lagi yang repot. Kamu tahu to bapakmu cuma nelayan miskin? Ndak usah banyak tingkah!” ayah memotong ucapanku. “Sudah kang, tidak apa-apa. Bono kan sudah saya anggap seperti anak sendiri.” kata Paman Salim menenangkan suasana. “Yo wis. Terserah kamu lah Lim. Tapi aku sebagai ayahnya jadi ikut sungkan sudah banyak merepotkan kamu Lim.” kata ayah seraya membuang puntung rokoknya. “Sudah-sudah kang. Jangan berlebihan.” kata Paman Salim tersenyum. “Bono, sekarang kamu antarkan uang ini kepada temanmu itu, kalau malu ajak Ihsan atau temanmu yang lain.” Aku hanya mengangguk, kemudian berpamitan mencium tangan Paman Salim dan ayah. Aku pergi bersama Ihsan, Ipung
104 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dan Ara. Sesampainya di Puskesmas, ku lihat Dani sudah ada disana. Wajahnya masih ketus melihatku, ku beranikan diri masuk dan menjenguk Widi yang sudah membaik. “Wid, bagaimana keadaanmu?” kataku lirih. “Ah cuma retak saja koq, seminggu juga sudah bisa main bareng lagi Bon.” katanya tersenyum. “Maafkan aku ya Wid, aku benar-benar tak sengaja dan menduga hal ini akan terjadi.” kataku menyesal. “Ahh sudah, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti Bon. Namanya juga musibah, iya kan?” katanya lembut. “Emm..ini aku mau memberikan ini, untuk membantu biaya pengobatanmu Wid.” kataku menyerahkan amplop itu. “Apa-apaan Bon? Enggak usah. Kamu mau jenguk saja aku sudah senang.” kata Widi menolaknya. “Eh tapi ini amanah dari pamanku. Tolong diterima saja biar jadi berkah.” kataku memohon.
105 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya sudah, aku terima. Terima kasih ya, salam buat pamanmu.” kata Widi bersedia menerima amplop itu. Aku mengangguk. “Oh iya, ini anak Paman Salim. Ihsan namanya, kemudian ini Ipung dan Ara teman baikku di kampung.” kataku memperkenalkan Ihsan, Ipung dan Ara pada Widi. Mereka berjabat tangan. Dani masih terlihat ketus. Belum bisa menerima apa yang terjadi pada teman baiknya, Widi. Widi melirik ke arah Dani. “Hei Dan, mukamu masih ditekuk saja? Apa bedanya mukamu dengan terpal kaki lima kalau masih saja seperti itu? Sudahlah, maafkan saja Bono!” canda Widi. Kami menahan senyum, termasuk Widi. Kemudian ku ulurkan tanganku lebih dulu. “Dan, kamu mau memaafkanku kan?”
106 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Dani mengangguk, kemudian memelukku. “Maafin aku juga Bon, aku sudah sempat memusuhimu. Kamu orang yang baik. Maaf.” “Iya, sekarang kita berenam adalah teman. Harus saling menjaga satu sama lain. Terutama menjaga Ara karena ia satusatunya perempuan. Bagaimana?” kataku bersemangat. Mereka
saling
memandang.
“Aku
setuju.”
Widi
mendahului. Diikuti Dani, Ihsan, Ipung dan juga Ara. Tawa canda hari ini menambah kesempurnaan kebersamaan kami. Karena kejadian itu pula, aku merasa memiliki teman yang sangat berarti bagiku. Dulu aku hanya berteman dengan Ipung dan Ara, kini temanku bertambah. Dani, Widi dan tentu saja Ihsan, kini ku sebut mereka berlima sebagai teman.
107 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
MASALAH BARU
Hari ini Widi sudah diijinkan untuk pulang ke rumah, hanya saja ia masih harus beristirahat. Kami menemaninya pulang dari Puskesmas. Kami hanya berjalan kaki menuju rumah Widi, orang tua Widi mengikuti kami dari belakang. Widi terlihat sangat senang walau tangannya harus dibalut perban dan kayu penopang. “Wid, lihat deh tanganmu udah kaya tangan Robocop saja, hahaha.” celoteh Dani. “Gundulmu! Sekali lagi bilang begitu, ku adu mulutmu dengan tanganku ini.” balas Widi. Mendengar Widi menggertak, Dani mulai salah tingkah. Kami menertawainya. “Hahaha. Aku gertak begitu saja sudah pucat mukamu Dan.” kata Widi menggoda.
108 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ah kamu Wid, tadi kan aku cuma bercanda.” kata Dani membela diri. “Tenang saja Dan. Aku tidak akan tega kepada temantemanku sendiri. Apalagi kamu, tanpa ku hajar saja wajahmu sudah babak belur permanen, hahaha.” kata Widi meledek. “Oh jadi skor kita sudah 2-1 nih?” kata Dani seraya merangkul Widi. “Auw..sakit! Tanganku.” teriak Widi. “Aduhhh kacian yang tangannya dibungkus seperti nangka yang mau matang, atit ya?” kata Dani kemudian mengelus dan meniup tangan Widi. “Ah minggir. Bisa-bisa tanganku tetanus.” kata Widi. “Ah kamu pikir nafasku ini mengandung bakteri Wid?” kata Dani cemberut. “Hei sudah, sudah. Kalian ini, dari tadi bertengkar terus.” kata Ara memotong. Mereka saling memandang kemudian membuang muka.
109 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Eh Wid. Rumahmu masih jauh?” tanyaku. “Ya sekitar satu setengah kilo lagi. Kenapa? Kakimu mau patah?” canda Widi. “Ah kamu Wid. Tangan belum juga sembuh masih saja bercanda seperti itu. Kualat lho?” kataku. “Iya nih, Widi memang seperti itu. Mentang-mentang badannya paling besar diantara kita berenam.” imbuh Dani. “Lho? Bukannya bagus? Jadi kalau ada yang mengganggu kalian biar aku saja yang menghadiahi mereka dengan tinjuku. Tapi tunggu tanganku sembuh dulu ya?” kata Widi. “Huuuu...” kami berlima bersorak. Kami larut dalam canda dan tawa. Tak terasa kami sampai di rumah Widi. Rumahnya cukup besar, aku yang baru pertama kali kerumahnya terdiam sesaat memuji keindahan rumahnya. “Ayo anak-anak, masuk saja.” teriak ayah Widi dari arah belakang. “Ayo, masuk!” ajak Widi.
110 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Wid, rumahmu besar.” kataku terkagum-kagum. “Ini bukan rumahku, tapi rumah orang tuaku. Besok kalau aku sudah besar, rumahku akan jauh lebih besar dari ini.” kata Widi bangga. “Kamu mau tinggal di goa, Wid? Rumah sebesar ini saja sudah luar biasa, eh ini mau lebih besar lagi!” kata Dani. Kami semua tertawa. Mereka berdua memang seperti itu, suka saling ejek tapi hanya untuk candaan saja. Tak lama beberapa gelas es teh tersaji di depan kami, sepiring kue bolu tak lupa menemani dinginnya es teh itu. “Ayo, dimakan kuenya. Tak usah malu-malu.” kata ibu Widi. “Terima kasih, bu.” Kami kompak dan serentak berebut mengambil kue bolu lebih dulu. “Kalian sudah berapa lama tak makan?” kata Widi dengan mimik heran.
111 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Wajar Wid, kue ibumu kan enak. Baunya saja sudah bikin air liur kami mengalir, apalagi rasanya emmmm.” kata Ihsan. “Kamu mau Wid? Ini aku suapi.” kata Ipung tiba-tiba menyodorkan sepotong kue ke mulut Widi. “Ahh apa-apa’an sih Pung? Aku makan sendiri.” kata Widi cemberut. “Cieeee..ternyata Ipung memendam rasa pada Widi.” kata Dani menggoda. Kami tertawa. “Hei..Ipung itu laki-laki dan aku masih normal tahu!” kata Widi seraya melempar potongan kue bolu ke arah Dani. “Wid, orang tuamu kan tergolong kaya. Terus kenapa kamu malah ikut Paket A, bukan sekolah biasa seperti Ihsan?” tanyaku penasaran. “Ohh..jadi dulu aku pernah bersekolah di SD tak jauh dari sini. Tapi karena aku sering berkelahi dengan teman sekelasku, akhirnya aku dikeluarkan. Kalau masuk sekolah normal, aku malu Bon. Mau bagaimana lagi? Orang tuaku memutuskan untuk
112 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
menyekolahkanku ke Paket A di sini. Tapi tak masalah, karena sekarang aku punya geng baru. Hahaha.” Kata Widi. “Geng? Boleh juga. Mau kita kasih nama apa geng kita Wid?” kata Ipung. “Bagaimana kalau Geng Antik?” kata Ara. “Apa artinya, Ra?” tanya Ihsan. “Geng Anak Cantik.” kata Ara sumringah. “Kamu pikir kita semua cantik, Ra?” kata Dani. “Oh iya, kan cuma aku yang cantik.” kata Ara tersenyum manja. “Wuuuu..” kami bersorak. “Bagaimana kalau Anker? Artinya Anak Keren. Kesannya juga seram.” kata Widi. “Wah, bagus tuh. Aku setuju!” kata Dani. “Aku juga!” kataku. Kemudian yang lain ikut menyetujui nama geng kami.
113 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Mulai sekarang kalau salah satu dari kita ada yang kesusahan harus kita bantu, kalau ada yang sedih kita hibur dan kalau ada yang senang harus berbagi dengan anggota geng lainnya. Bagaimana?” kata Widi. “Satu lagi Wid, bagaimana kalau kamu ketua geng-nya? Kan badanmu paling besar.” kataku. “Oke. Aku setuju.” kata Widi. Tak terasa kami terlibat perbincangan hebat tentang geng dan sesekali kami tertawa karena candaan Dani dan Widi. Hari mulai senja, kami berpamitan pulang. Ditengah jalan kami berpisah. Ara dan Dani berjalan ke arah utara sementara aku, Ipung dan Ihsan ke arah timur. “Bon, mulai hari ini enggak akan ada yang berani ganggu kita. Kita sudah punya Geng.” kata Ipung. “Iya, tapi bukan berarti kita mau cari musuh lho! Kita bikin geng kaya gini kan biar lebih akrab saja, bisa saling bantu dan lainnya.” kataku.
114 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono benar Pung.” Ihsan menimpali. Ipung hanya mengangguk-angguk. “Tunggu sebentar!” kataku menghentikan langkah melihat sesuatu yang sepertinya ku kenal. “Ada apa, Bon?” kata Ipung heran. Tanpa aba-aba aku lari ke arah rerumputan tak jauh dari jalan yang kami lalui. Ipung dan Ihsan mengikuti, mereka heran dengan tingkahku. “Kamu mencari apa, Bon?” kata Ihsan. “Itu, kamu lihat?” kataku menunjuk sesuatu. “Itu Doreng kan, Bon?” kata Ipung. “Doreng?” Ihsan bingung. “Doreng itu kucing kesayangan Bono yang hilang beberapa waktu yang lalu, San.” Ipung menjelaskan. Kemudian kami bertiga mendekati seekor kucing yang mirip sekali dengan Doreng. Ku lihat dengan jelas bekas luka
115 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dikepalanya sama persis seperti bekas luka di kepala Doreng. Tiba-tiba kucing itu lari menuju arah sungai kecil. “Pung, kamu cegat dari arah kanan! Kamu dari arah kiri, San!” perintahku pada Ipung dan Ihsan. Kami mengepung kucing itu dari 3 arah berbeda, ia terdesak. “Sini kucing manis, tak usah takut. Aku yakin kamu Doreng, sini sini..pus pus pus pus.” kataku agar ia tak takut. Semakin dekat ku lihat, semakin yakin kalau kucing itu adalah Doreng. Aku bersiap menangkapnya, ku ayunkan tangan dengan cepat dan “Auww” kucing itu mencakar lengan kananku kemudian lari. “Kamu baik-baik saja, Bon?” tanya Ipung. “Sakit tahu, cepat kejar saja kucing itu!” kataku kemudian lari mengejar kucing itu. Ia lari menuju rumah Mak Nasib. Ku lihat Mak Nasib sedang menjemur ikan asin seperti yang biasa ia lakukan. Secepat kilat kucing itu menyambar sebuah ikan asin yang sedang dijemur.
116 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono...kucingmu sudah bosan hidup ya!!!” teriak Mak Nasib marah. Kini aku yakin 100% kalau itu adalah Doreng. “Maaf mak..” kataku sambil terus lari mengejar Doreng. Aku dan Ipung tetap lari mengejar Doreng, sementara Ihsan sudah tertinggal karena mulai kelelahan. Sampailah kami disuatu semak, ku lihat Doreng masuk ke dalamnya. “Bon, itu dia masuk ke semak kering disitu.” Kata Ipung. “Ssstt diam, nanti dia lari lagi. Kamu siap disisi sebelah sana, siapa tahu dia lari.” kataku. Ipung mengangguk dan segera menuju ke sisi lainnya. Ku buka semak itu perlahan, ku dengar suara yang sepertinya tak asing. Ku lihat 5 ekor anak kucing ada di dalamnya, Doreng berdiri dan seakan-akan terganggu dengan kehadiranku. “Pung, sini pung!” kataku. “Ada apa?” kata Ipung mendekat.
117 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Itu, Doreng punya 5 ekor anak.” kataku antara senang dan sedih. “Wahh, biar aku ambil, Bon.” katanya. “Eits, jangan. Biarkan saja mereka bersama Doreng. Jangan ganggu mereka!” kataku menahan Ipung. “Hei mana Doreng?” kata Ihsan yang terlihat kepayahan. “Sstttt..lihat! Doreng sudah punya 5 ekor anak.” kataku mengulanginya. “Kenapa enggak dibawa pulang saja, Bon?” kata Ihsan. “Sudah biar saja, mungkin Doreng sudah ingin bebas. Lihat saja tanganku, dia sudah tak mau lagi ku peluk seperti dahulu.” kataku. “Coba lihat, warnanya!” kata Ihsan. “Aku suka yang hitam.” kataku. “Aku yang putih pirang itu, Bon.” kata Ihsan. “Kalau aku yang coklat itu.” kata Ipung.
118 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Eh teman-teman. Kalian janji ya, jangan ganggu Doreng. Jangan beri tahu siapapun kalau Doreng bersarang disini.” kataku. “Tenang saja, kami akan jaga rahasia ini kok. Iya kan San?” kata Ipung. Ihsan hanya mengangguk. “Hei, sedang apa kalian disitu?” Tiba-tiba Aceng dan Munir sudah ada di belakang kami, mereka mendekat. “Ah tidak ada apa-apa kok.” kataku seraya berusaha menutup kembali semak yang ku buka tadi. “Aku
enggak percaya!”
Kemudian
Aceng mencoba
mendorongku menjauh dari semak-semak itu. Aku bersikeras menahannya. “Aku sudah bilang, enggak ada apa-apa!” kataku membentak. “Oh..kamu berani, Bon?” kata Aceng. Sementara itu, Munir menarik Ipung dan Ihsan menjauh. “Sudah lebih baik kamu pergi saja, Ceng!” kataku.
119 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Wah kamu mau ku pukul lagi?” katanya menantang. Sekuat tenaga aku mendorongnya. Tak terima ia pun melepaskan tinjunya tepat ke arah pelipisku. Aku terjatuh, kali ini aku tak berdaya karena aku telah berjanji tak akan berkelahi lagi. Aceng membuka semak itu dan ia melihat Doreng dengan 5 ekor anaknya. “Oh jadi ini? Buat apa kucing seperti ini!” katanya seraya menendang Doreng hingga terpental. Melihat kejadian itu, entah apa yang merasuki tubuhku. Ku ambil batu sebesar genggaman tangan dan ku lemparkan ke arah Aceng. Batu itu tepat mengenai hidung Aceng, ia jatuh dan mengeluarkan darah. “Ahhhh hidungku!!!” kata Aceng kesakitan. Munir segera membawa pergi Aceng. Aku tahu ini akan berujung dengan amarah ayahku tapi masa bodoh. “Bon, gila kamu.” kata Ipung.
120 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ah masa bodoh. Biar tahu rasa dia! Dia pikir, dia yang paling hebat disini!” kataku penuh emosi. “Tapi
ayahmu,
Bon.
Ayahmu...”
katanya
coba
menyadarkanku. Aku terdiam sejenak. “Pung, aku pulang ke rumahmu saja ya?” kataku. “Kenapa, Bon?” tanya Ipung. “Kamu sendiri yang bilang. Pasti ayahku marah, kalau tahu aku berkelahi lagi.” kataku. Ihsan hanya terbengong keheranan. “Ya sudah, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita ceritakan kejadian ini kepada orangtuaku. Siapa tahu mereka bisa mengerti dan mengijinkanmu tinggal di rumahku.” kata Ipung. “San, kalau kamu bertemu ayahmu atau ayahku. Bilang saja kamu tak bertemu denganku! Jangan sampai mereka tahu aku ada di rumah Ipung.” kataku. Ihsan mengangguk, tanda ia mengerti. Kemudian aku pulang menuju rumah Ipung. Sesampainya disana, syukurlah orangtua Ipung mengijinkanku tinggal
121 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
sementara di rumah mereka. Orangtua Ipung mengerti benar tentang keadaanku, lagipula aku bisa mengajari Ipung beberapa pelajaran yang ku bisa. Ku harap ayah tak menemukanku disini, aku takut ayah akan memukuliku seperti tempo hari. Aku sungguh takut. Aku juga tak mau lagi merepotkan Mbah Menir dan Paman Salim, aku sangat jahat untuk orangorang sebaik mereka. Tapi bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Perasaan masa bodohku waktu itu membuatku kembali terlibat masalah besar.
122 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
JEJAK TERAKHIR
Sementara itu, Ihsan pulang ke rumahnya. Ia berlari segera menemui Mbah Menir dan ibunya. Kebetulan, ayahnya sedang bekerja. “Mbah..simbah..” katanya memanggil. “Iya ada apa le?” sahut Mbah Menir. “Mbah, Ihsan mau bercerita tapi tolong jangan kasih tahu ayah Bono ya mbah?” kata Ihsan sedikit gugup. “Lho lho lho, ada apa sih le?” kata Mbah Menir heran. “Begini mbah, tadi kami menemukan Doreng di semaksemak pinggir kali di sebelah sana.” kata Ihsan mulai bercerita. “Iya, njur piye le?” Tanya Mbah Menir mulai larut. “Tapi tiba-tiba, Aceng dan Munir menemukan kami sedang di sana. Mereka jahat mbah. Aceng menendang Doreng, karena tak terima Bono melemparkan batu ke arah Aceng. Aceng
123 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berdarah mbah. Bono takut pada ayahnya, sehingga ia tak mau pulang mbah.” kata Ihsan bercerita. “Terus sekarang Bono dimana le?” Mbah Menir khawatir. “Di rumah Ipung mbah.” jelas Ihsan. “Ya sudah. Sementara biar dia disana dulu, sekarang kita ke rumah Bono saja menemui ayahnya.” ajak Mbah Menir. “Jangan mbah, Bono melarang Ihsan member tahu ayahnya. Ia takut dipukul lagi.” Ihsan melarang. “Justru kita harus segera ceritakan kejadian ini, sebelum orang lain yang bercerita le.” kata Mbah Menir. “Sudah, ayo ikut simbah!” Ihsan dan Mbah Menir menuju rumahku. Sementara ibu Ihsan tinggal sendiri menunggui rumah Mbah Menir. Mereka bergegas menuju rumahku. Tapi belum sampai di rumahku, mereka melihat rumahku sudah cukup ramai di datangi beberapa orang. Orang-orang itu adalah ayah Aceng dan beberapa anak buahnya.
124 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Aku ini bosmu Wan! Sekarang kamu lihat apa yang terjadi pada anakku! Hidungnya robek terkena lemparan batu anakmu itu!” kata ayah Aceng marah-marah sambil menunjuk hidung anaknya yang diperban. “Tapi mas, tolong jangan berhentikan saya. Saya masih mau berkerja di kapal Mas Karso.” kata ayahku memohon. “Kalau memang ndak mau saya berhentikan, ya ganti rugi biaya pengobatan anakku!” kata ayah Aceng naik pitam. “Tapi uang darimana mas? Hasil melaut saya dengan perahu njenengan juga hanya cukup untuk makan.” kata ayahku. “Itu urusanmu! Kalau kamu tidak mampu mengganti biaya pengobatan anakku, ya sudah kamu tidak usah bekerja lagi, tidak usah melaut lagi dengan perahuku!” kata ayah Aceng. “Eh eh eh ada apa ini?” Mbah Menir memotong pembicaraan mereka. “Ini mbah, anak si Ridwan melempar anakku dengan batu. Ya sobek hidungnya. Lima jahitan mbah.” kata ayah Aceng.
125 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Masalah itu, aku sudah dengar dari Ihsan.” kata Mbah Menir. “Ndi bocahe mbah? Biar aku pukul anak itu!” kata ayah marah. “Kamu itu Wan, bisanya cuma memukuli anakmu saja! Dengarkan simbah dulu!” Kini Mbah Menir tak bisa menahan diri. Ayah terdiam, kaget melihat ekspresi Mbah Menir tak seperti biasanya. “Gini So, Wan. Tadi Ihsan sudah cerita sama simbah. Katanya Bono seperti itu karena Aceng menendang Doreng, kucing kesayangan Bono. Tak terima Bono melemparkan batu. Ya, akhirnya seperti yang kalian ketahui. Aceng terluka di hidungnya.” Cerita Mbah Menir. “Saya ndak mau tahu mbah. Yang saya mau sekarang, Ridwan mengganti biaya pengobatan anak saya!” kata ayah Aceng.
126 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Masalah ganti rugi itu gampang. Biar simbah yang ganti, kamu butuh berapa So?” kata Mbah Menir seraya mengeluarkan dompet dari balik kain kembennya. “Sebenarnya hanya 125 ribu mbah.” kata ayah Aceng. “Halah mung sakmono tok, ini simbah bayar!” kata Mbah Menir ketus. “Maaf ya mbah, bukan maksud saya mau menyinggung simbah.” kata ayah Aceng sungkan. Mbah Menir hanya melirik. Bagaimana pun juga Mbah Menir sangat dihormati oleh warga kampung karena jasa-jasanya. “Kamu juga Ceng! Sukanya mengganggu, meledek, mengejek Bono. Bono itu sudah seperti cucuku, kamu tahu apa akibatnya membuat aku marah?” kata Mbah Menir geram. Aceng ketakutan hanya bersembunyi di balik tubuh ayahnya. “Sekali lagi kamu buat Bono sedih atau terluka. Simbah sendiri yang akan memberi pelajaran buatmu! Besok kamu harus minta maaf pada Bono!” kata Mbah Menir bertambah murka.
127 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“I..iya mbah. Aceng janji tidak akan nakal lagi pada Bono. Aceng akan minta maaf padanya, mbah” kata Aceng. “Iya mbah. Maafkan kelakuan anak saya ya mbah?” kata ayahnya meminta maaf. “Yo wis tak tompo!” kata Mbah Menir. “Terima kasih mbah, terima kasih.” kata Aceng dan ayahnya. “Iya saya juga terima kasih mbah. Sudah banyak dibantu Mbah Menir.” kata ayahku haru. “Sudah Wan, sudah. Sekarang kita cari anakmu. Yang lain bubar, kamu juga So segera pulang rawat anakmu.” perintah Mbah Menir. “Baik Mbah.” kata ayah Aceng kemudian mengajak anak buahnya pergi. “Simbah tahu dimana Bono?” tanya ayahku.
128 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Simbah sebenarnya tahu, tapi kamu janji jangan pukuli anakmu lagi. Kalau sampai kamu pukuli anakmu lagi, simbah ndak segan-segan buat memukulimu!” kata Mbah Menir. “I..iya mbah. Saya heran kenapa hari ini simbah lebih galak daripada saya.” kata ayahku heran. “Ya begini kalau simbah sudah marah. Gunung pun bisa mbah telan.” kata Mbah Menir menahan senyum. Mereka menuju ke rumah Ipung untuk menemuiku. “Kamu di sini saja dulu Wan. Biar aku dan Ihsan yang masuk ke dalam.” kata Mbah Menir. Ayah menurut. “Assalamualaikum” Mbah Menir mengucapkan salam. “Wa’alaikumusalam, eh Mbah Menir. Ada apa mbah?” sahut ibu Ipung. “Bono ada di sini?” tanya Mbah Menir. “Iya ada mbah. Bono..Bono..ini dicari Mbah Menir.” Panggil ibu Ipung. Aku dan Ipung menuju ke serambi rumah.
129 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ayo le, pulang. Ndak baik merepotkan orang.” kata Mbah Menir. “Tapi Bono takut dengan ayah mbah.” kataku ketakutan. “Ndak apa-apa. Kalau ayahmu berani memukulmu, biar simbah pukul ayahmu sekuat tenaga. Begini-begini dulu simbah jago silat lho le.” canda Mbah Menir coba menenangkanku. “Iya mbah. Pung, aku pulang dulu ya? Terima kasih sudah ijinkan aku tinggal di rumahmu.” kataku. “Iya Bon, sama-sama. Kita kan sohib seperjuangan.” katanya Ipung seraya menepuk pundakku. Kami berpamitan pada keluarga Ipung dan pergi menuju rumahku. Baru beberapa langkah dari halaman rumah Ipung, ku lihat ayah bersender pada sebuah pohon besar. Ku lihat seakanakan, ayah akan menerkamku seperti singa kelaparan. “Mbah, ada ayah. Bono takut.” kataku berlindung dibalik tubuh Mbah Menir. “Sini le. Kemari!” kata ayahku.
130 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mbah
Menir
menarik
lenganku
dan
menyuruhku
menyambut perintah ayah. Aku berjalan tak mantap, aku takut ayah akan memukuliku lagi. Tiba-tiba “hap” tubuh besar ayah memeluk erat tubuhku. Aku kaget, terharu dan tak bisa berkata apa-apa. “Maafkan ayah ya le, tak bisa mendidikmu dengan baik. Ayah harus bekerja, jadi ayah tidak seperti dulu lagi saat masih ada ibumu. Ayah menyesal le.” kata ayahku sendu. “Iya ayah, maafkan Bono juga. Bono tidak melaksanakan nasehat ayah dengan baik.” kataku menyambut pelukan ayah dengan melingkarkan lengan memeluk ayah. “Nah kalau gitu kan enak dilihat.” kata Mbah Menir. “Iya mbah. Terima kasih ya mbah. Saya janji tidak akan memukuli Bono lagi.” kata ayah berdiri dan mencium tangan Mbah Menir tanda bakti. “Lha iya, memang almarhumah istrimu tidak sakit hatinya kalau ia lihat Bono kau perlakukan kasar?” kata Mbah Menir.
131 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya mba, maaf. Sekarang saya mengerti mbah.” kata ayahku lirih. “Ya sudah, sekarang Bono pulang ke rumah dengan ayah ya? Simbah pulang dengan Ihsan.” kata Mbah Menir. Aku mengangguk. Lalu kami pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, ku buatkan ayah segelas kopi tanpa ayah perintah. Kemudian coba lebih dekat dengan mengajaknya bicara. “Ini yah, Bono buatkan kopi panas.” kataku menyajikan segelas kopi panas. “Terima kasih ya le.” kata ayah kemudian meniup-niup gelas berisi kopi panas. “Ayah, sebentar lagi Bono ulang tahun. Bono sering lihat teman-teman yang lain merayakan ulang tahun. Senang yah jadi mereka, dapat hadiah dari orangtua mereka.” kataku. “Kamu juga ingin seperti mereka? Ingin ayah beri hadiah di hari ulang tahunmu?” kata ayah menebak arah pembicaraanku.
132 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ahh tidak yah tidak. Bono hanya bercerita saja koq, kesehatan ayah sudah jadi kado spesial buat Bono. Lagi pula Bono paham betul, ayah bekerja keras siang malam untuk mencukupi kebutuhan Bono. Jadi Bono tak berharap hadiah apapun.” kataku menyangkal. “Ya sudah kalau begitu. Yang penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita miliki sekarang. Makanya sekolah yang rajin ya le biar nasibmu lebih baik dari ayah.” kata ayah. “Iya yah. Bono pasti akan lebih rajin belajar dan tidak nakal lagi.” kataku. “Oh iya le, beberapa waktu yang lalu ayah membaca puisi untuk ibu yang kamu buat. Kamu pandai menulis ya le?” kata ayahku memuji. “Iya yah. Selain matematika, Bono juga suka pelajaran Bahasa Indonesia terutama menulis puisi yah. Oh iya, ayah taruh dimana puisi itu?” tanyaku.
133 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Di lemari buku-bukumu le. Coba bawa kemari biar ayah baca lagi. Sekalian bawa foto Ir. Soekarno yang tertempel di dinding ya le?” kata ayah menyuruhku. Aku bergegas mencari puisi itu dan foto Ir. Soekarno yang ayah maksud kemudian segera kembali membawanya pada ayah. “Ini yah.” Ku lihat ayah membaca puisiku dan mengangguk-angguk tanda ia paham dengan isi puisi itu. “Bagus le, kapan-kapan buatkan ayah juga ya?” kata ayah kemudian ia tersenyum lembut. Ayah melepas foto Ir. Soekarno dari piguranya kemudian memasukkan puisiku ke pigura itu. “Ini, simpan baik-baik! Jangan sampai rusak ya le?” kata ayah menyerahkan puisi yang sudah berpigura kepadaku. Ku raih puisi itu kemudian berkata, “Baik yah. Tapi bagaimana dengan foto Ir. Soekarno itu yah? Bukankah itu tokoh idola ayah?”
134 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Tidak apa-apa. Tancapkan saja foto ini ditempat semula, gunakan paku kecil agar foto ini tidak rusak ya le? Sudah sana, letakkan puisi itu ditempat yang kamu suka!” perintah ayah. Aku menuruti perintah ayah dan bergegas menuju kamar sementara ayah mengikutiku dari belakang. Ku tancapkan foto Ir. Soekarno terlebih dahulu dengan paku kecil di tempat semula. Kemudian ku buka penyangga piguranya dan ku letakkan puisi berpigura itu di atas meja kamarku. Aku tersenyum senang, ayah pun tersenyum turut senang. “Ya sudah, sekarang kita istirahat. Besok ayah mau berangkat melaut.” kata ayah. Aku hanya mengangguk, ku rebahkan tubuhku dan sepintas ku lihat ayah menuju bangku bambu di depan rumah. Dalam suasana senang, tak butuh waktu lama bagiku terlelap dalam tidur. Dalam tidur aku bermimpi. Aku bertemu ibu, kali ini ia menangis. Ku tanya ada apa gerangan yang terjadi pada ibu. Ia tak menjawab, sesekali ia hanya mengeluarkan satu kata yang
135 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
sama berulang-ulang. Aku coba mengerti apa yang ia katakan. “Ayah” itu kata yang ibu ucapkan. Aku coba bertanya, “Ayah kenapa bu?” Kini kata “Ayah” berganti menjadi “Laut”. Aku semakin bingung, aku tak mengerti apa yang ingin ibu sampaikan dalam mimpi. Tiba-tiba ibu menarikku, tangannya erat mencengkram lenganku. Ia membawaku ke pantai dan menunjuk ke suatu benda. Ku pahami benda itu semakin mendekat, aku coba berjalan beberapa langkah untuk memperjelas penglihatanku. Itu sebuah perahu, tapi semakin lama ku lihat ternyata perahu itu terbelah dua. Hanya bagian depan yang mengapung, sementara bagian lainnya entah dimana. Aku berpaling pada ibu dan bertanya, “Itu perahu siapa bu?” Ibu menjawab dengan menangis, “Ayah”. Mendengar jawaban itu, aku berteriak memanggil nama ayah, “Ayaaaahhh…ayaaahhhh”.
136 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku ingin meraih perahu itu, tapi entah bagaimana kakiku membatu tak dapat ku gerakkan. Aku memanggil ibu untuk membantuku, tetapi ia sudah menghilang. Aku ketakutan, aku menjerit sejadi-jadinya. Air laut mulai melahap sedikit demi sedikit tubuhku. “Ahhhhhhhh” aku terbangun. “Astagfirullahal adzim” Aku bergegas keluar rumah. Ayah sudah tak ada di bangku bamboo tempat biasa ia tidur. Ku lihat matahari belum muncul, “Ini belum subuh.” Aku berlari menuju pantai, ku lihat perahu yang biasa ayah gunakan melaut sudah tidak ada. Aku terduduk, kakiku lemas. Aku takut terjadi sesuatu pada ayah. Tak terasa aku menangis. Dan seakan-akan langit ikut menangis, hujan mengguyur tubuhku. Air mataku bercampur dengan air hujan yang membasahi tubuhku. Seakan-akan dinginnya angin yang menerpa tubuhku, tak ku rasakan.
137 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Dengan
guyuran
hujan
yang
semakin
deras,
aku
memandang ke selatan. Aku berharap ayah baik-baik saja. Tiba-tiba dari arah belakang ku dengar suara orang berteriak, “Hei, jangan disitu! Kemari! Anginnya kencang!” Aku tak peduli. Aku bertekad menunggu ayah disini. Seseorang bermantel biru mendekat dan menarikku. Aku berontak dan berkata, “Biar saja, aku sedang menunggu ayahku.” “Kamu mau bunuh diri atau bagaimana Bon?” katanya. Ku lihat, itu Mas Ikin. “Ayah dimana mas?” tanyaku. “Ayo kita berteduh dulu, nanti Mas Ikin ceritakan.” katanya membujukku. Aku menurutinya. Kami berteduh di sebuah gubuk di dekat pantai. Mas ikin membalutku dengan handuk, “Keringkan badanmu dengan handuk ini.”
138 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku mengusap-usap tubuhku yang basah dengan handuk itu kemudian bertanya, “Mas, apa ayah pergi melaut?” “Begini Bon, sebenarnya kami para nelayan sudah tahu akan terjadi hujan angin hari ini. Sangat berbahaya jika melaut, tapi ayahmu bersikeras untuk melaut hari ini. Jadi, ia bersama dua orang nelayan lainnya pergi melaut.” kata Mas Ikin. “Untuk apa ayah melaut, jika sudah tahu akan berbahaya mas?” tanyaku. “Emmm katanya sebentar lagi kamu ulang tahun ya? Ayahmu ingin sekali membelikanmu hadiah di hari ulang tahun nanti.” kata Mas Ikin. “Ayahh. Bono tak perlu hadiah, Bono hanya ingin ayah.” kataku menyesal. “Sudahlah, kita doakan saja ayahmu baik-baik saja.” kata Mas Ikin mengusap punggungku. Aku terdiam, menyalahkan diriku sendiri.
139 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mas Ikin terperanjat, ia melihat kegaduhan di satu sudut pantai. Kami mendekat. “Ada apa pak?” tanya mas Ikin. “Saat kami sedang melaut, kami melihat ada perahu yang tersapu ombak. Beruntung kami bisa menyelamatkan semua penumpangnya. Semua selamat, hanya satu yang sepertinya terluka parah.” kata salah seorang nelayan. “Coba kami bantu pak.” kata Mas Ikin. Perasaanku mulai was-was. Benar saja, yang ku lihat tergeletak di dalam perahu adalah ayah. “Ayaaahhhhh.” “Cepat angkat, angkat.” kata Mas Ikin memberi aba-aba nelayan lain untuk mengangkat tubuh ayah. “Bono, cepat kamu beri tahu Mbah Menir dan Paman Salim. Kita harus segera ke Puskesmas!” perintah Mas Ikin panik. Aku mengangguk dan berlari secepat mungkin menuju rumah Mbah Menir.
140 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Mbah…..Mbah Menir….Mbah.” aku berteriak menggedorgedor pintu rumah Mbah Menir. Mbah Menir keluar, aku memeluknya erat. “Ada apa le?” “Ayah terluka parah mbah. Perahunya tersapu ombak.” kataku tersedu-sedu. “Yaa Allah…Ayo cepat kita kesana, Lim susul kami di Puskesmas ya?” teriak Mbah Menir. Kami menuju Puskesmas, disana mobil ambulan telah siaga. “Mau dibawa kemana ini Kin?” tanya Mbah Menir pada Mas Ikin. “Rumah Sakit di kota mbah, katanya ada yang retak di tulang pinggul Mas Ridwan.” jelas Mas Ikin. “Mbah Menir dan Bono ikut ambulan saja, biar saya dan yang lain menyusul dengan mobil Mas Karso.” Aku dan Mbah Menir masuk ke dalam ambulan. Ku lihat ayah merintih, aku coba membisikkan di telinganya kalimat syahadat. Aku menangis.
141 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Perjalanan terasa panjang. Ambulan yang mengantarkan ayah ke Rumah Sakit harus diangkut dengan kapal menuju pelabuhan di kota. Dari pelabuhan ambulan melaju kencang menuju Rumah Sakit. Sesampainya di Rumah Sakit, ayah mendapat penanganan dari dokter di ruang gawat darurat. Aku tak mampu berkatakata, suasana sangat ramai tapi hatiku sepi. Aku, Mbah Menir, Ihsan, Paman dan Bibi Salim menunggu di depan ruang gawat darurat sementara mas Ikin dan Pak Karso ayah Aceng bersama beberapa warga kampung menunggu di luar Rumah Sakit. Aku menyandarkan kepalaku di paha Mbah Menir. Kami duduk bersebelahan. Tangannya lembut mengeluselus kepalaku. Setelah menunggu sekitar 2 jam, dokter keluar dari ruang gawat darurat. Paman Salim bertanya pada dokter, “Bagaimana keadaan pasien, dok?” “Anda keluarganya?” tanya dokter itu.
142 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya, saya saudaranya.” kata Paman Salim mengaku saudara ayah. “Baik. Ikut saya ke ruangan.” ajak dokter itu. Paman Salim dan dokter itu pergi, aku hanya melirik. Mereka pergi cukup lama, semua berusaha menghiburku tapi seakan aku tak peduli. Dari kejauhan ku lihat Paman Salim datang dengan wajah tertunduk. “Ada apa Lim?” tanya Mbah Menir. Paman Salim hanya tersenyum dan berjongkok didepanku. “Bono, ayah kamu sudah bisa dijenguk besok. Tapi paman mau tanya, kamu sayang ayahmu?” kata Paman Salim ramah. “Iya paman.” kataku lirih. “Kalau kamu sayang ayahmu, jangan pernah terlihat sedih di depannya. Ayahmu ingin kamu jadi orang yang kuat. Kamu janji ya?” kata Paman Salim. Aku hanya mengangguk.
143 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Tapi Bono, paman minta maaf harus sampaikan berita ini. Kata dokter ayahmu sudah tak dapat berjalan seperti sebelumnya. Ia lumpuh.” kata Paman Salim tak tega. Mendengar kata-kata Paman Salim hatiku remuk redam. Aku menahan sekuat tenaga air mataku tak keluar, tapi apa daya aku hanya anak 12 tahun. Ku peluk tubuh Mbah Menir dan menangis sejadi-jadinya. “Kenapa bisa begitu Lim?” kata Mbah Menir sedih. “Kata dokter, kemungkinan tulang pinggulnya retak karena terbentur karang. Itu yang menyebabkan syarafnya rusak dan Mas Ridwan lumpuh, bu.” jelas Paman Salim. “Astagfirullah..sabar ya le?” kata Mbah Menir tak hentihentinya mengusap kepalaku. “Sssttt sudah-sudah. Jangan menangis lagi sayang.” Bibi Salim membantu Mbah Menir menenangkanku. Ihsan hanya terbengong tak tahu harus berbuat apa.
144 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mbah Menir mengajakku keluar. Mas Ikin mendekat dan bertanya, “Bono kenapa mbah?” Mbah Menir meletakkan telunjuknya di atas mulut, memberi tanda untuk tidak bertanya. “Kamu tanya Salim saja di dalam.” kata Mbah Menir. Mbah
Menir
menidurkanku
di
atas
pangkuannya.
Kemudian seperti biasa, ia menyanyikan tembang jawa. Aku sesenggukan, pasrah pada apa yang sedang terjadi. Suara Mbah Menir merdu, aku tak kuasa menahan kantuk. Aku tertidur. Tak
terasa
subuh
datang.
Tangan
Mbah
Menir
membangunkanku. “Ayo sholat subuh dulu, le.” Ku gosok-gosok kelopak mataku. Mbah Menir menuntunku menuju mushola di Rumah Sakit. Kami sholat subuh berjamaah dengan beberapa orang yang sudah berkumpul di mushola itu. Selesai sholat, aku berdoa untuk ayah, ibu dan semua yang sudah menyayangiku.
145 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Selesai sholat subuh Mbah Menir mengajaku menjenguk ayah. Ku lihat kondisi ayah sudah cukup baik. Ayah tersenyum melihatku, aku berlari dan memeluknya. Ayah hanya bisa berbaring di atas kasur. “Ayah, kapan pulang? Besok Bono ulang tahun.” kataku. “Sabar ya le. Tidak apa-apa kan kalau kita berulang tahun di sini? Lihat, belum ulang tahun saja sudah banyak makanan.” canda ayah coba menghibur hatiku. “Tapi maaf ya le, ayah ndak bisa kasih kamu hadiah apaapa.” kata ayah menyesal. “Tidak yah, ada ayah di hari ulang tahun Bono saja itu sudah jadi hadiah yang istimewa yah.” kataku coba mengerti keadaan. “Kamu memang anak yang berbakti le. Maaf kalau selama ini ayah sering memarahi dan memukul. Ayah menyesal le.” kata ayah memandangku dalam.
146 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya yah. Bono tahu ayah menyayangi Bono, hanya terkadang Bono yang selalu membuat ayah marah. Melanggar nasehat ayah.” pelukkanku semakin erat. “Aduh yang lagi bersedih ria, sudah lah sebentar lagi kan Bono ulang tahun. Jangan sedih lagi. Mungkin dengan kejadian ini kita semua bisa introspeksi diri untuk jadi manusia yang lebih baik lagi.” kata Paman Salim memotong pembicaraanku dengan ayah. “Benar kata Pamanmu le. Sudah mulai hari ini tidak boleh ada yang sedih lagi.” kata ayah tersenyum. Aku membalas senyum ayah. “Oh iya le. Kamu kan janji mau membuatkan ayah puisi. Coba buatkan ayah le.” pinta ayah. “Baik yah. Bono buatkan dulu yah.” kataku bersemangat. “Paman Salim ada kertas dan pena, gunakan ini saja.” kata Paman Salim seraya menyerahkan kertas dan pena dari dalam tas kerjanya. Aku menerimanya dan mulai menulis.
147 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya sudah kang. Saya berangkat kerja dulu ya? Semalam saya sengaja membawa peralatan kantor, mumpung di kota kang jadi tidak bolak balik.” kata Paman Salim kemudian tertawa sungkan. Ayah hanya membalas dengan anggukan. “Bu, saya berangkat ya? Assalamualaikum.” kata Paman Salim berpamitan pada Mbah Menir. “Iya Lim. Hati-hati ya, jangan lupa bawakan Ridwan makanan yang enak-enak.” kata Mbah Menir. “Ah tidak usah Lim. Jangan repot-repot.” ayah melarang. “Tidak apa-apa kang. Insya Allah nanti saya bawakan.” kata Paman Salim kemudian keluar dari ruangan tempat ayah dirawat. Sementara itu pandanganku hanya tertuju pada bait-bait puisi yang ku tulis. Seakan tak mau mengganggu, mereka hanya memandangiku. Ayah, Mbah Menir dan Bibi Salim memandangi dari jauh. Sementara Ihsan coba membaca bait-bait yang ku tulis.
148 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ehhh jangan dibaca dulu!” kataku melarang. “Ihsan, jangan ganggu Bono nak.” kata Bibi Salim. “Ihh kok kamu jadi pelit sih?” kata Ihsan cemberut. “Bukannya pelit. Tapi puisi ini kan rahasia, aku ingin membacakannya untuk ayah.” kataku kemudian meledek Ihsan dengan menarik ujung hidungnya. “Ahhh. Sakit tahu! Ya sudah, aku juga bisa buat puisi! Ibuu, Ihsan mau kertas dan pena seperti Bono.” kata Ihsan manja. “Ibu ndak punya. Yuk kita beli saja di luar.” kata Bibi Salim kemudian mengajak Ihsan keluar. Tak terasa sebuah puisi indah telah ku buat. Mbah Menir mendekat ingin membacanya. Cepat-cepat ku lipat kertas itu. “Ehh simbah juga ndak boleh baca le?” kata Mbah Menir. “Jangan dulu mbah. Besok saja, Bono mau bacakan puisi ini dihari ulang tahun Bono.” kataku. “Yo wis lah. Sak karepmu.” kata simbah. Aku dan ayah tertawa.
149 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Waktu berganti waktu. Ku lihat Sang Surya mulai menyembunyikan dirinya di ufuk barat. Malam itu tak ada lagi tangis dan kesedihan. Yang ada hanyalah tawa, canda dan kebahagiaan. Terlebih saat Widi, Dani, Ipung dan Ara datang menjenguk ayahku. Bahkan Aceng datang bersama Pak Karso, ayahnya. “Kamu datang Ceng?” tanyaku. “Iya Bon. Maaf ya kalau selama ini aku jahat padamu. Aku ingin mulai hari ini kita berteman. Aku juga mengajak Munir. Tapi dia malu.” katanya. “Untuk apa malu? Mana dia?” kataku. Kami berjalan menemui Munir. “Munir. Kemari!” kataku. Ia hanya menggelengkan kepala. Aku mendekat dan merangkulnya. “Sudahlah. Tak perlu malu. Sekarang kita semua berteman. Tak boleh lagi ada yang bermusuhan.” kataku. Munir menahan
150 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
senyum kemudian malu menutupi muka dengan telapak tangannya. Kami semua tertawa. Seakan Allah telah mengatur semua ini. Ulang tahunku jatuh besok pada hari Minggu. Sehingga teman-teman bisa berkumpul bersamaku, walau di Rumah Sakit. Belum lagi, orangorang yang menyayangiku seperti ayah, Mbah Menir, Paman dan Bibi Salim ada saat aku berulang tahun. Bahkan Mas Ikin dan Pak Karso, bisa ikut berkumpul juga. Ini diluar dugaanku. Aku dan teman-teman bermain bersama di halaman Rumah Sakit. Beberapa anak-anak juga bermain disana. Aku senang. Karena kelelahan kami semua tertidur di bangku di ruangan tempat ayahku dirawat. Esok pagi, sesaat setelah aku terbangun. Mbah Menir dan Bibi Salim terlihat merapihkan ruangan. Sementara Pak Karso dan ayahku terlihat sedang berbincang-bincang. Mas Ikin membangunkanku dan anak-anak yang lain satu per satu kemudian menyuruh kami untuk sholat subuh.
151 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Setelah sholat shubuh, Mas Ikin menyuruh kami mandi. Kami bergantian memakai kamar mandi. Ihsan mandi terlebih dahulu, diikuti Dani, Ipung, Ara, Aceng, Munir, Widi dan terakhir aku. Selesai mandi Mbah Menir mengeringkan tubuhku dan memakaikan baju. Ku lihat semua sudah duduk rapih, orang dewasa duduk di kursi sementara anak-anak duduk di lantai. Ku lihat ayah juga duduk di kasurnya. Tapi kemana Paman Salim? Dia tak ada disini. Tiba-tiba dari arah pintu Paman Salim masuk dan berteriak, “Selamat Ulang Tahun Bono.” Paman Salim membawa sebuah kue tart lengkap dengan lilin dan hiasannya. Semua bertepuk tangan. “Yuk nyanyi selamat ulang tahun untuk Bono.” ajak Paman Salim. Semua bernyanyi. Aku sangat senang. Bulu kudukku merinding merasakan kebahagiaan dan kebersamaan saat itu. Kemudian aku meniup lilinnya dan memotong kue itu dibantu Bibi Salim menjadi beberapa bagian kemudian ku
152 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
bagikan pada semua teman-temanku. Kami lahap memakan kue itu, rasanya lezat. “Bono, katanya kamu mau membacakan puisi untuk ayah.” kata ayah mengingatkanku. “Oh iya, Bono hampir saja lupa yah.” kataku sambil menepuk kening kemudian bergegas mencari puisi yang telah ku buat untuk ayah. Seketika suasana menjadi hening saat aku mulai membuka kertas puisiku. Semuanya serius menyimak bait-bait yang aku bacakan. Bahkan Mbah Menir meneteskan air mata haru. Hari itu menjadi ulang tahun yang istimewa bagiku. Baru kali ini aku merayakan ulang tahun seperti teman-teman yang lain. Walau tak ada ibu dan ayah baru saja mengalami musibah, tapi semua itu terbayar dengan berkumpulnya orang-orang yang sangat ku sayang. Ayah, Mbah Menir, Mas Ikin, Paman Salim, Bibi Salim, Pak Karso dan teman-temanku.
153 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bono Sugiarto Jejak Terakhir
Ayah bisa mengarungi samudera. Mempertaruhkan nyawa demi anaknya. Ayah bisa melawan ganasnya dunia. Hanya didasari cinta pada anaknya.
Begitu hebatnya engkau ayah. Tak pernah mengeluh tubuhmu lelah. Begitu dahsyatnya engkau ayah. Selalu mengajariku untuk bertabah.
Hanya nasehat yang selalu kau ajarkan. Sebagai jejak terakhir sebelum kau berlayar. Dan hanya doa yang selalu ku panjatkan. Sebagai jejak terakhir sampai kau pulang berlayar.
154 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
vii
Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Penulis Zulfikkar PN
i
Persembahan Telah 3 tahun, cukup lama. Ku tulis berlembar-lembar cerita. Bukan kisah cinta remaja nan syahdu. Melainkan kisah anak tak beribu. Ialah anak penuh haru biru. Sumber inspirasi sanubariku. Ia yang datang dari kampung seberang. Kampung diantara lautan yang garang. Semangat pantang menyerah berkobar. Dalam tubuh kecil terdapat jiwa yang tegar. Apalah dia dibanding mereka si kaya raya. Namun lihat, ia lebih hebat dimata Tuhannya. Persembahan inilah jadi awal pembuka. Dimana dan darimana kisah ini bermula. Kisah suka duka si anak nelayan. Hatinya tulus lewati halang rintangan. Tak berlebihan jika dijadikan suatu teladan. Walau penuh cobaan percayalah pada Tuhan. Karena Dia-lah yang akan berikan jalan. Sebuah hikmah beserta tuntunan. Ku persembahkan kisah ini. Pada mereka yang masih miliki hati. Untuk melihat ke beberapa sisi. Bahwasanya hidup perlu disyukuri.
Cilacap, 11 Agustus 2013 Zulfikkar PN
ii
Daftar Isi Halaman Judul Persembahan Daftar Isi Kesan & Pesan Monolog Garis Hidup Nyonya Surati Kuburan Raibnya Si Doreng Ampun, Ayah Paman Salim & Saudara Baru Teman Masalah Baru Jejak Terakhir
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
i ii iii iv 1 8 21 37 49 59 73 90 107 122
iii
Kesan & Pesan
Tak ada yang lebih berarti daripada kesan dan pesan darimu kawan. Bantulah aku untuk menulis lebih baik lagi. Pastinya apa yang kau sampaikan melalui salah satu kolom dibawah ini akan menjadi inspirasi, motivasi sekaligus kenangan yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaan dan perhatian yang kau berikan melalui kolom kesan dan pesan yang sengaja ku lampirkan dalam buku ini.
Zulfikkar PN
iv
MONOLOG
Petang ini aku hanya duduk di bangku bambu yang menua di depan rumahku. Ku lihat lalu lalang orang-orang seakan tak memperdulikan keberadaanku. Mungkin aku tak ubahnya seonggok batu. Wajahku kuyu, ku sandarkan punggung pada dinding kayu rumahku. Pandanganku mulai menuju ke arah pantai, arah dimana ayah biasa muncul setelah pulang melaut. Namun, hanya kegelapan yang ku temukan. Terkejut aku dibuatnya, saat seekor nyamuk menggigit siku kiriku. Tak dapat ku lihat bentuknya, hanya suaranya saja yang mendengung kekenyangan. “Nguingg nguiinggg”. Ku garuk bentol-bentol di siku kiriku seraya beranjak mengambil sarung sebagai perlindungan seadanya. Ku pikir nyamuk-nyamuk itu tak pernah kenyang, masih saja berusaha menggigit kulitku melalu celah sarung yang mereka temukan.
1 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Jengkel dibuatnya, ku ambil sandal japit kemudian ku pukulkan ke udara, berharap membuat nyamuk-nyamuk itu pontang panting ketakutan. Namun sia-sia, mereka pandai menghindar. Aku heran apa enaknya darahku ini, padahal hanya makanan ala kadarnya yang masuk ke dalam tubuhku. Tak lama, suara adzan dari surau dekat rumah terdengar. Inilah hal yang paling aku suka untuk mengisi waktuku, sembahyang. Bergegas aku menuju surau, tak lupa rantai kecil pada pintu ku kaitkan agar pintu tetap tertutup rapat. Selesai sholat aku berdoa agar hasil melaut ayah melimpah dan ia kembali dengan selamat, tak lupa ku doakan ibu agar ia tetap damai di akhirat sana. Selesai sholat Isya, ku lihat beberapa anak bermain petak umpat. Aku tak ikut, malas, tak tertarik. Aku lebih memilih pulang dan merebahkan tubuhku di atas dipan dalam kamarku. Lampu bohlam yang menerangi kamarku mulai meredup, tanda usianya tak lama lagi. Aku menghela nafas, merasa bosan, aku berpikir mencari sesuatu untuk ku kerjakan.
2 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku melihat ke arah rak kecil di sisi kananku. Ku tarik sebuah kertas kosong yang mencuat diantara tumpukan buku-buku usang semasa aku sekolah dulu. Sesaat kemudian mulai ku bangun rasa rinduku pada ibu melalui sebuah puisi. Sejak umur 10 tahun aku memang sudah suka menulis. Belum jelas menulis apa, yang aku tulis hanya khayalan-khayalanku waktu itu. Mulai dari cita-citaku menjadi seorang guru sampai keinginanku memberangkatkan haji ayah dan ibu. Beberapa gambar yang mewakili cita-citaku juga sering ku buat. Aku rasa cita-cita itu kini hanya isapan jempol belaka, ah sudahlah, aku sedang rindu pada ibu, lebih baik ku tulis puisi untuknya. Sebelum ku tulis puisi untuk ibu, ku tulis dulu namaku di sudut kanan atas kertas itu. Bono Sugiarto, itulah nama yang ayah berikan padaku. Kata ayah nama itu diambil dari kalimat Rebo Dino Sugih Arto. Menurut ayah, waktu aku lahir tepatnya hari Rabu, hasil melaut ayah sedang bagus-bagusnya. Karena itu ayah menamaiku seperti itu. Ayah berharap aku jadi orang
3 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berhasil suatu saat nanti. Sayangnya, nama itu dinodai oleh beberapa tetangga dan teman sebayaku. Mereka lebih sering memanggilku Boncel. Mungkin lantaran tubuhku kurus dan pendek untuk ukuran anak usia 12 tahun. Tak apa, anggap saja mereka sedang khilaf. Seketika aku mulai khusyu menulis puisi untuk ibu. Ku mulai dengan menulis judulnya dan kemudian bait-baitnya. Sesekali ku gosok-gosokkan ujung pensil ke pelipisku, tanda aku sedang berpikir keras. Tiba-tiba suara hujan terdengar deras, membawa suasana syahdu menenangkanku. Udara dingin mulai menembus diantara sela-sela dinding kayu kamarku. Ku lihat bulir-bulir air saling berdesakkan membasahi jendela kamarku. Ku lanjutkan menulis puisiku untuk ibu. Ku coba menggambar wajah ibu dalam benakku agar dapat ku curahkan melalui selembar puisi. Bagaimana senyum manisnya, bagaimana sentuhan lembutnya, bagaimana suara merdunya. Imajinasiku mulai meloncat-loncat dari ingatan yang satu ke ingatan yang
4 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
lain. Ku sambung satu demi satu kata yang mungkin saja membuat ibu tersenyum senang. Ku lihat jam dinding yang menggantung, jarum pendekknya berada pada angka 9 dan jarum panjangnya berada pada angka 12. Pantas saja mataku mulai berat ku buka. Sesekali kepalaku terguncang karena rasa kantuk yang mulai mengganggu. Namun, aku masih bersemangat menuliskan beberapa bait puisi untuk ibu. Hanya ini yang dapat ku lakukan untuk menyambung rasa rinduku pada ibu. Segala daya upaya ku kerahkan untuk melawan rasa kantukku. Terjadi perkelahian yang sangat hebat karena aku masih ingin menulis puisi disaat mata mulai mengantuk. Rasanya kantuk ini mulai menghapus sedikit demi sedikit ingatanku. Kesal, ku buka lebar-lebar mata ini dan menampar setengah keras pipi kananku. Aku katakan pada diriku sendiri, “Ayo, jangan menyerah. Harus selesai.” Ku tarik nafas dalam-dalam dan bersiap menyelesaikan puisi yang ku buat. Aku sangat gigih menulis puisi itu, aku ingin
5 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
mempersembahkan itu untuk ibu. Kegigihanku tak sia-sia. Sepuluh menit kemudian, akhirnya puisi untuk ibu dapat ku selesaikan. Ku baca lagi bait-baitnya, meneliti jikalau ada kata yang kurang pantas dalam puisi itu. Aku rasa sudah bagus. Dengan senyum puas, ku lipat kertas puisi itu dan ku selipkan di bawah bantal tidurku. Aku berharap ibu akan menemuiku dalam mimpi dan membaca puisi yang telah ku buat untuknya. Aku mulai merebahkan tubuhku yang sudah tak tahan lagi karena kantuk. Tak butuh waktu lama, aku tertidur pulas. Ku lepaskan lelah dan kantukku bersama selembar puisi yang ku buat. Sebuah puisi rindu untukmu ibu.
6 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bono Sugiarto Rindu Untuk Ibu
Di malam penuh kesendirian. Anakmu rindu pada belaian. Terlintas sosok cantikmu ibu. Yang kini berada jauh dariku.
Hujan mengguyur basah rumah kita. Bawa ketenangan dari suara derasnya. Antarkan anakmu terlelap tidur, bu. Dengan nyanyian suara merdumu.
Anakmu rindu akan pelukmu. Ibu pasti mengetahui hal itu. Temui anakmu dalam mimpinya. Karena anakmu ingin bertegur sapa.
7 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
GARIS HIDUP
Kriiiinngg kriinggg kriiinggg…. Bunyi sepeda bersahutan menyambut mentari pagi. Aku meloncat dari tempat tidurku dan berlari menuju depan rumahku. Ku lihat anak-anak seusiaku sedang bergembira berangkat ke sekolah. “Senangnya mereka.” kataku dalam hati. Ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah musim libur sekolah usai. Tidak semua anak di kampung ini bisa bersekolah, hanya anak-anak yang beruntung bisa bersekolah. Dulu aku seperti mereka bisa pergi ke sekolah, sekarang tidak lagi. Penghasilan ayahku hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ibu masih ada, ia dan ayah berbagi tanggung jawab. Ayah yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, ibu yang bekerja serabutan untuk membiayai sekolahku.
8 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Sebenarnya aku ingin sekali bekerja membantu ayah, tapi ayah melarangnya karena aku belum cukup umur menurut ayah. Tiba-tiba aku rindu datang ke sekolah. Ku putuskan untuk pergi menuju bekas sekolahku, walau hanya sekedar melihat bagaimana bentuk gedungnya sekarang. Sebenarnya jarak rumah ke sekolah cukup jauh, namun aku tak perduli. Dalam perjalanan aku tak mengerti mengapa orang-orang yang ku temui terlihat aneh, seakan-akan mereka ingin menertawaiku. Sejurus kemudian aku mengerti. Ternyata saking rindunya, aku tak sadar pergi dengan muka yang dekil, tanpa alas kaki dan dengan baju yang berwarna coklat pudar yang seakan membusuk. Tapi biarlah, mereka berhak menilai tampilanku. Aku hentikan langkahku tak jauh dari gerbang sekolah. Aku berdiri di sana memperhatikan anak-anak yang lain berlarian masuk ke dalam sekolah. Anak-anak itu datang dengan beragam kendaraan. Kebanyakan dari mereka bahkan datang diantar oleh ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sedang yang lain datang
9 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
bergerombol tanpa diantar keluarga atau sanak familinya, mereka berjalan kaki. Tentu mereka lebih beruntung daripada aku yang kini hanya bisa berdiri di tepi jalan ini. Aku belum beranjak dari tempatku. Rasanya kakiku seperti terpaku. Sampai suasana di depan sekolah menjadi sunyi aku baru bergerak mendekat, ingin sekali menuju ke dalam tapi aku malu dengan keadaanku yang antah berantah seperti ini. “Bono, apa kabar?” teriak Pak Rimbo penjaga sekolah dari kejauhan seraya melambaikan tangannya. “Sini!” tambahnya, aku mendekatinya. “Baik-baik saja pak. Bagaimana dengan bapak?” tanyaku. “Ya, Alhamdulillah. Sehat segar bugar. Tuh lihat kumis bapak semakin lebat!” kata Pak Rimbo kemudian tertawa hingga kumisnya menutupi lubang hidung. “Jauh-jauh kesini, sedang apa di sini?” tambahnya. “Tidak pak. Hanya rindu dengan sekolah ini.” kataku.
10 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Rindu bapak juga tidak?” goda Pak Rimbo seraya menyolek ketiakku. “Ah, buat apa merindukan Pak Rimbo. Dulu Pak Rimbo kan sering menghukum saya.” kataku mengingat saat sekolah dulu. “Hahaha..siapa suruh datang terlambat?” kata Pak Rimbo. “Pak Rimbo seperti tidak tahu saja, jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh. Bayangkan pak, saya harus berangkat pukul 6 pagi, sementara untuk mandi saja saya butuh waktu 30 menit menimba air di sumur Pak. Itu juga kalau ada air bersih pak.” “Ya ya, tapi tugas bapak kan memang menghukum siswa yang terlambat. Jangan-jangan kamu kesini karena rindu bapak hukum ya?” kata Pak Rimbo tersenyum seraya mengambil cangkir kopinya. Aku tersenyum kecut. “Tidak pak, terima kasih!” “Oh ya Bono, kenapa dulu kamu keluar sekolah? Dengardengar masalah biaya?” tanya Pak Rimbo setelah meneguk kopi hangatnya. “Iya pak, tak ada uang buat sekolah.” kataku sedikit malu.
11 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kamu kan cukup pintar, terakhir dapat peringkat berapa?” tanya Pak Rimbo seraya melinting ujung kumisnya. “Dapat peringkat 7 pak.” jawabku. “Nah itu dia, sayang kan?” kata Pak Rimbo keras seraya menepuk punggungku, hampir saja mataku copot dibuatnya. Aku menelan ludah sejenak, “Iya pak, padahal Bono punya cita-cita jadi guru. Tapi kepergian ibu seakan-akan membuyarkan itu pak. Terkadang Bono pikir Tuhan tak adil.” kataku. “Hushh..jangan berkata seperti itu! Dosa! Tidak adil bagaimana maksudmu?” tanya Pak Rimbo. “Teman-teman Bono bisa bersekolah walau prestasi mereka tak sebagus Bono, bahkan suka membolos. Sementara Bono yang sangat semangat bersekolah, sekarang hanya bisa melihat mereka bersekolah. Ini karena Tuhan mengambil ibu, pak!” kataku mulai larut dalam kesedihan.
12 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, selalu ada hikmah dari cobaan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi bersabarlah, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya.” nasehat Pak Rimbo. “Ayah juga bilang seperti itu, tapi apa pak? Bono tak bisa melakukan apapun, ingin membantu ayah melaut saja tidak boleh!” kataku ketus. “Bono, pasti ayahmu punya alasan untuk melarangmu melaut. Mungkin karena usiamu belum pantas untuk melaut, atau bisa jadi ayahmu masih trauma dengan kejadian ibumu yang tenggelam saat ikut ayahmu melaut.” kata Pak Rimbo. “Pak Rimbo benar, Bono jadi rindu ibu.” kataku. Pak Rimbo sedikit terbata-bata, “Aahh..maaf Bono, bapak turut berduka cita. Ya sudahlah, jangan dibahas lagi. Kamu rindu guru-gurumu tidak?” Pak Rimbo mengalihkan pembicaraan. “Iya pak. Pasti mereka sedang sibuk mengajar ya pak?” kataku sambil mengernyitkan dahi mencoba melihat kegiatan di dalam kelas.
13 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Coba tengok saja sana, tapi jangan mengganggu ya?” kata Pak Rimbo mempersilahkan. “Siap pak jendral!” kataku seraya mengambil sikap hormat pada Pak Rimbo. Pak Rimbo hanya tertawa terkekeh. Aku pergi meninggalkan Pak Rimbo dan singgah di teras ruang kelas V, kelas terakhir aku bersekolah. Di sana aku mengintip proses belajar dari jendela dan sesekali ikut menghitung di atas tanah soal matematika yang diberikan oleh guru yang mengajar. Kalau saja aku masih sekolah mungkin saat ini aku sudah jadi siswa SMP. Dulu aku sangat suka sekali pelajaran matematika. Pelajaran yang sekarang sedang diajarkan. Ku rasa aku lebih cepat menghitung daripada murid di dalam. Tentu saja, aku hanya mengulang dan coba mengingat-ingat apa yang pernah aku pelajari dulu. Saat sedang asyik menghitung, aku dikagetkan oleh suara lembut dari arah belakang. “Bono?”
14 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku menoleh dan ku lihat Bu Astuti berdiri melihatku. Ia adalah guru kelas V, guru yang sama saat aku masih bersekolah. Dulu ia sangat baik padaku, bisa dikatakan ia adalah ibuku di sekolah. Ia datang dari luar desa, kemudian mengabdi di desaku. “Ehh Bu Astuti, maaf bu jadi mengganggu.” kataku tersipu malu. “Ahh tidak. Sudah lama ibu tidak melihatmu. Tapi badanmu sepertinya tidak jauh beda dengan terakhir kali ibu lihat.” kata Bu Astuti, pandangannya menggerayangi tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku hanya menunduk malu. Kemudian Bu Astuti mendekat dan melihat coretanku di atas tanah. Dia tersenyum dan berkata, “Apa cita-citamu nak?” “Guru seperti Bu Astuti. Tapi rasanya itu tak mungkin bu.” jawabku putus asa. “Kenapa tak mungkin?” tanya Bu Astuti.
15 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kata ayah, harus kuliah dulu kalau mau jadi guru seperti Bu Astuti. Sekolah saja Bono tidak selesai, apalagi kuliah?” kataku menahan diri tidak bersedih. “Andai saja ibu bisa membantumu nak. Tapi tunggu sebentar!” kata Bu Astuti seperti mengingat sesuatu kemudian ia masuk ke dalam kelas. “Ini untukmu.” kata Bu Astuti kembali seraya menyodorkan buku matematika kepadaku. Aku sangat senang. Ku terima dan ku peluk buku itu. “Terima kasih bu.” kataku girang. “Iya belajarlah dari buku itu.” kata Bu Astuti lembut. “Baik bu, tapi bagaimana dengan Bu Astuti?” kataku sungkan. “Oh ya, tak usah khawatir. Ibu punya dua buah buku yang sama. Bawa saja tak apa. Ibu sangat senang melihat semangat belajarmu. Dan sebagai hadiahnya, buku ini untukmu.”
16 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Terima kasih, bu. Terima kasih.” ku peluk Bu Astuti, erat sekali. Aku sangat senang, sama seperti aku sekolah dulu. Bu Astuti mengusap rambutku, seakan tak jijik dengan badan dan pakaianku yang kotor. “Bono, tetap rajin belajar ya? Walau sekarang kamu tak bersekolah lagi, tapi bukan berarti kamu juga harus berhenti belajar.” Bu Astuti menasehatiku. “Baik bu, apalagi Bu Astuti memberikan buku ini. Pasti Bono tambah semangat dalam belajar, bu.” kataku. “Bagus kalau begitu. Ya, sudah Bu Astuti mau melanjutkan mengajar ya? Jaga dan pelajari buku itu.” Bu Astuti tersenyum lembut padaku. “Baik, bu. Bono pamit pulang ya, bu? Assalamualaikum.” Tak sabar aku berpamitan pulang. “Wa’alaikumusalam.” Bu Astuti mempersilahkan, tak lupa ku cium tangannya. Di gerbang sekolah ku ambil sikap hormat pada Pak Rimbo dan berpamitan pulang juga padanya.
17 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Pak Rimbo, Bono pamit pulang!” kataku setengah keras. “Iya iya, hati-hati nak! eh bawa apa itu?” tanya Pak Rimbo. “Buku matematika pak, diberi Bu Astuti.” kataku sambil berlari kegirangan. “Owalah Bono..Bono.” kata Pak Rimbo menggelengkan kepala kemudian tersenyum. Aku
berlari
seraya
mengangkat
tinggi-tinggi
buku
matematika yang diberikan Bu Astuti. Sesampai di rumah, ku cari lagi buku-buku usangku. Ku buka lembar yang masih kosong dan ku kerjakan beberapa soal dari buku matematika itu. Aku sangat bersemangat. Walau mungkin cita-citaku menjadi guru jauh dari kenyataan, aku tidak mau menjadi orang yang bodoh. Aku ingin pintar seperti mereka yang masih bersekolah. Siapa tahu ada kesempatan suatu saat nanti. Kata kebanyakan orang hidup adalah sebuah pilihan. Setiap orang berhak memilih hidupnya masing-masing. Aku juga punya pilihan. Aku sudah terbiasa ditemani pantai, lautan, perahu dan
18 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
ikan-ikan. Tak salah jika kemudian pilihan hidupku sementara ini menjadi seorang nelayan seperti ayah. Hanya pekerjaan itu yang mungkin aku lakukan, sambil menunggu keajaiban dari Allah yang mampu mewujudkan cita-citaku menjadi seorang guru. Aku bahagia. Bukankah pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang bahagia mambuat segala pekerjaan menjadi mudah. Aku percaya bahwa inilah garis hidup yang Allah berikan padaku. Aku selalu bersyukur dengan semua itu. Aku yakin nelayan pun punya peranan penting dalam kehidupan, tak kalah dengan peran pentingnya seorang guru. Kalau tidak ada nelayan, bagaimana bisa kita semua menikmati lezatnya ikan dan makanan-makanan laut lainnya. Ibu yang tak pernah putus asa semasa hidupnya dan ayah yang tak lelah bekerja adalah penyemangat hidupku. Aku tahu pekerjaan menjadi seorang nelayan bukanlah pekerjaan yang hina. Aku ingin suatu saat kelak bisa hidup lebih baik dari orangtuaku kini. Aku sepakat dengan batinku untuk
19 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
terus berusaha menjadi anak yang patuh dan cinta pada orangtua. Agar di masa yang akan datang aku tidak hanya dapat berguna bagi orangtua melainkan juga untuk orang lain, agama, bangsa dan negara. Aku yakin orangtuaku tak mungkin menyesatkanku karena mereka sangat menyayangiku. Akan ku patuhi semua yang orangtuaku nasehatkan. Semua orangtua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kalau memang ini adalah garis hidupku. Aku yakin garis hidupku tidaklah buruk. Aku tinggal dengan orangtua yang sangat menyayangiku. Walau sekarang tinggal tersisa ayah, namun ku rasa ibu masih saja memantauku dari surga. Bukan karena
ayah
tak
ingin
aku
pandai
sehingga
ia
tak
menyekolahkanku. Namun karena tuntutan ekonomi yang memaksaku berhenti sekolah. Andai ayah mampu pasti ayah bisa menyekolahkanku hingga aku sarjana seperti yang pernah ku lihat di televisi Balai Desa. Tak apa aku ikhlas menerima semua ini. Buku yang di berikan Bu Astuti ini tidak akan aku
20 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
terlantarkan. Buku ini jadi suatu tanda bahwa masih ada orang yang percaya bahwa aku masih bisa mewujudkan cita-citaku. Kalau orang lain saja percaya, kenapa aku tidak? Kuncinya hanya rajin belajar walau dengan segala keterbatasan yang ada. Mungkin saja dari buku ini aku memiliki kesempatan menjadi guru seperti Bu Astuti. Insya Allah.
21 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
NYONYA SURATI
“Ipung, ayo lihat sabung ayam di lapangan!” ajakku. “Ah kamu bercanda Bon, kamu kan sudah tahu aku takut pada hewan itu!” kata Ipung cemberut. “Ciyee yang takut sama ayam, bibirnya manyun mau saingan sama ayam ya?” canda Ara. Kemudian aku dan Ara menertawai wajah Ipung yang terlihat lucu. Ipung hanya menatap polos kami berdua. Ara dan Ipung adalah teman bermainku, mereka sama sepertiku. Putus sekolah. Namun, dari segi umur aku lebih tua 2 tahun dari mereka. “Ya sudah, ya sudah, jangan cemberut lagi. Kita main kucing dan tikus saja yuk?” ajak Ara. “Ya aku setuju, lebih setuju lagi kalau Ipung yang jadi tikusnya. Lihat saja bibirnya, dari tadi manyun terus seperti bibir
22 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
tikus.” kataku kemudian tertawa. Tak mau dijadikan bulanbulanan, Ipung membalas, “Biar saja bibirku seperti bibir tikus, daripada bibirmu seperti bibir kuda!” Tawaku semakin keras seraya menepuk lengan kanan Ipung. Ara pun ikut tertawa, lagi-lagi Ipung hanya terbengongbengong. “Sudah, sudah. Ayo kita mulai hompimpa saja.” kata Ara. Kami
bertiga
mendekat
dan
mengambil
posisi
untuk
menentukan siapa yang jadi kucing, siapa yang jadi tikus. “Hompimpa alaiyum gambreng.” teriak kami bersamaan. “Ipung jadi kucing!” teriakku dan Ara. Kemudian aku dan Ara berlari menjauhi Ipung. Entah karena kesal atau apa, Ipung langsung mengejarku. “Bono, lari, cepat lari!” teriak Ara. Aku berlari secepat mungkin mencoba meloloskan diri dari kejaran Ipung. Na’as aku tersandung dan jatuh, Ipung menangkapku.
23 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kena!! Bono jadi kucing!” kata Ipung kemudian berlari menjauh dariku. Tiba-tiba dari arah berlawanan terdengar seseorang berteriak. “Woyy Boncel, enggak sekolah? Dasar miskin! hahahaha” begitulah ejekan usil Aceng teman satu kampungku. Hal itu yang membuat aku benci padanya. Sebenarnya, aku malu, aku selalu diejek olehnya hanya karena ia sekolah dan aku tidak. Masa bodoh, cuek saja. Kalau aku tak diajarkan sabar oleh ayah, sudah ku hantamkan mulutnya pada karang-karang laut. Mungkin lebih baik aku menjauhinya. Ara dan Ipung menarikku menjauhi Aceng yang baru saja pulang sekolah. “Sudah, ayo pergi saja!” kata Ara. “Iya Bono, kita bermain saja di karang besar itu!” imbuh Ipung. Aku hanya menuruti mereka. Dalam kegundahan aku berdiri dan berjalan menuju karang yang paling besar. Ku lepas alas kakiku dan bersila di puncaknya kemudian berlagak seperti nahkoda kapal menghibur diri.
24 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ombaknya sangat besar, penumpang diharap berhatihati!” teriakku dari atas karang berlagak mengemudikan kapal besar. Sementara Ipung dan Ara duduk di atas karang yang lebih rendah dari karang yang ku duduki. “Awas kapten, ada gunung raksasa!” teriak Ipung. “Baiklah, penumpang harap berhati-hati, kapal akan menikung tajam ke kanan.” kataku seraya menyondongkan badan ke kanan. Ipung dan Ara mengikuti gerakkanku. Saat sedang asyik berkhayal jadi nahkoda, dari kejauhan ku lihat Mbah Menir. Siang itu, ia sedang mencari sisa-sisa kerang laut yang menempel di antara karang-karang yang mencuat saat air laut surut dan menyisakan sedikit air dalam cekungan karang. “Ipung, Ara kalian main berdua dulu ya? Aku mau menemui Mbah Menir!” kataku. “Terus siapa yang jadi nahkodanya?” tanya Ipung. “Sini berdiri!” kataku menarik lengan Ipung.
25 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Sekarang ku lantik kamu jadi asisten nahkoda. Antarkan tuan putri Ara ke pulau Bali!” kataku kemudian menepuk bahu kanan dan kiri Ipung. “Siap!! Akan aku laksanakan kapten!” kata Ipung dengan posisi siap. Ara tersenyum melihat tingkah kami kemudian berteriak “Dasar gila!” kami bertiga tertawa. “Ah sudah. Aku mau bantu Mbah Menir dulu. Besok kita main lagi.” kataku. “Biar kami ikut bantu saja, bagaimana?” tawar Ara. “Ah jangan, kalian main saja berdua.” aku menolak. “Kenapa?” tanya Ara. “Kalian tidak tahu, di antara karang itu banyak cacingnya. Kalian tidak takut kalau cacing itu masuk ke dalam kaki kalian?” aku menakut-nakuti mereka. “Halah, bilang saja kamu takut upahnya dibagi tiga.” kata Ipung menyindir.
26 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hahaha...kalau sudah tahu ya sudah, kalian main saja berdua. Ayo sana!” aku mendorong mereka berdua agar pergi. “Ipung, ayo kita main lompat tali saja!” ajak Ara. “Dasar pelit kamu Bon. Ayo Ra!” Ipung melompat dari atas karang dan pergi dengan Ara. Ku lihat Mbah Menir semakin sibuk. Aku mendekatinya dan bertanya, “Mbah, Bono bantu ya?” “Ah, kamu le. Boleh. Nanti simbah masakan kerang laut.” Mendengar simbah menawariku makanan seenak itu, tentu aku tak menolak dan semakin bersemangat membantu Mbah Menir. Ku masukan satu per satu kerang yang ku cabut dari karang ke dalam kain jarit yang terikat kuat di badan Mbah Menir. Mbah Menir adalah bidan yang membantu persalinanku dulu. Ia sangat mengenal ibuku, karena Mbah Menir adalah teman karib nenekku yang juga sudah meninggal belasan tahun lalu. Jadi, ia banyak tahu tentang keluargaku. “Ayo le, sudah cukup banyak yang kita kumpulkan.” ajak Mbah Menir.
27 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku menurut dan mengikuti langkah Mbah Menir menuju rumahnya. “Nanti sesampainya di rumah, kamu bantu simbah mencuci kerangnya ya?” pinta Mbah Menir. “Baik mbah. Kalau buat Mbah Menir apapun Bono lakukan.” candaku. “Kalau begitu, sekalian saja nyapu, ngepel dan cuci baju simbah ya le?” Mbah Menir membalas candaku. “Ah kalau itu Bono menyerah mbah. Rumah simbah kan luasnya seperti lapangan sepak bola. Belum lagi baju-baju simbah kan mahal-mahal, kalau rusak bagaimana?” kataku. “Kamu bisa saja, le.” Mbah Menir mencubit gemas pipiku. Akhirnya kami sampai di rumah Mbah Menir. Rumahnya jauh lebih besar dari rumahku, dindingnya sudah berupa susunan batu bata dan semen. Beberapa perabotan rumahnya juga sudah lebih baik. Rimbun rindangnya pepohonan di halaman rumahnya
28 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
yang luas membuat suasana rumahnya sangat sejuk untuk cuaca pesisir pantai yang cenderung panas. “Duduk dulu, simbah mau mempersiapkan alat-alat memasaknya. Nanti jangan lupa bantu simbah mencuci kerangnya ya, le?” kata Mbah Menir. “Baik mbah.” Aku duduk di halaman rumahnya, Mbah Menir masuk ke dalam rumah. Ku rebahkan tubuhku pada lincak tua yang berderit menahan bobot tubuhku. “Ah, nyamannya.” pikirku. Mbah Menir terlihat sibuk mempersiapkan alat dan bahan memasak di
dapurnya. Merasa
sungkan, aku
beranjak
membantunya. “Mbah, mana? Katanya Bono yang mencuci kerang.“ kataku seraya mencari kerang yang akan ku cuci. “Owalah iya le, itu di belakang dekat sumur. Tinggal di cuci saja, sudah simbah siapkan tempatnya le.” kata Mbah Menir.
29 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Rumah simbah bagus ya? Baru kali ini Bono masuk rumah simbah yang baru.” kataku seraya mencuci kerang. “Ah, tidak jauh beda dengan rumahmu. Rumah simbah jelek.” Mbah Menir merendah. “Kamu terakhir kesini waktu ibumu meninggal. Jadi mungkin kamu pangling.” Aku tertegun. Aku ingat ibuku, Nyonya Surati. Ibu adalah sosok yang lembut dan penyayang. Ibu tak pernah sedikitpun marah kepadaku. Aku ingat, setiap aku menangis, ibu selalu mengusap rambutku dan memberiku segelas air hangat. Ya, Nyonya Surati, nama ibuku, sosok yang penuh perhatian. Tetangganya juga sangat segan padanya, tidak pernah sedikitpun dia meminta-minta untuk mencukupi hidupnya. Dia pekerja keras, pekerjaan halal apapun akan dia lakoni demi mendapat sedikit rizki untuk kebutuhan hidup. Bahkan ditengah kekurangannya, ibu tak ragu untuk membantu tetangganya walau harus mengeluarkan uang sekalipun. Aku bangga memiliki ibu seperti Nyonya Surati.
30 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Sayang, semua itu cepat berlalu. Terakhir aku melihat ibu saat umurku masih 10 tahun. Saat itu aku masih bersekolah walau dengan keterbatasan. Tas saja tak punya, alhasil kantung kresek aku jadikan alat untuk membawa buku-buku sekolahku. Sepatuku kumal, warisan ayah semasa sekolah dulu. Baju dan bukuku adalah hasil sumbangan dari sekolah untuk anak tak mampu. Saat itu aku sedang bersekolah, menerima pelajaran dari guruku. Tiba-tiba salah seorang tetanggaku berteriak histeris, “Bonooooo, Bonoooo, ibumu, ibumu...” Aku beranjak dari bangkuku dan bertanya, “Ibu kenapa?” “Ibumu tenggelam, meninggal!” Aku terhentak dan segera berlari menuju rumah. Disana ku dapati tetangga telah berkerumun. Ku lihat mayat ibu berada di tengah kerumunan bersama ayah yang menangisinya. Aku berlutut dan memeluk tubuh ibu yang basah dan dingin. Aku menangis, pahit menerima kenyataan.
31 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ibuuuuuuuuuu....” teriakku memekikan telinga. Rasanya aku tak rela melepaskan pelukkan ini. Aku ingin selalu bersama ibu. Ibulah pengobat hatiku kala aku sedih. Tapi kini, ibu telah tiada. Siapa yang sanggup mengobati kesedihanku ditinggal pergi ibu? Sampai tubuh ibu dimakamkan, aku masih mengingat senyumnya dengan jelas. “Hei..jangan melamun..” tiba-tiba suara Mbah Menir menyadarkanku. “Sudah bersih belum? Mau simbah masak kerangnya.” kata Mbah Menir mengagetkanku. “Oh iya mbah. Sudah, cangkangnya juga sudah Bono buang mbah.” kataku terkaget-kaget. “Kamu sedang melamunkan apa le?” tanya Mbah Menir. “Emmm..ibu, mbah. Sudah 2 tahun berlalu tapi Bono tetap ingat kejadian itu. Seringkali Bono rindu pada ibu.” kataku. “Ibumu itu memang luar biasa, le. Sama seperti kamu, santun, suka menolong, rajin ibadahnya. Dulu waktu ibumu
32 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
masih kecil, setiap sore ibumu sering membantu simbah memasak. Seperti kamu sekarang ini.” Mbah Menir bercerita. “Begitu mbah? Pantas saja ibu pintar memasak, ternyata simbah ya gurunya?” kataku buat Mbah Menir tersipu. Ku lihat Mbah Menir sangat cekatan memasukan bumbu dan mengolah kerang-kerang itu. Bau sedap mulai tercium. Air liurku mulai mengencer, lambungku seakan-akan meronta tak sabar ingin merasakan sedapnya masakan Mbah Menir. “Masakannya sudah jadi, ayo makan!” ajak Mbah Menir. Mbah Menir menyiapkan piring berisi nasi hangat untukku. Kemudian Mbah Menir menuangkan lauknya, Mbah Menir baik sekali sama seperti ibuku dulu. Seketika sosok ibu muncul dalam diri Mbah Menir, aku meneteskan air mata. Mbah Menir heran dan bertanya, “Kenapa menangis?” “Bono ingat ibu.” kataku lirih. Mbah Menir tersenyum, “Sudah, makan dahulu selagi nasimu masih hangat.”
33 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Senyum
Mbah
Menir
hampir
sama
seperti
ibu,
mendamaikan. Aku sangat nyaman berada di dekat Mbah Menir. Walau perawakannya jauh berbeda, tapi rasa sayang Mbah Menir kepadaku hampir sama seperti ibu. Aku rindu ibu. Tiba-tiba Mbah Menir beranjak dari bangkunya. “Tunggu sebentar le, ada yang ingin simbah tunjukan padamu!” Mbah Menir masuk ke kamarnya dan segera keluar dengan membawa sebuah radio yang kelihatannya sudah tua. Mbah Menir tersenyum dan memasukkan sebuah kaset ke dalam radio tua itu. Baru kali ini aku mengerti, ternyata radio tua itu juga bisa dijadikan pemutar kaset. Mbah Menir memutar sebuah lagu keroncong. Aku tak mengerti isi lagu itu. Tapi iramanya mendayu-dayu mengungkap kejayaan tempo dulu. Ku pegang radio itu dan menilik gerakan memutar di dalamnya. Penasaran aku dibuatnya. Mbah Menir berkata padaku, “Ini adalah lagu kenangan ibumu le, dahulu ibumu suka sekali memutar lagu ini.”
34 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kenapa ibu suka lagu ini mbah?” tanyaku penasaran. “Ini lagu masa muda ibumu dahulu, saat ibumu jatuh cinta pada ayahmu.” jelas Mbah Menir seraya tersenyum. “Jatuh cinta mbah? Apa itu mbah?” “Jatuh cinta itu, apa ya? Emmm kata anak muda jaman sekarang, jatuh cinta itu lope-lope.” jawabnya bercanda. “Lope-lope itu apa mbah?” tanyaku semakin penasaran. “Lope-lope itu ya orang yang suka pada lawan jenisnya.” Mbah Menir menjelaskan. Aku semakin tak mengerti. “Bono suka bermain dengan Ara, berarti Bono juga lopelope pada Ara ya mbah?” kataku dengan mata berbinar. Seketika Mbah Menir terdiam, menghentikan kunyahan nasi di mulutnya, sadar kalau aku belum mengerti betul tentang jatuh cinta. “Sudah, selesaikan makanmu dulu!” perintah Mbah Menir gugup menghindari pertanyaan lainnya yang lebih jauh. “Tapi simbah belum menjawab pertanyaan Bono.” kataku bersikeras.
35 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya nanti simbah jawab, habiskan nasimu dulu!” katanya. Aku makan dengan lahapnya, sangat jarang aku menikmati makanan selezat ini. Selain Mbah Menir, tidak ada tetangga yang sebaik dia. “Sudah selesai mbah. Biar Bono cuci piringnya.” “Ehhh, sudah tidak usah. Biar simbah saja! Hari sudah mulai petang, sebaiknya kamu pulang dan bawa kerang ini untuk lauk makan di rumah.” kata Mbah Menir seraya menyodorkan rantang berisi masakan kerang laut. “Terima kasih mbah.” kataku senang. “Tapi simbah tadi sudah janji, selesai makan simbah mau memberitahu apa Bono sudah lope-lope?” imbuhku masih penasaran. “Bono, lihat matahari sudah mau hilang dari langit. Kamu mau saat pulang nanti bertemu wewe gombel?” Mbah Menir menakutiku. “Ahhh tidak mbah.” aku merinding ketakutan.
36 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya sudah, cepatlah pulang. Bawa rantang itu untuk makan malam dengan ayahmu!” perintah Mbah Menir. Aku pun bergegas pulang sebelum matahari terbenam. “Iya mbah, Bono pulang dulu ya mbah? Assalamualaikum.“ “Wa’alaikumsalam putu lanang.” jawab Mbah Menir seraya tersenyum dan melambaikan tangan. Sesekali ku lihat isi rantang itu selama perjalanan pulang. Ku pikir ayah pasti akan senang. Karena malam ini tidak lagi makan makanan dengan bumbu garam saja. Dalam perasaan senang itu aku masih penasaran, jatuh cinta itu seperti apa? Suatu saat nanti Mbah Menir harus bertanggung jawab menghapus rasa penasaranku. Tak mungkin ia tak tahu, hanya Mbah Menir yang bisa memberiku jawaban karena aku tak berani bertanya pada ayah tentang jatuh cinta atau “lope-lope”.
37 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
DOA UNTUK IBU
“Allahu akbar..Allahu akbar...” Suara adzan memecah keheningan malam diiringi sinar mentari yang sayup-sayup kemerahan muncul dari arah timur. Aku terbangun dari mimpiku, ku seka mata yang masih enggan untuk ku buka. “Ah lagi-lagi ayah belum pulang.” Ku lihat sayur kerang yang ku sisakan untuk ayah semalam masih saja utuh. Aku bergegas mengambil air wudhu dan sarung usangku yang ku gantung pada paku yang menancap di tiang kayu rumahku. Aku berjalan terhuyung menuju surau kecil di kampungku. Aku mulai sholat berjamaah dengan khusyuk, sedikit menguap mungkin masih wajar untuk anak seusiaku. Seperti biasa aku berdoa untuk ayah dan ibu. Selepas sholat shubuh aku duduk di dekat pantai menunggu ayah pulang.
38 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Boncel! Mana kucing sialanmu itu!” suara menggelegar mengalahkan deru ombak. Tiba-tiba ku lihat dari arah belakang Mak Nasib mengacungkan gagang sapunya ke arahku, ia terlihat murka. “Aku tak tahu mak. Ada apa?” aku ketakutan. “Lagi-lagi ia mencuri ikan asinku. Dasar kucing kudisan!” “Awas kalau aku lihat dia, ku patahkan tulang punggungnya dengan sapu ini!” Mak Nasib terengah-engah. Aku hanya bergeming tak berani membantah. “Hei, mau kemana kau bocah?” Tanpa
perduli
aku
berlari
mencari
Doreng
dan
meninggalkan Mak Nasib yang masih jengkel. Berjam-jam ku telusuri sudut-sudut kampung namun aku tak menemukannya. Aku menuju rumah dan ku dapati Doreng terbujur di dekat kaki meja dengan memar di kepala. Aku berjongkok di dekat Doreng yang terkulai lemah dan merintih. Ku elus tengkuknya penuh
39 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
kasih sayang, ia pun membalasnya dengan menjilati tanganku seakan mengerti siapa empunya. “Kasihan sekali kau Reng, tunggu biar ku ambilkan air dan kain untuk menyeka memarmu.” kataku sedih. Ku petal kepalanya dengan kain basah. Lagi-lagi ia hanya merintih. Aku menatapnya iba. “Kamu jangan nakal lagi ya Reng? Sungguh biadab yang melukaimu. Biar saja, kita doakan saja tangannya pengkor sebelah.” gerutuku kesal. “Jangan sembarangan kalau bicara!” Tiba-tiba bulu kudukku meruap, sosok tinggi besar berdiri di belakangku. Perlahan ku palingkan wajah, “Ayah.” “Doreng kenapa le?” kata ayah dengan peluh yang mengucur bagai hujan barat. “Bono tak tahu yah, mungkin dipukul Mak Nasib. Tadi Bono bertemu Mak Nasib yang jengkel karena ikan asinnya dicuri Doreng lagi.” jelasku.
40 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Lain kali, jaga dan beri makan kucingmu dengan baik. Jadi, ia tidak mencuri ikan asin lagi.” kata ayah bijak. Aku hanya mengangguk. “Le, goreng beberapa ikan yang ayah dapat, sisakan sirip ekornya untuk Doreng!” perintah ayah seraya menyodorkan keranjang bambu berisi ikan. Aku segera mengambil dua ikan yang masih segar dan menggorengnya dengan bumbu garam. Ku sajikan ikan yang sudah matang ke hadapan ayah yang masih mengibas handuknya untuk menghilangkan panas tubuh. “Ini sayur dari siapa le?” tanya ayah seraya mencium rantang di atas meja. “Oh itu dari Mbah Menir, yah. Kemarin Bono membantu Mbah Menir mencari kerang, lalu Mbah Menir memberikan itu untuk kita. Tapi semalam ayah tidak pulang, jadi tidak habis, yah.” jelasku.
41 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Oh begitu, iya semalam ayah menginap di gubuk dekat pantai dengan Mas Ikin membetulkan jaring. Sepertinya belum bau, ayo kita makan saja le!” kata ayah. “Iya, yah. Kita habiskan saja, nanti mubazir.” kataku seraya menyendokkan nasi dari Mbah Menir sisa tadi malam untuk ayah. Ayah menahan tanganku, “Nasi itu buat kamu saja, ayah makan dengan singkong rebus sudah cukup.” Aku menurut. “Ayah, besok Bono ikut mencari ikan ya?”pintaku. “Meh ngopo?” kata ayah seraya mencuil ikan dan memakannya dengan singkong rebus. “Bono ingin membantu ayah bekerja. Bono bosan di rumah.” pintaku semakin menggebu. “Ndak usah Bono, kamu masih 12 tahun. Tunggu hingga kamu berumur 17 atau 19 tahun.” larang ayah. “Tapi Bono sudah cukup berani melawan ganasnya ombak laut, yah. Bono selalu jadi kapten nahkoda saat bermain dengan Ipung dan Ara.” kataku bersikeras.
42 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kamu pikir melaut itu seperti bermain, le?” kata ayah. “Kenapa sih, ayah selalu saja melarang Bono ikut ayah melaut!” kataku ketus. “Sudah diam! Makan saja ikannya, ra usah nglawan!” kata ayah meradang. Aku tersentak, kecewa dan masuk kamarku. Ku kunci pintu rapat-rapat dengan gerendel paku. Aku tahu ayah lelah, jadi emosinya cepat naik. Tapi tidak perlu membentakku seperti itu. Aku ingin membantu ayah bekerja. Aku kasihan pada ayah, meski kondisi fisiknya sudah mulai sakit-sakitan namun ia paksakan untuk bekerja. Aku duduk di lantai menghadap jendela. Ku lihat foto Ir. Soekarno idola ayahku tertempel di dinding kayu dekat jendela. Foto itu sudah memudar, namun ayah tetap menyimpannya. Ialah sosok yang jadi panutan ayah mendidik anaknya. Keras namun penyayang. Ayah memang sudah tak mampu menyekolahkanku. Namun, ia bisa memberi pelajaran hidup yang berharga.
43 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bagaimana dapat bertahan hidup dengan tidak menyusahkan orang lain. Ayah juga sangat telaten mengajariku membaca dan menulis huruf Arab. Kini aku bisa khatam Al-Qur’an juga karena jasa ayah. Tinggal di kampung yang tertutup kokohnya Pulau Nusakambangan memang tak mudah. Harus benar-benar berjuang mencari sesuap nasi. Wajar saja, jarak kampung ke kota sangat jauh. Apalagi jika harus melewati jalan darat, belum sampai di kota uang kami sudah habis untuk menumpang kendaraan umum. Hanya singkong yang mampu menjadi pengganti nasi. Tapi aku tetap bersyukur, karena bukan nasi kering yang ku telan dan menyumbat rasa lapar di perutku. Kampungku berada di balik Pulau Nusakambangan. Pulau penjara tempat penjahat kelas kakap pernah mendekam. Pulau dengan berbagai keseraman yang didengungkan, padahal kenyataannya bertolak belakang. Pulau Nusakambangan sangat eksotis. Aku sering menghabiskan akhir pekan di pasir putihnya
44 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
yang berkilauan bak pecahan permata. Kata ayah, dahulu kampungku adalah lautan. Kemudian tanah yang mengendap berubah jadi daratan. Daratan itu sering disinggahi nelayan untuk
beristirahat,
hingga
akhirnya
nelayan-nelayan
itu
membangun sebuah rumah dan jadilah kampungku sekarang. “Tok tok tok” Ayah mengetuk pintu dan memanggilku. “Bono. Keluar, le! Ayah ingin bicara denganmu.” Aku diam, tak menyahut sebagai protes atas sikap ayah tadi. “Le, ayah mau bicara. Cepat keluar!” kata ayah dengan nada meninggi. Dengan wajah masygul aku keluar dan duduk di bangku kayu bersama ayah. Ayah menatapku tajam. Aku takut membalas tatapannya. Aku hanya menunduk. “Kamu tahu kenapa ayah melarangmu melaut saat ini?” tanya ayah menggenggam pundakku. Aku hanya menggelengkan kepala.
45 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ingat peristiwa saat ibumu meninggal?” tanya ayah, binar matanya mulai meredup. Aku palingkan pandangan ke arah ayah dan aku tertegun memandang mata ayah. “Saat itu ibumu tenggelam karena perahu ayah tersapu ombak. Untungnya saat itu ayah berhasil meraih sebilah kayu yang melintas. Sementara ibumu....” ayah terdiam, bibirnya bergetar hebat dan air matanya mulai menetes. Untuk kedua kalinya setelah pemakaman ibu, ku lihat ayah menangis. Sosok keras dengan tubuh tinggi besar menangis di hadapanku. Rasa cintanya pada ibu sangat luar biasa. Aku memeluk ayah dan menahan air mataku dengan handuk yang tergantung di pundaknya. “Bono, kamu..kangen ibumu le?” tanya ayah lirih dengan nada terputus-putus. Aku mengangguk menahan tangis dengan bibirku. “Ayah juga kangen ibumu.” tambah ayah. “Kita ke kuburan ibu saja, yah.” ajakku.
46 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kamu mau ayah ajak ke sana, le?”tanya ayah seraya menyeka air mataku. Aku mengangguk tak sabar. Rasa rindu membuat ayah membawaku ke kuburan tak berpagar dekat rawa tempat ibu dimakamkan. Sore, hari itu juga. Batu nisannya hanya terlihat seujung kuku didesak bergumpal-gumpal ilalang. Aku melihatnya miris, apakah ibu nyaman dengan tempat peristirahatan terakhir yang buruk seperti ini? Aku saja gerah melihatnya. Ku ayunkan clurit menebas ilalang kurang ajar yang mengotori kuburan ibuku. Seandainya aku bisa kesini setiap hari, pasti kuburan ibu akan terlihat layak. Sayangnya, terlalu jauh dari rumah. Harus menggunakan perahu untuk menyeberang ke area makam. Sementara aku pun tak bisa menunggangi sepeda onthel milik ayah untuk menuju dermaga. Ayah mengusap nama ibu dengan kain basah. Pandangannya nanar seakan-akan ayah ingin memeluk ibu. Aku melihatnya dan mendekati ayah. Ayah tersadar, melihatku dan mengusap rambutku.
47 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, sudah. Sekarang doakan ibumu!” perintah ayah seraya memeluk pundakku. Hatiku berdebar, inikah rasa cinta ayah sebenarnya? Merinding. Sesaat aku seperti merasakan kehadiran ibu di sisi kananku sementara ayah memeluk pundak dari sisi kiriku. “Apa yang kamu tunggu? Ndang doakan ibumu!” perintah ayah mengagetkanku. “I..iya, yah” “Jangan lupa baca basmallah, nanti ayah amin-kan.” kata ayah mengingatkan. Aku bersiap mengambil sikap berdoa. Sebelumnya ku sentuh terlebih dahulu nisan ibu tepat pada namanya dengan tangan kananku. Dalam hati aku berkata, “ibu aku rindu.” Kemudian aku menengadahkan kedua tangan dan segera berdoa. “Ya Allah. Tempatkan ibuku dalam Surga ‘Adn-Mu. Dia adalah mujahid. Mati demi mencukupi kehidupan anaknya. Berjuang
di
jalan-Mu
menyehatkan
anaknya.
mendapatkan Entah
upah
dengan
apa
halal aku
untuk bisa
48 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
membalasnya, selain memberinya lantunan doa yang dapat membangunkannya dalam keadaan suci di hari akhir nanti. Sungguh aku tak marah pada-Mu yang telah menjemput ibuku saat aku masih sangat membutuhkannya. Justru dengan demikian aku dapat selalu mendoakannya. Mungkin aku akan jadi anak yang lalai jika aku masih dimanja lembut telapak tangan ibuku. Seperti teman-teman yang berani menentang ibunya, membuatnya menangis dan sakit hati. Sungguh aku tak ingin seperti mereka. Aku lebih baik mencium kaki ibuku yang berlumpur daripada harus membuatnya menangis dan sakit hati. Muliakanlah ibuku Ya Allah, agar aku dapat bertemu dengannya dan ia menyambutku dengan wangi minyak kasturi dari Surga. Amiin”
49 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
RAIBNYA SI DORENG
Suatu sore, saat aku sedang asyik melipat kertas yang ku sobek dari sebuah buku menjadi pesawat terbang mainan, ku lihat Doreng melintas beberapa kali di depan pintu kamarku. Heran, aku keluarkan kepalaku dari balik tiang pintu kamarku. Doreng melihatku dan menatapku tak biasa. Ku dekati ia, berjongkok dan menyuruhnya tidur berkali-kali, ku elus kepala hingga tengkuknya agar ia tenang. Namun, ketika aku berhenti mengelus, ia kembali beranjak dan memandangku seakan ada yang ingin ia sampaikan. “Kamu mau makan?” tanyaku sedikit bingung. Sesaat sebelum berdiri mengambil makanan untuk Doreng, ku lihat makanannya masih utuh hanya saja sedikit berantakan tidak pada posisi saat aku menaruhnya. Tak mengerti apa yang Doreng mau, ku tinggalkan saja ia. Aku kembali ke kamarku dan
50 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
memainkan pesawat terbang kertas yang baru ku buat. Sejenak ku lupakan si Doreng, bersenang-senang memainkan pesawat dari kertas yang terbang tinggi dan jatuh menukik tajam. Ku terbangkan berulang-ulang pesawat mainanku dan terbang
keluar
melalui
pintu
kamar.
Aku
berlari
menghampirinya, saat akan ku ambil, aku teringat pada Doreng. Dia sudah tidak ada. Aku pun melupakan pesawat mainanku, ku cari doreng di bawah kursi dan meja, di dapur, kemudian di sekitar rumah tapi hasilnya nihil, ia tak terlihat bahkan gerak geriknya. Ku panggil namanya, “Doreng..Reng..Pus..Pus..Pus..Pus.” Ia pun tak menyahut. Hatiku mulai hancur dibuatnya. Aku coba mencarinya di jalanan desa namun Doreng tetap tidak ada. Aku putuskan untuk mengajak Ipung dan Ara ikut mencarinya. Aku datangi rumah Ipung dan memanggilnya, “Ipung..Ipung.” “Iya Bon, ada apa?” katanya dari dalam rumah.
51 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kau sedang apa? Bantu aku mencari Doreng yuk!” kataku terlihat panik. “Hanya membantu ibu menata ikan asin. Doreng kemana?” katanya heran. “Ahhh mana ku tahu, dia pergi tapi ini tidak seperti biasanya. Ayo kamu bisa bantu tidak?” kataku tergesa-gesa. “Sebentar, aku pamit dulu pada ibu.” katanya seraya berlari menuju dapur kemudian ia kembali dengan menenteng sandal japitnya. “Ayo kita cari!” katanya. “Kita ke rumah Ara dulu, lebih banyak yang mencari lebih baik.” kataku dengan langkah cepat. Ipung mengikuti langkahku. Tak lama kami sampai di rumah Ara, ku lihat ia sedang menyirami tanaman di depan rumahnya. “Araa...” teriakku dari kejauhan, ia menoleh ke arahku. “Kamu bisa bantu aku?” kataku. “Bantu apa Bon? Aku sedang menyirami tanaman ini.” katanya seraya menuangkan air dari gayungnya.
52 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bantu aku cari Doreng, kalau sudah ketemu nanti kami bantu menyirami tanamanmu.” kataku seraya menarik gayung yang digenggam Ara. “Ada apa sih?” kata Ara penasaran. “Sudah nanti ku jelaskan, ayo bantu cari dulu!” kataku seraya menarik tangan Ara, ia terlihat sempoyongan. “Aduhh sabar dong.” wajahnya cemberut. Kami bertiga pergi mencari Doreng hingga ke arah pantai. Di pantai aku bertemu Mas Ikin, teman ayahku melaut. Ia lebih muda dari ayahku. “Mas, lihat Doreng?” tanyaku. “Enggak Bon, Doreng hilang?” tanyanya. “Iya mas, enggak tahu pergi kemana.” jawabku panik. “Nanti
juga
pulang
sendiri
Bon.”
kata
Mas
Ikin
menenangkan. “Kali ini Bono rasa berbeda mas, dia tak pernah jauh dari rumah, kalau pun jauh, Bono panggil pasti dia mendekat.”
53 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
bibirku mulai melengkung sedih, khawatir pada Doreng. Melihatku yang sedang tak baik, ayah mendekat. “Ono opo le?” tanya ayah. Aku berlari memeluk pinggul ayah, “Doreng hilang yah.” Ayah menghela nafas, “Sudah, tunggu saja di rumah. Kalau belum juga kembali, besok kita cari bersama.” kata ayah ikut menenangkan. “Ayo pulang, hari sudah semakin petang. Ipung dan Ara juga pulang ya?” ajak ayah. Mereka mengangguk. Ayah mengantar Ipung dan Ara terlebih dahulu. Kemudian aku pun pulang bersama ayah, sesekali pandanganku fokus melihat ke arah celah-celah semak belukar yang ku lewati, berharap Doreng terlihat. Sore berganti malam, biasanya aku tengah asyik bercanda dengan Doreng. Tapi malam ini berbeda, hanya suara jangkrik yang bergiliran menggelitik telingaku. Ah, aku tak sabar menanti
54 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
esok pagi, aku ingin matahari segera terbit. Kesepian, ku dekati ayah yang sedang membetulkan jaring. “Yah, besok mau cari Doreng kemana?” tanyaku. “Di sekitar kampung saja, kalau tidak ketemu ya di kampung sebelah.” kata ayah yakin. “Kalau tidak ketemu juga yah?” tanyaku memastikan. “Ya doakan saja ia masih hidup.” jawab ayah seraya memandangku. “Kalau Doreng sudah mati yah?” tanyaku lugu. “Ya doakan saja masuk surga.” jawab ayah setengah tersenyum. “Iya yah, tapi kalo masuk neraka bagaimana yah?” aku semakin mempersulit. Ayah mulai menggaruk kepalanya, “Emmm, kalau masuk neraka ya berarti sekarang Doreng sudah gosong.” canda ayah kemudian tertawa. “Sudah sana, masuk! Di luar dingin.” perintah ayah.
55 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku masuk ke dalam dengan sedikit menggerutu, ayah tak serius menjawab pertanyaan terakhirku. Ku raih pesawat mainanku yang tergeletak di atas dipan kemudian ku terbangkan sesekali. Pandanganku tertuju pada langit-langit rumah yang dipenuhi sarang laba-laba. Berkali-kali ku pahami lagi, ada apa dengan Doreng hingga ia tak ku temukan lagi. Otakku mulai dipenuhi dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana dan mengapa. Pertanyaan yang berjejal di otakku menguras energi dan seketika aku tertidur. Pagi-pagi sekali setelah selesai sholat shubuh, aku menarik tangan ayah untuk menepati janjinya mencari Doreng. “Ayah, ayo kita cari Doreng!” aku tak sabar. “Iya ayo, sabar to le.” kata ayah seraya meraih topinya dari atas meja. Aku dan ayah mulai mencarinya, menelusuri sudut-sudut desa hingga kami lelah. Aku hampir putus asa karena tak ada tanda-tanda Doreng akan ku temukan.
56 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Sudah kita pulang saja, le. Tunggu saja dia pulang sendiri. Doreng itu kan kucing yang pintar.” hibur ayah. Aku hanya mengangguk. Sesampainya di rumah aku duduk di kursi kayu dekat meja makan. Wajahku terlihat muram, mengetahui perihal yang sedang dialami anaknya Ayah berkata, “Sudahlah, pasrahkan saja.” Namun, aku tetap saja tak rela. Hampir tiga tahun bersama tak bisa dianggap sebentar untuk begitu saja melupakannya. Seakan aku sudah terikat secara batin dengan Doreng. Ibu yang menemukannya di pinggir jalan kemudian memberikannya padaku. Ku namai ia Doreng karena bulunya memiliki campuran warna pirang, hitam dan putih. Dulu ibu dan aku senang bercanda dengannya. Ia sangat suka memainkan bola dan bertingkah lucu. Doreng adalah kucing betina yang penurut, tidak seperti kebanyakan kucing kampung yang cenderung bertindak agresif. Kalau pun ia mencuri ikan asin yang sedang dijemur, itu karena aku lupa memberinya makan.
57 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Setelah ibu meninggal, Doreng satu-satunya teman bermainku di rumah. Saat aku bermain dengannya, seakan-akan ibu turut hadir menemaniku. Kini semua tinggal kenangan, Doreng tidak juga ku temukan. Aku sedih. Setiap memikirkan Doreng aku selalu mengingat betapa manjanya dia dulu. Betapa cerdasnya dan betapa khas dengkurannya saat ia tidur. Aku masih ingat suaranya ketika ku panggil untuk makan, "meonngg meoonggg", begitu juga setiap kali aku mengelus kepalanya. Belum lagi tingkah lucunya saat menarik-narik tali jaring yang terkadang membuat ayah marah besar. Aku mengingatnya dengan baik. Ia sudah seperti keluarga di rumah ini. Kini aku harus percaya Doreng ada di tempat yang baik sekarang. Kucing manis itu pasti sedang bahagia entah dimana. Sedikit ada penyesalan yang terlintas, berharap bisa memutar waktu. Andai saja waktu itu aku tak sibuk dengan pesawat
mainanku
dan
menggendong
Doreng
untuk
58 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
menenangkannya. Mungkin saat ini Doreng masih ada dan bermain bersamaku. Aku merindukan Doreng, mungkin Doreng juga merindukanku kalau ia masih hidup. Perasaan seperti ini terulang kembali, sama seperti saat aku kehilangan ibu. Aku sangat sedih, menangis dan tak bisa ku katakan bahwa aku baikbaik saja. Setiap hal yang terjadi pasti ada dampaknya dalam hidupku selanjutnya. Ku pastikan setelah kejadian ini, aku akan benar-benar sendiri tanpa Doreng. Aku coba menerima ini sebagai serentetan ujian yang Allah berikan padaku. Allah sudah mengatur semua ini, bukan untuk melemahkanku tapi untuk menguatkanku. La haula wala quwwata illa billah.
59 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
AMPUN, AYAH
Sebulan setelah Doreng menghilang, hatiku masih saja gundah dibuatnya. Beruntung aku masih memiliki teman seperti Ipung dan Ara. Aku hanya mampu bermain-main dengan mereka di tepian pantai. Di sudut yang lain, ayah bersama nelayan lainnya sedang sibuk membetulkan jaring. Ku ambil ranting kering tak jauh dariku. Kemudian ku gambar ayah, ibu, aku dan tak lupa Doreng dengan ikan asin kesukaannya. Ipung dan Ara berjongkok mengamati gambarku. Agar tak tersapu ombak, ku beri batu-batu mengitari gambar yang ku buat. Ternyata batu yang ku temukan tak cukup kuat menahan ombak. Ku putuskan mencari batu yang lebih besar sedikit lebih jauh dari tempat aku menggambar. “Ara tolong jaga gambarku dulu ya! Aku dan Ipung mau cari batu yang lebih besar!” kataku.
60 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya, aku jaga. Tapi jangan lama-lama ombaknya cukup besar.” kata Ara khawatir. “Ayo Pung. Kamu cari di sebelah sana, aku di sana! Cari yang seukuran kepalan tangan!” perintahku. Ipung mengangguk tanda ia telah mengerti. Ku ambil satu persatu dan ku kumpulkan ke dalam bagian depan kausku yang ku bentuk menjadi semacam wadah. Cukup lama aku mencari batu-batu itu, setelah ku pikir cukup aku kembali ke tempat dimana aku menggambar. “Ipung, sudah belum?” aku berteriak. “Ya sudah cukup, ini aku dapat banyak.” kata Ipung sambil menunjukkan kantung kresek berisi batu-batu yang cukup besar. “Dapat kantung kresek darimana Pung?” “Itu ada yang hanyut, ku lihat masih bagus jadi aku ambil.” “Cerdas kamu Pung!” pujiku buat Ipung tertawa bangga. “Siapa dulu? I.P.U.N.G gitu lho.” katanya sombong.
61 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Haduh. Baru dipuji sedikit, sudah lebar hidungmu, Pung. Ayo cepat kita kembali ke tempat kita menggambar tadi.” kataku. “Pasti wajah Ara sudah tak berbentuk karena bosan menunggu kita.” tambah Ipung. Kami tertawa. Kami segera kembali ke tempat kami menggambar. Dari kejauhan aku melihat ada yang aneh dengan gambar yang ku buat tadi. Aku mendekat dan berdiri tepat dimana aku menggambar. Alangkah terkejutnya ketika ku lihat gambarku sudah hancur porak poranda. Bukan karena ombak, ku lihat ada bekas sapuan kaki. Ara juga terduduk menangis. “Ara, siapa yang melakukan ini?” kataku kesal. Ara menunjuk ke suatu arah. Mataku mulai mencari pelakunya searah telunjuk Ara mengarah. Tak jauh ku lihat Aceng dan Munir membawa ranting yang ku gunakan untuk menggambar tadi. Sepertinya aku tahu siapa pelakunya. “Pung, kamu di sini saja. Jaga Ara!” kataku dongkol.
62 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya Bon. Kamu mau kemana?” katanya seraya membantu Ara berdiri. “Sudah diam saja di sini!” teriakku spontan. Aku berlari ke arah Aceng dan Munir kemudian berteriak, “woooooy!”. Mereka tersentak dan melihatku datang dengan wajah dongkol. Aku bertanya pada mereka, “Kalian yang menghancurkan gambar yang ku buat di sebelah sana?” “Kalau
iya
memang
kenapa?”
kata
Aceng
seraya
mematahkan ranting yang ku gunakan menggambar tadi. Aku hanya terdiam menahan kesal, tanganku mulai mengepal. Melihat reaksiku, Aceng menantang, “Berani? Ayo pukul!”. Aceng mendorongku hingga aku jatuh terduduk. Aku pikir walau badan Aceng lebih besar aku tidaklah takut, yang jadi masalah adalah ia bersama Munir, aku kalah jumlah. Mengajak Ipung membantuku berkelahi tak mungkin, ia penakut. Dengan ayam saja ia tak berani, apalagi harus menghadapi dua orang ini.
63 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kenapa diam saja? Takut?” bentak Aceng sok jagoan. Ingin sekali aku menghantam mulutnya, namun lagi-lagi nasehat ayah menahanku untuk bertindak brutal. “Ibumu sudah mati! Doreng juga sudah hilang mungkin dia juga mati sama seperti ibumu! Buat apa kamu gambar?” Aceng semakin menjadi-jadi. Kali ini sepertinya ia tak bisa ku biarkan, ku genggam pasir dan melemparkannya ke arah Aceng. “Ahhhh…Boncel sialan!!” Tak terima Aceng mencoba memukulku. Bogemnya tepat mengenai pelipisku. Segera aku membalasnya, ku hantamkan bogemku ke arah dagunya. Mantap, ia terhuyung. Akhirnya berkelahilah kami, Aceng tertinju beberapa kali kemudian meminta bantuan Munir. “Nir, bantu! Jangan diam saja! Kampret!” kata Aceng. Munir hendak menangkapku dari belakang tapi terkena tendanganku. Tendanganku tepat masuk ke bagian dadanya. Munir menahan nafas kesakitan. Ku lakukan tendangan yang
64 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
sama pada Aceng, namun nahas usahaku gagal. Aceng berhasil menangkap kaki kananku dan menariknya hingga aku jatuh tersungkur. Seketika Munir menggenggam kaki kiriku. Bersamasama mereka mengarakku hingga siku tanganku terluka terkena pecahan cangkang kerang. Mas Ikin yang kebetulan melintas melihat kejadian itu. Ia segera memberitahu ayahku, ”Mas, anakmu berkelahi dengan Aceng dan Munir.” “Owalah, dimana mereka?” tanya ayah naik pitam. “Di sudut pantai sebelah sana, mas.” kata Mas Ikin seraya menunjuk ke suatu arah. “Ayo kita ke sana, Kin.” ajak ayah. Ayah dan Mas Ikin mendekat. “Wooy, bubar!” teriak Mas Ikin dari kejauhan. Melihat ayahku datang, Aceng dan Munir lari ketakutan.
65 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Awas kalau ketemu, aku hajar kamu Cel!” kata Aceng masih bernapsu untuk berkelahi. Aku pun lari ketakutan, aku takut ayah akan memarahiku. “Ipung, Ara cepat kalian pulang saja!” teriakku seraya berlari menjauhi ayah dan Mas Ikin. Aku menuju rumah Mbah Menir, berharap perlindungan di sana. Sesampainya di rumah Mbah Menir, “Mbah..Mbah Menir, ini Bono mbah. Assalamualaikum.” kataku memanggil Mbah Menir dari luar rumah. Tak lama Mbah Menir keluar dengan muka terkaget-kaget, “Wa’alaikumsalam. Ealah putu lanang. Kamu kenapa kotor seperti itu? Tanganmu juga terluka?” “Tadi Bono berkelahi dengan Aceng dan Munir mbah. Mereka mengejek Bono mbah. Bono tak tahan lagi.” jelasku. “Owalah Bono..Bono..kamu ini rajin sholat, rajin ngaji. Koq yo sampai berkelahi seperti itu?” tanya Mbah Menir iba melihatku. “Nanti ayahmu bisa marah.” tambahnya.
66 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya mbah, Bono khilaf. Bono takut ayah marah.” kataku dengan suara lirih. “Ya sudah, lepas bajumu. Biar simbah mandikan, lalu mbah obati lukamu.” kata Mbah Menir seraya membuka kausku. Mbah Menir memandikanku. Setelah mandi aku tidak boleh pergi dulu oleh Mbah Menir. Aku hanya bermain sendirian di rumah Mbah Menir, meski pintu pagar terbuka aku tidak berani keluar takut durhaka kepada orang yang lebih tua. Aku duduk dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, walau sebenarnya aku berpikir kalau bertemu Aceng lagi, aku ingin sekali memukul perutnya sampai ia terjatuh dan muntah darah. “Sini le, mana sikunya?” kata Mbah Menir dari arah belakang. Mbah Menir mengobatiku dengan obat merah, pedih sekali rasanya. “Sakit le?” tanya Mbah Menir. Aku hanya mengangguk dengan mata terpejam. Disuruhnya aku duduk di beranda rumahnya agar obat merahnya cepat kering oleh angin. Aku
67 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
meniup-niup lukaku menghilangkan rasa pedih yang masih menggelayut di sikuku. Sesaat kemudian aku terpekur menyesali perbuatanku tadi. “Andai saja aku bisa menahan emosiku, pasti tidak begini kejadiannya. Tapi mereka pantas mendapatkannya, paling tidak mereka tahu bahwa aku bukanlah pengecut.” Ku lihat Mbah Menir sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya, jadi aku tak mau mengganggunya. Aku hanya memandang ke sekeliling rumah Mbah Menir, berharap ayah tidak menyusulku ke sini. Namun tiba-tiba dari kejauhan ku dengar suara yang ku kenal memanggilku, “Bono..Bono..” itu suara ayah. Bergegas aku menghampiri Mbah Menir, ketakutan. “Mbah, ayah datang. Bono takut.” kataku bersembunyi di balik punggung Mbah Menir yang sedang berjongkok mencuci piring. “Sudah, kamu di sini saja dulu. Jangan takut, biar simbah yang temui ayahmu.” kata Mbah Menir.
68 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mbah Menir menuju ke teras rumah dan mempersilahkan ayah masuk. “Bono di sini mbah?” tanya ayahku. “Iya, tapi..” belum selesai Mbah Menir bicara ayah hendak menuju dapur, dengan cepat Mbah Menir menahannya. “Ehhh tunggu dulu, duduk dulu!” kata Mbah Menir lembut. Aku tak berani keluar, aku hanya mengintip dari balik tirai yang menggantung di pintu dapur Mbah Menir. “Sudah, istigfar saja dulu. Tenangkan dirimu, baru aku perbolehkan kamu bertemu anakmu.” nasehat Mbah Menir kepada ayah. “Dasar anak nakal mbah, sudah diberi tahu jangan berkelahi. Wani-wanine nglanggar perintahku mbah.” kata ayah marah. “Ehhh namanya juga anak-anak. Lagi pula Bono seperti itu karena temannya yang mendahului. Dia sakit hati karena ejekan temannya. Tapi ra usah kuatir, tadi simbah sudah memberi tahu
69 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bono, mana yang benar, mana yang salah.” kata Mbah Menir bijak. “Sudah, simbah tak perlu ikut campur. Itu sudah kewajiban dan tanggung jawabku sebagai ayahnya.” kata ayah seraya berdiri dan menerobos masuk ke dalam dapur. Ayah mendapatiku tersudut diantara rak dan meja makan. “Heh
bocah
sontoloyo.
Ayo
pulang!”
suara
ayah
menggelegar. Ayah menarik tanganku. “Sabar Wan, dia masih kecil. Dia anakmu. Eling..eling.” Mbah Menir berusaha menahan, namun tubuh rentanya tak kuat menahan ayah yang berbadan kekar. Mbah Menir hanya menangisiku. Ayah semakin kesal karena aku coba menahan tarikan ayah. “Heh wani koe? Meh dadi preman? Iyo? Hah?” kata ayah semakin murka. Ayah yang sudah kehilangan kesabaran mengambil sebatang ranting dari pohon di depan rumah Mbah
70 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Menir dan terus dipukulkannya berkali-kali ke punggungku. Aku hanya bisa menangis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. “Ampun yah..ampun ayah..” kataku kesakitan, namun ayah tak menghiraukannya dan terus memukulku berkali-kali. Tetangga yang melihat kegaduhan itu hanya terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Ayah cukup lama memukul-mukul punggungku dengan ranting. Sakit sekali. Ku rasakan darah mulai menetes dari kulitku yang terkelupas. “Sudah Wan, sudah! Kasihan Bono.” kata Mbah Menir menangis. Ayah pun menghentikan pukulannya, merasa puas telah menghukumku dengan sadis. “Putuku lanang. Kasihan sekali kamu le.” Mbah Menir segera menggendongku masuk ke dalam rumah, sementara ayah hanya terdiam mulai menyadari ia keliru. “Aduhhh, sakit mbah. Punggungku.” aku mengeluh. Mbah Menir membuka bajuku dan terperanjat melihat luka-luka di punggungku. Aku menangis kesakitan. Sambil menyiram lukaku
71 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dengan air, Mbah Menir ikut menangis. Aku menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukaku terkena air. “Mbah sudah mbah. Sakit. Pedih.” Belum sembuh luka di sikuku, muncul lagi luka-luka di punggungku. Rasanya hari itu aku benar-benar sedang celaka. Mbah Menir mengobati luka di punggungku dengan obat merah dan membalutnya dengan kain kasa. “Auw mbah. Sakit sekali. Rasanya seperti ayah masih saja memukuli Bono mbah.” kataku. “Sudah, malam ini kamu tidur di sini saja.” pinta Mbah Menir. Aku melihat ke arah ayah, yang terduduk seakan-akan menyesali perbuatannya. Mbah Menir melihat gerak gerikku yang meminta persetujuan ayah. “Malam ini Bono tidur di rumahku saja.” kata Mbah Menir pada ayah. Ayah melihat Mbah Menir dan mengangguk. Ayah sengaja membiarkanku tidur di rumah Mbah Menir. Mungkin
72 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dalam hatinya muncul perasaan tak tega melihat luka-luka yang aku alami karena perbuatannya. Tak lama ayah berpamitan pulang, ia terlihat lesu hingga kata maaf lupa ia utarakan. Langkahnya sangat berat, aku khawatir pada ayah. “Bono, istirahat saja di kamar simbah ya?” ajak Mbah Menir. Aku hanya mengangguk, menurut. Aku tidur tengkurap dan berharap ayah baik-baik saja. Dalam hati aku berkata, “Ayah maafkan Bono. Bono berjanji tidak akan nakal lagi. Tidak akan melanggar perintah dan nasehat ayah lagi. Bono tidak ingin di cambuk ayah lagi dengan ranting-ranting itu. Maafkan Bono ayah...” Mbah Menir setia menemaniku, mengusap keningku seraya menyanyikan tembang jawa. Aku tak mengerti apa judulnya, tapi terdengar sangat lembut, sejuk di hati. Hanya kalimat ”Lir ilir lir ilir ...” yang ku ingat. Tak terasa, air mata berlinang mengantarku terlelap tidur.
73 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
PAMAN SALIM & SAUDARA BARU
Sudah dua hari ini aku tinggal di rumah Mbah Menir. Bukan karena aku tak ingin pulang melainkan Mbah Menir menahanku. Menurutnya, tunggulah beberapa hari sampai ayah datang menjemput. Mbah Menir sudah menganggapku seperti cucunya sendiri, jadi aku pun tak sungkan dengannya. Terkadang aku mencuri waktu untuk pulang ke rumah sekedar menengok keadaan rumahku dari kejauhan. Terlihat sepi, mungkin ayah sedang melaut. Aku pun bergegas kembali ke rumah Mbah Menir, aku tak mau mengecewakannya. Aku turuti saja apa yang Mbah Menir katakan, pastinya Mbah Menir lebih tahu mana yang baik untukku. Seperti biasa, selesai membantu Mbah Menir mengerjakan pekerjaan rumah aku bermain di halamannya. Terkadang Ipung dan Ara menemaniku bermain di rumah Mbah Menir. Tapi kali
74 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
ini tidak, mungkin mereka sedang sibuk membantu orang tua masing-masing. Ku mainkan beberapa permainan sederhana hanya untuk menghibur diriku sendiri. Mbah Menir turut serta hanya untuk menemaniku bermain. Walaupun Mbah Menir sudah berumur 74 tahun, namun ia masih sangat fasih memainkan beberapa permainan tradisional. Aku lebih sering dikalahkan olehnya dalam memainkan beberapa permainan. Sore itu kami sedang asyik bermain suramanda. Di beberapa kesempatan, aku pernah memainkannya bersama teman-teman. Tetapi selalu ada saja yang mengejekku, terkadang aku ingin sekali menjadi orang lain. Menjadi Aceng yang berasal dari keluarga berada, ayahnya adalah pemilik kapalkapal untuk melaut. Ayahku pun bekerja kepada ayahnya. Hidupnya serba dicukupi oleh ayahnya, bahkan di beberapa acara, ayahnya mampu mengadakan panggung hiburan yang megah.
Tak
dipungkiri
lagi,
hidupnya
terjamin
apalagi
sekolahnya. Sungguh senang menjadi dirinya. Tapi kata ayah
75 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berdosa jika aku tak mensyukuri apa yang telah Allah berikan untukku. Ayah sangat melarangku untuk mengeluh. Ayah pernah berujar, “Jangan pernah mengeluh sedikit pun, karena kalau kamu mengeluh 1 detik saja, Allah juga akan menunda rezekimu 1 detik.” Kini hubunganku dengan ayah sedikit merenggang karena peristiwa yang lalu. Aku ingin sekali bertemu ayah, tapi aku masih takut padanya. Entahlah, esok atau lusa aku harus bertemu ayah, tentu saja jika Mbah Menir sudah mengijinkan. Aku duduk di salah satu batu besar di halaman rumah Mbah Menir, melihat Mbah Menir memainkan gilirannya bermain. Tiba-tiba seorang anak datang mendekati dan memanggil Mbah Menir. “Mbah…” dia menyapa kemudian mencium tangan Mbah Menir.
Mbah
Menir
menghentikan
permainannya
dan
mengamati anak itu. “Siapa ya?” “Ihsan mbah.” katanya.
76 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Owalah Ihsan? Cucu simbah.” kata Mbah Menir kemudian menggendongnya. Tak berapa lama orang tua anak itu datang dan mencium tangan Mbah Menir. “Apa kabar bu?” tanya ayah anak itu. “Baik, Alhamdulillah. Ada apa gerangan kamu pulang kampung, Lim?” tanya Mbah Menir. “Iya bu, rencananya kami sekeluarga akan tinggal disini. Karena saya dipindahtugaskan di kantor cabang Cilacap.” “Oh, yo syukur. Ibu jadi ada teman di rumah.” “Ini siapa, bu?” ayah anak itu melihat ke arahku. “Oh iya ini Bono. Anak Surati teman SD-mu.” “Owalah, sudah gede kamu jang?” kata ayah anak itu kemudian mengusap rambutku. Aku menatap Mbah Menir, meminta penjelasannya. Mbah Menir menatapku dan mengerti maksudku.
77 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, ini anak simbah. Salim namanya. Dulu Salim ini teman ibumu waktu SD. Waktu Salim berangkat ke Jakarta, kamu masih kecil. Jadi mungkin kamu lupa.” jelas Mbah Menir. “Ayo cium tangan dulu!” lanjutnya. Aku mencium tangan Paman Salim dan memperkenalkan diri, “ Saya Bono, paman.” “Ya ya, ini istri paman dan ini anak paman, Ihsan namanya.” kata Paman Salim memperkenalkan istri dan anaknya. Aku mencium tangan istrinya dan menjabat tangan Ihsan, anak Paman Salim. “Kelas berapa kamu jang?” tanya Paman Salim. Aku menggelengkan kepala. Kemudian Mbah Menir coba menjelaskan, “Begini Salim, Bono ini putus sekolah. Terakhir kali ia duduk di kelas V.” “Kenapa putus sekolah, bu?” tanya Paman Salim.
78 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya setelah ibunya meninggal. Ia putus sekolah karena masalah biaya.” jelas Mbah Menir. “Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Jadi Surati sudah meninggal bu?” tanya Paman Salim terguncang. Mbah Menir hanya mengangguk. “Tujuh tahun sudah saya meninggalkan kampung ini. Bekerja dan tinggal di Jakarta. Tak tahu kabar di sini.” kata Paman Salim. “Kasihan anak ini. Tak ada yang mengurusnya.” kata Mbah Menir memelukku. “Kemana Kang Ridwan, ayahnya?” tanya Paman Salim. “Ridwan seperti biasa, melaut. Ia bertemu ayahnya seminggu mungkin hanya tiga kali karena ayahnya sibuk di laut. Kalaupun di rumah, ayahnya sibuk membetulkan jaring.” jelas Mbah Menir. “Kasihan kamu jang. Paman ada sesuatu, ini terima.” Paman Salim menyodorkan selembar lima puluh ribu rupiah.
79 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Untuk apa paman?” “Untukmu Bono, anggap saja hadiah dari paman.” Paman Salim tersenyum. Aku bingung, aku tak ingin menolak namun ayah pernah berpesan jangan menerima hadiah apapun dari orang lain. Aku pun menggelengkan kepala. “Kenapa?” “Ayah melarang Bono menerima hadiah dari orang lain paman.” kataku tak enak hati. “Paman bukan orang lain, paman ini anak Mbah Menir, kalau kamu menganggap Mbah Menir sebagai nenekmu, tak ada salahnya kan kalau kamu menganggap Paman Salim sebagai pamanmu?” kata Paman Salim ramah. “Lagipula, paman kan teman karib ibumu Bono. Sudahlah terima saja.” tambahnya. “Tidak paman. Terima kasih.” Aku bertahan pada keputusanku. Paman Salim menatap dalam mataku kemudian ia
80 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berkata, “Apa yang harus paman lakukan agar kamu mau menerima uang ini?” Aku berpikir sejenak. “Bagaimana kalau Bono bekerja untuk paman? Pekerjaan apapun asal halal akan Bono lakukan paman.” Paman Salim tersenyum. “Ya ya, baiklah. Boleh paman lihat nilai-nilai saat kamu sekolah dulu?” “Untuk apa paman?” kataku heran. “Katanya
kamu
mau
bekerja,
paman
tidak
bisa
mempekerjakanmu kalau nilai-nilaimu di sekolah tidak baik.” jelas Paman Salim. “Ada di rumah, paman. Tapi Bono belum berani ke rumah.” “Lho, kenapa?” Aku melihat Mbah Menir, berharap ia mau membantuku menjelaskannya pada Paman Salim.
81 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ohh begini Lim, beberapa hari yang lalu Bono dihukum oleh ayahnya. Karenanya, ia masih takut untuk bertemu ayahnya.” jelas Mbah Menir. “Begitu? Mau paman antar?” Sekali lagi aku melihat Mbah Menir. Ia mengangguk, pertanda ia mengijinkanku pulang ke rumah. “Ayo jang!” ajak Paman Salim. Aku dan Paman Salim pergi menuju rumahku. Sementara Mbah Menir menemani istri dan anak Paman Salim di rumahnya. Sesampainya di rumah. Aku mengetuk pintu rumahku namun tak ada yang membukanya. Coba ku raih kait rantai yang menahan pintu dan ku buka. Ternyata tak ada seorang pun. Dengan hati bingung, aku mempersilahkan Paman Salim duduk. “Silahkan duduk paman.” “Oh ya, Terima kasih.” “Sebentar Bono cari rapor Bono dulu, paman.” “Ya silahkan, cari saja dulu tak perlu terburu-buru.”
82 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Ku acak-acak tumpukan buku di salah satu rak mejaku. Beberapa menit kemudian aku menemukan buku raporku. Ku serahkan buku rapor itu kepada Paman Salim. “Ini paman rapor Bono, sudah rusak tapi masih terlihat jelas tulisannya.” kataku malu menunjukan rapor itu. Paman Salim terlihat mengamatinya dengan seksama kemudian ia tersenyum. “Nilai rapormu bagus Bono?” “Terima kasih paman, tapi Bono paling suka pelajaran matematika.” “Kenapa kamu tidak melanjutkan Kejar Paket A saja?” “Kejar Paket A itu apa paman?” aku bingung baru mendengar. “Kamu belum tahu? Kejar Paket A itu ya sama dengan sekolah SD, hanya saja Kejar Paket A dikhususkan untuk orang yang putus sekolah seperti kamu, Bono.” “Tapi apa ayah Bono sanggup membiayainya, paman?”
83 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Begini saja, kamu tidak perlu khawatir. Kamu paman bantu ikut Kejar Paket A, tapi kamu harus bantu Ihsan selama ia bersekolah disini. Kebetulan sekarang ia naik kelas V. Kamu masih ingat pelajaranmu waktu kelas V?” “Masih, paman. Walau sudah tidak bersekolah, Bono masih sering baca buku-buku sekolah Bono.” “Nah, kalau begitu bantu dia belajar dan temani bermain, bagaimana?” “Paman, Bono tanya ayah dulu ya?” “Iya Bono tak perlu buru-buru. Nah, sekarang simpan saja buku rapormu. Lagipula kamu belum cukup dewasa untuk bekerja seperti paman.” “Baik paman!” kataku kemudian menyimpan buku raporku kembali. Tiba-tiba dari arah pintu ayah muncul. Ku lihat tubuhnya lunglai, mukanya pun pucat. “Bono, ini siapa?” kata ayah.
84 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ini Paman Salim yah, anak Mbah Menir, katanya teman ibu juga dulu.” kataku menjelaskan. Paman Salim menoleh ke arah ayah kemudian tersenyum. “Oh, Salim? Piye kabare?” kata ayah seraya tertawa lebar dan memeluk Paman Salim. “Ya ya, aku baik- baik saja. Bagaimana denganmu, kang?” tanya Paman Salim. “Ya, cukup sehat. Hanya saja pandanganku mulai kabur jadi dari pintu tadi aku kurang jelas melihatmu.” kata ayah menepuk bahu Paman Salim. “Silahkan duduk!” lanjut ayah. “Dapat apa hari ini, kang?” tanya Paman Salim. Kakang (kakak) adalah sebutan akrab Paman Salim kepada ayah. Mereka berdua terlihat sangat akrab, seperti dua sahabat yang lama tak jumpa. “Yahh, cuma dapat ikan layur. Itu pun tak sebanyak biasanya Lim. Kamu bagaimana di Kalimantan? Wah wis dadi wong penak saiki yo? Hahaha.” kata ayah.
85 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hahaha. Kang Ridwan bisa saja. Ya, Alhamdulillah, kang. Rejeki saya di luar kota, tapi sebentar lagi rejeki saya tak jauh dari sini.” kata Paman Salim. “Maksudmu?” tanya ayah heran. “Iya, tak lama lagi saya dipindahtugaskan di Cilacap, kang. Jadi lebih bisa dekat dengan ibu. Sebenarnya di kota sudah disediakan rumah. Tapi tidak saya ambil. Saya lebih memilih tinggal di sini, kasihan ibu sudah tua, kang.” jelas Paman Salim. “Malah bagus to? Kuwi jenenge anak eling wong tuo, ora elok ngorbanke wong tuo mung nggo urusan dunyo. Toh nanti kita juga bakal tua Lim, kalau bukan anak, siapa yang mau peduli tur ngopeni kita.” kata ayah menasehati seraya menyalakan rokok 234 kesukaannya. “Bukannya sekarang kita sudah tua, kang?” canda Paman Salim seraya menepuk siku kanan ayah. “Wah, iya ya? Gara-gara ketemu kamu, aku jadi merasa masih muda, Lim.” balas ayah.
86 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hahaha. Kang Ridwan bisa saja.” Paman Salim sungkan. Sekitar 45 menit mereka asyik berbincang-bincang. Sementara itu, aku hanya duduk di dekat meja makan memperhatikan mereka. “Oh ya, begini kang. Saya mau minta ijin, berhubung Ihsan mau sekolah disini, kebetulan juga naik kelas V. Saya meminta Bono untuk mengajari dan menemani Ihsan selama disini. Nantinya, Bono saya bantu sekolah kejar Paket A. Bagaimana kang?” kata Paman Salim meminta izin. “Sssttt. Ora usah repot-repot. Kalau mengajari dan menemani
anakmu
boleh-boleh
saja
Lim.
Tapi
harus
membebanimu untuk menyekolahkannya, ndak usah.” kata ayah seraya menggoyangkan telapak tangannya. “Tapi kang, Bono anak yang pintar. Dia ingin melanjutkan sekolahnya. Saya pun tak keberatan kang.” kata Paman Salim berusaha meyakinkan ayah.
87 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Begini ya lim. Kamu itu kan harus menyekolahkan anakmu juga, belum lagi harus mencukupi kebutuhan rumah tangga. Iya sekarang kamu masih sanggup, lha nanti kalau kamu mulai kesulitan. Apa ndak yang repot aku juga? Bono juga kasihan harus putus sekolah lagi. Wis ben, anakku dadi nelayan wis apik koq.” jelas ayah menolak permintaan Paman Salim. “Iya memang benar kita tidak tahu bagaimana nanti. Tapi rezeki Allah yang mengatur kang. Insya Allah saya sanggup menyekolahkan Bono sampai lulus tingkat SD, bahkan kuliah bersama Ihsan.” Paman Salim sedikit memaksa. “Ya sudah, terserah kamu saja lim. Tapi aku cuma minta, jangan pernah menyesal sudah menyekolahkan Bono.” kata ayah. Tiba-tiba ayah batuk hebat. Tangan kirinya memegang kencang lehernya menahan batuk di tenggorokannya. Ayah terlihat membungkuk-bungkuk karena batuk itu.
88 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono, ambilkan air minum untuk ayahmu!” Paman Salim segera menyuruhku mengambilkan air minum. Aku berlari menuju dapur dan ku ambilkan air minum untuk ayah. “Ya, sudah-sudah. Aku sudah tidak apa-apa.” kata ayah. “Bono, bilang terima kasih pada Paman Salim.” perintah ayah. Aku segera menjabat tangan Paman Salim dan menciumnya. “Terima kasih paman.” kataku. “Iya Bono. Jangan kecewakan paman ya? Buat paman bangga dengan prestasimu nanti.” kata Paman Salim. Aku hanya mengangguk. “Wah anakku sekolah meneh. Sing rajin yo le. Ayah cuma bisa kasih doa semoga kamu jadi anak yang sukses. Ndak seperti ayahmu.” kata ayah setengah tersenyum, ku lihat matanya berkaca-kaca. “Iya yah.” ku peluk tubuh ayah, ia membalasnya erat sekali. Paman Salim mengusap-usap punggungku. Seketika Paman Salim sudah seperti orang tuaku saja.
89 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Akhirnya keinginanku melanjutkan sekolah terkabul. Tak henti-hentinya ku ucapkan hamdallah sebagai tanda syukurku pada Allah yang telah mendatangkan Paman Salim untuk membantuku. Disisi lain, kini aku punya saudara baru. Ya, dialah Ihsan anak Paman Salim. Saudara dari kota dan yang pasti dia tidak jahat padaku seperti teman-teman kebanyakan. Aku sudah tak sabar ingin mengenalkan Ihsan kepada dua teman baikku, Ipung dan Ara. Kini aku memiliki saudara baru, Ihsan saudara dari ibu kota.
90 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
TEMAN
Pagi ini aku sangat senang. Karena hari ini aku mulai melanjutkan sekolahku. Walau hanya masuk kejar paket A di sebuah sanggar belajar, namun aku sudah sangat bersyukur. Paling tidak cita-citaku menjadi guru kembali terbuka. Aku berangkat bersama Paman Salim dan Ihsan. Kami berboncengan mengendarai motor Paman Salim. Seperti halnya aku, hari ini adalah hari baru untuk Ihsan. Ini hari pertamanya masuk sekolah baru setelah pindah ke kampung ini. Kebetulan jarak sekolahnya dan sanggar belajarku hanya berjarak 200 meter, karena itu kami berangkat bersama. Walau bukan sekolah formal, tapi sanggar belajar ini benarbenar hebat. Paman Salim tidak salah memilihkanku tempat ini, ia juga membelikanku tas, sepatu, baju sampai buku-buku baru untukku. Aku menyukai semua yang Paman Salim belikan.
91 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Begitu juga teman-teman baruku, aku suka bergaul dengan mereka, mereka sangat baik padaku. Tak terasa aku sudah begitu akrab dengan beberapa teman baru. Bel tanda pulang dibunyikan, aku pulang bersama 2 orang teman baruku Widi dan Dani. Sebelumnya, aku dan Ihsan dijanjikan akan dijemput oleh Bibi Salim, istri Paman Salim. Ku lihat Bibi sudah menunggu di depan sekolah Ihsan. Aku sengaja meminta ijin padanya untuk pulang bersama teman baruku karena ia harus menunggu Ihsan pulang, baru kami bisa pulang bersama. Ku pikir daripada menunggu, lebih baik aku pulang lebih dahulu sekaligus agar lebih dekat dengan teman baruku, Widi dan Dani. Ya, sekolah formal dan sanggar belajar memang memiliki waktu belajar yang berbeda. Aku pulang lebih dulu daripada Ihsan. Ketika pulang sekolah aku, Widi dan Dani melewati sebuah kebun milik sanggar. Saat itu kami melihat buah mangga yang ranum menguning bergelantungan.
92 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Hai, lihat mangganya banyak yang sudah matang!” kata Widi sambil menunjuk ke salah satu pohon mangga. “Kita ambil saja yuk!“ ajak Dani. “Enggak ah, aku takut! “ sahutku. ”Nanti kalau ketahuan orang bagaimana?” “Ah, dasar kamu. Nyalinya kecil.“ sahut si Widi. Mendengar ucapan Widi, akhirnya aku terhasut. Aku menyetujui ajakan mereka, tentunya jantungku berdegub kencang. Dengan hati-hati, kami memanjat pagar bambu yang mengelilingi kebun. “Hati-hati, ada pakunya.” bisik Widi. “Tolong pegang tas-ku, Dan.” perintahku pada Dani. Kemudian aku memanjat dinding bambu itu. “Sini, lempar tas-ku.” perintahku lagi pada Dani. Dani melempar tas milik kami bertiga ke dalam kebun kemudian ia masuk ke dalam kebun diikuti Widi.
93 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Kemudian kami memanjat pohon mangga itu bersamaan. “Hai hati-hati memanjatnya!” Widi memperingatkan kami. Ketika sampai di atas, kami menemukan pemandangan yang menakjubkan. Betapa tidak? Di dalam kebun, kami tidak hanya menemukan mangga yang membuat air liur mengalir, tetapi kami juga melihat kolam ikan yang cukup luas. Ketika kami asyik mengamati, tiba-tiba muncul seseorang yang meneriaki kami untuk turun. “Hai, turun!” Dengan segera kami turun dari pohon itu dan mengambil langkah seribu. “Lari......” teriak Widi mengomandoi kami. Dalam perjalanan pulang kami membahas kejadian tadi. “Untung saja tadi tidak ditangkap oleh orang itu, kalo tertangkap bisa habis kita. Belum lagi kalau ayahku tahu.” kataku terengah-engah ketakutan. “Baru segitu saja sudah takut, itu belum apa-apa. Besok kita ambil mangganya.” kata Widi.
94 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya aku setuju, bagaimana denganmu Bon?” kata Dani seraya menyikut lenganku. “Ah
kalau
sampai
tertangkap
bagaimana?”
kataku
khawatir. “Bukan apa-apa, ayahku galak.” tambahku. “Kali ini tidak akan ketahuan, kita cepat-cepat ambil mangganya sebelum ada orang yang melihat kita.” kata Widi. “Tapi..” belum selesai aku bicara, Dani memotong. “Alah bilang saja kamu tak punya nyali Bon.” Untuk kedua kalinya aku terhasut, tak mau diremehkan. Karena belum sempat mengambil sebiji pun buah mangga, kami sepakat untuk menyelinap masuk ke dalam kebun esok harinya. Esok harinya, seperti biasa kami belajar dalam kelas. Setelah menghabiskan waktu 6 jam. Guru kami sedang bersiapsiap untuk mengakhiri pelajaran hari itu. ”Anak-anak, tugas latihan yang hari Senin kemarin sudah bapak periksa. Ada yang bagus ada yang kurang bagus nilainya. Bagi anak-anak yang kurang bagus, bapak memberi kesempatan
95 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
untuk memperbaiki nilai. Kalian kerjakan soal di halaman 14 buku cetak matematika. Mengerti?” “Mengerti pak!” kami menjawab serentak. “Baik. Ini bapak bagikan hasil tugas latihan kemarin.” kata pak guru kemudian memanggil nama siswanya satu per satu. “Semua sudah mendapat hasilnya ya?” kata pak guru. “Sudah pak!” sekali lagi kami kompak menjawab. “Ya sudah, kalau begitu ketua kelas memimpin doa pulang!” perintah pak guru. Setelah berdoa kami semua pulang dan tak lupa mencium tangan pak guru sebelum meninggalkan kelas. Sesuai kesepakatan kemarin, aku, Widi dan Dani kembali memasuki kebun mangga milik sanggar. “Hei Bono, tugasmu berjaga saja disini. Beri tahu kami jika ada orang yang datang. Sementara aku yang memanjat dan memetik buah mangga lalu Dani yang menangkapnya dari bawah. Bagaimana?” kata Widi menjelaskan rencananya.
96 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Kita pilih dulu saja pohon yang akan kita panjat.” usul Dani. “Kamu disini saja, aku dan Widi mau mencari-cari pohon yang akan kita panjat.” tambahnya. Aku hanya mengangguk. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisku, terus terang aku takut. Tapi aku tak mau diremehkan oleh mereka. Saat sedang berjaga tak jauh dari pagar bambu, Widi mengagetkanku dengan suaranya. “Bono, kemari!” kata Widi setengah berteriak. “Ada apa?” kataku mendekat. “Lihat ada sarang burung di atas sana.” kata Widi seraya menunjuk segumpal sarang burung di ujung salah satu pohon. “Kamu berani ambil sarang burung itu, Wid?” tanyaku. “Aku berani tidak sepertimu yang penakut.” katanya. “Ahh siapa takut, aku berani memanjat pohon ini hingga ke ujung.” kataku tak terima disepelekan. “Baik. Bagaimana kalau kita taruhan, siapa yang lebih dulu mendapatkan sarang burung itu, dia yang menang. Dan yang
97 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
kalah, harus memberikan semua uang sakunya hari ini pada yang menang.” kata Widi menantangku. “Siapa takut, tapi biar adil, kita titipkan uang saku kita pada Dani dahulu. Bagaimana?” saranku. “Baik. Dan, ini pegang uang saku kami. Awas kalau sampai hilang 100 rupiah saja, uang sakumu yang akan kami ambil.” kata Widi mengancam. “I..iya Wid, aku jaga.” kata Dani seraya memasukkan uang saku kami ke dalam saku bajunya. Kami bersiap. Aku melepas sepatuku dan menekuk celana panjangku ke atas. Dani memberi aba-aba. “Siap? Tiga Dua Satu Mulai!” Seketika aku dan Widi melompat menaiki pohon itu. Widi terlihat cepat sekali meraih dahan dan melangkahkan kakinya naik ke atas pohon. Aku tak mau kalah, ku percepat gerakanku layaknya Tarzan. Kami berdua sangat cepat mendekat pada sarang burung itu. Aku hampir berhasil meraih sarang burung itu
98 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
tapi tangan Widi lebih cepat. Spontan ku tarik lengannya dan meraih sarang burung itu. Tiba-tiba “Ahhh” Widi berteriak dan jatuh ke tanah. Tubuhnya keras menghantam tanah, aku panik. Aku bersegera turun dan mendekati Widi yang sudah menggelinjang kesakitan. “Wid, maaf aku tak sengaja.” kataku cemas. Widi tak menjawab hanya mengerang kesakitan. Ku peluk tubuhnya dan menangis, ku ucapkan maaf berkali-kali. Aku menyesal. “Toloonggg..toloongg..”
Dani
berteriak
meminta
pertolongan pada orang yang berlalu lalang di dekat kebun. Tak lama pembina sanggar datang. Ia dan beberapa orang menggendong Widi dan membawanya ke Puskesmas terdekat. Aku terdiam penuh penyesalan. “Bono, kenapa kamu buat Widi jatuh?” kata Dani menghakimi. Kerumunan manusia tanpa komando juga mulai bising membicarakanku.
99 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Aku tak sengaja, sungguh. Aku tak tahu kalau tindakanku membuatnya jatuh.” kataku sedih. Dani yang harusnya menenangkanku justru memasang wajah ketus dan pergi meninggalkanku. Aku berlari mendahului Dani, menuju orang-orang yang menggendong tubuh Widi. Sesampainya di Puskesmas, Widi mendapat perawatan intensif. Beberapa jam menunggu, dokter yang menangani Widi keluar dan menjelaskan bahwasanya Widi baik-baik saja. Hanya tangannya retak, perlu istirahat. “Sudah kalian pulang saja! Orang tua Widi sudah datang.” perintah pembina sanggar. “Baik, bu.” Widi pergi meninggalkanku. Sementara itu, Paman Salim menemui ayahku di rumah. “Kang, kang sudah dengar belum kejadian tadi di sanggar?” kata Paman Salim panik. “Ono opo to?” kata ayah kebingungan.
100 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Anakmu tadi bermain di kebun mangga milik sanggar. Dan yang aku dengar, dia membuat temannya jatuh dari pohon mangga. Sekarang temannya ada di Puskesmas kampung.” kata Paman Salim panik. “Aku bilang apa Lim? Anak itu tidak perlu sekolah lagi, cuma bikin repot kamu to?” kata ayah dengan wajah menahan marah. “Bukan kang. Bukan itu yang aku khawatirkan, namanya musibah, siapa yang tahu? Maksudku, apa benar kabar tersebut? Mungkin Kang Ridwan lebih tahu.” jelas Paman Salim. “Ah mbuh. Ra sah dipikir Lim.” kata ayah ketus. Paman Salim mendekat, merangkul pundak ayah. Ia tahu bahwa sebenarnya ayahku sangat mengkhawatirkanku, hanya saja ia tak mau terlihat lemah dengan memanjakanku. Saat mereka sedang berbincang-bincang di rumah, aku sedang dalam perjalanan pulang. Dengan langkah gontai aku pulang menuju rumah. Bajuku kusut, basah dimana-mana karena
101 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
peluh yang menetes deras dari sekujur tubuh. Sesekali aku menengok ke kiri dan ke kanan, tetapi kepalaku lebih sering menunduk, menghitung jumlah kerikil di jalan yang sedang ku lewati. Rasa bersalah terus menghantuiku. Belum lagi kalau ayah atau Paman Salim tahu, aku panik. Benar saja, belum sampai rumah ku lihat dua sosok bertubuh tegap berdiri di depan rumah, mereka adalah ayah dan Paman Salim. Tak sadar tanganku meremas-remas ujung baju hingga tak berbentuk lagi, aku takut. “Bono, sini jang!” Paman Salim memanggilku seraya mengayunkan tangannya. Ayah hanya diam terpaku. Aku mendekat. “Ada apa Paman?” tanyaku gemetar. “Ganti bajumu dulu, setelah itu makan. Paman sudah belikan ayam goreng untukmu.” kata Paman Salim ramah menyambutku. Ku lihat ayah masih saja berdiri, kali ini ia menyalakan rokok di mulutnya.
102 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Sikap Paman Salim melunturkan dugaanku. Ku ganti bajuku yang sudah lengket berkeringat, kemudian makan dengan lahapnya.
Paman
Salim
memperhatikanku
kemudian
ia
tersenyum. Sementara ayah masih diluar menghabiskan rokoknya. “Sudah makannya?” tanya Paman Salim. “Sudah Paman.” kataku puas kekenyangan. “Cuci piringmu, lalu temui paman di sini ya? Ada yang ingin paman berikan padamu.” kata Paman Salim dengan gaya ramahnya yang khas. Setelah mencuci piring, aku menemui Paman Salim. “Ada apa paman?” “Ini tolong berikan pada temanmu yang jatuh dari pohon tadi. Paman sudah dengar ceritanya dari Ihsan.” katanya. Paman Salim menyodorkan amplop berisi uang yang tak ku tahu berapa jumlahnya. Lagi-lagi Paman Salim membuatku terharu.
103 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Terima kasih paman, maaf Bono selalu merepotkan.” kataku sungkan. “Mbok yo sadar to le! Kamu itu sudah disekolahkan sama pamanmu. Jangan buat yang macem-macem. Sekarang sudah begini, pamanmu lagi yang repot. Kamu tahu to bapakmu cuma nelayan miskin? Ndak usah banyak tingkah!” ayah memotong ucapanku. “Sudah kang, tidak apa-apa. Bono kan sudah saya anggap seperti anak sendiri.” kata Paman Salim menenangkan suasana. “Yo wis. Terserah kamu lah Lim. Tapi aku sebagai ayahnya jadi ikut sungkan sudah banyak merepotkan kamu Lim.” kata ayah seraya membuang puntung rokoknya. “Sudah-sudah kang. Jangan berlebihan.” kata Paman Salim tersenyum. “Bono, sekarang kamu antarkan uang ini kepada temanmu itu, kalau malu ajak Ihsan atau temanmu yang lain.” Aku hanya mengangguk, kemudian berpamitan mencium tangan Paman Salim dan ayah. Aku pergi bersama Ihsan, Ipung
104 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dan Ara. Sesampainya di Puskesmas, ku lihat Dani sudah ada disana. Wajahnya masih ketus melihatku, ku beranikan diri masuk dan menjenguk Widi yang sudah membaik. “Wid, bagaimana keadaanmu?” kataku lirih. “Ah cuma retak saja koq, seminggu juga sudah bisa main bareng lagi Bon.” katanya tersenyum. “Maafkan aku ya Wid, aku benar-benar tak sengaja dan menduga hal ini akan terjadi.” kataku menyesal. “Ahh sudah, tidak apa-apa. Aku bisa mengerti Bon. Namanya juga musibah, iya kan?” katanya lembut. “Emm..ini aku mau memberikan ini, untuk membantu biaya pengobatanmu Wid.” kataku menyerahkan amplop itu. “Apa-apaan Bon? Enggak usah. Kamu mau jenguk saja aku sudah senang.” kata Widi menolaknya. “Eh tapi ini amanah dari pamanku. Tolong diterima saja biar jadi berkah.” kataku memohon.
105 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya sudah, aku terima. Terima kasih ya, salam buat pamanmu.” kata Widi bersedia menerima amplop itu. Aku mengangguk. “Oh iya, ini anak Paman Salim. Ihsan namanya, kemudian ini Ipung dan Ara teman baikku di kampung.” kataku memperkenalkan Ihsan, Ipung dan Ara pada Widi. Mereka berjabat tangan. Dani masih terlihat ketus. Belum bisa menerima apa yang terjadi pada teman baiknya, Widi. Widi melirik ke arah Dani. “Hei Dan, mukamu masih ditekuk saja? Apa bedanya mukamu dengan terpal kaki lima kalau masih saja seperti itu? Sudahlah, maafkan saja Bono!” canda Widi. Kami menahan senyum, termasuk Widi. Kemudian ku ulurkan tanganku lebih dulu. “Dan, kamu mau memaafkanku kan?”
106 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Dani mengangguk, kemudian memelukku. “Maafin aku juga Bon, aku sudah sempat memusuhimu. Kamu orang yang baik. Maaf.” “Iya, sekarang kita berenam adalah teman. Harus saling menjaga satu sama lain. Terutama menjaga Ara karena ia satusatunya perempuan. Bagaimana?” kataku bersemangat. Mereka
saling
memandang.
“Aku
setuju.”
Widi
mendahului. Diikuti Dani, Ihsan, Ipung dan juga Ara. Tawa canda hari ini menambah kesempurnaan kebersamaan kami. Karena kejadian itu pula, aku merasa memiliki teman yang sangat berarti bagiku. Dulu aku hanya berteman dengan Ipung dan Ara, kini temanku bertambah. Dani, Widi dan tentu saja Ihsan, kini ku sebut mereka berlima sebagai teman.
107 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
MASALAH BARU
Hari ini Widi sudah diijinkan untuk pulang ke rumah, hanya saja ia masih harus beristirahat. Kami menemaninya pulang dari Puskesmas. Kami hanya berjalan kaki menuju rumah Widi, orang tua Widi mengikuti kami dari belakang. Widi terlihat sangat senang walau tangannya harus dibalut perban dan kayu penopang. “Wid, lihat deh tanganmu udah kaya tangan Robocop saja, hahaha.” celoteh Dani. “Gundulmu! Sekali lagi bilang begitu, ku adu mulutmu dengan tanganku ini.” balas Widi. Mendengar Widi menggertak, Dani mulai salah tingkah. Kami menertawainya. “Hahaha. Aku gertak begitu saja sudah pucat mukamu Dan.” kata Widi menggoda.
108 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ah kamu Wid, tadi kan aku cuma bercanda.” kata Dani membela diri. “Tenang saja Dan. Aku tidak akan tega kepada temantemanku sendiri. Apalagi kamu, tanpa ku hajar saja wajahmu sudah babak belur permanen, hahaha.” kata Widi meledek. “Oh jadi skor kita sudah 2-1 nih?” kata Dani seraya merangkul Widi. “Auw..sakit! Tanganku.” teriak Widi. “Aduhhh kacian yang tangannya dibungkus seperti nangka yang mau matang, atit ya?” kata Dani kemudian mengelus dan meniup tangan Widi. “Ah minggir. Bisa-bisa tanganku tetanus.” kata Widi. “Ah kamu pikir nafasku ini mengandung bakteri Wid?” kata Dani cemberut. “Hei sudah, sudah. Kalian ini, dari tadi bertengkar terus.” kata Ara memotong. Mereka saling memandang kemudian membuang muka.
109 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Eh Wid. Rumahmu masih jauh?” tanyaku. “Ya sekitar satu setengah kilo lagi. Kenapa? Kakimu mau patah?” canda Widi. “Ah kamu Wid. Tangan belum juga sembuh masih saja bercanda seperti itu. Kualat lho?” kataku. “Iya nih, Widi memang seperti itu. Mentang-mentang badannya paling besar diantara kita berenam.” imbuh Dani. “Lho? Bukannya bagus? Jadi kalau ada yang mengganggu kalian biar aku saja yang menghadiahi mereka dengan tinjuku. Tapi tunggu tanganku sembuh dulu ya?” kata Widi. “Huuuu...” kami berlima bersorak. Kami larut dalam canda dan tawa. Tak terasa kami sampai di rumah Widi. Rumahnya cukup besar, aku yang baru pertama kali kerumahnya terdiam sesaat memuji keindahan rumahnya. “Ayo anak-anak, masuk saja.” teriak ayah Widi dari arah belakang. “Ayo, masuk!” ajak Widi.
110 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Wid, rumahmu besar.” kataku terkagum-kagum. “Ini bukan rumahku, tapi rumah orang tuaku. Besok kalau aku sudah besar, rumahku akan jauh lebih besar dari ini.” kata Widi bangga. “Kamu mau tinggal di goa, Wid? Rumah sebesar ini saja sudah luar biasa, eh ini mau lebih besar lagi!” kata Dani. Kami semua tertawa. Mereka berdua memang seperti itu, suka saling ejek tapi hanya untuk candaan saja. Tak lama beberapa gelas es teh tersaji di depan kami, sepiring kue bolu tak lupa menemani dinginnya es teh itu. “Ayo, dimakan kuenya. Tak usah malu-malu.” kata ibu Widi. “Terima kasih, bu.” Kami kompak dan serentak berebut mengambil kue bolu lebih dulu. “Kalian sudah berapa lama tak makan?” kata Widi dengan mimik heran.
111 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Wajar Wid, kue ibumu kan enak. Baunya saja sudah bikin air liur kami mengalir, apalagi rasanya emmmm.” kata Ihsan. “Kamu mau Wid? Ini aku suapi.” kata Ipung tiba-tiba menyodorkan sepotong kue ke mulut Widi. “Ahh apa-apa’an sih Pung? Aku makan sendiri.” kata Widi cemberut. “Cieeee..ternyata Ipung memendam rasa pada Widi.” kata Dani menggoda. Kami tertawa. “Hei..Ipung itu laki-laki dan aku masih normal tahu!” kata Widi seraya melempar potongan kue bolu ke arah Dani. “Wid, orang tuamu kan tergolong kaya. Terus kenapa kamu malah ikut Paket A, bukan sekolah biasa seperti Ihsan?” tanyaku penasaran. “Ohh..jadi dulu aku pernah bersekolah di SD tak jauh dari sini. Tapi karena aku sering berkelahi dengan teman sekelasku, akhirnya aku dikeluarkan. Kalau masuk sekolah normal, aku malu Bon. Mau bagaimana lagi? Orang tuaku memutuskan untuk
112 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
menyekolahkanku ke Paket A di sini. Tapi tak masalah, karena sekarang aku punya geng baru. Hahaha.” Kata Widi. “Geng? Boleh juga. Mau kita kasih nama apa geng kita Wid?” kata Ipung. “Bagaimana kalau Geng Antik?” kata Ara. “Apa artinya, Ra?” tanya Ihsan. “Geng Anak Cantik.” kata Ara sumringah. “Kamu pikir kita semua cantik, Ra?” kata Dani. “Oh iya, kan cuma aku yang cantik.” kata Ara tersenyum manja. “Wuuuu..” kami bersorak. “Bagaimana kalau Anker? Artinya Anak Keren. Kesannya juga seram.” kata Widi. “Wah, bagus tuh. Aku setuju!” kata Dani. “Aku juga!” kataku. Kemudian yang lain ikut menyetujui nama geng kami.
113 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Mulai sekarang kalau salah satu dari kita ada yang kesusahan harus kita bantu, kalau ada yang sedih kita hibur dan kalau ada yang senang harus berbagi dengan anggota geng lainnya. Bagaimana?” kata Widi. “Satu lagi Wid, bagaimana kalau kamu ketua geng-nya? Kan badanmu paling besar.” kataku. “Oke. Aku setuju.” kata Widi. Tak terasa kami terlibat perbincangan hebat tentang geng dan sesekali kami tertawa karena candaan Dani dan Widi. Hari mulai senja, kami berpamitan pulang. Ditengah jalan kami berpisah. Ara dan Dani berjalan ke arah utara sementara aku, Ipung dan Ihsan ke arah timur. “Bon, mulai hari ini enggak akan ada yang berani ganggu kita. Kita sudah punya Geng.” kata Ipung. “Iya, tapi bukan berarti kita mau cari musuh lho! Kita bikin geng kaya gini kan biar lebih akrab saja, bisa saling bantu dan lainnya.” kataku.
114 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono benar Pung.” Ihsan menimpali. Ipung hanya mengangguk-angguk. “Tunggu sebentar!” kataku menghentikan langkah melihat sesuatu yang sepertinya ku kenal. “Ada apa, Bon?” kata Ipung heran. Tanpa aba-aba aku lari ke arah rerumputan tak jauh dari jalan yang kami lalui. Ipung dan Ihsan mengikuti, mereka heran dengan tingkahku. “Kamu mencari apa, Bon?” kata Ihsan. “Itu, kamu lihat?” kataku menunjuk sesuatu. “Itu Doreng kan, Bon?” kata Ipung. “Doreng?” Ihsan bingung. “Doreng itu kucing kesayangan Bono yang hilang beberapa waktu yang lalu, San.” Ipung menjelaskan. Kemudian kami bertiga mendekati seekor kucing yang mirip sekali dengan Doreng. Ku lihat dengan jelas bekas luka
115 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
dikepalanya sama persis seperti bekas luka di kepala Doreng. Tiba-tiba kucing itu lari menuju arah sungai kecil. “Pung, kamu cegat dari arah kanan! Kamu dari arah kiri, San!” perintahku pada Ipung dan Ihsan. Kami mengepung kucing itu dari 3 arah berbeda, ia terdesak. “Sini kucing manis, tak usah takut. Aku yakin kamu Doreng, sini sini..pus pus pus pus.” kataku agar ia tak takut. Semakin dekat ku lihat, semakin yakin kalau kucing itu adalah Doreng. Aku bersiap menangkapnya, ku ayunkan tangan dengan cepat dan “Auww” kucing itu mencakar lengan kananku kemudian lari. “Kamu baik-baik saja, Bon?” tanya Ipung. “Sakit tahu, cepat kejar saja kucing itu!” kataku kemudian lari mengejar kucing itu. Ia lari menuju rumah Mak Nasib. Ku lihat Mak Nasib sedang menjemur ikan asin seperti yang biasa ia lakukan. Secepat kilat kucing itu menyambar sebuah ikan asin yang sedang dijemur.
116 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Bono...kucingmu sudah bosan hidup ya!!!” teriak Mak Nasib marah. Kini aku yakin 100% kalau itu adalah Doreng. “Maaf mak..” kataku sambil terus lari mengejar Doreng. Aku dan Ipung tetap lari mengejar Doreng, sementara Ihsan sudah tertinggal karena mulai kelelahan. Sampailah kami disuatu semak, ku lihat Doreng masuk ke dalamnya. “Bon, itu dia masuk ke semak kering disitu.” Kata Ipung. “Ssstt diam, nanti dia lari lagi. Kamu siap disisi sebelah sana, siapa tahu dia lari.” kataku. Ipung mengangguk dan segera menuju ke sisi lainnya. Ku buka semak itu perlahan, ku dengar suara yang sepertinya tak asing. Ku lihat 5 ekor anak kucing ada di dalamnya, Doreng berdiri dan seakan-akan terganggu dengan kehadiranku. “Pung, sini pung!” kataku. “Ada apa?” kata Ipung mendekat.
117 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Itu, Doreng punya 5 ekor anak.” kataku antara senang dan sedih. “Wahh, biar aku ambil, Bon.” katanya. “Eits, jangan. Biarkan saja mereka bersama Doreng. Jangan ganggu mereka!” kataku menahan Ipung. “Hei mana Doreng?” kata Ihsan yang terlihat kepayahan. “Sstttt..lihat! Doreng sudah punya 5 ekor anak.” kataku mengulanginya. “Kenapa enggak dibawa pulang saja, Bon?” kata Ihsan. “Sudah biar saja, mungkin Doreng sudah ingin bebas. Lihat saja tanganku, dia sudah tak mau lagi ku peluk seperti dahulu.” kataku. “Coba lihat, warnanya!” kata Ihsan. “Aku suka yang hitam.” kataku. “Aku yang putih pirang itu, Bon.” kata Ihsan. “Kalau aku yang coklat itu.” kata Ipung.
118 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Eh teman-teman. Kalian janji ya, jangan ganggu Doreng. Jangan beri tahu siapapun kalau Doreng bersarang disini.” kataku. “Tenang saja, kami akan jaga rahasia ini kok. Iya kan San?” kata Ipung. Ihsan hanya mengangguk. “Hei, sedang apa kalian disitu?” Tiba-tiba Aceng dan Munir sudah ada di belakang kami, mereka mendekat. “Ah tidak ada apa-apa kok.” kataku seraya berusaha menutup kembali semak yang ku buka tadi. “Aku
enggak percaya!”
Kemudian
Aceng mencoba
mendorongku menjauh dari semak-semak itu. Aku bersikeras menahannya. “Aku sudah bilang, enggak ada apa-apa!” kataku membentak. “Oh..kamu berani, Bon?” kata Aceng. Sementara itu, Munir menarik Ipung dan Ihsan menjauh. “Sudah lebih baik kamu pergi saja, Ceng!” kataku.
119 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Wah kamu mau ku pukul lagi?” katanya menantang. Sekuat tenaga aku mendorongnya. Tak terima ia pun melepaskan tinjunya tepat ke arah pelipisku. Aku terjatuh, kali ini aku tak berdaya karena aku telah berjanji tak akan berkelahi lagi. Aceng membuka semak itu dan ia melihat Doreng dengan 5 ekor anaknya. “Oh jadi ini? Buat apa kucing seperti ini!” katanya seraya menendang Doreng hingga terpental. Melihat kejadian itu, entah apa yang merasuki tubuhku. Ku ambil batu sebesar genggaman tangan dan ku lemparkan ke arah Aceng. Batu itu tepat mengenai hidung Aceng, ia jatuh dan mengeluarkan darah. “Ahhhh hidungku!!!” kata Aceng kesakitan. Munir segera membawa pergi Aceng. Aku tahu ini akan berujung dengan amarah ayahku tapi masa bodoh. “Bon, gila kamu.” kata Ipung.
120 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ah masa bodoh. Biar tahu rasa dia! Dia pikir, dia yang paling hebat disini!” kataku penuh emosi. “Tapi
ayahmu,
Bon.
Ayahmu...”
katanya
coba
menyadarkanku. Aku terdiam sejenak. “Pung, aku pulang ke rumahmu saja ya?” kataku. “Kenapa, Bon?” tanya Ipung. “Kamu sendiri yang bilang. Pasti ayahku marah, kalau tahu aku berkelahi lagi.” kataku. Ihsan hanya terbengong keheranan. “Ya sudah, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita ceritakan kejadian ini kepada orangtuaku. Siapa tahu mereka bisa mengerti dan mengijinkanmu tinggal di rumahku.” kata Ipung. “San, kalau kamu bertemu ayahmu atau ayahku. Bilang saja kamu tak bertemu denganku! Jangan sampai mereka tahu aku ada di rumah Ipung.” kataku. Ihsan mengangguk, tanda ia mengerti. Kemudian aku pulang menuju rumah Ipung. Sesampainya disana, syukurlah orangtua Ipung mengijinkanku tinggal
121 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
sementara di rumah mereka. Orangtua Ipung mengerti benar tentang keadaanku, lagipula aku bisa mengajari Ipung beberapa pelajaran yang ku bisa. Ku harap ayah tak menemukanku disini, aku takut ayah akan memukuliku seperti tempo hari. Aku sungguh takut. Aku juga tak mau lagi merepotkan Mbah Menir dan Paman Salim, aku sangat jahat untuk orangorang sebaik mereka. Tapi bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Perasaan masa bodohku waktu itu membuatku kembali terlibat masalah besar.
122 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
JEJAK TERAKHIR
Sementara itu, Ihsan pulang ke rumahnya. Ia berlari segera menemui Mbah Menir dan ibunya. Kebetulan, ayahnya sedang bekerja. “Mbah..simbah..” katanya memanggil. “Iya ada apa le?” sahut Mbah Menir. “Mbah, Ihsan mau bercerita tapi tolong jangan kasih tahu ayah Bono ya mbah?” kata Ihsan sedikit gugup. “Lho lho lho, ada apa sih le?” kata Mbah Menir heran. “Begini mbah, tadi kami menemukan Doreng di semaksemak pinggir kali di sebelah sana.” kata Ihsan mulai bercerita. “Iya, njur piye le?” Tanya Mbah Menir mulai larut. “Tapi tiba-tiba, Aceng dan Munir menemukan kami sedang di sana. Mereka jahat mbah. Aceng menendang Doreng, karena tak terima Bono melemparkan batu ke arah Aceng. Aceng
123 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
berdarah mbah. Bono takut pada ayahnya, sehingga ia tak mau pulang mbah.” kata Ihsan bercerita. “Terus sekarang Bono dimana le?” Mbah Menir khawatir. “Di rumah Ipung mbah.” jelas Ihsan. “Ya sudah. Sementara biar dia disana dulu, sekarang kita ke rumah Bono saja menemui ayahnya.” ajak Mbah Menir. “Jangan mbah, Bono melarang Ihsan member tahu ayahnya. Ia takut dipukul lagi.” Ihsan melarang. “Justru kita harus segera ceritakan kejadian ini, sebelum orang lain yang bercerita le.” kata Mbah Menir. “Sudah, ayo ikut simbah!” Ihsan dan Mbah Menir menuju rumahku. Sementara ibu Ihsan tinggal sendiri menunggui rumah Mbah Menir. Mereka bergegas menuju rumahku. Tapi belum sampai di rumahku, mereka melihat rumahku sudah cukup ramai di datangi beberapa orang. Orang-orang itu adalah ayah Aceng dan beberapa anak buahnya.
124 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Aku ini bosmu Wan! Sekarang kamu lihat apa yang terjadi pada anakku! Hidungnya robek terkena lemparan batu anakmu itu!” kata ayah Aceng marah-marah sambil menunjuk hidung anaknya yang diperban. “Tapi mas, tolong jangan berhentikan saya. Saya masih mau berkerja di kapal Mas Karso.” kata ayahku memohon. “Kalau memang ndak mau saya berhentikan, ya ganti rugi biaya pengobatan anakku!” kata ayah Aceng naik pitam. “Tapi uang darimana mas? Hasil melaut saya dengan perahu njenengan juga hanya cukup untuk makan.” kata ayahku. “Itu urusanmu! Kalau kamu tidak mampu mengganti biaya pengobatan anakku, ya sudah kamu tidak usah bekerja lagi, tidak usah melaut lagi dengan perahuku!” kata ayah Aceng. “Eh eh eh ada apa ini?” Mbah Menir memotong pembicaraan mereka. “Ini mbah, anak si Ridwan melempar anakku dengan batu. Ya sobek hidungnya. Lima jahitan mbah.” kata ayah Aceng.
125 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Masalah itu, aku sudah dengar dari Ihsan.” kata Mbah Menir. “Ndi bocahe mbah? Biar aku pukul anak itu!” kata ayah marah. “Kamu itu Wan, bisanya cuma memukuli anakmu saja! Dengarkan simbah dulu!” Kini Mbah Menir tak bisa menahan diri. Ayah terdiam, kaget melihat ekspresi Mbah Menir tak seperti biasanya. “Gini So, Wan. Tadi Ihsan sudah cerita sama simbah. Katanya Bono seperti itu karena Aceng menendang Doreng, kucing kesayangan Bono. Tak terima Bono melemparkan batu. Ya, akhirnya seperti yang kalian ketahui. Aceng terluka di hidungnya.” Cerita Mbah Menir. “Saya ndak mau tahu mbah. Yang saya mau sekarang, Ridwan mengganti biaya pengobatan anak saya!” kata ayah Aceng.
126 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Masalah ganti rugi itu gampang. Biar simbah yang ganti, kamu butuh berapa So?” kata Mbah Menir seraya mengeluarkan dompet dari balik kain kembennya. “Sebenarnya hanya 125 ribu mbah.” kata ayah Aceng. “Halah mung sakmono tok, ini simbah bayar!” kata Mbah Menir ketus. “Maaf ya mbah, bukan maksud saya mau menyinggung simbah.” kata ayah Aceng sungkan. Mbah Menir hanya melirik. Bagaimana pun juga Mbah Menir sangat dihormati oleh warga kampung karena jasa-jasanya. “Kamu juga Ceng! Sukanya mengganggu, meledek, mengejek Bono. Bono itu sudah seperti cucuku, kamu tahu apa akibatnya membuat aku marah?” kata Mbah Menir geram. Aceng ketakutan hanya bersembunyi di balik tubuh ayahnya. “Sekali lagi kamu buat Bono sedih atau terluka. Simbah sendiri yang akan memberi pelajaran buatmu! Besok kamu harus minta maaf pada Bono!” kata Mbah Menir bertambah murka.
127 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“I..iya mbah. Aceng janji tidak akan nakal lagi pada Bono. Aceng akan minta maaf padanya, mbah” kata Aceng. “Iya mbah. Maafkan kelakuan anak saya ya mbah?” kata ayahnya meminta maaf. “Yo wis tak tompo!” kata Mbah Menir. “Terima kasih mbah, terima kasih.” kata Aceng dan ayahnya. “Iya saya juga terima kasih mbah. Sudah banyak dibantu Mbah Menir.” kata ayahku haru. “Sudah Wan, sudah. Sekarang kita cari anakmu. Yang lain bubar, kamu juga So segera pulang rawat anakmu.” perintah Mbah Menir. “Baik Mbah.” kata ayah Aceng kemudian mengajak anak buahnya pergi. “Simbah tahu dimana Bono?” tanya ayahku.
128 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Simbah sebenarnya tahu, tapi kamu janji jangan pukuli anakmu lagi. Kalau sampai kamu pukuli anakmu lagi, simbah ndak segan-segan buat memukulimu!” kata Mbah Menir. “I..iya mbah. Saya heran kenapa hari ini simbah lebih galak daripada saya.” kata ayahku heran. “Ya begini kalau simbah sudah marah. Gunung pun bisa mbah telan.” kata Mbah Menir menahan senyum. Mereka menuju ke rumah Ipung untuk menemuiku. “Kamu di sini saja dulu Wan. Biar aku dan Ihsan yang masuk ke dalam.” kata Mbah Menir. Ayah menurut. “Assalamualaikum” Mbah Menir mengucapkan salam. “Wa’alaikumusalam, eh Mbah Menir. Ada apa mbah?” sahut ibu Ipung. “Bono ada di sini?” tanya Mbah Menir. “Iya ada mbah. Bono..Bono..ini dicari Mbah Menir.” Panggil ibu Ipung. Aku dan Ipung menuju ke serambi rumah.
129 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ayo le, pulang. Ndak baik merepotkan orang.” kata Mbah Menir. “Tapi Bono takut dengan ayah mbah.” kataku ketakutan. “Ndak apa-apa. Kalau ayahmu berani memukulmu, biar simbah pukul ayahmu sekuat tenaga. Begini-begini dulu simbah jago silat lho le.” canda Mbah Menir coba menenangkanku. “Iya mbah. Pung, aku pulang dulu ya? Terima kasih sudah ijinkan aku tinggal di rumahmu.” kataku. “Iya Bon, sama-sama. Kita kan sohib seperjuangan.” katanya Ipung seraya menepuk pundakku. Kami berpamitan pada keluarga Ipung dan pergi menuju rumahku. Baru beberapa langkah dari halaman rumah Ipung, ku lihat ayah bersender pada sebuah pohon besar. Ku lihat seakanakan, ayah akan menerkamku seperti singa kelaparan. “Mbah, ada ayah. Bono takut.” kataku berlindung dibalik tubuh Mbah Menir. “Sini le. Kemari!” kata ayahku.
130 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mbah
Menir
menarik
lenganku
dan
menyuruhku
menyambut perintah ayah. Aku berjalan tak mantap, aku takut ayah akan memukuliku lagi. Tiba-tiba “hap” tubuh besar ayah memeluk erat tubuhku. Aku kaget, terharu dan tak bisa berkata apa-apa. “Maafkan ayah ya le, tak bisa mendidikmu dengan baik. Ayah harus bekerja, jadi ayah tidak seperti dulu lagi saat masih ada ibumu. Ayah menyesal le.” kata ayahku sendu. “Iya ayah, maafkan Bono juga. Bono tidak melaksanakan nasehat ayah dengan baik.” kataku menyambut pelukan ayah dengan melingkarkan lengan memeluk ayah. “Nah kalau gitu kan enak dilihat.” kata Mbah Menir. “Iya mbah. Terima kasih ya mbah. Saya janji tidak akan memukuli Bono lagi.” kata ayah berdiri dan mencium tangan Mbah Menir tanda bakti. “Lha iya, memang almarhumah istrimu tidak sakit hatinya kalau ia lihat Bono kau perlakukan kasar?” kata Mbah Menir.
131 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya mba, maaf. Sekarang saya mengerti mbah.” kata ayahku lirih. “Ya sudah, sekarang Bono pulang ke rumah dengan ayah ya? Simbah pulang dengan Ihsan.” kata Mbah Menir. Aku mengangguk. Lalu kami pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, ku buatkan ayah segelas kopi tanpa ayah perintah. Kemudian coba lebih dekat dengan mengajaknya bicara. “Ini yah, Bono buatkan kopi panas.” kataku menyajikan segelas kopi panas. “Terima kasih ya le.” kata ayah kemudian meniup-niup gelas berisi kopi panas. “Ayah, sebentar lagi Bono ulang tahun. Bono sering lihat teman-teman yang lain merayakan ulang tahun. Senang yah jadi mereka, dapat hadiah dari orangtua mereka.” kataku. “Kamu juga ingin seperti mereka? Ingin ayah beri hadiah di hari ulang tahunmu?” kata ayah menebak arah pembicaraanku.
132 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ahh tidak yah tidak. Bono hanya bercerita saja koq, kesehatan ayah sudah jadi kado spesial buat Bono. Lagi pula Bono paham betul, ayah bekerja keras siang malam untuk mencukupi kebutuhan Bono. Jadi Bono tak berharap hadiah apapun.” kataku menyangkal. “Ya sudah kalau begitu. Yang penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita miliki sekarang. Makanya sekolah yang rajin ya le biar nasibmu lebih baik dari ayah.” kata ayah. “Iya yah. Bono pasti akan lebih rajin belajar dan tidak nakal lagi.” kataku. “Oh iya le, beberapa waktu yang lalu ayah membaca puisi untuk ibu yang kamu buat. Kamu pandai menulis ya le?” kata ayahku memuji. “Iya yah. Selain matematika, Bono juga suka pelajaran Bahasa Indonesia terutama menulis puisi yah. Oh iya, ayah taruh dimana puisi itu?” tanyaku.
133 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Di lemari buku-bukumu le. Coba bawa kemari biar ayah baca lagi. Sekalian bawa foto Ir. Soekarno yang tertempel di dinding ya le?” kata ayah menyuruhku. Aku bergegas mencari puisi itu dan foto Ir. Soekarno yang ayah maksud kemudian segera kembali membawanya pada ayah. “Ini yah.” Ku lihat ayah membaca puisiku dan mengangguk-angguk tanda ia paham dengan isi puisi itu. “Bagus le, kapan-kapan buatkan ayah juga ya?” kata ayah kemudian ia tersenyum lembut. Ayah melepas foto Ir. Soekarno dari piguranya kemudian memasukkan puisiku ke pigura itu. “Ini, simpan baik-baik! Jangan sampai rusak ya le?” kata ayah menyerahkan puisi yang sudah berpigura kepadaku. Ku raih puisi itu kemudian berkata, “Baik yah. Tapi bagaimana dengan foto Ir. Soekarno itu yah? Bukankah itu tokoh idola ayah?”
134 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Tidak apa-apa. Tancapkan saja foto ini ditempat semula, gunakan paku kecil agar foto ini tidak rusak ya le? Sudah sana, letakkan puisi itu ditempat yang kamu suka!” perintah ayah. Aku menuruti perintah ayah dan bergegas menuju kamar sementara ayah mengikutiku dari belakang. Ku tancapkan foto Ir. Soekarno terlebih dahulu dengan paku kecil di tempat semula. Kemudian ku buka penyangga piguranya dan ku letakkan puisi berpigura itu di atas meja kamarku. Aku tersenyum senang, ayah pun tersenyum turut senang. “Ya sudah, sekarang kita istirahat. Besok ayah mau berangkat melaut.” kata ayah. Aku hanya mengangguk, ku rebahkan tubuhku dan sepintas ku lihat ayah menuju bangku bambu di depan rumah. Dalam suasana senang, tak butuh waktu lama bagiku terlelap dalam tidur. Dalam tidur aku bermimpi. Aku bertemu ibu, kali ini ia menangis. Ku tanya ada apa gerangan yang terjadi pada ibu. Ia tak menjawab, sesekali ia hanya mengeluarkan satu kata yang
135 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
sama berulang-ulang. Aku coba mengerti apa yang ia katakan. “Ayah” itu kata yang ibu ucapkan. Aku coba bertanya, “Ayah kenapa bu?” Kini kata “Ayah” berganti menjadi “Laut”. Aku semakin bingung, aku tak mengerti apa yang ingin ibu sampaikan dalam mimpi. Tiba-tiba ibu menarikku, tangannya erat mencengkram lenganku. Ia membawaku ke pantai dan menunjuk ke suatu benda. Ku pahami benda itu semakin mendekat, aku coba berjalan beberapa langkah untuk memperjelas penglihatanku. Itu sebuah perahu, tapi semakin lama ku lihat ternyata perahu itu terbelah dua. Hanya bagian depan yang mengapung, sementara bagian lainnya entah dimana. Aku berpaling pada ibu dan bertanya, “Itu perahu siapa bu?” Ibu menjawab dengan menangis, “Ayah”. Mendengar jawaban itu, aku berteriak memanggil nama ayah, “Ayaaaahhh…ayaaahhhh”.
136 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku ingin meraih perahu itu, tapi entah bagaimana kakiku membatu tak dapat ku gerakkan. Aku memanggil ibu untuk membantuku, tetapi ia sudah menghilang. Aku ketakutan, aku menjerit sejadi-jadinya. Air laut mulai melahap sedikit demi sedikit tubuhku. “Ahhhhhhhh” aku terbangun. “Astagfirullahal adzim” Aku bergegas keluar rumah. Ayah sudah tak ada di bangku bamboo tempat biasa ia tidur. Ku lihat matahari belum muncul, “Ini belum subuh.” Aku berlari menuju pantai, ku lihat perahu yang biasa ayah gunakan melaut sudah tidak ada. Aku terduduk, kakiku lemas. Aku takut terjadi sesuatu pada ayah. Tak terasa aku menangis. Dan seakan-akan langit ikut menangis, hujan mengguyur tubuhku. Air mataku bercampur dengan air hujan yang membasahi tubuhku. Seakan-akan dinginnya angin yang menerpa tubuhku, tak ku rasakan.
137 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Dengan
guyuran
hujan
yang
semakin
deras,
aku
memandang ke selatan. Aku berharap ayah baik-baik saja. Tiba-tiba dari arah belakang ku dengar suara orang berteriak, “Hei, jangan disitu! Kemari! Anginnya kencang!” Aku tak peduli. Aku bertekad menunggu ayah disini. Seseorang bermantel biru mendekat dan menarikku. Aku berontak dan berkata, “Biar saja, aku sedang menunggu ayahku.” “Kamu mau bunuh diri atau bagaimana Bon?” katanya. Ku lihat, itu Mas Ikin. “Ayah dimana mas?” tanyaku. “Ayo kita berteduh dulu, nanti Mas Ikin ceritakan.” katanya membujukku. Aku menurutinya. Kami berteduh di sebuah gubuk di dekat pantai. Mas ikin membalutku dengan handuk, “Keringkan badanmu dengan handuk ini.”
138 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Aku mengusap-usap tubuhku yang basah dengan handuk itu kemudian bertanya, “Mas, apa ayah pergi melaut?” “Begini Bon, sebenarnya kami para nelayan sudah tahu akan terjadi hujan angin hari ini. Sangat berbahaya jika melaut, tapi ayahmu bersikeras untuk melaut hari ini. Jadi, ia bersama dua orang nelayan lainnya pergi melaut.” kata Mas Ikin. “Untuk apa ayah melaut, jika sudah tahu akan berbahaya mas?” tanyaku. “Emmm katanya sebentar lagi kamu ulang tahun ya? Ayahmu ingin sekali membelikanmu hadiah di hari ulang tahun nanti.” kata Mas Ikin. “Ayahh. Bono tak perlu hadiah, Bono hanya ingin ayah.” kataku menyesal. “Sudahlah, kita doakan saja ayahmu baik-baik saja.” kata Mas Ikin mengusap punggungku. Aku terdiam, menyalahkan diriku sendiri.
139 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mas Ikin terperanjat, ia melihat kegaduhan di satu sudut pantai. Kami mendekat. “Ada apa pak?” tanya mas Ikin. “Saat kami sedang melaut, kami melihat ada perahu yang tersapu ombak. Beruntung kami bisa menyelamatkan semua penumpangnya. Semua selamat, hanya satu yang sepertinya terluka parah.” kata salah seorang nelayan. “Coba kami bantu pak.” kata Mas Ikin. Perasaanku mulai was-was. Benar saja, yang ku lihat tergeletak di dalam perahu adalah ayah. “Ayaaahhhhh.” “Cepat angkat, angkat.” kata Mas Ikin memberi aba-aba nelayan lain untuk mengangkat tubuh ayah. “Bono, cepat kamu beri tahu Mbah Menir dan Paman Salim. Kita harus segera ke Puskesmas!” perintah Mas Ikin panik. Aku mengangguk dan berlari secepat mungkin menuju rumah Mbah Menir.
140 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Mbah…..Mbah Menir….Mbah.” aku berteriak menggedorgedor pintu rumah Mbah Menir. Mbah Menir keluar, aku memeluknya erat. “Ada apa le?” “Ayah terluka parah mbah. Perahunya tersapu ombak.” kataku tersedu-sedu. “Yaa Allah…Ayo cepat kita kesana, Lim susul kami di Puskesmas ya?” teriak Mbah Menir. Kami menuju Puskesmas, disana mobil ambulan telah siaga. “Mau dibawa kemana ini Kin?” tanya Mbah Menir pada Mas Ikin. “Rumah Sakit di kota mbah, katanya ada yang retak di tulang pinggul Mas Ridwan.” jelas Mas Ikin. “Mbah Menir dan Bono ikut ambulan saja, biar saya dan yang lain menyusul dengan mobil Mas Karso.” Aku dan Mbah Menir masuk ke dalam ambulan. Ku lihat ayah merintih, aku coba membisikkan di telinganya kalimat syahadat. Aku menangis.
141 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Perjalanan terasa panjang. Ambulan yang mengantarkan ayah ke Rumah Sakit harus diangkut dengan kapal menuju pelabuhan di kota. Dari pelabuhan ambulan melaju kencang menuju Rumah Sakit. Sesampainya di Rumah Sakit, ayah mendapat penanganan dari dokter di ruang gawat darurat. Aku tak mampu berkatakata, suasana sangat ramai tapi hatiku sepi. Aku, Mbah Menir, Ihsan, Paman dan Bibi Salim menunggu di depan ruang gawat darurat sementara mas Ikin dan Pak Karso ayah Aceng bersama beberapa warga kampung menunggu di luar Rumah Sakit. Aku menyandarkan kepalaku di paha Mbah Menir. Kami duduk bersebelahan. Tangannya lembut mengeluselus kepalaku. Setelah menunggu sekitar 2 jam, dokter keluar dari ruang gawat darurat. Paman Salim bertanya pada dokter, “Bagaimana keadaan pasien, dok?” “Anda keluarganya?” tanya dokter itu.
142 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya, saya saudaranya.” kata Paman Salim mengaku saudara ayah. “Baik. Ikut saya ke ruangan.” ajak dokter itu. Paman Salim dan dokter itu pergi, aku hanya melirik. Mereka pergi cukup lama, semua berusaha menghiburku tapi seakan aku tak peduli. Dari kejauhan ku lihat Paman Salim datang dengan wajah tertunduk. “Ada apa Lim?” tanya Mbah Menir. Paman Salim hanya tersenyum dan berjongkok didepanku. “Bono, ayah kamu sudah bisa dijenguk besok. Tapi paman mau tanya, kamu sayang ayahmu?” kata Paman Salim ramah. “Iya paman.” kataku lirih. “Kalau kamu sayang ayahmu, jangan pernah terlihat sedih di depannya. Ayahmu ingin kamu jadi orang yang kuat. Kamu janji ya?” kata Paman Salim. Aku hanya mengangguk.
143 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Tapi Bono, paman minta maaf harus sampaikan berita ini. Kata dokter ayahmu sudah tak dapat berjalan seperti sebelumnya. Ia lumpuh.” kata Paman Salim tak tega. Mendengar kata-kata Paman Salim hatiku remuk redam. Aku menahan sekuat tenaga air mataku tak keluar, tapi apa daya aku hanya anak 12 tahun. Ku peluk tubuh Mbah Menir dan menangis sejadi-jadinya. “Kenapa bisa begitu Lim?” kata Mbah Menir sedih. “Kata dokter, kemungkinan tulang pinggulnya retak karena terbentur karang. Itu yang menyebabkan syarafnya rusak dan Mas Ridwan lumpuh, bu.” jelas Paman Salim. “Astagfirullah..sabar ya le?” kata Mbah Menir tak hentihentinya mengusap kepalaku. “Sssttt sudah-sudah. Jangan menangis lagi sayang.” Bibi Salim membantu Mbah Menir menenangkanku. Ihsan hanya terbengong tak tahu harus berbuat apa.
144 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Mbah Menir mengajakku keluar. Mas Ikin mendekat dan bertanya, “Bono kenapa mbah?” Mbah Menir meletakkan telunjuknya di atas mulut, memberi tanda untuk tidak bertanya. “Kamu tanya Salim saja di dalam.” kata Mbah Menir. Mbah
Menir
menidurkanku
di
atas
pangkuannya.
Kemudian seperti biasa, ia menyanyikan tembang jawa. Aku sesenggukan, pasrah pada apa yang sedang terjadi. Suara Mbah Menir merdu, aku tak kuasa menahan kantuk. Aku tertidur. Tak
terasa
subuh
datang.
Tangan
Mbah
Menir
membangunkanku. “Ayo sholat subuh dulu, le.” Ku gosok-gosok kelopak mataku. Mbah Menir menuntunku menuju mushola di Rumah Sakit. Kami sholat subuh berjamaah dengan beberapa orang yang sudah berkumpul di mushola itu. Selesai sholat, aku berdoa untuk ayah, ibu dan semua yang sudah menyayangiku.
145 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Selesai sholat subuh Mbah Menir mengajaku menjenguk ayah. Ku lihat kondisi ayah sudah cukup baik. Ayah tersenyum melihatku, aku berlari dan memeluknya. Ayah hanya bisa berbaring di atas kasur. “Ayah, kapan pulang? Besok Bono ulang tahun.” kataku. “Sabar ya le. Tidak apa-apa kan kalau kita berulang tahun di sini? Lihat, belum ulang tahun saja sudah banyak makanan.” canda ayah coba menghibur hatiku. “Tapi maaf ya le, ayah ndak bisa kasih kamu hadiah apaapa.” kata ayah menyesal. “Tidak yah, ada ayah di hari ulang tahun Bono saja itu sudah jadi hadiah yang istimewa yah.” kataku coba mengerti keadaan. “Kamu memang anak yang berbakti le. Maaf kalau selama ini ayah sering memarahi dan memukul. Ayah menyesal le.” kata ayah memandangku dalam.
146 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Iya yah. Bono tahu ayah menyayangi Bono, hanya terkadang Bono yang selalu membuat ayah marah. Melanggar nasehat ayah.” pelukkanku semakin erat. “Aduh yang lagi bersedih ria, sudah lah sebentar lagi kan Bono ulang tahun. Jangan sedih lagi. Mungkin dengan kejadian ini kita semua bisa introspeksi diri untuk jadi manusia yang lebih baik lagi.” kata Paman Salim memotong pembicaraanku dengan ayah. “Benar kata Pamanmu le. Sudah mulai hari ini tidak boleh ada yang sedih lagi.” kata ayah tersenyum. Aku membalas senyum ayah. “Oh iya le. Kamu kan janji mau membuatkan ayah puisi. Coba buatkan ayah le.” pinta ayah. “Baik yah. Bono buatkan dulu yah.” kataku bersemangat. “Paman Salim ada kertas dan pena, gunakan ini saja.” kata Paman Salim seraya menyerahkan kertas dan pena dari dalam tas kerjanya. Aku menerimanya dan mulai menulis.
147 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ya sudah kang. Saya berangkat kerja dulu ya? Semalam saya sengaja membawa peralatan kantor, mumpung di kota kang jadi tidak bolak balik.” kata Paman Salim kemudian tertawa sungkan. Ayah hanya membalas dengan anggukan. “Bu, saya berangkat ya? Assalamualaikum.” kata Paman Salim berpamitan pada Mbah Menir. “Iya Lim. Hati-hati ya, jangan lupa bawakan Ridwan makanan yang enak-enak.” kata Mbah Menir. “Ah tidak usah Lim. Jangan repot-repot.” ayah melarang. “Tidak apa-apa kang. Insya Allah nanti saya bawakan.” kata Paman Salim kemudian keluar dari ruangan tempat ayah dirawat. Sementara itu pandanganku hanya tertuju pada bait-bait puisi yang ku tulis. Seakan tak mau mengganggu, mereka hanya memandangiku. Ayah, Mbah Menir dan Bibi Salim memandangi dari jauh. Sementara Ihsan coba membaca bait-bait yang ku tulis.
148 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
“Ehhh jangan dibaca dulu!” kataku melarang. “Ihsan, jangan ganggu Bono nak.” kata Bibi Salim. “Ihh kok kamu jadi pelit sih?” kata Ihsan cemberut. “Bukannya pelit. Tapi puisi ini kan rahasia, aku ingin membacakannya untuk ayah.” kataku kemudian meledek Ihsan dengan menarik ujung hidungnya. “Ahhh. Sakit tahu! Ya sudah, aku juga bisa buat puisi! Ibuu, Ihsan mau kertas dan pena seperti Bono.” kata Ihsan manja. “Ibu ndak punya. Yuk kita beli saja di luar.” kata Bibi Salim kemudian mengajak Ihsan keluar. Tak terasa sebuah puisi indah telah ku buat. Mbah Menir mendekat ingin membacanya. Cepat-cepat ku lipat kertas itu. “Ehh simbah juga ndak boleh baca le?” kata Mbah Menir. “Jangan dulu mbah. Besok saja, Bono mau bacakan puisi ini dihari ulang tahun Bono.” kataku. “Yo wis lah. Sak karepmu.” kata simbah. Aku dan ayah tertawa.
149 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Waktu berganti waktu. Ku lihat Sang Surya mulai menyembunyikan dirinya di ufuk barat. Malam itu tak ada lagi tangis dan kesedihan. Yang ada hanyalah tawa, canda dan kebahagiaan. Terlebih saat Widi, Dani, Ipung dan Ara datang menjenguk ayahku. Bahkan Aceng datang bersama Pak Karso, ayahnya. “Kamu datang Ceng?” tanyaku. “Iya Bon. Maaf ya kalau selama ini aku jahat padamu. Aku ingin mulai hari ini kita berteman. Aku juga mengajak Munir. Tapi dia malu.” katanya. “Untuk apa malu? Mana dia?” kataku. Kami berjalan menemui Munir. “Munir. Kemari!” kataku. Ia hanya menggelengkan kepala. Aku mendekat dan merangkulnya. “Sudahlah. Tak perlu malu. Sekarang kita semua berteman. Tak boleh lagi ada yang bermusuhan.” kataku. Munir menahan
150 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
senyum kemudian malu menutupi muka dengan telapak tangannya. Kami semua tertawa. Seakan Allah telah mengatur semua ini. Ulang tahunku jatuh besok pada hari Minggu. Sehingga teman-teman bisa berkumpul bersamaku, walau di Rumah Sakit. Belum lagi, orangorang yang menyayangiku seperti ayah, Mbah Menir, Paman dan Bibi Salim ada saat aku berulang tahun. Bahkan Mas Ikin dan Pak Karso, bisa ikut berkumpul juga. Ini diluar dugaanku. Aku dan teman-teman bermain bersama di halaman Rumah Sakit. Beberapa anak-anak juga bermain disana. Aku senang. Karena kelelahan kami semua tertidur di bangku di ruangan tempat ayahku dirawat. Esok pagi, sesaat setelah aku terbangun. Mbah Menir dan Bibi Salim terlihat merapihkan ruangan. Sementara Pak Karso dan ayahku terlihat sedang berbincang-bincang. Mas Ikin membangunkanku dan anak-anak yang lain satu per satu kemudian menyuruh kami untuk sholat subuh.
151 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Setelah sholat shubuh, Mas Ikin menyuruh kami mandi. Kami bergantian memakai kamar mandi. Ihsan mandi terlebih dahulu, diikuti Dani, Ipung, Ara, Aceng, Munir, Widi dan terakhir aku. Selesai mandi Mbah Menir mengeringkan tubuhku dan memakaikan baju. Ku lihat semua sudah duduk rapih, orang dewasa duduk di kursi sementara anak-anak duduk di lantai. Ku lihat ayah juga duduk di kasurnya. Tapi kemana Paman Salim? Dia tak ada disini. Tiba-tiba dari arah pintu Paman Salim masuk dan berteriak, “Selamat Ulang Tahun Bono.” Paman Salim membawa sebuah kue tart lengkap dengan lilin dan hiasannya. Semua bertepuk tangan. “Yuk nyanyi selamat ulang tahun untuk Bono.” ajak Paman Salim. Semua bernyanyi. Aku sangat senang. Bulu kudukku merinding merasakan kebahagiaan dan kebersamaan saat itu. Kemudian aku meniup lilinnya dan memotong kue itu dibantu Bibi Salim menjadi beberapa bagian kemudian ku
152 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
bagikan pada semua teman-temanku. Kami lahap memakan kue itu, rasanya lezat. “Bono, katanya kamu mau membacakan puisi untuk ayah.” kata ayah mengingatkanku. “Oh iya, Bono hampir saja lupa yah.” kataku sambil menepuk kening kemudian bergegas mencari puisi yang telah ku buat untuk ayah. Seketika suasana menjadi hening saat aku mulai membuka kertas puisiku. Semuanya serius menyimak bait-bait yang aku bacakan. Bahkan Mbah Menir meneteskan air mata haru. Hari itu menjadi ulang tahun yang istimewa bagiku. Baru kali ini aku merayakan ulang tahun seperti teman-teman yang lain. Walau tak ada ibu dan ayah baru saja mengalami musibah, tapi semua itu terbayar dengan berkumpulnya orang-orang yang sangat ku sayang. Ayah, Mbah Menir, Mas Ikin, Paman Salim, Bibi Salim, Pak Karso dan teman-temanku.
153 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
Bono Sugiarto Jejak Terakhir
Ayah bisa mengarungi samudera. Mempertaruhkan nyawa demi anaknya. Ayah bisa melawan ganasnya dunia. Hanya didasari cinta pada anaknya.
Begitu hebatnya engkau ayah. Tak pernah mengeluh tubuhmu lelah. Begitu dahsyatnya engkau ayah. Selalu mengajariku untuk bertabah.
Hanya nasehat yang selalu kau ajarkan. Sebagai jejak terakhir sebelum kau berlayar. Dan hanya doa yang selalu ku panjatkan. Sebagai jejak terakhir sampai kau pulang berlayar.
154 Jejak Terakhir : hanya sebuah kisah anak nelayan
vii
Related Documents

Novel Jejak Terakhir
February 2021 15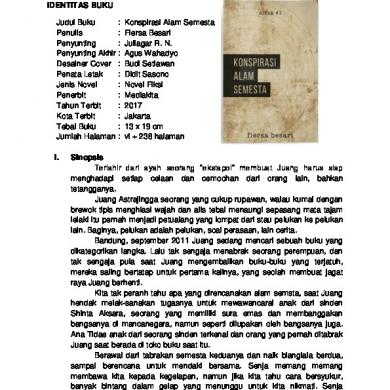
Novel
February 2021 4
Novel
February 2021 4
Jejak Prabowo
January 2021 2
Aqessa Aninda - Dua Jejak
January 2021 4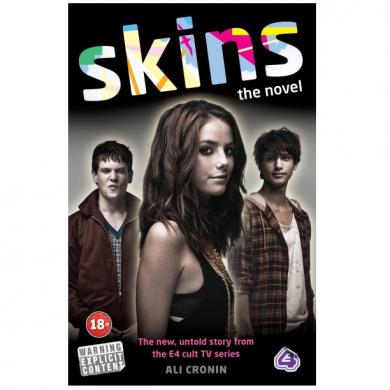
Skins Novel
February 2021 4More Documents from "Borja Best"
