Web Media Kerjabudaya Edisi 072001
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Web Media Kerjabudaya Edisi 072001 as PDF for free.
More details
- Words: 31,345
- Pages: 23
Loading documents preview...
PicoSearch EDITORIAL
Cari!
Edisi No 07 Tahun 2001
Kata Globalisasi sudah menjadi salam pengunci dalam mantramantra penyejuk suasana krisis permanen. Para ekonom, sekaligus juru bicara pasar modal, berlomba-lomba memberikan petuah agar pemerintah dan rakyat Indonesia mematuhi “anjuran” lembaga keuangan internasional seperti 10 Perintah Allah. Konon, hanya dengan bersikap taat dan takzim begini Indonesia akan mampu bersaing dalam era globalisasi, dan dapat keluar menjadi pemenang. Laiknya tukang obat, mereka menceracau pula tentang kiat mencapai “keunggulan komparatif”, sambil jajakan yang masih tersisa di negeri ini: dari tanah, tenaga, sampai buah pikiran. Di antara haru-biru dan ketakjuban yang ditimbulkan Tragedi 11 September di Amerika Serikat, globalisasi tampilkan wajah buasnya. Jantung kekuasaan imperium dunia diguncang, dan seluruh sel yang sepakat menghidupinya dalam geram menerkam peluang. Perang global pun dikobarkan, sebelum jelas benar sosok sang musuh. Maling teriak maling atas nama “kebebasan dan demokrasi”. Entah “kebebasan” untuk siapa dan “demokrasi” yang mana. Yang jelas, modal berputar cepat meminyaki mesin-mesin tempur melaju ke dataran gersang yang merupakan gerbang menuju sumber minyak di Laut Kaspia. Globalisasi adalah kata pembenar bagi operasi gurita lembaga keuangan internasional serta perusahaan-perusahaan multinasional untuk pelipatgandaan dan pemusatan modal di tangan segelintir orang. Dengan bantuan pemerintahan yang korup dan otoriter, lembaga-lembaga internasional ini menjalankan operasi pemerataan kemiskinan melalui perang dan hutang. Dan, sekarang, setelah para gembong Komunis dianggap sudah bertekuk lutut, mereka temukan sebutan yang tepat bagi siapa pun yang menentang operasi ini: TERORIS. Edisi Media Kerja Budaya kali ini sarat angka dan data. Di tengah kesibukan JKB mempersiapkan sejumlah kegiatan lain, seperti Diskusi Bulan Purnama, Pameran Tunggal Dolorosa Sinaga, dan Kampanye Anti-Kekerasan dan Perdamaian Generasi Putih, dewan redaksi mencoba melacak gerak Bank Dunia, IMF, WTO dan negara-negara mapan yang bergabung dalam G-8. Institusiinstitusi ini lah yang mempersiapkan prasarana bagi perusahaanperusahaan multinasional untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin di segala penjuru dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerja kami dipermudah oleh perangkat yang dibangun oleh globalisasi itu sendiri: internet dan email. Namun, justru di sini tantangannya: bagaimana kita bisa mengambil-alih perangkat yang berpotensi membebaskan untuk, paling tidak, mengganggu derap penghancuran kemanusiaan berlanjut. Kami tahu kami tidak sendirian. Seperti yang akan diulas dalam salah satu bagian Pokok, perlawanan terhadap globalisasi merebak di seluruh dunia. Berbeda dengan gerakan perlawanan rakyat di dekade 1970an, gerakan anti-globalisasi tidak dipimpin oleh tokoh, organisasi massa atau partai politik tertentu. Ribuan organisasi masyarakat dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda terlibat dalam aksi-aksi yang beragam sepanjang 2000. Dalam satu organisasi kadang-kadang hanya beranggotakan 5-10 orang, tetapi masing-masing individu mempunyai kemampuan dan tanggung jawab yang jelas. Satu hal yang mempersatukan mereka: penolakan terhadap aturan-aturan main yang dibuat oleh segelintir orang dan lembaga tertentu atas kehidupan mereka sehari-hari.
Pokok Media Kerjabudaya Merayakan Kesengsaraan Sepuluh tahun lalu di mana-mana ada gairah luar biasa menyambut perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Orang ramai bicara tentang keajaiban globalisasi. Namun semua itu hanya dinikmati segelintir orang saja.
Globalisasi Perlawanan "Satu-satunya yang pantas menjadi global adalah perlawanan," demikian pengarang Arundhati Roy dari India, menyambut gerakan anti-globalisasi yang semakin meluas. Dari Seattle sampai Genoa, dari Chiapas sampai Jenewa, protes di Hyderabad, India sampai konperensi perlawanan terhadap globalisasi di Porto Alegre menunjukkan bahwa mengakhiri globalisasi kesengsaraan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
Jalan Neoliberal Bagi Indonesia Indonesia dalam cengkeraman tangan neoliberalisme dari dulu hingga sekarang. Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
Data Bicara Profil Institut Sekulir, membangun Gereja Kaum Miskin Mateus Goncalves
Pat Gulipat Puisi Husnul Khuluqi Kritik Seni Pledoi Mendobrak Si Moni Kamasra STSI-Bali
Klasik Resink dan Mitos Penjajahan 350 Tahun Razif
Cerita Pendek Segelas Kopi Darpan Ariawinangun
Esai Kesembuhan Semu Kapitalisme Thailand Arif Rusli
Logika Kultura Pasar John Roosa
Resensi Buku Saat-Saat Lampu Kuning, Saat-Saat Menggugat Diri Eddie Sius RL.
Tokoh Arnold C. Ap, Membangun Budaya Pembebasan Ibe Karyanto
Berita Pustaka Sisipan Media Kerjabudaya
Pemimpin Redaksi
●
●
●
●
Subversi Menegakkan Imperium: Politik Luar Negeri Amerika Serikat Surat Robert S. McNamara tentang Bantuan Militer kepada Indonesia pada 1965 Memerangi Terorisme, Menggerogoti Demokrasi di Indonesia Seabad Perlawanan di Filipina
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email versi teks
©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Merayakan Kesengsaraan Tim Media Kerja Budaya Sepuluh tahun lalu di mana-mana ada gairah luar biasa menyambut perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Orang ramai bicara tentang keajaiban globalisasi: makan siang dengan beras Thailand, daging Selandia Baru, sayuran segar dari Cianjur, sendok-garpu buatan Tiongkok, gelas keramik dari Perancis di atas meja antik dari dua abad lalu karya pengrajin India; perubahan pola komunikasi yang mengubah dimensi ruang dan waktu, akses ke beritaberita terbaru dari lima benua dalam hitungan detik, hubungan langsung ke tempat-tempat yang tak terbayangkan sebelumnya, dan seterusnya… dan seterusnya. Setiap hari industri komunikasi dan elektronik mencipta produk baru dan manusia semakin tenggelam dalam dunia maya: sebuah desa global di mana batas negara-bangsa menjadi tidak relevan dan cita-cita tentang perombakan struktur masyarakat adalah dongeng masa lalu. “Inilah akhir dari sejarah,” ujar Francis Fukuyama. Jika benar demikian, maka perjalanan umat manusia selama berabad-abad sungguh menyedihkan. Saat ini diperkirakan masih ada 840 juta orang menderita kekurangan gizi. Satu dari delapan orang di planet ini adalah pengangguran. Mayoritas mereka buta huruf dan tingkat harapan hidupnya kurang dari 60 tahun. Nasib anak-anak lebih buruk lagi. Satu dari empat anak di dunia sekarang menderita kekurangan gizi, dan setiap menit ada empat anak yang meninggal dunia penyakit diare dan gangguan pencernaan lainnya. Semua ini adalah produk globalisasi yang dirayakan sebagai “akhir dari sejarah”. Laporan UNDP tahun 1999 memberi gambaran lebih jauh tentang globalisasi dan hasil-hasilnya. Dalam waktu sepuluh tahun terjadi pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang. Tiga orang terkaya di dunia saat ini menguasai aset yang nilainya sama dengan milik 600 juta orang di 48 negeri termiskin. Kemakmuran mengalir dari tempat-tempat termiskin dan terburuk yang mungkin dibayangkan manusia ke pusat perdagangan dan keuangan negara industri maju. Saat ini seperlima penduduk di negeri-negeri paling kaya menguasai 86 persen produk domestik bruto dunia, 82 persen pasar ekspor dunia, 68 persen penanaman modal langsung dan 74 persen saluran telepon di dunia. Sementara seperlima penduduk di negeri-negeri termiskin hanya memiliki satu persen di masing-masing sektor. Kemajuan teknologi yang menjadi bintang utama era globalisasi pun hanya berlaku bagi segelintir orang saja. Sekarang ini tercatat baru lima persen penduduk dunia yang menggunakan Internet dan 88 persen di antaranya tinggal di negeri industri maju, sementara lebih dari satu milyar penduduk dunia sampai hari ini belum pernah melihat pesawat telepon dalam hidupnya. Globalisasi Sebagai Strategi Ada banyak mitos yang menyelubungi istilah globalisasi. “Rasanya sekarang ini semuanya bergantung pada tangan Adam Smith yang tak terlihat – semua ini ada di luar kontrol negeri mana pun, institusi apa pun,” kata Jeffrey Garten, pimpinan Yale School of Management. Dengan kata lain, globalisasi adalah proses alamiah yang tak dapat dihindari. Tapi kenyataannya tidak demikian. UNDP memperkirakan biaya menghapus kemiskinan di seluruh dunia secara efektif saat ini hanya satu persen dari pendapatan dunia sekarang. Dana yang diperlukan untuk memberantas tuntas kemiskinan di 20 negeri termiskin untuk selama-lamanya hanya sekitar US$5,5 milyar, sementara penduduk dunia menghabiskan US$7,2 milyar per bulan untuk membeli fast food. Jelas bahwa ketimpangan di dunia bukanlah perkara nasib atau proses alamiah yang tak terelakkan, tapi sebuah keputusan politik. Kapitalisme adalah sistem yang senantiasa berada dalam krisis dan menuntut para pemilik dagang, pengusaha dan pedagang serta birokrat – singkatnya elit penguasa sistem – terusmenerus merumuskan strategi baru untuk mengakhirinya. Prinsipnya sederhana, yakni menggarap dan mengubah segala menjadi ladang keuntungan, serta menaklukkan segala rintangan dan perlawanan yang membatasinya. Di abad-abad lalu sistem itu berkembang dengan merampas dan menguasai tanah serta sumber daya alam lainnya, lalu menjadikan para pemilik atau masyarakat yang mengontrolnya secara kolektif sebagai tenaga upahan. Di masa selanjutnya umat manusia menyaksikan semakin banyak bidang kehidupan yang dicaplok dan ditaklukkan oleh logika akumulasi, dengan menempatkan pasar dan prinsip jual-beli di dalamnya. Perusakan lingkungan, biaya rumah sakit yang mahal karena penghapusan subsidi sesungguhnya mengalir dari strategi yang sama, seperti halnya penguasa di zaman kolonial menggunakan uang dalam sistem pajak mereka. Semuanya memaksa orang menjual apa saja – termasuk tenaga kerja dan kadang tubuhnya – untuk dapat melanjutkan hidup. Ekspansi sistem ini bergerak terus menggerayangi kehidupan di segala bidang, termasuk pengetahuan dan kekayaan intelektual manusia. Sekarang ini sudah ada jutaan penemuan dan gagasan diberi hak paten yang membuat orang lain harus membayar untuk memanfaatkannya. Dan sekitar 90 persen hak paten itu dikuasai oleh perusahaan dan individu di negeri industri maju. Termasuk di dalamnya hak paten atas ribuan bibit tanaman dan teknologi pertanian yang sebelumnya adalah milik kolektif rakyat pedesaan di negeri berkembang. Semua strategi ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis oleh elit penguasa sistem dengan dukungan intelektual yang luar biasa. Bank Dunia sebagai salah satu lembaga penyusun strategi yang terpenting misalnya mempekerjakan sekitar 10.000 ahli dalam berbagai bidang yang beroperasi di seluruh dunia. Seperti istilah “menciptakan peradaban” dipakai dalam penaklukan berdarah di zaman kolonial, “globalisasi” adalah selubung ideologis dari strategi penaklukan di zaman modern, yang bahkan lebih berdarah. Pasar Bebas Versus Demokrasi Karl Polanyi dalam karya Great Transformation berbicara tentang gerak pasar yang secara inheren tak berbatas dan cenderung mengancam keselamatan manusia. Tapi saat menulis buku itu di 1944 ia menilai bangsa-bangsa tidak lagi menempatkan sistem ekonomi sebagai dasar gerak masyarakat, “dan keunggulan masyarakat atas sistem itu sudah dipastikan”. Ramalannya sungguh tepat, tapi penilaiannya keliru. Apa yang dikhawatirkannya justru menjadi kenyataan. Tepat pada tahun yang sama para pejabat pemerintah, bankir, pemilik industri dan pedagang dari Amerika Serikat dan Inggris berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire. Perang hampir usai dan kelas penguasa di kedua negara melihat ancaman naiknya gerakan rakyat dan Uni Soviet berkuasa di Eropa Barat. Untuk menghalangi kemungkinan itu maka dibentuk lembagalembaga internasional yang dapat memajukan doktrin akumulasi modal dan memperkuat sektor usaha, yang kini dikenal dengan sebutan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Sementara IMF menggunakan tabungannya untuk menalangi kerugian yang dilanda sebuah negara agar dapat melanjutkan perdagangan, Bank Dunia bertugas memberi pinjaman kepada pemerintah-pemerintah di dunia untuk membangun kembali jalan raya, rel kereta api, jembatan, pelabuhan dan semua infrastruktur yang tidak menghasilkan keuntungan. Maksudnya tidak lain agar pemerintah bersangkutan punya cukup uang sehingga tak perlu menyedot pajak terlalu besar dari pihak swasta. Dalam waktu singkat keduanya tumbuh menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia. Sebelum menerima pinjaman, negara yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti pedoman pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai “program penyesuaian struktural”. Program ini tujuannya tidak lain untuk menyesuaikan perekonomian sebuah negara dengan logika akumulasi modal dan memberi keleluasaan pihak swasta – terutama perusahaan transnasional – untuk menikmati keuntungan di sana. Semua keputusan dibuat oleh segelintir elit nasional yang bekerjasama dengan para pejabat lembagalembaga tersebut, kalau perlu dengan melangkahi lembaga perwakilan atau proses demokratik lainnya. Pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi tidak berhenti di sana. Dengan panji freedom and democracy para elit penguasa melancarkan perang, subversi dan teror untuk menegakkan perekonomian yang “bebas dan terbuka”: kudeta atas pemerintahan Soekarno, pembunuhan Patrice Lumumba di Kongo, penggulingan Salvador Allende di Chile dan Perang Vietnam. Di atas kemenangan yang berdarah kemudian ditempatkan diktator-diktator seperti Jenderal Manuel Noriega di Panama, Jenderal Augusto Pinochet di Chile, Jenderal Jorge Rafael Videla di Argentina, Mobutu Sese Seko di Kongo, dan George Papadopoulos di Yunani. Sasarannya adalah semua kekuatan, pemerintahan dan pemimpin yang berusaha menempuh jalan lain untuk membangun negerinya. Di samping menggulingkan pemerintahan, menculik dan membunuh pemimpin, elit penguasa ini juga tak segan merongrong pemerintahan yang tetap bersikeras memilih jalan pembangunan berbeda dengan bermacam cara, mulai dari mendirikan pemerintahan tandingan atau oposisi bersenjata seperti yang terjadi di Mozambique, Angola dan Nikaragua, sampai embargo total seperti yang dialami Kuba sampai sekarang. Di masa lalu, Amerika Serikat yang menjadi motor penggerak ekspansi ini menggunakan dalih Perang Dingin untuk membenarkan tindakannya. Tapi setelah perang ini berlalu, para penguasa dunia mencari sasaran-sasaran baru di Amerika Tengah, Selatan dan jazirah Arab. Kekerasan adalah bagian penting dari ekspansi kapitalisme atau globalisasi ini, seperti dikatakan Thomas Friedman, kolumnis harian New York Times, “tangan pasar yang tersembunyi takkan berjalan tanpa kepalan yang tersembunyi pula. McDonald takkan tumbuh subur tanpa McDonnell Douglas, pabrik pesawat tempur F-15.” Dan Amerika Serikat membuktikannya, dengan mengangkat mantan menteri pertahanan Robert McNamara menjadi presiden Bank Dunia selama tigabelas tahun. Kekerasan di zaman ini bukan hanya pelengkap untuk mencapai tujuan, tapi juga menjadi bisnis tersendiri. Setiap tahun para penguasa di dunia menghabiskan dana US$600 milyar untuk melengkapi persenjataan, peralatan dan pasukan. Di negara-negara penguasa dunia, industri senjata adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan memberi pendapatan besar. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Dengan mengirim senjata, melatih personel, dan menjual peralatan, negara industri seperti Amerika Serikat dapat mengeruk keuntungan besar sekaligus memperkuat posisinya sebagai pembina, pelatih dan penasehat pasukan militer di seluruh dunia. Dan semua itu, tentu saja, atas nama kebebasan dan demokrasi. Neoliberalisme Menoreh Nasib Dunia Para pendukung sistem bukan tidak sadar bahwa banyak orang menderita, mengkritik dan melawan apa yang mereka ciptakan. Tahun 1980-an, Margaret Thatcher yang baru diangkat menjadi perdana menteri Inggris menyatakan bahwa dunia “tidak punya pilihan lain.” Apa yang dimiliki sekarang jauh lebih baik dari apa yang mungkin diberikan oleh pemikiran dan sistem lain di dunia. Keruntuhan Uni Soviet pada 1989 memperkuat keyakinan itu, dan kaum intelektual pun ramai-ramai menghujat semua sistem alternatif sebagai barang rongsokan yang ketinggalan zaman. Seringkali tidak disadari bahwa globalisasi dan pemikiran para elit penguasa berdiri di atas doktrin-doktrin yang jauh lebih tua dan usang dibandingkan alternatif yang dihujat. Sumber utamanya adalah pemikiran liberal dari tiga abad lalu yang mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian sebuah bangsa. Persaingan adalah mesin pendorong untuk menciptakan manusia dan sistem yang unggul. Paham ini berkembang pesat menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa yang merambah ke seluruh penjuru dunia. Gerak laju ini terhenti sesaat ketika terjadi Depresi Besar 1930-an. Di tengah kesulitan hidup yang luar biasa, John Maynard Keynes tampil dengan konsep bahwa kapitalisme takkan bertahan jika pemerintah dan bank-bank sentral tidak turun tangan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kepentingan bersama. Tapi krisis besar di 1970-an membuat para penguasa dunia kembali beralih pada liberalisme, sekali ini dengan gaya baru, sehingga dikenal dengan sebutan neoliberalisme. Seperti liberalisme tiga abad lalu, neoliberalisme juga menghendaki tegaknya kekuasaan pasar dan “membebaskan” arus modal dan barang dari campur tangan negara. Tapi seiring dengan semakin banyaknya bidang kehidupan yang disedot ke dalam logika akumulasi modal, maka tuntutan pun semakin meluas, mulai dari memotong anggaran bagi pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, menghapus pelayanan sosial bagi orang miskin, sampai swastanisasi perusahaan negara. Doktrin itu dilancarkan dengan gencar, dan hampir selalu dengan paksaan. Setelah Allende digulingkan pada 1973 dengan bantuan penuh dari CIA, Milton Friedman dari Universitas Chicago menjadi penasehat ekonomi Chile. Ia bekerjasama dengan kediktatoran Pinochet untuk merombak seluruh konsep pemerintahan rakyat dan economia popular yang diterapkan sebelumnya, dan menjadikan negeri itu laboratorium pertama bagi eksperimen neoliberalisme. Dalam duapuluh tahun selanjutnya hampir seluruh Amerika Latin dan Tengah dikuasai oleh rezim-rezim neoliberal. Hasilnya pun segera nampak. Di Meksiko tingkat upah menurun drastis sekitar 40% sementara biaya hidup melonjak sampai 80%. Sekitar 20.000 usaha kecil dan menengah gulung tikar sementara lebih dari seribu perusahaan negara dikuasai oleh swasta. Seperti dikatakan Subcommandante Marcos, salah satu pimpinan gerakan Zapatista di hutan Chiapas, Meksiko, bahwa neoliberalisme ingin mengubah dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan raksasa, di mana para penguasa membeli segalanya, mulai dari orang Indian, perempuan, tenaga buruh dan juga kedaulatan negara. Rangkaian “keberhasilan” inilah yang membawa para penguasa negara industri maju mencapai kesepakatan Washington pada 1980-an, yang mendesak negara-negara lain di dunia memeluk ekonomi terbuka dan perdagangan bebas. Selanjutnya bermacam lembaga, forum dan kesepakatan baru terus-menerus dibuat untuk memperluas kekuasaan, seperti AFTA di Asia Tenggara, NAFTA di Amerika Utara dan Meksiko dan APEC untuk seluruh wilayah Asia-Pasifik. Doktrin neoliberal menyebutnya sebagai lembaga kerjasama ekonomi, tapi kenyataannya seluruh agenda diajukan oleh para pemodal dan birokrat pendukungnya, dan keputusankeputusannya tidak pernah mengingkari kepentingan mereka. Masalah sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup tentu saja tidak masuk dalam agenda karena hanya akan mengurangi kelancaran menghisap keuntungan. Sementara itu berbagai skema dikeluarkan untuk menyerahkan hajat hidup orang banyak ke tangan segelintir orang saja. Kesepakatan Multilateral mengenai Investasi (MAI) misalnya mengharuskan pemerintah anggotanya membayar kerugian yang diderita perusahaan jika mereka mengubah kebijakan publiknya. Tidak ada lagi perlindungan dan kontrol pemerintah terhadap kehidupan ekonomi karena dalam doktrin perdagangan bebas dinilai tidak efektif dan menciptakan “distorsi pasar”. Dengan kata lain, tidak ada kontrol rakyat atau demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, dan kemungkinan memilih jalan hidup berbeda pun semakin kecil. Setidaknya untuk sementara waktu… ●
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
●
Globalisasi di Internet
●
Dalam Bahasa Mereka Sendiri
Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Globalisasi Perlawanan Tim Media Kerja Budaya " Satu-satunya yang pantas menjadi global adalah perlawanan,” demikian pengarang Arundhati Roy dari India, menyambut gerakan anti-globalisasi yang semakin meluas. Hampir setiap pertemuan pemimpin bisnis, kepala negara dan lembaga keuangan internasional dihadang oleh kelompok masyarakat yang bergabung dengan aktivis dari seluruh penjuru dunia. Pada November 1999 di Seattle, sekitar 30.000 aktivis bergabung dalam aksi protes besar menentang pertemuan WTO. Dari kampanye di media massa dan demonstrasi yang kecil dan sporadis, gerakan anti-globalisasi mulai menerapkan taktik baru: menghalangi jalannya pertemuan internasional yang mereka dakwa akan semakin menyengsarakan dunia. Media komersial menyambut gelombang anti-protes itu dengan nada miring. Sasaran utamanya tentu adalah aksi perusakan yang dilakukan oleh berbagai kelompok, untuk memperlihatkan bahwa aksi anti-globalisasi sama dengan kerusuhan dan karena itu harus ditindak tegas. Para birokrat dan pemimpin bisnis pun menimpali. “Anak-anak itu tidak tahu apa pun tentang globalisasi. Mereka hanya kumpulan orang frustrasi yang berpikir dengan aksi semacam itu dunia akan menjadi lebih baik.” Tentu tidak dijelaskan bahwa frustrasi itu bersumber dari kesengsaraan yang mulai dirasakan oleh kaum muda, terutama rakyat pekerja, negara industri maju. Selama sepuluh tahun terakhir terjadi pemecatan massal, pengurangan upah, pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan, dan berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Dalam tiga tahun terakhir semakin banyak orang dan kelompok yang terlibat dalam gerakan itu, termasuk di kota-kota yang dikenal tenang dan damai. Sebelum mobilisasi dilakukan di seluruh pelosok kota, mulai dari tembok rumah sampai meja restoran diberi tanda seperti S-26 atau A-16 yang menandakan bulan dan tanggal, sebagai undangan aksi kepada masyarakat. Puluhan ribu orang kemudian bergabung pada hari yang ditetapkan untuk melancarkan aksi protes, yang kadang diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan. Bentrokan semakin sering terjadi karena para aktivis biasanya memasang blokade untuk menghalangi para pejabat dan pengusaha menghadiri pertemuan. Di Genoa, bulan April lalu, sekitar 300.000 aktivis dari seluruh dunia berkumpul untuk menghalangi pertemuan negara industri maju yang tergabung dalam kelompok G-8. Polisi bereaksi keras, menyerang para demonstran dan membunuh seorang aktivis asal Italia, Carlo Giuliani. Seorang carabineri menembaknya sampai jatuh, lalu tubuhnya dilindas dua kali sehingga meninggal seketika. Kekerasan tidak berhenti di sana. Puluhan aktivis yang ditahan di penjara Bolzaneto menjadi bulan-bulanan para penjaga, tentara dan polisi. Pekerja media dan aktivis yang memegang kamera dikejar-kejar, dan pusat komunikasi dan media yang didirikan para aktivis di sebuah kompleks sekolah dihancurkan. “Pembantaian Genoa” demikian para aktivis menyebut kejadian itu, justru memicu protes di seluruh penjuru dunia. Aksi solidaritas terjadi di berbagai negara dan menegaskan sikap para aktivis menentang globalisasi dan aparat kekerasan yang melindunginya. Arus Balik dari Selatan Pada 1 Januari 1994, bertepatan dengan berlakunya Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), terjadi pemberontakan di propinsi Chiapas, Meksiko bagian selatan. Sekelompok petani Indian yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) menduduki sebuah kota dan menyerukan perlawanan umum. Tapi berbeda dengan gerakan perlawanan bersenjata di Amerika Latin pada tahun 1970-an, kelompok ini tidak bertujuan merebut kekuasaan dengan kekerasan. Mereka hanya berseru kepada rakyat dunia untuk membangun jaringan antarbenua untuk melawan neoliberalisme. Di tahun-tahun selanjutnya, gerakan Zapatista menyelenggarakan berbagai pertemuan besar yang melibatkan ribuan aktivis serikat buruh, organisasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kelompok perempuan, perhimpunan mahasiswa dan banyak lainnya. Tujuan pertemuan ini pun bukan untuk menciptakan organisasi baru, tapi untuk membahas strategi bersama bagi bermacam kelompok berbeda. Dalam pertemuan kedua di bulan Agustus 1997, sejumlah aktivis berkumpul untuk merencanakan aksi protes menentang WTO yang menjadi simbol dan alat utama globalisasi kesengsaraan. Untuk mengatur kegiatan dan menghimpun kekuatan mereka membentuk Peoples’ Global Action Against “Free” Trade and the WTO yang disingkat PGA. Aksi pertama berlangsung akhir Mei 1998 di Jenewa untuk menentang konperensi WTO tingkat menteri yang kedua. Dan bersamaan dengan itu di 28 negara, ratusan organisasi melancarkan aksi-aksi protes yang melibatkan jutaan orang. Di jalan-jalan kota Hyderabad, India, setengah juta orang turun ke jalan menentang konperensi itu, sementara di Brasil 50.000 orang, terutama kaum tani tak bertanah, melancarkan aksi serupa. Tahun berikutnya gelombang protes pun semakin meningkat dan meluas. Pada 18 Juni PGA melancarkan aksi global menentang pusatpusat keuangan dunia. Sekitar 100 kota di 40 negara dilanda aksi protes, mulai dari Australia sampai Zimbabwe, Swedia sampai Korea Selatan, Chile dan Republik Ceko. Energi perlawanan yang mulai meluas kemudian mengalir ke negara-negara industri maju, pusat berkumpulnya para penguasa dunia untuk menentukan kebijakan yang menyengsarakan mayoritas penduduk dunia. Tujuannya bukan untuk menghentikan globalisasi itu sendiri, melainkan mengubah prinsip dan cara yang di satu sisi memperkuat dan memperkaya perusahaan-perusahaan raksasa dan di sisi lain melemahkan rakyat dunia, dan membuat mereka semakin miskin. Karena itu sasarannya bukan hanya satu-dua kebijakan yang dianggap merugikan, melainkan seluruh lembaga yang merancang sistem tersebut, terutama IMF, Bank Dunia dan WTO. Gelombang perlawanan ini tidak berhenti pada aksi-aksi protes dan bicara saja, sekalipun media komersial memberi kesan demikian. Hampir semua organisasi yang terlibat di dalamnya memiliki pekerjaan nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di berbagai bidang, mulai dari pertanian, penanganan anak jalanan sampai perlindungan perempuan dari kekerasan. Di Brasil salah satu motor penggerak perlawanan adalah MST, yang menghimpun petani untuk menduduki tanah-tanah tak terpakai di wilayah selatan dan mengembangkan program kesejahteraan secara demokratik (ulasan tentang MST dimuat di MKB edisi 05/2001) Sementara di Filipina ada kelompok Gabriela, yang membela hak-hak perempuan dan menentang berbagai tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan. Dalam perkembangannya semakin banyak kelompok masyarakat yang terlibat, mulai dari perhimpunan warga di tingkat desa, organisasi penulis, persatuan guru, serikat buruh, lembaga bantuan hukum, perkumpulan ibu rumah tangga, komunitas kesenian, organisasi lingkungan hidup, veteran perang, penjaga toko sampai kaum ulama. Keragaman dan tidak adanya satu pusat, justru menjadi kekuatan utama. Mengatasi Perbedaan Membangun gerakan berskala global tentu punya beragam masalah. Dalam aksi-aksi protes yang terakhir semakin banyak aktivis yang menyadari perlunya merumuskan tujuan yang lebih jelas, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Perlawanan yang mengandalkan “musuh bersama” (globalisasi neoliberal) memang bisa memobilisasi kekuatan dengan cepat, tapi tidak cukup untuk membuat perubahan berarti. Di samping itu tuntutan-tuntutan jangka pendek juga dirasakan perlu, untuk merebut “kemenangan kecil” dari tangan penguasa dunia. Untuk itu jaringan aktivis dari berbagai belahan dunia mulai menyelenggarakan pertemuan dan konperensi yang membahas berbagai aspek globalisasi dan perlawanan terhadapnya. Di Porto Alegre, Brasil bagian selatan, ribuan aktivis berkumpul dalam Forum Sosial Dunia bulan Januari lalu, bertepatan dengan penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia. Sementara itu di bulan Juni berlangsung pertemuan Liga Internasional Perjuangan Rakyat yang dihadiri oleh bermacam organisasi dari lima benua. Walau tidak semuanya menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai nasib gerakan di masa mendatang, forum seperti ini sangat berguna sebagai tempat mempertemukan berbagai kecenderungan yang ada. Masalah lain yang sekarang menjadi perdebatan besar adalah penggunaan kekerasan, yang dipicu oleh bentrokan berulangkali dengan aparat keamanan dalam aksi-aksi protes di Eropa dan Amerika Serikat. Para pendukung gerakan non-kekerasan menganggap serangan terhadap toko-toko dan petugas tidak dapat dibenarkan, dan akan merugikan gerakan secara keseluruhan. Sementara di pihak lain dikatakan bahwa hanya dengan kekerasan media komersial akan memberi perhatian, yang menjadi jalan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Perdebatan berlangsung sengit dan menajam pada masalah kepemimpinan dalam gerakan. Tapi seiring berkembangnya gerakan protes, masing-masing pihak mulai melihat kelebihan dan kelemahan setiap posisi. Di satu pihak para penganjur kekerasan semakin mengikatkan diri pada gerakan dan menghindari bentrokan, sebaliknya aktivis lainnya bisa memahami aksi pelemparan bangunan tertentu yang dianggap sebagai simbol globalisasi neoliberal. Gelombang protes terus berlanjut, begitu pula dengan pemikiran dan praktek pembebasan di kampung dan kota berbagai belahan dunia. Banyak juga yang melakukannya karena tidak ada pilihan lain. Mengakhiri globalisasi kesengsaraan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
●
Indymedia, Membangun Media Gerakan
●
2000, Tahun Perlawanan
●
Mengadili Globalisasi
Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Jalan Neoliberal Bagi Indonesia Tim Media Kerja Budaya Hindia Belanda adalah gabus tempat Belanda mengapung, bunyi slogan penguasa kolonial di akhir abad ke-19. Perkebunan swasta dan pemerintah kolonial yang terbentang dari Deli sampai Banyuwangi menghasilkan ratusan juta gulden yang mengalir masuk ke kantong para pemiliknya di negara induk. Hasil kerja kuli kontrak dan buruh perkebunan yang hidup dalam kondisi seperti budak inilah yang menjadi dasar bagi tumbuhnya imperium. Seperti halnya bekas tanah jajahan yang lain, pada 1945 Indonesia meraih kemerdekaan dalam keadaan terkuras. Para pejabat republik harus bergantian memakai kendaraan yang ditinggalkan Belanda maupun Jepang, sementara departemen-departemen pemerintah harus berbagi ruang dan perabotan yang serba terbatas di bangunan yang sama. Perang selama empat tahun membuat kehidupan ekonomi porak-poranda. Di banyak tempat rakyat bergerak mengambil kembali tanah dan milik mereka yang dirampas penguasa kolonial. Tapi gerakan merebut kembali kehidupan ini terhenti ketika perundingan terakhir antara pejabat republik dengan penguasa kolonial – di bawah pengawasan Amerika Serikat – memutuskan semua perusahaan dan perkebunan harus dikembalikan kepada pemilik lamanya. Bukan itu saja. Sementara Belanda mendapat berkah bantuan Marshall Plan sebesar US$359 juta dan ratusan juta lainnya dalam bentuk peralatan militer dan kredit, Amerika Serikat menekan pemerintah Indonesia untuk mengambilalih hutang negara Hindia Belanda sebesar US $1,13 milyar. Ironisnya sekitar US$800 juta hutang itu adalah biaya perang mencegah kemerdekaan Indonesia. Selama 20 tahun negeri yang baru merdeka ini harus membangun kembali perekonomian, di bawah tekanan negara industri maju yang ingin segera mencaplok kembali apa yang direbut oleh dekolonisasi, subversi dan pemberontakan yang didukung oleh Amerika Serikat, serta kemiskinan merajalela akibat struktur kolonialisme yang tidak dirombak. Korupsi, Kekerasan dan Neoliberalisme 14 Februari 1966. Presiden Soekarno dengan sisa-sisa kekuatan yang terus digerogoti mengeluarkan UU No. 1/1966: Indonesia keluar dari IMF dan Bank Dunia yang “ternyata merupakan konsentrasi kaum neo-kolonialisme dan imperialis yang mengutamakan kepentingan golongannya daripada anggota-anggotanya termasuk negara-negara yang baru merdeka dan belum berkembang ekonominya.” Di tengah krisis yang parah, langkah itu tidak banyak artinya. Kekuasaannya tinggal menghitung hari. Para petinggi militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, dengan dukungan negara industri maju, lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan raksasa, sudah siap merangsak untuk merebut kekuasaan itu dari tangannya. Setengah sampai satu juta orang yang dituduh PKI atau terlibat dengan satu lain cara dengan partai tersebut dibunuh, sementara ratusan ribu lainnya disekap dalam kamp-kamp di seluruh Indonesia. Buku sejarah resmi dan para pemenang merayakannya sebagai tindakan heroik “menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman komunis”. Banyak korban dan keluarga mereka sebenarnya tidak pernah berurusan dengan komunisme maupun berencana merebut kekuasaan dari tangan Soekarno seperti yang dituduhkan penguasa. Dan bagi mereka sejarah punya makna berbeda. Diperkirakan lebih dari dua juta orang kehilangan tanah dan milik mereka dalam berbagai operasi penumpasan, dan harus hidup sebagai pengungsi di tanah air sendiri. Sebagian tewas dibunuh, sementara lainnya dijadikan tenaga kerja paksa oleh penguasa militer di pertambangan dan perkebunan. Keluarga tercerai-berai, memisahkan anak-anak selamanya dari orang tua mereka. Cap “komunis” yang ditetapkan penguasa dan pengikutnya adalah hukuman mati secara sosial. Mereka yang dikenai cap – termasuk ribuan ahli fisika, matematika, filologi, sastrawan dan dokter bedah – hanya boleh menjual tenaga sebagai kuli bangunan untuk menyambung hidup. Praktek yang sama dengan cap berbeda – seperti Islam radikal, gerombolan pengacau keamanan atau separatis – terus digunakan untuk memaksa semua orang membanting harga diri dan tenaganya, dan berdisiplin dalam Orde Baru. Sementara kekuasaan politik dan ekonomi terpusat di tangan segelintir keluarga elit Orde Baru, jutaan orang terjerembab dalam kantong-kantong kemiskinan yang semakin lebar dan berkembang-biak, melampaui apa yang pernah mereka alami di zaman kolonial. Dengan petunjuk dari para ekonom dan pejabat Orde Baru serta lembaga keuangan internasional dan negara industri maju, pemerintahan Soeharto menghapus semua hambatan bagi modal internasional untuk menguasai sumber daya alam dan tenaga manusia di Indonesia. Awal tahun 1971 sebuah kesepakatan dibuat untuk membagi-bagi mineral Indonesia kepada perusahaan asing seperti Caltex, Frontier, IIAPCO-Sinclair dan Gulf-Western. Empat tahun sebelumnya, Soeharto terlebih dahulu menyerahkan 1,2 juta hektar tanah di Papua kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto. Aturan fiskal disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan ini mengalirkan pendapatannya langsung ke pusatpusat kemakmuran di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa. Boom minyak yang sempat memberi keleluasaan bagi pemerintahan Soeharto pada tahun 1970an tidak berlangsung lama, dan seperti kebanyakan negeri Dunia Ketiga lainnya, Indonesia mulai mengembangkan “perekonomian terbuka”. Lahan-lahan baru dibuka untuk eksploitasi sumber daya alam dan pabrik manufaktur ringan. IMF dan Bank Dunia pun memuji angkaangka pertumbuhan ekonomi, dan rezim Soeharto pun menikmati kucuran kredit, penanaman modal langsung, serta perlindungan politik bagi apa pun yang mereka lakukan di dalam negeri. Pada saat bersamaan, proses industrialisasi ini menyingkirkan jutaan orang lain dari tanah mereka. Banyak di antaranya yang lari ke kota pada usia sangat muda untuk menjual tenaga, sebagai buruh pabrik, kuli angkut maupun pekerja seks. Mereka bekerja delapan sampai duabelas jam, di bawah disiplin keras para pengusaha dan manajer, dengan upah yang hanya cukup untuk makan, sedikit pakaian dan menyewa sebuah kamar kos bersama tiga atau empat rekan lainnya. Salah satu hasil pembangunan gaya Orde Baru adalah korupsi yang meresap ke dalam struktur kekuasaan, dari tingkat kelurahan sampai istana presiden. Para pejabat tinggi maupun rendah menetapkan bermacam pungutan untuk segala hal, mulai dari investasi dan perdagangan sampai mendaftarkan anak ke sekolah dan mengurus KTP. Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) disebutkan antara 20-30% dana hutang luar negeri yang disalurkan melalui Bank Dunia mengalir masuk ke kantong para pejabat pemerintah untuk memperkaya diri dan memperluas pengaruh politiknya. Di Timor Lorosae pada 1999 ditemukan bukti-bukti bahwa sebagian hasil hutang itu juga digunakan untuk membiayai kegiatan milisi pro-integrasi yang bersama TNI kemudian menghancurkan wilayah itu. Krisis dan Tegaknya Neoliberalisme Pertengahan tahun 1990-an para penguasa dunia menyambut Indonesia sebagai “keajaiban ekonomi baru”, menyusul Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Sampai awal tahun 1997 Bank Dunia pun menilai masa depan perekonomian sangat cerah. Tapi krisis finansial mengubah segalanya. Seluruh borok pembangunan yang bersandar pada hutang luar negeri dan ekspansi kapitalisme di segala pelosok dan bidang kehidupan mulai memperlihatkan warna asli yang suram. Pemerintahan Soeharto masih berusaha menolak dan menghindari konsekuensi dengan berbagai cara, dan semakin keras kepala. Ia menolak agenda liberalisasi IMF untuk melindungi kepentingan keluarganya, menculik dan membunuh sejumlah aktivis mahasiswa dan menempatkan keluarga serta para kroni di posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Persekutuan aneh terbentuk antara para penganjur liberalisasi dan aktivis yang menentang kediktatoran di bawah payung “reformasi”. Ketika Soeharto mengundurkan diri, arus yang pertama segera mengambil tempat di depan. Kurang dari dua bulan sesudahnya IMF mendesak Habibie untuk mengambilalih tanggung jawab membayar hutang yang ditinggalkan rezim Soeharto. Kesepakatan dibuat dan angka-angka hutang pun semakin membengkak. Dalam waktu tiga tahun setelah krisis hutang luar negeri Indoneisa mencapai US$144 milyar, dengan komposisi 60% hutang pemerintah dan 40% hutang swasta. Tapi sebagian besar hutang pemerintah pun dipakai untuk menalangi hutang dan menyuntikkan modal kepada bank-bank swasta yang bangkrut. Para pejabat IMF dan Bank Dunia, serta kaum intelektual pendukung neoliberalisme di Indonesia, mengkritik sistem perbankan Indonesia yang rapuh, padahal sepuluh tahun sebelumnya mendorong program deregulasi perbankan tanpa pengawasan dari pemerintah. Amerika Serikat yang selama 32 tahun mendukung kekuasaan Soeharto dalam waktu singkat berubah mengungkap kebobrokan, korupsi dan penyelewengan, dengan menuduh “kebudayaan Asia” sebagai biang keladinya. Kredit milyaran dolar yang tidak dapat dibayar kembali dikutuk sebagai biang penyakit, padahal sebelumnya semua orang memujinya sebagai energi untuk menggerakkan roda pembangunan. Kaum elit sibuk berdebat dan rakyat lagi yang jadi korbannya. Pemecatan massal terjadi di manamana dan kekerasan meningkat akibat frustrasi yang mendalam. Dipicu oleh perebutan kuasa di kalangan elit, dalam waktu dua tahun Indonesia diubah menjadi medan pertempuran yang berakibat 10.000 orang tewas dan memaksa lebih dari satu setengah juta penduduk hidup sebagai pengungsi. Sementara pemotongan subsidi untuk kesehatan dan pendidikan yang diperintahkan IMF membuat jutaan anak terancam kematian dan tidak akan berkembang secara kultural. Reformasi yang sebelumnya dibayangkan sebagai energi pembebasan, menjadi jalan penaklukan seluruh negeri di bawah kekuasaan neoliberalisme. Hutang adalah alat utama menekan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan tata ekonomi neoliberal. Milyaran dolar yang dipinjam rezim Soeharto dan kroninya dari IMF, Bank Dunia dan negara industri maju untuk menyingkirkan rakyat, kini harus dibayar kembali oleh para korban. Tuntutan agar hutang di masa lalu dihapuskan, tidak digubris. Menurut lembagalembaga keuangan internasional itu, “Indonesia bukanlah negara miskin, dan mampu membayar kembali seluruh hutangnya”. Dan untuk itu mereka pun menyiapkan “paket reformasi” perekonomian yang mengharuskan pemerintah membuka semua sektor kehidupan menjadi lahan cari untung, dan menyedot Indonesia secara bulat-utuh ke dalam arus yang mengalir ke pusat-pusat kemakmuran di negara industri maju. Tiga kali pergantian pemerintah tidak mengubah keadaan ini, malah sebagian menilainya semakin parah saja. Selama tiga tahun terakhir kita menyaksikan tarik-ulur pemerintah dan IMF dalam merumuskan letter of intent (LOI), yang memuat nasib perekonomian Indonesia di masa mendatang, dan tak satu pun kemenangan bagi rakyat yang berhasil dicatat. Lahir Bukan untuk Menjadi Budak Krisis, kekerasan dan sistem politik yang seperti selalu berujung di jalan buntu, mendesak orang untuk berpikir sendiri tentang cara mempertahankan hidup. Di pedesaan ratusan ribu petani bergerak mengambilalih tanah yang dirampas semasa Orde Baru. Di Rambang lubai, Palembang, riban petani menuntut tanah yang dirampas dengan kekerasan oleh PT Musi Hutan Persada milik PT Barito Pasifik. Sementara di Lombok Tengah rakyat menduduki kantor PT Pengembangan Pariwisata Lombok dan menuntut 1.250 hektar tanah mereka dikembalikan. Proyek pariwisata yang dikelola oleh perusahaan Indra Rukmana dan Pieter Gontha dianggap hanya menciptakan kesenjangan yang makin lebar. Elit lokal yang semasa Orde Baru menduduki tempat terhormat pun tidak didengar, karena sudah terlalu lama bersekongkol dengan perusahaan swasta. Di sektor industri buruh memprotes berbagai kebijakan dan praktek yang merugikan, mulai dari penetapan upah minimum yang rendah sampai pada penggelapan dana Jamsostek, dan memprotes pemecatan terhadap rekan kerja dengan alasan “perusahaan merugi”. Di pabrik dan tempat kerja lainnya buruh membentuk serikat-serikat untuk membela kepentingannya. Gerakan perempuan menyambut krisis dengan aksi-aksi protes menentang kenaikan harga, pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan yang membuat hidup semakin sengsara. Perlawanan kerap dihadapi dengan kekerasan dan provokasi untuk meledakkan amarah menjadi kerusuhan rasial, etnik atau agama. Ribuan orang terjerembab ke dalam perangkap, mengobarkan permusuhan kepada sesama dan menjadi budak mesin penghancuran. Segelintir elit terus dibiarkan mengambil keputusan besar dan menyengsarakan hidup banyak orang. Mungkin kita perlu sejumlah besar orang yang melakukan hal-hal kecil untuk mengubah semua ini. Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Institut Sekulir: Membangun Gereja Kaum Miskin Mateus Gonçalves Maria Lourdes Martins, seorang suster muda yang baru menyele saikan kuliah di STFK Prandyaidya, Yogyakarta, kembali ke kampung halamannya, Timor Lorosae. Ia bertekad mewujudkan gagasan yang dikembangkannya selama kuliah, untuk membangun lembaga yang dapat mengabdi pada masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat, khsusnya mereka yang paling menderita di daerah-daerah terpencil dan terlupakan. Pada 1990 ia membentuk Institut Sekulir di Dare, sekitar sepuluh kilometer di selatan kota Dili, dan menghimpun sejumlah anggota yang kemudian hidup bersama masyarakat dan bekerja di sana. Selain membantu dan mendampingi dalam penghayatan dan pengembangan iman, lembaga ini juga bergerak mengembangkan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat agar mereka bisa mencapai taraf hidup yang layak. Konsepnya sederhana, menyelamatkan dunia dengan kekuatan dunia dan melalui kehidupan dunia sendiri. Di zaman pendudukan Indonesia, kegiatan seperti ini tentu dinilai aneh, bahkan oleh gereja Katolik sendiri. Tidak sedikit pejabat gereja yang berkomentar “miring” karena menganggap bahwa lembaga ini seperti mau menjadi gereja baru yang berlawanan dengan tradisi gereja di Timor Lorosae. Tapi bagi Mana Lou, (Tetun, Mana = Kakak), begitu ia biasa dipanggil, persoalannya adalah bagaimana mengembangkan pemikiran baru tentang apa artinya menjadi gereja. Mana Lou jarang berfilsafat atau bermain-main dengan konsep tentang kegiatannya. Baginya sederhana saja. Unsur paling penting adalah persaudaraan dan persekutuan, pembagian kerja merata sehingga semua dapat mengambil bagian di dalamnya. Untuk itu dibentuk kelompokkelompok yang dibantu oleh seorang pembimbing. Tugasnya bukanlah memahami Injil di tingkat wacana dan menghapal isinya, tapi bagaimana menghayati isinya melalui kerja bersama kaum miskin yang dipinggirkan oleh “pembangunan”. Di Dare saat ini Institut Sekulir menampung anak-anak yang kehilangan orang tuanya setelah penghancuran Timor Lorosae pada 1999. Diskusi adalah hal penting dalam perumusan dan pelaksanaan program institut. Para suster yang dididik Mana Lou tidak datang untuk berkotbah, tapi untuk berdiskusi mengenai segala hal menyangkut keimanan maupun peran gereja d Timor Lorosae saat ini. Kebudayaan menjadi sangat penting, karena dengan cara itulah gereja dapat berkomunikasi, tidak sekadar menyampaikan pesan-pesan dari luar kepada komunitas yang bersangkutan. Dari diskusidiskusi itulah setiap kelompok menentukan program kerjanya, mulai dari penyediaan bibit tanaman yang diperlukan petani sampai pada pengembangan usaha. Para anggota institut hidup layaknya masyarakat umum. Mereka tidak menggunakan jubah seperti biasa dikenakan suster dan pekerja gereja lainnya, karena mengemban konsep “sekuliritas” (ke-duniawi-an). Seringkali para pekerja yang “sekulir” ini dianggap sebagai pembantu yang hanya melengkapi kegiatan “resmi” gereja, tapi justru Mana Lou menekankan bahwa gerakan sekulir ini adalah panggilan khas dengan kharisma tersendiri. Mereka yang terlibat diharapkan hidup seperti biasa dalam dunia, tapi tanpa terikat dengan hal-hal yang duniawi. Dengan begini orang dapat menghayati kemiskinan, sebagai orang yang sungguhsungguh tidak punya sesuatu kecuali hati nurani untuk melayani sesama. “Berada di dunia, bukan berarti kita mencari untung dari dunia atau mencari pegangan serta tempat tinggal tetap di dunia,” kata Mana Lou. Berpijak di Basis Kegiatan Institut Sekulir dimulai dan bermuara di basis-basis. Tidak ada keinginan untuk ikut bermain atau bersaing dalam birokrasi gereja. Bekerja di basis adalah prinsip, dan setiap anggota yang ingin terlibat bertolak dari sana. Di zaman pendudukan Indonesia, kegiatan Mana Lou masih sangat terbatas, karena pembatasan gerak oleh TNI. Walau begitu kontak dan hubungan dengan komunitas basis sudah mulai dijalin, dan berkembang setelah rakyat Timor Lorosae menentukan pilihannya dalam referendum pada 1999. Di Liquiça, sekitar 30 kilometer sebelah barat kota Dili, Institut Sekulir terlibat dalam kegiatan menjahit untuk kelompok perempuan, dan juga berdiskusi tentang perawatan anak, baik secara fisik maupun rohani. Karena keterlibatannya yang luas dan kongkret inilah, Mana Lou juga sering diminta untuk menangani pemulangan pengungsi, mengusahakan rekonsiliasi di antara warga dan membangun perdamaian bersama-sama. Begitu pula dalam kegiatan pemilihan umum yang baru lalu, Institut Sekulir memberikan pendidikan mengenai konstitusi dan berdiskusi tentang bermacam hal, mulai dari posisi perempuan, anak dan keluarga dalam konstitusi sampai sistem kenegaraan, ekonomi dan hukum. Pekerjaan di basis bermula dari diskusi. Bagi Mana Lou rakyat menderita karena selalu dituntut untuk mendengarkan penguasa. Tidak pernah penguasa yang mendengar dan rakyat berbicara. Salah satu prinsip yang berusaha ditegakkan adalah memberi kesempatan kepada semua orang, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, untuk berbicara dan duduk merundingkan masalah bersama-sama. Bagi masyarakat bekas jajahan seperti Timor Lorosae, semua ini adalah langkah awal bagi pembebasan yang lebih luas. Hanya dengan begini masalah-masalah yang dihadapi rakyat dalam keseharian bisa terangkat, dibicarakan dan dicari pemecahannya. “Tidak mungkin pemerintah atau orang-orang besar itu bisa menyelesaikan masalah, kalau mengenali masalahnya saja tidak mau,” ujar Mana Lou. Pembebasan bagi Institut Sekulir dimulai dari memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang untuk menghadapi masalah mereka dengan caranya sendiri. Untuk itu Institut sering mengajak anak-anak untuk menggali kebudayaannya sendiri, bernyanyi, menari dan menampilkan kreasi mereka, agar tidak terus dihinggapi trauma kekerasan dan larut dalam kesedihan terus-menerus. Kegembiraan dan kesenangan pada hidup adalah langkah pertama untuk bebas. Untuk memperdalam pengetahuan anggota dan menambah kekuatan basis, Institut bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak memberdayakan masyarakat, seperti Forum Komunikasi Perempuan Loro Sae (Fokupers) untuk masalah-masalah perempuan, Yayasan HAK dan perhimpunan pengacara untuk bidang hak asasi manusia. Dari diskusi dengan bermacam kalangan, Institut dapat memperkaya pengetahuan sekaligus mengajak semakin banyak orang terlibat dalam penguatan gerakan tingkat basis ini. Tapi pelajaran paling berharga selalu didapat justru dari masyarakat “dampingan”. Sejak awal Mana Lou berpikir tentang gereja yang kontekstual, yang membiarkan masyarakat bebas mengembangkan kepercayaan lama pra-gereja. Baginya, Portugis menjadikan gereja sebagai alat untuk memuluskan penjajahan, lalu membunuh segala kepercayaan yang ada sebelumnya. Padahal kekuatan spiritual atau keyakinan seseorang sangat bergantung pada cara seseorang itu melakukannya. Gereja adalah salah satu tradisi saja, dan norma-norma (Eropa) yang ditanamkan di dalamnya belum tentu sejalan. Gereja menurutnya, harus memberi kesempatan orang mencari jalan keimanannya sendiri, bukan hanya dengan mengekor pada tradisi mapan yang datang dari luar. Paksaan adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, bukan hanya karena melanggar hak seseorang, tapi juga karena tidak akan benar-benar meresap ke dalam hati. Dengan pendekatan seperti ini Institut Sekulir diterima secara luas oleh masyarakat, dan saat ini sudah mengembangkan kegiatannya di distrik-distrik lain, seperti Liquiça, Aileu dan Same di bagian barat dan tengah Timor Lorosae. Religiositas Rakyat Para pekerja institut memahami bahwa ada bermacam lapis penindasan terhadap rakyat. Kolonialisme Portugis dan militerisme Indonesia memang nampak di permukaan, tapi bukan berarti bahwa penindasan hanya berhenti di tingkat itu. Rakyat Timor Lorosae selama ratusan tahun juga hidup dalam budaya feodal, eksploitasi oleh tuan-tuan tanah dan raja-raja kecil yang diangkat oleh penguasa kolonial untuk menjadi tuan atas kaumnya sendiri. Ada juga dari mereka yang menikmati posisi itu, sekalipun sama-sama menderita di bawah kekuasaan asing. Realitas ini mengganggu pikiran Mana Lou dan membawanya berkenalan dengan ide-ide teolog terkenal Leonado Boff yang menulis buku Igreja Carisma e Poder, Ensaios de Eclesiologia Militante, pada tahun 1982. Di sini Boff menguraikan pandangannya bahwa gereja sudah seharusnya berpijak pada realitas. Khusus di Dunia Ketiga gereja yang mengagungkan posisinya sendiri ternyata justru mendukung penindasan, seperti terjadi di banyak negara jajahan. Kritik Boff menjadi dasar bagi Mana Lou saat menyusun skripsi dan juga merumuskan dasar-dasar kegiatan Institut Sekulir. Seluruh energinya kemudian dikerahkan untuk mengkritik hirarki gereja melalui kerja, bukan sekadar menulis sindiran dan bergunjing di belakang sambil menikmati segala fasilitas yang disediakan oleh hirarki itu. Bagi Mana Lou, gereja tidak bisa mengajar bagaimana orang menjadi saleh. Sebaliknya gereja harus melihat apa yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat. Misionaris Portugis sejak awal kedatangannya memperkenalkan nilai Kristiani melalui devosi (unjuk kesetiaan) kepada simbolsimbol, para santo lengkap dengan segala pesta yang terkait dengannya. Dari perspektif kritis, praktek semacam ini tentu sudah “ketinggalan zaman”, tapi bagaimanapun gereja harus bertolak dari apa yang ada, dan mencoba membuat perubahan dengan kekuatan masyarakat sendiri. Rakyat memiliki caranya sendiri untuk mengembangkan keimanan atau religiositas. Dan dengan keimanan pula orang bertahan menghadapi segala bentuk penindasan dan siksaan selama berabad-abad. Dalam situasi penderitaan yang hebat, agama dan keimanan menjadi satusatunya pegangan yang tidak dapat dirampas. Perjuangan kemerdekaan Timor Lorosae juga membuktikan agama berperan penting untuk meneguhkan sikap melawan penindasan. Agama dalam hal ini sungguh-sungguh menjadi milik rakyat dan memiliki arti tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Keimanan tidak terbatas pada pemujaan terhadap simbol-simbol. Kolonialisme Portugis dan militeris Indonesia tidak memahami semua ini, seperti terlihat dari patung Kristus Raja di ujung timur kota Dili. “Rakyat tahu bahwa patung itu bukan milik mereka, maka hampir tidak ada orang yang datang berziarah ke sana,” kata Mana Lou. “Itu patung Kristus Politicus, hanya benda yang dibuat untuk merebut simpati rakyat.” Religiositas rakyat berkembang di basis-basis, dari pertemuan berkala untuk membahas nilainilai Kristiani di pemukiman kumuh, desa atau dusun dan ladang pertanian. Para pendamping, begitulah Mana Lou menyebut pekerja gerejanya, mengajar sekaligus belajar mendalami keimanan berdasarkan praktek kehidupan sehari-hari. Pengembangan iman menurutnya hanya bermakna jika dapat menjadi sumbangan dan memberi kualitas baru bagi gerak membebaskan diri dari belenggu penindasan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Ketika basis-basis berkembang menjadi organisasi swadaya, ketika umat sadar dan tidak mempercayai segala manipulasi, seperti kecurangan dalam pemilihan umum, atau paternalisme negara, dan mampu bangkit sendiri, maka religiositas tumbuh bersamanya. Melayani Rakyat, Mengabdi Tuhan Vox Populi, Vox Dei. Sebuah rumusan yang sering dilafalkan para pemimpin, tapi jarang dipraktekkan. Sebaliknya Institut Sekulir mencoba untuk tidak terperangkap dalam dunia jargon dan mengembangkan penghayatan konsep-konsep itu melalui pekerjaan di tingkat basis. Para anggota Institut memenuhi panggilan khususnya sebagai “orang awam” (istilah dalam hirarki gereja bagi orang yang tidak diajar khusus untuk menjadi pemimpin), untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Pelayanan terhadap rakyat adalah karya kerasulan yang utama berdasar tiga nasehat dasar dalam Injil: kemurnian, ketaatan dan kemiskinan. Tapi kehadiran mereka bukan tanpa soal. Seringkali rakyat mengharapkan pemikiran dan kepemimpinan dari luar, setelah sekian lama hidup di bawah patronase. Sementara anggota Institut juga menekankan bahwa rakyat hanya mungkin kuat jika menyadari apa yang mereka miliki, bukan hanya melihat apa yang datang dari luar. Dalam proses yang kadang berlangsung bertahun-tahun, akhirnya kesadaran bersama bahwa “gereja milik rakyat” pun bisa berkembang, di mana kaum miskin menghayati religiositas dalam perjuangannya untuk mencapai kehidupan lebih baik. Keputusan-keputusan penting mengenai karya kerasulan tidak dilakukan sekelompok kecil pemimpin seperti biasanya ditemui dalam hirarki gereja, tapi oleh rakyat di tingkat basis. Dialog menggantikan sabda-sabda, dan kerjasama menggantikan perintah. Saling belajar adalah prinsip penting, karena anggota Institut menyadari keterbatasan mereka sebagai manusia. Bagi Timor Lorosae yang hidup selama berabad-abad dalam budaya paternalisme, langkah Institut Sekulir memang tidak lazim dan mendobrak sikap pasif terhadap penderitaan rakyat yang kadang diperlihatkan oleh hirarki. Namun bukan berarti bahwa Institut Sekulir telah meninggalkan segala tradisi yang ada. Pelajaran agama yang “klasik” dengan cara membacakan ajaran dan mendengarkan khotbah tetap menjadi bagian penting. Tapi semua itu kemudian diolah lebih lanjut dalam dialog dan karya kreatif. Hanya dengan mencipta orang bisa mengembangkan imannya, demikian berulangkali para pekerja Institut berujar. Keberanian untuk mendesak, berpikir dan mencipta yang akan membawa perubahan sekaligus pendalaman nilai-nilai agama. Dalam konteks ini Institut Sekulir menghayati keputusan-keputusan dalam Konsili Vatikan II yang menekankan pentingnya dialog antara hirarki gereja dan umat atau rakyat, serta gerakan teologi yang membela dan memperjuangkan rakyat miskin di Dunia Ketiga. Rakyat Timor Lorosae yang sedang menempuh perjalanan berat menuju kemerdekaan, patut bersyukur dan bangga akan adanya gerakan Institut Sekulir, yang terus berjuang mengadakan perubahan dan pembaruan, sekalipun menghadapi tantangan dan cobaan yang berat. Kesabaran dalam melayani rakyat menjadi teladan bahwa perubahan tidak datang melalui caci-maki, kritik dan debat berkepanjangan, melainkan kerja nyata bersama rakyat. Mateus Gonçalves, anggota Sahe Institute for Liberation, Dili, Timor Lorosae
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
PUISI HUSNUL KHULUQI Catatan 30 Juni 2000 baju celana telah kukemas di kardus bekas indomie hatiku berbunga, senang sekali wajah ibu, kakak-kakak perempuanku juga ponakan-ponakanku yang sekian lama kurindu bagai menari-nari di mataku ya, selepas gajian sore ini aku akan pulang kampung mengobati rasa kangen di hati keluar dari loket pengambilan gaji kuhitung uangku, hutang-hutangku juga uang sewa rumah petak kepalaku mendadak pusing ternyata aku banyak hutang ternyata aku banyak kebutuhan dan keinginan untuk pulang kampung terpaksa kutunda lagi 2000 Ada yang Menangis ada yang menangis dialah tetangga kita yang suaminya kena phk karena ikut unjuk rasa suami tak lagi kerja hidup kian sulit padahal anak-anak mesti sekolah dan bila dapur tak lagi ngebul apakah masih ada harapan untuk perut yang lapar? ada yang menangis dialah tetangga kita apakah kau juga mendengarnya 2000 Mati Lampu di Rumah Petak malam tambah muram udara tambah pengap hidup tambah gelap sebatang lilin menyala tegak meleleh habis dalam sekejap malam tambah muram saja hidup semakin penuh teka-teki langkah kaki kian tak pasti semakin surut, semakin ke tepi dan esok hariku tak pernah kutahu 2000 Sayur Kangkung, Ikan Asin sayur kangkung, ikan asin menu yang dihapal lidahku sungguh sudah tak asing tiap hari mampir bibirku sayur kangkung, ikan asin tak perlu aku tolak tak perlu aku benci karena itu yang mampu kubeli 2000 Husnul Khuluqi, selain menulis puisi, sehari-hari ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil di Karawaci, Tangerang.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
Cari!
PicoSearch
Cari!
Pledoi Mendobrak Si Moni Kamasra STSI Denpasar Awal Dari Si Moni. Layaknya sebuah gerakan yang bermaksud mendobrak, menabrak, menggasak, mengkritik dan sejenisnya sudah dapat dibayangkan reaksi balik atau efek yang bakal ditimbulkan. Demikian halnya dengan gelar seni rupa ‘Mendobrak Hegemoni’ Kamasra STSI Denpasar yang berlangsung pada Februari 2001 di Lapangan Puputan Badung, kontan saja mendapat tanggapan dari semua pemain seni rupa yang terkena kritik. Reaksi balik mereka tidak kalah kerasnya bahkan ikut-ikutan memaki, mengejek, menuduh dsb, yang semakin menunjukkan kualitas ‘keseniorannya’. Mereka ternyata kebakaran jenggot plus kumis ketika merasakan egonya dikocok, namun tidak sedikit yang acuh tak acuh. Di sisi lain sejumlah seniman, pakar, menunjukkan kenetralannya dalam menanggapi persoalan ini. Paling tidak ada yang berusaha menilai secara proporsional. Tapi kami berpikir inilah saat yang tepat untuk lebih menggairahkan wacana seni rupa Bali yang telah lama impoten ditelan romantisme kebalian dan jayanya kolonialisasi seni dan orientalisme Timur yang sangat turistik. Wacana orientalisme Barat yang secara tidak sadar dipakai oleh elite Indonesia untuk melihat kesenian kita. Dari sini sebenarnya benih hegemonisasi secara umum, khususnya di bidang seni sudah terjadi. Orang mengatakan ini ‘penjajahan ide’. Sekali lagi, awal gerakan ini adalah sebagai sebuah gerakan kultural dan penyadaran yang membuka mata tentang kondisi seni yang tidak kondusif dan kritik terhadap personal yang dianggap menghujat tidaklah dimaksudkan untuk menjatuhkan nama atau kelompok-kelompok seni tertentu. Di samping itu, kami sadar bahwa pemahaman mengenai gerakan ini di masyarakat dan pelaku seni sungguh-sunguh sangat ‘dangkal’. Reaksi masih seputar cara mengkritik, dan menganggap gerakan ini akibat kecemburuan seniman muda bahkan kelompok seniman yang dianggap frustrasi. Mereka menjuluki kami sebagai drunken master dengan jurus-jurus mabuknya. Bahkan dominasi opini berani berasumsi bahwa gerakan ini sebagai gerakan tanpa arah, penuh intrik, konspirasi politik dan konflik pribadi untuk saling menjatuhkan. Bahkan opini yang berkembang mencurigai gerakan ini didalangi oleh pihak atau kelompok tertentu. Pola berpikir yang bernuansa intel jaman Orba ini sangatlah paranoid. Mereka berasumsi bahwa mahasiswa tidak cukup pintar untuk bisa menganalisis suatu fenomena sehingga haruslah ada aktor/dalang pintar di balik gerakan ini dan kecurigaan akan adanya penyandang dana sebagai sponsor. Bagi mereka yang biasa berpikir dalam hitungan M, yang rela membatalkan membeli mercy untuk ‘tujuan mulia’ seni-perdamaian dan terbiasa dengan eksibisi yang glamor di gedung museum-galeri yang megah atau di ruang pamer hotel bintang lima (dengan model lotere seperti SDSB) dengan katalog luks yang dipenuhi kata sambutan orang-orang berkuasa, tentu saja menganggap mustahil kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan dana pas-pasan. Sindrom kecurigaan orang kaya memandang modal besar lebih utama dibanding menjual visi dan sedikit kenekatan. Keterlaluan barangkali diobok-oboknya lembaga STSI secara berlebihan dalam bentuk penekanan dominasi yang terkesan melangkahi otoritas. Contohnya tuntutan untuk memberi sanksi akademis berupa pemecatan bahkan upaya hukum terhadap mahasiswa yang terlibat dalam gerakan ini. Akhirnya masalah ini menjadi semacam konflik personal antara yang dikritik dan mengkritik. Keadaan semakin keruh karena media massa yang seharusnya mampu mewacanakan konflik secara objektif dan proporsional malah memuat pemberitaan sangat tendensius dan tidak berimbang. Situasi ini mengakibatkan tidak terjadinya dialektika dan proses diskusi yang sehat dan dinamis. Keadaan pasca ‘Mendobrak’ yang mirip benang kusut ini tentulah akan merugikan kedua belah pihak. Dengan mencoba untuk merefleksikan secara keseluruhan polemik, wacana, isu dan konspirasi yang berkembang maka sudah sepantasnya kita maju selangkah dengan mencoba meninggalkan ego, apologi dan pembenaran yang sifatnya sepihak dari kedua belah pihak. Dengan rendah hati bersedia menuju ruang dialog karena betapapun peliknya permasalahan selalu terbuka untuk dibicarakan demi sebuah penjernihan. Seputar Cara Mengkritik Dalam polemik seputar acara ‘Mendobrak Hegemoni’ itu, hal yang paling mengedepan adalah soal cara mengkritik yang dalam anggapan mereka sebagai sesuatu yang kebablasan, kasar, anarkis, barbar, dsb. Cara ini segera dicap sebagai perilaku kekanak-kanakan, gaya Orde Baru dan preman yang tak berwawasan, dianggap melanggar etika, moral dan pelecehan terhadap kelompok tertentu, institusi maupun personal yang terkena kritik. Namun anehnya tanggapan mereka tidak sedikit yang terjebak dalam cara mengkritik yang sama bahkan disertai ancaman. Bukankah hal semacam ini menunjukkan realitas ‘kebarbaran’ yang ada pada tiap individu maupun kelompok bahkan pada setiap kebudayaan maupun peradaban. Penilaian semacam itu juga bisa muncul akibat ada yang merasa dirugikan dari kemapanan yang telah mereka ciptakan. Sebagai sebuah metode mengkritik yang tendensius bahkan vulgar model di atas tentu sah-sah saja. Hal ini tentu didasari oleh alasan yang setidaknya bisa diterima oleh akal sehat dan bukan sekedar kebablasan yang membabi buta. Persoalan akan menjadi runyam ketika metode semacam ini dibenturkan oleh persepsi yang bersumber dari etika, moral maupun tata nilai yang sering kali anti-kebebasan dan bersifat memvonis secara terburu-buru. Di sinilah diperlukan keterbukaan untuk melihat suatu hal dan konteks persoalan yang hendak dikritik. Disadari atau tidak, persoalan yang hendak didobrak oleh Kamasra sudah dalam tahap emergency sehingga diperlukan metode yang bersifat shock therapy yang sangat efektif. Lagi pula bukankah ini merupakan ekspresi yang muncul akibat kemuakan yang berlebihan. Menjelekkan belum tentu sejelek yang disangka, walaupun mengandung senda gurau dan keakraban di dalamnya dan masih dalam bingkai seni bahasa komunikasi dalam suatu komunitas. Soal kata yang sangat ‘puitis’ seperti, “fuck you, bapak-bapak kok ngga paham sih bahasa anak muda, sekali-sekali dengerin dong mp3 Limp Bizkit atau lagu kelompok Jamrud”, di situ bertebaran kata atau idiom yang luar biasa ‘puitis’. Atau dalam salah satu puisinya Sutardji menyelipkan kata pukimay yang artinya... Dan setidaknya sebagai trik untuk mengangkat persoalan ternyata lumayan efektif. Terlepas dari tujuan yang bermaksud merusak harmoni sosial. Kenapa kami mempermasalahkan orang-orang dan bukannya sistem ‘anonim’, yang menurut beberapa orang jauh lebih ‘elegan’? Karena kami anggap mereka adalah para ‘tokoh-tokoh kunci’ yang menjadi panutan banyak seniman. Sesungguhnya orang-orang seperti Erawan, Gunarsa dan Wianta itu sudah menjadi patron dalam kancah seni rupa Bali terutama bagi beberapa seniman muda. Sampai ada istilah ‘Erawanisme’ yang berarti dia bahkan sudah bukan person lagi melainkan sudah menjadi suatu isme tersendiri. Figur Erawan sendiri sudah menjadi sebuah ‘institusi’. Bisakah kita menampik keberadaan ‘faktor’ Gunarsa dari eksistensi Sanggar Dewata Indonesia (SDI)? Sebagai ‘institusi’ dia bukan lagi menjadi wilayah personal belaka melainkan menjadi wilayah umum dan anonim. Dan itu artinya dia bisa dikritik sebagai institusi dan terlepas dari personnya. Mengkritik sebuah sistem yang anonim akan memberi ruang tempat ‘berkilah’ bagi person-person yang menjadi komponen dalam sistem itu. Saling tunjuk hidung orang lain dalam sistem yang sama dan merasa ‘bukan saya’ akan menjadi jawaban yang klise. Metode memang tidak akan berhenti cuma sebagai cara dan bisa saja menimbulkan efek yang bermacam-macam terlebih hal ini berhadapan dengan kemapanan budaya (budaya Bali yang menempatkan etika dan moral dalam posisi yang istimewa), sehingga tak berlebihan apabila ada selentingan yang muncul, jika kegiatan ini tidak terjadi di Bali barangkali ceritanya tidak akan heboh. Wacana Hegemoni Dalam katalog pameran yang sangat sederhana namun laris manis itu, kami telah mengatakan bahwa elemen-elemen seni rupa (seniman, art dealer, spekulan, kolektor, galeri, museum, kritikus, jurnalis seni, media massa, dsb) di Bali dan Indonesia telah berkongsi dalam menciptakan iklim hegemoni seni. Tentunya dengan perkongsian yang telah merasuk kepala semua pelaku seni rupa, akhirnya menciptakan koor bersama untuk berteriak satu kata, satu motivasi yaitu: duit. Adanya jaringan kepentingan semacam ini dengan sangat mudah dibaca adanya hegemoni yang berarti kekuasaan secara berlebihan. Ada pengamat seni rupa Bali yang mengatakan gerakan ini mengacaukan peta seni rupa kontemporer Bali, yang memang sudah kacau semenjak dahulu karena kuasa duit. Kami hanya bisa memberikan jawaban bahwa gerakan ‘Mendobrak Hegemoni’ ini memang lahir untuk melakukan proses dekonstruksi terhadap peta seni rupa Bali yang dikuasai oleh gembonggembong mafioso seni dan kongsi antara para cukong-kolektor seni. Tapi kami ingin melakukan aksi kultural dan alternatif menentang semua dominasi itu. Ekspresi jelaslah tidak ingin mengekang orang lain untuk berpendapat dan berekspresi. Tetaplah berpikir bahwa hanya perubahan yang abadi, dengan kritik dan wacana baru yang terus berkembang. Disamping itu, wacana dan aksi seni rupa dominasi yang berperang dengan alternatif, dibingkai dalam dunia besar kapitalisme dan industrialisasi seni rupa yang sangat tidak menghiraukan dunia estetis dan kreatif. Wacana dominasi yang kami maksudkan memang sangat sederhana dan sulit untuk membuat pemegang kekuasaan untuk sadar diri. Kelompok-kelompok seni semacam Sanggar Dewata Indonesia dengan wacana dominasi simbolisme dan ikon kebalian bisalah dipakai sebuah contoh. Wacana dominasi ini bisa mereka ciptakan karena dukungan kongsi pemain seni yang sudah mereka pegang di semua lini. Akhirnya meraka hadir sebagai sesuatu yang sangat hebat dan maha sempurna. Tapi, kacaunya meniadakan kelompok atau wacana alternatif yang lain. Disinilah mereka telah menciptakan hegemonisasi seni yang terus terang saja katanya, tidak mereka sadari. Hegemoni sebagai sebuah jaringan kepentingan di mana masing-masing komponen pemain seni rupa mempunyai peran yang berbeda, namun tidak jarang kelompok pemain tertentu, semisal kelompok seniman senior mempunyai otoritas yang sangat kuat. sehingga kelompok lainnya menjadi tidak berdaya. Dalam hal ini konteks hegemoni pada masing-masing elemen pemain seni rupa telah dicoba diletakkan bagi kepentingan analisis terhadap perkembangan dinamika seni rupa pada skala lokal di Bali. Melalui perilaku, gejala dan beberapa fakta yang tidak selalu mudah dilacak namun kerap menjadi perbincangan keseharian. Komponen pertama adalah kelompok seniman.Yang menarik dalam hal ini adalah kelompok Sanggar Dewata Indonesia (SDI), sebuah kelompok perupa terbesar dan tertua di Bali saat ini. Awalnya Kelompok ini dimotori oleh seniman jebolan ISI Yogyakarta yamg pentolannya sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh seni rupa di Bali, menjadi patron dalam sanggar maupun dalam skala yang lebih luas. Konsep yang mereka dendangkan adalah ikhwal spiritualisme Hindu Bali dan budaya Hindu Bali, yang oleh pengamat seni rupa Jean Couteau dibaca sebagai wacana identiter. Karya-karya mereka memang sebagian besar mengambil, mencomot atau terinspirasi dari ikon-ikon dan khasanah budaya Bali. Pencapaian dan pengembangan teknis yang sangat ekspresif seperti efeks, nyapu, dan plototan sangat signifikan sebagai pencapaian teknik yang jauh dari teknik melukis tradisional terdahulu. Mereka menjual estetika, kecenderungan besar yang sering dibaca sebagai ekspresionisme berikut variannya. Capaian estetika modern ini menemukan momentum pasar yang sangat potensial didorong adanya boom lukisan dan perkembangan pasar lukisan di Bali. Bisnis kesenian mulai marak. Di sinilah pasar mulai menunjukkan otoritasnya. Banyaknya GunarsaGunarsaan, Erawan-Erawanan dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan hal ini menghegemoni dirinya sendiri seperti kecenderungan repetisi, ‘memproduksi’ karya sebanyakbanyaknya untuk ditebar merata pada setiap galeri yang ada dengan kalkulasi satu hari minimal harus ada satu yang laku. Misalnya 10 juta perbiji perhari. Motivasi pasar mendorong bertebarannya karya-karya generasi muda dengan kecenderungan plagiat/epigon. Ikon-ikon budaya pun dengan mudah ditawarkan sebagai konsumsi, misalnya pemakaian simbol yang mengesankan seolah senimannya adalah pendukung militan budaya Bali. Bukan hendak bicara sakral yang diprofankan, tapi eksploitasi yang perlu dikhawatirkan dan seringkali kecenderungan memakai simbol sebagai dagangan akan menutup mata terhadap realitas objek seni yang lain. Hegemoni estetika semacam ini menjadi kecenderungan bahkan sampai merasuk dalam iklim pendidikan seni di akademi-akademi, ini tentu sangat berbahaya bagi proses pendidikan. Komponen yang kedua adalah pebisnis seni. Menjamurnya galeri-galeri komersial pada sentrasentra pariwisata di Bali. Betapa menggiurkannya bisnis seni rupa berarti percetakan uang. Kalau mau jujur semua galeri berwajah seragam, tidak punya visi seni karena terutama adalah bisa menyediakan dagangan yang laku untuk dijual. Tidak usah susah-susah berinvestasi, para perupa muda yang mempunyai potensi ke depan, langsung saja mencari tahu lukisan siapa yang laku, lalu harus dikejar. Dagangannya mirip pasar swalayan yang menyediakan mulai dari lukisan tradisi sampai modern, kontemporer dan sebagainya, dari pelukis muda sampai pelukis yang sudah uzur, bahkan kalau sudah kepepet pelukis yang masih hidup dibilang sudah mati, biar harganya terdongkrak. Logikanya pelukis yang menyandang gelar Alm. tidak berproduksi lagi, dengan sedikit penawaran tinggi maka harga karyanya menjadi mahal. Galeri hanya giat membikin brosur mewah di setiap brosur wisata dan tidak merasa risih tidak memiliki kurator atau penilai karya yang berwibawa. Acuan kurasi: nol besar!! Mereka berlomba memberi prosentase yang tidak rasional, menurut gosip 50% untuk jasa wisata atau guide dan cuma beberapa persen untuk pelukis. Pemain bisnis seni rupa di Bali untuk kurun waktu yang sangat lama nampaknya dipegang oleh raja galeri. Baru dari beberapa dekade yang lalu muncul spekulan-spekulan kakap bahkan spekulan yang muncul dari tanah Jawi, mulai banyak agenagen pengorder dan pengepul yang menyusup langsung ke studio pelukis. Museum-museum yang ada di Bali juga menunjukkan tata kerja atau model permainan yang tak terlalu jauh berbeda dengan galeri. Dari model publikasi yang lebih giat berpromosi ke luar negeri bahkan ada yang membuat buku dalam bahasa Inggris. Koleksi juga seragam, lalu di mana peran edukasi dan dokumentasi dari sebuah museum? Komponen ketiga adalah kritikus dan jurnalis seni. Kritikus dan jurnalis dipesan untuk menulis. Tetapi objektivitas mulai hilang ketika model tulisan yang berbau iklan dengan analisis yang sering kali tanpa acuan yang kritis dan menyanjung secara berlebihan, buntutnya adalah peran wacana dan acuan apresiasi menjadi terabaikan. Masyarakat, pencinta seni dan kolektor tak terdidik dalam berapresiasi. Maka jangan heran kalau lukisan yang laku dalam sebuah pameran sampai ada yang dikocok bak lotere (pemenangnya dapat kanvas kosong dan kemudian dilukis on the spot, langsung dibubuhi tanda tangan dan diangkut selagi catnya masih basah) dan bukan karena apresiasi. Demikian juga peran media dalam memberitakan kegiatan gelar seni karya seniman beken tertentu yang itu-itu saja, sering over dosis dan memuji-muji berlebihan sehingga terkesan media sebagai pengiklan galeri maupun pelukis. Gambaran di atas menunjukkan betapa runyamnya atmosfer berkesenian di Bali. Barang seni menjadi mirip benda pakai, objek utilitas seperti TV, kondom, komputer dan sebagainya. Idealisme, kreatifitas, eksperimentasi yang lekat dengan kerja seni menjadi dikorbankan. Seniman kehilangan kredo-kredo berkeseniannya karena terhegemoni oleh faktor-faktor eksternal pasar yang semestinya diletakkan sebagai sebuah efek terhadap kualitas seni yang mampu dihasilkan oleh sang seniman. Logika pasar juga bisa berlaku bahwa barang yang diproduksi terlalu banyak akan kehilangan kemampuan nilai tawarnya. Kalau karya seni mengikuti logika semacam itu maka seni berada pada posisi tawar yang terendah bahkan diobral. Sebuah acuan estetika dengan membangun image nilai dan nilai pasar sadar atau tidak akan menimbulkan hegemoni dengan motivasi yang sangat beragam. Kalau meminjam ikon estetika tertentu masih dalam kerangka motivasi pencarian, merupakan suatu hal positif dan wajar dalam berkreasi, namun motivasi material semata sangatlah berbahaya bagi idealisme sebuah pencarian. Hegemoni dalam sistem dan estetika inilah yang sebetulnya hendak didobrak atau dikritik. Kritik yang berkehendak mengadakan perubahan. Sistem yang didobrak bisa melakukan otokritik dan yang lain bisa bikin alternatif atau saling melebur diri. Demikian juga dobrakan estetika tidak secara otomatis harus menawarkan sesuatu yang baru secara seketika. Spirit perubahan paling tidak mampu melakukan semacam antitesis dalam mencari alternatif sebagai bentuk penawaran yang mungkin akan relatif berbeda tergantung proses dan dinamika sebuah gerakan. Tidak berlebihan kalau ada pengamat yang mengatakan gerakan ini telah mengacaukan peta seni rupa kontemporer Bali. Ini barang kali konsekwensi logis dari sebuah gerakan yang menimbulkan semacam implikasi atau efek yang bisa tidak terduga terhadap siapapun yang berkepentingan di dalamnya. Konsekwensi yang paling riil bagi pengkritik barangkali adalah komitmen, integritas moral terhadap rel dan keyakinan yang telah didendangkan dan dipertaruhkan. m KAMASRA (Keluarga Mahasiswa Seni Rupa) STSI Denpasar, Bali.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Resink dan Mitos Penjajahan 350 Tahun Razif Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itulah satu dari sedikit warisan pemikiran pra-Orba yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam upacara-upacara resmi, para pejabat yang merasa perlu memobilisasi semangat orang, selalu mengucapkannya. Sejak 1930-an, gerakan nasionalis menjadikan pernyataan ini sebagai bahan agitasi dan propagandanya. Menariknya, pada saat bersamaan di kalangan penguasa kolonial pun ada perdebatan serupa. Para pemilik perkebunan, birokrat kolonial dengan dukungan kalangan konservatif di Belanda bergabung dalam Vaderlandsche Club, yang ingin melanggengkan kolonialisme setidaknya untuk 350 tahun lagi, dan tidak melihat perlunya “berbaik hati” pada orang bumiputra melalui Politik Etis, karena ternyata hanya melahirkan pemberontakan. Pada 1926-27 terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan serikat-serikat rakyat di Jawa dan Sumatera Barat. Kalangan konservatif mendapat angin untuk menindas gerakan nasionalis dan sekaligus menyingkirkan pendukung Politik Etis dari birokrasi kolonial. Posisi mereka ditentang oleh kelompok Stuw yang berbasis di Leiden, dengan anggota-anggota seperti J.H.A. Logeman dan H.J. van Mook. Mereka didukung oleh sarjana-sarjana kolonial yang berpendapat bahwa Belanda tidak pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun, dan karena itu tuntutan “melanjutkan penjajahan” untuk kurun waktu yang sama, menjadi tidak masuk akal. Mereka berpendapat sebaiknya negeri induk memberi kemerdekaan secara bertahap, dan mengelola sumber daya alam serta kegiatan ekonomi bersama-sama, seperti layaknya negara persemakmuran di bawah Inggris. Menindas gerakan nasionalis adalah pemborosan di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip Etis yang dikembangkan sebelumnya. Perdebatan itu tertunda ketika kekuasaan kolonial dipenggal oleh serbuan Jepang pada 1942. Gerakan nasionalis menjadikan arogansi Vaderlandsche Club sebagai bahan propaganda dan menulis kembali sejarah dengan membalik seluruh argumentasi yang terkandung di dalamnya. Apa yang oleh Vaderlandsche Club disebut sebagai kejayaan menjadi penindasan, pahlawan menjadi penjahat dan sebaliknya. Tapi keduanya sepakat bahwa Indonesia memang dijajah Belanda selama 350 tahun. Di tengah pergulatan ini muncul Gertrudes Johan Resink, mahasiswa sekolah hukum di Batavia, keturunan Indo-Belanda yang lahir di Yogyakarta pada 1911. Ia mendalami sistem hukum Indonesia, terutama hukum antar bangsa di bawah asuhan J. H.A. Logeman, tokoh kelompok Stuw. Setelah menyelesaikan karya pertamanya mengenai sejarah hukum Madura, Resink bekerja sebagai pegawai negeri di sekretariat Gubenur Jenderal Buitenzorg (Bogor) hingga kedatangan balatentara Jepang. Pada 1947 ia menjadi satu dari sedikit ahli hukum yang tetap bertahan di Indonesia. Ia menggantikan Logeman mengajar di almamaternya, yang telah diubah menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Indonesia. Selama sepuluh tahun ia meneliti kembali hubungan Indonesia-Belanda dari perspektif hukum, untuk membongkar apa yang menurutnya adalah mitos-mitos, termasuk klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Ia adalah orang pertama yang secara kritis mengkaji kembali kebijakan pemerintah kolonial sejak abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Hasilnya adalah rangkaian esei yang kemudian dibukukan dan diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Indonesia, dengan judul Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910. Dengan perhatian utama pada keputusan pemerintah kolonial “yang dilupakan” baik oleh sejarawan Belanda, tokoh Vaderlandsche Club maupun gerakan nasionalis Indonesia, ia ingin membuktikan bahwa klaim penjajahan selama 350 tahun adalah mitos belaka. Menurutnya, pada dekade pertama abad ke-20 di kepulauan Indonesia masih tersebar daerah-daerah swapraja dan kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka. Ia menunjuk Regeeringreglement (peraturan pemerintah) 1854, yang menyatakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda memiliki wewenang untuk mengumumkan perang dan mengadakan perdamaian, serta membuat perjanjian raja-raja di seluruh Nusantara. Sampai abad ke-19 bahkan ada kerajaan-kerajaan yang cukup kuat dan “berada dalam hubungan setara” dengan penguasa kolonial, seperti Ternate dan Tidore. Hubungan antara pemerintah kolonial dan kerajaan-kerajaan yang merdeka diatur dalam kontrak atau perjanjian. Artinya ada kerjasama antara penguasa kolonial dan kerajaan-kerajaan tersebut untuk mengelola sumber daya ekonomi sambil mempertahankan kedaulatan masingmasing. Tidak ada serangan bersenjata, pengiriman pasukan atau penaklukan seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Di Surakarta dan Yogyakarta yang masih merupakan daerah swapraja misalnya sewa tanah berjalan tanpa hambatan dan tidak ada keributan seperti halnya di tempat-tempat lain. Para penguasa kraton dan Gubernur Jenderal berhubungan baik. Melihat semua ini Resink kemudian menganggap kerajaan-kerajaan yang merdeka ini mirip dengan protekorat atau daerah di bawah perlindungan negara Hindia Belanda. Dalam esei “Dari Debu Sebuah Taufan Penghancuran Patung-Patung” yang terbit 1956, Resink membandingkan kekuasaan Majapahit, VOC dan Hindia Belanda. Seperti C.C. Berg seorang sarjana kolonial terkemuka, ia mengatakan kekuasaan Majapahit harus dilihat dari segi lalu lintas perdagangan rempah-rempah yang tidak hanya menghubungkan pulau-pulau di Nusantara, tapi juga mengaitkannya dengan pelabuhan India serta daerah pantai di Laut Tengah. Kekuasaan Hindia Belanda tidak pernah sampai sejauh itu. Artinya klaim bahwa Belanda menguasai Nusantara seperti halnya Majapahit menguasai wilayah itu pun gugur. Apalagi jika dibandingkan VOC (cikal-bakal negara Hindia Belanda) yang hanya berkuasa di sebagian kecil wilayah dan sangat terbatas pula. Klaim penjajahan selama 350 tahun pun semakin terlihat rapuh ketika dihadapkan pada fakta-fakta dasar seperti ini. Ia mengakui bahwa orang Belanda memang tinggal dan bekerjasama dengan orang bumiputra selama ratusan tahun, mungkin juga melakukan kejahatan di sana-sini, tapi jelas tidak menguasai keseluruhan wilayahnya. Perhatian lainnya adalah daerah-daerah di luar Jawa yang sangat sedikit disinggung dalam penulisan sejarah nasional. Kaum nasionalis biasanya menggunakan contoh perkebunan di Sumatera dan Jawa untuk menunjukkan penindasan yang hebat. Tidak ada yang bisa menyangkal itu, tapi Resink ingin membuktikan bahwa di samping itu masih ada wilayahwilayah yang berdiri sendiri dan merdeka. Ia menggunakan nota H. Colijn yang menguraikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di daerah-daerah luar Jawa. Dari nota ini ia mendapat gambaran tentang situasi politik di berbagai daerah menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hasil pengamatannya kemudian disusun menjadi esei “Negara-Negara Pribumi di Nusantara Timur”, untuk menunjukkan bahwa sampai kurun itu sebenarnya ada negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya. Ia melihat bahwa di mata pemerintah kolonial sendiri, semua wilayah itu dianggap otonom dan sejajar. Perlakuan itu bukan hanya bagi negeri-negeri yang memang masih merdeka seperti Kalimantan Selatan dan Lombok, tapi juga bagi wilayah yang mengadakan perjanjian dengan Belanda dan mengakuinya sebagai kekuasaan tertinggi, seperti Aceh, daerah bawah di Jambi dan Riau. Dalam karangan terakhir di kumpulan itu, Resink menegaskan kembali masalah kedaulatan ini. Sekalipun raja-raja bumiputra mengakui penguasa kolonial sebagai kekuasaan tertinggi dan menyapa gubernur jenderal dengan sebutan “yang dipertuan besar” dalam perjanjianperjanjiannya, status mereka sesungguhnya setara. Negeri seperti Aceh dan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan sekalipun berhubungan dengan Belanda, harus diperlakukan seperti Montenegro atau Monaco dalam hukum internasional. Resink adalah pendukung kemerdekaan Indonesia. Ia sama sekali tidak menyangkal hak rakyat untuk merdeka, dan sangat kritis terhadap kekuasaan kolonial. Namun simpati atau keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan menurutnya tidak bisa tenggelam dalam kesalahan melihat fakta-fakta, apalagi mengembangkan mitos-mitos yang tidak berdasar. Karena itulah ia bersikeras membuktikan bahwa penjajahan selama 350 tahun adalah mitos belaka. Memang dari sudut hukum, bukti-bukti yang diajukannya mendukung argumentasi itu. Tapi persoalannya kemudian bagaimana cara kita memahami bukti-bukti yang ada. Cukup jelas bahwa Resink berpegangan pada paham legalistik, yang berkutat pada rumusan hukum dan segala konsekuensi logisnya. Akibatnya ia seringkali tidak melihat struktur yang melandasi produk hukum itu. Singkatnya, memisahkan antara eksploitasi kolonial dengan produk hukum yang dibuatnya. Hukum baginya adalah sesuatu yang netral dan harus dibaca “seperti adanya”. Karena itulah kerajaan-kerajan merdeka dianggapnya berada dalam hubungan setara dengan pemerintah kolonial. Mereka membentuk partnership dan bukan hubungan penguasa dan yang dikuasai. Pemerintah kolonial, seperti dijabarkan dalam perjanjian-perjanjiannya, bertindak sebagai pelindung kerajaan sambil tetap menghargai kedaulatan masing-masing. Tapi sebaliknya Resink tidak melihat hubungan sesungguhnya antara wilayah tersebut dengan penguasa kolonial, di luar jalur hukum. Eksploitasi ekonomi, ekspansi kekuasaan kolonial terus berlangsung, terlepas ada tidaknya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian dengan Sultan Siak pada 1889 yang menjadi syarat bagi penguasa kolonial untuk menguasai tambang timah. Begitu pula perjanjian dengan Sumatera Timur pada 1909 yang mengakui kebesaran raja setempat tapi di sisi lain mengubah daerah kekuasaannya menjadi sebuah cultuurgebied (daerah perkebunan) yang menghasilkan jutaan gulden setiap tahunnya untuk para pemilik perkebunan. Dalam perjanjian itu disebutkan adanya platselijke raad atau semacam dewan pemerintahan, tapi kekuasaannya hanya sebatas “kedaulatan politik”, sementara urusan ekonomi dan eksploitasi, termasuk pengerahan tenaga kerja yang terkenal kejam, diserahkan sepenuhnya kepada pemilik perkebunan. Begitu pula dengan Nota Colijn yang menjadi rujukannya untuk memahami “kedaulatan” wilayah-wilayah merdeka di bagian timur Nusantara. Dalam nota itu berulangkali ditekankan bahwa negeri-negeri yang “merdeka” berada di bawah kekuasaan kolonial. Persoalan lain, Resink juga nampaknya mengabaikan gerakan protes dan perlawanan rakyat yang me luas sejak abad ke-19, sementara para penguasa feodal di masing-masing wilayah menikmati “kesetaraan” dengan penguasa kolonial. Justru penaklukan kalangan elit dan perlawanan rakyat adalah ciri tanah jajahan di mana pun. Artinya, kemerdekaan tidak dapat diukur hanya dari sisi hukum, tapi harus melihat keseluruhan cara hidup masyarakat yang bersangkutan. Studi Resink dan cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh keinginan “meluruskan sejarah” dari salah paham, baik di kalangan sarjana kolonial konservatif maupun gerakan nasionalis. Ia masuk dalam sebuah perdebatan panjang yang menariknya sampai pada kesimpulan sama dengan kepentingan yang bertolak belakang. Sementara kaum konservatif mengklaim penjajahan selama 350 tahun sebagai pembenaran untuk melanjutkan kolonialisme, gerakan nasionalis mengklaim kurun yang sama sebagai dasar untuk membebaskan diri. Di tahun 1950-an, saat Resink menulis esei-eseinya yang mahsyur itu, gerakan nasionalis sedang naik pasang. Komentarnya memang menimbulkan perdebatan kembali di kalangan nasionalis dan intelektual sezaman. Komentar dan kritiknya yang tajam terhadap salah paham kaum nasionalis atas sejarahnya sendiri menjadi catatan penting bahwa propaganda tidak bisa bertahan atas dasar-dasar yang rentan dan salah. Sebaliknya perlu kita ingat bahwa Resink juga mengabaikan berbagai hal, termasuk hal-hal terpenting mengenai hubungan eksploitatif antara penguasa kolonial dan rakyat tanah jajahan. Kesepakatan dan perjanjian dalam bahasa yang santun tidak dengan sendirinya mencerminkan “kesetaraan”. Sumatera Timur mungkin menjadi contoh yang menonjol, sementara berdaulat di bidang politik, eksploitasi menyebabkan ratusan ribu orang menderita sebagai kuli kontrak yang nyaris seperti budak. Bagaimanapun, karya Resink memberi sumbangan berharga untuk menyadari bahwa kemerdekaan secara legal-formal dan kedaulatan hukum, tidak dengan sendirinya berarti pembebasan menyeluruh dari hubungan-hubungan yang menindas. Razif, pekerja pada Jaringan Kerja Budaya
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Segelas Kopi Darpan Ariawinangun Ketika masih mendiami rumahnya yang dulu, berdua dengan Bi Simah, sehari-harinya dia menjadi upas desa. Namanya pun dirangkai dengan jabatannya: Upas Karma. Seperti umumnya upas, pekerjaannya tak lebih dari mengantar surat, menjaga kantor desa, menata aula sebelum rapat, atau— jika tak ada lagi pekerjaan kantor yang harus diselesaikan—membersihkan rerumputan yang tumbuh liar di pekarangan balai desa. Pagi-pagi benar dia sudah berangkat dari rumahnya, mendahului para staf desa. Membuka pintu dan jendela, membersihkan meja, menyapu dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya. Pulangnya paling belakang, setelah tak ada lagi staf desa yang tinggal di kantor, setelah menutup jendela dan pintu, setelah membereskan kembali meja dan kursi, dan setelah tak ada lagi yang harus dikerjakan. Begitu dan begitu seterusnya. Kadang-kadang, jika ada rapat di balai desa sampai malam, subuh hari dia baru pulang, menginap di balai desa. Belakangan, ketika hari pemilihan kembali kepala desa semakin dekat, saat semua staf desa kesibukannya meningkat, Upas Karma hanyut pula dalam kesibukan itu. Selain melakukan pekerjaan rutinnya, ia harus pula mengerjakan tugas-tugas ekstra: ke sana ke mari membuntuti jurutulis menyensus calon pemilih. Ia ikut membantu mendaftar. Ikut juga mengurusi administrasi panitia pilkades walaupun hanya jadi pengantar surat. Bahkan, ia diminta pula untuk menyebarkan pengaruh, bersama dengan staf lainnya. Ia diminta mendukung lurah hormat yang sekarang mencalonkan diri lagi. Sejatinya ia melakukan itu karena terpaksa, karena seluruh staf desa di situ sebenarnya anak buah lurah hormat. Walaupun sekarang ini pemerintahan desa sudah dipegang oleh pejabat sementara, namun pada dasarnya tidak ada perubahan. Soalnya, yang menjadi PJS-nya pun adiknya Lurah Nawi, lurah hormat itu. Wajar jika semua staf desa mendukung Lurah Nawi. Bagaimana tidak. Dan dia, bagaimana bisa berbeda dari staf lain? Dari hari ke hari, Upas Karma semakin sibuk. Mungkin karena terlalu sibuk, suatu hari Upas Karma cuma bisa meringkuk di kamarnya. Badannya demam. Makanan yang disodorkan oleh Bi Simah ditolaknya. Pahit katanya, dan kepala seperti mau pecah. “Kenapa Mang Karma, Bi?” kata Jurutulis kepada Bi Simah di luar rumah. “Tahu tuh, Ulis? Meringkuk saja kerjanya dari pagi.” “Kalau sudah baikan, suruh cepat kembali ke desa. Bilang sedang banyak kerjaan,” kata Jurutulis sambil pergi, tanpa mau menunggu jawaban dari Bi Simah. Melayat kek, gerutu Bi Simah dalah hatinya. Malamnya Upas Karma malah semakin merintih-rintih, membuat khawatir Bi Simah. Bi Simah lalu menyuruh Icih—anak tetangganya—membeli air soda dan aspirin. Setelah minum air soda dengan aspirin, demamnya mulai mereda. Dari seluruh tubuhnya keluar keringat. Namun Bi Simah tetap menyelimutinya dengan kain berlapis-lapis. Biar seluruh keringat keluar, katanya. “Mencari apa atuh, Abah?” gumam Bi Simah sambil memperbaiki letak selimut di tubuh Upas Karma. “Kerja dari pagi buta sampai sore. Badan sendiri tak terurus. Mending kalau gajinya besar. Apa untungnya jadi upas. Apa bedanya dengan kuli menyabit.” Mang Karma tidak menjawab. Cuma pikirannya yang terus nyerocos. Kuli menyabit? Palingpaling disebut kuli dekil. Begitu pikirannya. Walaupun dari segi penghasilan bisa melibihi gaji upas, tetap saja disebut kuli. Sementara jadi upas, setidaknya ia dikenal sebagai pegawai desa. Ada punya wibawa. Beda dengan kuli. Kalau memberi atau menyampaikan perintah kepada orang lain, menyampaikan perintah rapat kepada masyarakat misalnya, selalu dituruti. Kalau kuli dekil? Kuli? Paling-paling cuma bisa diperintah dan disuruh-suruh orang, harus taat perintah pegawai. Soalnya dia sendiri pernah mengalami, ketika masih menjadi buruh tani. Waktu itu musim Pemilu. Oleh Karyu—adik tirinya yang tinggal di kota— ia disuruh berbeda dari orang kebanyakan, memilih gambar yang tidak umum buat orang kampung. Setelah Pemilu jadi gunjingan. Orang-orang menyebarkan isu, bahwa ada orang di desa itu yang berkhianat. Mang Karma dipanggil ke balai desa. Esok harinya ia disuruh gorol sendirian, membersihkan rerumputan di pinggir-pinggir jalan sepanjang totoang. Seminggu ia habiskan waktunya di situ. Ternyata itu pun tak cukup. Setiap harinya ia harus juga menerima gunjingan-gunjingan staf desa yang membuat telinganya panas. Semisal gunjingan, “Siapa yang mau jadi orang kota? Pantasnya kalau orang kampung ya jadi kuli. Jangan jadi jagoan.” “Negara demokrasi, Kang. Kita bebas memilih!” kata Karyu waktu itu. Tapi buktinya, ia harus menampung semua omongan busuk orang kampung. Mana yang benar? Begitu Mang Karma selalu bertanya. Setelah dipikirkannya matang-matang, dan setelah anak-anaknya juga menyalahkan dia, Mang Karma baru sadar kalau dia sedang melawan arus. Akhirnya, segala perintah selalu ia turuti walaupun seringkali ia menerimanya dengan rasa tidak senang. Oleh karena itu, begitu pikirnya, kalau ia hanya jadi kuli tentu akan selalu dipermainkan orang lain. Mendingan jadi pegawai desa seperti sekarang ini. Walau hidup melarat, tapi masih ada yang mau menghargai, masih ada yang mau minta pertolongannya. Lagian, kalau dia punya keperluan-keperluan kecil, tidak susah untuk bicara sama jurutulis atau lurah. Tinggal ngomong. Dan jika nasib lagi baik, tidak sulit bagi dia untuk memperoleh sekadar seribu atau dua ribu dari hasil dia membantu orang yang butuh tenaganya. Kalau kuli dekil? Kuli? Ia memang tidak bermimpi jadi lurah, atau jadi sekdes, atau kepala urusan. Tidak. Lagian untuk jadi lurah tidak cukup uang satu atau dua juta, tapi harus puluhan juta. Memang, semua itu tidak sia-sia, karena ketika sudah jadi lurah pemasukan akan datang dari mana-mana. Bagi Mang Karma, menjadi upas saja sudah jadi keberuntungannya. Ternyata orang-orang desa masih mau mengakui keberadaan dia. Walaupun hanya jadi upas, ia tetap dianggap sebagai staf di desa. Masih punya kesempatan menyuruh atau memerintah orang lain. Untungnya, Upas Karma sakitnya tidak lama. Tiga hari kemudian, dia sudah ikut sibuk kembali karena pelaksanaan pilkades tinggal beberapa minggu lagi. Tenaganya betul-betul diabdikan buat kepentingan desa. “Mang Karma, besok pindah rumah saja. Tempati tuh ruangan belakang balai desa,” kata Lurah Nawi, lurah hormat yang kemudian mencalonkan diri lagi. “Lurah dan Sekdes sudah saya beritahu,” katanya lagi. Upas Karma untuk sesaat seperti orang bingung. Tidak terpikir dia harus ngomong apa. Karena yang pertama-tama melintas dalam pikirannya: dari rumah bilik dia harus menempati ruangan belakang balai desa yang sudah berlantai tegel, bertembok, berlangit-langit, dan berjendela kaca. Sementara rumahnya yang selama ini ditempati jangankan berlangit-langit, gentingnya saja sudah banyak yang bolong. Lantainya tanah, dindingnya bilik bambu, dan jendelanya hanya anyaman bambu pula yang dikaitkan dengan seutas kawat. Esok harinya, Upas Karma resmi menempati ruangan belakang balai desa. Bi Simah yang biasanya menghadapi tungku tanah, kini bisa menyalakan kompor hadiah dari Lurah Nawi. Selain itu Mang Karma bisa tiduran santai di kursi busa yang sudah tak terpakai lagi di desa. Walaupun kursi bekas, tapi masih lebih baik daripada kursi kayu reyot yang ada di rumahnya sendiri. Suatu sore, ketika Upas Karma sedang menikmati segelas kopi sambil duduk-duduk di kursi busa, datanglah Lurah Nawi. Menengok, katanya. Mang Karma sekarang tak lagi kikuk kedatangan tamu hanya karena tamu harus diterima di saung butut. Ketika harus mempersilahkan tamu masuk atau duduk, ia tak harus malu: ada kursi busa sekarang. “Tentu Mang Karma kerasan di sini,” kata Lurah Nawi ramah sambil duduk di kursi busa. Upas Karma hanya bisa menjawab dengan tertawa. “Bagaimana Bi Simah, apa sudah bisa menyalakan kompor?” Upas Karma lagi-lagi menjawabnya dengan tertawa. Sementara Bi Simah yang menguping obrolan itu dari belakang agak tersinggung. Memang aku orang utan yang tak tahu kompor, gerutunya dalam hati. Obrolan mereka, sambil menikmati kopi, sudah ngalor-ngidul. Sampai suatu ketika, Lurah Nawi berpamitan pulang. Si tuan rumah kemudian mengantarkannya ke halaman. Sebelum pergi, Lurah Nawi menegaskan sebuah pesan, “Jangan lupa, Mang. Minggu depan Si Nurja dan Si Nana harus sudah pasti sikapnya. Kalau tetap mau membelot... ah, pikirkan saja oleh Mang Karma. Masak...!” Upas Karma mengangguk pelan. Setelah tamu pergi, Bi Simah mendekatinya. “Nah, mau bagaimana kalau sudah begini?” “Tahulah...,” jawab Upas Karma sambil tetap terpaku di halaman. “Eh, ya harus dipikir atuh, Abah!” Upas Karma tak menjawab lagi. Ia kembali ke dalam, diikuti Bi Simah yang terus mengganggu dengan omongan. “Abah yang begitu mah, kenapa mau saja jadi pegawai desa. Apa untungnya jadi upas. Kalo jadi jurutulis sih masih mending, ada penghasilannya. Kalau sudah begini, kita harus bagaimana? Abah kan tahu kalau Si Nurja dan Si Nana itu kepala batu.” “Sudah! Aku yang akan ngomong sama mereka. Bukan kamu!” Upas Karma membentak, agar istrinya diam. Bi Simah cemberut, lalu pergi ke belakang. Tinggal Upas Karma sekarang yang tampak bingung. Lurah Nawi, adalah atasannya. Sementara pada Nurja dan Nana—anakanaknya—dia tahu betul tabiatnya. Terdorong keinginannya untuk segera mendapat keputusan, malam itu juga dia mendatangi rumah Nurja. Dia ceritakan keinginannya. Hanya saja dia tak berani berterus terang kalau dia sebenarnya didesak oleh Lurah Nawi. “Eh, Abah, seperti tidak tahu saja. Apa jadinya desa kita kalau Lurah Nawi terpilih lagi? Lihat yang sudah-sudah, rakyat kecil juga yang sengsara. Pungutan sumbangan dibesar-besarkan, hasilnya tidak ada,” kata Nurja, menjawab desakan bapaknya. “Habis aku harus bagaimana, Nur?” Upas Karma bingung sendiri. “Ya begitulah, Bah. Silahkan kalau Abah mau milih lagi Lurah Nawi mah, tapi saya tidak akan. Kapok!” jawab Nurja lagi. Lalu dia mendekati bapaknya, lalu berbisik, “Abah tidak tahu ya. Kata PPL, Lurah Nawi itu suka makan uang subsidi. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan, membangun mesjid, membuat jalan, habis dia makan sendiri....” “Tahu apa kamu, Nurja!” Upas Karma cepat memotong. “Lha, Abah selama ini tahu apa?” Nurja malah balik bertanya. Upas Karma hanya bisa melotot. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Malam sudah larut ketika Upas Karma pamit pulang. Sebelum pergi ia menyempatkan bicara lagi sama Nurja, “Dari semula aku tidak mau memaksa kamu. Biar kalian berpikir sendiri. Mau mendukung Lurah Nawi ke, atau Haji Sukur kek, terserah kamu.” “Saya juga begitu, Bah,” jawab Nurja. Malam berikutnya, Upas Karma berkunjung ke rumah Nana, anaknya yang kedua. Tapi jawaban Nana tidak jauh berbeda dengan kakaknya. “Orang sekampung sudah tahu, Bah, kalau Lurah Nawi itu tukang korupsi. Tapi kalau Abah takut kehilangan pekerjaan mah, ya terserah, saya tak bisa melarang Abah mendukung Lurah Nawi.” Upas Karma menenggak gelas kopi yang disodorkan istri Nana. Seminggu sebelum pilkades, Upas Karma sudah kembali menempati rumahnya yang dulu. Kalau dihitung, tak sampai sebulan dia menempati ruangan belakang balai desa, karena keburu disuruh pergi oleh Hansip Kurdi. Katanya ruangan belakang itu akan dibersihkan dulu, sesuai perintah Lurah Nawi. “Masa iya cuma mau dibersihkan?” gerutu Bi Simah. Sementara Upas Karma tak bisa berkatakata lagi. Hanya saja, dia merasa tersinggung dengan kata-kata Hansip Kurdi, “Oh ya, kunci desa mau saya ambil, Mang.” Upas Karma lalu menyerahkan kunci itu. Ternyata tak cukup sampai di situ, karena Hansip Kurdi bicara lagi, “Kata Lurah Nawi, besok Mang Karma di rumah saja. Di desa sekarang sudah ada Mang Sukri, Upas baru.” *** Mang Karma, bekas upas desa, terbangun dari dipan tempat tidurnya, setelah dikagetkan oleh kokok ayam jago dari belakang rumah, tepat di samping telinganya. Ia sempoyongan berjalan ke ruangan tengah, lalu duduk di bangku kayu reyot miliknya. Ia tersenyum seperti teringat sesuatu yang lucu. Di meja sudah terhidang segelas kopi dan sepiring singkong rebus. Saat menyodorkan tangannya hendak meraih gelas kopi, pandangannya tertumbuk ke sudut kamar tidur. Tepat di situ, bilik bambunya menganga, seperti biasa digunakan kucing berlalu lalang. Ia seperti baru sadar, kalau selama ini telah menelantarkan rumahnya sendiri. Pandangannya lalu diarahkan ke atas. Sarang laba-laba berajutan di palang-palang genting. Lalu ia mengamati gentingnya. Tak terbayangkan, jika hari itu hujan tiba-tiba turun dengan angin yang kencang. Ia lalu meraih gelas kopi. Pelan-pelan diminumnya, sambil dirasakan alirannya di tenggorokan. Setelah beberapa tegukan, Mang Karma kembali terdiam. Dalam hatinya saja dia bicara, “Inilah duniaku. Dunia segelas kopi di pagi hari, dengan pikiran bebas mau apa aku hari ini. Tidak dipaksa orang, atau takut. Ah, kenapa aku selama ini diperdaya oleh sesuatu yang tidak jelas. Meninggalkan duniaku sendiri yang bebas-merdeka seperti ini. Tapi baiklah, karena itu semua ada hikmahnya juga. Aku jadi tahu tabiat dari orang-orang itu. Masa bodoh, siapa yang minggu depan akan terpilih jadi lurah.” Ia kembali meneguk kopi. Tiba-tiba terdengar teriakan istrinya dari belakang, “Abah, bukannya mau memperbaiki tungku!” pilkades: Pemilihan Kepala Desa lurah hormat: Lurah yang sudah habis masa jabatannya. gorol: Kerja bakti. totoang: Jalan yang memanjang antara satu kampung dengan kampung lainnya. sekdes: Sekretaris Desa. PPL: Petugas Penyuluh Lapangan. Darpan Ariawinangun, cerpenis Sunda yang biasa bolak-balik Jakarta—Bandung—Garut. Cerpen ini diterjemahkan sendiri oleh penulisnya dari cerita pendek berbahasa Sunda Cikopi Sagelas yang termuat dalam buku antologi cerita pendek Nu Harayang Dihargaan, Bandung: Rahmat Cijulang, 1998, hlm. 81—90. Cerita pendek ini pertama kali dipublikasikan pada 1993 di Koran Sunda Galura Bandung.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Kesembuhan Semu Kapitalisme Thailand Arif Rusli Ibarat pengidap virus HIV yang berusaha menyembunyikan hasil diagnosa lanjutan, pemerintah Thailand cenderung terlalu hati-hati untuk bicara soal kapan dan sejauh mana taraf kesembuhan ekonomi negerinya. Pekan silam, Perdana Menteri Thaksin dengan ketus mempertanyakan kapabilitas ketua Asosiasi Bankir Thailand, Chulakorn, yang memprediksikan bahwa Thailand paling kurang butuh waktu 8 tahun untuk benar-benar keluar dari krisis ekonomi. Bagi Thaksin, komentar pesimis semacam ini dianggapnya sebagai tudingan terhadap ketidakmampuannya membereskan krisis ekonomi Thailand sekaligus menihilkan ikrarnya dalam kampanye pemilu empat bulan silam. Waktu itu, dia menjanjikan akan membereskan ekonomi Thailand dalam waktu kurang dari empat tahun. Nyatanya data-data kredit macet dan rendahnya arus modal yang beredar, memaksa para bankir IMF, bankir dan ekonom Thai untuk memilih sikap pesimis soal kesembuhan ekonomi negeri ini. Thailand sebelum krisis mempunyai investasi asing sekitar 41,1% terbesar setelah Korea Selatan yang mencapai 52,5 %. Dan ketika Thailand dihantam krisis yang paling utama mengalami kerusakan adalah angkat kakinya para investor asing, hampir 78 % aliran modal keluar (capital flight) Thailand, ini mempunyai akibat dengan meningkatnya deretan orang miskin, sekitar 10 juta orang tidak mempunyai pekerjaan dan harus hidup dengan 100 bath (Rp. 4000,-) per-hari. Ciri umum dari krisis ekonomi di Asia dan juga terjadi di Thailand di 1997 adalah mencari kesalahan pada prilaku, etika dan akhlak pemilik modal dan birokrasi. Cara pandang ini adalah dasar pijakan dari berbagai ekonom Thai. Sementara IMF dan Bank Dunia dalam melakukan penilaian terhadap kinerja ekonomi selama krisis berlangsung menegaskan “selama 10 tahun terakhir perekonomian Thailand membawa pengaruh pada kemakmuran mayoritas rakyat banyak, tetapi setelah mengalami krisis Thailand harus menghidupi perekonomiannya dari kucuran dana publik.” Penilaian para para pejabat Bank Dunia dan IMF untuk perwakilan Thailand itu berarti masyarakat Thai dibebani oleh berbagai macam jenis pajak dan penjualan sumber daya mineral dan keuangan atau yang dikenal melalui proses akumulasi primitif. Thailand boleh dikatakan negeri yang tidak pernah dijajah, tetapi tidak pernah lepas dari hubungannya dengan imperialisme. Dari paket Miyazawa Plan yang berjumlah US$ 6 miliar untuk negeri Asia yang terjangkit krisis ekonomi, Thailand mendapatkan US$ 2 milyar yang dipergunakan untuk restrukturisasi perbankan dan mendongkrak mata uang Bath. Sebagai imbalannya lembaga-lembaga Bretton Wood, ini menginginkan perusahaan dan perbankan Thailand dikelola oleh swasta. Ini menandakan pemaksaan liberalisasi oleh negeri-negeri imperialis, terutama Amerika-Serikat, yang mempunyai mata uang dolar yang begitu kuat sebagai prasyarat untuk memimpin liberalisasi. Tolok ukur kesembuhan perekonomian Thailand ditaksir dengan berkurangnya hambatanhambatan dalam privatisasi, liberalisasi pasar, khususnya korupsi dan penyelewengan dana untuk kebutuhan lain.Tak heran, rekomendasi utama dari Bank Dunia dan IMF adalah melakukan reformasi hukum perbankan untuk mempermudah pembayaran utang dan penyelesaian kredit macet. Lalu yang terpenting jangan keluar dari sistem ekonomi pasar atau menghambat arus keluar masuknya modal. Pemerintahan Thaksin juga menambah ekspor tenaga kerja atau buruh migran sebagai pemasukan anggaran negara. Dari ekspor tenaga kerja ini administrasi Thaksin dapat memperoleh US$ 4 juta pada 1999. Di sisi lain, IMF hanya merekomendasikan agar pemerintah memajukan sektor pendidikan, membangun keahlian dan jaring pengaman sosial. Pada masa puncak krisis, Bank Dunia hanya mengalokasikan US$ 43 juta ke program sosial, bandingkan dengan US$ 2 milliar ke program liberalisasi pasar dan reformasi hukum dan regulasi. Tidak mengherankan kalau dana pinjaman ini lebih banyak menguap dalam birokrasi, terutama dalam rangka melaksanakan sistem elektoral. Padahal, data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa upah di wilayah nonindustri, seperti wilayah tenggara dan tengah Thailand anjlok sangat tajam semasa krisis berlangsung. Mereka yang paling parah kondisinya adalah buruh lulusan sekolah dasar atau yang berpendidikan lebih rendah. Jumlah tenaga kerja setingkat ini bertambah dengan mudiknya para pekerja konstruksi dan real estate dari Bangkok. Sementara itu, orang-orang terkaya yang tercakup dalam 20% dari populasi tetap saja menikmati keuntungan dari krisis ekonomi antara 1996-1998. Mereka ini sebelum krisis menjabat sebagai manajer bank. Thaksin Shinawarta, bilioner yang sekarang menjadi Perdana Menteri Thailand, mengeruk 100% keuntungan dari spekulasi di pasar uang. Konon, uang hasil spekulasi itu dipakai untuk membiayai kampanye politiknya. Spekulasi atau korupsi adalah cara yang diizinkan oleh IMF dan Bank Dunia untuk para elit politik mencapai tampuk kekuasaan, karena dengan cara seperti ini para elit politik tidak lagi mengontrol kelua -masuknya aliran modal. Boleh dikatakan borjuasi Thailand disingkirkan untuk turut berperan dalam mengontrol perusahaan-perusahaan multi-nasional (MNC), bahkan perusahaan-perusahaan nasional. Perusahaan-perusahaan nasional Thailand setelah diterpa krisis belum dapat bangkit kembali. Sedangkan MNC terus menerus memasok barang-barangnya ke negeri gajah putih ini dan mereka saling berkompetisi, tetapi tidak mematikan malah sebaliknya saling melengkapi. Sebagai contoh perusahaan mobil Ford dari Amerika Serikat masuk ke Thailand dan bekerjasama dengan perusahaan mobil Honda dari Jepang. Mereka sama-sama menguasai pasar otomotif di Thailand. Sedangkan sektor industri real state dan petrokimia yang menjadi sarang spekulasi dan korupsi di Thailand diambil alih oleh Bank Sumitomo, Jepang. Pengambil alihan perusahaan-perusahaan nasional Thailand oleh perusahaan asing tidak berati praktek spekulasi dan korupsi diberantas, ini tetap dipelihara, dengan cara seperti ini akumulasi modal akan terus mengalir ke metropolis. Prabat Patnaik dengan cekatan merumuskan krisis di Asia Tenggara dan Timur dipicu dengan mempertahankan praktek penyelenggaraan pemerintahan lama, seperti spekulasi dan korupsi. Dari sini negeri Thailand akan terus memohon pemberian utang baru dan pembayarannya melalui penjualan sumber alam dan perusahaan-perusahaan nasional. Pengalihan saham itu juga diikuti dengan penciutan cabang usaha atau masuk kategori bangkrut. Akibatnya ratusan ribu tenaga kerja di sektor-sektor tersebut menganggur. Hampir setengah juta orang tenaga kerja dari Myanmar diburu dan dipaksa pulang ke negerinya pada pertengahan 1998. Dengan alasan penertiban tenaga kerja asing, pemerintah Thai mendorong supaya lapangan kerja yang ditinggalkan itu bisa diisi oleh warga negara Thai. Di 1997, menurut departemen tenaga kerja Thailand, lebih dari 2 juta warga negara Thailand menganggur dan mengalami peningkatan empat kali lipat pada 1999, yakni 10 juta orang. Tingkat pengangguran yang tinggi membuat lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, situasi yang membuat geram lembaga keuangan internasional. Mereka menginginkan agar warga Thai bekerja sebagai apa saja, asalkan menghasilkan devisa untuk membayar utang. Lebih parah lagi, ratusan usaha kecil dan menengah harus gulung tikar setelah krisis ekonomi. Usaha-usaha bertujuan substitusi impor ini tidak mampu melunasi utang yang dipinjam dari bank-bank domestik. Hal ini ikut menyumbang pertambahan jumlah tenaga kerja yang mengandalkan kesempatan kerja di industri besar. Sampai saat ini sektor-sektor usaha seperti garment, sepatu dan elektronika tetap belum pulih. Malah di sektor industri manufaktur elektronik, pemecatan terus berlangsung, akibat rendahnya permintaan pasar ekspor barang di elektronik di Jepang dan Amerika, dua negara yang menjadi tujuan ekspor utama komoditi elektronik Thailand. Setelah krisis menimpa Thailand, kalangan kelas menengah kehilangan kepercayaan terhadap propaganda strategi ekonomi berorientasi ekspor. Rata-rata perusahaan domestik yang berorientasi ekspor harus tutup. Banyak pengusaha atau mantan direktur perusahaan berorientasi ekspor yang terjun ke sektor usaha menengah yang sudah mapan, seperti kerajinan emas, berlian, pengemasan produk makanan kaleng, mainan anak-anak atau sektor makanan. Pasca krisis banyak restoran kecil bermunculan. Umumnya usaha semacam ini mengincar pasar dalam negeri. Sampai sejauh ini belum tampak apa sumbangan sektor ini terhadap pemulihan ekonomi, karena sebagian besar usaha hanya bisa memperoleh kredit kecil dan menggunakan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Kecenderungan ini muncul sejak tiga tahun silam, setelah para ekonom ramai-ramai melarikan diri dengan membahas konsep ekonomi swadaya yang diutarakan oleh Raja Bhumibol. Banyak pembenaran yang dipakai untuk menggalang ekonomi swadaya, salah satunya mencari pembenaran moral dari ajaran Budhisme soal keseimbangan materi dan rohani. Bersamaan dengan itu ekonom nasionalis menuding lembaga keuangan internasional yang mendorong persaingan bebas telah menjerumuskan bangsa Thai ke jurang kehancuran. Para ekonom nasionalis mengalami kegagalan, karena menganggap remeh fetishism sebagai suatu keniscayaan dalam hubungan sosial kapitalisme, dimana disiplin besi untuk menghasilkan produk diredam oleh kepuasan semu untuk memburu berbagai komoditas baru. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang menghubungkan krisis ekonomi di Thailand dengan kejenuhan pasar internasional atau domestik akibat membanjirnya produk serupa. Para politisi bicara soal swasembada sebagai lawan dari ekonomi berorientasi ekspor. Namun, belum ada arahan yang mempertimbangkan kemungkinan kejenuhan pasar, akibat berlombalombanya usaha kecil dan menengah memproduksi komoditas yang sama. Banyak pedagang dan penjaga toko, mengeluh bahwa para pengunjung hanya mengolok etalase untuk mengecek harga, tapi jarang yang membeli. Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa keadaan sekarang lebih buruk dari 1997. Birokrasi yang selama ini menjadi juru stempel dan kerap kurang kreatif, ikut latah mencari-cari bentuk ekonomi swasembada di tingkat pedesaan dan menyokong fasilitas kredit untuk usahausaha yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Padahal usaha-usaha swasembada yang sejati sama sekali tidak membutuhkan kredit tambahan dari pemerintah, karena umumnya mereka tidak terlampau mengandalkan pasar dalam arti suatu tempat komoditas dikumpulkan dan dijual sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Namun birokrasi sebagai tempat untuk melayani masuknya modal internasional, harus aktif memberikan kredit agar akumulasi modal bergerak kembali. Di tengah-tengah krisis yang tak kunjung sembuh, para bankir, ekonom dan pemerintah terbagi dalam dua kelompok. Yang satu berusaha mengambil jarak dari rekomendasi IMF dan berkampanye soal ekonomi swasembada yang mandiri dari campur tangan asing dan satu kelompok lain ikut mendorong penerapan reformasi ekonomi seluas-luasnya, artinya ikut liberalisasi pasar dan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomis tadi. Kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya, maka diktat rekomendasi dari lembaga keuangan menjadi pegangan dari pemerintah Thaksin. Pemerintah Thaksin mengambil inisiatif dengan memperkuat mekanisme hukum Thailand Asset Management Corporation untuk memberesi kredit macet di bank-bank negara, serta membentuk kerja sama investasi (matching fund) dengan Malaysia dan Brunei. Pemerintah Thailand mengambil bagian 25% dari pendanaan tersebut. Terdapat dua hal yang menggiatkan investor di Thailand. Pertama memperoleh pinjaman dari bank-bank luar negeri yang semuanya dapat mengalir secara aktif berkat dorongan IMF, tersedianya tingkat suku bunga yang bisa dicicil untuk pengembaliannya. Persoalan lain yang muncul, sistem lama yang masih tersisa—spekulan—sebagai kelas baru dan operator keuangan. Aktor ini yang menjadi penghubung utama dengan pasar modal di luar negeri dan menyusun aliran modal internasional. Orang-orang ini juga menjadi operator liberalisasi keuangan, menjalankan kepentingan-kepentingan lembaga donor dan memperkuat posisi lembaga keuangan internasional sebagai polisi pemburu bagi siapa saja yang tidak membayar utang. Acuan: Prabhat Patnaik. “Capitalism in Asia at the End of the Millenium.” Monthly Review. July-August. 1999 Thongchai Winichakul. “The Origins of Thailand Crisis.” Jurnal Contemporary Asia. AugustSeptember 2000. Arif Rusli, kontributor MKB yang bermukim di Bangkok, Thailand.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Pasar John Roosa Pasar sering dibayangkan sebagai wilayah yang merdeka. Di samping itu, dikenal pula istilah ‘pasar bebas’ untuk menjuluki pasar yang tidak dikendalikan negara. Pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat selalu mengunggulkan pasar bebas dalam retorika mereka. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, dua lembaga internasional yang paling berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia sekarang, boleh berbangga karena semua negeri yang mereka pinjami uang telah berhasil membebaskan pasar dari kendali negara. Istilah “pasar bebas” sungguh memikat kalangan bermodal dari segala penjuru dunia di abad baru ini. Jika gerakangerakan sosialis pada abad ke-19 dan ke-20 berjuang untuk ‘membebaskan kaum proletar’, gerakan hak-hak sipil berjuang untuk ‘membebaskan rakyat tertindas’ (seperti kaum kulit hitam di Amerika Serikat), dan gerakan-gerakan pembebasan nasional berjuang untuk ‘membebaskan bangsa-bangsa yang terjajah’, kaum kapitalis gencar mengumandangkan slogan ‘bebaskan pasar’. Sementara Amnesty Internasional membangun gerakan mendunia untuk pembebasan narapidana politik, IMF dan Bank Dunia menyebut dirinya sebagai gerakan mendunia untuk pembebasan pengusaha dari kontrol negara. Kaum kapitalis selalu berbicara dalam bahasa kebebasan, dan mereka percaya bahwa pasar merupakan anasir hakiki untuk pencapaian kebebasan manusia. Kita perlu berpikir kritis tentang konsep ini: apa artinya pasar bebas? Ketika pemerintah AS, IMF dan Bank Dunia menyatakan bahwa mereka membebaskan pasar, dan dengan demikian membebaskan rakyat pula dari kemiskinan, kita patut mempertentangkannya dengan cerita dari sisi seberang. Tak satu negara pun yang menjalankan kebijakan penyesuaian struktural (SAP) – kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia sekarang – di bawah tekanan IMF selama 30 tahun terakhir sanggup membangun perekonomian yang kuat, stabil dan maju. Lembagalembaga ‘globalisasi’ ini ternyata menghancurkan perekonomian nasional di Amerika Latin, Afrika dan Asia, meningkatkan kemiskinan, dan menegakkan kembali sistem kolonial di mana perusahaan-perusahaan multinasional dari AS, Eropa dan Jepang mendominasi kekayaan dan sumber alam dunia. Di Indonesia mereka memaksa pemerintahan ‘reformasi’ membayar setiap rupiah hutang pemerintahan Soeharto ke bank-bank asing, dan dengan begitu menyedot habis dana pemerintah yang diperlukan untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Melihat kenyataan serupa ini, kita bisa berasumsi bahwa ‘pasar bebas’ dalam wacana lembaga-lembaga ini merupakan istilah pengganti ‘kolonialisme’. Sebenarnya relatif mudah menunjukkan bukti kemunafikan di balik penggunaan istilah ‘pasar bebas’ oleh lembaga-lembaga globalisasi tersebut. Tetapi pengetahuan akan kemunafikan sang pembicara tidak selalu diikuti dengan pemahaman tentang konsep-konsep yang dibicarakan. Ilmu sosial membutuhkan lebih dari sekedar tuduhan sederhana atas kesenjangan antara kata dan perbuatan, yaitu penelitian tentang apa sesungguhnya yang dikerjakan, dan pengkajian secara seksama terhadap bagaimana kata merepresentasikan atau salah merepresentasikan realitas. Untuk memahami istilah ‘pasar bebas’, ada baiknya kita pelajari beberapa hal yang secara fundamental berkaitan dengannya. Kita semua punya pemahaman minimal tentang apa itu pasar. Dalam definisi yang paling sederhana misalnya, pasar adalah lokasi fisik di mana komoditi dipertukarkan. Seperti pasar di desa dan kota, tempat para pedagang berkumpul untuk menjual sayuran, daging dan ikan, buahbuahan, dan sebagainya, ada bermacam pedagang dan pembeli. Pedagang bisa menjualnya ke pembeli mana pun, begitu pula pembeli bisa membeli barang dari pedagang mana pun. Kadangkadang tawar-menawar soal harga bisa menjadi sangat tegang karena masing-masing pihak punya kepentingan berbeda: pembeli inginkan harga terendah, pedagang inginkan keuntungan tertinggi. Tetapi ada pemahaman tersembunyi di antara keduanya bahwa tidak ada unsur paksaan dalam proses transaksi tersebut. Maka, pasar tampil sebagai wilayah kontrak dengan konsensus lisan antara pembeli dan pedagang. Jika saya membeli pepaya seharga Rp 3.000, itu berarti ada kontrak walau tidak tertulis antara saya dan si pedagang. Kami bertemu sebagai pihak yang setara dan sepakat dengan kontrak ini. Saya tak todongkan pistol di kepalanya, begitu pula dia tak todongkan pistol di kepala saya. Kemudian, apa arti istilah ‘bebas’ sehubungan dengan pasar? Kalau kita lanjutkan contoh perdagangan di pasar di atas, orang akan berkata bahwa kebebasan tergantung pada apakah anda penjual atau pembeli. Bagi pedagang, kebebasan berarti menjual tanpa paksaan dari pihak lain: mereka tak dipaksa memberikan barang dagangan mereka tanpa dibayar ke polisi, tentara atau preman; mereka tak dipaksa oleh peraturan pemerintah untuk menjual barang dagangannya di bawah harga yang sudah mereka tentukan. Bagi pembeli, kebebasan berarti mampu membeli tanpa paksaan; tak satu pedagang pun memaksa mereka membeli hanya dari seorang pedagang saja, dan para pedagang juga tidak melakukan konspirasi bersama untuk menaikkan harga barang setinggi mungkin. Pembeli melihat kompetisi antar pedagang sebagai elemen kebebasan mereka; apabila mereka hanya berhadapan dengan satu pedagang atau kumpulan pedagang yang bersatu, mereka tak punya kekuatan tawar. Di banyak kota industri atau pertambangan yang terpencil, ada tradisi penyelenggaraan ‘toko perusahaan’ (company store). Perusahaan pengelola pabrik atau pertambangan memiliki semua toko yang ada di wilayah operasinya dan buruh perusahaan itu pun mau tidak mau harus berbelanja di toko-toko tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian mereka. Perusahaan bisa saja menaikkan semua harga barang secara sembarangan karena para buruh tak punya kendaraan dan waktu untuk berperjalanan ke kota atau pusat perbelanjaan lain di luar daerah bekerjanya. Tradisi ‘toko perusahaan’ semacam ini sudah membatasi kebebasan pembeli untuk memilih barang dan dari siapa mereka ingin membeli barang. Jadi kebebasan dalam pasar berarti bahwa baik pembeli maupun pedagang bisa menyepakati suatu kontrak secara bebas, tanpa salah satu pihak menggunakan paksaan. Dengan demikian pasar bebas adalah adanya kesempatan bagi semua untuk membeli dan menjual sesuka hatinya. Seperti yang dinyatakan Ellen Meiksins Wood, “hampir setiap definisi ‘pasar’ di kamus berkonotasi sebuah kesempatan.” (Wood 1994, p. 15) Semakin bebas suatu pasar, semakin banyak barang dan jasa tersedia, semakin banyak pilihan bagi pedagang pun pembeli. Kitab suci para kapitalis dewasa ini, yaitu buku Milton Friedman Free to Choose (1980), menampilkan pasar sebagai arena bertemunya berbagai orang dengan kekuasaan setara, masing-masing berjuang untuk memperoleh pilihan terbanyak dalam hal yang mereka beli dan jual. Yang mengacaukan pasar, menurut Friedman, adalah intervensi negara. Negara, dengan kekuatan pemaksanya, bisa membatasi rentang pilihan yang ada bagi pembeli dan penjual. Sejauh ini, kita baru mempertimbangkan tampak pasar di desa dan kota yang terlihat seharihari. Tapi mari kita tinggalkan kegaduhan pasar melewati ruas-ruas jalan raya menuju daerah pedesaan tempat sayur dan buah-buahan ditanam sebelum dijual ke pasar. Di sini pula kita temui perkebunan teh, tebu dan kelapa sawit yang hasilnya dijual ke seluruh dunia. Jika di pasarpasar tadi kita melihat tempat pertukaran komoditi, di ladang ini kita menjumpai tempat produksi komoditi. Ada jenis pasar yang berbeda di sini: pasar tenaga kerja. Buruh menjual tenaganya pada pemilik tanah dan perkebunan. Pasar jenis ini jelas berkaitan langsung dengan paksaan dan kekuasaan, dan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Taraf upah ditentukan oleh kekuatan buruh berhadapan dengan majikan. Dalam beberapa kasus, para buruh begitu tak berkuasa sehingga mereka bahkan tidak dibayar dan status mereka merosot tidak lebih dari budak. Tenaga kerja merupakan komoditi khusus. Dengan berperan sebagai pedagang yang menjual tenaga kerjanya, seorang buruh tidak hanya menyerahkan suatu obyek yang ada di luar dirinya, seperti pepaya. Ia mengasingkan sebagian dirinya, aktivitas otot, syaraf dan otaknya. Belum pernah tercatat dalam sejarah manusia ada pasar tenaga kerja yang merupakan pasar antar pihak yang setara. Buruh menjual dirinya karena mereka tak punya uang dan tenaga kerja mereka dibeli oleh mereka yang punya uang. Apabila buruh dalam posisi setara dengan pembeli tenaganya, mereka tak akan pernah menjual tenaganya. Dalam teori ekonomi standar (teori ekonomi yang diajarkan di universitas-universitas di Indonesia merupakan imitasi yang diajarkan di universitas-universitas di AS), pasar tenaga kerja ditampilkan seperti layaknya pasar lainnya, sebagai arena antar pihak yang setara bernegosiasi untuk mencapai konsensus dalam sebuah kontrak. Buruh digambarkan bisa begitu saja membeli tenaga kerja majikan seperti halnya majikan bisa membeli tenaga kerja sang buruh. Jika buruh rajin menabung upahnya (yang dianggap modalnya), suatu saat dia akan mampu menjadi kapitalis. Dalam teori ekonomi standar tak ada ide tentang kelas, kekuatan tak berimbang antar kelas. Jika kita melihat pasar hanya sebagai situs pihak-pihak yang setara, kita berarti mengabaikan ketidaksetaraan pemilikan properti dan kekuasaan di situs produksi. Sekarang, kalau saya pergi ke warung dan membeli teh, antara pemilik warung dan saya, tak ada perbedaan kekuasaan. Tetapi teh itu sendiri diproduksi di perkebunan oleh para buruh yang tertindas, yang setiap usahanya untuk mengorganisir diri pasti akan dihalangi oleh pemilik perkebunan. Sejarah teh di Indonesia, seperti halnya sejarah kopi dan tembakau, adalah kisah bergelimang darah dan penindasan. Sebagai ilustrasi, silakan membaca buku Jan Breman tentang bentuk-bentuk brutal pengendalian buruh di perkebunan kolonial, Menjinakkan Sang Kuli yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Tak ada kebebasan memilih bagi buruh. Pilihan yang mereka miliki hanyalah bekerja atau lapar. Memilih sakit atau bahkan mati karena lapar tentu tidak bisa kita sebut ekspresi kebebasan. Pasar sudah ada selama ribuan tahun. Pada hakikatnya tak ada yang salah dengan pasar itu sendiri. Pada masa peradaban Mesir marak perdagangan antar daratan dan lintas lautan dengan aneka macam komoditi. Yang penting kita pertimbangkan adalah milik (property): Bagaimana hubungan kepemilikan antar orang? Apa hubungan kuasa antara satu pihak dengan pihak lain? Adanya pasar berarti ada konsepsi tentang milik. Pedagang menjual sesuatu yang dia miliki. (Siasat pedagang sekaligus pencuri yang paling jitu adalah menjual barang curiannya kepada pemilik awal barang tersebut.) Karakter pasar bergantung pada hubungan kepemilikan yang sudah terbangun dalam masyarakat. Sebagai gambaran, ketika para pedagang Belanda pertama kali berlayar ke kepulauan Nusantara pada awal abad ke-17, mereka membeli rempah-rempah di berbagai kota pelabuhan tanpa memiliki semeter tanah pun di wilayah ini. Mereka membeli rempah-rempah dari pedagang lain yang membawa rempah-rempah tersebut dari daerah pedalaman tempat barang dagangan itu diproduksi. Pada saat itu belum ada perkebunan. Berbagai kelompok etnis dan kekerabatan menanam lada, pala, dan rempah-rempah lain yang ada pada saat itu; tapi, mereka tidak bekerja banting tulang di bawah ancaman cambuk. Baru pada akhir abad ke-18 dan 19 ketika para pedagang Belanda ini berhasil memperoleh kekuasaan politik, mereka mulai mengendalikan proses produksi rempah-rempah. Konsumen di Eropa tidak tahu-menahu asal-muasal rempah-rempah ini hanya dengan melihatnya di tokotoko di Amsterdam. Apakah barang-barang itu diproduksi oleh orang yang bebas atau budak tak tampak di medan jual-beli. Contoh serupa, konsumen sepatu Nike di AS hanya bisa melihat sepatu terpajang di etalase, tanpa pengetahuan tentang pabrik-pabrik pemeras keringat buruh Indonesia tempat memproduksi sepatu-sepatu tersebut. Komoditi, barang mati tak bicara, tidak menunjukkan relasi kuasa di tempat mereka diproduksi. Mereka diam di pasar menunggu dijual. Para ekonom yang mengagungkan “pasar” sebagai arena kebebasan dan kesetaraan mengekor belaka pada perspektif buta ini dan mengabaikan kondisi sosial yang menaungi proses produksi komoditi. Seorang sejarawan dan ahli antropologi Karl Polanyi (1886-1964) dalam buku klasik dan ternamanya, The Great Transformation (1944), berbicara tentang bagaimana karakter pasar secara kualitatif berubah sekitar 1500-1600an di Eropa. Buku ini seharusnya menjadi bacaan wajib bagi semua pelajar dan ahli ilmu sosial. Ia berpendapat bahwa manusia, selama jutaan tahun, untuk kelangsungan hidupnya bergantung pada barang-barang yang tidak dijadikan komoditi. Di masyarakat jaman purba dan pertengahan yang diperdagangkan di pasar bukanlah barang kebutuhan sehari-hari, melainkan barang-barang khusus. Misalnya, sebagai bagian dari komunitas agraris seseorang memproduksi bahan makanan, seperti beras atau gandum, dan menerima bagiannya dari panen bersama. Jadi, ia tidak perlu membeli bahan-bahan ini di pasar. Yang tersedia di pasar sekadar barang-barang tambahan seperti garam atau lada yang dibawa dari Asia, atau benda-benda mewah untuk kaum elit pengumpul pajak di kota. Pedagang tidak mengendalikan proses produksi komoditi yang mereka jual; mereka hanya membelinya di satu tempat dengan harga murah dan membawanya ke tempat lain untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Hal pokok yang diutarakan Polanyi adalah bahwa kelangsungan hidup manusia tidak sepenuhnya tergantung pada pasar. Ia beranggapan bahwa “ekonomi” bukanlah ranah kegiatan yang terpisah. Berbeda dengan yang terjadi sekarang, dahulu tidak ada konsep tentang ekonomi yang berfungsi menurut hukum-hukumnya sendiri tanpa ada kaitan dengan masyarakat atau keinginan manusia. Pedagang tidak mengendalikan negara. Pada saat itu ada pasar, tetapi kegiatan dan wilayahnya “termaktub” dalam hubungan-hubungan komunal, kekerabatan, keagamaan dan politis. “Transformasi besar-besaran” yang merupakan judul buku Polanyi adalah proses komodifikasi tiga hal pada awal era modern Eropa, yaitu tanah, buruh dan waktu, yang sebelumnya tak pernah terjadi. Polanyi, yang sampai taraf tertentu mengikuti pemikiran Karl Marx pada abad ke-19, berpendapat bahwa kapitalisme bukanlah suatu sistem ekonomi di mana pasar menjadi lebih bebas atau di mana para pedagang dibebaskan dari pembatasan yang diterapkan kekuasaan feodal. Yang mendefinisikan kapitalisme adalah penggusuran orang dari tanah mereka secara besar-besaran. Begitu orang tak memiliki tanah, seperti yang terjadi di Inggris sejak abad ke-16, mereka harus bergantung pada pasar untuk bertahan hidup. Kalau kita mengamati hubungan sosial kepemilikan, kita akan menemukan bahwa pasar di bawah kapitalisme berkaitan dengan desakan, yaitu, desakan untuk berpartisipasi dalam pasar. Mereka yang tak bermilik hanya punya pilihan terbatas antara bekerja atau kelaparan. Sekarang mayoritas orang di negeri-negeri kapitalis maju seperti AS tidak memiliki modal; mereka hidup dari pekerjaan yang berupah jam-jaman. Mereka tidak hidup dari perolehan keuntungan saham, bunga, atau pembagian keuntungan perusahaan. Sejarah kapitalisme sebenarnya adalah sejarah penggusuran orang dari tanahnya dan penciptaan pasar tenaga kerja yang terus-menerus berkembang meluas. Mereka yang mendukung perkembangan kapitalisme dan ‘pasar bebas’ di Indonesia harus mengamati dengan serius negara-negara ‘berkembang’ seperti AS: konsekuensi tak terhindarkan dari perkembangan kapitalisme adalah pesatnya pertumbuhan kelas orang-orang bermilik (propertied class). Konsentrasi kekayaan di AS dewasa ini luar biasa besarnya: di satu sisi ada ‘surplus’ penduduk yang masif dan tidak mendapat bagian apa-apa dari ‘pasar bebas’; di sisi lain, hidup segelintir milyuner. Pemerintah AS banyak mengerahkan pendapatan pajak mereka untuk mendisiplinkan ‘surplus’ manusia tak bermilik ini dengan kekuatan polisi. Lebih dari 1 juta orang Amerika berada di penjara – jumlah total narapidana terbesar dan perkapita tertinggi di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang mengunggulkan ‘pasar bebas’ memuja filsuf Skotlandia Adam Smith (1723-90), yang menulis buku The Wealth of Nations (1776), sebagai pemikir tentang ‘pasar bebas’. Buku teks standar ilmu ekonomi ini disebut ‘neoklasik’ karena berisi pembaruan ide-ide Adam Smith yang bersama David Ricardo (1772-1823), dianggap sebagai ekonom ‘klasik’. Pembaharuan ini dilakukan dengan menghilangkan pendapat Smith dan Ricardo mengenai teori kerja tentang nilai (labor theory of value), yaitu teori tentang nilai komoditi yang ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang termaktub di dalamnya. Pikiran-pikiran ekonomi “marginalist” yang muncul pada paruh akhir abad ke-19, diwakili oleh ekonom-ekonom seperti W.S. Jevons (1835-82) dan Alfred Marshall (1842-1924), menyatakan bahwa nilai komoditi pada dasarnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan. Dan itulah ajaran utama yang bisa diperoleh dari ilmu ekonomi standar dewasa ini. Adam Smith sebenarnya bukanlah penjelmaan awal ekonom IMF di masa kini. Apabila kita baca karyanya, kita akan melihat bahwa Smith masih tetap mengharapkan negara mendukung kesejahteraan publik dan tidak begitu saja menghilang, seperti yang diinginkan IMF. Ia bahkan berpikir bahwa pedagang, kaum yang hidupnya dari keuntungan, akan menciptakan anarki apabila mereka mengendalikan negara karena mereka terutama dimotivasi oleh kepentingan mereka pribadi dan bukannya kepentingan umum. Ia mengkhawatirkan munculnya anarki pasar, dan kesewenang-wenangan pedagang menjadi prinsip-prinsip pemandu kehidupan sosial. Smith mendukung perkembangan kapitalisme, itu pasti – ia menginginkan buruh menjadi lebih produktif melalui pembagian tenaga dan kemajuan teknologi yang lebih canggih. Tetapi ia ingin supaya pasar dikendalikan secara bijaksana oleh “negarawan”, sedemikian rupa sehingga pasar itu bisa melayani kepentingan sosial yang berguna bagi publik. Ia menyatakan bahwa bukunya merupakan latihan di bidang “ekonomi politik”, yaitu ilmu bagi “negarawan atau pembuat undang-undang” supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Salah satu ajaran Smith yang perlu kita pertimbangkan benar dewasa ini: “Usulan perundangundangan atau aturan perdagangan baru apa pun yang datang dari tatanan ini [para majikan yang hidup dari keuntungan] harus selalu didengarkan dengan kewaspadaan luar biasa, dan tidak pernah boleh diberlakukan sebelum dikaji secara seksama dan mendalam, bukan hanya dengan perhatian yang paling teliti, tetapi juga dengan kecurigaan. Usulan itu datang dari kaum yang kepentingannya tidak pernah sepenuhnya sama dengan kepentingan publik, yang secara umum berkepentingan untuk menipu dan bahkan menindas publik.” Smith mungkin akan terperanjat membaca karya Milton Friedman yang begitu polos berasumsi seakan-akan kepentingan kaum kapitalis berjalan selaras seimbang dengan kepentingan masyarakat luas. Umumnya dipercaya bahwa pada masa depresi mendunia di 1930an pasar di bawah kapitalisme bersifat anarkis. Pasar bergerak mengikuti siklus liar ledakan dan kemerosotan perdagangan. Ketika begitu banyak orang bergantung pada pasar untuk bertahan hidup (menjual tenaga kerja mereka untuk upah dan membeli kebutuhan sehari-hari dengan upahnya) jenis fluktuasi tak terkendali serupa ini menyebabkan penderitaan sosial secara massal. Ekonomi terencana di Republik Sosialis Uni Soviet kemudian tampak sebagai pilihan yang sepenuhnya rasional dan praktis bagi banyak orang pintar karena kinerja kapitalisme yang kacau balau saat itu. Kapitalisme tampak tak bisa bertahan lama kecuali jika pasar dikendalikan oleh aturan-aturan negara. Itulah sebabnya karya ekonom John Maynard Keynes (1883-1946) menjadi penting. Tulisan-tulisannya menunjukkan bagaimana investasi dan pengeluaran negara bisa mencegah keliaran fluktuasi siklus perdagangan dan menjaga supaya kapitalisme bisa lancar bekerja. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi paska PD II di Eropa barat, AS dan Jepang diraih oleh kaum elit ekonomi yang bekerja sejalan dengan ide-ide Keynes. Ide-ide dan praktek Keynesian ditinggalkan pada 1970-an dan 1980-an ketika para kapitalis menganggap bahwa anarki pasar itu hanyalah dongeng masa lalu. Gagasan Milton Friedman meraih pengaruh lebih besar. Di banyak negara maju, industri negara diswastakan dan tunjangan kesejahteraan bagi pengangguran dan kaum miskin dihapus. Negeri-negeri ini memulai peperangannya terhadap kaum miskin. Pertumbuhan pesat jumlah narapidana di AS beranjak pada awal 1980-an. Dalam logika standar para ekonom dewasa ini pilihan yang ada hanyalah antara pasar bebas dan ekonomi terencana, dan pilihan terakhir telah terbukti salah dengan runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Tapi sebenarnya ada lebih dari dua pilihan di atas. Bagi mereka yang selalu berbicara tentang pasar bebas, kita harus mengamati mereka dengan kecurigaan dan bertanya: pasar yang mana? Pasar seperti apa? Kebebasan untuk siapa? Saya akan mengusulkan tiga rekomendasi: Pertama, kita harus berpikir tentang peraturan negara terhadap pasar. Bahkan ekonom neoklasik kelas berat sekali pun menyadari bahwa negeri seperti Indonesia, paling tidak, membutuhkan kontrol terhadap masuk-keluarnya modal asing. Salah satu alasan penting kejatuhan ekonomi pada 1997 adalah cepatnya melayang modal asing yang ditanam di bank dan pasar saham. Rezim Soeharto, berdasarkan saran IMF dan pemerintah AS, menciptakan pasar bebas untuk uang. Tanpa modal domestik yang cukup besar, ekonomi Indonesia bisa diguncang oleh keluar-masuknya modal asing yang tidak diatur. Banyak ekonom setelah melihat krisis di Asia, Meksiko, dan Brazil mempertimbangkan kembali ide-ide Keynes. Kedua, kita harus berpikir tentang perluasan kemampuan rakyat untuk bertahan hidup dengan akses ke sumber daya alam yang tidak dikomoditi. Banyak orang di Indonesia bertahan hidup dalam krisis karena mereka masih bisa memperoleh makanan dari hasil tanah mereka sendiri, mengambil bahan mentah dari hutan, atau dari sungai dan laut. Contohnya: Indonesia sekarang menyelenggarakan pasar bebas untuk industri kayu. Pedagang yang seringkali merangkap sebagai perampok bisa membayar pejabat pemerintah, menyapu bersih hutan yang ada dan mengekspor kayu hasil hutan tersebut. Hutan di Kalimantan dan Sumatra dihancurkan dengan cepat oleh saudagar-saudagar kayu seperti ini sehingga rakyat tak punya lagi akses ke sumbersumber penghidupan di dalam hutan. Pasar bebas di bidang perkayuan ini harus dihentikan. Ketiga, kita harus mengerti bahwa tidak semua keterlibatan negara dalam ekonomi itu buruk. Jika negara yang ada sangat korup, seperti Indonesia, memang tipis harapan akan ada perbaikan dengan adanya intervensi negara. Tetapi negara yang demokratis bisa secara efektif melakukan intervensi dan secara positif menyumbang pada kesejahteraan masyarakat. Apabila pengoperasian negara itu transparan, para pejabatnya pun tidak punya ruang terlalu luas untuk melakukan korupsi. Demokrasi, seperti berulangkali ditekankan ekonom pemenang Nobel, Amartya Sen, merupakan unsur hakiki untuk perkembangan ekonomi justru karena negara memiliki peran penting di dalamnya. Masyarakat Indonesia menginginkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai dan baik. Jelas para pedagang tak akan mampu menyediakan pelayanan seperti ini kecuali bagi segelintir elit yang bisa membayar cukup banyak. Negara harus terlibat dalam penyelenggaraan klinik kesehatan dan sekolah untuk warganya (bahkan Adam Smith mendukung perlunya subsidi negara untuk pendidikan). Dan apabila negara diharapkan terlibat dalam penyediaan pelayanan masyarakat yang vital seperti ini maka negara itu harus demokratis. Mereka yang menuntut “pemerintahan yang bersih” dan “penyelenggaraan negara oleh kaum profesional” secara netral sebagai syarat pemerintahan yang efektif tanpa mengatakan apa-apa tentang demokrasi sebenarnya sudah membohongi publik. Referensi: Friedman, Milton, and Friedman, Rose, Free to Choose: A Personal Statement (New York: Harcourt Brace Jovanivich, 1980) Polanyi, Karl, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (first published 1944; reprint, Boston: Beacon Press, 1957). Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (first published 1776; reprint, Oxford: Clarendon Press, 1976) Wood, Ellen Meiskins, “From Opportunity to Imperative: The History of the Market,” Monthly Review, 46: 3 (July-August 1994). John Roosa, sejarawan yang bekerja di Universitas California, Berkeley, AS.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Arnold Clemens Ap Membangun Budaya Pembebasan IBE Karyanto Keprihatinan dan perjuangan masya rakat Papua adalah keprihatinan dan perjuangan warga manusia yang terus menerus hidup di bawah kekuasaan represif yang mengontrol dan mengendalikan kehidupan harian. Berbagai sikap dan bentuk perlawanan masyarakat Papua, yang kemudan diberi label GPK, GPL dan sebagainya akan menjadi lebih terang kalau dipahami dalam konteks kepentingan pemerintah Indonesia baik pada zaman pemerintahan Soekarno dan terlebih lagi pada masa rezim Orde Baru. Tidak mengherankan kalau gerakan masyarakat Papua yang mengembangkan seni-budaya asli Papua pun dianggap sebagai aksi masyarakat yang potensial mengancam kepentingan pemerintah. Penangkapan dan pembunuhan Arnold Clements Ap, seorang antropolog, penyair dan musisi ternama, pada April 1984 oleh tentara hanyalah satu contoh dari sekian banyak tindakan represi pemerintah Indonesia yang sudah jauh melampaui batas-batas kemanusiaan. Nama Arnold Clements Ap tidak populer di telinga orang Indonesia, tapi nama yang sama sempat membuat penguasa Orde Baru gerah. Ia dijebak lari keluar dari penjara, lalu Kopassandha dikirim untuk membunuhnya di tepi pantai. Seperti di wilayah-wilayah yang tinggi tingkat represi militernya, rakyat Papua sudah bisa menduga apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Arnold Ap, yang begitu setia dan konsisten dengan gerakan kebudayaannya. Bahkan Arnold sendiri pernah kepada teman-temannya menegaskan konsekuensi macam apa yang akan menyertai aktivitasnya. Sekalipun orang-orang pada umumnya dan orang-orang istimewa macam Arnold sudah menduga apa yang akan terjadi, namun hanya rezim penguasa, tepatnya tentara, yang bisa memastikan kapan dan konsekuensi macam apa yang akan menimpa orang-orang yang setia pada perjuangan kemanusiaan. Tak ada yang menduga kalau tentara begitu cepat merenggut nyawa pejuang pembebasan ini. Usianya saat itu baru 38 tahun. Akhir November 1983 Arnold masih dipercaya memimipin rombongan keseniannya untuk menyambut kedatangan tamu, para istri atase perwira militer asing yang dipimpin istri Jenderal L.B. Moerdani, yang berkunjung ke Papua. Arnold sama sekali tidak berpikir kalau kesenian yang dibawakan pada hari itu akan menjadi aktivitasnya yang terakhir dalam seluruh rangkaian gerakan kebudayaan yang dibangun bersama teman-temannya. Keesokan harinya rombongan pasukan berpakaian preman mengambil Arnold dari rumah kediamannya. Tidak jelas Arnold akan dibawa ke mana. Keluarganya hanya diberitahu bahwa Arnold akan di bawa ke satu tempat. Tapi gerombolan penculik terlalu gegabah jika menganggap tidak ada satu pun orang tahu keberadaan Arnold setelah diambil dari rumahnya. Tidak lama berselang harian Sinar Harapan memberitakan peristiwa penangkapan dan penahanan itu. Hanya segelintir orang Indonesia yang bereaksi atas tragedi tersebut, termasuk Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) waktu itu. Dalam pernyataannya ia menggugat supaya penangkapan dan penahanan Arnold Ap diproses sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan YLBHI dan dua tulisan yang diturunkan Sinar Harapan dalam satu minggu terbitannya sudah cukup untuk membuat tentara, tepatnya Kopassus (Kopassandha waktu itu) marah. Sinar Harapan terancam bredel, kalau tidak segera minta maaf dan bersedia mendengarkan “kebenaran” cerita versi tentara. Berita tentang penangkapan dan penahanan Arnold menggerakkan pemuda Papua yang sedang belajar di Jakarta. Ottis Simopiaref dan tiga temannya melancarkan protes ke DPR-RI. Aksi pembelaan terhadap kejadian yang dialami Arnold Ap tersebut membuat pihak intelijen Kopassandha semakin gerah. Pengawasan dan upaya penangkapan terhadap keempat pemuda tersebut semakin intensif. Menyadari keselamatan mereka terancam, keempat pemuda Papua minta suaka pada Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Setelah dua minggu berlindung di sana, mereka berhasil diterbangkan ke Belanda. Sementara itu di Papua, tentara belum juga berhasil mengorek informasi dari Arnold Ap tentang bukti keterlibatannya dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dengan sendirinya tidak ada dasar kuat untuk membenarkan penangkapan dan penahanannya selama berbulan-bulan. Segala cara sudah ditempuh, tapi bukti tetap tak diperoleh. Karena memang sudah menjadi sasaran untuk disingkirkan, maka rencana lain pun mulai disusun. Bukti keterlibatan dan sebagainya menjadi tidak penting; satu-satunya persoalan sekarang adalah membuktikan bahwa Arnold Ap dengan satu atau lain cara pantas dihukum. April 1984 seorang polisi asal Papua berhasil membujuk Arnold Ap dan keempat temannya untuk melarikan diri dari tahanan Polda. Pelarian, lebih tepatnya rencana perburuan, berjalan mulus kecuali bagi dua teman Arnold. Satu memutuskan berpisah di tengah jalan dan kemudian selamat, sementara satunya terbawa ombak ketika harus berenang mencapai perahu yang akan membawa mereka ke suatu tempat. Beberapa hari Arnold Ap dan kedua temannya didamparkan di pegunungan Cylops, sebelum katanya akan dibawa ke tempat yang lebih aman. Selama beberapa hari itu Arnold Ap mendapatkan pasokan makanan yang diantar dengan perahu yang juga dipakai untuk melarikan diri. Selang beberapa hari perahu datang lagi, kali ini bukan makanan yang dibawa melainkan gerombolan pasukan Kopassandha lengkap dengan senjata. Tanpa perlawanan berarti tentara menyarangkan tiga butir peluru di tubuh Arnold. Dalam keadaan luka parah Arnold dibawa dengan perahu menuju Jayapura. Mungkin tidak akan ada yang tahu kematian Arnold kalau saja perawat tidak memeriksa kamar jenazah RSAD Aryoko hari itu. Dengan berani perawat tersebut mengabarkan kematian Arnold Ap kepada teman-temannya. Karena berita sudah menyebar dan masyarakat terlanjur tahu, tentara pun terpaksa menyerahkan jasad Arnold pada keluarganya. Ratusan masyarakat Papua mengiringi kepergian jasad Arnold Ap menuju tempat perisitirahatannya terakhir sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu pujian. Arnold Ap meninggal, tapi perjuangan dan gerakan kebudayaan yang pernah dibangun memberi inspirasi yang terus bergema melampaui sungai, gunung dan lautan. Mambesak Mendesak Pembebasan Kultural Arnold Ap lahir di Pulau Numfor, dekat Biak, pada1945. Ia mengambil bidang studi geografi di Universitas Cenderawasih, dan sangat tekun mempelajari seluk-beluk Papua yang luar biasa kaya. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang tekun. Seorang pembimbingnya, Dr. Malcolm Walker menganggap Arnold sebagai “orang yang punya prinsip” dan konsisten dengan komitmennya untuk belajar memahami dan mengembangkan kebudayaan masyarakatnya. Kesan serupa juga muncul dari beberapa sarjana dari luar negeri dan pejuang HAM Indonesia yang pernah bertemu dengannya. Sementara rekan-rekannya di Papua sendiri menganggap Arnold sebagai perwujudan budaya Papua. Gagasan Arnold untuk mulai membangun strategi gerak kebudayaannya berawal dari langkah sederhana sebagai anak muda. Awal 1970-an Arnold Ap dan beberapa teman mahasiswanya mendirikan group band Manyori (Burung Nuri). Meskipun warna kebarat-baratan masih kental dalam permainan musiknya, namun kelompok yang terdiri dari tiga personil ini – Arnold Ap, Joupi Jouwei dan Sam Kapissa – cukup populer. Atas desakan teman-temannya Arnold kemudian bersedia memberikan pelayanan pada jemaat Gereja Kristen Injil dengan memainkan lagu-lagu rohani di gereja. Perjumpaannya dengan lagu-lagu gereja yang kuat berkiblat pada gaya Eropa mengusik Arnold. Semangatnya sebagai orang Papua menggugah Arnold untuk mencoba menciptakan lagu dan irama musik gereja yang berakar dari kebudayaannya sendiri. Mulailah Arnold bersama dengan teman seniman lainnya, Damianus Wariap Kuri, menggarap musik gereja dalam irama Biak-Numfor. Pada awalnya upaya tersebut mendapat tentangan dari orang-orang tua jemaat Gereja. Bisa dimaklumi karena misionaris Eropa yang membawa agama Kristen masuk ke kawasan Teluk Saerera sebelumnya telah menganggap kafir hampir seluruh aspek budaya Saerera. Namun tentangan tidak berlangsung lama. Dalam waktu yang cukup singkat gerakan pribumisasi musik liturgi gereja mendapat sambutan dan dukungan. Salah satu dukungan kuat datang dari Dr. Danielo C. Ajamiseba, linguis pertama Papua yang baru menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Dukungan berikutnya datang dari para pendeta muda lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan para sarjana lulusan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Perkembangan pribumisasi musik liturgi gereja mendorong Arnold Ap untuk semakin tekun berupaya mengembangkan seni-budaya Papua yang lainnya. Karena minat dan bakatnya di berbagai bidang, ia diangkat menjadi Kepala Museum Universitas Cenderawasih oleh pimpinan Lembaga Antropologi, Ign Suharno. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk mematangkan gagasan dan melahirkan karya-karya kreatif. Perhatian Arnold pada seni budaya Papua pun mulai mengembang keluar dari lintas batas Biak-Numfor dan kawasan Saerera. Perjalanannya penelitiannya ke beberapa kampung di wilayah berbagai suku di Papua digunakan sekaligus sebagai kesempatan untuk mencatat dan merekam lagu-lagu, tarian dan ekspresi kebudayaan rakyat lainnya. Semakin mendalam pengetahuannya, semakin ia tak puas melihat kebijakan dan praktek aparat pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan “asli” Papua. Di satu sisi ia melihatnya sebagai upaya penaklukan. Orang Papua dibiarkan memelihara bentukbentuk kebudayaan yang ada – itu pun sangat terbatas – tapi tidak bisa mengembangkan isi apalagi semangat pembebasan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain ia melihat upaya itu semata-mata untuk menjual kebudayaan Papua, lagi-lagi dengan melepas isi dari bentuknya. Kebudayaan Papua sering dipakai oleh para pembuat film, disaner mode dan sebagainya, sebagai bukti “kebudayaan primitif” di Indonesia. Akibatnya rakyat Papua, khususnya para seniman dan pekerja budaya, seringkali tanpa sadar terseret melayani kepentingan promosi semacam itu dengan menciptakan tarian “asli kreasi baru” yang tidak memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat. Arnold juga prihatin melihat kecenderungan merebaknya lagu-lagu diatonis yang dinilainya jauh dari semangat rakyat Papua yang selalu menyanyikan lagu dalam nada minor. Lebih dari lima tahun Arnold Ap melakukan studi serius tentang seni tari dan musik Papua sebelum akhirnya bersama beberapa temannya memutuskan untuk mempublikasikan musik dan tari hasil studi mereka. Arnold dan teman-temannya pertama kali menampilkan musik dan tari dalam rangka acara peringatan 17 Agustus 1978 yang diselenggarakan di halaman Lok Budaya, Museum Antropologi Universitas Cenderawasih. Pementasan itu kemudian dicatat sebagai tanggal lahirnya komunitas kerja seni-budaya “Mambesak”. Arnold keberatan terhadap gagasan temannya yang mengusulkan untuk mempertahankan nama Manyori dengan alasan burung Nuri merupakan burung suci yang dihormati oleh masyarakat Biak-Numfor saja. Sedangkan Mambesak, yang berarti burung Cendrawasih, merupakan burung suci yang dihormati oleh masyarakat di seluruh Papua Barat. Pilihan nama tersebut jelas memperlihatkan keluasan pemahaman Arnold terhadap kebudayaan Papua di satu sisi, sekaligus memperlihatkan kesadaran perjuangan Arnold yang tidak lagi terbatas pada suku tertentu di sisi lain. Dalam rapat pembentukan pengurus pertama di Agustus 1978, Arnold dipilih sebagai koordinator. Sejak saat itu komunitas seni-budaya Mambesak seakan tak pernah berhenti menyelenggarakan berbagai bentuk pementasan di berbagai wilayah Papua Barat, bahkan pernah diutus sebagai wakil kesenian Papua dalam sebuah festival senibudaya yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun yang sama dengan berdirinya Mambesak, atas usulan Ign. Suharno, Arnold Ap diangkat menjadi penanggungjawab siaran Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra program RRI Jayapura. Siaran tersebut resminya adalah program yang dikelola Universitas Cenderawasih untuk memperkenalkan kebudayaan daerah dan membangkitkan serta mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah. Tapi kemudian, setelah penunjukan Arnold, program tersebut sepenuhnya diasuh oleh gerakan Mambesak. Melalui program radio yang dirancang secara kreatif Arnold membangun kesadaran baru rakyat Papua. Dengan cerdik dan jenaka Arnold sering menyisipkan ajakan untuk lebih mengenali akar budayanya sendiri. Tidak jarang Arnold juga menggunakan program siaran radionya untuk menyebarkan analisa sederhana tentang pengetahuan umum. Sebagai sarjana muda geografi yang tertarik pada persoalan ekologi, Arnold melalui corong radionya berusaha merangsang masyarakat Papua pedalaman untuk menjaga kelestarian alam, hutan. Tak jarang melalui corong yang sama Arnold mengecam kebijakan-kebijakan resmi dan tindakan aparat pemerintah yang sering justru merugikan masyarakat Papua, seperti ketika pemerintah memberikan bantuan beras untuk bantuan kelaparan. Ini tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat Papua yang tidak biasa dan tidak memiliki fasilitas memasak beras. Tiga prinsip yang dijaga Arnold dan berhasil menjadikan program siaran radionya populer di masyarakat, yaitu penggunaan bahasa Indonesia logat Papua sebagai bahasa pengantar, penyajian uraian-uraian pokok tentang unsur kebudayaan Papua serta pengetahuanpengetahuan aktual, dan ketiga penyiaran lagu rakyat dan cerita-cerita jenaka yang berakar pada kebudayaan rakyat suku-suku di bagian utara. Siaran dan lagu-lagu Mambesak yang diputar dalam program radio Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra pun merambah melintasi batas telinga masyarakat Papua. Cukup banyak masyarakat Papua di luar negeri merasa mendapatkan semangat perjuangannya kembali ketika mendengarkan program-program radio yang dibawakan Arnold dan teman-temannya. Tapi sebaliknya para penguasa mulai cemas melihat popularitas program radio dan rekaman lagu-lagu yang dihasilkan Mambesak semakin populer. Kebudayaan Dengan Keringat Sendiri Arnold bukan hanya seorang seniman. Sebagai intelektual ia terkenal cerdas dan tajam melihat bermacam persoalan. Kepribadian yang kuat dan komitmen yang besar pada gerakan rakyat membuat Arnold tak mau tunduk pada berbagai tawaran yang datang dari luar. Ia paham bahwa aksi-aksi kebudayaan hanya mungkin berkembang menjadi gerakan, jika hidup dari dukungan masyararakatnya sendiri, bukan bergantung pada kekuatan lain. Dan mayarakat hanya akan mendukung jika memang merasa memiliki, atau mendapat tempat dalam gerakan tersebut. Di samping melakukan penelitian, bermain di pentas dan membuat rekaman, Arnold pun mencurahkan sebagian tenaganya untuk menggalang dana dari masyarakat sendiri. Gagasan tersebut disambut baik oleh teman-temannya di Mambesak. Mereka kemudian menjajakan kaset yang berisi rekaman lagu-lagu rakyat yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Papua atau lagu Papua garapan sendiri. Dengan menjual kaset Mambesak mengayuh dua pekerjaan sekaligus. Di satu sisi niat menyebarkan kasanah musik dan lagu-lagu rakyat Papua yang sudah mulai banyak ditindih dengan budaya asing bisa berjalan dan di sisi lain Mambesak terbantu untuk menjalankan gerakannya dari hasil penjualan kaset yang sama. Sebuah pekerjaan yang berat karena para aktivis tiba-tiba harus menghadapi kepentingan dagang dari pihak produser yang bahkan sempat memicu ketegangan di antara anggota kelompoknya. Sebelum meninggal, Arnold Ap sempat menyaksikan perkembangan gairah rakyat Papua, yang ingin menghirup kesegaran roh seni dan budayanya sendiri. Kelompok musik Papua bermunculan di mana-mana. Pemakaian pita kaset untuk penyebaran lagu-lagu Papua menjadi semacam revolusi komunikasi tersendiri. Dari sumber yang sama, musik dan lagu tradisi Papua, berbagai kelompok musik mencoba menawarkan bermacam ragam bentuk kepada masyarakat. “Yang satu ingin me-Papua-kan musik populer, sedang yang lain ingin mempopulerkan musiklagu Papua,” kata Sam Kapissa, salah satu tokoh Mambesak yang kemudian mengembangkan aksinya sendiri di luar Mambesak. Revolusi pita kaset mulai terasa menjelang pertengahan 1980an. Bulan-bulan menjelang natal kaset lagu-lagu natal dan gerejani bernapas Papua membanjiri toko-toko kaset. Lagu-lagu natal dan gerejani dari kaset yang senada mulai terdengar di berbagai tempat umum seperti lingkungan kampus, bandara Abepura dan tempat-tempat umum lain. Masyarakat Papua seperti menemukan kembali kepercayaan diri yang selama ini direnggut oleh kekuatan asing. Sejalan dengan perkembangan gerakan kebudayaan yang dipelopori Arnold Ap dan temantemannya di Mambesak, tentara pun semakin khawatir akan kemungkinan menguatnya gerakan pembangkangan dan perlawanan masyarakat Papua terhadap kekuasaan rezim. Memang sejak awal orang Papua bisa memperkirakan bahwa kegiatan Arnold yang begitu berpengaruh akan dilihat sebagai ancaman oleh rezim. Berkembangnya kebudayaan dan kesadaran di kalangan rakyat, adalah ancaman besar karena sulit diukur dan dikendalikan. Aparat intelijen bersusahpayah mencari hubungan Arnold dan kelompok Mambesak dengan OPM atau gerakan perlawanan lainnya. Arnold berulangkali ditahan dan diinterogasi, tapi karena posisinya dalam masyarakat dan perhatian luas dari berbagai pihak, ia pun dilepas kembali. Upaya menemukan “bukti-bukti keterlibatan” pun kandas. Keputusan pun akhirnya datang, Arnold Ap harus disingkirkan. Bukti, alasan dan sebagainya bisa ditentukan belakangan. Aparat bergerak, menangkap, menyiksa lalu membunuh, dan membuat laporannya sendiri. Jerit menagih keadilan dan kemanusiaan pun hilang ditelan perintah-perintah tegas, suara handie-talkie dan letusan senapan yang membunuh Arnold. Arnold Ap meninggal sebagai pejuang kebudayaan Papua. Rakyat menghormatinya sebagai konor yang berarti filsuf atau orang suci yang dipercaya memiliki kharisma dan kekuatan. Sekitar 500 orang hadir dalam pemakamannya yang dijaga ketat oleh aparat. Tubuhnya sudah ditanam, tapi semangatnya meluap-luap ke segala penjuru, beranak-pinak melanjutkan apa yang pernah diperjuangkannya. IBE Karyanto, pekerja pada Jaringan Kerja Budaya dan Rektor pada Universitas Sanggara 'Akar'
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
BERITA PUSTAKA
100 Tahun Bung Karno 6 Juni 1901-2001: Sebuah Liber Amicorum Editor: Joesoef Isak, Penerbit Hasta Mitra, Jakarta, Juni 2001 Liber Amicorum atau kumpulan tulisan mengenai 100 tahun Bung Karno ini ditulis oleh 22 pengarang dari bermacam sudut pandang. Beberapa penulis menekankan pada peranan Amerika Serikat dalam rangka mendongkel kepemimpinan Bung Karno, sebagaimana yang diguratkan oleh Pramoedya Ananta Toer, “Soekarno pernah menyatakan bahwa abad ke 20 adalah abad intervensi, dimana kekuatan-kekuatan adikuasa dengan seenaknya mengaduk-aduk urusan intern pada negeri lain.” Sedangkan penulis lainnya menekankan pada pemikiran Bung Karno serta implikasinya pada proses nation building sebagaimana ditulis oleh Hersri Setiawan, “Bung Karno satu-satunya presiden dari satu negara muda yang menerima 26 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas bergengsi dari seluruh penjuru dunia. Salah satunya dari Universitas Gajah Mada untuk bidang sejarah. Menurut Soekarno, penulisan sejarah Indonesia harus diubah, pertama: sebagai bangsa muda yang baru merdeka, harus menulis ulang sejarah sendiri; kedua, dalam menulis ulang sejarah sendiri itu, orientasi kesejarahan harus dibalik, tidak ke barat tapi ke timur, tidak ke India atau Belanda tapi ke Indonesia sendiri!” Demikian pula Ben Anderson menegaskan “setelah Soekarno meninggal, kehadirannya tetap hidup, tidak ada rivalnya di Asia Tenggara yang dapat menandinginya kecuali almarhum Ho Chi Minh. Harapan yang diberikan Soekarno cukup jelas dibuktikan dengan dukungan luar biasa bagi anaknya Megawati yang sebaliknya tidak punya keistimewaan sama sekali. Buku ini sebagaimana ditegaskan oleh Joesoef Isak, berbeda dengan tulisan lainnya tentang Soekarno, lebih terarah dan menampilkan Soekarno sebagai manusia biasa saja.
Made In Indonesia: Indonesian Workers Since Suharto Pengarang: Dan La Botz Penerbit: South End Press. Cambridge, Massachusetts, 2001 Dinamika baru pergerakan buruh di Indonesia yang muncul pada 1990-an membantu menjungkirkan kebrutalan kediktaktoran Suharto pada 1998. Melalui beberapa wawancara personal dengan para aktivis yang memimpin lahirnya kembali perjuangan untuk hak-hak demokrasi di negeri terbesar keempat di dunia, La Botz menggambarkan pelajaran-pelajaran yang bernilai untuk kaum buruh di Amerika Serikat yang mencoba membangun solidaritas buruh internasional. La Botz membawa kita masuk ke dalam organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik, perjuangan unit-unit kerja serikat-serikat buruh baru dengan perusahaanperusahaan multinasional seperti Nike. Juga memaparkan bagaimana LSM dan kelompokkelompok mahasiswa menempa hubungan dengan kelas buruh. Kekuatan-kekuatan pendapatnya menawarkan harapan terbaik untuk masa depan demokrasi sejati bagi Indonesia.
Dunia Sukab: Sejumlah Cerita Penulis Seno Gumira Ajidarma Penerbit Buku Kompas, Jakarta Juni, 2001 Tentu saja permainan antara fakta dan fiksi ini merupakan pekerjaan rumah yang menarik dalam perbincangan makna, namun tentu bukan itu yang dibicarakan oleh Seno Gumira Ajidarma (SGA). Nama Sukab muncul begitu saja dalam tokoh cerita pendek SGA: Sukab pernah menjadi nama remaja 17 tahun, pemuda parlente, pernah menjadi penggiring bola absurd dan tokoh yang numpang lewat saja, tanpa sempat menjadi sebuah karakter. Sebetulnya Sukab pun pernah mati, bahkan lebih dari sekali. Kumpulan cerita pendek Dunia Sukab dibagi tiga oleh SGA. Dengan kocak SGA menceritakan bagaimana seorang pegawai negeri yang korup terjangkit The Pinoccio Disease. Semacam penyakit hidung panjang yang setiap menit terus memanjang, karena begitu rakus dan mahir mengendus dimana uang yang dapat dikorup. Hal yang juga menarik dari cerita pendek Sukab, SGA berimajinasi mengenai nasib korban, pelaku dari perkosaan Mei 1998 di 2039. Digambarkan anak yang dilahirkan tidak lagi mempunyai identitas dan terus mempertanyakan anak siapa sebenarya. Demikian pula dengan pelaku, yang sulit untuk mengakui kepada anaknya atau istrinya bahwa ia sebenarnya orang yang melakukan perbuatan kriminal. 1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
SUBVERSI MENEGAKKAN IMPERIUM Politik Luar Negeri Amerika Serikat “Amerika harus menghalangi negara lain yang ingin menyaingi kepemimpinan kita atau ingin mengubah tatanan politik dan ekonomi sekarang ini… Kita harus memelihara mekanisme untuk menghambat para pesaing, sekalipun mereka hanya ingin berperan lebih besar secara regional maupun global.” Demikian pernyataan dalam Pedoman Perencanaan Pertahanan yang dikeluarkan Pentagon untuk 1994-99. Sejarah memang membuktikannya. Menurut John Stockwell, mantan pejabat CIA yang kemudian menulis buku tentang pengalamannya, dinas intelijen itu melancarkan sekitar 3.000 operasi rahasia besar dan 10.000 operasi kecil, yang dirancang untuk “merusak, menciptakan destabilisasi di negeri lain dan memaksa pemerintahnya untuk mengikuti kehendak Amerika Serikat”. Hampir semuanya diarahkan kepada negara, pemerintahan dan pemimpin yang kebijakannya bertentangan dengan kepentingan negeri itu. Menurut perkiraannya sekitar enam juta orang tewas akibat operasi-operasi tersebut. Mesin politik luar negeri Amerika Serikat, menurut para pejabatnya sendiri, digerakkan oleh berbagai kepentingan dasar yang dapat dirumuskan sebagai berikut: •Menciptakan dunia yang aman bagi perusahaan Amerika •Meningkatkan pendapatan perusahaan kontraktor senjata dan peralatan militer yang sudah memberi sumbangan besar kepada anggota kongres. •Menghalangi munculnya masyarakat yang bisa menjadi alternatif model kapitalisme. •Memperluas hegemoni politik dan ekonomi seluas mungkin, yang sesuai dengan citranya sebagai “negara adidaya”. Untuk membenarkan tindakannya, Amerika Serikat melancarkan propaganda “jihad melawan komunis internasional” dan memobilisasi kekuatan-kekuatan di negara sasaran untuk terlibat di dalamnya. Setelah Perang Dunia II, pasukan dan dinas intelijen Amerika Serikat berpetualang di lebih dari 70 negara di dunia. Daftar di bawah ini disusun berdasarkan artikel William Blum dalam Z Magazine dua tahun lalu. Sejak penerbitan itu AS masih terus melakukan serangan dan intervensi. Salah satu yang terbaru adalah rencana serangan total ke Afghanistan yang didakwa melindungi pelaku serangan teroris ke New York dan Washington pada11 September lalu. Tiongkok, 1945-49 Dalam perang saudara, AS berpihak pada Chiang Kai-shek melawan gerakan komunis pimpinan Mao Tse-tung, yang selama Perang Dunia menjadi sekutu mereka. AS mengerahkan mantan lawannya, yaitu serdadu-serdadu Jepang yang kalah dalam Perang Dunia, untuk bertempur melawan mantan sekutunya. Chiang Kai-shek kalah dan melarikan diri ke Taiwan pada1949. Italia, 1947-48 Dengan semua muslihat yang ada dalam dunia intelijen, AS melakukan intervensi dalam pemilihan umum untuk menghalangi Partai Komunis keluar sebagai pemenang yang sah. Tindakan ini dilakukan, menurut para pejabatnya, “untuk menyelamatkan demokrasi” di Italia. Partai Komunis akhirnya kalah, dan selama dekade-dekade selanjutnya, CIA bersama perusahaan Amerika terus-menerus melakukan intervensi, mencurahkan dana jutaan dolar dan melancarkan perang psikologis untuk mencegah Partai Komunis berkuasa. Yunani, 1947-49 AS terlibat dalam perang saudara di pihak neo-fasis melawan gerakan kiri Yunani yang berperang melawan Nazi dalam Perang Dunia. Kaum neo-fasis akhirnya menang dan melembagakan sebuah rezim yang sangat brutal. CIA membantunya dengan mendirikan dinas intelijen dalam negeri, KYP. Lembaga ini, seperti polisi rahasia di mana pun, menggunakan berbagai metode kekerasan yang mengerikan, termasuk penyiksaan secara sistematis, untuk menaklukkan lawan-lawannya. Filipina, 1945-53 Militer AS bertempur melawan gerakan kiri (Hukbalahap), yang saat itu sedang bertempur melawan invasi Jepang. Setelah Perang Dunia, AS terus memerangi gerakan itu, dan menempatkan sejumlah presiden boneka, yang berpuncak pada kediktatoran Ferdinand Marcos. Korea Selatan, 1945-53 Setelah Perang Dunia, AS menindas kekuatan progresif kerakyatan dan berdiri di pihak kaum konservatif yang sebelumnya berkolaborasi dengan Jepang. Untuk waktu yang lama negeri itu kemudian dikuasai oleh rezim-rezim yang korup, reaksioner dan brutal. Albania, 1949-53 AS dan Inggris gagal menggulingkan pemerintahan komunis dan menaikkan pemerintahan proBarat yang beranggotakan keluarga kerajaan dan kolaborator dengan kaum fasis Italia dan Nazi. Jerman, 1950-an CIA melancarkan kampanye sabotase, teror, muslihat kotor dan perang psikologis melawan Jerman Timur. Kampanye ini adalah salah satu faktor yang akhirnya menciptakan Tembok Berlin pada 1961. Iran, 1953 Perdana Menteri Mossadegh digulingkan dalam operasi gabungan AS dan Inggris. Mossadegh dipilih oleh mayoritas anggota parlemen, lalu memimpin gerakan untuk menasionalisasi perusahaan minyak milik Inggris, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi di Iran waktu itu. Dengan kudeta itu, Shah Iran kembali dengan kekuasaan absolut dan memulai pemerintahan selama 25 tahun yang penuh penindasan dan teror. Sementara itu industri minyak diserahkan kembali kepada pemilik asing dengan komposisi Inggris dan Amerika masing-masing 40 persen, sementara negeri lainnya 20 persen. Guatemala, 1953-1990 CIA mengorganisir kudeta untuk menggulingkan pemerintahan progresif Jacobo Arbenz yang dipilih secara demokratik. Kudeta itu menjadi awal dari gelombang kekerasan selama 40 tahun, yang penuh dengan pasukan pembunuh (death squads), penyiksaan, penculikan, eksekusi massal dan kekejaman lain yang tak terbayangkan. Diperkirakan 100.000 orang menjadi korban, dan menjadi salah satu babak paling kejam dalam sejarah abad ke-20. Arbenz sebelumnya menasionalisasi perusahaan AS, United Fruit Company, yang memiliki ikatan erat dengan elit penguasa AS. Untuk membenarkan tindakannya, Washington menyatakan Guatemala saat itu terancam serbuan dari Uni Soviet. Suatu hal yang tidak masuk akal karena Uni Soviet tidak memperlihatkan minat terhadap negeri itu, dan bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik. Masalah sesungguhnya di mata Washington, di samping kepentingan melindungi United Fruit Company, adalah ancaman menyebarnya sosial-demokrasi Guatemala ke negeri-negeri lain di Amerika Latin. Timur Tengah, 1956-58 Doktrin Eisenhower menyatakan bahwa AS, “siap menggunakan kekuatan bersenjatanya untuk membantu” negeri mana pun di Timur Tengah yang “meminta bantuan melawan agresi bersenjata dari negeri mana pun yang berada di bawah kontrol komunisme internasional.” Maksud sesungguhnya dari doktrin itu adalah bahwa tak satu pun kekuatan yang akan dibiarkan mendominasi, atau memiliki pengaruh besar di Timur Tengah dan ladang-ladang minyaknya, kecuali Amerika Serikat. Dan siapa pun yang mencobanya, dengan sendirinya adalah “Komunis”. Dengan garis kebijakan ini, AS dua kali berusaha menggulingkan pemerintah di Syria, menggelar show of force pasukan di Mediterania untuk menakut-nakuti gerakan yang menentang pemerintahan pro-AS di Jordania dan Lebanon dengan menempatkan 14.000 tentara di Lebanon. AS juga beberapa kali bersekongkol untuk menggulingkan atau membunuh Nasser di Mesir dan menghancurkan nasionalisme Timur Tengah yang dikembangkannya. Indonesia, 1957-58 Sukarno, seperti Nasser, adalah pemimpin Dunia Ketiga yang tidak disukai oleh AS. Ia dengan tegas memilih netral dalam Perang Dingin dan beberapa kali berkunjung ke Uni Soviet dan Tiongkok. Ia memimpin nasionalisasi perusahaan swasta milik bekas penguasa kolonial Belanda dan menolak menindas Partai Komunis Indonesia yang saat itu memilih jalan legal dan damai, serta mendapat hasil-hasil mengesankan dalam pemilihan umum. Kebijakan semacam itu, di mata AS, akan menyebarkan “pikiran yang salah” bagi pemimpin Dunia Ketiga yang lain. CIA mulai mempengaruhi pemilihan umum dengan uang, merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno, memerasnya dengan sebuah film porno yang palsu, dan bergabung dengan pasukan militer pembangkang untuk melancarkan perang terhadap pemerintah pusat. Namun Soekarno selamat dari semua upaya menghancurkan itu. Guyana, 1953-64 Selama sebelas tahun, Inggris dan AS lagi-lagi berusaha menghalangi seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis untuk menjalankan pemerintahan. Cheddi Jagan adalah seorang pemimpin Dunia Ketiga yang berusaha netral dan independen. Ia dipilih tiga kali dalam pemilihan umum. Walau pandangannya lebih ke kiri dibandingkan Soekarno atau Arbenz, kebijakan pemerintahnya tidak revolusioner. Tapi bagi AS, ia tetap momok yang menakutkan, karena bisa menjadi contoh sukses bagi mereka yang ingin membangun alternatif terhadap kapitalisme. Dengan bermacam taktik – mulai dari melancarkan pemogokan umum, menyebarkan informasi palsu sampai terorisme dengan legitimasi hukum Inggris, Jagan akhirnya berhasil disingkirkan pada 1964. Semuanya dilakukan di bawah perintah langsung John F. Kennedy, mengikuti jejak Eisenhower sebelumnya. Di 1980-an, Guyana menjadi negeri termiskin di dunia. Ekspor utamanya adalah manusia. Vietnam, 1950-73 Petualangan dimulai ketika AS berpihak pada Perancis, bekas penguasa kolonial dan kolaborator Jepang, melawan Ho Chi Minh dan pengikutnya yang bekerjasama dengan tentara sekutu dan menghargai segala dari Amerika. Namun, Ho Chi Minh, adalah orang komunis. Ia menulis sejumlah surat kepada Presiden Truman dan Deplu AS untuk meminta bantuan Amerika untuk mendukung kemerdekaan Vietnam dari Perancis dan menemukan penyelesaian damai bagi negerinya. Semua permintaannya ditolak. Ho Chi Minh menggunakan baris pertama proklamasi Amerika untuk naskah proklamasi negerinya, “Semua orang diciptakan sama. Mereka diberkahi Sang Pencipta dengan…” Tapi semua ini tidak ada artinya bagi Washington. Ho Chi Minh di mata mereka tetaplah seorang komunis. Setelah berperang selama 23 tahun yang berakibat satu juta orang lebih tewas, AS menarik kekuatan militernya dari Vietnam. Kebanyakan orang mengatakan AS kalah dalam perang itu. Tapi penghancuran yang mereka lakukan dengan menyebar racun di tanah dan gen manusia yang akan mendekam selama sekian generasi, Washington berhasil mencapai sasaran utamanya: mencegah munculnya sebuah alternatif pembangunan di Asia. Kamboja, 1955-73 Pangeran Sihanouk adalah salah satu tokoh lain yang tidak mau menjadi antek Amerika. Setelah bertahun-tahun pemerintahan Nixon/Kissinger menyerang pemerintahannya, termasuk merencanakan pembunuhan atas dirinya dan menghujani negeri itu dengan bom di 1969-70, Washington akhirnya berhasil menggulingkan Sihanouk dalam kudeta di 1970. Kudeta itu memberi peluang bagi Pol Pot dan Khmer Merah memasuki gelanggang. Lima tahun kemudian mereka berhasil merebut kekuasaan. Tapi pemboman yang dilakukan AS selama lima tahun telah menghancurkan ekonomi tradisional Kamboja untuk selamanya. Kebijakan Khmer Merah justru menambah kesengsaraan bagi rakyat di negeri yang dirundung malang ini. Dan ironisnya, AS mendukung Pol Pot secara militer maupun diplomatik, setelah Khmer Merah dikalahkan Vietnam. Kongo, 1960-65 Pada Juni 1960, Patrice Lumumba menjadi perdana menteri pertama Kongo setelah merebut kemerdekaan dari Belgia. Tapi Belgia mempertahankan kekuasaannya di propinsi Katanga yang kaya akan mineral. Para pejabat penting dalam pemerintahan Eisenhower memiliki hubungan erat dengan perusahaan-perusahaan yang menguasainya. Dalam upacara kemerdekaan, di hadapan sejumlah tamu asing, Lumumba menyerukan pembebasan politik dan ekonomi bagi negerinya, dan membuat daftar ketidakadilan yang dialami rakyat setempat di tangan penguasa kolonial. Bagi AS, pidato itu cukup sebagai bukti bahwa Lumumba adalah seorang “Komunis”. Sebelas hari kemudian, propinsi Katanga memisahkan diri dan September Lumumba dipecat oleh presiden atas anjuran AS. Januari 1961 ia dibunuh atas permintaan langsung Dwight Eisenhower. Setelah itu Kongo, yang diubah menjadi Zaire, dilanda perang saudara selama bertahun-tahun, yang membawa Mobutu Sese Seko ke puncak kekuasaan. Mobutu bukan orang asing bagi CIA. Ia berkuasa selama lebih dari 30 tahun, dengan tingkat korupsi dan kekejaman yang mengerikan, bahkan bagi para pendukungnya di CIA. Rakyat hidup dalam kemiskinan yang parah di negeri yang kaya akan sumberdaya alam, sementara Mobutu menjadi seorang multimilyuner. Brasil, 1961-64 Presiden João Goulart melalukan kesalahan yang sama seperti pemimpin Dunia Ketiga lainnya. Ia menerapkan politik luar negeri yang independen, membangun hubungan dengan negerinegeri sosialis dan menentang sanksi terhadap Kuba. Pemerintahannya menetapkan hukum yang membatasi jumlah keuntungan yang boleh dibawa perusahaan multinasional keluar dari negerinya. Ia juga menasionalisasi salah satu anak perusahaan ITT dan melancarkan perbaikan di bidang sosial-ekonomi. Jaksa Agung AS Robert Kennedy merasa terganggu karena Goulart membiarkan sejumlah “komunis” memegang posisi penting dalam pemerintahannya. Goulart sendiri sama sekali bukan tokoh radikal. Ia seorang tuan tanah jutawan, dan Katolik taat berkalung medali Bunda Maria di lehernya. Namun, semua itu tidak cukup untuk melindunginya. Pada 1964 ia digulingkan melalui kudeta militer yang melibatkan AS. Sikap resmi pemerintah di Washington waktu itu, “memang disayangkan bahwa demokrasi digulingkan di Brasil… tapi, bagaimanapun, negeri itu berhasil diselamatkan dari ancaman komunisme.” Selama 15 tahun kemudian, rezim militer melembagakan semua ciri yang kemudian dikenal sebagai “model kediktatoran Amerika Latin”: Kongres dibubarkan, oposisi politik ditiadakan sampai nyaris punah, habeas corpus ditiadakan dalam kasus “kejahatan politik”, kritik terhadap presiden dilarang oleh undang-undang, serikat buruh diambilalih oleh agen pemerintah, gerakan protes dihadapi polisi dan militer yang menembaki massa, rumah petani dibakar, para ulama menghadapi represi brutal… penculikan, pasukan pembunuh, dan penyiksaan dalam skala yang mengerikan. Rezim militer menyebut semua itu “program rehabilitas moral” bagi Brasil. Washington mengikuti perkembangan itu dengan gembira. Brasil memutus hubungan dengan Kuba dan menjadi salah satu sekutu terdekat AS di Amerika Latin. Republik Dominika, 1963-66 Pada Februari 1963, Juan Bosch menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis sejak 1924. Ia berhaluan liberal dan anti-komunis, yang menjadi bukti untuk menyangkal dugaan bahwa AS hanya mendukung kediktatoran militer. Sebelum dilantik menjadi presiden ia mendapat perlakuan istimewa di Washington. Bosch teguh pada pendiriannya. Ia menyerukan reformasi agraria, perumahan dengan sewa rendah, nasionalisasi perusahaan, dan membatasi penanaman modal asing yang bersifat eksploitatif, dan kebijakan lainnya yang khas pemimpin liberal Dunia Ketiga. Ia juga sungguhsungguh menegakkan kebebasan sipil: orang Komunis, atau siapa pun yang dicap demikian, dibiarkan bebas kecuali sungguh-sungguh melanggar hukum. Sejumlah pejabat dan anggota kongres AS mulai merasa tidak nyaman dengan rencana-rencana Bosch, dan juga sikapnya yang independen. Reformasi agraria dan nasionalisasi adalah masalah “panas” bagi Washington, yang menurut mereka secara bertahap akan merangkak menuju sosialisme. Sebagian pers AS menuduh Bosch sudah ketularan “penyakit merah”. Pada September, sepatu lars militer berderap dan Bosch digulingkan. Amerika Serikat yang bisa menghalangi kudeta militer di Amerika Latin hanya dengan menunjukkan wajah tidak senang, tidak berbuat apa-apa. Sembilan belas bulan kemudian, pemberontakan terjadi dengan tujuan membawa Bosch yang hidup di pengasingan kembali berkuasa. AS mengirim 23.000 tentara untuk menghancurkan pemberontakan itu. Kuba, sejak 1959 Fidel Castro mulai berkuasa awal 1959. Dewan Keamanan Nasional AS mengadakan pertemuan pada10 Maret 1959. Salah satu agenda pembahasannya adalah kemungkinan mendirikan “pemerintahan lain untuk berkuasa di Kuba.” Setelah itu selama 40 tahun AS melancarkan serangan teroris, pemboman, invasi militer dalam skala penuh, sanksi, embargo, isolasi dan pembunuhan, karena Kuba menjadi ancaman serius dengan menjadi contoh bagi Amerika Latin. Dunia takkan pernah tahu masyarakat apa yang mungkin dibangun Kuba seandainya dibiarkan berkembang bebas, tanpa ancaman senjata dan invasi. Idealisme, visi dan kecakapan berlimpah untuk menjadi model pembangunan yang lain. Tapi kita takkan pernah tahu, dan itulah yang sesungguhnya diinginkan AS. Indonesia, 1965 Setelah perebutan kuasa yang rumit dengan sidik jari AS di mana-mana, Soekarno berhasil digulingkan. Sebagai gantinya muncul Jenderal Soeharto. Pembantaian terjadi terhadap anggota PKI, orang yang dituduh PKI, simpatisan PKI maupun orang yang dituduh berhubungan dengan satu atau lain cara berhubungan dengan komunisme. Suratkabar New York Times menyebutnya, “salah satu pembantaian massal yang paling biadab dalam sejarah politik modern.” Antara setengah sampai satu juta orang diduga terbunuh. Baru kemudian diketahui bahwa kedutaan besar AS menyusun daftar lima ribu “orang Komunis”, dari pimpinan teras sampai kader desa, dan menyerahkannya kepada Angkatan Darat. Daftar itu kemudian dipakai untuk mengejar dan membunuh siapa pun yang tertera di sana. “Sungguh bantuan besar bagi Angkatan Darat. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan mungkin tangan saya juga berlumuran darah,” kata seorang diplomat AS. “Tapi tidak apaapa. Ada kalanya kita harus bersikap keras pada saat yang menentukan.” Chile, 1964-73 Salvador Allende adalah mimpi buruk bagi imperialisme Washington. Tidak ada yang lebih buruk dari melihat seorang Marxis terpilih menjadi presiden, yang menghargai konstitusi dan semakin populer di kalangan rakyat. Kehadirannya mengguncang batu pondasi menara anti-komunis yang dibangun Washington. Doktrin yang dipelihara selama puluhan tahun pun runtuh: bahwa kaum “komunis” yang menang melalui kekerasan dan penipuan, dan mempertahankan kekuasaan dengan teror dan cuci otak. Allende terpilih menjadi presiden 1970, setelah sebelumnya AS terus berupaya menggagalkannya dengan segala cara. CIA dan seluruh mesin politik luar negeri AS melakukan apa saja untuk menggerogoti pemerintahan Allende, khususnya menggalang kemarahan di kalangan militer. Akhirnya pada bulan September 1973, militer menggulingkan pemerintahan kerakyatan dan membunuh Allende. Seluruh negeri ditutup dari dunia luar selama seminggu. Tank dan serdadu berkeliaran di jalan-jalan kota, stadion olahraga penuh dengan orang yang menunggu eksekusi dan tubuh-tubuh para korban ditumpuk di pinggir jalan atau mengapung di sungai. Serdadu menyerang perempuan yang mengenakan celana panjang dengan merobek bagian kakinya, sambil berteriak “Di Chile perempuan pakai rok!” Kaum miskin kembali ke kesengsaraan, dan penguasa di Washington serta lembaga keuangan internasional kembali menikmati aliran uang dari Chile. Lebih dari tiga ribu orang dieksekusi, sementara ribuan lainnya disiksa atau lenyap tak berbekas. Yunani, 1964-74 Kudeta militer terjadi pada April 1967, hanya dua hari sebelum kampanye pemilihan umum dimulai, yang hampir pasti akan membawa pemimpin liberal George Papandreou kembali menjadi perdana menteri. Ia terpilih bulan Februari 1964 dengan dukungan terbesar dalam sejarah pemilihan umum Yunani modern. Gerakan untuk menggulingkannya pun dimulai, sebagai kerjasama militer Yunani dan pasukan serta dinas intelijen AS yang ditempatkan di sana. Kudeta 1967 itu diikuti pemberlakuan keadaan darurat perang: sensor, penangkapan, pemukulan, penyiksaan dan pembunuhan membawa delapan ribu korban dalam bulan pertama. Semua ini dilakukan seiring dengan kampanye “menyelamatkan bangsa dari ancaman Komunis”. Semua pengaruh yang dianggap merusak moral dan subversif menjadi sasaran, termasuk rok pendek, rambut panjang dan suratkabar asing. Di bawah kekuasaan militer kaum muda diwajibkan pergi ke gereja. Tapi penyiksaan adalah yang paling menakutkan dalam mimpi buruk Yunani selama tujuh tahun itu. James Becket, seorang pengacara Amerika yang dikirim ke Yunani oleh Amnesty International, pada Desember 1969 menulis bahwa “perkiraan kasar, tidak kurang dari dua ribu” orang yang disiksa, dengan cara-cara yang sangat mengerikan, seringkali dengan peralatan yang disediakan AS. Becket memberi laporan berikut: Ratusan tahanan di penjara harus mendengarkan pidato Inspektur Basil Lambrou, yang duduk di belakang mejanya sambil yang memperlihatkan simbol merah, putih biru dari barang bantuan AS. Ia berusaha memperlihatkan bahwa perlawanan mereka sia-sia saja. “Kalian bodoh berpikir bisa melakukan apa saja. Dunia ini terbagi dua. Ada komunis di satu pihak dan dunia bebas di sisi lain. Rusia dan Amerika, tidak ada yang lain. Nah, kita ini apa? Amerika. Di belakang saya ada pemerintah, di belakang pemerintah ada NATO, dan di belakang NATO ada Amerika. Jadi kalian takkan menang melawan kami. Kami ini adalah Amerika.” George Papandreou sama sekali bukan seorang yang radikal. Ia seorang liberal yang juga antikomunis. Namun putranya, Andreas yang akan mewarisi kekuasaannya, sedikit lebih ke kiri dari ayahnya dan tidak pernah menyembunyikan keinginan membawa Yunani keluar dari Perang Dingin. Timor Lorosae, 1975-1999 Indonesia menginvasi Timor Lorosae yang baru memproklamasikan kemerdekaannya dari Portugal. Invasi dilancarkan tepat sehari setelah Presiden AS Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger meninggalkan Indonesia. Mereka mengizinkan Soeharto menggunakan senjata buatan AS dalam invasi itu, padahal menurut undang-undang AS sendiri, senjata itu tidak boleh dipakai untuk menyerang. Namun Indonesia adalah alat Washington yang paling berharga di Asia Tenggara. Amnesty International memperkirakan pada 1989, pasukan Indonesia yang mencaplok Timor Lorosae dengan kekerasan, membunuh sekitar 200.000 dari 600.000 sampai 700.000 penduduk. AS dengan konsisten mendukung klaim Indonesia atas Timor Lorosae (tidak seperti PBB dan Uni Eropa), dan menganggap remeh pembantaian yang terjadi. Pada saat bersamaan AS terus menyediakan perlengkapan dan pelatihan bagi militer Indonesia untuk melancarkan tugas mereka. Nikaragua, 1978-89 Ketika gerakan Sandinista berhasil menggulingkan kediktatoran Somoza pada 1978, AS langsung melihat bayangan munculnya “Kuba yang lain” di wilayah Amerika Tengah. Di masa pemerintahan Carter, usaha untuk menyabot revolusi itu dilakukan melalui diplomasi dan tekanan ekonomi. Tapi ketika Reagan mulai berkuasa, metode kekerasanlah yang digunakan. Selama delapan tahun, rakyat Nikaragua diserang oleh pasukan yang diasuh Washington, “gerilyawan” Kontra. Anggotanya direkrut dari jajaran Garda Nasional yang terkenal kejam di zaman Somoza dan para pendukung kediktatoran lainnya. Mereka melancarkan perang total untuk menghancurkan semua program sosial dan ekonomi progresif pemerintahan Sandinista, dengan membakar sekolah dan klinik medis, perkosaan, penyiksaan, meledakkan pelabuhan, pemboman dan berondongan peluru. Ronald Reagan menyebut mereka “pejuang pembebasan”. Grenada, 1979-84 Apa yang membuat negara besar seperti AS melakukan invasi ke negeri dengan penduduk 110.000, jika bukan ketakutannya akan komunisme. Maurice Bishop dan pengikutnya merebut kekuasaan pada 1979, dan sekalipun kebijakan mereka tidak revolusioner seperti halnya Kuba, Washington lagi-lagi didorong ketakutan akan munculnya “Kuba baru”, terutama ketika para pemimpin Grenada mendapat sambutan hangat di negeri-negeri Amerika Tengah. Taktik destabiliasi terhadap pemerintahan Bishop dimulai segera setelah mereka berkuasa dan terus berlanjut sampai tahun 1983. Pada Oktober 1983 AS melakukan invasi dan tidak mendapat perlawanan berarti, walau 135 prajuritnya terbunuh atau terluka. Sekitar 400 orang Grenada menjadi korban bersama 84 orang Kuba, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Akhir 1984 berlangsung pemilu yang dimenangkan oleh calon yang didukung pemerintahan Reagan. Setahun kemudian, sebuah organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa polisi dan pasukan anti-pemberontakan Grenada yang dilatih AS semakin terkenal karena kekejaman, penangkapan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Hak-hak sipil pun semakin digerogoti. April 1989, pemerintah mengeluarkan daftar lebih dari 80 buku yang dilarang masuk. Empat bulan kemudian, perdana menteri membekukan parlemen. Libya, 1981-89 Libya menolak menjadi antek Washington di Timur Tengah. Pemimpinnya, Muammar elQaddafi, terlalu angkuh di mata Washington dan karena itu harus dihukum. Pesawat AS menembak jatuh dua pesawat Libya yang terbang di atas wilayah mereka sendiri. AS juga menjatuhkan bom di negeri itu, yang menewaskan 40 orang, termasuk putri Qaddafi. Di samping itu ada berbagai upaya untuk membunuh pemimpin itu, operasi untuk menggulingkan kekuasaannya, dan kampanye disinformasi, sanksi ekonomi dan menuduh Libya berada di balik peledakan pesawat PanAm 103 tanpa bukti cukup. Panama, 1989 Pesawat pembom AS kembali beraksi. Bulan Desember 1989 sebuah perkampungan di Panama City musnah dan 1.500 orang kehilangan rumah mereka. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari melawan pasukan Panama, dan laporan resmi menyatakan 500-an orang tewas. Sumber lain dengan bukti-bukti cukup menyatakan ribuan orang yang tewas sementara sekitar tiga ribu orang lainnya luka-luka. 23 orang Amerika tewas sementara 324 luka-luka. Dalam wawancara dengan Presiden Bush, seorang wartawan bertanya: “Apakah memang pantas mengirim orang untuk menemui ajalnya seperti itu, hanya untuk menangkap Noriega?” Bush menjawab, “Saya tahu setiap nyawa itu berharga. Tapi saya pikir, semua itu pantas terjadi.” Manuel Noriega selama bertahun-tahun menjadi sekutu dan informan AS sampai akhirnya dirasa tidak berguna lagi. Tapi penangkapan dirinya bukan satu-satunya alasan untuk menyerang. Bush juga ingin mengirim pesan kepada rakyat Nikaragua, yang akan mengikuti pemilihan umum dalam waktu dua bulan, bahwa mereka akan bernasib sama jika kembali memilih Sandinista. Bush juga ingin menunjukkan otot militernya kepada Kongres bahwa AS tetap perlu pasukan siap-tempur yang besar sekalipun Uni Soviet sudah bubar. Dalam penjelasan resminya, Washington mengatakan Noriega ditangkap karena terlibat perdagangan obat bius, sesuatu yang sudah diketahui oleh AS sejak lama dan tidak pernah dipersoalkan sebelumnya. Irak, 1990-an Selama 40 siang dan malam, AS membom salah satu bangsa termaju di Timur Tengah, menghancurkan baik ibukota lama maupun baru. Sekitar 85 juta kilogram bom menghujani rakyat Irak dan menjadi serangan udara paling terpusat dalam sejarah dunia. Senjata uranium pun dijatuhkan, yang membakar manusia, menyebabkan kanker, dan meledakkan kilang minyak serta gudang senjata kimia dan biologi. Pencemaran udara akibat pemboman itu luar biasa, dan mungkin belum pernah terjadi di mana pun juga. Banyak serdadu yang sengaja dipendam hidup-hidup, infrastruktur hancur dengan akibat luar biasa bagi kesehatan. Sanksi ekonomi masih berlanjut yang membuat penderitaan semakin parah; mungkin sekitar satu juta anak meninggal karena serangan ini. Irak sebelumnya adalah kekuatan militer terbesar di jazirah Arab. Dan bagi Washington ini adalah kejahatan. Noam Chomsky pernah menulis, “Telah menjadi doktrin dalam kebijakan luar negeri AS sejak 1940-an bahwa sumber energi yang tiada bandingannya di wilayah Teluk harus dikuasai oleh AS dan negara sekutunya. Tidak satu pun kekuatan setempat yang independen akan dibiarkan tumbuh dan berpengaruh dalam penanganan produksi serta penetapan harga minyak.” Afghanistan, 1979-92 AS mengucurkan dana milyaran dolar untuk membiayai perang menentang pemerintahan berkuasa yang didukung Uni Soviet. Sebelumnya, operasi CIA terus memancing intervensi Uni Soviet yang akhirnya memang dilakukan. AS akhirnya keluar sebagai pemenang, dan kaum perempuan seperti kebanyakan rakyat Afghanistan ada di pihak yang kalah. Lebih dari satu juta orang tewas, tiga juta cacat seumur hidup dan lima juta orang mengungsi, sama dengan separuh jumlah penduduknya. El Salvador, 1980-92 Para pembangkang El Salvador selalu berusaha bekerja di dalam sistem. Tapi dengan dukungan AS, pemerintah terus bermain curang dalam pemilihan umum dan membunuh ratusan orang yang terlibat dalam aksi protes dan pemogokan. Di 1980, para pembangkang mulai angkat senjata dan perang saudara pun terjadi. Secara resmi kehadiran militer di AS di El Salvador terbatas sebagai penasehat. Tapi dalam kenyataan, personel militer AS dan CIA memainkan peran aktif. Sekitar 20 orang AS tewas atau terluka karena pesawat atau helikopter mereka ditembak jatuh ketika sedang melakukan serangan dan terbang di atas daerah pertempuran. Di samping itu ada bukti cukup bahwa AS juga terlibat dalam pertempuran di darat. Perang itu secara resmi berakhir tahun 1992 setelah 75.000 orang tewas dan departemen keuangan AS mengucurkan enam milyar dolar. Jalan bagi perubahan sosial mendasar semakin tertutup. Negeri itu tetap ada di tangan segelintir orang kaya. Orang miskin tetap saja miskin, dan para pembangkang tetap menghadapi pasukan pembunuh di mana-mana. Haiti, 1987-94 Selama 30 tahun kediktatoran keluarga Duvalier berkuasa dengan dukungan penuh pemerintah AS. Jean Baptiste Aristide yang progresif kemudian terpilih menjadi presiden, tapi kembali digulingkan pada 1991 melalui kudeta militer pengikut Duvalier. Washington kemudian bersedia menaikkan kembali Aristide dengan syarat ia tidak akan membuat kebijakan yang menguntungkan orang miskin dan merugikan orang kaya, dan bahwa ia akan berpegang teguh pada doktrin pasar bebas. Yugoslavia, 1999 Hujan bom AS menyeret negeri itu kembali ke zaman pra-industri. Tapi penguasa di Washington mengklaim intervensi itu dilakukan atas dasar “kemanusiaan”. Mudah-mudahan penjelasan di atas bisa membantu kita memahami apa maksud sesungguhnya. 1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Surat Robert S. McNamara tentang Bantuan Militer kepada Indonesia pada 1965
Robert S. McNamara, Menteri Pertahanan AS dari 1964 - 1968, pada masa pemerintahan J. F. Kennedy dan L. B. Johnson
RAHASIA KEMENTERIAN PERTAHANAN WASHINGTON 1 Maret 1967 MEMORANDUM UNTUK PRESIDEN SUBJEK: Efektifitas Bantuan militer AS untuk Indonesia Pengambilalihan kekuasaan Kepresidenan oleh Jenderal Suharto menegaskan perubahan signifikan dalam orientasi politik Indonesia yang telah terjadi selama enam belas bulan terakhir. Perubahan ini dimulai pada 1 Oktober 1965, ketika Angkatan Darat Indonesia, yang dipimpin Jenderal Suharto, menghentikan kudeta yang digerakkan kaum Komunis, dan kemudian berlanjut dengan memusnahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang beranggotakan tiga juta orang sebagai organisasi politik yang efektif. Setelah menghancurkan PKI, Angkatan Darat beralih ke pekerjaan yang lebih sulit, yaitu melucuti kekuasaan politik Presiden Soekarno dan mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia supaya meninggalkan hubungan erat dengan Peking dan menyesuaikan diri dengan negara-negara tetangganya dan Amerika Serikat. Proses ini tampaknya sekarang telah memasuki tahap akhir; Angkatan Darat Indonesia hampir memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pemerintahan Indonesia. Saya percaya bahwa Program Bantuan Militer (MAP) kita untuk Indonesia selama beberapa tahun terakhir memberikan sumbangan yang berarti bagi pembentukan orientasi Angkatan Darat yang anti-komunis, pro-AS, dan mendorong institusi ini untuk bergerak menentang PKI ketika kesempatan itu dihadirkan. Bahwa PKI sesungguhnya sangat menyadari tentangan naluriah ini di dalam tubuh Angkatan Darat diperlihatkan dengan kenyataan bahwa lima dari enam jenderal yang dibunuh PKI pada 1 Oktober yang menentukan itu telah menerima pelatihan di sekolah-sekolah Angkatan Darat AS dan dikenal sebagai para sahabat Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, setelah Angkatan Darat menumpas pemberontakan tersebut, tugas-tugas utama diberikan kepada para perwira yang pernah dilatih di AS. Suharto sendiri tidak pernah dilatih di AS, tetapi tigabelas anggota terpenting dalam jajaran staf-nya, kelompok yang sekarang memerintah Indonesia, menjalani pelatihan di Amerika Serikat dibawah MAP. Menurut penilaian saya, keputusan kita untuk menanam modal sekitar US$ 5 juta untuk memberangkatkan 2.100 anggota militer Indonesia mengikuti pelatihan di Amerika Serikat, dan melanjutkan program, bahkan selama tahun-tahun suram 1963-65 ketika Sukarno mengadakan konfrontasi terhadap Malaysia dan bekerja sangat erat dengan Peking, merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan orientasi elit politik Indonesia yang baru. Jumlah keseluruhan Program Bantuan Militer kita untuk Indonesia dari 1950 hingga 1965 sebesar US$63,2 juta. Sekitar US$59 juta telah diberikan pada 1959-1965. Dua pertiganya (US $40 juta) disalurkan ke Angkatan Darat, termasuk lebih dari 100.000 senjata ringan, 2.000 truk dan kendaraan lainnya, dan peralatan komunikasi taktis. Saat Sukarno memulai konfrontasi terhadap Malaysia pada 1963, kita menghilangkan butir program yang dianggap akan mendukung kemampuan ofensif Indonesia, namun kita tetap menyediakan senjata ringan untuk mendukung kemampuan pengamanan internal Angkatan Darat. Pada 1962 kita memperluas Program Bantuan Militer dengan memasukkan perlengkapan permesinan untuk program aksi masyarakat yang dijalankan Angkatan Darat. Peralatan senilai total US$ 3 juta telah dikirimkan antara 1962 dan 1964. Program aksi masyarakat merupakan buah pikiran Jenderal Nasution (sekarang Ketua MPRS) dan Jenderal Yani (salah satu Jenderal yang dibunuh oleh kaum Komunis pada Oktober 1965). Kedua jenderal ini percaya bahwa Angkatan Darat membutuhkan program yang dapat memperbaiki citranya di mata rakyat Indonesia ketika berhadapan dengan PKI. Aspek lain program aksi masyarakat ini adalah mengirimkan perwira-perwira muda cemerlang dari Angkatan Darat ke Amerika Serikat untuk mengikuti latihan (di Harvard, Syracuse, dan beberapa lembaga lain) yang mempersiapkan mereka menjalankan tanggungjawab manajemen tingkat tinggi. Latihan ini ternyata sangat bernilai ketika Angkatan Darat mengambil kendali pemerintahan. Kita menangguhkan pengiriman peralatan baru ke Indonesia pada September 1964. Pada Maret 1965 kita membatalkan sisa bantuan program, kecuali pelatihan bagi orang Indonesia yang sudah berada di Amerika Serikat. Alokasi sejumlah US$ 23 juta untuk peralatan, jasa, dan pelatihan dibatalkan, dan kemudian dana tersebut ditarik kembali. Kendati demikian, kita mempertahankan hubungan dekat dengan pimpinan Angkatan Darat Indonesia melalui ataseatase militer kita dan Kelompok Penghubung Pertahanan, yang tetap dijaga keberadaannya dengan jumlah staf minimum, bahkan setelah dihentikannya Program Bantuan Militer. Pada September 1966, saat Angkatan Darat telah mengisolasi Sukarno dan secara resmi mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia, kita memulihkan program pelatihan militer untuk para perwira militer (dengan biaya US$ 400.000 untuk tahun fiskal 1967). Tekanan utama dalam pelatihan ini pada peningkatan kemampuan aksi masyarakat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selama seminggu terakhir ini, kita memutuskan untuk menambah dana Program Bantuan Militer untuk tahun fiskal 67 sebesar US$ 2 juta agar tersedia suku cadang untuk peralatan permesinan yang dikirim sebelumnya dan juga beberapa peralatan baru— seluruhnya untuk program aksi masyarakat. Pada tahun fiskal 68 kita merencanakan untuk memberi Indonesia sebesar US$ 6 juta untuk Program Bantuan Militer, terutama untuk mendukung program aksi masyarakat. Agaknya terlalu membesar-besarkan apabila kita mengklaim bahwa bantuan militer dan pelatihan yang kita berikan sepenuhnya berpengaruh terhadap pembentukan orientasi antikomunis Angkatan Darat Indonesia, atau bahkan menjadi faktor utama yang menyebabkan Angkatan Darat Indonesia menentang PKI dan membuat Indonesia meninggalkan orientasi proPeking nya. Namun, saya sangat percaya bahwa program ini, seiring dengan simpati berkelanjutan dan dukungan bagi Angkatan Darat, mendorong para pemimpinnya untuk percaya bahwa mereka bisa memperhitungkan dukungan AS saat mereka menentang PKI dan, kemudian, menghadapi Sukarno. Kebijakan kita yang tegas di Vietnam juga telah berperan dalam membentuk sikap Angkatan Darat yang menguntungkan bagi tujuan kita di Asia Tenggara. Satu setengah tahun yang lalu, Indonesia merupakan ancaman yang menakutkan bagi AS dan Dunia Bebas. Sekarang, harapan itu secara dramatis berubah ke arah yang lebih baik. Pemerintahan Jenderal Soeharto mengemudikan Indonesia kembali ke sosok yang menjanjikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Robert S. McNamara 1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Memerangi Terorisme, Menggerogoti Demokrasi di Indonesia Diambil dari X-URL: http://www.fpif.org/commentary/0109inddem_body.html
John Gershman Pihak yang segera beruntung dari penekanan prioritas pemerintahan Presiden Bush pada perang terhadap terorisme mungkin adalah militer Indonesia. Kekuatan militer inilah yang bermain di belakang penghancuran Timor Lorosae pada 1999 dan berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Papua Barat dan Aceh, begitu juga di daerah-daerah lain di kepulauan Indonesia. Kemungkinan ini muncul dari hasil bincang-bincang antara Presiden Megawati dan Presiden Bush minggu lalu di Gedung Putih. Perbincangan itu sendiri tujuannya untuk melibatkan Indonesia, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dalam peperangan melawan terorisme. Presiden Megawati Sukarnoputri bertemu dengan Presiden George W. Bush minggu ini, dan ia merupakan kepala negara pertama yang mengunjungi Amerika Serikat sejak serangan teroris pada 11 September. Presiden Bush sudah mengundang Megawati sejak akhir Juli lalu setelah dia menduduki jabatan presiden, mengikuti pemberhentian Abdurrahman Wahid. Pertemuan kedua kepala negara ini banyak mengungkapkan bagaimana pemerintahan Bush berniat mengkonsolidasikan koalisi internasional yang baru terbentuk untuk melawan terorisme, terutama di antara negara-negara berkembang. Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya ini karena posisinya sebagai negeri demokratik berpenduduk Muslim terbanyak dan meningkatnya peran politik organisasi-organisasi Islam sejak runtuhnya rejim Orde Baru pada 1998. Ada pula dugaan bahwa beberapa kelompok Islam radikal di Indonesia berkaitan dengan organisasi Osama bin Laden, Al Qaeda. Strategi Bush tampaknya merupakan campuran antara bantuan dan hubungan perdagangan yang dikombinasikan dengan penguatan hubungan bilateral antar institusi militer. Komitmen Presiden Bush di bidang ekonomi melibatkan: paling tidak $130 juta dalam bentuk bantuan bilateral untuk tahun fiskal 2002 (terutama untuk reformasi hukum), $10 juta untuk bantuan kepada pengungsi internal (IDPs), $5 juta untuk upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi di propinsi Aceh yang hancur lebur oleh pertempuran, $2 juta untuk membantu pemulangan pengungsi di Nusa Tenggara Timur, dan $10 juta untuk pelatihan polisi. Selanjutnya, pemerintahan Bush akan menyiapkan $100 juta keuntungan tambahan di bawah peraturan Generalized System of Preferences (GSP) yang memungkinkan 11 produk tambahan memasuki pasar AS tanpa pajak. Akhirnya, Presiden Bush mengumumkan bahwa tiga badan keuangan perdagangan – the ExportImport Bank, Perusahaan Investasi Swasta Luar Negeri (OPIC), dan Badan Perdagangan dan Pembangunan AS – telah mengembangkan ikhtiar gabungan di bidang keuangan dan perdagangan untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Tiga badan ini akan bertanggungjawab untuk menyediakan sebanyak $400 juta untuk mendorong perdagangan dan investasi di Indonesia, terutama di sektor gas dan minyak bumi. Upaya-upaya di bidang ekonomi ini boleh dikatakan tak terlalu besar, dan kebijakan makroekonomi Indonesia masih tetap di bawah pengawasan Dana Moneter Internasional (IMF). Penekanan pada reformasi hukum paling tidak dinyatakan sebagai target yang penting. Sebuah Laporan Survey terbaru tentang Persepsi Warga Negara terhadap Sektor Keadilan di Indonesia (Survey Report on Citizens’ Perceptions Of The Indonesian Justice Sector) dari Asia Foundation dan AC Nielsen (http://www.asiafoundation.org/pdf/IndoLaw.pdf) mengungkapkan beberapa temuan yang menggelisahkan tentang sebuah negeri yang berupaya membangun institusi untuk sistem demokrasi yang rapuh. Lebih dari separuh orang dewasa di Indonesia tidak bisa memberikan satu contoh pun tentang hak yang mereka miliki. Lebih dari 60% responden menyatakan polisi mudah saja meminta uang suap untuk mengambil tindakan terhadap apa pun, sementara 30%-35% berpikir bahwa pengadilan hanyalah untuk mereka yang kaya dan merupakan tempat “berbahaya” untuk mencari keadilan. Namun, bahayanya adalah, upaya menegakkan hukum, menjalankan reformasi hukum, dan menghormati hak-hak asasi manusia akan digerogoti oleh meningkatnya dukungan untuk dan kerjasama pemerintah AS dengan militer Indonesia. Masalah utama dalam agenda pemerintah AS di pertemuan tersebut adalah hubungan bilateral militer. Beberapa laporan terbaru dari Dewan Hubungan Luar Negeri dan Rand Corporation, keduanya dipublikasikan beberapa saat sebelum tragedi 11 September, menyarankan supaya pemerintahan Bush memperkuat kerjasama dengan Indonesia secara umum dan militer Indonesia secara khusus. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memerangi peningkatan pengaruh kelompok-kelompok Islam radikal, sekaligus mempersiapkan pembangunan basis pertahanan yang kuat untuk menghadapi Republik Rakyat Cina di wilayah Asia Tenggara. Laporan Dewan Hubungan Internasional, Amerika Serikat dan Asia Tenggara: Agenda Kebijakan untuk Pemerintahan Baru ini patut diperhatikan karena ia dirancang oleh Dov Zakheim, perancang Pentagon pada masa pemerintahan Reagan, yang sekarang bekerja di Pentagon [Gedung Pertahanan Militer AS, ed.]. Keterlibatan militer Indonesia dalam pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan pembantaian di Timor Lorosae segera setelah pelaksanaan referendum untuk kemerdekaan pada 1999 telah mendorong Kongres AS [parlemen, ed.] untuk mempertegas pembatasan yang sudah ada dalam hal kerjasama bilateral militer. Undang-undang yang disahkan Kongres saat itu membatasi penjualan senjata dan pelatihan militer sampai sejumlah kriteria dipenuhi, termasuk peningkatan kontrol sipil terhadap kegiatan militer, transparansi lebih luas dalam hal pembiayaan militer, dan tanggung-gugat pejabat militer yang menyepakati tindakan pelanggaran HAM. Pejabat Sekretariat Negara dalam pemerintahan Bush mengakui bahwa militer Indonesia masih harus memenuhi kriteria dasar tersebut, dan dalam banyak hal, situasi di Indonesia sebenarnya memburuk. Misalnya, beberapa perwira yang memegang posisi pemberi komando di Timor Lorosae pada 1999 bukan saja belum dibawa ke pengadilan, tetapi justru mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Selain itu, ada problem serius dengan transparansi anggaran militer. Sejumlah ahli memperkirakan bahwa hanya 25-30% anggaran militer didapatkan dari dana pemerintah, sedangkan sisanya diperoleh melalui “pemajakan” terhadap pengerukan sumber daya alam, uang suap, dan bentuk-bentuk pembiayaan “informal” lainnya. Pelanggaran HAM semakin meningkat di Aceh dan Papua Barat, wilayah-wilayah dimana gerakan yang menuntut pemisahan kedaulatan cukup kuat. Namun, pemerintahan Bush mengumumkan kemarin beberapa keringanan dalam pembatasan terhadap hubungan bilateral di bidang militer antara Indonesia dan Amerika. Kendati pihak eksekutif belum meminta Kongres AS untuk mencabut pembatasan terhadap penjualan senjata dan pelatihan, pemerintahan Bush sudah mengambil kebijakan terpisah di bagian lain. Walaupun ada bukti terus-menerus bahwa militer masih bisa bertindak dengan kekebalan hukum (impunity), Presiden Bush dan Megawati bersepakat untuk: ●
●
●
●
memperluas hubungan sederhana dan memulihkan pertemuan teratur antara militer Indonesia dan AS untuk mendukung upaya Indonesia melaksanakan reformasi dan profesionalisasi militer. Kegiatan-kegiatan yang berlibat di dalamnya antara lain partisipasi Indonesia dalam berbagai konperensi, latihan multilateral, pertukaran pendapat dalam soal-soal seperti reformasi militer, hukum militer, investigasi, pembiayaan dan transparansi anggaran, termasuk pula operasi gabungan untuk penanggulangan masalah kemanusiaan dan pemberian bantuan kemanusiaan. menyelenggarakan Dialog Keamanan secara bilateral di bawah pengawasan menteri pertahanan non-militer dari kedua negara untuk mendorong “peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam hal pertahanan dan keamanan di Indonesia”. meminta Kongres AS menganggarkan $400.000 untuk mendidik masyarakat sipil di Indonesia tentang masalah-masalah pertahanan melalui program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional yang diperluas [Expanded International Military Education and Training, E-IMET]. mencabut embargo terhadap penjualan komersial barang-barang pertahanan yang tak mematikan ke Indonesia, dengan syarat setiap permintaan individual harus dipelajari kasus demi kasus, sesuai dengan praktek standar yang diberlakukan di Amerika.
Pembenaran untuk peningkatan hubungan militer ini diajukan oleh Rand Corporation [sebuah lembaga konsultan ternama di AS, ed.], yang berpendapat bahwa “hubungan dengan militer Indonesia akan meningkatkan kemampuan Amerika Serikat untuk mempromosikan model demokratik profesionalisme militer di Indonesia”. Klaim ini jelas bermasalah – jika keterlibatan AS dengan militer Indonesia memang begitu kondusif untuk tumbuhnya profesionalisme, apa hasil hubungan dekat mereka selama tiga dekade di bawah pemerintahan Orde Barunya Soeharto? Seperti yang dinyatakan dalam laporan International Crisis Group pada Juli 2001, “hubungan militer belum pernah efektif sampai saat ini dalam menghasilkan militer Indonesia yang memenuhi standar kekuatan yang modern, profesional, di bawah kendali orang sipil atau pun mendorong stabilitas jangka panjang di Indonesia.” Catatan HAM untuk Megawati pun mengandung kelemahan. Sebagai seorang nasionalis yang gigih, ia menentang referendum di Timor Lorosae yang membawa negeri itu ke kemerdekaannya. Ia berhubungan cukup dekat dengan militer, sambil memberi tempat pada empat jendral purnawirawan dalam kabinetnya. Ia sudah mengambil beberapa tindakan permulaan untuk menjawab tuntutan penentuan nasib sendiri dari penduduk Aceh dan Papua Barat. Salah satu undang-undang yang sudah ditandatangani Megawati sebagai presiden adalah Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan undang-undang serupa untuk Papua Barat sedang dipertimbangkan oleh parlemen Indonesia. Kedua usulan perundang-undangan itu dipandang tidak memadai di wilayah masing-masing, dan represi meningkat sejak Megawati menjadi presiden. Sebelum 11 September paling tidak usulan untuk memperkuat kembali hubungan militer Indonesia-AS ditentang oleh beberapa tokoh kunci di Kongres dan kelompok-kelompok HAM karena terus berlangsungnya pelanggaran HAM oleh militer Indonesia, dan bertahannya kekebalan hukum di kalangan pejabat tinggi militer Indonesia yang diduga bersepakat dengan pelanggaran HAM di Timor Lorosae dan di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya sekarang apakah semangat kerjasama antar dua negara yang menandai periode sejak serangan teroris ke AS tersebut akan meluas sampai ke upaya pemerintahan Bush memperkuat militer yang bisa menggerogoti nilai-nilai utama kebebasan dan demokrasi? Padahal perang terhadap terorisme ini konon untuk menegakkan kebebasan dan demokrasi. John Gershman <[email protected]> adalah salah satu direktur program Hubungan Global di organisasi Interhemispheric Resource Center dan editor Asia/Pacific untuk Foreign Policy in Focus.
1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Seabad Perlawanan di Filipina Dominasi AS di Filipina dipicu oleh perang melawan Spanyol sejak akhir abad ke-19. Sementara pemerintah AS mengobarkan pembebasan Filipina dari penjajahan Spanyol, rakyat melihatnya sebagai invasi baru untuk mengganti penguasa yang satu dengan yang lain. Sejak pergantian abad, ketika AS berhasil mengalahkan Spanyol dan mengambilalih kekuasaan, gerak perlawanan pun dimulai dan mencatat nama-nama seperti Bonifacio dan Hukbalahap. Di 1970-an, gerakan menentang intervensi AS semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya perlawanan terhadap kediktatoran Marcos. Seiring dengan kejatuhan Marcos, kesempatan untuk menghimpun kekuatan yang lebih luas semakin terbuka, dan menjadikan kehadiran pangkalan AS di Subic Bay dan Clark sebagai sasaran. Di 1986 gerakan itu mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan referendum tentang kehadiran pangkalan. Sekitar 25 juta orang dengan hak pilih memberikan suara dan hasilnya 76% di antaranya menolak pangkalan militer AS. Mereka juga mendukung pasal-pasal yang menjunjung perdamaian dan pernyataan Filipina sebagai daerah bebas nuklir dalam konstitusi yang baru. Momentum berikutnya adalah perundingan pemerintah AS dan Senat Filipina untuk memperpanjang kontrak pangkalan di negeri tersebut pada 1991. Sebelumnya tidak pernah ada kesulitan apa pun karena Senat Filipina sangat konservatif dan mendukung segala yang diinginkan AS dari mereka. Tapi situasi sudah berubah. Demonstrasi besar terjadi di manamana. Dalam waktu beberapa hari gerakan perdamaian berhasil menghimpun ratusan ribu orang di depan gedung Senat Filipina untuk menentang perpanjangan kontrak tersebut. Di bawah desakan yang hebat, akhirnya Senat memutuskan untuk menolak perpanjangan itu. Pemerintah Filipina memberi waktu satu tahun kepada AS untuk menarik puluhan ribu tentara beserta senjata dan peralatannya. Simbol kekuasaan AS di wilayah itu pun ditutup. Semua itu tentu membuat pemerintah AS yang selalu menganggap para penguasa di Filipina sebagai adik kami yang berkulit coklat [our brown little brothers], jengkel. Skema baru pun diluncurkan, yakni Perjanjian Kunjungan Pasukan [VFA, Visiting Forces Agreement], yang mengatur “kunjungan” pasukan AS ke Filipina lengkap dengan segala hak istimewa yang mereka peroleh di masa lalu. Seorang pejabat AS dalam laporan rahasianya tanpa ragu mengatakan, “kesepakatan itu terutama untuk melayani dan melindungi AS. Pentagon dan Kamp Aguinaldo akan membungkus itu dengan menyebut “keuntungan” bagi Angkatan Bersenjata Filipina dari kesepakatan itu, seperti pelatihan dan peralatan.” Pada 1999 kesepakatan itu diratifikasi oleh Senat dan mengundang protes dari berbagai kalangan. Para veteran gerakan anti-pangkalan bersekutu dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari gerakan buruh dan petani, perempuan, pelajar dan mahasiswa, serta kalangan intelektual membentuk Junk VFA Movement. Ada beberapa alasan yang melandasi protes ini: ●
●
●
●
●
●
VFA membiarkan militer AS menggunakan 22 pelabuhan dan semua landasan pesawat di seluruh Filipina tanpa batas. VFA menyerahkan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh personel militer AS di Filipina kepada sistem peradilan militer AS sendiri. Keputusan ini tentu akan membawa kembali perlakuan sewenang-wenang yang dihadapi rakyat Filipina, seperti kekerasan seksual dan perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak, dan bahkan pembunuhan seperti yang berulangkali terjadi ketika pangkalan AS masih berdiri. VFA melanggar prinsip kedaulatan Filipina sebagai bangsa dengan menghalangi wewenang untuk menerapkan pajak, meminta paspor dan surat izin mengemudi prajurit AS, meninjau kapal-kapal pengangkut serta fasilitas milik AS untuk memastikan bahwa segalanya dilakukan sesuai dengan hukum. VFA akan menyuburkan prostitusi, pengunaan narkoba dan berbagai persoalan sosial serta lingkungan hidup yang pernah terjadi dalam sejarah kehadiran militer AS di Filipina. VFA akan kembali menjadikan Filipina sebagai pangkalan AS untuk melancarkan perang dan serangan militer ke berbagai negara, seperti yang terjadi di masa lalu ketika AS menyerang Tiongkok, Uni Soviet, Korea, Indonesia, Kamboja dan Irak dari basis-basis mereka di Filipina. VFA akan membuka jalan bagi militer AS untuk kembali mendukung kelas penguasa yang reaksioner seperti yang terjadi di masa kediktatoran dan akan menindas gerakan rakyat demokratik.
Keputusan Senat itu dianggap melanggar konstitusi dan juga segala pencapaian setelah kediktatoran Marcos berakhir. Gerakan protes mulai menjalar ke AS sendiri yang melibatkan gerakan solidaritas dan perdamaian di negeri itu. Perjuangan terus berlanjut. (Tim Media Kerja Budaya) 1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Organisasi ini dibentuk tahun 1994 di Marrakesh setelah negosiasi panjang mengenai perdagangan dunia yang dikenal dengan sebutan Putaran Uruguay. Beranggotakan 137 negara, organisasi ini menjadi forum untuk membicarakan kesepakatan dagang internasional, mengawasi dan menegakkan pelaksanaannya. Dalam Putaran Uruguay, negara-negara secara bertahap diminta mengurangi hambatan tarif demi kemajuan perdagangan. Pembentukan WTO memuluskan agenda perusahaan raksasa untuk menghapus semua hambatan bagi perdagangan internasional. Negara-negara dituntut menghapus semua undang-undang dan peraturan yang bersifat melindungi pasar, menghambat arus modal dan barang. Jika semula perusahaan raksasa selalu menjadikan negara Dunia Ketiga sebagai sasaran – antara lain karena dikenal korup atau mudah dibeli – maka dengan WTO sasarannya adalah semua pemerintahan dan lembaga yang melindungi buruh, konsumen, perempuan atau lingkungan hidup. Semua pertimbangan perlindungan dihapus, dan diganti dengan prinsip “keuntungan apa yang bisa didapat”. Sekarang ini WTO mulai berfungsi sebagai pengadilan internasional untuk menyelesaikan perselisihan dagang antarnegara. Masalahnya pengadilan ini jauh dari keadilan, karena doktrin neoliberal tentang perdagangan bebas adalah hukum dasarnya dan para petugas pengadilan tidak lain adalah kaum profesional yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan untuk membela kepentingan mereka. Dalam setiap kasus yang dibawa ke pengadilan ini, kepentingan perusahaan selalu menang dan pemerintahan serta rakyat menjadi korban. Misalnya dalam sengketa antara industri perikanan internasional melawan pemerintah AS yang menggunakan hukum perlindungan satwa langka, sengketa industri minyak Venezuela melawan Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat, dan banyak lainnya. Indonesia saat ini adalah anggota WTO dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melemahkan kekuatannya sendiri dan masyarakat tentu saja, demi kepentingan dagang dan cari untung. (fn) ●
Globalisasi di Internet
●
Dalam Bahasa Mereka Sendiri
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
GLOBALISASI DI INTERNET Diskusi tentang globalisasi sudah cukup lama disiarkan melalui jaringan Internet. Ratusan situs didirikan untuk bertukar pikiran, menyampaikan berita dan informasi tentang segala aspek globalisasi. Jumlahnya terus membengkak dan kadang membuat para pengguna kewalahan dan angkat tangan. Berikut beberapa situs terpilih yang berhasil dihimpun oleh redaksi MKB. Hampir semuanya adalah portal informasi (information gateway) yang menghubungkan pengguna dengan ratusan dan bermacam sumber informasi lainnya. Selamat mencoba.
Corporation Watch. Perhatian utamanya adalah perilaku perusahaan raksasa yang menguasai perekonomian dunia. Situs dibagi ke dalam beberapa topik dan ditata dengan baik. Memuat banyak artikel dan tulisan mengenai globalisasi, lembaga keuangan internasional dan masalah-masalah yang ditimbulkan. Alamat: www.corpwatch.org Focus on the South. Melihat globalisasi dari perspektif Dunia Ketiga. Situs ditata dengan menarik dan mempermudah orang mendapatkan informasi yang diinginkan. Banyak artikel dan tulisan lain dari intelektual-aktivis Dunia Ketiga seperti Vandana Shiva, Arundhati Roy dan Walden Bello. Alamat: www.focusweb.org Peoples’ Global Action. Situs aktivis Dunia Ketiga yang menentang globalisasi neoliberal dalam berbagai bahasa. Memuat berita aksi dan gerakan perlawanan di negara-negara Selatan, berikut pernyataan dan dokumen, serta link ke berbagai organisasi perlawanan. Alamat: www.agp.org Robinsón Rojas Archive. Situs ini didirikan seorang akademisi, yang memuat banyak informasi tentang globalisasi dan tata ekonomi dunia. Penataan situsnya tidak terlalu baik, karena banyak informasi yang ditampilkan langsung di halaman awal, sehingga cenderung membingungkan. Namun, koleksi tulisan, laporan dan dokumentasinya sangat berguna. Alamat: www.rrojasdatabank.org War on Want and Globalization. Melihat globalisasi dari perspektif rakyat pekerja. Banyak informasi mengenai dampak globalisasi neoliberal terhadap buruh di berbagai sektor dan negara. Link ke situs-situs organisasi rakyat pekerja lainnya sangat berguna. Alamat: www.globalworkplace.org Z-Net. Situs progresif yang sangat besar, dengan informasi mengenai berbagai masalah dari perspektif progresif. Di samping analisis tentang situasi sekarang juga memiliki seksi tentang alternatif terhadap globalisasi. Arsip artikel dan tulisannya patut dikunjungi. Alamat: www.zmag.org Bahan dalam bahasa Indonesia sementara ini masih sangat terbatas. Beberapa artikel terjemahan dan tulisan sendiri tersebar di berbagai situs dan belum ada upaya untuk mengumpulkannya. Tapi ada beberapa situs yang dapat membantu globalisasi dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Down to Earth. Memproduksi lembar fakta dan berita dalam bahasa Indonesia. Perhatian utamanya adalah lingkungan hidup, tapi dilihat dalam perspektif ekspansi globalisasi neoliberal. Lembar fakta mengenai lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan ADB sangat berguna. Ada beberapa link yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan. Alamat: www. gn.apc.org/dte E-Che’s Page. Bagian dari situs yang dikelola oleh Edi Cahyono. Memuat beberapa artikel dan pamflet dalam bahasa Indonesia mengenai lembaga keuangan internasional dan neoliberalisme. Arsip mengenai sejarah Indonesia dan masalah perburuhan juga membantu. Alamat: www.geocities. com/edicahy Indo-Marxist. Situs ini memuat tulisan mengenai neoliberalisme dan perkembangan globalisasi dari perspektif kiri. Di samping itu ada arsip besar karya klasik dalam bahasa Indonesia. Alamat: http:// members.xoom.com/indomarxist/
●
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
●
Dalam Bahasa Mereka Sendiri
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
DALAM BAHASA MEREKA SENDIRI Kadang sukar dipercaya bahwa kesengsaraan di dunia sekarang adalah hasil karya manusia. Media massa selalu menampilkan para elit penguasa sistem sebagai kumpulan manusia santun, yang ramah dan baik hati. Tapi, tidak selamanya orang bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Berikut beberapa kutipan yang dapat membuka mata untuk melihat orang seperti apa yang sesungguhnya menggerakkan dan merayakan globalisasi kesengsaraan ini. “Jika dunia seperti sebuah pasar besar, maka semua pegawai akan bersaing dengan semua orang di dunia yang mampu melakukan pekerjaannya. Kita tahu ada banyak orang seperti itu, dan umumnya mereka itu lapar.” (Andrew Grove, Presiden Intel Corp. dalam bukunya High Output Management) “Ini di antara kita saja. Apa tidak lebih baik jika Bank Dunia menganjurkan pembuangan limbah industri yang kotor lebih banyak ke negara berkembang? Dalam logika ekonomi membuang limbah beracun ke negeri berpenghasilan rendah bukan tindakan tercela dan kita harus berani menghadapinya. Saya selalu berpikir bahwa Afrika yang jarang penduduknya, tentu juga sedikit polusinya; pencemaran udara di sana masih sangat rendah dibandingkan Los Angeles atau Mexico City. Dan itu tidak efisien.” (Lawrence Summers, Wakil Sekretaris Bank Dunia, dalam sebuah memo internal, 1991) “Hanya sedikit kecenderungan yang dapat menggerogoti landasan dasar masyarakat kita yang bebas. Salah satunya adalah jika kita membiarkan para pemimpin perusahaan memikul tanggung jawab sosial lain di luar mengeruk uang sebanyak mungkin bagi para pemegang saham mereka.” (Milton Friedman, dalam bukunya Capitalism and Freedom) “Masyarakat apa yang tidak mengenal keserakahan? Masalah tata sosial sekarang adalah bagaimana menciptakan sistem di mana keserakahan tidak begitu menyakitkan; dan itulah kapitalisme.” (Milton Friedman dalam majalah Playboy, 1973) “Saya tidak tahu satu pun produk yang ditemukan oleh laboratorium atau perusahaan raksasa. Bahkan alat pencukur listrik dan tempat pemanas bukan berasal dari sana. Perusahaan raksasa selama ini hanya bergerak masuk, membeli semuanya dan menghisap para pencipta yang kecil.” (John Molloy, wakil presiden General Electrics, dalam bukunya Molloy’s Live for Success, 1983) “Kekuatan kapitalisme untuk menjembatani kesenjangan antara yang kaya dan miskin memang luar biasa. Dan saya pikir, dari tahun ke tahun, kesenjangan itu semakin kecil.” (Bill Gates, pimpinan Microsoft, 1997. Saat setengah penduduk dunia hidup dari upah $2 per hari, Gates berpenghasilan $96 setiap detik!) “Saya tidak tahu mengapa industri farmasi terus dituntut untuk berbuat [baik]. Tak seorang pun menuntut Renault memberi mobil kepada orang yang belum punya mobil.” (Bernard Lemoine, direktur asosiasi industri farmasi Perancis, Januari 2000)
●
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
●
Globalisasi di Internet
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Indymedia, Membangun Media Gerakan Media komersial adalah senjata ampuh dalam globalisasi neoliberal, khusus nya untuk membentuk citra buruk setiap usaha perlawanan. Untuk menghadapi itu dalam aksi protes di Seattle bulan November 1999, jurnalis-aktivis dan pekerja media membentuk Independent Media Center (IMC) yang lebih dikenal dengan sebutan Indymedia. Sejak saat itu jaringan ini dikelola secara kolektif oleh aktivis, jurnalis independen, teknisi dan pekerja media. “Kami membantu rakyat yang terus bekerja membuat dunia lebih baik, di tengah distorsi media komersial dan ketidakinginan mereka untuk meliput usaha-usaha pembebasan manusia,” bunyi pernyataan di situs mereka. Tugas utamanya adalah menjadi clearinghouse informasi yang menyediakan laporan dari lapangan, foto, rekaman suara dan video, yang kemudian disiarkan melalui Internet dan saluran televisi publik. Jaringan Internet adalah saluran utamanya, dan dalam waktu kurang dari setahun situs Indymedia menjadi salah satu sumber paling populer untuk mengikuti berita-berita tentang aksi anti-globalisasi di seluruh dunia. Jaringan media ini mengutamakan desentralisasi dan bersifat otonom. Setiap kota dan komunitas didorong untuk menciptakan “pusat kegiatan” sendiri, lalu menghubungkannya dengan “pusat-pusat” yang lain. Saat ini sudah ada ratusan pusat semacam itu di seluruh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Meksiko, Cekoslowakia, Afrika Selatan, Belgia, Perancis, Italia dan setiap waktu terus bertambah seiring meningkatnya gelombang protes anti-globalisasi di seluruh dunia. Dana dan bantuan teknis untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan di masing-masing pusat diperoleh dari sumbangan pribadi dan beberapa lembaga yang bersimpati seperti Free Speech TV, Paper Tiger TV, ProtestNet, Radio for Peace International, Public Citizen, FAIR, puluhan stasiun televisi dan radio komunitas lainnya dan organisasi pekerja media. ●
2000, Tahun Perlawanan
●
Mengadili Globalisasi
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
2000, Tahun Perlawanan Peralihan milenium ini menjadi mimpi buruk bagi para penguasa dunia. Hampir semua pertemuan penting dihadang oleh gerakan protes yang melibatkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu negara. Sementara itu di negara-negara Selatan berlangsung ratusan aksi, mulai dari demonstrasi damai sampai pemogokan massal di berbagai sektor. · Sekitar seribu aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang turun ke jalan raya di kota Jakarta pada Januari, memprotes pertemuan CGI yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia. Sementara itu di Ekuador terjadi pemberontakan rakyat menentang kebijakan neoliberal. · Pada Februari di Bangkok jaringan rakyat miskin pedesaan dan aktivis perkotaan melancarkan protes terhadap pertemuan lima tahunan Konperensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). · Pada awal April, protes rakyat menentang globalisasi semakin meluas, yang bermula dari lapangan kota Cochabamba, Bolivia. Ribuan penduduk setempat memaksa perusahaan Bechtel yang akan mengambil alih (swastanisasi) pelayanan air minum untuk keluar dari negeri itu. Penguasa membalas dengan memberlakukan negara dalam keadaan bahaya. · Saat 30.000 aktivis dari seluruh dunia menyerbu Washington dan mengepung markas IMF dan Bank Dunia, aksi solidaritas dalam jumlah yang sama terjadi di berbagai negeri Dunia Ketiga, termasuk Brasil dan Afrika Selatan. Di Lusaka dan Nairobi, kelompok perempuan melancarkan aksi serupa di bawah tekanan hebat dan akhirnya dibubarkan paksa oleh polisi. · Awal Mei, pertemuan Bank Pembangunan Asia (ADB) di kota Chiang Mai diguncang demonstrasi 5.000 mahasiswa, pengangguran, aktivis lingkungan dan rakyat pedesaan yang tergusur. Polisi yang mengawal pertemuan itu sempat kewalahan. · Pada 10 Mei, gerakan serikat buruh India menyerukan pemogokan umum yang ternyata diikuti oleh separuh angkatan kerja di negeri itu. Mereka menetang kebijakan neoliberal rancangan Bank Dunia yang akan berakibat pemecatan massal. Aksi protes terjadi di berbagai kota, melibatkan sekitar 200.000 buruh. Hari berikutnya, dua puluh juta buruh India melancarkan aksi mogok. Mereka secara eksplisit memprotes penyerahan kedaulatan nasional India ke tangan IMF dan Bank Dunia. · Sekitar 80.000 orang melancarkan aksi menentang IMF di Argentina pada pertengahan Mei. Penguasa membalas dengan penggebukan massal yang menyebabkan banyak orang terluka. Di Turki pada waktu bersamaan pemerintah juga menindas demonstrasi yang menentang kebijakan “mengencangkan ikat pinggang”. · Pada Juni, ribuan orang turun ke jalan-jalan raya di Port-au-Prince, Haiti, dalam rangkaian aksi menentang hutang luar negeri. Sementara itu di Paraguay serikat-serikat buruh menyerukan pemogokan umum selama dua hari untuk menentang swastanisasi yang dipaksakan IMF. · Di Nigeria pada bulan yang sama, serikat-serikat buruh bersekutu dengan penduduk Lagos dalam pemogokan massal menentang kenaikan harga minyak yang dianjurkan IMF. Aksi itu membuat para pejabat IMF mempersingkat jadwal kunjungannya di negeri itu. · Pada Juli, serikat buruh Korea Selatan berulangkali melancarkan pemogokan dan protes menentang kebijakan “mengencangkan ikat pinggang” yang dianjurkan oleh IMF. · Sebulan kemudian, gerakan kiri di Brasil mengadakan plebisit tentang program IMF di Brasil. Lebih dari enam juta orang memberikan suara, dan mayoritas menyatakan menolak. · Pada September aksi solidaritas mendukung S-26 berlangsung di seluruh dunia. Di Afrika Selatan, ribuan aktivis turun ke jalan-jalan di Durban, berdemonstrasi di depan kedutaan besar AS di Cape Town dan membuat arak-arakan menuju markas perusahaan terbesar di Afrika (Anglo American Corp). Para petugas keamanan perusahaan itu menghadapinya dengan kekerasan dan semprotan air lada ke wajah para aktivis. · Belasan ribu buruh, mahasiswa dan aktivis gerakan sosial berkonfrontasi dengan aparat keamanan di Seoul tanggal 20 Oktober. Aksi itu diarahkan pada pertemuan antara pemimpinpemimpin Eropa dan Asia di kota itu. ●
Indymedia, Membangun Media Gerakan
●
Mengadili Globalisasi
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Mengadili Globalisasi Pada April 2000 berlangsung pertemuan negara-negara Selatan di Havana, Kuba. Hadir di sana para pemimpin Dunia Ketiga, termasuk Abdurrahman Wahid sebagai presiden Indonesia waktu itu. Fidel Castro sebagai tuan rumah pertemuan itu, menyampaikan pidato untuk mewakili pandangan rakyat tertindas. Berikut cuplikannya, “Limapuluh tahun yang lalu kita diberi janji bahwa suatu hari takkan ada lagi kesenjangan antara negeri maju dan berkembang. Kita diberi janji roti dan keadilan; tapi saat ini kita semakin jarang makan roti dan ketidakadilan pun meningkat. Neoliberalisme bisa membuat dunia menjadi global tapi tidak bisa berkuasa atas milyaran orang yang lapar akan roti dan keadilan. Gambar-gambar ibu dan anak korban kekeringan dan bencana lainnya di seluruh Afrika mengingatkan kita pada kamp-kamp konsentrasi di Jerman semasa Nazi; gambar-gambar itu membawa kembali ingatan akan tumpukan mayat dan laki-laki, perempuan serta anak-anak yang sekarat. Kita perlu menggelar Nuremberg* lagi untuk mengadili tatanan ekonomi yang dipaksakan kepada kita sekarang. Dengan kelaparan dan penyakit yang bisa disembuhkan tatanan ini setiap tiga tahun membunuh lebih banyak laki-laki, perempuan dan anak-anak daripada jumlah korban Perang Dunia Kedua selama enam tahun. Kita perlu berdiskusi di sini tentang apa yang harus dilakukan. Di Kuba kami biasanya berkata, “Tanah Air atau Mati!” Dalam pertemuan negeri-negeri Dunia Ketiga ini kita bisa bilang: “Bersatu dan menegakkan kerjasama yang erat, atau mati bersama!” * Nuremberg adalah kota tempat pengadilan para penjahat perang Nazi Jerman digelar.
●
Indymedia, Membangun Media Gerakan
●
2000, Tahun Perlawanan
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
Cari!
Edisi No 07 Tahun 2001
Kata Globalisasi sudah menjadi salam pengunci dalam mantramantra penyejuk suasana krisis permanen. Para ekonom, sekaligus juru bicara pasar modal, berlomba-lomba memberikan petuah agar pemerintah dan rakyat Indonesia mematuhi “anjuran” lembaga keuangan internasional seperti 10 Perintah Allah. Konon, hanya dengan bersikap taat dan takzim begini Indonesia akan mampu bersaing dalam era globalisasi, dan dapat keluar menjadi pemenang. Laiknya tukang obat, mereka menceracau pula tentang kiat mencapai “keunggulan komparatif”, sambil jajakan yang masih tersisa di negeri ini: dari tanah, tenaga, sampai buah pikiran. Di antara haru-biru dan ketakjuban yang ditimbulkan Tragedi 11 September di Amerika Serikat, globalisasi tampilkan wajah buasnya. Jantung kekuasaan imperium dunia diguncang, dan seluruh sel yang sepakat menghidupinya dalam geram menerkam peluang. Perang global pun dikobarkan, sebelum jelas benar sosok sang musuh. Maling teriak maling atas nama “kebebasan dan demokrasi”. Entah “kebebasan” untuk siapa dan “demokrasi” yang mana. Yang jelas, modal berputar cepat meminyaki mesin-mesin tempur melaju ke dataran gersang yang merupakan gerbang menuju sumber minyak di Laut Kaspia. Globalisasi adalah kata pembenar bagi operasi gurita lembaga keuangan internasional serta perusahaan-perusahaan multinasional untuk pelipatgandaan dan pemusatan modal di tangan segelintir orang. Dengan bantuan pemerintahan yang korup dan otoriter, lembaga-lembaga internasional ini menjalankan operasi pemerataan kemiskinan melalui perang dan hutang. Dan, sekarang, setelah para gembong Komunis dianggap sudah bertekuk lutut, mereka temukan sebutan yang tepat bagi siapa pun yang menentang operasi ini: TERORIS. Edisi Media Kerja Budaya kali ini sarat angka dan data. Di tengah kesibukan JKB mempersiapkan sejumlah kegiatan lain, seperti Diskusi Bulan Purnama, Pameran Tunggal Dolorosa Sinaga, dan Kampanye Anti-Kekerasan dan Perdamaian Generasi Putih, dewan redaksi mencoba melacak gerak Bank Dunia, IMF, WTO dan negara-negara mapan yang bergabung dalam G-8. Institusiinstitusi ini lah yang mempersiapkan prasarana bagi perusahaanperusahaan multinasional untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin di segala penjuru dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerja kami dipermudah oleh perangkat yang dibangun oleh globalisasi itu sendiri: internet dan email. Namun, justru di sini tantangannya: bagaimana kita bisa mengambil-alih perangkat yang berpotensi membebaskan untuk, paling tidak, mengganggu derap penghancuran kemanusiaan berlanjut. Kami tahu kami tidak sendirian. Seperti yang akan diulas dalam salah satu bagian Pokok, perlawanan terhadap globalisasi merebak di seluruh dunia. Berbeda dengan gerakan perlawanan rakyat di dekade 1970an, gerakan anti-globalisasi tidak dipimpin oleh tokoh, organisasi massa atau partai politik tertentu. Ribuan organisasi masyarakat dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda terlibat dalam aksi-aksi yang beragam sepanjang 2000. Dalam satu organisasi kadang-kadang hanya beranggotakan 5-10 orang, tetapi masing-masing individu mempunyai kemampuan dan tanggung jawab yang jelas. Satu hal yang mempersatukan mereka: penolakan terhadap aturan-aturan main yang dibuat oleh segelintir orang dan lembaga tertentu atas kehidupan mereka sehari-hari.
Pokok Media Kerjabudaya Merayakan Kesengsaraan Sepuluh tahun lalu di mana-mana ada gairah luar biasa menyambut perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Orang ramai bicara tentang keajaiban globalisasi. Namun semua itu hanya dinikmati segelintir orang saja.
Globalisasi Perlawanan "Satu-satunya yang pantas menjadi global adalah perlawanan," demikian pengarang Arundhati Roy dari India, menyambut gerakan anti-globalisasi yang semakin meluas. Dari Seattle sampai Genoa, dari Chiapas sampai Jenewa, protes di Hyderabad, India sampai konperensi perlawanan terhadap globalisasi di Porto Alegre menunjukkan bahwa mengakhiri globalisasi kesengsaraan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
Jalan Neoliberal Bagi Indonesia Indonesia dalam cengkeraman tangan neoliberalisme dari dulu hingga sekarang. Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
Data Bicara Profil Institut Sekulir, membangun Gereja Kaum Miskin Mateus Goncalves
Pat Gulipat Puisi Husnul Khuluqi Kritik Seni Pledoi Mendobrak Si Moni Kamasra STSI-Bali
Klasik Resink dan Mitos Penjajahan 350 Tahun Razif
Cerita Pendek Segelas Kopi Darpan Ariawinangun
Esai Kesembuhan Semu Kapitalisme Thailand Arif Rusli
Logika Kultura Pasar John Roosa
Resensi Buku Saat-Saat Lampu Kuning, Saat-Saat Menggugat Diri Eddie Sius RL.
Tokoh Arnold C. Ap, Membangun Budaya Pembebasan Ibe Karyanto
Berita Pustaka Sisipan Media Kerjabudaya
Pemimpin Redaksi
●
●
●
●
Subversi Menegakkan Imperium: Politik Luar Negeri Amerika Serikat Surat Robert S. McNamara tentang Bantuan Militer kepada Indonesia pada 1965 Memerangi Terorisme, Menggerogoti Demokrasi di Indonesia Seabad Perlawanan di Filipina
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email versi teks
©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Merayakan Kesengsaraan Tim Media Kerja Budaya Sepuluh tahun lalu di mana-mana ada gairah luar biasa menyambut perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Orang ramai bicara tentang keajaiban globalisasi: makan siang dengan beras Thailand, daging Selandia Baru, sayuran segar dari Cianjur, sendok-garpu buatan Tiongkok, gelas keramik dari Perancis di atas meja antik dari dua abad lalu karya pengrajin India; perubahan pola komunikasi yang mengubah dimensi ruang dan waktu, akses ke beritaberita terbaru dari lima benua dalam hitungan detik, hubungan langsung ke tempat-tempat yang tak terbayangkan sebelumnya, dan seterusnya… dan seterusnya. Setiap hari industri komunikasi dan elektronik mencipta produk baru dan manusia semakin tenggelam dalam dunia maya: sebuah desa global di mana batas negara-bangsa menjadi tidak relevan dan cita-cita tentang perombakan struktur masyarakat adalah dongeng masa lalu. “Inilah akhir dari sejarah,” ujar Francis Fukuyama. Jika benar demikian, maka perjalanan umat manusia selama berabad-abad sungguh menyedihkan. Saat ini diperkirakan masih ada 840 juta orang menderita kekurangan gizi. Satu dari delapan orang di planet ini adalah pengangguran. Mayoritas mereka buta huruf dan tingkat harapan hidupnya kurang dari 60 tahun. Nasib anak-anak lebih buruk lagi. Satu dari empat anak di dunia sekarang menderita kekurangan gizi, dan setiap menit ada empat anak yang meninggal dunia penyakit diare dan gangguan pencernaan lainnya. Semua ini adalah produk globalisasi yang dirayakan sebagai “akhir dari sejarah”. Laporan UNDP tahun 1999 memberi gambaran lebih jauh tentang globalisasi dan hasil-hasilnya. Dalam waktu sepuluh tahun terjadi pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang. Tiga orang terkaya di dunia saat ini menguasai aset yang nilainya sama dengan milik 600 juta orang di 48 negeri termiskin. Kemakmuran mengalir dari tempat-tempat termiskin dan terburuk yang mungkin dibayangkan manusia ke pusat perdagangan dan keuangan negara industri maju. Saat ini seperlima penduduk di negeri-negeri paling kaya menguasai 86 persen produk domestik bruto dunia, 82 persen pasar ekspor dunia, 68 persen penanaman modal langsung dan 74 persen saluran telepon di dunia. Sementara seperlima penduduk di negeri-negeri termiskin hanya memiliki satu persen di masing-masing sektor. Kemajuan teknologi yang menjadi bintang utama era globalisasi pun hanya berlaku bagi segelintir orang saja. Sekarang ini tercatat baru lima persen penduduk dunia yang menggunakan Internet dan 88 persen di antaranya tinggal di negeri industri maju, sementara lebih dari satu milyar penduduk dunia sampai hari ini belum pernah melihat pesawat telepon dalam hidupnya. Globalisasi Sebagai Strategi Ada banyak mitos yang menyelubungi istilah globalisasi. “Rasanya sekarang ini semuanya bergantung pada tangan Adam Smith yang tak terlihat – semua ini ada di luar kontrol negeri mana pun, institusi apa pun,” kata Jeffrey Garten, pimpinan Yale School of Management. Dengan kata lain, globalisasi adalah proses alamiah yang tak dapat dihindari. Tapi kenyataannya tidak demikian. UNDP memperkirakan biaya menghapus kemiskinan di seluruh dunia secara efektif saat ini hanya satu persen dari pendapatan dunia sekarang. Dana yang diperlukan untuk memberantas tuntas kemiskinan di 20 negeri termiskin untuk selama-lamanya hanya sekitar US$5,5 milyar, sementara penduduk dunia menghabiskan US$7,2 milyar per bulan untuk membeli fast food. Jelas bahwa ketimpangan di dunia bukanlah perkara nasib atau proses alamiah yang tak terelakkan, tapi sebuah keputusan politik. Kapitalisme adalah sistem yang senantiasa berada dalam krisis dan menuntut para pemilik dagang, pengusaha dan pedagang serta birokrat – singkatnya elit penguasa sistem – terusmenerus merumuskan strategi baru untuk mengakhirinya. Prinsipnya sederhana, yakni menggarap dan mengubah segala menjadi ladang keuntungan, serta menaklukkan segala rintangan dan perlawanan yang membatasinya. Di abad-abad lalu sistem itu berkembang dengan merampas dan menguasai tanah serta sumber daya alam lainnya, lalu menjadikan para pemilik atau masyarakat yang mengontrolnya secara kolektif sebagai tenaga upahan. Di masa selanjutnya umat manusia menyaksikan semakin banyak bidang kehidupan yang dicaplok dan ditaklukkan oleh logika akumulasi, dengan menempatkan pasar dan prinsip jual-beli di dalamnya. Perusakan lingkungan, biaya rumah sakit yang mahal karena penghapusan subsidi sesungguhnya mengalir dari strategi yang sama, seperti halnya penguasa di zaman kolonial menggunakan uang dalam sistem pajak mereka. Semuanya memaksa orang menjual apa saja – termasuk tenaga kerja dan kadang tubuhnya – untuk dapat melanjutkan hidup. Ekspansi sistem ini bergerak terus menggerayangi kehidupan di segala bidang, termasuk pengetahuan dan kekayaan intelektual manusia. Sekarang ini sudah ada jutaan penemuan dan gagasan diberi hak paten yang membuat orang lain harus membayar untuk memanfaatkannya. Dan sekitar 90 persen hak paten itu dikuasai oleh perusahaan dan individu di negeri industri maju. Termasuk di dalamnya hak paten atas ribuan bibit tanaman dan teknologi pertanian yang sebelumnya adalah milik kolektif rakyat pedesaan di negeri berkembang. Semua strategi ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis oleh elit penguasa sistem dengan dukungan intelektual yang luar biasa. Bank Dunia sebagai salah satu lembaga penyusun strategi yang terpenting misalnya mempekerjakan sekitar 10.000 ahli dalam berbagai bidang yang beroperasi di seluruh dunia. Seperti istilah “menciptakan peradaban” dipakai dalam penaklukan berdarah di zaman kolonial, “globalisasi” adalah selubung ideologis dari strategi penaklukan di zaman modern, yang bahkan lebih berdarah. Pasar Bebas Versus Demokrasi Karl Polanyi dalam karya Great Transformation berbicara tentang gerak pasar yang secara inheren tak berbatas dan cenderung mengancam keselamatan manusia. Tapi saat menulis buku itu di 1944 ia menilai bangsa-bangsa tidak lagi menempatkan sistem ekonomi sebagai dasar gerak masyarakat, “dan keunggulan masyarakat atas sistem itu sudah dipastikan”. Ramalannya sungguh tepat, tapi penilaiannya keliru. Apa yang dikhawatirkannya justru menjadi kenyataan. Tepat pada tahun yang sama para pejabat pemerintah, bankir, pemilik industri dan pedagang dari Amerika Serikat dan Inggris berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire. Perang hampir usai dan kelas penguasa di kedua negara melihat ancaman naiknya gerakan rakyat dan Uni Soviet berkuasa di Eropa Barat. Untuk menghalangi kemungkinan itu maka dibentuk lembagalembaga internasional yang dapat memajukan doktrin akumulasi modal dan memperkuat sektor usaha, yang kini dikenal dengan sebutan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Sementara IMF menggunakan tabungannya untuk menalangi kerugian yang dilanda sebuah negara agar dapat melanjutkan perdagangan, Bank Dunia bertugas memberi pinjaman kepada pemerintah-pemerintah di dunia untuk membangun kembali jalan raya, rel kereta api, jembatan, pelabuhan dan semua infrastruktur yang tidak menghasilkan keuntungan. Maksudnya tidak lain agar pemerintah bersangkutan punya cukup uang sehingga tak perlu menyedot pajak terlalu besar dari pihak swasta. Dalam waktu singkat keduanya tumbuh menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia. Sebelum menerima pinjaman, negara yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti pedoman pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai “program penyesuaian struktural”. Program ini tujuannya tidak lain untuk menyesuaikan perekonomian sebuah negara dengan logika akumulasi modal dan memberi keleluasaan pihak swasta – terutama perusahaan transnasional – untuk menikmati keuntungan di sana. Semua keputusan dibuat oleh segelintir elit nasional yang bekerjasama dengan para pejabat lembagalembaga tersebut, kalau perlu dengan melangkahi lembaga perwakilan atau proses demokratik lainnya. Pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi tidak berhenti di sana. Dengan panji freedom and democracy para elit penguasa melancarkan perang, subversi dan teror untuk menegakkan perekonomian yang “bebas dan terbuka”: kudeta atas pemerintahan Soekarno, pembunuhan Patrice Lumumba di Kongo, penggulingan Salvador Allende di Chile dan Perang Vietnam. Di atas kemenangan yang berdarah kemudian ditempatkan diktator-diktator seperti Jenderal Manuel Noriega di Panama, Jenderal Augusto Pinochet di Chile, Jenderal Jorge Rafael Videla di Argentina, Mobutu Sese Seko di Kongo, dan George Papadopoulos di Yunani. Sasarannya adalah semua kekuatan, pemerintahan dan pemimpin yang berusaha menempuh jalan lain untuk membangun negerinya. Di samping menggulingkan pemerintahan, menculik dan membunuh pemimpin, elit penguasa ini juga tak segan merongrong pemerintahan yang tetap bersikeras memilih jalan pembangunan berbeda dengan bermacam cara, mulai dari mendirikan pemerintahan tandingan atau oposisi bersenjata seperti yang terjadi di Mozambique, Angola dan Nikaragua, sampai embargo total seperti yang dialami Kuba sampai sekarang. Di masa lalu, Amerika Serikat yang menjadi motor penggerak ekspansi ini menggunakan dalih Perang Dingin untuk membenarkan tindakannya. Tapi setelah perang ini berlalu, para penguasa dunia mencari sasaran-sasaran baru di Amerika Tengah, Selatan dan jazirah Arab. Kekerasan adalah bagian penting dari ekspansi kapitalisme atau globalisasi ini, seperti dikatakan Thomas Friedman, kolumnis harian New York Times, “tangan pasar yang tersembunyi takkan berjalan tanpa kepalan yang tersembunyi pula. McDonald takkan tumbuh subur tanpa McDonnell Douglas, pabrik pesawat tempur F-15.” Dan Amerika Serikat membuktikannya, dengan mengangkat mantan menteri pertahanan Robert McNamara menjadi presiden Bank Dunia selama tigabelas tahun. Kekerasan di zaman ini bukan hanya pelengkap untuk mencapai tujuan, tapi juga menjadi bisnis tersendiri. Setiap tahun para penguasa di dunia menghabiskan dana US$600 milyar untuk melengkapi persenjataan, peralatan dan pasukan. Di negara-negara penguasa dunia, industri senjata adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan memberi pendapatan besar. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Dengan mengirim senjata, melatih personel, dan menjual peralatan, negara industri seperti Amerika Serikat dapat mengeruk keuntungan besar sekaligus memperkuat posisinya sebagai pembina, pelatih dan penasehat pasukan militer di seluruh dunia. Dan semua itu, tentu saja, atas nama kebebasan dan demokrasi. Neoliberalisme Menoreh Nasib Dunia Para pendukung sistem bukan tidak sadar bahwa banyak orang menderita, mengkritik dan melawan apa yang mereka ciptakan. Tahun 1980-an, Margaret Thatcher yang baru diangkat menjadi perdana menteri Inggris menyatakan bahwa dunia “tidak punya pilihan lain.” Apa yang dimiliki sekarang jauh lebih baik dari apa yang mungkin diberikan oleh pemikiran dan sistem lain di dunia. Keruntuhan Uni Soviet pada 1989 memperkuat keyakinan itu, dan kaum intelektual pun ramai-ramai menghujat semua sistem alternatif sebagai barang rongsokan yang ketinggalan zaman. Seringkali tidak disadari bahwa globalisasi dan pemikiran para elit penguasa berdiri di atas doktrin-doktrin yang jauh lebih tua dan usang dibandingkan alternatif yang dihujat. Sumber utamanya adalah pemikiran liberal dari tiga abad lalu yang mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian sebuah bangsa. Persaingan adalah mesin pendorong untuk menciptakan manusia dan sistem yang unggul. Paham ini berkembang pesat menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa yang merambah ke seluruh penjuru dunia. Gerak laju ini terhenti sesaat ketika terjadi Depresi Besar 1930-an. Di tengah kesulitan hidup yang luar biasa, John Maynard Keynes tampil dengan konsep bahwa kapitalisme takkan bertahan jika pemerintah dan bank-bank sentral tidak turun tangan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kepentingan bersama. Tapi krisis besar di 1970-an membuat para penguasa dunia kembali beralih pada liberalisme, sekali ini dengan gaya baru, sehingga dikenal dengan sebutan neoliberalisme. Seperti liberalisme tiga abad lalu, neoliberalisme juga menghendaki tegaknya kekuasaan pasar dan “membebaskan” arus modal dan barang dari campur tangan negara. Tapi seiring dengan semakin banyaknya bidang kehidupan yang disedot ke dalam logika akumulasi modal, maka tuntutan pun semakin meluas, mulai dari memotong anggaran bagi pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, menghapus pelayanan sosial bagi orang miskin, sampai swastanisasi perusahaan negara. Doktrin itu dilancarkan dengan gencar, dan hampir selalu dengan paksaan. Setelah Allende digulingkan pada 1973 dengan bantuan penuh dari CIA, Milton Friedman dari Universitas Chicago menjadi penasehat ekonomi Chile. Ia bekerjasama dengan kediktatoran Pinochet untuk merombak seluruh konsep pemerintahan rakyat dan economia popular yang diterapkan sebelumnya, dan menjadikan negeri itu laboratorium pertama bagi eksperimen neoliberalisme. Dalam duapuluh tahun selanjutnya hampir seluruh Amerika Latin dan Tengah dikuasai oleh rezim-rezim neoliberal. Hasilnya pun segera nampak. Di Meksiko tingkat upah menurun drastis sekitar 40% sementara biaya hidup melonjak sampai 80%. Sekitar 20.000 usaha kecil dan menengah gulung tikar sementara lebih dari seribu perusahaan negara dikuasai oleh swasta. Seperti dikatakan Subcommandante Marcos, salah satu pimpinan gerakan Zapatista di hutan Chiapas, Meksiko, bahwa neoliberalisme ingin mengubah dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan raksasa, di mana para penguasa membeli segalanya, mulai dari orang Indian, perempuan, tenaga buruh dan juga kedaulatan negara. Rangkaian “keberhasilan” inilah yang membawa para penguasa negara industri maju mencapai kesepakatan Washington pada 1980-an, yang mendesak negara-negara lain di dunia memeluk ekonomi terbuka dan perdagangan bebas. Selanjutnya bermacam lembaga, forum dan kesepakatan baru terus-menerus dibuat untuk memperluas kekuasaan, seperti AFTA di Asia Tenggara, NAFTA di Amerika Utara dan Meksiko dan APEC untuk seluruh wilayah Asia-Pasifik. Doktrin neoliberal menyebutnya sebagai lembaga kerjasama ekonomi, tapi kenyataannya seluruh agenda diajukan oleh para pemodal dan birokrat pendukungnya, dan keputusankeputusannya tidak pernah mengingkari kepentingan mereka. Masalah sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup tentu saja tidak masuk dalam agenda karena hanya akan mengurangi kelancaran menghisap keuntungan. Sementara itu berbagai skema dikeluarkan untuk menyerahkan hajat hidup orang banyak ke tangan segelintir orang saja. Kesepakatan Multilateral mengenai Investasi (MAI) misalnya mengharuskan pemerintah anggotanya membayar kerugian yang diderita perusahaan jika mereka mengubah kebijakan publiknya. Tidak ada lagi perlindungan dan kontrol pemerintah terhadap kehidupan ekonomi karena dalam doktrin perdagangan bebas dinilai tidak efektif dan menciptakan “distorsi pasar”. Dengan kata lain, tidak ada kontrol rakyat atau demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, dan kemungkinan memilih jalan hidup berbeda pun semakin kecil. Setidaknya untuk sementara waktu… ●
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
●
Globalisasi di Internet
●
Dalam Bahasa Mereka Sendiri
Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Globalisasi Perlawanan Tim Media Kerja Budaya " Satu-satunya yang pantas menjadi global adalah perlawanan,” demikian pengarang Arundhati Roy dari India, menyambut gerakan anti-globalisasi yang semakin meluas. Hampir setiap pertemuan pemimpin bisnis, kepala negara dan lembaga keuangan internasional dihadang oleh kelompok masyarakat yang bergabung dengan aktivis dari seluruh penjuru dunia. Pada November 1999 di Seattle, sekitar 30.000 aktivis bergabung dalam aksi protes besar menentang pertemuan WTO. Dari kampanye di media massa dan demonstrasi yang kecil dan sporadis, gerakan anti-globalisasi mulai menerapkan taktik baru: menghalangi jalannya pertemuan internasional yang mereka dakwa akan semakin menyengsarakan dunia. Media komersial menyambut gelombang anti-protes itu dengan nada miring. Sasaran utamanya tentu adalah aksi perusakan yang dilakukan oleh berbagai kelompok, untuk memperlihatkan bahwa aksi anti-globalisasi sama dengan kerusuhan dan karena itu harus ditindak tegas. Para birokrat dan pemimpin bisnis pun menimpali. “Anak-anak itu tidak tahu apa pun tentang globalisasi. Mereka hanya kumpulan orang frustrasi yang berpikir dengan aksi semacam itu dunia akan menjadi lebih baik.” Tentu tidak dijelaskan bahwa frustrasi itu bersumber dari kesengsaraan yang mulai dirasakan oleh kaum muda, terutama rakyat pekerja, negara industri maju. Selama sepuluh tahun terakhir terjadi pemecatan massal, pengurangan upah, pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan, dan berbagai kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Dalam tiga tahun terakhir semakin banyak orang dan kelompok yang terlibat dalam gerakan itu, termasuk di kota-kota yang dikenal tenang dan damai. Sebelum mobilisasi dilakukan di seluruh pelosok kota, mulai dari tembok rumah sampai meja restoran diberi tanda seperti S-26 atau A-16 yang menandakan bulan dan tanggal, sebagai undangan aksi kepada masyarakat. Puluhan ribu orang kemudian bergabung pada hari yang ditetapkan untuk melancarkan aksi protes, yang kadang diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan. Bentrokan semakin sering terjadi karena para aktivis biasanya memasang blokade untuk menghalangi para pejabat dan pengusaha menghadiri pertemuan. Di Genoa, bulan April lalu, sekitar 300.000 aktivis dari seluruh dunia berkumpul untuk menghalangi pertemuan negara industri maju yang tergabung dalam kelompok G-8. Polisi bereaksi keras, menyerang para demonstran dan membunuh seorang aktivis asal Italia, Carlo Giuliani. Seorang carabineri menembaknya sampai jatuh, lalu tubuhnya dilindas dua kali sehingga meninggal seketika. Kekerasan tidak berhenti di sana. Puluhan aktivis yang ditahan di penjara Bolzaneto menjadi bulan-bulanan para penjaga, tentara dan polisi. Pekerja media dan aktivis yang memegang kamera dikejar-kejar, dan pusat komunikasi dan media yang didirikan para aktivis di sebuah kompleks sekolah dihancurkan. “Pembantaian Genoa” demikian para aktivis menyebut kejadian itu, justru memicu protes di seluruh penjuru dunia. Aksi solidaritas terjadi di berbagai negara dan menegaskan sikap para aktivis menentang globalisasi dan aparat kekerasan yang melindunginya. Arus Balik dari Selatan Pada 1 Januari 1994, bertepatan dengan berlakunya Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), terjadi pemberontakan di propinsi Chiapas, Meksiko bagian selatan. Sekelompok petani Indian yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) menduduki sebuah kota dan menyerukan perlawanan umum. Tapi berbeda dengan gerakan perlawanan bersenjata di Amerika Latin pada tahun 1970-an, kelompok ini tidak bertujuan merebut kekuasaan dengan kekerasan. Mereka hanya berseru kepada rakyat dunia untuk membangun jaringan antarbenua untuk melawan neoliberalisme. Di tahun-tahun selanjutnya, gerakan Zapatista menyelenggarakan berbagai pertemuan besar yang melibatkan ribuan aktivis serikat buruh, organisasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kelompok perempuan, perhimpunan mahasiswa dan banyak lainnya. Tujuan pertemuan ini pun bukan untuk menciptakan organisasi baru, tapi untuk membahas strategi bersama bagi bermacam kelompok berbeda. Dalam pertemuan kedua di bulan Agustus 1997, sejumlah aktivis berkumpul untuk merencanakan aksi protes menentang WTO yang menjadi simbol dan alat utama globalisasi kesengsaraan. Untuk mengatur kegiatan dan menghimpun kekuatan mereka membentuk Peoples’ Global Action Against “Free” Trade and the WTO yang disingkat PGA. Aksi pertama berlangsung akhir Mei 1998 di Jenewa untuk menentang konperensi WTO tingkat menteri yang kedua. Dan bersamaan dengan itu di 28 negara, ratusan organisasi melancarkan aksi-aksi protes yang melibatkan jutaan orang. Di jalan-jalan kota Hyderabad, India, setengah juta orang turun ke jalan menentang konperensi itu, sementara di Brasil 50.000 orang, terutama kaum tani tak bertanah, melancarkan aksi serupa. Tahun berikutnya gelombang protes pun semakin meningkat dan meluas. Pada 18 Juni PGA melancarkan aksi global menentang pusatpusat keuangan dunia. Sekitar 100 kota di 40 negara dilanda aksi protes, mulai dari Australia sampai Zimbabwe, Swedia sampai Korea Selatan, Chile dan Republik Ceko. Energi perlawanan yang mulai meluas kemudian mengalir ke negara-negara industri maju, pusat berkumpulnya para penguasa dunia untuk menentukan kebijakan yang menyengsarakan mayoritas penduduk dunia. Tujuannya bukan untuk menghentikan globalisasi itu sendiri, melainkan mengubah prinsip dan cara yang di satu sisi memperkuat dan memperkaya perusahaan-perusahaan raksasa dan di sisi lain melemahkan rakyat dunia, dan membuat mereka semakin miskin. Karena itu sasarannya bukan hanya satu-dua kebijakan yang dianggap merugikan, melainkan seluruh lembaga yang merancang sistem tersebut, terutama IMF, Bank Dunia dan WTO. Gelombang perlawanan ini tidak berhenti pada aksi-aksi protes dan bicara saja, sekalipun media komersial memberi kesan demikian. Hampir semua organisasi yang terlibat di dalamnya memiliki pekerjaan nyata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di berbagai bidang, mulai dari pertanian, penanganan anak jalanan sampai perlindungan perempuan dari kekerasan. Di Brasil salah satu motor penggerak perlawanan adalah MST, yang menghimpun petani untuk menduduki tanah-tanah tak terpakai di wilayah selatan dan mengembangkan program kesejahteraan secara demokratik (ulasan tentang MST dimuat di MKB edisi 05/2001) Sementara di Filipina ada kelompok Gabriela, yang membela hak-hak perempuan dan menentang berbagai tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan. Dalam perkembangannya semakin banyak kelompok masyarakat yang terlibat, mulai dari perhimpunan warga di tingkat desa, organisasi penulis, persatuan guru, serikat buruh, lembaga bantuan hukum, perkumpulan ibu rumah tangga, komunitas kesenian, organisasi lingkungan hidup, veteran perang, penjaga toko sampai kaum ulama. Keragaman dan tidak adanya satu pusat, justru menjadi kekuatan utama. Mengatasi Perbedaan Membangun gerakan berskala global tentu punya beragam masalah. Dalam aksi-aksi protes yang terakhir semakin banyak aktivis yang menyadari perlunya merumuskan tujuan yang lebih jelas, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Perlawanan yang mengandalkan “musuh bersama” (globalisasi neoliberal) memang bisa memobilisasi kekuatan dengan cepat, tapi tidak cukup untuk membuat perubahan berarti. Di samping itu tuntutan-tuntutan jangka pendek juga dirasakan perlu, untuk merebut “kemenangan kecil” dari tangan penguasa dunia. Untuk itu jaringan aktivis dari berbagai belahan dunia mulai menyelenggarakan pertemuan dan konperensi yang membahas berbagai aspek globalisasi dan perlawanan terhadapnya. Di Porto Alegre, Brasil bagian selatan, ribuan aktivis berkumpul dalam Forum Sosial Dunia bulan Januari lalu, bertepatan dengan penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia. Sementara itu di bulan Juni berlangsung pertemuan Liga Internasional Perjuangan Rakyat yang dihadiri oleh bermacam organisasi dari lima benua. Walau tidak semuanya menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai nasib gerakan di masa mendatang, forum seperti ini sangat berguna sebagai tempat mempertemukan berbagai kecenderungan yang ada. Masalah lain yang sekarang menjadi perdebatan besar adalah penggunaan kekerasan, yang dipicu oleh bentrokan berulangkali dengan aparat keamanan dalam aksi-aksi protes di Eropa dan Amerika Serikat. Para pendukung gerakan non-kekerasan menganggap serangan terhadap toko-toko dan petugas tidak dapat dibenarkan, dan akan merugikan gerakan secara keseluruhan. Sementara di pihak lain dikatakan bahwa hanya dengan kekerasan media komersial akan memberi perhatian, yang menjadi jalan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Perdebatan berlangsung sengit dan menajam pada masalah kepemimpinan dalam gerakan. Tapi seiring berkembangnya gerakan protes, masing-masing pihak mulai melihat kelebihan dan kelemahan setiap posisi. Di satu pihak para penganjur kekerasan semakin mengikatkan diri pada gerakan dan menghindari bentrokan, sebaliknya aktivis lainnya bisa memahami aksi pelemparan bangunan tertentu yang dianggap sebagai simbol globalisasi neoliberal. Gelombang protes terus berlanjut, begitu pula dengan pemikiran dan praktek pembebasan di kampung dan kota berbagai belahan dunia. Banyak juga yang melakukannya karena tidak ada pilihan lain. Mengakhiri globalisasi kesengsaraan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
●
Indymedia, Membangun Media Gerakan
●
2000, Tahun Perlawanan
●
Mengadili Globalisasi
Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Jalan Neoliberal Bagi Indonesia Tim Media Kerja Budaya Hindia Belanda adalah gabus tempat Belanda mengapung, bunyi slogan penguasa kolonial di akhir abad ke-19. Perkebunan swasta dan pemerintah kolonial yang terbentang dari Deli sampai Banyuwangi menghasilkan ratusan juta gulden yang mengalir masuk ke kantong para pemiliknya di negara induk. Hasil kerja kuli kontrak dan buruh perkebunan yang hidup dalam kondisi seperti budak inilah yang menjadi dasar bagi tumbuhnya imperium. Seperti halnya bekas tanah jajahan yang lain, pada 1945 Indonesia meraih kemerdekaan dalam keadaan terkuras. Para pejabat republik harus bergantian memakai kendaraan yang ditinggalkan Belanda maupun Jepang, sementara departemen-departemen pemerintah harus berbagi ruang dan perabotan yang serba terbatas di bangunan yang sama. Perang selama empat tahun membuat kehidupan ekonomi porak-poranda. Di banyak tempat rakyat bergerak mengambil kembali tanah dan milik mereka yang dirampas penguasa kolonial. Tapi gerakan merebut kembali kehidupan ini terhenti ketika perundingan terakhir antara pejabat republik dengan penguasa kolonial – di bawah pengawasan Amerika Serikat – memutuskan semua perusahaan dan perkebunan harus dikembalikan kepada pemilik lamanya. Bukan itu saja. Sementara Belanda mendapat berkah bantuan Marshall Plan sebesar US$359 juta dan ratusan juta lainnya dalam bentuk peralatan militer dan kredit, Amerika Serikat menekan pemerintah Indonesia untuk mengambilalih hutang negara Hindia Belanda sebesar US $1,13 milyar. Ironisnya sekitar US$800 juta hutang itu adalah biaya perang mencegah kemerdekaan Indonesia. Selama 20 tahun negeri yang baru merdeka ini harus membangun kembali perekonomian, di bawah tekanan negara industri maju yang ingin segera mencaplok kembali apa yang direbut oleh dekolonisasi, subversi dan pemberontakan yang didukung oleh Amerika Serikat, serta kemiskinan merajalela akibat struktur kolonialisme yang tidak dirombak. Korupsi, Kekerasan dan Neoliberalisme 14 Februari 1966. Presiden Soekarno dengan sisa-sisa kekuatan yang terus digerogoti mengeluarkan UU No. 1/1966: Indonesia keluar dari IMF dan Bank Dunia yang “ternyata merupakan konsentrasi kaum neo-kolonialisme dan imperialis yang mengutamakan kepentingan golongannya daripada anggota-anggotanya termasuk negara-negara yang baru merdeka dan belum berkembang ekonominya.” Di tengah krisis yang parah, langkah itu tidak banyak artinya. Kekuasaannya tinggal menghitung hari. Para petinggi militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, dengan dukungan negara industri maju, lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan raksasa, sudah siap merangsak untuk merebut kekuasaan itu dari tangannya. Setengah sampai satu juta orang yang dituduh PKI atau terlibat dengan satu lain cara dengan partai tersebut dibunuh, sementara ratusan ribu lainnya disekap dalam kamp-kamp di seluruh Indonesia. Buku sejarah resmi dan para pemenang merayakannya sebagai tindakan heroik “menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman komunis”. Banyak korban dan keluarga mereka sebenarnya tidak pernah berurusan dengan komunisme maupun berencana merebut kekuasaan dari tangan Soekarno seperti yang dituduhkan penguasa. Dan bagi mereka sejarah punya makna berbeda. Diperkirakan lebih dari dua juta orang kehilangan tanah dan milik mereka dalam berbagai operasi penumpasan, dan harus hidup sebagai pengungsi di tanah air sendiri. Sebagian tewas dibunuh, sementara lainnya dijadikan tenaga kerja paksa oleh penguasa militer di pertambangan dan perkebunan. Keluarga tercerai-berai, memisahkan anak-anak selamanya dari orang tua mereka. Cap “komunis” yang ditetapkan penguasa dan pengikutnya adalah hukuman mati secara sosial. Mereka yang dikenai cap – termasuk ribuan ahli fisika, matematika, filologi, sastrawan dan dokter bedah – hanya boleh menjual tenaga sebagai kuli bangunan untuk menyambung hidup. Praktek yang sama dengan cap berbeda – seperti Islam radikal, gerombolan pengacau keamanan atau separatis – terus digunakan untuk memaksa semua orang membanting harga diri dan tenaganya, dan berdisiplin dalam Orde Baru. Sementara kekuasaan politik dan ekonomi terpusat di tangan segelintir keluarga elit Orde Baru, jutaan orang terjerembab dalam kantong-kantong kemiskinan yang semakin lebar dan berkembang-biak, melampaui apa yang pernah mereka alami di zaman kolonial. Dengan petunjuk dari para ekonom dan pejabat Orde Baru serta lembaga keuangan internasional dan negara industri maju, pemerintahan Soeharto menghapus semua hambatan bagi modal internasional untuk menguasai sumber daya alam dan tenaga manusia di Indonesia. Awal tahun 1971 sebuah kesepakatan dibuat untuk membagi-bagi mineral Indonesia kepada perusahaan asing seperti Caltex, Frontier, IIAPCO-Sinclair dan Gulf-Western. Empat tahun sebelumnya, Soeharto terlebih dahulu menyerahkan 1,2 juta hektar tanah di Papua kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto. Aturan fiskal disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan ini mengalirkan pendapatannya langsung ke pusatpusat kemakmuran di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa. Boom minyak yang sempat memberi keleluasaan bagi pemerintahan Soeharto pada tahun 1970an tidak berlangsung lama, dan seperti kebanyakan negeri Dunia Ketiga lainnya, Indonesia mulai mengembangkan “perekonomian terbuka”. Lahan-lahan baru dibuka untuk eksploitasi sumber daya alam dan pabrik manufaktur ringan. IMF dan Bank Dunia pun memuji angkaangka pertumbuhan ekonomi, dan rezim Soeharto pun menikmati kucuran kredit, penanaman modal langsung, serta perlindungan politik bagi apa pun yang mereka lakukan di dalam negeri. Pada saat bersamaan, proses industrialisasi ini menyingkirkan jutaan orang lain dari tanah mereka. Banyak di antaranya yang lari ke kota pada usia sangat muda untuk menjual tenaga, sebagai buruh pabrik, kuli angkut maupun pekerja seks. Mereka bekerja delapan sampai duabelas jam, di bawah disiplin keras para pengusaha dan manajer, dengan upah yang hanya cukup untuk makan, sedikit pakaian dan menyewa sebuah kamar kos bersama tiga atau empat rekan lainnya. Salah satu hasil pembangunan gaya Orde Baru adalah korupsi yang meresap ke dalam struktur kekuasaan, dari tingkat kelurahan sampai istana presiden. Para pejabat tinggi maupun rendah menetapkan bermacam pungutan untuk segala hal, mulai dari investasi dan perdagangan sampai mendaftarkan anak ke sekolah dan mengurus KTP. Dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) disebutkan antara 20-30% dana hutang luar negeri yang disalurkan melalui Bank Dunia mengalir masuk ke kantong para pejabat pemerintah untuk memperkaya diri dan memperluas pengaruh politiknya. Di Timor Lorosae pada 1999 ditemukan bukti-bukti bahwa sebagian hasil hutang itu juga digunakan untuk membiayai kegiatan milisi pro-integrasi yang bersama TNI kemudian menghancurkan wilayah itu. Krisis dan Tegaknya Neoliberalisme Pertengahan tahun 1990-an para penguasa dunia menyambut Indonesia sebagai “keajaiban ekonomi baru”, menyusul Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Sampai awal tahun 1997 Bank Dunia pun menilai masa depan perekonomian sangat cerah. Tapi krisis finansial mengubah segalanya. Seluruh borok pembangunan yang bersandar pada hutang luar negeri dan ekspansi kapitalisme di segala pelosok dan bidang kehidupan mulai memperlihatkan warna asli yang suram. Pemerintahan Soeharto masih berusaha menolak dan menghindari konsekuensi dengan berbagai cara, dan semakin keras kepala. Ia menolak agenda liberalisasi IMF untuk melindungi kepentingan keluarganya, menculik dan membunuh sejumlah aktivis mahasiswa dan menempatkan keluarga serta para kroni di posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Persekutuan aneh terbentuk antara para penganjur liberalisasi dan aktivis yang menentang kediktatoran di bawah payung “reformasi”. Ketika Soeharto mengundurkan diri, arus yang pertama segera mengambil tempat di depan. Kurang dari dua bulan sesudahnya IMF mendesak Habibie untuk mengambilalih tanggung jawab membayar hutang yang ditinggalkan rezim Soeharto. Kesepakatan dibuat dan angka-angka hutang pun semakin membengkak. Dalam waktu tiga tahun setelah krisis hutang luar negeri Indoneisa mencapai US$144 milyar, dengan komposisi 60% hutang pemerintah dan 40% hutang swasta. Tapi sebagian besar hutang pemerintah pun dipakai untuk menalangi hutang dan menyuntikkan modal kepada bank-bank swasta yang bangkrut. Para pejabat IMF dan Bank Dunia, serta kaum intelektual pendukung neoliberalisme di Indonesia, mengkritik sistem perbankan Indonesia yang rapuh, padahal sepuluh tahun sebelumnya mendorong program deregulasi perbankan tanpa pengawasan dari pemerintah. Amerika Serikat yang selama 32 tahun mendukung kekuasaan Soeharto dalam waktu singkat berubah mengungkap kebobrokan, korupsi dan penyelewengan, dengan menuduh “kebudayaan Asia” sebagai biang keladinya. Kredit milyaran dolar yang tidak dapat dibayar kembali dikutuk sebagai biang penyakit, padahal sebelumnya semua orang memujinya sebagai energi untuk menggerakkan roda pembangunan. Kaum elit sibuk berdebat dan rakyat lagi yang jadi korbannya. Pemecatan massal terjadi di manamana dan kekerasan meningkat akibat frustrasi yang mendalam. Dipicu oleh perebutan kuasa di kalangan elit, dalam waktu dua tahun Indonesia diubah menjadi medan pertempuran yang berakibat 10.000 orang tewas dan memaksa lebih dari satu setengah juta penduduk hidup sebagai pengungsi. Sementara pemotongan subsidi untuk kesehatan dan pendidikan yang diperintahkan IMF membuat jutaan anak terancam kematian dan tidak akan berkembang secara kultural. Reformasi yang sebelumnya dibayangkan sebagai energi pembebasan, menjadi jalan penaklukan seluruh negeri di bawah kekuasaan neoliberalisme. Hutang adalah alat utama menekan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan tata ekonomi neoliberal. Milyaran dolar yang dipinjam rezim Soeharto dan kroninya dari IMF, Bank Dunia dan negara industri maju untuk menyingkirkan rakyat, kini harus dibayar kembali oleh para korban. Tuntutan agar hutang di masa lalu dihapuskan, tidak digubris. Menurut lembagalembaga keuangan internasional itu, “Indonesia bukanlah negara miskin, dan mampu membayar kembali seluruh hutangnya”. Dan untuk itu mereka pun menyiapkan “paket reformasi” perekonomian yang mengharuskan pemerintah membuka semua sektor kehidupan menjadi lahan cari untung, dan menyedot Indonesia secara bulat-utuh ke dalam arus yang mengalir ke pusat-pusat kemakmuran di negara industri maju. Tiga kali pergantian pemerintah tidak mengubah keadaan ini, malah sebagian menilainya semakin parah saja. Selama tiga tahun terakhir kita menyaksikan tarik-ulur pemerintah dan IMF dalam merumuskan letter of intent (LOI), yang memuat nasib perekonomian Indonesia di masa mendatang, dan tak satu pun kemenangan bagi rakyat yang berhasil dicatat. Lahir Bukan untuk Menjadi Budak Krisis, kekerasan dan sistem politik yang seperti selalu berujung di jalan buntu, mendesak orang untuk berpikir sendiri tentang cara mempertahankan hidup. Di pedesaan ratusan ribu petani bergerak mengambilalih tanah yang dirampas semasa Orde Baru. Di Rambang lubai, Palembang, riban petani menuntut tanah yang dirampas dengan kekerasan oleh PT Musi Hutan Persada milik PT Barito Pasifik. Sementara di Lombok Tengah rakyat menduduki kantor PT Pengembangan Pariwisata Lombok dan menuntut 1.250 hektar tanah mereka dikembalikan. Proyek pariwisata yang dikelola oleh perusahaan Indra Rukmana dan Pieter Gontha dianggap hanya menciptakan kesenjangan yang makin lebar. Elit lokal yang semasa Orde Baru menduduki tempat terhormat pun tidak didengar, karena sudah terlalu lama bersekongkol dengan perusahaan swasta. Di sektor industri buruh memprotes berbagai kebijakan dan praktek yang merugikan, mulai dari penetapan upah minimum yang rendah sampai pada penggelapan dana Jamsostek, dan memprotes pemecatan terhadap rekan kerja dengan alasan “perusahaan merugi”. Di pabrik dan tempat kerja lainnya buruh membentuk serikat-serikat untuk membela kepentingannya. Gerakan perempuan menyambut krisis dengan aksi-aksi protes menentang kenaikan harga, pemotongan subsidi kesehatan dan pendidikan yang membuat hidup semakin sengsara. Perlawanan kerap dihadapi dengan kekerasan dan provokasi untuk meledakkan amarah menjadi kerusuhan rasial, etnik atau agama. Ribuan orang terjerembab ke dalam perangkap, mengobarkan permusuhan kepada sesama dan menjadi budak mesin penghancuran. Segelintir elit terus dibiarkan mengambil keputusan besar dan menyengsarakan hidup banyak orang. Mungkin kita perlu sejumlah besar orang yang melakukan hal-hal kecil untuk mengubah semua ini. Tim Media Kerja Budaya: Hilmar Farid, Razif, Sentot Setyosiswanto.
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Institut Sekulir: Membangun Gereja Kaum Miskin Mateus Gonçalves Maria Lourdes Martins, seorang suster muda yang baru menyele saikan kuliah di STFK Prandyaidya, Yogyakarta, kembali ke kampung halamannya, Timor Lorosae. Ia bertekad mewujudkan gagasan yang dikembangkannya selama kuliah, untuk membangun lembaga yang dapat mengabdi pada masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat, khsusnya mereka yang paling menderita di daerah-daerah terpencil dan terlupakan. Pada 1990 ia membentuk Institut Sekulir di Dare, sekitar sepuluh kilometer di selatan kota Dili, dan menghimpun sejumlah anggota yang kemudian hidup bersama masyarakat dan bekerja di sana. Selain membantu dan mendampingi dalam penghayatan dan pengembangan iman, lembaga ini juga bergerak mengembangkan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat agar mereka bisa mencapai taraf hidup yang layak. Konsepnya sederhana, menyelamatkan dunia dengan kekuatan dunia dan melalui kehidupan dunia sendiri. Di zaman pendudukan Indonesia, kegiatan seperti ini tentu dinilai aneh, bahkan oleh gereja Katolik sendiri. Tidak sedikit pejabat gereja yang berkomentar “miring” karena menganggap bahwa lembaga ini seperti mau menjadi gereja baru yang berlawanan dengan tradisi gereja di Timor Lorosae. Tapi bagi Mana Lou, (Tetun, Mana = Kakak), begitu ia biasa dipanggil, persoalannya adalah bagaimana mengembangkan pemikiran baru tentang apa artinya menjadi gereja. Mana Lou jarang berfilsafat atau bermain-main dengan konsep tentang kegiatannya. Baginya sederhana saja. Unsur paling penting adalah persaudaraan dan persekutuan, pembagian kerja merata sehingga semua dapat mengambil bagian di dalamnya. Untuk itu dibentuk kelompokkelompok yang dibantu oleh seorang pembimbing. Tugasnya bukanlah memahami Injil di tingkat wacana dan menghapal isinya, tapi bagaimana menghayati isinya melalui kerja bersama kaum miskin yang dipinggirkan oleh “pembangunan”. Di Dare saat ini Institut Sekulir menampung anak-anak yang kehilangan orang tuanya setelah penghancuran Timor Lorosae pada 1999. Diskusi adalah hal penting dalam perumusan dan pelaksanaan program institut. Para suster yang dididik Mana Lou tidak datang untuk berkotbah, tapi untuk berdiskusi mengenai segala hal menyangkut keimanan maupun peran gereja d Timor Lorosae saat ini. Kebudayaan menjadi sangat penting, karena dengan cara itulah gereja dapat berkomunikasi, tidak sekadar menyampaikan pesan-pesan dari luar kepada komunitas yang bersangkutan. Dari diskusidiskusi itulah setiap kelompok menentukan program kerjanya, mulai dari penyediaan bibit tanaman yang diperlukan petani sampai pada pengembangan usaha. Para anggota institut hidup layaknya masyarakat umum. Mereka tidak menggunakan jubah seperti biasa dikenakan suster dan pekerja gereja lainnya, karena mengemban konsep “sekuliritas” (ke-duniawi-an). Seringkali para pekerja yang “sekulir” ini dianggap sebagai pembantu yang hanya melengkapi kegiatan “resmi” gereja, tapi justru Mana Lou menekankan bahwa gerakan sekulir ini adalah panggilan khas dengan kharisma tersendiri. Mereka yang terlibat diharapkan hidup seperti biasa dalam dunia, tapi tanpa terikat dengan hal-hal yang duniawi. Dengan begini orang dapat menghayati kemiskinan, sebagai orang yang sungguhsungguh tidak punya sesuatu kecuali hati nurani untuk melayani sesama. “Berada di dunia, bukan berarti kita mencari untung dari dunia atau mencari pegangan serta tempat tinggal tetap di dunia,” kata Mana Lou. Berpijak di Basis Kegiatan Institut Sekulir dimulai dan bermuara di basis-basis. Tidak ada keinginan untuk ikut bermain atau bersaing dalam birokrasi gereja. Bekerja di basis adalah prinsip, dan setiap anggota yang ingin terlibat bertolak dari sana. Di zaman pendudukan Indonesia, kegiatan Mana Lou masih sangat terbatas, karena pembatasan gerak oleh TNI. Walau begitu kontak dan hubungan dengan komunitas basis sudah mulai dijalin, dan berkembang setelah rakyat Timor Lorosae menentukan pilihannya dalam referendum pada 1999. Di Liquiça, sekitar 30 kilometer sebelah barat kota Dili, Institut Sekulir terlibat dalam kegiatan menjahit untuk kelompok perempuan, dan juga berdiskusi tentang perawatan anak, baik secara fisik maupun rohani. Karena keterlibatannya yang luas dan kongkret inilah, Mana Lou juga sering diminta untuk menangani pemulangan pengungsi, mengusahakan rekonsiliasi di antara warga dan membangun perdamaian bersama-sama. Begitu pula dalam kegiatan pemilihan umum yang baru lalu, Institut Sekulir memberikan pendidikan mengenai konstitusi dan berdiskusi tentang bermacam hal, mulai dari posisi perempuan, anak dan keluarga dalam konstitusi sampai sistem kenegaraan, ekonomi dan hukum. Pekerjaan di basis bermula dari diskusi. Bagi Mana Lou rakyat menderita karena selalu dituntut untuk mendengarkan penguasa. Tidak pernah penguasa yang mendengar dan rakyat berbicara. Salah satu prinsip yang berusaha ditegakkan adalah memberi kesempatan kepada semua orang, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, untuk berbicara dan duduk merundingkan masalah bersama-sama. Bagi masyarakat bekas jajahan seperti Timor Lorosae, semua ini adalah langkah awal bagi pembebasan yang lebih luas. Hanya dengan begini masalah-masalah yang dihadapi rakyat dalam keseharian bisa terangkat, dibicarakan dan dicari pemecahannya. “Tidak mungkin pemerintah atau orang-orang besar itu bisa menyelesaikan masalah, kalau mengenali masalahnya saja tidak mau,” ujar Mana Lou. Pembebasan bagi Institut Sekulir dimulai dari memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang untuk menghadapi masalah mereka dengan caranya sendiri. Untuk itu Institut sering mengajak anak-anak untuk menggali kebudayaannya sendiri, bernyanyi, menari dan menampilkan kreasi mereka, agar tidak terus dihinggapi trauma kekerasan dan larut dalam kesedihan terus-menerus. Kegembiraan dan kesenangan pada hidup adalah langkah pertama untuk bebas. Untuk memperdalam pengetahuan anggota dan menambah kekuatan basis, Institut bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak memberdayakan masyarakat, seperti Forum Komunikasi Perempuan Loro Sae (Fokupers) untuk masalah-masalah perempuan, Yayasan HAK dan perhimpunan pengacara untuk bidang hak asasi manusia. Dari diskusi dengan bermacam kalangan, Institut dapat memperkaya pengetahuan sekaligus mengajak semakin banyak orang terlibat dalam penguatan gerakan tingkat basis ini. Tapi pelajaran paling berharga selalu didapat justru dari masyarakat “dampingan”. Sejak awal Mana Lou berpikir tentang gereja yang kontekstual, yang membiarkan masyarakat bebas mengembangkan kepercayaan lama pra-gereja. Baginya, Portugis menjadikan gereja sebagai alat untuk memuluskan penjajahan, lalu membunuh segala kepercayaan yang ada sebelumnya. Padahal kekuatan spiritual atau keyakinan seseorang sangat bergantung pada cara seseorang itu melakukannya. Gereja adalah salah satu tradisi saja, dan norma-norma (Eropa) yang ditanamkan di dalamnya belum tentu sejalan. Gereja menurutnya, harus memberi kesempatan orang mencari jalan keimanannya sendiri, bukan hanya dengan mengekor pada tradisi mapan yang datang dari luar. Paksaan adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, bukan hanya karena melanggar hak seseorang, tapi juga karena tidak akan benar-benar meresap ke dalam hati. Dengan pendekatan seperti ini Institut Sekulir diterima secara luas oleh masyarakat, dan saat ini sudah mengembangkan kegiatannya di distrik-distrik lain, seperti Liquiça, Aileu dan Same di bagian barat dan tengah Timor Lorosae. Religiositas Rakyat Para pekerja institut memahami bahwa ada bermacam lapis penindasan terhadap rakyat. Kolonialisme Portugis dan militerisme Indonesia memang nampak di permukaan, tapi bukan berarti bahwa penindasan hanya berhenti di tingkat itu. Rakyat Timor Lorosae selama ratusan tahun juga hidup dalam budaya feodal, eksploitasi oleh tuan-tuan tanah dan raja-raja kecil yang diangkat oleh penguasa kolonial untuk menjadi tuan atas kaumnya sendiri. Ada juga dari mereka yang menikmati posisi itu, sekalipun sama-sama menderita di bawah kekuasaan asing. Realitas ini mengganggu pikiran Mana Lou dan membawanya berkenalan dengan ide-ide teolog terkenal Leonado Boff yang menulis buku Igreja Carisma e Poder, Ensaios de Eclesiologia Militante, pada tahun 1982. Di sini Boff menguraikan pandangannya bahwa gereja sudah seharusnya berpijak pada realitas. Khusus di Dunia Ketiga gereja yang mengagungkan posisinya sendiri ternyata justru mendukung penindasan, seperti terjadi di banyak negara jajahan. Kritik Boff menjadi dasar bagi Mana Lou saat menyusun skripsi dan juga merumuskan dasar-dasar kegiatan Institut Sekulir. Seluruh energinya kemudian dikerahkan untuk mengkritik hirarki gereja melalui kerja, bukan sekadar menulis sindiran dan bergunjing di belakang sambil menikmati segala fasilitas yang disediakan oleh hirarki itu. Bagi Mana Lou, gereja tidak bisa mengajar bagaimana orang menjadi saleh. Sebaliknya gereja harus melihat apa yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat. Misionaris Portugis sejak awal kedatangannya memperkenalkan nilai Kristiani melalui devosi (unjuk kesetiaan) kepada simbolsimbol, para santo lengkap dengan segala pesta yang terkait dengannya. Dari perspektif kritis, praktek semacam ini tentu sudah “ketinggalan zaman”, tapi bagaimanapun gereja harus bertolak dari apa yang ada, dan mencoba membuat perubahan dengan kekuatan masyarakat sendiri. Rakyat memiliki caranya sendiri untuk mengembangkan keimanan atau religiositas. Dan dengan keimanan pula orang bertahan menghadapi segala bentuk penindasan dan siksaan selama berabad-abad. Dalam situasi penderitaan yang hebat, agama dan keimanan menjadi satusatunya pegangan yang tidak dapat dirampas. Perjuangan kemerdekaan Timor Lorosae juga membuktikan agama berperan penting untuk meneguhkan sikap melawan penindasan. Agama dalam hal ini sungguh-sungguh menjadi milik rakyat dan memiliki arti tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Keimanan tidak terbatas pada pemujaan terhadap simbol-simbol. Kolonialisme Portugis dan militeris Indonesia tidak memahami semua ini, seperti terlihat dari patung Kristus Raja di ujung timur kota Dili. “Rakyat tahu bahwa patung itu bukan milik mereka, maka hampir tidak ada orang yang datang berziarah ke sana,” kata Mana Lou. “Itu patung Kristus Politicus, hanya benda yang dibuat untuk merebut simpati rakyat.” Religiositas rakyat berkembang di basis-basis, dari pertemuan berkala untuk membahas nilainilai Kristiani di pemukiman kumuh, desa atau dusun dan ladang pertanian. Para pendamping, begitulah Mana Lou menyebut pekerja gerejanya, mengajar sekaligus belajar mendalami keimanan berdasarkan praktek kehidupan sehari-hari. Pengembangan iman menurutnya hanya bermakna jika dapat menjadi sumbangan dan memberi kualitas baru bagi gerak membebaskan diri dari belenggu penindasan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Ketika basis-basis berkembang menjadi organisasi swadaya, ketika umat sadar dan tidak mempercayai segala manipulasi, seperti kecurangan dalam pemilihan umum, atau paternalisme negara, dan mampu bangkit sendiri, maka religiositas tumbuh bersamanya. Melayani Rakyat, Mengabdi Tuhan Vox Populi, Vox Dei. Sebuah rumusan yang sering dilafalkan para pemimpin, tapi jarang dipraktekkan. Sebaliknya Institut Sekulir mencoba untuk tidak terperangkap dalam dunia jargon dan mengembangkan penghayatan konsep-konsep itu melalui pekerjaan di tingkat basis. Para anggota Institut memenuhi panggilan khususnya sebagai “orang awam” (istilah dalam hirarki gereja bagi orang yang tidak diajar khusus untuk menjadi pemimpin), untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Pelayanan terhadap rakyat adalah karya kerasulan yang utama berdasar tiga nasehat dasar dalam Injil: kemurnian, ketaatan dan kemiskinan. Tapi kehadiran mereka bukan tanpa soal. Seringkali rakyat mengharapkan pemikiran dan kepemimpinan dari luar, setelah sekian lama hidup di bawah patronase. Sementara anggota Institut juga menekankan bahwa rakyat hanya mungkin kuat jika menyadari apa yang mereka miliki, bukan hanya melihat apa yang datang dari luar. Dalam proses yang kadang berlangsung bertahun-tahun, akhirnya kesadaran bersama bahwa “gereja milik rakyat” pun bisa berkembang, di mana kaum miskin menghayati religiositas dalam perjuangannya untuk mencapai kehidupan lebih baik. Keputusan-keputusan penting mengenai karya kerasulan tidak dilakukan sekelompok kecil pemimpin seperti biasanya ditemui dalam hirarki gereja, tapi oleh rakyat di tingkat basis. Dialog menggantikan sabda-sabda, dan kerjasama menggantikan perintah. Saling belajar adalah prinsip penting, karena anggota Institut menyadari keterbatasan mereka sebagai manusia. Bagi Timor Lorosae yang hidup selama berabad-abad dalam budaya paternalisme, langkah Institut Sekulir memang tidak lazim dan mendobrak sikap pasif terhadap penderitaan rakyat yang kadang diperlihatkan oleh hirarki. Namun bukan berarti bahwa Institut Sekulir telah meninggalkan segala tradisi yang ada. Pelajaran agama yang “klasik” dengan cara membacakan ajaran dan mendengarkan khotbah tetap menjadi bagian penting. Tapi semua itu kemudian diolah lebih lanjut dalam dialog dan karya kreatif. Hanya dengan mencipta orang bisa mengembangkan imannya, demikian berulangkali para pekerja Institut berujar. Keberanian untuk mendesak, berpikir dan mencipta yang akan membawa perubahan sekaligus pendalaman nilai-nilai agama. Dalam konteks ini Institut Sekulir menghayati keputusan-keputusan dalam Konsili Vatikan II yang menekankan pentingnya dialog antara hirarki gereja dan umat atau rakyat, serta gerakan teologi yang membela dan memperjuangkan rakyat miskin di Dunia Ketiga. Rakyat Timor Lorosae yang sedang menempuh perjalanan berat menuju kemerdekaan, patut bersyukur dan bangga akan adanya gerakan Institut Sekulir, yang terus berjuang mengadakan perubahan dan pembaruan, sekalipun menghadapi tantangan dan cobaan yang berat. Kesabaran dalam melayani rakyat menjadi teladan bahwa perubahan tidak datang melalui caci-maki, kritik dan debat berkepanjangan, melainkan kerja nyata bersama rakyat. Mateus Gonçalves, anggota Sahe Institute for Liberation, Dili, Timor Lorosae
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
PUISI HUSNUL KHULUQI Catatan 30 Juni 2000 baju celana telah kukemas di kardus bekas indomie hatiku berbunga, senang sekali wajah ibu, kakak-kakak perempuanku juga ponakan-ponakanku yang sekian lama kurindu bagai menari-nari di mataku ya, selepas gajian sore ini aku akan pulang kampung mengobati rasa kangen di hati keluar dari loket pengambilan gaji kuhitung uangku, hutang-hutangku juga uang sewa rumah petak kepalaku mendadak pusing ternyata aku banyak hutang ternyata aku banyak kebutuhan dan keinginan untuk pulang kampung terpaksa kutunda lagi 2000 Ada yang Menangis ada yang menangis dialah tetangga kita yang suaminya kena phk karena ikut unjuk rasa suami tak lagi kerja hidup kian sulit padahal anak-anak mesti sekolah dan bila dapur tak lagi ngebul apakah masih ada harapan untuk perut yang lapar? ada yang menangis dialah tetangga kita apakah kau juga mendengarnya 2000 Mati Lampu di Rumah Petak malam tambah muram udara tambah pengap hidup tambah gelap sebatang lilin menyala tegak meleleh habis dalam sekejap malam tambah muram saja hidup semakin penuh teka-teki langkah kaki kian tak pasti semakin surut, semakin ke tepi dan esok hariku tak pernah kutahu 2000 Sayur Kangkung, Ikan Asin sayur kangkung, ikan asin menu yang dihapal lidahku sungguh sudah tak asing tiap hari mampir bibirku sayur kangkung, ikan asin tak perlu aku tolak tak perlu aku benci karena itu yang mampu kubeli 2000 Husnul Khuluqi, selain menulis puisi, sehari-hari ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil di Karawaci, Tangerang.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
Cari!
PicoSearch
Cari!
Pledoi Mendobrak Si Moni Kamasra STSI Denpasar Awal Dari Si Moni. Layaknya sebuah gerakan yang bermaksud mendobrak, menabrak, menggasak, mengkritik dan sejenisnya sudah dapat dibayangkan reaksi balik atau efek yang bakal ditimbulkan. Demikian halnya dengan gelar seni rupa ‘Mendobrak Hegemoni’ Kamasra STSI Denpasar yang berlangsung pada Februari 2001 di Lapangan Puputan Badung, kontan saja mendapat tanggapan dari semua pemain seni rupa yang terkena kritik. Reaksi balik mereka tidak kalah kerasnya bahkan ikut-ikutan memaki, mengejek, menuduh dsb, yang semakin menunjukkan kualitas ‘keseniorannya’. Mereka ternyata kebakaran jenggot plus kumis ketika merasakan egonya dikocok, namun tidak sedikit yang acuh tak acuh. Di sisi lain sejumlah seniman, pakar, menunjukkan kenetralannya dalam menanggapi persoalan ini. Paling tidak ada yang berusaha menilai secara proporsional. Tapi kami berpikir inilah saat yang tepat untuk lebih menggairahkan wacana seni rupa Bali yang telah lama impoten ditelan romantisme kebalian dan jayanya kolonialisasi seni dan orientalisme Timur yang sangat turistik. Wacana orientalisme Barat yang secara tidak sadar dipakai oleh elite Indonesia untuk melihat kesenian kita. Dari sini sebenarnya benih hegemonisasi secara umum, khususnya di bidang seni sudah terjadi. Orang mengatakan ini ‘penjajahan ide’. Sekali lagi, awal gerakan ini adalah sebagai sebuah gerakan kultural dan penyadaran yang membuka mata tentang kondisi seni yang tidak kondusif dan kritik terhadap personal yang dianggap menghujat tidaklah dimaksudkan untuk menjatuhkan nama atau kelompok-kelompok seni tertentu. Di samping itu, kami sadar bahwa pemahaman mengenai gerakan ini di masyarakat dan pelaku seni sungguh-sunguh sangat ‘dangkal’. Reaksi masih seputar cara mengkritik, dan menganggap gerakan ini akibat kecemburuan seniman muda bahkan kelompok seniman yang dianggap frustrasi. Mereka menjuluki kami sebagai drunken master dengan jurus-jurus mabuknya. Bahkan dominasi opini berani berasumsi bahwa gerakan ini sebagai gerakan tanpa arah, penuh intrik, konspirasi politik dan konflik pribadi untuk saling menjatuhkan. Bahkan opini yang berkembang mencurigai gerakan ini didalangi oleh pihak atau kelompok tertentu. Pola berpikir yang bernuansa intel jaman Orba ini sangatlah paranoid. Mereka berasumsi bahwa mahasiswa tidak cukup pintar untuk bisa menganalisis suatu fenomena sehingga haruslah ada aktor/dalang pintar di balik gerakan ini dan kecurigaan akan adanya penyandang dana sebagai sponsor. Bagi mereka yang biasa berpikir dalam hitungan M, yang rela membatalkan membeli mercy untuk ‘tujuan mulia’ seni-perdamaian dan terbiasa dengan eksibisi yang glamor di gedung museum-galeri yang megah atau di ruang pamer hotel bintang lima (dengan model lotere seperti SDSB) dengan katalog luks yang dipenuhi kata sambutan orang-orang berkuasa, tentu saja menganggap mustahil kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan dana pas-pasan. Sindrom kecurigaan orang kaya memandang modal besar lebih utama dibanding menjual visi dan sedikit kenekatan. Keterlaluan barangkali diobok-oboknya lembaga STSI secara berlebihan dalam bentuk penekanan dominasi yang terkesan melangkahi otoritas. Contohnya tuntutan untuk memberi sanksi akademis berupa pemecatan bahkan upaya hukum terhadap mahasiswa yang terlibat dalam gerakan ini. Akhirnya masalah ini menjadi semacam konflik personal antara yang dikritik dan mengkritik. Keadaan semakin keruh karena media massa yang seharusnya mampu mewacanakan konflik secara objektif dan proporsional malah memuat pemberitaan sangat tendensius dan tidak berimbang. Situasi ini mengakibatkan tidak terjadinya dialektika dan proses diskusi yang sehat dan dinamis. Keadaan pasca ‘Mendobrak’ yang mirip benang kusut ini tentulah akan merugikan kedua belah pihak. Dengan mencoba untuk merefleksikan secara keseluruhan polemik, wacana, isu dan konspirasi yang berkembang maka sudah sepantasnya kita maju selangkah dengan mencoba meninggalkan ego, apologi dan pembenaran yang sifatnya sepihak dari kedua belah pihak. Dengan rendah hati bersedia menuju ruang dialog karena betapapun peliknya permasalahan selalu terbuka untuk dibicarakan demi sebuah penjernihan. Seputar Cara Mengkritik Dalam polemik seputar acara ‘Mendobrak Hegemoni’ itu, hal yang paling mengedepan adalah soal cara mengkritik yang dalam anggapan mereka sebagai sesuatu yang kebablasan, kasar, anarkis, barbar, dsb. Cara ini segera dicap sebagai perilaku kekanak-kanakan, gaya Orde Baru dan preman yang tak berwawasan, dianggap melanggar etika, moral dan pelecehan terhadap kelompok tertentu, institusi maupun personal yang terkena kritik. Namun anehnya tanggapan mereka tidak sedikit yang terjebak dalam cara mengkritik yang sama bahkan disertai ancaman. Bukankah hal semacam ini menunjukkan realitas ‘kebarbaran’ yang ada pada tiap individu maupun kelompok bahkan pada setiap kebudayaan maupun peradaban. Penilaian semacam itu juga bisa muncul akibat ada yang merasa dirugikan dari kemapanan yang telah mereka ciptakan. Sebagai sebuah metode mengkritik yang tendensius bahkan vulgar model di atas tentu sah-sah saja. Hal ini tentu didasari oleh alasan yang setidaknya bisa diterima oleh akal sehat dan bukan sekedar kebablasan yang membabi buta. Persoalan akan menjadi runyam ketika metode semacam ini dibenturkan oleh persepsi yang bersumber dari etika, moral maupun tata nilai yang sering kali anti-kebebasan dan bersifat memvonis secara terburu-buru. Di sinilah diperlukan keterbukaan untuk melihat suatu hal dan konteks persoalan yang hendak dikritik. Disadari atau tidak, persoalan yang hendak didobrak oleh Kamasra sudah dalam tahap emergency sehingga diperlukan metode yang bersifat shock therapy yang sangat efektif. Lagi pula bukankah ini merupakan ekspresi yang muncul akibat kemuakan yang berlebihan. Menjelekkan belum tentu sejelek yang disangka, walaupun mengandung senda gurau dan keakraban di dalamnya dan masih dalam bingkai seni bahasa komunikasi dalam suatu komunitas. Soal kata yang sangat ‘puitis’ seperti, “fuck you, bapak-bapak kok ngga paham sih bahasa anak muda, sekali-sekali dengerin dong mp3 Limp Bizkit atau lagu kelompok Jamrud”, di situ bertebaran kata atau idiom yang luar biasa ‘puitis’. Atau dalam salah satu puisinya Sutardji menyelipkan kata pukimay yang artinya... Dan setidaknya sebagai trik untuk mengangkat persoalan ternyata lumayan efektif. Terlepas dari tujuan yang bermaksud merusak harmoni sosial. Kenapa kami mempermasalahkan orang-orang dan bukannya sistem ‘anonim’, yang menurut beberapa orang jauh lebih ‘elegan’? Karena kami anggap mereka adalah para ‘tokoh-tokoh kunci’ yang menjadi panutan banyak seniman. Sesungguhnya orang-orang seperti Erawan, Gunarsa dan Wianta itu sudah menjadi patron dalam kancah seni rupa Bali terutama bagi beberapa seniman muda. Sampai ada istilah ‘Erawanisme’ yang berarti dia bahkan sudah bukan person lagi melainkan sudah menjadi suatu isme tersendiri. Figur Erawan sendiri sudah menjadi sebuah ‘institusi’. Bisakah kita menampik keberadaan ‘faktor’ Gunarsa dari eksistensi Sanggar Dewata Indonesia (SDI)? Sebagai ‘institusi’ dia bukan lagi menjadi wilayah personal belaka melainkan menjadi wilayah umum dan anonim. Dan itu artinya dia bisa dikritik sebagai institusi dan terlepas dari personnya. Mengkritik sebuah sistem yang anonim akan memberi ruang tempat ‘berkilah’ bagi person-person yang menjadi komponen dalam sistem itu. Saling tunjuk hidung orang lain dalam sistem yang sama dan merasa ‘bukan saya’ akan menjadi jawaban yang klise. Metode memang tidak akan berhenti cuma sebagai cara dan bisa saja menimbulkan efek yang bermacam-macam terlebih hal ini berhadapan dengan kemapanan budaya (budaya Bali yang menempatkan etika dan moral dalam posisi yang istimewa), sehingga tak berlebihan apabila ada selentingan yang muncul, jika kegiatan ini tidak terjadi di Bali barangkali ceritanya tidak akan heboh. Wacana Hegemoni Dalam katalog pameran yang sangat sederhana namun laris manis itu, kami telah mengatakan bahwa elemen-elemen seni rupa (seniman, art dealer, spekulan, kolektor, galeri, museum, kritikus, jurnalis seni, media massa, dsb) di Bali dan Indonesia telah berkongsi dalam menciptakan iklim hegemoni seni. Tentunya dengan perkongsian yang telah merasuk kepala semua pelaku seni rupa, akhirnya menciptakan koor bersama untuk berteriak satu kata, satu motivasi yaitu: duit. Adanya jaringan kepentingan semacam ini dengan sangat mudah dibaca adanya hegemoni yang berarti kekuasaan secara berlebihan. Ada pengamat seni rupa Bali yang mengatakan gerakan ini mengacaukan peta seni rupa kontemporer Bali, yang memang sudah kacau semenjak dahulu karena kuasa duit. Kami hanya bisa memberikan jawaban bahwa gerakan ‘Mendobrak Hegemoni’ ini memang lahir untuk melakukan proses dekonstruksi terhadap peta seni rupa Bali yang dikuasai oleh gembonggembong mafioso seni dan kongsi antara para cukong-kolektor seni. Tapi kami ingin melakukan aksi kultural dan alternatif menentang semua dominasi itu. Ekspresi jelaslah tidak ingin mengekang orang lain untuk berpendapat dan berekspresi. Tetaplah berpikir bahwa hanya perubahan yang abadi, dengan kritik dan wacana baru yang terus berkembang. Disamping itu, wacana dan aksi seni rupa dominasi yang berperang dengan alternatif, dibingkai dalam dunia besar kapitalisme dan industrialisasi seni rupa yang sangat tidak menghiraukan dunia estetis dan kreatif. Wacana dominasi yang kami maksudkan memang sangat sederhana dan sulit untuk membuat pemegang kekuasaan untuk sadar diri. Kelompok-kelompok seni semacam Sanggar Dewata Indonesia dengan wacana dominasi simbolisme dan ikon kebalian bisalah dipakai sebuah contoh. Wacana dominasi ini bisa mereka ciptakan karena dukungan kongsi pemain seni yang sudah mereka pegang di semua lini. Akhirnya meraka hadir sebagai sesuatu yang sangat hebat dan maha sempurna. Tapi, kacaunya meniadakan kelompok atau wacana alternatif yang lain. Disinilah mereka telah menciptakan hegemonisasi seni yang terus terang saja katanya, tidak mereka sadari. Hegemoni sebagai sebuah jaringan kepentingan di mana masing-masing komponen pemain seni rupa mempunyai peran yang berbeda, namun tidak jarang kelompok pemain tertentu, semisal kelompok seniman senior mempunyai otoritas yang sangat kuat. sehingga kelompok lainnya menjadi tidak berdaya. Dalam hal ini konteks hegemoni pada masing-masing elemen pemain seni rupa telah dicoba diletakkan bagi kepentingan analisis terhadap perkembangan dinamika seni rupa pada skala lokal di Bali. Melalui perilaku, gejala dan beberapa fakta yang tidak selalu mudah dilacak namun kerap menjadi perbincangan keseharian. Komponen pertama adalah kelompok seniman.Yang menarik dalam hal ini adalah kelompok Sanggar Dewata Indonesia (SDI), sebuah kelompok perupa terbesar dan tertua di Bali saat ini. Awalnya Kelompok ini dimotori oleh seniman jebolan ISI Yogyakarta yamg pentolannya sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh seni rupa di Bali, menjadi patron dalam sanggar maupun dalam skala yang lebih luas. Konsep yang mereka dendangkan adalah ikhwal spiritualisme Hindu Bali dan budaya Hindu Bali, yang oleh pengamat seni rupa Jean Couteau dibaca sebagai wacana identiter. Karya-karya mereka memang sebagian besar mengambil, mencomot atau terinspirasi dari ikon-ikon dan khasanah budaya Bali. Pencapaian dan pengembangan teknis yang sangat ekspresif seperti efeks, nyapu, dan plototan sangat signifikan sebagai pencapaian teknik yang jauh dari teknik melukis tradisional terdahulu. Mereka menjual estetika, kecenderungan besar yang sering dibaca sebagai ekspresionisme berikut variannya. Capaian estetika modern ini menemukan momentum pasar yang sangat potensial didorong adanya boom lukisan dan perkembangan pasar lukisan di Bali. Bisnis kesenian mulai marak. Di sinilah pasar mulai menunjukkan otoritasnya. Banyaknya GunarsaGunarsaan, Erawan-Erawanan dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan hal ini menghegemoni dirinya sendiri seperti kecenderungan repetisi, ‘memproduksi’ karya sebanyakbanyaknya untuk ditebar merata pada setiap galeri yang ada dengan kalkulasi satu hari minimal harus ada satu yang laku. Misalnya 10 juta perbiji perhari. Motivasi pasar mendorong bertebarannya karya-karya generasi muda dengan kecenderungan plagiat/epigon. Ikon-ikon budaya pun dengan mudah ditawarkan sebagai konsumsi, misalnya pemakaian simbol yang mengesankan seolah senimannya adalah pendukung militan budaya Bali. Bukan hendak bicara sakral yang diprofankan, tapi eksploitasi yang perlu dikhawatirkan dan seringkali kecenderungan memakai simbol sebagai dagangan akan menutup mata terhadap realitas objek seni yang lain. Hegemoni estetika semacam ini menjadi kecenderungan bahkan sampai merasuk dalam iklim pendidikan seni di akademi-akademi, ini tentu sangat berbahaya bagi proses pendidikan. Komponen yang kedua adalah pebisnis seni. Menjamurnya galeri-galeri komersial pada sentrasentra pariwisata di Bali. Betapa menggiurkannya bisnis seni rupa berarti percetakan uang. Kalau mau jujur semua galeri berwajah seragam, tidak punya visi seni karena terutama adalah bisa menyediakan dagangan yang laku untuk dijual. Tidak usah susah-susah berinvestasi, para perupa muda yang mempunyai potensi ke depan, langsung saja mencari tahu lukisan siapa yang laku, lalu harus dikejar. Dagangannya mirip pasar swalayan yang menyediakan mulai dari lukisan tradisi sampai modern, kontemporer dan sebagainya, dari pelukis muda sampai pelukis yang sudah uzur, bahkan kalau sudah kepepet pelukis yang masih hidup dibilang sudah mati, biar harganya terdongkrak. Logikanya pelukis yang menyandang gelar Alm. tidak berproduksi lagi, dengan sedikit penawaran tinggi maka harga karyanya menjadi mahal. Galeri hanya giat membikin brosur mewah di setiap brosur wisata dan tidak merasa risih tidak memiliki kurator atau penilai karya yang berwibawa. Acuan kurasi: nol besar!! Mereka berlomba memberi prosentase yang tidak rasional, menurut gosip 50% untuk jasa wisata atau guide dan cuma beberapa persen untuk pelukis. Pemain bisnis seni rupa di Bali untuk kurun waktu yang sangat lama nampaknya dipegang oleh raja galeri. Baru dari beberapa dekade yang lalu muncul spekulan-spekulan kakap bahkan spekulan yang muncul dari tanah Jawi, mulai banyak agenagen pengorder dan pengepul yang menyusup langsung ke studio pelukis. Museum-museum yang ada di Bali juga menunjukkan tata kerja atau model permainan yang tak terlalu jauh berbeda dengan galeri. Dari model publikasi yang lebih giat berpromosi ke luar negeri bahkan ada yang membuat buku dalam bahasa Inggris. Koleksi juga seragam, lalu di mana peran edukasi dan dokumentasi dari sebuah museum? Komponen ketiga adalah kritikus dan jurnalis seni. Kritikus dan jurnalis dipesan untuk menulis. Tetapi objektivitas mulai hilang ketika model tulisan yang berbau iklan dengan analisis yang sering kali tanpa acuan yang kritis dan menyanjung secara berlebihan, buntutnya adalah peran wacana dan acuan apresiasi menjadi terabaikan. Masyarakat, pencinta seni dan kolektor tak terdidik dalam berapresiasi. Maka jangan heran kalau lukisan yang laku dalam sebuah pameran sampai ada yang dikocok bak lotere (pemenangnya dapat kanvas kosong dan kemudian dilukis on the spot, langsung dibubuhi tanda tangan dan diangkut selagi catnya masih basah) dan bukan karena apresiasi. Demikian juga peran media dalam memberitakan kegiatan gelar seni karya seniman beken tertentu yang itu-itu saja, sering over dosis dan memuji-muji berlebihan sehingga terkesan media sebagai pengiklan galeri maupun pelukis. Gambaran di atas menunjukkan betapa runyamnya atmosfer berkesenian di Bali. Barang seni menjadi mirip benda pakai, objek utilitas seperti TV, kondom, komputer dan sebagainya. Idealisme, kreatifitas, eksperimentasi yang lekat dengan kerja seni menjadi dikorbankan. Seniman kehilangan kredo-kredo berkeseniannya karena terhegemoni oleh faktor-faktor eksternal pasar yang semestinya diletakkan sebagai sebuah efek terhadap kualitas seni yang mampu dihasilkan oleh sang seniman. Logika pasar juga bisa berlaku bahwa barang yang diproduksi terlalu banyak akan kehilangan kemampuan nilai tawarnya. Kalau karya seni mengikuti logika semacam itu maka seni berada pada posisi tawar yang terendah bahkan diobral. Sebuah acuan estetika dengan membangun image nilai dan nilai pasar sadar atau tidak akan menimbulkan hegemoni dengan motivasi yang sangat beragam. Kalau meminjam ikon estetika tertentu masih dalam kerangka motivasi pencarian, merupakan suatu hal positif dan wajar dalam berkreasi, namun motivasi material semata sangatlah berbahaya bagi idealisme sebuah pencarian. Hegemoni dalam sistem dan estetika inilah yang sebetulnya hendak didobrak atau dikritik. Kritik yang berkehendak mengadakan perubahan. Sistem yang didobrak bisa melakukan otokritik dan yang lain bisa bikin alternatif atau saling melebur diri. Demikian juga dobrakan estetika tidak secara otomatis harus menawarkan sesuatu yang baru secara seketika. Spirit perubahan paling tidak mampu melakukan semacam antitesis dalam mencari alternatif sebagai bentuk penawaran yang mungkin akan relatif berbeda tergantung proses dan dinamika sebuah gerakan. Tidak berlebihan kalau ada pengamat yang mengatakan gerakan ini telah mengacaukan peta seni rupa kontemporer Bali. Ini barang kali konsekwensi logis dari sebuah gerakan yang menimbulkan semacam implikasi atau efek yang bisa tidak terduga terhadap siapapun yang berkepentingan di dalamnya. Konsekwensi yang paling riil bagi pengkritik barangkali adalah komitmen, integritas moral terhadap rel dan keyakinan yang telah didendangkan dan dipertaruhkan. m KAMASRA (Keluarga Mahasiswa Seni Rupa) STSI Denpasar, Bali.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Resink dan Mitos Penjajahan 350 Tahun Razif Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itulah satu dari sedikit warisan pemikiran pra-Orba yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam upacara-upacara resmi, para pejabat yang merasa perlu memobilisasi semangat orang, selalu mengucapkannya. Sejak 1930-an, gerakan nasionalis menjadikan pernyataan ini sebagai bahan agitasi dan propagandanya. Menariknya, pada saat bersamaan di kalangan penguasa kolonial pun ada perdebatan serupa. Para pemilik perkebunan, birokrat kolonial dengan dukungan kalangan konservatif di Belanda bergabung dalam Vaderlandsche Club, yang ingin melanggengkan kolonialisme setidaknya untuk 350 tahun lagi, dan tidak melihat perlunya “berbaik hati” pada orang bumiputra melalui Politik Etis, karena ternyata hanya melahirkan pemberontakan. Pada 1926-27 terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan serikat-serikat rakyat di Jawa dan Sumatera Barat. Kalangan konservatif mendapat angin untuk menindas gerakan nasionalis dan sekaligus menyingkirkan pendukung Politik Etis dari birokrasi kolonial. Posisi mereka ditentang oleh kelompok Stuw yang berbasis di Leiden, dengan anggota-anggota seperti J.H.A. Logeman dan H.J. van Mook. Mereka didukung oleh sarjana-sarjana kolonial yang berpendapat bahwa Belanda tidak pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun, dan karena itu tuntutan “melanjutkan penjajahan” untuk kurun waktu yang sama, menjadi tidak masuk akal. Mereka berpendapat sebaiknya negeri induk memberi kemerdekaan secara bertahap, dan mengelola sumber daya alam serta kegiatan ekonomi bersama-sama, seperti layaknya negara persemakmuran di bawah Inggris. Menindas gerakan nasionalis adalah pemborosan di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip Etis yang dikembangkan sebelumnya. Perdebatan itu tertunda ketika kekuasaan kolonial dipenggal oleh serbuan Jepang pada 1942. Gerakan nasionalis menjadikan arogansi Vaderlandsche Club sebagai bahan propaganda dan menulis kembali sejarah dengan membalik seluruh argumentasi yang terkandung di dalamnya. Apa yang oleh Vaderlandsche Club disebut sebagai kejayaan menjadi penindasan, pahlawan menjadi penjahat dan sebaliknya. Tapi keduanya sepakat bahwa Indonesia memang dijajah Belanda selama 350 tahun. Di tengah pergulatan ini muncul Gertrudes Johan Resink, mahasiswa sekolah hukum di Batavia, keturunan Indo-Belanda yang lahir di Yogyakarta pada 1911. Ia mendalami sistem hukum Indonesia, terutama hukum antar bangsa di bawah asuhan J. H.A. Logeman, tokoh kelompok Stuw. Setelah menyelesaikan karya pertamanya mengenai sejarah hukum Madura, Resink bekerja sebagai pegawai negeri di sekretariat Gubenur Jenderal Buitenzorg (Bogor) hingga kedatangan balatentara Jepang. Pada 1947 ia menjadi satu dari sedikit ahli hukum yang tetap bertahan di Indonesia. Ia menggantikan Logeman mengajar di almamaternya, yang telah diubah menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Indonesia. Selama sepuluh tahun ia meneliti kembali hubungan Indonesia-Belanda dari perspektif hukum, untuk membongkar apa yang menurutnya adalah mitos-mitos, termasuk klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Ia adalah orang pertama yang secara kritis mengkaji kembali kebijakan pemerintah kolonial sejak abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Hasilnya adalah rangkaian esei yang kemudian dibukukan dan diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Indonesia, dengan judul Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910. Dengan perhatian utama pada keputusan pemerintah kolonial “yang dilupakan” baik oleh sejarawan Belanda, tokoh Vaderlandsche Club maupun gerakan nasionalis Indonesia, ia ingin membuktikan bahwa klaim penjajahan selama 350 tahun adalah mitos belaka. Menurutnya, pada dekade pertama abad ke-20 di kepulauan Indonesia masih tersebar daerah-daerah swapraja dan kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka. Ia menunjuk Regeeringreglement (peraturan pemerintah) 1854, yang menyatakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda memiliki wewenang untuk mengumumkan perang dan mengadakan perdamaian, serta membuat perjanjian raja-raja di seluruh Nusantara. Sampai abad ke-19 bahkan ada kerajaan-kerajaan yang cukup kuat dan “berada dalam hubungan setara” dengan penguasa kolonial, seperti Ternate dan Tidore. Hubungan antara pemerintah kolonial dan kerajaan-kerajaan yang merdeka diatur dalam kontrak atau perjanjian. Artinya ada kerjasama antara penguasa kolonial dan kerajaan-kerajaan tersebut untuk mengelola sumber daya ekonomi sambil mempertahankan kedaulatan masingmasing. Tidak ada serangan bersenjata, pengiriman pasukan atau penaklukan seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Di Surakarta dan Yogyakarta yang masih merupakan daerah swapraja misalnya sewa tanah berjalan tanpa hambatan dan tidak ada keributan seperti halnya di tempat-tempat lain. Para penguasa kraton dan Gubernur Jenderal berhubungan baik. Melihat semua ini Resink kemudian menganggap kerajaan-kerajaan yang merdeka ini mirip dengan protekorat atau daerah di bawah perlindungan negara Hindia Belanda. Dalam esei “Dari Debu Sebuah Taufan Penghancuran Patung-Patung” yang terbit 1956, Resink membandingkan kekuasaan Majapahit, VOC dan Hindia Belanda. Seperti C.C. Berg seorang sarjana kolonial terkemuka, ia mengatakan kekuasaan Majapahit harus dilihat dari segi lalu lintas perdagangan rempah-rempah yang tidak hanya menghubungkan pulau-pulau di Nusantara, tapi juga mengaitkannya dengan pelabuhan India serta daerah pantai di Laut Tengah. Kekuasaan Hindia Belanda tidak pernah sampai sejauh itu. Artinya klaim bahwa Belanda menguasai Nusantara seperti halnya Majapahit menguasai wilayah itu pun gugur. Apalagi jika dibandingkan VOC (cikal-bakal negara Hindia Belanda) yang hanya berkuasa di sebagian kecil wilayah dan sangat terbatas pula. Klaim penjajahan selama 350 tahun pun semakin terlihat rapuh ketika dihadapkan pada fakta-fakta dasar seperti ini. Ia mengakui bahwa orang Belanda memang tinggal dan bekerjasama dengan orang bumiputra selama ratusan tahun, mungkin juga melakukan kejahatan di sana-sini, tapi jelas tidak menguasai keseluruhan wilayahnya. Perhatian lainnya adalah daerah-daerah di luar Jawa yang sangat sedikit disinggung dalam penulisan sejarah nasional. Kaum nasionalis biasanya menggunakan contoh perkebunan di Sumatera dan Jawa untuk menunjukkan penindasan yang hebat. Tidak ada yang bisa menyangkal itu, tapi Resink ingin membuktikan bahwa di samping itu masih ada wilayahwilayah yang berdiri sendiri dan merdeka. Ia menggunakan nota H. Colijn yang menguraikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di daerah-daerah luar Jawa. Dari nota ini ia mendapat gambaran tentang situasi politik di berbagai daerah menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hasil pengamatannya kemudian disusun menjadi esei “Negara-Negara Pribumi di Nusantara Timur”, untuk menunjukkan bahwa sampai kurun itu sebenarnya ada negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya. Ia melihat bahwa di mata pemerintah kolonial sendiri, semua wilayah itu dianggap otonom dan sejajar. Perlakuan itu bukan hanya bagi negeri-negeri yang memang masih merdeka seperti Kalimantan Selatan dan Lombok, tapi juga bagi wilayah yang mengadakan perjanjian dengan Belanda dan mengakuinya sebagai kekuasaan tertinggi, seperti Aceh, daerah bawah di Jambi dan Riau. Dalam karangan terakhir di kumpulan itu, Resink menegaskan kembali masalah kedaulatan ini. Sekalipun raja-raja bumiputra mengakui penguasa kolonial sebagai kekuasaan tertinggi dan menyapa gubernur jenderal dengan sebutan “yang dipertuan besar” dalam perjanjianperjanjiannya, status mereka sesungguhnya setara. Negeri seperti Aceh dan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan sekalipun berhubungan dengan Belanda, harus diperlakukan seperti Montenegro atau Monaco dalam hukum internasional. Resink adalah pendukung kemerdekaan Indonesia. Ia sama sekali tidak menyangkal hak rakyat untuk merdeka, dan sangat kritis terhadap kekuasaan kolonial. Namun simpati atau keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan menurutnya tidak bisa tenggelam dalam kesalahan melihat fakta-fakta, apalagi mengembangkan mitos-mitos yang tidak berdasar. Karena itulah ia bersikeras membuktikan bahwa penjajahan selama 350 tahun adalah mitos belaka. Memang dari sudut hukum, bukti-bukti yang diajukannya mendukung argumentasi itu. Tapi persoalannya kemudian bagaimana cara kita memahami bukti-bukti yang ada. Cukup jelas bahwa Resink berpegangan pada paham legalistik, yang berkutat pada rumusan hukum dan segala konsekuensi logisnya. Akibatnya ia seringkali tidak melihat struktur yang melandasi produk hukum itu. Singkatnya, memisahkan antara eksploitasi kolonial dengan produk hukum yang dibuatnya. Hukum baginya adalah sesuatu yang netral dan harus dibaca “seperti adanya”. Karena itulah kerajaan-kerajan merdeka dianggapnya berada dalam hubungan setara dengan pemerintah kolonial. Mereka membentuk partnership dan bukan hubungan penguasa dan yang dikuasai. Pemerintah kolonial, seperti dijabarkan dalam perjanjian-perjanjiannya, bertindak sebagai pelindung kerajaan sambil tetap menghargai kedaulatan masing-masing. Tapi sebaliknya Resink tidak melihat hubungan sesungguhnya antara wilayah tersebut dengan penguasa kolonial, di luar jalur hukum. Eksploitasi ekonomi, ekspansi kekuasaan kolonial terus berlangsung, terlepas ada tidaknya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian dengan Sultan Siak pada 1889 yang menjadi syarat bagi penguasa kolonial untuk menguasai tambang timah. Begitu pula perjanjian dengan Sumatera Timur pada 1909 yang mengakui kebesaran raja setempat tapi di sisi lain mengubah daerah kekuasaannya menjadi sebuah cultuurgebied (daerah perkebunan) yang menghasilkan jutaan gulden setiap tahunnya untuk para pemilik perkebunan. Dalam perjanjian itu disebutkan adanya platselijke raad atau semacam dewan pemerintahan, tapi kekuasaannya hanya sebatas “kedaulatan politik”, sementara urusan ekonomi dan eksploitasi, termasuk pengerahan tenaga kerja yang terkenal kejam, diserahkan sepenuhnya kepada pemilik perkebunan. Begitu pula dengan Nota Colijn yang menjadi rujukannya untuk memahami “kedaulatan” wilayah-wilayah merdeka di bagian timur Nusantara. Dalam nota itu berulangkali ditekankan bahwa negeri-negeri yang “merdeka” berada di bawah kekuasaan kolonial. Persoalan lain, Resink juga nampaknya mengabaikan gerakan protes dan perlawanan rakyat yang me luas sejak abad ke-19, sementara para penguasa feodal di masing-masing wilayah menikmati “kesetaraan” dengan penguasa kolonial. Justru penaklukan kalangan elit dan perlawanan rakyat adalah ciri tanah jajahan di mana pun. Artinya, kemerdekaan tidak dapat diukur hanya dari sisi hukum, tapi harus melihat keseluruhan cara hidup masyarakat yang bersangkutan. Studi Resink dan cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh keinginan “meluruskan sejarah” dari salah paham, baik di kalangan sarjana kolonial konservatif maupun gerakan nasionalis. Ia masuk dalam sebuah perdebatan panjang yang menariknya sampai pada kesimpulan sama dengan kepentingan yang bertolak belakang. Sementara kaum konservatif mengklaim penjajahan selama 350 tahun sebagai pembenaran untuk melanjutkan kolonialisme, gerakan nasionalis mengklaim kurun yang sama sebagai dasar untuk membebaskan diri. Di tahun 1950-an, saat Resink menulis esei-eseinya yang mahsyur itu, gerakan nasionalis sedang naik pasang. Komentarnya memang menimbulkan perdebatan kembali di kalangan nasionalis dan intelektual sezaman. Komentar dan kritiknya yang tajam terhadap salah paham kaum nasionalis atas sejarahnya sendiri menjadi catatan penting bahwa propaganda tidak bisa bertahan atas dasar-dasar yang rentan dan salah. Sebaliknya perlu kita ingat bahwa Resink juga mengabaikan berbagai hal, termasuk hal-hal terpenting mengenai hubungan eksploitatif antara penguasa kolonial dan rakyat tanah jajahan. Kesepakatan dan perjanjian dalam bahasa yang santun tidak dengan sendirinya mencerminkan “kesetaraan”. Sumatera Timur mungkin menjadi contoh yang menonjol, sementara berdaulat di bidang politik, eksploitasi menyebabkan ratusan ribu orang menderita sebagai kuli kontrak yang nyaris seperti budak. Bagaimanapun, karya Resink memberi sumbangan berharga untuk menyadari bahwa kemerdekaan secara legal-formal dan kedaulatan hukum, tidak dengan sendirinya berarti pembebasan menyeluruh dari hubungan-hubungan yang menindas. Razif, pekerja pada Jaringan Kerja Budaya
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Segelas Kopi Darpan Ariawinangun Ketika masih mendiami rumahnya yang dulu, berdua dengan Bi Simah, sehari-harinya dia menjadi upas desa. Namanya pun dirangkai dengan jabatannya: Upas Karma. Seperti umumnya upas, pekerjaannya tak lebih dari mengantar surat, menjaga kantor desa, menata aula sebelum rapat, atau— jika tak ada lagi pekerjaan kantor yang harus diselesaikan—membersihkan rerumputan yang tumbuh liar di pekarangan balai desa. Pagi-pagi benar dia sudah berangkat dari rumahnya, mendahului para staf desa. Membuka pintu dan jendela, membersihkan meja, menyapu dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya. Pulangnya paling belakang, setelah tak ada lagi staf desa yang tinggal di kantor, setelah menutup jendela dan pintu, setelah membereskan kembali meja dan kursi, dan setelah tak ada lagi yang harus dikerjakan. Begitu dan begitu seterusnya. Kadang-kadang, jika ada rapat di balai desa sampai malam, subuh hari dia baru pulang, menginap di balai desa. Belakangan, ketika hari pemilihan kembali kepala desa semakin dekat, saat semua staf desa kesibukannya meningkat, Upas Karma hanyut pula dalam kesibukan itu. Selain melakukan pekerjaan rutinnya, ia harus pula mengerjakan tugas-tugas ekstra: ke sana ke mari membuntuti jurutulis menyensus calon pemilih. Ia ikut membantu mendaftar. Ikut juga mengurusi administrasi panitia pilkades walaupun hanya jadi pengantar surat. Bahkan, ia diminta pula untuk menyebarkan pengaruh, bersama dengan staf lainnya. Ia diminta mendukung lurah hormat yang sekarang mencalonkan diri lagi. Sejatinya ia melakukan itu karena terpaksa, karena seluruh staf desa di situ sebenarnya anak buah lurah hormat. Walaupun sekarang ini pemerintahan desa sudah dipegang oleh pejabat sementara, namun pada dasarnya tidak ada perubahan. Soalnya, yang menjadi PJS-nya pun adiknya Lurah Nawi, lurah hormat itu. Wajar jika semua staf desa mendukung Lurah Nawi. Bagaimana tidak. Dan dia, bagaimana bisa berbeda dari staf lain? Dari hari ke hari, Upas Karma semakin sibuk. Mungkin karena terlalu sibuk, suatu hari Upas Karma cuma bisa meringkuk di kamarnya. Badannya demam. Makanan yang disodorkan oleh Bi Simah ditolaknya. Pahit katanya, dan kepala seperti mau pecah. “Kenapa Mang Karma, Bi?” kata Jurutulis kepada Bi Simah di luar rumah. “Tahu tuh, Ulis? Meringkuk saja kerjanya dari pagi.” “Kalau sudah baikan, suruh cepat kembali ke desa. Bilang sedang banyak kerjaan,” kata Jurutulis sambil pergi, tanpa mau menunggu jawaban dari Bi Simah. Melayat kek, gerutu Bi Simah dalah hatinya. Malamnya Upas Karma malah semakin merintih-rintih, membuat khawatir Bi Simah. Bi Simah lalu menyuruh Icih—anak tetangganya—membeli air soda dan aspirin. Setelah minum air soda dengan aspirin, demamnya mulai mereda. Dari seluruh tubuhnya keluar keringat. Namun Bi Simah tetap menyelimutinya dengan kain berlapis-lapis. Biar seluruh keringat keluar, katanya. “Mencari apa atuh, Abah?” gumam Bi Simah sambil memperbaiki letak selimut di tubuh Upas Karma. “Kerja dari pagi buta sampai sore. Badan sendiri tak terurus. Mending kalau gajinya besar. Apa untungnya jadi upas. Apa bedanya dengan kuli menyabit.” Mang Karma tidak menjawab. Cuma pikirannya yang terus nyerocos. Kuli menyabit? Palingpaling disebut kuli dekil. Begitu pikirannya. Walaupun dari segi penghasilan bisa melibihi gaji upas, tetap saja disebut kuli. Sementara jadi upas, setidaknya ia dikenal sebagai pegawai desa. Ada punya wibawa. Beda dengan kuli. Kalau memberi atau menyampaikan perintah kepada orang lain, menyampaikan perintah rapat kepada masyarakat misalnya, selalu dituruti. Kalau kuli dekil? Kuli? Paling-paling cuma bisa diperintah dan disuruh-suruh orang, harus taat perintah pegawai. Soalnya dia sendiri pernah mengalami, ketika masih menjadi buruh tani. Waktu itu musim Pemilu. Oleh Karyu—adik tirinya yang tinggal di kota— ia disuruh berbeda dari orang kebanyakan, memilih gambar yang tidak umum buat orang kampung. Setelah Pemilu jadi gunjingan. Orang-orang menyebarkan isu, bahwa ada orang di desa itu yang berkhianat. Mang Karma dipanggil ke balai desa. Esok harinya ia disuruh gorol sendirian, membersihkan rerumputan di pinggir-pinggir jalan sepanjang totoang. Seminggu ia habiskan waktunya di situ. Ternyata itu pun tak cukup. Setiap harinya ia harus juga menerima gunjingan-gunjingan staf desa yang membuat telinganya panas. Semisal gunjingan, “Siapa yang mau jadi orang kota? Pantasnya kalau orang kampung ya jadi kuli. Jangan jadi jagoan.” “Negara demokrasi, Kang. Kita bebas memilih!” kata Karyu waktu itu. Tapi buktinya, ia harus menampung semua omongan busuk orang kampung. Mana yang benar? Begitu Mang Karma selalu bertanya. Setelah dipikirkannya matang-matang, dan setelah anak-anaknya juga menyalahkan dia, Mang Karma baru sadar kalau dia sedang melawan arus. Akhirnya, segala perintah selalu ia turuti walaupun seringkali ia menerimanya dengan rasa tidak senang. Oleh karena itu, begitu pikirnya, kalau ia hanya jadi kuli tentu akan selalu dipermainkan orang lain. Mendingan jadi pegawai desa seperti sekarang ini. Walau hidup melarat, tapi masih ada yang mau menghargai, masih ada yang mau minta pertolongannya. Lagian, kalau dia punya keperluan-keperluan kecil, tidak susah untuk bicara sama jurutulis atau lurah. Tinggal ngomong. Dan jika nasib lagi baik, tidak sulit bagi dia untuk memperoleh sekadar seribu atau dua ribu dari hasil dia membantu orang yang butuh tenaganya. Kalau kuli dekil? Kuli? Ia memang tidak bermimpi jadi lurah, atau jadi sekdes, atau kepala urusan. Tidak. Lagian untuk jadi lurah tidak cukup uang satu atau dua juta, tapi harus puluhan juta. Memang, semua itu tidak sia-sia, karena ketika sudah jadi lurah pemasukan akan datang dari mana-mana. Bagi Mang Karma, menjadi upas saja sudah jadi keberuntungannya. Ternyata orang-orang desa masih mau mengakui keberadaan dia. Walaupun hanya jadi upas, ia tetap dianggap sebagai staf di desa. Masih punya kesempatan menyuruh atau memerintah orang lain. Untungnya, Upas Karma sakitnya tidak lama. Tiga hari kemudian, dia sudah ikut sibuk kembali karena pelaksanaan pilkades tinggal beberapa minggu lagi. Tenaganya betul-betul diabdikan buat kepentingan desa. “Mang Karma, besok pindah rumah saja. Tempati tuh ruangan belakang balai desa,” kata Lurah Nawi, lurah hormat yang kemudian mencalonkan diri lagi. “Lurah dan Sekdes sudah saya beritahu,” katanya lagi. Upas Karma untuk sesaat seperti orang bingung. Tidak terpikir dia harus ngomong apa. Karena yang pertama-tama melintas dalam pikirannya: dari rumah bilik dia harus menempati ruangan belakang balai desa yang sudah berlantai tegel, bertembok, berlangit-langit, dan berjendela kaca. Sementara rumahnya yang selama ini ditempati jangankan berlangit-langit, gentingnya saja sudah banyak yang bolong. Lantainya tanah, dindingnya bilik bambu, dan jendelanya hanya anyaman bambu pula yang dikaitkan dengan seutas kawat. Esok harinya, Upas Karma resmi menempati ruangan belakang balai desa. Bi Simah yang biasanya menghadapi tungku tanah, kini bisa menyalakan kompor hadiah dari Lurah Nawi. Selain itu Mang Karma bisa tiduran santai di kursi busa yang sudah tak terpakai lagi di desa. Walaupun kursi bekas, tapi masih lebih baik daripada kursi kayu reyot yang ada di rumahnya sendiri. Suatu sore, ketika Upas Karma sedang menikmati segelas kopi sambil duduk-duduk di kursi busa, datanglah Lurah Nawi. Menengok, katanya. Mang Karma sekarang tak lagi kikuk kedatangan tamu hanya karena tamu harus diterima di saung butut. Ketika harus mempersilahkan tamu masuk atau duduk, ia tak harus malu: ada kursi busa sekarang. “Tentu Mang Karma kerasan di sini,” kata Lurah Nawi ramah sambil duduk di kursi busa. Upas Karma hanya bisa menjawab dengan tertawa. “Bagaimana Bi Simah, apa sudah bisa menyalakan kompor?” Upas Karma lagi-lagi menjawabnya dengan tertawa. Sementara Bi Simah yang menguping obrolan itu dari belakang agak tersinggung. Memang aku orang utan yang tak tahu kompor, gerutunya dalam hati. Obrolan mereka, sambil menikmati kopi, sudah ngalor-ngidul. Sampai suatu ketika, Lurah Nawi berpamitan pulang. Si tuan rumah kemudian mengantarkannya ke halaman. Sebelum pergi, Lurah Nawi menegaskan sebuah pesan, “Jangan lupa, Mang. Minggu depan Si Nurja dan Si Nana harus sudah pasti sikapnya. Kalau tetap mau membelot... ah, pikirkan saja oleh Mang Karma. Masak...!” Upas Karma mengangguk pelan. Setelah tamu pergi, Bi Simah mendekatinya. “Nah, mau bagaimana kalau sudah begini?” “Tahulah...,” jawab Upas Karma sambil tetap terpaku di halaman. “Eh, ya harus dipikir atuh, Abah!” Upas Karma tak menjawab lagi. Ia kembali ke dalam, diikuti Bi Simah yang terus mengganggu dengan omongan. “Abah yang begitu mah, kenapa mau saja jadi pegawai desa. Apa untungnya jadi upas. Kalo jadi jurutulis sih masih mending, ada penghasilannya. Kalau sudah begini, kita harus bagaimana? Abah kan tahu kalau Si Nurja dan Si Nana itu kepala batu.” “Sudah! Aku yang akan ngomong sama mereka. Bukan kamu!” Upas Karma membentak, agar istrinya diam. Bi Simah cemberut, lalu pergi ke belakang. Tinggal Upas Karma sekarang yang tampak bingung. Lurah Nawi, adalah atasannya. Sementara pada Nurja dan Nana—anakanaknya—dia tahu betul tabiatnya. Terdorong keinginannya untuk segera mendapat keputusan, malam itu juga dia mendatangi rumah Nurja. Dia ceritakan keinginannya. Hanya saja dia tak berani berterus terang kalau dia sebenarnya didesak oleh Lurah Nawi. “Eh, Abah, seperti tidak tahu saja. Apa jadinya desa kita kalau Lurah Nawi terpilih lagi? Lihat yang sudah-sudah, rakyat kecil juga yang sengsara. Pungutan sumbangan dibesar-besarkan, hasilnya tidak ada,” kata Nurja, menjawab desakan bapaknya. “Habis aku harus bagaimana, Nur?” Upas Karma bingung sendiri. “Ya begitulah, Bah. Silahkan kalau Abah mau milih lagi Lurah Nawi mah, tapi saya tidak akan. Kapok!” jawab Nurja lagi. Lalu dia mendekati bapaknya, lalu berbisik, “Abah tidak tahu ya. Kata PPL, Lurah Nawi itu suka makan uang subsidi. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan, membangun mesjid, membuat jalan, habis dia makan sendiri....” “Tahu apa kamu, Nurja!” Upas Karma cepat memotong. “Lha, Abah selama ini tahu apa?” Nurja malah balik bertanya. Upas Karma hanya bisa melotot. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Malam sudah larut ketika Upas Karma pamit pulang. Sebelum pergi ia menyempatkan bicara lagi sama Nurja, “Dari semula aku tidak mau memaksa kamu. Biar kalian berpikir sendiri. Mau mendukung Lurah Nawi ke, atau Haji Sukur kek, terserah kamu.” “Saya juga begitu, Bah,” jawab Nurja. Malam berikutnya, Upas Karma berkunjung ke rumah Nana, anaknya yang kedua. Tapi jawaban Nana tidak jauh berbeda dengan kakaknya. “Orang sekampung sudah tahu, Bah, kalau Lurah Nawi itu tukang korupsi. Tapi kalau Abah takut kehilangan pekerjaan mah, ya terserah, saya tak bisa melarang Abah mendukung Lurah Nawi.” Upas Karma menenggak gelas kopi yang disodorkan istri Nana. Seminggu sebelum pilkades, Upas Karma sudah kembali menempati rumahnya yang dulu. Kalau dihitung, tak sampai sebulan dia menempati ruangan belakang balai desa, karena keburu disuruh pergi oleh Hansip Kurdi. Katanya ruangan belakang itu akan dibersihkan dulu, sesuai perintah Lurah Nawi. “Masa iya cuma mau dibersihkan?” gerutu Bi Simah. Sementara Upas Karma tak bisa berkatakata lagi. Hanya saja, dia merasa tersinggung dengan kata-kata Hansip Kurdi, “Oh ya, kunci desa mau saya ambil, Mang.” Upas Karma lalu menyerahkan kunci itu. Ternyata tak cukup sampai di situ, karena Hansip Kurdi bicara lagi, “Kata Lurah Nawi, besok Mang Karma di rumah saja. Di desa sekarang sudah ada Mang Sukri, Upas baru.” *** Mang Karma, bekas upas desa, terbangun dari dipan tempat tidurnya, setelah dikagetkan oleh kokok ayam jago dari belakang rumah, tepat di samping telinganya. Ia sempoyongan berjalan ke ruangan tengah, lalu duduk di bangku kayu reyot miliknya. Ia tersenyum seperti teringat sesuatu yang lucu. Di meja sudah terhidang segelas kopi dan sepiring singkong rebus. Saat menyodorkan tangannya hendak meraih gelas kopi, pandangannya tertumbuk ke sudut kamar tidur. Tepat di situ, bilik bambunya menganga, seperti biasa digunakan kucing berlalu lalang. Ia seperti baru sadar, kalau selama ini telah menelantarkan rumahnya sendiri. Pandangannya lalu diarahkan ke atas. Sarang laba-laba berajutan di palang-palang genting. Lalu ia mengamati gentingnya. Tak terbayangkan, jika hari itu hujan tiba-tiba turun dengan angin yang kencang. Ia lalu meraih gelas kopi. Pelan-pelan diminumnya, sambil dirasakan alirannya di tenggorokan. Setelah beberapa tegukan, Mang Karma kembali terdiam. Dalam hatinya saja dia bicara, “Inilah duniaku. Dunia segelas kopi di pagi hari, dengan pikiran bebas mau apa aku hari ini. Tidak dipaksa orang, atau takut. Ah, kenapa aku selama ini diperdaya oleh sesuatu yang tidak jelas. Meninggalkan duniaku sendiri yang bebas-merdeka seperti ini. Tapi baiklah, karena itu semua ada hikmahnya juga. Aku jadi tahu tabiat dari orang-orang itu. Masa bodoh, siapa yang minggu depan akan terpilih jadi lurah.” Ia kembali meneguk kopi. Tiba-tiba terdengar teriakan istrinya dari belakang, “Abah, bukannya mau memperbaiki tungku!” pilkades: Pemilihan Kepala Desa lurah hormat: Lurah yang sudah habis masa jabatannya. gorol: Kerja bakti. totoang: Jalan yang memanjang antara satu kampung dengan kampung lainnya. sekdes: Sekretaris Desa. PPL: Petugas Penyuluh Lapangan. Darpan Ariawinangun, cerpenis Sunda yang biasa bolak-balik Jakarta—Bandung—Garut. Cerpen ini diterjemahkan sendiri oleh penulisnya dari cerita pendek berbahasa Sunda Cikopi Sagelas yang termuat dalam buku antologi cerita pendek Nu Harayang Dihargaan, Bandung: Rahmat Cijulang, 1998, hlm. 81—90. Cerita pendek ini pertama kali dipublikasikan pada 1993 di Koran Sunda Galura Bandung.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Kesembuhan Semu Kapitalisme Thailand Arif Rusli Ibarat pengidap virus HIV yang berusaha menyembunyikan hasil diagnosa lanjutan, pemerintah Thailand cenderung terlalu hati-hati untuk bicara soal kapan dan sejauh mana taraf kesembuhan ekonomi negerinya. Pekan silam, Perdana Menteri Thaksin dengan ketus mempertanyakan kapabilitas ketua Asosiasi Bankir Thailand, Chulakorn, yang memprediksikan bahwa Thailand paling kurang butuh waktu 8 tahun untuk benar-benar keluar dari krisis ekonomi. Bagi Thaksin, komentar pesimis semacam ini dianggapnya sebagai tudingan terhadap ketidakmampuannya membereskan krisis ekonomi Thailand sekaligus menihilkan ikrarnya dalam kampanye pemilu empat bulan silam. Waktu itu, dia menjanjikan akan membereskan ekonomi Thailand dalam waktu kurang dari empat tahun. Nyatanya data-data kredit macet dan rendahnya arus modal yang beredar, memaksa para bankir IMF, bankir dan ekonom Thai untuk memilih sikap pesimis soal kesembuhan ekonomi negeri ini. Thailand sebelum krisis mempunyai investasi asing sekitar 41,1% terbesar setelah Korea Selatan yang mencapai 52,5 %. Dan ketika Thailand dihantam krisis yang paling utama mengalami kerusakan adalah angkat kakinya para investor asing, hampir 78 % aliran modal keluar (capital flight) Thailand, ini mempunyai akibat dengan meningkatnya deretan orang miskin, sekitar 10 juta orang tidak mempunyai pekerjaan dan harus hidup dengan 100 bath (Rp. 4000,-) per-hari. Ciri umum dari krisis ekonomi di Asia dan juga terjadi di Thailand di 1997 adalah mencari kesalahan pada prilaku, etika dan akhlak pemilik modal dan birokrasi. Cara pandang ini adalah dasar pijakan dari berbagai ekonom Thai. Sementara IMF dan Bank Dunia dalam melakukan penilaian terhadap kinerja ekonomi selama krisis berlangsung menegaskan “selama 10 tahun terakhir perekonomian Thailand membawa pengaruh pada kemakmuran mayoritas rakyat banyak, tetapi setelah mengalami krisis Thailand harus menghidupi perekonomiannya dari kucuran dana publik.” Penilaian para para pejabat Bank Dunia dan IMF untuk perwakilan Thailand itu berarti masyarakat Thai dibebani oleh berbagai macam jenis pajak dan penjualan sumber daya mineral dan keuangan atau yang dikenal melalui proses akumulasi primitif. Thailand boleh dikatakan negeri yang tidak pernah dijajah, tetapi tidak pernah lepas dari hubungannya dengan imperialisme. Dari paket Miyazawa Plan yang berjumlah US$ 6 miliar untuk negeri Asia yang terjangkit krisis ekonomi, Thailand mendapatkan US$ 2 milyar yang dipergunakan untuk restrukturisasi perbankan dan mendongkrak mata uang Bath. Sebagai imbalannya lembaga-lembaga Bretton Wood, ini menginginkan perusahaan dan perbankan Thailand dikelola oleh swasta. Ini menandakan pemaksaan liberalisasi oleh negeri-negeri imperialis, terutama Amerika-Serikat, yang mempunyai mata uang dolar yang begitu kuat sebagai prasyarat untuk memimpin liberalisasi. Tolok ukur kesembuhan perekonomian Thailand ditaksir dengan berkurangnya hambatanhambatan dalam privatisasi, liberalisasi pasar, khususnya korupsi dan penyelewengan dana untuk kebutuhan lain.Tak heran, rekomendasi utama dari Bank Dunia dan IMF adalah melakukan reformasi hukum perbankan untuk mempermudah pembayaran utang dan penyelesaian kredit macet. Lalu yang terpenting jangan keluar dari sistem ekonomi pasar atau menghambat arus keluar masuknya modal. Pemerintahan Thaksin juga menambah ekspor tenaga kerja atau buruh migran sebagai pemasukan anggaran negara. Dari ekspor tenaga kerja ini administrasi Thaksin dapat memperoleh US$ 4 juta pada 1999. Di sisi lain, IMF hanya merekomendasikan agar pemerintah memajukan sektor pendidikan, membangun keahlian dan jaring pengaman sosial. Pada masa puncak krisis, Bank Dunia hanya mengalokasikan US$ 43 juta ke program sosial, bandingkan dengan US$ 2 milliar ke program liberalisasi pasar dan reformasi hukum dan regulasi. Tidak mengherankan kalau dana pinjaman ini lebih banyak menguap dalam birokrasi, terutama dalam rangka melaksanakan sistem elektoral. Padahal, data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa upah di wilayah nonindustri, seperti wilayah tenggara dan tengah Thailand anjlok sangat tajam semasa krisis berlangsung. Mereka yang paling parah kondisinya adalah buruh lulusan sekolah dasar atau yang berpendidikan lebih rendah. Jumlah tenaga kerja setingkat ini bertambah dengan mudiknya para pekerja konstruksi dan real estate dari Bangkok. Sementara itu, orang-orang terkaya yang tercakup dalam 20% dari populasi tetap saja menikmati keuntungan dari krisis ekonomi antara 1996-1998. Mereka ini sebelum krisis menjabat sebagai manajer bank. Thaksin Shinawarta, bilioner yang sekarang menjadi Perdana Menteri Thailand, mengeruk 100% keuntungan dari spekulasi di pasar uang. Konon, uang hasil spekulasi itu dipakai untuk membiayai kampanye politiknya. Spekulasi atau korupsi adalah cara yang diizinkan oleh IMF dan Bank Dunia untuk para elit politik mencapai tampuk kekuasaan, karena dengan cara seperti ini para elit politik tidak lagi mengontrol kelua -masuknya aliran modal. Boleh dikatakan borjuasi Thailand disingkirkan untuk turut berperan dalam mengontrol perusahaan-perusahaan multi-nasional (MNC), bahkan perusahaan-perusahaan nasional. Perusahaan-perusahaan nasional Thailand setelah diterpa krisis belum dapat bangkit kembali. Sedangkan MNC terus menerus memasok barang-barangnya ke negeri gajah putih ini dan mereka saling berkompetisi, tetapi tidak mematikan malah sebaliknya saling melengkapi. Sebagai contoh perusahaan mobil Ford dari Amerika Serikat masuk ke Thailand dan bekerjasama dengan perusahaan mobil Honda dari Jepang. Mereka sama-sama menguasai pasar otomotif di Thailand. Sedangkan sektor industri real state dan petrokimia yang menjadi sarang spekulasi dan korupsi di Thailand diambil alih oleh Bank Sumitomo, Jepang. Pengambil alihan perusahaan-perusahaan nasional Thailand oleh perusahaan asing tidak berati praktek spekulasi dan korupsi diberantas, ini tetap dipelihara, dengan cara seperti ini akumulasi modal akan terus mengalir ke metropolis. Prabat Patnaik dengan cekatan merumuskan krisis di Asia Tenggara dan Timur dipicu dengan mempertahankan praktek penyelenggaraan pemerintahan lama, seperti spekulasi dan korupsi. Dari sini negeri Thailand akan terus memohon pemberian utang baru dan pembayarannya melalui penjualan sumber alam dan perusahaan-perusahaan nasional. Pengalihan saham itu juga diikuti dengan penciutan cabang usaha atau masuk kategori bangkrut. Akibatnya ratusan ribu tenaga kerja di sektor-sektor tersebut menganggur. Hampir setengah juta orang tenaga kerja dari Myanmar diburu dan dipaksa pulang ke negerinya pada pertengahan 1998. Dengan alasan penertiban tenaga kerja asing, pemerintah Thai mendorong supaya lapangan kerja yang ditinggalkan itu bisa diisi oleh warga negara Thai. Di 1997, menurut departemen tenaga kerja Thailand, lebih dari 2 juta warga negara Thailand menganggur dan mengalami peningkatan empat kali lipat pada 1999, yakni 10 juta orang. Tingkat pengangguran yang tinggi membuat lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, situasi yang membuat geram lembaga keuangan internasional. Mereka menginginkan agar warga Thai bekerja sebagai apa saja, asalkan menghasilkan devisa untuk membayar utang. Lebih parah lagi, ratusan usaha kecil dan menengah harus gulung tikar setelah krisis ekonomi. Usaha-usaha bertujuan substitusi impor ini tidak mampu melunasi utang yang dipinjam dari bank-bank domestik. Hal ini ikut menyumbang pertambahan jumlah tenaga kerja yang mengandalkan kesempatan kerja di industri besar. Sampai saat ini sektor-sektor usaha seperti garment, sepatu dan elektronika tetap belum pulih. Malah di sektor industri manufaktur elektronik, pemecatan terus berlangsung, akibat rendahnya permintaan pasar ekspor barang di elektronik di Jepang dan Amerika, dua negara yang menjadi tujuan ekspor utama komoditi elektronik Thailand. Setelah krisis menimpa Thailand, kalangan kelas menengah kehilangan kepercayaan terhadap propaganda strategi ekonomi berorientasi ekspor. Rata-rata perusahaan domestik yang berorientasi ekspor harus tutup. Banyak pengusaha atau mantan direktur perusahaan berorientasi ekspor yang terjun ke sektor usaha menengah yang sudah mapan, seperti kerajinan emas, berlian, pengemasan produk makanan kaleng, mainan anak-anak atau sektor makanan. Pasca krisis banyak restoran kecil bermunculan. Umumnya usaha semacam ini mengincar pasar dalam negeri. Sampai sejauh ini belum tampak apa sumbangan sektor ini terhadap pemulihan ekonomi, karena sebagian besar usaha hanya bisa memperoleh kredit kecil dan menggunakan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Kecenderungan ini muncul sejak tiga tahun silam, setelah para ekonom ramai-ramai melarikan diri dengan membahas konsep ekonomi swadaya yang diutarakan oleh Raja Bhumibol. Banyak pembenaran yang dipakai untuk menggalang ekonomi swadaya, salah satunya mencari pembenaran moral dari ajaran Budhisme soal keseimbangan materi dan rohani. Bersamaan dengan itu ekonom nasionalis menuding lembaga keuangan internasional yang mendorong persaingan bebas telah menjerumuskan bangsa Thai ke jurang kehancuran. Para ekonom nasionalis mengalami kegagalan, karena menganggap remeh fetishism sebagai suatu keniscayaan dalam hubungan sosial kapitalisme, dimana disiplin besi untuk menghasilkan produk diredam oleh kepuasan semu untuk memburu berbagai komoditas baru. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang menghubungkan krisis ekonomi di Thailand dengan kejenuhan pasar internasional atau domestik akibat membanjirnya produk serupa. Para politisi bicara soal swasembada sebagai lawan dari ekonomi berorientasi ekspor. Namun, belum ada arahan yang mempertimbangkan kemungkinan kejenuhan pasar, akibat berlombalombanya usaha kecil dan menengah memproduksi komoditas yang sama. Banyak pedagang dan penjaga toko, mengeluh bahwa para pengunjung hanya mengolok etalase untuk mengecek harga, tapi jarang yang membeli. Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa keadaan sekarang lebih buruk dari 1997. Birokrasi yang selama ini menjadi juru stempel dan kerap kurang kreatif, ikut latah mencari-cari bentuk ekonomi swasembada di tingkat pedesaan dan menyokong fasilitas kredit untuk usahausaha yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Padahal usaha-usaha swasembada yang sejati sama sekali tidak membutuhkan kredit tambahan dari pemerintah, karena umumnya mereka tidak terlampau mengandalkan pasar dalam arti suatu tempat komoditas dikumpulkan dan dijual sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Namun birokrasi sebagai tempat untuk melayani masuknya modal internasional, harus aktif memberikan kredit agar akumulasi modal bergerak kembali. Di tengah-tengah krisis yang tak kunjung sembuh, para bankir, ekonom dan pemerintah terbagi dalam dua kelompok. Yang satu berusaha mengambil jarak dari rekomendasi IMF dan berkampanye soal ekonomi swasembada yang mandiri dari campur tangan asing dan satu kelompok lain ikut mendorong penerapan reformasi ekonomi seluas-luasnya, artinya ikut liberalisasi pasar dan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomis tadi. Kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya, maka diktat rekomendasi dari lembaga keuangan menjadi pegangan dari pemerintah Thaksin. Pemerintah Thaksin mengambil inisiatif dengan memperkuat mekanisme hukum Thailand Asset Management Corporation untuk memberesi kredit macet di bank-bank negara, serta membentuk kerja sama investasi (matching fund) dengan Malaysia dan Brunei. Pemerintah Thailand mengambil bagian 25% dari pendanaan tersebut. Terdapat dua hal yang menggiatkan investor di Thailand. Pertama memperoleh pinjaman dari bank-bank luar negeri yang semuanya dapat mengalir secara aktif berkat dorongan IMF, tersedianya tingkat suku bunga yang bisa dicicil untuk pengembaliannya. Persoalan lain yang muncul, sistem lama yang masih tersisa—spekulan—sebagai kelas baru dan operator keuangan. Aktor ini yang menjadi penghubung utama dengan pasar modal di luar negeri dan menyusun aliran modal internasional. Orang-orang ini juga menjadi operator liberalisasi keuangan, menjalankan kepentingan-kepentingan lembaga donor dan memperkuat posisi lembaga keuangan internasional sebagai polisi pemburu bagi siapa saja yang tidak membayar utang. Acuan: Prabhat Patnaik. “Capitalism in Asia at the End of the Millenium.” Monthly Review. July-August. 1999 Thongchai Winichakul. “The Origins of Thailand Crisis.” Jurnal Contemporary Asia. AugustSeptember 2000. Arif Rusli, kontributor MKB yang bermukim di Bangkok, Thailand.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Pasar John Roosa Pasar sering dibayangkan sebagai wilayah yang merdeka. Di samping itu, dikenal pula istilah ‘pasar bebas’ untuk menjuluki pasar yang tidak dikendalikan negara. Pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat selalu mengunggulkan pasar bebas dalam retorika mereka. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, dua lembaga internasional yang paling berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia sekarang, boleh berbangga karena semua negeri yang mereka pinjami uang telah berhasil membebaskan pasar dari kendali negara. Istilah “pasar bebas” sungguh memikat kalangan bermodal dari segala penjuru dunia di abad baru ini. Jika gerakangerakan sosialis pada abad ke-19 dan ke-20 berjuang untuk ‘membebaskan kaum proletar’, gerakan hak-hak sipil berjuang untuk ‘membebaskan rakyat tertindas’ (seperti kaum kulit hitam di Amerika Serikat), dan gerakan-gerakan pembebasan nasional berjuang untuk ‘membebaskan bangsa-bangsa yang terjajah’, kaum kapitalis gencar mengumandangkan slogan ‘bebaskan pasar’. Sementara Amnesty Internasional membangun gerakan mendunia untuk pembebasan narapidana politik, IMF dan Bank Dunia menyebut dirinya sebagai gerakan mendunia untuk pembebasan pengusaha dari kontrol negara. Kaum kapitalis selalu berbicara dalam bahasa kebebasan, dan mereka percaya bahwa pasar merupakan anasir hakiki untuk pencapaian kebebasan manusia. Kita perlu berpikir kritis tentang konsep ini: apa artinya pasar bebas? Ketika pemerintah AS, IMF dan Bank Dunia menyatakan bahwa mereka membebaskan pasar, dan dengan demikian membebaskan rakyat pula dari kemiskinan, kita patut mempertentangkannya dengan cerita dari sisi seberang. Tak satu negara pun yang menjalankan kebijakan penyesuaian struktural (SAP) – kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia sekarang – di bawah tekanan IMF selama 30 tahun terakhir sanggup membangun perekonomian yang kuat, stabil dan maju. Lembagalembaga ‘globalisasi’ ini ternyata menghancurkan perekonomian nasional di Amerika Latin, Afrika dan Asia, meningkatkan kemiskinan, dan menegakkan kembali sistem kolonial di mana perusahaan-perusahaan multinasional dari AS, Eropa dan Jepang mendominasi kekayaan dan sumber alam dunia. Di Indonesia mereka memaksa pemerintahan ‘reformasi’ membayar setiap rupiah hutang pemerintahan Soeharto ke bank-bank asing, dan dengan begitu menyedot habis dana pemerintah yang diperlukan untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Melihat kenyataan serupa ini, kita bisa berasumsi bahwa ‘pasar bebas’ dalam wacana lembaga-lembaga ini merupakan istilah pengganti ‘kolonialisme’. Sebenarnya relatif mudah menunjukkan bukti kemunafikan di balik penggunaan istilah ‘pasar bebas’ oleh lembaga-lembaga globalisasi tersebut. Tetapi pengetahuan akan kemunafikan sang pembicara tidak selalu diikuti dengan pemahaman tentang konsep-konsep yang dibicarakan. Ilmu sosial membutuhkan lebih dari sekedar tuduhan sederhana atas kesenjangan antara kata dan perbuatan, yaitu penelitian tentang apa sesungguhnya yang dikerjakan, dan pengkajian secara seksama terhadap bagaimana kata merepresentasikan atau salah merepresentasikan realitas. Untuk memahami istilah ‘pasar bebas’, ada baiknya kita pelajari beberapa hal yang secara fundamental berkaitan dengannya. Kita semua punya pemahaman minimal tentang apa itu pasar. Dalam definisi yang paling sederhana misalnya, pasar adalah lokasi fisik di mana komoditi dipertukarkan. Seperti pasar di desa dan kota, tempat para pedagang berkumpul untuk menjual sayuran, daging dan ikan, buahbuahan, dan sebagainya, ada bermacam pedagang dan pembeli. Pedagang bisa menjualnya ke pembeli mana pun, begitu pula pembeli bisa membeli barang dari pedagang mana pun. Kadangkadang tawar-menawar soal harga bisa menjadi sangat tegang karena masing-masing pihak punya kepentingan berbeda: pembeli inginkan harga terendah, pedagang inginkan keuntungan tertinggi. Tetapi ada pemahaman tersembunyi di antara keduanya bahwa tidak ada unsur paksaan dalam proses transaksi tersebut. Maka, pasar tampil sebagai wilayah kontrak dengan konsensus lisan antara pembeli dan pedagang. Jika saya membeli pepaya seharga Rp 3.000, itu berarti ada kontrak walau tidak tertulis antara saya dan si pedagang. Kami bertemu sebagai pihak yang setara dan sepakat dengan kontrak ini. Saya tak todongkan pistol di kepalanya, begitu pula dia tak todongkan pistol di kepala saya. Kemudian, apa arti istilah ‘bebas’ sehubungan dengan pasar? Kalau kita lanjutkan contoh perdagangan di pasar di atas, orang akan berkata bahwa kebebasan tergantung pada apakah anda penjual atau pembeli. Bagi pedagang, kebebasan berarti menjual tanpa paksaan dari pihak lain: mereka tak dipaksa memberikan barang dagangan mereka tanpa dibayar ke polisi, tentara atau preman; mereka tak dipaksa oleh peraturan pemerintah untuk menjual barang dagangannya di bawah harga yang sudah mereka tentukan. Bagi pembeli, kebebasan berarti mampu membeli tanpa paksaan; tak satu pedagang pun memaksa mereka membeli hanya dari seorang pedagang saja, dan para pedagang juga tidak melakukan konspirasi bersama untuk menaikkan harga barang setinggi mungkin. Pembeli melihat kompetisi antar pedagang sebagai elemen kebebasan mereka; apabila mereka hanya berhadapan dengan satu pedagang atau kumpulan pedagang yang bersatu, mereka tak punya kekuatan tawar. Di banyak kota industri atau pertambangan yang terpencil, ada tradisi penyelenggaraan ‘toko perusahaan’ (company store). Perusahaan pengelola pabrik atau pertambangan memiliki semua toko yang ada di wilayah operasinya dan buruh perusahaan itu pun mau tidak mau harus berbelanja di toko-toko tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian mereka. Perusahaan bisa saja menaikkan semua harga barang secara sembarangan karena para buruh tak punya kendaraan dan waktu untuk berperjalanan ke kota atau pusat perbelanjaan lain di luar daerah bekerjanya. Tradisi ‘toko perusahaan’ semacam ini sudah membatasi kebebasan pembeli untuk memilih barang dan dari siapa mereka ingin membeli barang. Jadi kebebasan dalam pasar berarti bahwa baik pembeli maupun pedagang bisa menyepakati suatu kontrak secara bebas, tanpa salah satu pihak menggunakan paksaan. Dengan demikian pasar bebas adalah adanya kesempatan bagi semua untuk membeli dan menjual sesuka hatinya. Seperti yang dinyatakan Ellen Meiksins Wood, “hampir setiap definisi ‘pasar’ di kamus berkonotasi sebuah kesempatan.” (Wood 1994, p. 15) Semakin bebas suatu pasar, semakin banyak barang dan jasa tersedia, semakin banyak pilihan bagi pedagang pun pembeli. Kitab suci para kapitalis dewasa ini, yaitu buku Milton Friedman Free to Choose (1980), menampilkan pasar sebagai arena bertemunya berbagai orang dengan kekuasaan setara, masing-masing berjuang untuk memperoleh pilihan terbanyak dalam hal yang mereka beli dan jual. Yang mengacaukan pasar, menurut Friedman, adalah intervensi negara. Negara, dengan kekuatan pemaksanya, bisa membatasi rentang pilihan yang ada bagi pembeli dan penjual. Sejauh ini, kita baru mempertimbangkan tampak pasar di desa dan kota yang terlihat seharihari. Tapi mari kita tinggalkan kegaduhan pasar melewati ruas-ruas jalan raya menuju daerah pedesaan tempat sayur dan buah-buahan ditanam sebelum dijual ke pasar. Di sini pula kita temui perkebunan teh, tebu dan kelapa sawit yang hasilnya dijual ke seluruh dunia. Jika di pasarpasar tadi kita melihat tempat pertukaran komoditi, di ladang ini kita menjumpai tempat produksi komoditi. Ada jenis pasar yang berbeda di sini: pasar tenaga kerja. Buruh menjual tenaganya pada pemilik tanah dan perkebunan. Pasar jenis ini jelas berkaitan langsung dengan paksaan dan kekuasaan, dan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Taraf upah ditentukan oleh kekuatan buruh berhadapan dengan majikan. Dalam beberapa kasus, para buruh begitu tak berkuasa sehingga mereka bahkan tidak dibayar dan status mereka merosot tidak lebih dari budak. Tenaga kerja merupakan komoditi khusus. Dengan berperan sebagai pedagang yang menjual tenaga kerjanya, seorang buruh tidak hanya menyerahkan suatu obyek yang ada di luar dirinya, seperti pepaya. Ia mengasingkan sebagian dirinya, aktivitas otot, syaraf dan otaknya. Belum pernah tercatat dalam sejarah manusia ada pasar tenaga kerja yang merupakan pasar antar pihak yang setara. Buruh menjual dirinya karena mereka tak punya uang dan tenaga kerja mereka dibeli oleh mereka yang punya uang. Apabila buruh dalam posisi setara dengan pembeli tenaganya, mereka tak akan pernah menjual tenaganya. Dalam teori ekonomi standar (teori ekonomi yang diajarkan di universitas-universitas di Indonesia merupakan imitasi yang diajarkan di universitas-universitas di AS), pasar tenaga kerja ditampilkan seperti layaknya pasar lainnya, sebagai arena antar pihak yang setara bernegosiasi untuk mencapai konsensus dalam sebuah kontrak. Buruh digambarkan bisa begitu saja membeli tenaga kerja majikan seperti halnya majikan bisa membeli tenaga kerja sang buruh. Jika buruh rajin menabung upahnya (yang dianggap modalnya), suatu saat dia akan mampu menjadi kapitalis. Dalam teori ekonomi standar tak ada ide tentang kelas, kekuatan tak berimbang antar kelas. Jika kita melihat pasar hanya sebagai situs pihak-pihak yang setara, kita berarti mengabaikan ketidaksetaraan pemilikan properti dan kekuasaan di situs produksi. Sekarang, kalau saya pergi ke warung dan membeli teh, antara pemilik warung dan saya, tak ada perbedaan kekuasaan. Tetapi teh itu sendiri diproduksi di perkebunan oleh para buruh yang tertindas, yang setiap usahanya untuk mengorganisir diri pasti akan dihalangi oleh pemilik perkebunan. Sejarah teh di Indonesia, seperti halnya sejarah kopi dan tembakau, adalah kisah bergelimang darah dan penindasan. Sebagai ilustrasi, silakan membaca buku Jan Breman tentang bentuk-bentuk brutal pengendalian buruh di perkebunan kolonial, Menjinakkan Sang Kuli yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Tak ada kebebasan memilih bagi buruh. Pilihan yang mereka miliki hanyalah bekerja atau lapar. Memilih sakit atau bahkan mati karena lapar tentu tidak bisa kita sebut ekspresi kebebasan. Pasar sudah ada selama ribuan tahun. Pada hakikatnya tak ada yang salah dengan pasar itu sendiri. Pada masa peradaban Mesir marak perdagangan antar daratan dan lintas lautan dengan aneka macam komoditi. Yang penting kita pertimbangkan adalah milik (property): Bagaimana hubungan kepemilikan antar orang? Apa hubungan kuasa antara satu pihak dengan pihak lain? Adanya pasar berarti ada konsepsi tentang milik. Pedagang menjual sesuatu yang dia miliki. (Siasat pedagang sekaligus pencuri yang paling jitu adalah menjual barang curiannya kepada pemilik awal barang tersebut.) Karakter pasar bergantung pada hubungan kepemilikan yang sudah terbangun dalam masyarakat. Sebagai gambaran, ketika para pedagang Belanda pertama kali berlayar ke kepulauan Nusantara pada awal abad ke-17, mereka membeli rempah-rempah di berbagai kota pelabuhan tanpa memiliki semeter tanah pun di wilayah ini. Mereka membeli rempah-rempah dari pedagang lain yang membawa rempah-rempah tersebut dari daerah pedalaman tempat barang dagangan itu diproduksi. Pada saat itu belum ada perkebunan. Berbagai kelompok etnis dan kekerabatan menanam lada, pala, dan rempah-rempah lain yang ada pada saat itu; tapi, mereka tidak bekerja banting tulang di bawah ancaman cambuk. Baru pada akhir abad ke-18 dan 19 ketika para pedagang Belanda ini berhasil memperoleh kekuasaan politik, mereka mulai mengendalikan proses produksi rempah-rempah. Konsumen di Eropa tidak tahu-menahu asal-muasal rempah-rempah ini hanya dengan melihatnya di tokotoko di Amsterdam. Apakah barang-barang itu diproduksi oleh orang yang bebas atau budak tak tampak di medan jual-beli. Contoh serupa, konsumen sepatu Nike di AS hanya bisa melihat sepatu terpajang di etalase, tanpa pengetahuan tentang pabrik-pabrik pemeras keringat buruh Indonesia tempat memproduksi sepatu-sepatu tersebut. Komoditi, barang mati tak bicara, tidak menunjukkan relasi kuasa di tempat mereka diproduksi. Mereka diam di pasar menunggu dijual. Para ekonom yang mengagungkan “pasar” sebagai arena kebebasan dan kesetaraan mengekor belaka pada perspektif buta ini dan mengabaikan kondisi sosial yang menaungi proses produksi komoditi. Seorang sejarawan dan ahli antropologi Karl Polanyi (1886-1964) dalam buku klasik dan ternamanya, The Great Transformation (1944), berbicara tentang bagaimana karakter pasar secara kualitatif berubah sekitar 1500-1600an di Eropa. Buku ini seharusnya menjadi bacaan wajib bagi semua pelajar dan ahli ilmu sosial. Ia berpendapat bahwa manusia, selama jutaan tahun, untuk kelangsungan hidupnya bergantung pada barang-barang yang tidak dijadikan komoditi. Di masyarakat jaman purba dan pertengahan yang diperdagangkan di pasar bukanlah barang kebutuhan sehari-hari, melainkan barang-barang khusus. Misalnya, sebagai bagian dari komunitas agraris seseorang memproduksi bahan makanan, seperti beras atau gandum, dan menerima bagiannya dari panen bersama. Jadi, ia tidak perlu membeli bahan-bahan ini di pasar. Yang tersedia di pasar sekadar barang-barang tambahan seperti garam atau lada yang dibawa dari Asia, atau benda-benda mewah untuk kaum elit pengumpul pajak di kota. Pedagang tidak mengendalikan proses produksi komoditi yang mereka jual; mereka hanya membelinya di satu tempat dengan harga murah dan membawanya ke tempat lain untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Hal pokok yang diutarakan Polanyi adalah bahwa kelangsungan hidup manusia tidak sepenuhnya tergantung pada pasar. Ia beranggapan bahwa “ekonomi” bukanlah ranah kegiatan yang terpisah. Berbeda dengan yang terjadi sekarang, dahulu tidak ada konsep tentang ekonomi yang berfungsi menurut hukum-hukumnya sendiri tanpa ada kaitan dengan masyarakat atau keinginan manusia. Pedagang tidak mengendalikan negara. Pada saat itu ada pasar, tetapi kegiatan dan wilayahnya “termaktub” dalam hubungan-hubungan komunal, kekerabatan, keagamaan dan politis. “Transformasi besar-besaran” yang merupakan judul buku Polanyi adalah proses komodifikasi tiga hal pada awal era modern Eropa, yaitu tanah, buruh dan waktu, yang sebelumnya tak pernah terjadi. Polanyi, yang sampai taraf tertentu mengikuti pemikiran Karl Marx pada abad ke-19, berpendapat bahwa kapitalisme bukanlah suatu sistem ekonomi di mana pasar menjadi lebih bebas atau di mana para pedagang dibebaskan dari pembatasan yang diterapkan kekuasaan feodal. Yang mendefinisikan kapitalisme adalah penggusuran orang dari tanah mereka secara besar-besaran. Begitu orang tak memiliki tanah, seperti yang terjadi di Inggris sejak abad ke-16, mereka harus bergantung pada pasar untuk bertahan hidup. Kalau kita mengamati hubungan sosial kepemilikan, kita akan menemukan bahwa pasar di bawah kapitalisme berkaitan dengan desakan, yaitu, desakan untuk berpartisipasi dalam pasar. Mereka yang tak bermilik hanya punya pilihan terbatas antara bekerja atau kelaparan. Sekarang mayoritas orang di negeri-negeri kapitalis maju seperti AS tidak memiliki modal; mereka hidup dari pekerjaan yang berupah jam-jaman. Mereka tidak hidup dari perolehan keuntungan saham, bunga, atau pembagian keuntungan perusahaan. Sejarah kapitalisme sebenarnya adalah sejarah penggusuran orang dari tanahnya dan penciptaan pasar tenaga kerja yang terus-menerus berkembang meluas. Mereka yang mendukung perkembangan kapitalisme dan ‘pasar bebas’ di Indonesia harus mengamati dengan serius negara-negara ‘berkembang’ seperti AS: konsekuensi tak terhindarkan dari perkembangan kapitalisme adalah pesatnya pertumbuhan kelas orang-orang bermilik (propertied class). Konsentrasi kekayaan di AS dewasa ini luar biasa besarnya: di satu sisi ada ‘surplus’ penduduk yang masif dan tidak mendapat bagian apa-apa dari ‘pasar bebas’; di sisi lain, hidup segelintir milyuner. Pemerintah AS banyak mengerahkan pendapatan pajak mereka untuk mendisiplinkan ‘surplus’ manusia tak bermilik ini dengan kekuatan polisi. Lebih dari 1 juta orang Amerika berada di penjara – jumlah total narapidana terbesar dan perkapita tertinggi di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang mengunggulkan ‘pasar bebas’ memuja filsuf Skotlandia Adam Smith (1723-90), yang menulis buku The Wealth of Nations (1776), sebagai pemikir tentang ‘pasar bebas’. Buku teks standar ilmu ekonomi ini disebut ‘neoklasik’ karena berisi pembaruan ide-ide Adam Smith yang bersama David Ricardo (1772-1823), dianggap sebagai ekonom ‘klasik’. Pembaharuan ini dilakukan dengan menghilangkan pendapat Smith dan Ricardo mengenai teori kerja tentang nilai (labor theory of value), yaitu teori tentang nilai komoditi yang ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang termaktub di dalamnya. Pikiran-pikiran ekonomi “marginalist” yang muncul pada paruh akhir abad ke-19, diwakili oleh ekonom-ekonom seperti W.S. Jevons (1835-82) dan Alfred Marshall (1842-1924), menyatakan bahwa nilai komoditi pada dasarnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan. Dan itulah ajaran utama yang bisa diperoleh dari ilmu ekonomi standar dewasa ini. Adam Smith sebenarnya bukanlah penjelmaan awal ekonom IMF di masa kini. Apabila kita baca karyanya, kita akan melihat bahwa Smith masih tetap mengharapkan negara mendukung kesejahteraan publik dan tidak begitu saja menghilang, seperti yang diinginkan IMF. Ia bahkan berpikir bahwa pedagang, kaum yang hidupnya dari keuntungan, akan menciptakan anarki apabila mereka mengendalikan negara karena mereka terutama dimotivasi oleh kepentingan mereka pribadi dan bukannya kepentingan umum. Ia mengkhawatirkan munculnya anarki pasar, dan kesewenang-wenangan pedagang menjadi prinsip-prinsip pemandu kehidupan sosial. Smith mendukung perkembangan kapitalisme, itu pasti – ia menginginkan buruh menjadi lebih produktif melalui pembagian tenaga dan kemajuan teknologi yang lebih canggih. Tetapi ia ingin supaya pasar dikendalikan secara bijaksana oleh “negarawan”, sedemikian rupa sehingga pasar itu bisa melayani kepentingan sosial yang berguna bagi publik. Ia menyatakan bahwa bukunya merupakan latihan di bidang “ekonomi politik”, yaitu ilmu bagi “negarawan atau pembuat undang-undang” supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Salah satu ajaran Smith yang perlu kita pertimbangkan benar dewasa ini: “Usulan perundangundangan atau aturan perdagangan baru apa pun yang datang dari tatanan ini [para majikan yang hidup dari keuntungan] harus selalu didengarkan dengan kewaspadaan luar biasa, dan tidak pernah boleh diberlakukan sebelum dikaji secara seksama dan mendalam, bukan hanya dengan perhatian yang paling teliti, tetapi juga dengan kecurigaan. Usulan itu datang dari kaum yang kepentingannya tidak pernah sepenuhnya sama dengan kepentingan publik, yang secara umum berkepentingan untuk menipu dan bahkan menindas publik.” Smith mungkin akan terperanjat membaca karya Milton Friedman yang begitu polos berasumsi seakan-akan kepentingan kaum kapitalis berjalan selaras seimbang dengan kepentingan masyarakat luas. Umumnya dipercaya bahwa pada masa depresi mendunia di 1930an pasar di bawah kapitalisme bersifat anarkis. Pasar bergerak mengikuti siklus liar ledakan dan kemerosotan perdagangan. Ketika begitu banyak orang bergantung pada pasar untuk bertahan hidup (menjual tenaga kerja mereka untuk upah dan membeli kebutuhan sehari-hari dengan upahnya) jenis fluktuasi tak terkendali serupa ini menyebabkan penderitaan sosial secara massal. Ekonomi terencana di Republik Sosialis Uni Soviet kemudian tampak sebagai pilihan yang sepenuhnya rasional dan praktis bagi banyak orang pintar karena kinerja kapitalisme yang kacau balau saat itu. Kapitalisme tampak tak bisa bertahan lama kecuali jika pasar dikendalikan oleh aturan-aturan negara. Itulah sebabnya karya ekonom John Maynard Keynes (1883-1946) menjadi penting. Tulisan-tulisannya menunjukkan bagaimana investasi dan pengeluaran negara bisa mencegah keliaran fluktuasi siklus perdagangan dan menjaga supaya kapitalisme bisa lancar bekerja. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi paska PD II di Eropa barat, AS dan Jepang diraih oleh kaum elit ekonomi yang bekerja sejalan dengan ide-ide Keynes. Ide-ide dan praktek Keynesian ditinggalkan pada 1970-an dan 1980-an ketika para kapitalis menganggap bahwa anarki pasar itu hanyalah dongeng masa lalu. Gagasan Milton Friedman meraih pengaruh lebih besar. Di banyak negara maju, industri negara diswastakan dan tunjangan kesejahteraan bagi pengangguran dan kaum miskin dihapus. Negeri-negeri ini memulai peperangannya terhadap kaum miskin. Pertumbuhan pesat jumlah narapidana di AS beranjak pada awal 1980-an. Dalam logika standar para ekonom dewasa ini pilihan yang ada hanyalah antara pasar bebas dan ekonomi terencana, dan pilihan terakhir telah terbukti salah dengan runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Tapi sebenarnya ada lebih dari dua pilihan di atas. Bagi mereka yang selalu berbicara tentang pasar bebas, kita harus mengamati mereka dengan kecurigaan dan bertanya: pasar yang mana? Pasar seperti apa? Kebebasan untuk siapa? Saya akan mengusulkan tiga rekomendasi: Pertama, kita harus berpikir tentang peraturan negara terhadap pasar. Bahkan ekonom neoklasik kelas berat sekali pun menyadari bahwa negeri seperti Indonesia, paling tidak, membutuhkan kontrol terhadap masuk-keluarnya modal asing. Salah satu alasan penting kejatuhan ekonomi pada 1997 adalah cepatnya melayang modal asing yang ditanam di bank dan pasar saham. Rezim Soeharto, berdasarkan saran IMF dan pemerintah AS, menciptakan pasar bebas untuk uang. Tanpa modal domestik yang cukup besar, ekonomi Indonesia bisa diguncang oleh keluar-masuknya modal asing yang tidak diatur. Banyak ekonom setelah melihat krisis di Asia, Meksiko, dan Brazil mempertimbangkan kembali ide-ide Keynes. Kedua, kita harus berpikir tentang perluasan kemampuan rakyat untuk bertahan hidup dengan akses ke sumber daya alam yang tidak dikomoditi. Banyak orang di Indonesia bertahan hidup dalam krisis karena mereka masih bisa memperoleh makanan dari hasil tanah mereka sendiri, mengambil bahan mentah dari hutan, atau dari sungai dan laut. Contohnya: Indonesia sekarang menyelenggarakan pasar bebas untuk industri kayu. Pedagang yang seringkali merangkap sebagai perampok bisa membayar pejabat pemerintah, menyapu bersih hutan yang ada dan mengekspor kayu hasil hutan tersebut. Hutan di Kalimantan dan Sumatra dihancurkan dengan cepat oleh saudagar-saudagar kayu seperti ini sehingga rakyat tak punya lagi akses ke sumbersumber penghidupan di dalam hutan. Pasar bebas di bidang perkayuan ini harus dihentikan. Ketiga, kita harus mengerti bahwa tidak semua keterlibatan negara dalam ekonomi itu buruk. Jika negara yang ada sangat korup, seperti Indonesia, memang tipis harapan akan ada perbaikan dengan adanya intervensi negara. Tetapi negara yang demokratis bisa secara efektif melakukan intervensi dan secara positif menyumbang pada kesejahteraan masyarakat. Apabila pengoperasian negara itu transparan, para pejabatnya pun tidak punya ruang terlalu luas untuk melakukan korupsi. Demokrasi, seperti berulangkali ditekankan ekonom pemenang Nobel, Amartya Sen, merupakan unsur hakiki untuk perkembangan ekonomi justru karena negara memiliki peran penting di dalamnya. Masyarakat Indonesia menginginkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai dan baik. Jelas para pedagang tak akan mampu menyediakan pelayanan seperti ini kecuali bagi segelintir elit yang bisa membayar cukup banyak. Negara harus terlibat dalam penyelenggaraan klinik kesehatan dan sekolah untuk warganya (bahkan Adam Smith mendukung perlunya subsidi negara untuk pendidikan). Dan apabila negara diharapkan terlibat dalam penyediaan pelayanan masyarakat yang vital seperti ini maka negara itu harus demokratis. Mereka yang menuntut “pemerintahan yang bersih” dan “penyelenggaraan negara oleh kaum profesional” secara netral sebagai syarat pemerintahan yang efektif tanpa mengatakan apa-apa tentang demokrasi sebenarnya sudah membohongi publik. Referensi: Friedman, Milton, and Friedman, Rose, Free to Choose: A Personal Statement (New York: Harcourt Brace Jovanivich, 1980) Polanyi, Karl, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (first published 1944; reprint, Boston: Beacon Press, 1957). Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (first published 1776; reprint, Oxford: Clarendon Press, 1976) Wood, Ellen Meiskins, “From Opportunity to Imperative: The History of the Market,” Monthly Review, 46: 3 (July-August 1994). John Roosa, sejarawan yang bekerja di Universitas California, Berkeley, AS.
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Arnold Clemens Ap Membangun Budaya Pembebasan IBE Karyanto Keprihatinan dan perjuangan masya rakat Papua adalah keprihatinan dan perjuangan warga manusia yang terus menerus hidup di bawah kekuasaan represif yang mengontrol dan mengendalikan kehidupan harian. Berbagai sikap dan bentuk perlawanan masyarakat Papua, yang kemudan diberi label GPK, GPL dan sebagainya akan menjadi lebih terang kalau dipahami dalam konteks kepentingan pemerintah Indonesia baik pada zaman pemerintahan Soekarno dan terlebih lagi pada masa rezim Orde Baru. Tidak mengherankan kalau gerakan masyarakat Papua yang mengembangkan seni-budaya asli Papua pun dianggap sebagai aksi masyarakat yang potensial mengancam kepentingan pemerintah. Penangkapan dan pembunuhan Arnold Clements Ap, seorang antropolog, penyair dan musisi ternama, pada April 1984 oleh tentara hanyalah satu contoh dari sekian banyak tindakan represi pemerintah Indonesia yang sudah jauh melampaui batas-batas kemanusiaan. Nama Arnold Clements Ap tidak populer di telinga orang Indonesia, tapi nama yang sama sempat membuat penguasa Orde Baru gerah. Ia dijebak lari keluar dari penjara, lalu Kopassandha dikirim untuk membunuhnya di tepi pantai. Seperti di wilayah-wilayah yang tinggi tingkat represi militernya, rakyat Papua sudah bisa menduga apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Arnold Ap, yang begitu setia dan konsisten dengan gerakan kebudayaannya. Bahkan Arnold sendiri pernah kepada teman-temannya menegaskan konsekuensi macam apa yang akan menyertai aktivitasnya. Sekalipun orang-orang pada umumnya dan orang-orang istimewa macam Arnold sudah menduga apa yang akan terjadi, namun hanya rezim penguasa, tepatnya tentara, yang bisa memastikan kapan dan konsekuensi macam apa yang akan menimpa orang-orang yang setia pada perjuangan kemanusiaan. Tak ada yang menduga kalau tentara begitu cepat merenggut nyawa pejuang pembebasan ini. Usianya saat itu baru 38 tahun. Akhir November 1983 Arnold masih dipercaya memimipin rombongan keseniannya untuk menyambut kedatangan tamu, para istri atase perwira militer asing yang dipimpin istri Jenderal L.B. Moerdani, yang berkunjung ke Papua. Arnold sama sekali tidak berpikir kalau kesenian yang dibawakan pada hari itu akan menjadi aktivitasnya yang terakhir dalam seluruh rangkaian gerakan kebudayaan yang dibangun bersama teman-temannya. Keesokan harinya rombongan pasukan berpakaian preman mengambil Arnold dari rumah kediamannya. Tidak jelas Arnold akan dibawa ke mana. Keluarganya hanya diberitahu bahwa Arnold akan di bawa ke satu tempat. Tapi gerombolan penculik terlalu gegabah jika menganggap tidak ada satu pun orang tahu keberadaan Arnold setelah diambil dari rumahnya. Tidak lama berselang harian Sinar Harapan memberitakan peristiwa penangkapan dan penahanan itu. Hanya segelintir orang Indonesia yang bereaksi atas tragedi tersebut, termasuk Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) waktu itu. Dalam pernyataannya ia menggugat supaya penangkapan dan penahanan Arnold Ap diproses sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan YLBHI dan dua tulisan yang diturunkan Sinar Harapan dalam satu minggu terbitannya sudah cukup untuk membuat tentara, tepatnya Kopassus (Kopassandha waktu itu) marah. Sinar Harapan terancam bredel, kalau tidak segera minta maaf dan bersedia mendengarkan “kebenaran” cerita versi tentara. Berita tentang penangkapan dan penahanan Arnold menggerakkan pemuda Papua yang sedang belajar di Jakarta. Ottis Simopiaref dan tiga temannya melancarkan protes ke DPR-RI. Aksi pembelaan terhadap kejadian yang dialami Arnold Ap tersebut membuat pihak intelijen Kopassandha semakin gerah. Pengawasan dan upaya penangkapan terhadap keempat pemuda tersebut semakin intensif. Menyadari keselamatan mereka terancam, keempat pemuda Papua minta suaka pada Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Setelah dua minggu berlindung di sana, mereka berhasil diterbangkan ke Belanda. Sementara itu di Papua, tentara belum juga berhasil mengorek informasi dari Arnold Ap tentang bukti keterlibatannya dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dengan sendirinya tidak ada dasar kuat untuk membenarkan penangkapan dan penahanannya selama berbulan-bulan. Segala cara sudah ditempuh, tapi bukti tetap tak diperoleh. Karena memang sudah menjadi sasaran untuk disingkirkan, maka rencana lain pun mulai disusun. Bukti keterlibatan dan sebagainya menjadi tidak penting; satu-satunya persoalan sekarang adalah membuktikan bahwa Arnold Ap dengan satu atau lain cara pantas dihukum. April 1984 seorang polisi asal Papua berhasil membujuk Arnold Ap dan keempat temannya untuk melarikan diri dari tahanan Polda. Pelarian, lebih tepatnya rencana perburuan, berjalan mulus kecuali bagi dua teman Arnold. Satu memutuskan berpisah di tengah jalan dan kemudian selamat, sementara satunya terbawa ombak ketika harus berenang mencapai perahu yang akan membawa mereka ke suatu tempat. Beberapa hari Arnold Ap dan kedua temannya didamparkan di pegunungan Cylops, sebelum katanya akan dibawa ke tempat yang lebih aman. Selama beberapa hari itu Arnold Ap mendapatkan pasokan makanan yang diantar dengan perahu yang juga dipakai untuk melarikan diri. Selang beberapa hari perahu datang lagi, kali ini bukan makanan yang dibawa melainkan gerombolan pasukan Kopassandha lengkap dengan senjata. Tanpa perlawanan berarti tentara menyarangkan tiga butir peluru di tubuh Arnold. Dalam keadaan luka parah Arnold dibawa dengan perahu menuju Jayapura. Mungkin tidak akan ada yang tahu kematian Arnold kalau saja perawat tidak memeriksa kamar jenazah RSAD Aryoko hari itu. Dengan berani perawat tersebut mengabarkan kematian Arnold Ap kepada teman-temannya. Karena berita sudah menyebar dan masyarakat terlanjur tahu, tentara pun terpaksa menyerahkan jasad Arnold pada keluarganya. Ratusan masyarakat Papua mengiringi kepergian jasad Arnold Ap menuju tempat perisitirahatannya terakhir sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu pujian. Arnold Ap meninggal, tapi perjuangan dan gerakan kebudayaan yang pernah dibangun memberi inspirasi yang terus bergema melampaui sungai, gunung dan lautan. Mambesak Mendesak Pembebasan Kultural Arnold Ap lahir di Pulau Numfor, dekat Biak, pada1945. Ia mengambil bidang studi geografi di Universitas Cenderawasih, dan sangat tekun mempelajari seluk-beluk Papua yang luar biasa kaya. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang tekun. Seorang pembimbingnya, Dr. Malcolm Walker menganggap Arnold sebagai “orang yang punya prinsip” dan konsisten dengan komitmennya untuk belajar memahami dan mengembangkan kebudayaan masyarakatnya. Kesan serupa juga muncul dari beberapa sarjana dari luar negeri dan pejuang HAM Indonesia yang pernah bertemu dengannya. Sementara rekan-rekannya di Papua sendiri menganggap Arnold sebagai perwujudan budaya Papua. Gagasan Arnold untuk mulai membangun strategi gerak kebudayaannya berawal dari langkah sederhana sebagai anak muda. Awal 1970-an Arnold Ap dan beberapa teman mahasiswanya mendirikan group band Manyori (Burung Nuri). Meskipun warna kebarat-baratan masih kental dalam permainan musiknya, namun kelompok yang terdiri dari tiga personil ini – Arnold Ap, Joupi Jouwei dan Sam Kapissa – cukup populer. Atas desakan teman-temannya Arnold kemudian bersedia memberikan pelayanan pada jemaat Gereja Kristen Injil dengan memainkan lagu-lagu rohani di gereja. Perjumpaannya dengan lagu-lagu gereja yang kuat berkiblat pada gaya Eropa mengusik Arnold. Semangatnya sebagai orang Papua menggugah Arnold untuk mencoba menciptakan lagu dan irama musik gereja yang berakar dari kebudayaannya sendiri. Mulailah Arnold bersama dengan teman seniman lainnya, Damianus Wariap Kuri, menggarap musik gereja dalam irama Biak-Numfor. Pada awalnya upaya tersebut mendapat tentangan dari orang-orang tua jemaat Gereja. Bisa dimaklumi karena misionaris Eropa yang membawa agama Kristen masuk ke kawasan Teluk Saerera sebelumnya telah menganggap kafir hampir seluruh aspek budaya Saerera. Namun tentangan tidak berlangsung lama. Dalam waktu yang cukup singkat gerakan pribumisasi musik liturgi gereja mendapat sambutan dan dukungan. Salah satu dukungan kuat datang dari Dr. Danielo C. Ajamiseba, linguis pertama Papua yang baru menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Dukungan berikutnya datang dari para pendeta muda lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan para sarjana lulusan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Perkembangan pribumisasi musik liturgi gereja mendorong Arnold Ap untuk semakin tekun berupaya mengembangkan seni-budaya Papua yang lainnya. Karena minat dan bakatnya di berbagai bidang, ia diangkat menjadi Kepala Museum Universitas Cenderawasih oleh pimpinan Lembaga Antropologi, Ign Suharno. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk mematangkan gagasan dan melahirkan karya-karya kreatif. Perhatian Arnold pada seni budaya Papua pun mulai mengembang keluar dari lintas batas Biak-Numfor dan kawasan Saerera. Perjalanannya penelitiannya ke beberapa kampung di wilayah berbagai suku di Papua digunakan sekaligus sebagai kesempatan untuk mencatat dan merekam lagu-lagu, tarian dan ekspresi kebudayaan rakyat lainnya. Semakin mendalam pengetahuannya, semakin ia tak puas melihat kebijakan dan praktek aparat pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan “asli” Papua. Di satu sisi ia melihatnya sebagai upaya penaklukan. Orang Papua dibiarkan memelihara bentukbentuk kebudayaan yang ada – itu pun sangat terbatas – tapi tidak bisa mengembangkan isi apalagi semangat pembebasan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain ia melihat upaya itu semata-mata untuk menjual kebudayaan Papua, lagi-lagi dengan melepas isi dari bentuknya. Kebudayaan Papua sering dipakai oleh para pembuat film, disaner mode dan sebagainya, sebagai bukti “kebudayaan primitif” di Indonesia. Akibatnya rakyat Papua, khususnya para seniman dan pekerja budaya, seringkali tanpa sadar terseret melayani kepentingan promosi semacam itu dengan menciptakan tarian “asli kreasi baru” yang tidak memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat. Arnold juga prihatin melihat kecenderungan merebaknya lagu-lagu diatonis yang dinilainya jauh dari semangat rakyat Papua yang selalu menyanyikan lagu dalam nada minor. Lebih dari lima tahun Arnold Ap melakukan studi serius tentang seni tari dan musik Papua sebelum akhirnya bersama beberapa temannya memutuskan untuk mempublikasikan musik dan tari hasil studi mereka. Arnold dan teman-temannya pertama kali menampilkan musik dan tari dalam rangka acara peringatan 17 Agustus 1978 yang diselenggarakan di halaman Lok Budaya, Museum Antropologi Universitas Cenderawasih. Pementasan itu kemudian dicatat sebagai tanggal lahirnya komunitas kerja seni-budaya “Mambesak”. Arnold keberatan terhadap gagasan temannya yang mengusulkan untuk mempertahankan nama Manyori dengan alasan burung Nuri merupakan burung suci yang dihormati oleh masyarakat Biak-Numfor saja. Sedangkan Mambesak, yang berarti burung Cendrawasih, merupakan burung suci yang dihormati oleh masyarakat di seluruh Papua Barat. Pilihan nama tersebut jelas memperlihatkan keluasan pemahaman Arnold terhadap kebudayaan Papua di satu sisi, sekaligus memperlihatkan kesadaran perjuangan Arnold yang tidak lagi terbatas pada suku tertentu di sisi lain. Dalam rapat pembentukan pengurus pertama di Agustus 1978, Arnold dipilih sebagai koordinator. Sejak saat itu komunitas seni-budaya Mambesak seakan tak pernah berhenti menyelenggarakan berbagai bentuk pementasan di berbagai wilayah Papua Barat, bahkan pernah diutus sebagai wakil kesenian Papua dalam sebuah festival senibudaya yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun yang sama dengan berdirinya Mambesak, atas usulan Ign. Suharno, Arnold Ap diangkat menjadi penanggungjawab siaran Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra program RRI Jayapura. Siaran tersebut resminya adalah program yang dikelola Universitas Cenderawasih untuk memperkenalkan kebudayaan daerah dan membangkitkan serta mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah. Tapi kemudian, setelah penunjukan Arnold, program tersebut sepenuhnya diasuh oleh gerakan Mambesak. Melalui program radio yang dirancang secara kreatif Arnold membangun kesadaran baru rakyat Papua. Dengan cerdik dan jenaka Arnold sering menyisipkan ajakan untuk lebih mengenali akar budayanya sendiri. Tidak jarang Arnold juga menggunakan program siaran radionya untuk menyebarkan analisa sederhana tentang pengetahuan umum. Sebagai sarjana muda geografi yang tertarik pada persoalan ekologi, Arnold melalui corong radionya berusaha merangsang masyarakat Papua pedalaman untuk menjaga kelestarian alam, hutan. Tak jarang melalui corong yang sama Arnold mengecam kebijakan-kebijakan resmi dan tindakan aparat pemerintah yang sering justru merugikan masyarakat Papua, seperti ketika pemerintah memberikan bantuan beras untuk bantuan kelaparan. Ini tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat Papua yang tidak biasa dan tidak memiliki fasilitas memasak beras. Tiga prinsip yang dijaga Arnold dan berhasil menjadikan program siaran radionya populer di masyarakat, yaitu penggunaan bahasa Indonesia logat Papua sebagai bahasa pengantar, penyajian uraian-uraian pokok tentang unsur kebudayaan Papua serta pengetahuanpengetahuan aktual, dan ketiga penyiaran lagu rakyat dan cerita-cerita jenaka yang berakar pada kebudayaan rakyat suku-suku di bagian utara. Siaran dan lagu-lagu Mambesak yang diputar dalam program radio Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra pun merambah melintasi batas telinga masyarakat Papua. Cukup banyak masyarakat Papua di luar negeri merasa mendapatkan semangat perjuangannya kembali ketika mendengarkan program-program radio yang dibawakan Arnold dan teman-temannya. Tapi sebaliknya para penguasa mulai cemas melihat popularitas program radio dan rekaman lagu-lagu yang dihasilkan Mambesak semakin populer. Kebudayaan Dengan Keringat Sendiri Arnold bukan hanya seorang seniman. Sebagai intelektual ia terkenal cerdas dan tajam melihat bermacam persoalan. Kepribadian yang kuat dan komitmen yang besar pada gerakan rakyat membuat Arnold tak mau tunduk pada berbagai tawaran yang datang dari luar. Ia paham bahwa aksi-aksi kebudayaan hanya mungkin berkembang menjadi gerakan, jika hidup dari dukungan masyararakatnya sendiri, bukan bergantung pada kekuatan lain. Dan mayarakat hanya akan mendukung jika memang merasa memiliki, atau mendapat tempat dalam gerakan tersebut. Di samping melakukan penelitian, bermain di pentas dan membuat rekaman, Arnold pun mencurahkan sebagian tenaganya untuk menggalang dana dari masyarakat sendiri. Gagasan tersebut disambut baik oleh teman-temannya di Mambesak. Mereka kemudian menjajakan kaset yang berisi rekaman lagu-lagu rakyat yang dikumpulkan dari berbagai daerah di Papua atau lagu Papua garapan sendiri. Dengan menjual kaset Mambesak mengayuh dua pekerjaan sekaligus. Di satu sisi niat menyebarkan kasanah musik dan lagu-lagu rakyat Papua yang sudah mulai banyak ditindih dengan budaya asing bisa berjalan dan di sisi lain Mambesak terbantu untuk menjalankan gerakannya dari hasil penjualan kaset yang sama. Sebuah pekerjaan yang berat karena para aktivis tiba-tiba harus menghadapi kepentingan dagang dari pihak produser yang bahkan sempat memicu ketegangan di antara anggota kelompoknya. Sebelum meninggal, Arnold Ap sempat menyaksikan perkembangan gairah rakyat Papua, yang ingin menghirup kesegaran roh seni dan budayanya sendiri. Kelompok musik Papua bermunculan di mana-mana. Pemakaian pita kaset untuk penyebaran lagu-lagu Papua menjadi semacam revolusi komunikasi tersendiri. Dari sumber yang sama, musik dan lagu tradisi Papua, berbagai kelompok musik mencoba menawarkan bermacam ragam bentuk kepada masyarakat. “Yang satu ingin me-Papua-kan musik populer, sedang yang lain ingin mempopulerkan musiklagu Papua,” kata Sam Kapissa, salah satu tokoh Mambesak yang kemudian mengembangkan aksinya sendiri di luar Mambesak. Revolusi pita kaset mulai terasa menjelang pertengahan 1980an. Bulan-bulan menjelang natal kaset lagu-lagu natal dan gerejani bernapas Papua membanjiri toko-toko kaset. Lagu-lagu natal dan gerejani dari kaset yang senada mulai terdengar di berbagai tempat umum seperti lingkungan kampus, bandara Abepura dan tempat-tempat umum lain. Masyarakat Papua seperti menemukan kembali kepercayaan diri yang selama ini direnggut oleh kekuatan asing. Sejalan dengan perkembangan gerakan kebudayaan yang dipelopori Arnold Ap dan temantemannya di Mambesak, tentara pun semakin khawatir akan kemungkinan menguatnya gerakan pembangkangan dan perlawanan masyarakat Papua terhadap kekuasaan rezim. Memang sejak awal orang Papua bisa memperkirakan bahwa kegiatan Arnold yang begitu berpengaruh akan dilihat sebagai ancaman oleh rezim. Berkembangnya kebudayaan dan kesadaran di kalangan rakyat, adalah ancaman besar karena sulit diukur dan dikendalikan. Aparat intelijen bersusahpayah mencari hubungan Arnold dan kelompok Mambesak dengan OPM atau gerakan perlawanan lainnya. Arnold berulangkali ditahan dan diinterogasi, tapi karena posisinya dalam masyarakat dan perhatian luas dari berbagai pihak, ia pun dilepas kembali. Upaya menemukan “bukti-bukti keterlibatan” pun kandas. Keputusan pun akhirnya datang, Arnold Ap harus disingkirkan. Bukti, alasan dan sebagainya bisa ditentukan belakangan. Aparat bergerak, menangkap, menyiksa lalu membunuh, dan membuat laporannya sendiri. Jerit menagih keadilan dan kemanusiaan pun hilang ditelan perintah-perintah tegas, suara handie-talkie dan letusan senapan yang membunuh Arnold. Arnold Ap meninggal sebagai pejuang kebudayaan Papua. Rakyat menghormatinya sebagai konor yang berarti filsuf atau orang suci yang dipercaya memiliki kharisma dan kekuatan. Sekitar 500 orang hadir dalam pemakamannya yang dijaga ketat oleh aparat. Tubuhnya sudah ditanam, tapi semangatnya meluap-luap ke segala penjuru, beranak-pinak melanjutkan apa yang pernah diperjuangkannya. IBE Karyanto, pekerja pada Jaringan Kerja Budaya dan Rektor pada Universitas Sanggara 'Akar'
1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
BERITA PUSTAKA
100 Tahun Bung Karno 6 Juni 1901-2001: Sebuah Liber Amicorum Editor: Joesoef Isak, Penerbit Hasta Mitra, Jakarta, Juni 2001 Liber Amicorum atau kumpulan tulisan mengenai 100 tahun Bung Karno ini ditulis oleh 22 pengarang dari bermacam sudut pandang. Beberapa penulis menekankan pada peranan Amerika Serikat dalam rangka mendongkel kepemimpinan Bung Karno, sebagaimana yang diguratkan oleh Pramoedya Ananta Toer, “Soekarno pernah menyatakan bahwa abad ke 20 adalah abad intervensi, dimana kekuatan-kekuatan adikuasa dengan seenaknya mengaduk-aduk urusan intern pada negeri lain.” Sedangkan penulis lainnya menekankan pada pemikiran Bung Karno serta implikasinya pada proses nation building sebagaimana ditulis oleh Hersri Setiawan, “Bung Karno satu-satunya presiden dari satu negara muda yang menerima 26 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas bergengsi dari seluruh penjuru dunia. Salah satunya dari Universitas Gajah Mada untuk bidang sejarah. Menurut Soekarno, penulisan sejarah Indonesia harus diubah, pertama: sebagai bangsa muda yang baru merdeka, harus menulis ulang sejarah sendiri; kedua, dalam menulis ulang sejarah sendiri itu, orientasi kesejarahan harus dibalik, tidak ke barat tapi ke timur, tidak ke India atau Belanda tapi ke Indonesia sendiri!” Demikian pula Ben Anderson menegaskan “setelah Soekarno meninggal, kehadirannya tetap hidup, tidak ada rivalnya di Asia Tenggara yang dapat menandinginya kecuali almarhum Ho Chi Minh. Harapan yang diberikan Soekarno cukup jelas dibuktikan dengan dukungan luar biasa bagi anaknya Megawati yang sebaliknya tidak punya keistimewaan sama sekali. Buku ini sebagaimana ditegaskan oleh Joesoef Isak, berbeda dengan tulisan lainnya tentang Soekarno, lebih terarah dan menampilkan Soekarno sebagai manusia biasa saja.
Made In Indonesia: Indonesian Workers Since Suharto Pengarang: Dan La Botz Penerbit: South End Press. Cambridge, Massachusetts, 2001 Dinamika baru pergerakan buruh di Indonesia yang muncul pada 1990-an membantu menjungkirkan kebrutalan kediktaktoran Suharto pada 1998. Melalui beberapa wawancara personal dengan para aktivis yang memimpin lahirnya kembali perjuangan untuk hak-hak demokrasi di negeri terbesar keempat di dunia, La Botz menggambarkan pelajaran-pelajaran yang bernilai untuk kaum buruh di Amerika Serikat yang mencoba membangun solidaritas buruh internasional. La Botz membawa kita masuk ke dalam organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik, perjuangan unit-unit kerja serikat-serikat buruh baru dengan perusahaanperusahaan multinasional seperti Nike. Juga memaparkan bagaimana LSM dan kelompokkelompok mahasiswa menempa hubungan dengan kelas buruh. Kekuatan-kekuatan pendapatnya menawarkan harapan terbaik untuk masa depan demokrasi sejati bagi Indonesia.
Dunia Sukab: Sejumlah Cerita Penulis Seno Gumira Ajidarma Penerbit Buku Kompas, Jakarta Juni, 2001 Tentu saja permainan antara fakta dan fiksi ini merupakan pekerjaan rumah yang menarik dalam perbincangan makna, namun tentu bukan itu yang dibicarakan oleh Seno Gumira Ajidarma (SGA). Nama Sukab muncul begitu saja dalam tokoh cerita pendek SGA: Sukab pernah menjadi nama remaja 17 tahun, pemuda parlente, pernah menjadi penggiring bola absurd dan tokoh yang numpang lewat saja, tanpa sempat menjadi sebuah karakter. Sebetulnya Sukab pun pernah mati, bahkan lebih dari sekali. Kumpulan cerita pendek Dunia Sukab dibagi tiga oleh SGA. Dengan kocak SGA menceritakan bagaimana seorang pegawai negeri yang korup terjangkit The Pinoccio Disease. Semacam penyakit hidung panjang yang setiap menit terus memanjang, karena begitu rakus dan mahir mengendus dimana uang yang dapat dikorup. Hal yang juga menarik dari cerita pendek Sukab, SGA berimajinasi mengenai nasib korban, pelaku dari perkosaan Mei 1998 di 2039. Digambarkan anak yang dilahirkan tidak lagi mempunyai identitas dan terus mempertanyakan anak siapa sebenarya. Demikian pula dengan pelaku, yang sulit untuk mengakui kepada anaknya atau istrinya bahwa ia sebenarnya orang yang melakukan perbuatan kriminal. 1 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
SUBVERSI MENEGAKKAN IMPERIUM Politik Luar Negeri Amerika Serikat “Amerika harus menghalangi negara lain yang ingin menyaingi kepemimpinan kita atau ingin mengubah tatanan politik dan ekonomi sekarang ini… Kita harus memelihara mekanisme untuk menghambat para pesaing, sekalipun mereka hanya ingin berperan lebih besar secara regional maupun global.” Demikian pernyataan dalam Pedoman Perencanaan Pertahanan yang dikeluarkan Pentagon untuk 1994-99. Sejarah memang membuktikannya. Menurut John Stockwell, mantan pejabat CIA yang kemudian menulis buku tentang pengalamannya, dinas intelijen itu melancarkan sekitar 3.000 operasi rahasia besar dan 10.000 operasi kecil, yang dirancang untuk “merusak, menciptakan destabilisasi di negeri lain dan memaksa pemerintahnya untuk mengikuti kehendak Amerika Serikat”. Hampir semuanya diarahkan kepada negara, pemerintahan dan pemimpin yang kebijakannya bertentangan dengan kepentingan negeri itu. Menurut perkiraannya sekitar enam juta orang tewas akibat operasi-operasi tersebut. Mesin politik luar negeri Amerika Serikat, menurut para pejabatnya sendiri, digerakkan oleh berbagai kepentingan dasar yang dapat dirumuskan sebagai berikut: •Menciptakan dunia yang aman bagi perusahaan Amerika •Meningkatkan pendapatan perusahaan kontraktor senjata dan peralatan militer yang sudah memberi sumbangan besar kepada anggota kongres. •Menghalangi munculnya masyarakat yang bisa menjadi alternatif model kapitalisme. •Memperluas hegemoni politik dan ekonomi seluas mungkin, yang sesuai dengan citranya sebagai “negara adidaya”. Untuk membenarkan tindakannya, Amerika Serikat melancarkan propaganda “jihad melawan komunis internasional” dan memobilisasi kekuatan-kekuatan di negara sasaran untuk terlibat di dalamnya. Setelah Perang Dunia II, pasukan dan dinas intelijen Amerika Serikat berpetualang di lebih dari 70 negara di dunia. Daftar di bawah ini disusun berdasarkan artikel William Blum dalam Z Magazine dua tahun lalu. Sejak penerbitan itu AS masih terus melakukan serangan dan intervensi. Salah satu yang terbaru adalah rencana serangan total ke Afghanistan yang didakwa melindungi pelaku serangan teroris ke New York dan Washington pada11 September lalu. Tiongkok, 1945-49 Dalam perang saudara, AS berpihak pada Chiang Kai-shek melawan gerakan komunis pimpinan Mao Tse-tung, yang selama Perang Dunia menjadi sekutu mereka. AS mengerahkan mantan lawannya, yaitu serdadu-serdadu Jepang yang kalah dalam Perang Dunia, untuk bertempur melawan mantan sekutunya. Chiang Kai-shek kalah dan melarikan diri ke Taiwan pada1949. Italia, 1947-48 Dengan semua muslihat yang ada dalam dunia intelijen, AS melakukan intervensi dalam pemilihan umum untuk menghalangi Partai Komunis keluar sebagai pemenang yang sah. Tindakan ini dilakukan, menurut para pejabatnya, “untuk menyelamatkan demokrasi” di Italia. Partai Komunis akhirnya kalah, dan selama dekade-dekade selanjutnya, CIA bersama perusahaan Amerika terus-menerus melakukan intervensi, mencurahkan dana jutaan dolar dan melancarkan perang psikologis untuk mencegah Partai Komunis berkuasa. Yunani, 1947-49 AS terlibat dalam perang saudara di pihak neo-fasis melawan gerakan kiri Yunani yang berperang melawan Nazi dalam Perang Dunia. Kaum neo-fasis akhirnya menang dan melembagakan sebuah rezim yang sangat brutal. CIA membantunya dengan mendirikan dinas intelijen dalam negeri, KYP. Lembaga ini, seperti polisi rahasia di mana pun, menggunakan berbagai metode kekerasan yang mengerikan, termasuk penyiksaan secara sistematis, untuk menaklukkan lawan-lawannya. Filipina, 1945-53 Militer AS bertempur melawan gerakan kiri (Hukbalahap), yang saat itu sedang bertempur melawan invasi Jepang. Setelah Perang Dunia, AS terus memerangi gerakan itu, dan menempatkan sejumlah presiden boneka, yang berpuncak pada kediktatoran Ferdinand Marcos. Korea Selatan, 1945-53 Setelah Perang Dunia, AS menindas kekuatan progresif kerakyatan dan berdiri di pihak kaum konservatif yang sebelumnya berkolaborasi dengan Jepang. Untuk waktu yang lama negeri itu kemudian dikuasai oleh rezim-rezim yang korup, reaksioner dan brutal. Albania, 1949-53 AS dan Inggris gagal menggulingkan pemerintahan komunis dan menaikkan pemerintahan proBarat yang beranggotakan keluarga kerajaan dan kolaborator dengan kaum fasis Italia dan Nazi. Jerman, 1950-an CIA melancarkan kampanye sabotase, teror, muslihat kotor dan perang psikologis melawan Jerman Timur. Kampanye ini adalah salah satu faktor yang akhirnya menciptakan Tembok Berlin pada 1961. Iran, 1953 Perdana Menteri Mossadegh digulingkan dalam operasi gabungan AS dan Inggris. Mossadegh dipilih oleh mayoritas anggota parlemen, lalu memimpin gerakan untuk menasionalisasi perusahaan minyak milik Inggris, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi di Iran waktu itu. Dengan kudeta itu, Shah Iran kembali dengan kekuasaan absolut dan memulai pemerintahan selama 25 tahun yang penuh penindasan dan teror. Sementara itu industri minyak diserahkan kembali kepada pemilik asing dengan komposisi Inggris dan Amerika masing-masing 40 persen, sementara negeri lainnya 20 persen. Guatemala, 1953-1990 CIA mengorganisir kudeta untuk menggulingkan pemerintahan progresif Jacobo Arbenz yang dipilih secara demokratik. Kudeta itu menjadi awal dari gelombang kekerasan selama 40 tahun, yang penuh dengan pasukan pembunuh (death squads), penyiksaan, penculikan, eksekusi massal dan kekejaman lain yang tak terbayangkan. Diperkirakan 100.000 orang menjadi korban, dan menjadi salah satu babak paling kejam dalam sejarah abad ke-20. Arbenz sebelumnya menasionalisasi perusahaan AS, United Fruit Company, yang memiliki ikatan erat dengan elit penguasa AS. Untuk membenarkan tindakannya, Washington menyatakan Guatemala saat itu terancam serbuan dari Uni Soviet. Suatu hal yang tidak masuk akal karena Uni Soviet tidak memperlihatkan minat terhadap negeri itu, dan bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik. Masalah sesungguhnya di mata Washington, di samping kepentingan melindungi United Fruit Company, adalah ancaman menyebarnya sosial-demokrasi Guatemala ke negeri-negeri lain di Amerika Latin. Timur Tengah, 1956-58 Doktrin Eisenhower menyatakan bahwa AS, “siap menggunakan kekuatan bersenjatanya untuk membantu” negeri mana pun di Timur Tengah yang “meminta bantuan melawan agresi bersenjata dari negeri mana pun yang berada di bawah kontrol komunisme internasional.” Maksud sesungguhnya dari doktrin itu adalah bahwa tak satu pun kekuatan yang akan dibiarkan mendominasi, atau memiliki pengaruh besar di Timur Tengah dan ladang-ladang minyaknya, kecuali Amerika Serikat. Dan siapa pun yang mencobanya, dengan sendirinya adalah “Komunis”. Dengan garis kebijakan ini, AS dua kali berusaha menggulingkan pemerintah di Syria, menggelar show of force pasukan di Mediterania untuk menakut-nakuti gerakan yang menentang pemerintahan pro-AS di Jordania dan Lebanon dengan menempatkan 14.000 tentara di Lebanon. AS juga beberapa kali bersekongkol untuk menggulingkan atau membunuh Nasser di Mesir dan menghancurkan nasionalisme Timur Tengah yang dikembangkannya. Indonesia, 1957-58 Sukarno, seperti Nasser, adalah pemimpin Dunia Ketiga yang tidak disukai oleh AS. Ia dengan tegas memilih netral dalam Perang Dingin dan beberapa kali berkunjung ke Uni Soviet dan Tiongkok. Ia memimpin nasionalisasi perusahaan swasta milik bekas penguasa kolonial Belanda dan menolak menindas Partai Komunis Indonesia yang saat itu memilih jalan legal dan damai, serta mendapat hasil-hasil mengesankan dalam pemilihan umum. Kebijakan semacam itu, di mata AS, akan menyebarkan “pikiran yang salah” bagi pemimpin Dunia Ketiga yang lain. CIA mulai mempengaruhi pemilihan umum dengan uang, merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno, memerasnya dengan sebuah film porno yang palsu, dan bergabung dengan pasukan militer pembangkang untuk melancarkan perang terhadap pemerintah pusat. Namun Soekarno selamat dari semua upaya menghancurkan itu. Guyana, 1953-64 Selama sebelas tahun, Inggris dan AS lagi-lagi berusaha menghalangi seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis untuk menjalankan pemerintahan. Cheddi Jagan adalah seorang pemimpin Dunia Ketiga yang berusaha netral dan independen. Ia dipilih tiga kali dalam pemilihan umum. Walau pandangannya lebih ke kiri dibandingkan Soekarno atau Arbenz, kebijakan pemerintahnya tidak revolusioner. Tapi bagi AS, ia tetap momok yang menakutkan, karena bisa menjadi contoh sukses bagi mereka yang ingin membangun alternatif terhadap kapitalisme. Dengan bermacam taktik – mulai dari melancarkan pemogokan umum, menyebarkan informasi palsu sampai terorisme dengan legitimasi hukum Inggris, Jagan akhirnya berhasil disingkirkan pada 1964. Semuanya dilakukan di bawah perintah langsung John F. Kennedy, mengikuti jejak Eisenhower sebelumnya. Di 1980-an, Guyana menjadi negeri termiskin di dunia. Ekspor utamanya adalah manusia. Vietnam, 1950-73 Petualangan dimulai ketika AS berpihak pada Perancis, bekas penguasa kolonial dan kolaborator Jepang, melawan Ho Chi Minh dan pengikutnya yang bekerjasama dengan tentara sekutu dan menghargai segala dari Amerika. Namun, Ho Chi Minh, adalah orang komunis. Ia menulis sejumlah surat kepada Presiden Truman dan Deplu AS untuk meminta bantuan Amerika untuk mendukung kemerdekaan Vietnam dari Perancis dan menemukan penyelesaian damai bagi negerinya. Semua permintaannya ditolak. Ho Chi Minh menggunakan baris pertama proklamasi Amerika untuk naskah proklamasi negerinya, “Semua orang diciptakan sama. Mereka diberkahi Sang Pencipta dengan…” Tapi semua ini tidak ada artinya bagi Washington. Ho Chi Minh di mata mereka tetaplah seorang komunis. Setelah berperang selama 23 tahun yang berakibat satu juta orang lebih tewas, AS menarik kekuatan militernya dari Vietnam. Kebanyakan orang mengatakan AS kalah dalam perang itu. Tapi penghancuran yang mereka lakukan dengan menyebar racun di tanah dan gen manusia yang akan mendekam selama sekian generasi, Washington berhasil mencapai sasaran utamanya: mencegah munculnya sebuah alternatif pembangunan di Asia. Kamboja, 1955-73 Pangeran Sihanouk adalah salah satu tokoh lain yang tidak mau menjadi antek Amerika. Setelah bertahun-tahun pemerintahan Nixon/Kissinger menyerang pemerintahannya, termasuk merencanakan pembunuhan atas dirinya dan menghujani negeri itu dengan bom di 1969-70, Washington akhirnya berhasil menggulingkan Sihanouk dalam kudeta di 1970. Kudeta itu memberi peluang bagi Pol Pot dan Khmer Merah memasuki gelanggang. Lima tahun kemudian mereka berhasil merebut kekuasaan. Tapi pemboman yang dilakukan AS selama lima tahun telah menghancurkan ekonomi tradisional Kamboja untuk selamanya. Kebijakan Khmer Merah justru menambah kesengsaraan bagi rakyat di negeri yang dirundung malang ini. Dan ironisnya, AS mendukung Pol Pot secara militer maupun diplomatik, setelah Khmer Merah dikalahkan Vietnam. Kongo, 1960-65 Pada Juni 1960, Patrice Lumumba menjadi perdana menteri pertama Kongo setelah merebut kemerdekaan dari Belgia. Tapi Belgia mempertahankan kekuasaannya di propinsi Katanga yang kaya akan mineral. Para pejabat penting dalam pemerintahan Eisenhower memiliki hubungan erat dengan perusahaan-perusahaan yang menguasainya. Dalam upacara kemerdekaan, di hadapan sejumlah tamu asing, Lumumba menyerukan pembebasan politik dan ekonomi bagi negerinya, dan membuat daftar ketidakadilan yang dialami rakyat setempat di tangan penguasa kolonial. Bagi AS, pidato itu cukup sebagai bukti bahwa Lumumba adalah seorang “Komunis”. Sebelas hari kemudian, propinsi Katanga memisahkan diri dan September Lumumba dipecat oleh presiden atas anjuran AS. Januari 1961 ia dibunuh atas permintaan langsung Dwight Eisenhower. Setelah itu Kongo, yang diubah menjadi Zaire, dilanda perang saudara selama bertahun-tahun, yang membawa Mobutu Sese Seko ke puncak kekuasaan. Mobutu bukan orang asing bagi CIA. Ia berkuasa selama lebih dari 30 tahun, dengan tingkat korupsi dan kekejaman yang mengerikan, bahkan bagi para pendukungnya di CIA. Rakyat hidup dalam kemiskinan yang parah di negeri yang kaya akan sumberdaya alam, sementara Mobutu menjadi seorang multimilyuner. Brasil, 1961-64 Presiden João Goulart melalukan kesalahan yang sama seperti pemimpin Dunia Ketiga lainnya. Ia menerapkan politik luar negeri yang independen, membangun hubungan dengan negerinegeri sosialis dan menentang sanksi terhadap Kuba. Pemerintahannya menetapkan hukum yang membatasi jumlah keuntungan yang boleh dibawa perusahaan multinasional keluar dari negerinya. Ia juga menasionalisasi salah satu anak perusahaan ITT dan melancarkan perbaikan di bidang sosial-ekonomi. Jaksa Agung AS Robert Kennedy merasa terganggu karena Goulart membiarkan sejumlah “komunis” memegang posisi penting dalam pemerintahannya. Goulart sendiri sama sekali bukan tokoh radikal. Ia seorang tuan tanah jutawan, dan Katolik taat berkalung medali Bunda Maria di lehernya. Namun, semua itu tidak cukup untuk melindunginya. Pada 1964 ia digulingkan melalui kudeta militer yang melibatkan AS. Sikap resmi pemerintah di Washington waktu itu, “memang disayangkan bahwa demokrasi digulingkan di Brasil… tapi, bagaimanapun, negeri itu berhasil diselamatkan dari ancaman komunisme.” Selama 15 tahun kemudian, rezim militer melembagakan semua ciri yang kemudian dikenal sebagai “model kediktatoran Amerika Latin”: Kongres dibubarkan, oposisi politik ditiadakan sampai nyaris punah, habeas corpus ditiadakan dalam kasus “kejahatan politik”, kritik terhadap presiden dilarang oleh undang-undang, serikat buruh diambilalih oleh agen pemerintah, gerakan protes dihadapi polisi dan militer yang menembaki massa, rumah petani dibakar, para ulama menghadapi represi brutal… penculikan, pasukan pembunuh, dan penyiksaan dalam skala yang mengerikan. Rezim militer menyebut semua itu “program rehabilitas moral” bagi Brasil. Washington mengikuti perkembangan itu dengan gembira. Brasil memutus hubungan dengan Kuba dan menjadi salah satu sekutu terdekat AS di Amerika Latin. Republik Dominika, 1963-66 Pada Februari 1963, Juan Bosch menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis sejak 1924. Ia berhaluan liberal dan anti-komunis, yang menjadi bukti untuk menyangkal dugaan bahwa AS hanya mendukung kediktatoran militer. Sebelum dilantik menjadi presiden ia mendapat perlakuan istimewa di Washington. Bosch teguh pada pendiriannya. Ia menyerukan reformasi agraria, perumahan dengan sewa rendah, nasionalisasi perusahaan, dan membatasi penanaman modal asing yang bersifat eksploitatif, dan kebijakan lainnya yang khas pemimpin liberal Dunia Ketiga. Ia juga sungguhsungguh menegakkan kebebasan sipil: orang Komunis, atau siapa pun yang dicap demikian, dibiarkan bebas kecuali sungguh-sungguh melanggar hukum. Sejumlah pejabat dan anggota kongres AS mulai merasa tidak nyaman dengan rencana-rencana Bosch, dan juga sikapnya yang independen. Reformasi agraria dan nasionalisasi adalah masalah “panas” bagi Washington, yang menurut mereka secara bertahap akan merangkak menuju sosialisme. Sebagian pers AS menuduh Bosch sudah ketularan “penyakit merah”. Pada September, sepatu lars militer berderap dan Bosch digulingkan. Amerika Serikat yang bisa menghalangi kudeta militer di Amerika Latin hanya dengan menunjukkan wajah tidak senang, tidak berbuat apa-apa. Sembilan belas bulan kemudian, pemberontakan terjadi dengan tujuan membawa Bosch yang hidup di pengasingan kembali berkuasa. AS mengirim 23.000 tentara untuk menghancurkan pemberontakan itu. Kuba, sejak 1959 Fidel Castro mulai berkuasa awal 1959. Dewan Keamanan Nasional AS mengadakan pertemuan pada10 Maret 1959. Salah satu agenda pembahasannya adalah kemungkinan mendirikan “pemerintahan lain untuk berkuasa di Kuba.” Setelah itu selama 40 tahun AS melancarkan serangan teroris, pemboman, invasi militer dalam skala penuh, sanksi, embargo, isolasi dan pembunuhan, karena Kuba menjadi ancaman serius dengan menjadi contoh bagi Amerika Latin. Dunia takkan pernah tahu masyarakat apa yang mungkin dibangun Kuba seandainya dibiarkan berkembang bebas, tanpa ancaman senjata dan invasi. Idealisme, visi dan kecakapan berlimpah untuk menjadi model pembangunan yang lain. Tapi kita takkan pernah tahu, dan itulah yang sesungguhnya diinginkan AS. Indonesia, 1965 Setelah perebutan kuasa yang rumit dengan sidik jari AS di mana-mana, Soekarno berhasil digulingkan. Sebagai gantinya muncul Jenderal Soeharto. Pembantaian terjadi terhadap anggota PKI, orang yang dituduh PKI, simpatisan PKI maupun orang yang dituduh berhubungan dengan satu atau lain cara berhubungan dengan komunisme. Suratkabar New York Times menyebutnya, “salah satu pembantaian massal yang paling biadab dalam sejarah politik modern.” Antara setengah sampai satu juta orang diduga terbunuh. Baru kemudian diketahui bahwa kedutaan besar AS menyusun daftar lima ribu “orang Komunis”, dari pimpinan teras sampai kader desa, dan menyerahkannya kepada Angkatan Darat. Daftar itu kemudian dipakai untuk mengejar dan membunuh siapa pun yang tertera di sana. “Sungguh bantuan besar bagi Angkatan Darat. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan mungkin tangan saya juga berlumuran darah,” kata seorang diplomat AS. “Tapi tidak apaapa. Ada kalanya kita harus bersikap keras pada saat yang menentukan.” Chile, 1964-73 Salvador Allende adalah mimpi buruk bagi imperialisme Washington. Tidak ada yang lebih buruk dari melihat seorang Marxis terpilih menjadi presiden, yang menghargai konstitusi dan semakin populer di kalangan rakyat. Kehadirannya mengguncang batu pondasi menara anti-komunis yang dibangun Washington. Doktrin yang dipelihara selama puluhan tahun pun runtuh: bahwa kaum “komunis” yang menang melalui kekerasan dan penipuan, dan mempertahankan kekuasaan dengan teror dan cuci otak. Allende terpilih menjadi presiden 1970, setelah sebelumnya AS terus berupaya menggagalkannya dengan segala cara. CIA dan seluruh mesin politik luar negeri AS melakukan apa saja untuk menggerogoti pemerintahan Allende, khususnya menggalang kemarahan di kalangan militer. Akhirnya pada bulan September 1973, militer menggulingkan pemerintahan kerakyatan dan membunuh Allende. Seluruh negeri ditutup dari dunia luar selama seminggu. Tank dan serdadu berkeliaran di jalan-jalan kota, stadion olahraga penuh dengan orang yang menunggu eksekusi dan tubuh-tubuh para korban ditumpuk di pinggir jalan atau mengapung di sungai. Serdadu menyerang perempuan yang mengenakan celana panjang dengan merobek bagian kakinya, sambil berteriak “Di Chile perempuan pakai rok!” Kaum miskin kembali ke kesengsaraan, dan penguasa di Washington serta lembaga keuangan internasional kembali menikmati aliran uang dari Chile. Lebih dari tiga ribu orang dieksekusi, sementara ribuan lainnya disiksa atau lenyap tak berbekas. Yunani, 1964-74 Kudeta militer terjadi pada April 1967, hanya dua hari sebelum kampanye pemilihan umum dimulai, yang hampir pasti akan membawa pemimpin liberal George Papandreou kembali menjadi perdana menteri. Ia terpilih bulan Februari 1964 dengan dukungan terbesar dalam sejarah pemilihan umum Yunani modern. Gerakan untuk menggulingkannya pun dimulai, sebagai kerjasama militer Yunani dan pasukan serta dinas intelijen AS yang ditempatkan di sana. Kudeta 1967 itu diikuti pemberlakuan keadaan darurat perang: sensor, penangkapan, pemukulan, penyiksaan dan pembunuhan membawa delapan ribu korban dalam bulan pertama. Semua ini dilakukan seiring dengan kampanye “menyelamatkan bangsa dari ancaman Komunis”. Semua pengaruh yang dianggap merusak moral dan subversif menjadi sasaran, termasuk rok pendek, rambut panjang dan suratkabar asing. Di bawah kekuasaan militer kaum muda diwajibkan pergi ke gereja. Tapi penyiksaan adalah yang paling menakutkan dalam mimpi buruk Yunani selama tujuh tahun itu. James Becket, seorang pengacara Amerika yang dikirim ke Yunani oleh Amnesty International, pada Desember 1969 menulis bahwa “perkiraan kasar, tidak kurang dari dua ribu” orang yang disiksa, dengan cara-cara yang sangat mengerikan, seringkali dengan peralatan yang disediakan AS. Becket memberi laporan berikut: Ratusan tahanan di penjara harus mendengarkan pidato Inspektur Basil Lambrou, yang duduk di belakang mejanya sambil yang memperlihatkan simbol merah, putih biru dari barang bantuan AS. Ia berusaha memperlihatkan bahwa perlawanan mereka sia-sia saja. “Kalian bodoh berpikir bisa melakukan apa saja. Dunia ini terbagi dua. Ada komunis di satu pihak dan dunia bebas di sisi lain. Rusia dan Amerika, tidak ada yang lain. Nah, kita ini apa? Amerika. Di belakang saya ada pemerintah, di belakang pemerintah ada NATO, dan di belakang NATO ada Amerika. Jadi kalian takkan menang melawan kami. Kami ini adalah Amerika.” George Papandreou sama sekali bukan seorang yang radikal. Ia seorang liberal yang juga antikomunis. Namun putranya, Andreas yang akan mewarisi kekuasaannya, sedikit lebih ke kiri dari ayahnya dan tidak pernah menyembunyikan keinginan membawa Yunani keluar dari Perang Dingin. Timor Lorosae, 1975-1999 Indonesia menginvasi Timor Lorosae yang baru memproklamasikan kemerdekaannya dari Portugal. Invasi dilancarkan tepat sehari setelah Presiden AS Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger meninggalkan Indonesia. Mereka mengizinkan Soeharto menggunakan senjata buatan AS dalam invasi itu, padahal menurut undang-undang AS sendiri, senjata itu tidak boleh dipakai untuk menyerang. Namun Indonesia adalah alat Washington yang paling berharga di Asia Tenggara. Amnesty International memperkirakan pada 1989, pasukan Indonesia yang mencaplok Timor Lorosae dengan kekerasan, membunuh sekitar 200.000 dari 600.000 sampai 700.000 penduduk. AS dengan konsisten mendukung klaim Indonesia atas Timor Lorosae (tidak seperti PBB dan Uni Eropa), dan menganggap remeh pembantaian yang terjadi. Pada saat bersamaan AS terus menyediakan perlengkapan dan pelatihan bagi militer Indonesia untuk melancarkan tugas mereka. Nikaragua, 1978-89 Ketika gerakan Sandinista berhasil menggulingkan kediktatoran Somoza pada 1978, AS langsung melihat bayangan munculnya “Kuba yang lain” di wilayah Amerika Tengah. Di masa pemerintahan Carter, usaha untuk menyabot revolusi itu dilakukan melalui diplomasi dan tekanan ekonomi. Tapi ketika Reagan mulai berkuasa, metode kekerasanlah yang digunakan. Selama delapan tahun, rakyat Nikaragua diserang oleh pasukan yang diasuh Washington, “gerilyawan” Kontra. Anggotanya direkrut dari jajaran Garda Nasional yang terkenal kejam di zaman Somoza dan para pendukung kediktatoran lainnya. Mereka melancarkan perang total untuk menghancurkan semua program sosial dan ekonomi progresif pemerintahan Sandinista, dengan membakar sekolah dan klinik medis, perkosaan, penyiksaan, meledakkan pelabuhan, pemboman dan berondongan peluru. Ronald Reagan menyebut mereka “pejuang pembebasan”. Grenada, 1979-84 Apa yang membuat negara besar seperti AS melakukan invasi ke negeri dengan penduduk 110.000, jika bukan ketakutannya akan komunisme. Maurice Bishop dan pengikutnya merebut kekuasaan pada 1979, dan sekalipun kebijakan mereka tidak revolusioner seperti halnya Kuba, Washington lagi-lagi didorong ketakutan akan munculnya “Kuba baru”, terutama ketika para pemimpin Grenada mendapat sambutan hangat di negeri-negeri Amerika Tengah. Taktik destabiliasi terhadap pemerintahan Bishop dimulai segera setelah mereka berkuasa dan terus berlanjut sampai tahun 1983. Pada Oktober 1983 AS melakukan invasi dan tidak mendapat perlawanan berarti, walau 135 prajuritnya terbunuh atau terluka. Sekitar 400 orang Grenada menjadi korban bersama 84 orang Kuba, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Akhir 1984 berlangsung pemilu yang dimenangkan oleh calon yang didukung pemerintahan Reagan. Setahun kemudian, sebuah organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa polisi dan pasukan anti-pemberontakan Grenada yang dilatih AS semakin terkenal karena kekejaman, penangkapan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Hak-hak sipil pun semakin digerogoti. April 1989, pemerintah mengeluarkan daftar lebih dari 80 buku yang dilarang masuk. Empat bulan kemudian, perdana menteri membekukan parlemen. Libya, 1981-89 Libya menolak menjadi antek Washington di Timur Tengah. Pemimpinnya, Muammar elQaddafi, terlalu angkuh di mata Washington dan karena itu harus dihukum. Pesawat AS menembak jatuh dua pesawat Libya yang terbang di atas wilayah mereka sendiri. AS juga menjatuhkan bom di negeri itu, yang menewaskan 40 orang, termasuk putri Qaddafi. Di samping itu ada berbagai upaya untuk membunuh pemimpin itu, operasi untuk menggulingkan kekuasaannya, dan kampanye disinformasi, sanksi ekonomi dan menuduh Libya berada di balik peledakan pesawat PanAm 103 tanpa bukti cukup. Panama, 1989 Pesawat pembom AS kembali beraksi. Bulan Desember 1989 sebuah perkampungan di Panama City musnah dan 1.500 orang kehilangan rumah mereka. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari melawan pasukan Panama, dan laporan resmi menyatakan 500-an orang tewas. Sumber lain dengan bukti-bukti cukup menyatakan ribuan orang yang tewas sementara sekitar tiga ribu orang lainnya luka-luka. 23 orang Amerika tewas sementara 324 luka-luka. Dalam wawancara dengan Presiden Bush, seorang wartawan bertanya: “Apakah memang pantas mengirim orang untuk menemui ajalnya seperti itu, hanya untuk menangkap Noriega?” Bush menjawab, “Saya tahu setiap nyawa itu berharga. Tapi saya pikir, semua itu pantas terjadi.” Manuel Noriega selama bertahun-tahun menjadi sekutu dan informan AS sampai akhirnya dirasa tidak berguna lagi. Tapi penangkapan dirinya bukan satu-satunya alasan untuk menyerang. Bush juga ingin mengirim pesan kepada rakyat Nikaragua, yang akan mengikuti pemilihan umum dalam waktu dua bulan, bahwa mereka akan bernasib sama jika kembali memilih Sandinista. Bush juga ingin menunjukkan otot militernya kepada Kongres bahwa AS tetap perlu pasukan siap-tempur yang besar sekalipun Uni Soviet sudah bubar. Dalam penjelasan resminya, Washington mengatakan Noriega ditangkap karena terlibat perdagangan obat bius, sesuatu yang sudah diketahui oleh AS sejak lama dan tidak pernah dipersoalkan sebelumnya. Irak, 1990-an Selama 40 siang dan malam, AS membom salah satu bangsa termaju di Timur Tengah, menghancurkan baik ibukota lama maupun baru. Sekitar 85 juta kilogram bom menghujani rakyat Irak dan menjadi serangan udara paling terpusat dalam sejarah dunia. Senjata uranium pun dijatuhkan, yang membakar manusia, menyebabkan kanker, dan meledakkan kilang minyak serta gudang senjata kimia dan biologi. Pencemaran udara akibat pemboman itu luar biasa, dan mungkin belum pernah terjadi di mana pun juga. Banyak serdadu yang sengaja dipendam hidup-hidup, infrastruktur hancur dengan akibat luar biasa bagi kesehatan. Sanksi ekonomi masih berlanjut yang membuat penderitaan semakin parah; mungkin sekitar satu juta anak meninggal karena serangan ini. Irak sebelumnya adalah kekuatan militer terbesar di jazirah Arab. Dan bagi Washington ini adalah kejahatan. Noam Chomsky pernah menulis, “Telah menjadi doktrin dalam kebijakan luar negeri AS sejak 1940-an bahwa sumber energi yang tiada bandingannya di wilayah Teluk harus dikuasai oleh AS dan negara sekutunya. Tidak satu pun kekuatan setempat yang independen akan dibiarkan tumbuh dan berpengaruh dalam penanganan produksi serta penetapan harga minyak.” Afghanistan, 1979-92 AS mengucurkan dana milyaran dolar untuk membiayai perang menentang pemerintahan berkuasa yang didukung Uni Soviet. Sebelumnya, operasi CIA terus memancing intervensi Uni Soviet yang akhirnya memang dilakukan. AS akhirnya keluar sebagai pemenang, dan kaum perempuan seperti kebanyakan rakyat Afghanistan ada di pihak yang kalah. Lebih dari satu juta orang tewas, tiga juta cacat seumur hidup dan lima juta orang mengungsi, sama dengan separuh jumlah penduduknya. El Salvador, 1980-92 Para pembangkang El Salvador selalu berusaha bekerja di dalam sistem. Tapi dengan dukungan AS, pemerintah terus bermain curang dalam pemilihan umum dan membunuh ratusan orang yang terlibat dalam aksi protes dan pemogokan. Di 1980, para pembangkang mulai angkat senjata dan perang saudara pun terjadi. Secara resmi kehadiran militer di AS di El Salvador terbatas sebagai penasehat. Tapi dalam kenyataan, personel militer AS dan CIA memainkan peran aktif. Sekitar 20 orang AS tewas atau terluka karena pesawat atau helikopter mereka ditembak jatuh ketika sedang melakukan serangan dan terbang di atas daerah pertempuran. Di samping itu ada bukti cukup bahwa AS juga terlibat dalam pertempuran di darat. Perang itu secara resmi berakhir tahun 1992 setelah 75.000 orang tewas dan departemen keuangan AS mengucurkan enam milyar dolar. Jalan bagi perubahan sosial mendasar semakin tertutup. Negeri itu tetap ada di tangan segelintir orang kaya. Orang miskin tetap saja miskin, dan para pembangkang tetap menghadapi pasukan pembunuh di mana-mana. Haiti, 1987-94 Selama 30 tahun kediktatoran keluarga Duvalier berkuasa dengan dukungan penuh pemerintah AS. Jean Baptiste Aristide yang progresif kemudian terpilih menjadi presiden, tapi kembali digulingkan pada 1991 melalui kudeta militer pengikut Duvalier. Washington kemudian bersedia menaikkan kembali Aristide dengan syarat ia tidak akan membuat kebijakan yang menguntungkan orang miskin dan merugikan orang kaya, dan bahwa ia akan berpegang teguh pada doktrin pasar bebas. Yugoslavia, 1999 Hujan bom AS menyeret negeri itu kembali ke zaman pra-industri. Tapi penguasa di Washington mengklaim intervensi itu dilakukan atas dasar “kemanusiaan”. Mudah-mudahan penjelasan di atas bisa membantu kita memahami apa maksud sesungguhnya. 1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Surat Robert S. McNamara tentang Bantuan Militer kepada Indonesia pada 1965
Robert S. McNamara, Menteri Pertahanan AS dari 1964 - 1968, pada masa pemerintahan J. F. Kennedy dan L. B. Johnson
RAHASIA KEMENTERIAN PERTAHANAN WASHINGTON 1 Maret 1967 MEMORANDUM UNTUK PRESIDEN SUBJEK: Efektifitas Bantuan militer AS untuk Indonesia Pengambilalihan kekuasaan Kepresidenan oleh Jenderal Suharto menegaskan perubahan signifikan dalam orientasi politik Indonesia yang telah terjadi selama enam belas bulan terakhir. Perubahan ini dimulai pada 1 Oktober 1965, ketika Angkatan Darat Indonesia, yang dipimpin Jenderal Suharto, menghentikan kudeta yang digerakkan kaum Komunis, dan kemudian berlanjut dengan memusnahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang beranggotakan tiga juta orang sebagai organisasi politik yang efektif. Setelah menghancurkan PKI, Angkatan Darat beralih ke pekerjaan yang lebih sulit, yaitu melucuti kekuasaan politik Presiden Soekarno dan mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia supaya meninggalkan hubungan erat dengan Peking dan menyesuaikan diri dengan negara-negara tetangganya dan Amerika Serikat. Proses ini tampaknya sekarang telah memasuki tahap akhir; Angkatan Darat Indonesia hampir memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pemerintahan Indonesia. Saya percaya bahwa Program Bantuan Militer (MAP) kita untuk Indonesia selama beberapa tahun terakhir memberikan sumbangan yang berarti bagi pembentukan orientasi Angkatan Darat yang anti-komunis, pro-AS, dan mendorong institusi ini untuk bergerak menentang PKI ketika kesempatan itu dihadirkan. Bahwa PKI sesungguhnya sangat menyadari tentangan naluriah ini di dalam tubuh Angkatan Darat diperlihatkan dengan kenyataan bahwa lima dari enam jenderal yang dibunuh PKI pada 1 Oktober yang menentukan itu telah menerima pelatihan di sekolah-sekolah Angkatan Darat AS dan dikenal sebagai para sahabat Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, setelah Angkatan Darat menumpas pemberontakan tersebut, tugas-tugas utama diberikan kepada para perwira yang pernah dilatih di AS. Suharto sendiri tidak pernah dilatih di AS, tetapi tigabelas anggota terpenting dalam jajaran staf-nya, kelompok yang sekarang memerintah Indonesia, menjalani pelatihan di Amerika Serikat dibawah MAP. Menurut penilaian saya, keputusan kita untuk menanam modal sekitar US$ 5 juta untuk memberangkatkan 2.100 anggota militer Indonesia mengikuti pelatihan di Amerika Serikat, dan melanjutkan program, bahkan selama tahun-tahun suram 1963-65 ketika Sukarno mengadakan konfrontasi terhadap Malaysia dan bekerja sangat erat dengan Peking, merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan orientasi elit politik Indonesia yang baru. Jumlah keseluruhan Program Bantuan Militer kita untuk Indonesia dari 1950 hingga 1965 sebesar US$63,2 juta. Sekitar US$59 juta telah diberikan pada 1959-1965. Dua pertiganya (US $40 juta) disalurkan ke Angkatan Darat, termasuk lebih dari 100.000 senjata ringan, 2.000 truk dan kendaraan lainnya, dan peralatan komunikasi taktis. Saat Sukarno memulai konfrontasi terhadap Malaysia pada 1963, kita menghilangkan butir program yang dianggap akan mendukung kemampuan ofensif Indonesia, namun kita tetap menyediakan senjata ringan untuk mendukung kemampuan pengamanan internal Angkatan Darat. Pada 1962 kita memperluas Program Bantuan Militer dengan memasukkan perlengkapan permesinan untuk program aksi masyarakat yang dijalankan Angkatan Darat. Peralatan senilai total US$ 3 juta telah dikirimkan antara 1962 dan 1964. Program aksi masyarakat merupakan buah pikiran Jenderal Nasution (sekarang Ketua MPRS) dan Jenderal Yani (salah satu Jenderal yang dibunuh oleh kaum Komunis pada Oktober 1965). Kedua jenderal ini percaya bahwa Angkatan Darat membutuhkan program yang dapat memperbaiki citranya di mata rakyat Indonesia ketika berhadapan dengan PKI. Aspek lain program aksi masyarakat ini adalah mengirimkan perwira-perwira muda cemerlang dari Angkatan Darat ke Amerika Serikat untuk mengikuti latihan (di Harvard, Syracuse, dan beberapa lembaga lain) yang mempersiapkan mereka menjalankan tanggungjawab manajemen tingkat tinggi. Latihan ini ternyata sangat bernilai ketika Angkatan Darat mengambil kendali pemerintahan. Kita menangguhkan pengiriman peralatan baru ke Indonesia pada September 1964. Pada Maret 1965 kita membatalkan sisa bantuan program, kecuali pelatihan bagi orang Indonesia yang sudah berada di Amerika Serikat. Alokasi sejumlah US$ 23 juta untuk peralatan, jasa, dan pelatihan dibatalkan, dan kemudian dana tersebut ditarik kembali. Kendati demikian, kita mempertahankan hubungan dekat dengan pimpinan Angkatan Darat Indonesia melalui ataseatase militer kita dan Kelompok Penghubung Pertahanan, yang tetap dijaga keberadaannya dengan jumlah staf minimum, bahkan setelah dihentikannya Program Bantuan Militer. Pada September 1966, saat Angkatan Darat telah mengisolasi Sukarno dan secara resmi mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia, kita memulihkan program pelatihan militer untuk para perwira militer (dengan biaya US$ 400.000 untuk tahun fiskal 1967). Tekanan utama dalam pelatihan ini pada peningkatan kemampuan aksi masyarakat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selama seminggu terakhir ini, kita memutuskan untuk menambah dana Program Bantuan Militer untuk tahun fiskal 67 sebesar US$ 2 juta agar tersedia suku cadang untuk peralatan permesinan yang dikirim sebelumnya dan juga beberapa peralatan baru— seluruhnya untuk program aksi masyarakat. Pada tahun fiskal 68 kita merencanakan untuk memberi Indonesia sebesar US$ 6 juta untuk Program Bantuan Militer, terutama untuk mendukung program aksi masyarakat. Agaknya terlalu membesar-besarkan apabila kita mengklaim bahwa bantuan militer dan pelatihan yang kita berikan sepenuhnya berpengaruh terhadap pembentukan orientasi antikomunis Angkatan Darat Indonesia, atau bahkan menjadi faktor utama yang menyebabkan Angkatan Darat Indonesia menentang PKI dan membuat Indonesia meninggalkan orientasi proPeking nya. Namun, saya sangat percaya bahwa program ini, seiring dengan simpati berkelanjutan dan dukungan bagi Angkatan Darat, mendorong para pemimpinnya untuk percaya bahwa mereka bisa memperhitungkan dukungan AS saat mereka menentang PKI dan, kemudian, menghadapi Sukarno. Kebijakan kita yang tegas di Vietnam juga telah berperan dalam membentuk sikap Angkatan Darat yang menguntungkan bagi tujuan kita di Asia Tenggara. Satu setengah tahun yang lalu, Indonesia merupakan ancaman yang menakutkan bagi AS dan Dunia Bebas. Sekarang, harapan itu secara dramatis berubah ke arah yang lebih baik. Pemerintahan Jenderal Soeharto mengemudikan Indonesia kembali ke sosok yang menjanjikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Robert S. McNamara 1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Memerangi Terorisme, Menggerogoti Demokrasi di Indonesia Diambil dari X-URL: http://www.fpif.org/commentary/0109inddem_body.html
John Gershman Pihak yang segera beruntung dari penekanan prioritas pemerintahan Presiden Bush pada perang terhadap terorisme mungkin adalah militer Indonesia. Kekuatan militer inilah yang bermain di belakang penghancuran Timor Lorosae pada 1999 dan berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Papua Barat dan Aceh, begitu juga di daerah-daerah lain di kepulauan Indonesia. Kemungkinan ini muncul dari hasil bincang-bincang antara Presiden Megawati dan Presiden Bush minggu lalu di Gedung Putih. Perbincangan itu sendiri tujuannya untuk melibatkan Indonesia, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dalam peperangan melawan terorisme. Presiden Megawati Sukarnoputri bertemu dengan Presiden George W. Bush minggu ini, dan ia merupakan kepala negara pertama yang mengunjungi Amerika Serikat sejak serangan teroris pada 11 September. Presiden Bush sudah mengundang Megawati sejak akhir Juli lalu setelah dia menduduki jabatan presiden, mengikuti pemberhentian Abdurrahman Wahid. Pertemuan kedua kepala negara ini banyak mengungkapkan bagaimana pemerintahan Bush berniat mengkonsolidasikan koalisi internasional yang baru terbentuk untuk melawan terorisme, terutama di antara negara-negara berkembang. Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya ini karena posisinya sebagai negeri demokratik berpenduduk Muslim terbanyak dan meningkatnya peran politik organisasi-organisasi Islam sejak runtuhnya rejim Orde Baru pada 1998. Ada pula dugaan bahwa beberapa kelompok Islam radikal di Indonesia berkaitan dengan organisasi Osama bin Laden, Al Qaeda. Strategi Bush tampaknya merupakan campuran antara bantuan dan hubungan perdagangan yang dikombinasikan dengan penguatan hubungan bilateral antar institusi militer. Komitmen Presiden Bush di bidang ekonomi melibatkan: paling tidak $130 juta dalam bentuk bantuan bilateral untuk tahun fiskal 2002 (terutama untuk reformasi hukum), $10 juta untuk bantuan kepada pengungsi internal (IDPs), $5 juta untuk upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi di propinsi Aceh yang hancur lebur oleh pertempuran, $2 juta untuk membantu pemulangan pengungsi di Nusa Tenggara Timur, dan $10 juta untuk pelatihan polisi. Selanjutnya, pemerintahan Bush akan menyiapkan $100 juta keuntungan tambahan di bawah peraturan Generalized System of Preferences (GSP) yang memungkinkan 11 produk tambahan memasuki pasar AS tanpa pajak. Akhirnya, Presiden Bush mengumumkan bahwa tiga badan keuangan perdagangan – the ExportImport Bank, Perusahaan Investasi Swasta Luar Negeri (OPIC), dan Badan Perdagangan dan Pembangunan AS – telah mengembangkan ikhtiar gabungan di bidang keuangan dan perdagangan untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Tiga badan ini akan bertanggungjawab untuk menyediakan sebanyak $400 juta untuk mendorong perdagangan dan investasi di Indonesia, terutama di sektor gas dan minyak bumi. Upaya-upaya di bidang ekonomi ini boleh dikatakan tak terlalu besar, dan kebijakan makroekonomi Indonesia masih tetap di bawah pengawasan Dana Moneter Internasional (IMF). Penekanan pada reformasi hukum paling tidak dinyatakan sebagai target yang penting. Sebuah Laporan Survey terbaru tentang Persepsi Warga Negara terhadap Sektor Keadilan di Indonesia (Survey Report on Citizens’ Perceptions Of The Indonesian Justice Sector) dari Asia Foundation dan AC Nielsen (http://www.asiafoundation.org/pdf/IndoLaw.pdf) mengungkapkan beberapa temuan yang menggelisahkan tentang sebuah negeri yang berupaya membangun institusi untuk sistem demokrasi yang rapuh. Lebih dari separuh orang dewasa di Indonesia tidak bisa memberikan satu contoh pun tentang hak yang mereka miliki. Lebih dari 60% responden menyatakan polisi mudah saja meminta uang suap untuk mengambil tindakan terhadap apa pun, sementara 30%-35% berpikir bahwa pengadilan hanyalah untuk mereka yang kaya dan merupakan tempat “berbahaya” untuk mencari keadilan. Namun, bahayanya adalah, upaya menegakkan hukum, menjalankan reformasi hukum, dan menghormati hak-hak asasi manusia akan digerogoti oleh meningkatnya dukungan untuk dan kerjasama pemerintah AS dengan militer Indonesia. Masalah utama dalam agenda pemerintah AS di pertemuan tersebut adalah hubungan bilateral militer. Beberapa laporan terbaru dari Dewan Hubungan Luar Negeri dan Rand Corporation, keduanya dipublikasikan beberapa saat sebelum tragedi 11 September, menyarankan supaya pemerintahan Bush memperkuat kerjasama dengan Indonesia secara umum dan militer Indonesia secara khusus. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memerangi peningkatan pengaruh kelompok-kelompok Islam radikal, sekaligus mempersiapkan pembangunan basis pertahanan yang kuat untuk menghadapi Republik Rakyat Cina di wilayah Asia Tenggara. Laporan Dewan Hubungan Internasional, Amerika Serikat dan Asia Tenggara: Agenda Kebijakan untuk Pemerintahan Baru ini patut diperhatikan karena ia dirancang oleh Dov Zakheim, perancang Pentagon pada masa pemerintahan Reagan, yang sekarang bekerja di Pentagon [Gedung Pertahanan Militer AS, ed.]. Keterlibatan militer Indonesia dalam pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan pembantaian di Timor Lorosae segera setelah pelaksanaan referendum untuk kemerdekaan pada 1999 telah mendorong Kongres AS [parlemen, ed.] untuk mempertegas pembatasan yang sudah ada dalam hal kerjasama bilateral militer. Undang-undang yang disahkan Kongres saat itu membatasi penjualan senjata dan pelatihan militer sampai sejumlah kriteria dipenuhi, termasuk peningkatan kontrol sipil terhadap kegiatan militer, transparansi lebih luas dalam hal pembiayaan militer, dan tanggung-gugat pejabat militer yang menyepakati tindakan pelanggaran HAM. Pejabat Sekretariat Negara dalam pemerintahan Bush mengakui bahwa militer Indonesia masih harus memenuhi kriteria dasar tersebut, dan dalam banyak hal, situasi di Indonesia sebenarnya memburuk. Misalnya, beberapa perwira yang memegang posisi pemberi komando di Timor Lorosae pada 1999 bukan saja belum dibawa ke pengadilan, tetapi justru mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Selain itu, ada problem serius dengan transparansi anggaran militer. Sejumlah ahli memperkirakan bahwa hanya 25-30% anggaran militer didapatkan dari dana pemerintah, sedangkan sisanya diperoleh melalui “pemajakan” terhadap pengerukan sumber daya alam, uang suap, dan bentuk-bentuk pembiayaan “informal” lainnya. Pelanggaran HAM semakin meningkat di Aceh dan Papua Barat, wilayah-wilayah dimana gerakan yang menuntut pemisahan kedaulatan cukup kuat. Namun, pemerintahan Bush mengumumkan kemarin beberapa keringanan dalam pembatasan terhadap hubungan bilateral di bidang militer antara Indonesia dan Amerika. Kendati pihak eksekutif belum meminta Kongres AS untuk mencabut pembatasan terhadap penjualan senjata dan pelatihan, pemerintahan Bush sudah mengambil kebijakan terpisah di bagian lain. Walaupun ada bukti terus-menerus bahwa militer masih bisa bertindak dengan kekebalan hukum (impunity), Presiden Bush dan Megawati bersepakat untuk: ●
●
●
●
memperluas hubungan sederhana dan memulihkan pertemuan teratur antara militer Indonesia dan AS untuk mendukung upaya Indonesia melaksanakan reformasi dan profesionalisasi militer. Kegiatan-kegiatan yang berlibat di dalamnya antara lain partisipasi Indonesia dalam berbagai konperensi, latihan multilateral, pertukaran pendapat dalam soal-soal seperti reformasi militer, hukum militer, investigasi, pembiayaan dan transparansi anggaran, termasuk pula operasi gabungan untuk penanggulangan masalah kemanusiaan dan pemberian bantuan kemanusiaan. menyelenggarakan Dialog Keamanan secara bilateral di bawah pengawasan menteri pertahanan non-militer dari kedua negara untuk mendorong “peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam hal pertahanan dan keamanan di Indonesia”. meminta Kongres AS menganggarkan $400.000 untuk mendidik masyarakat sipil di Indonesia tentang masalah-masalah pertahanan melalui program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional yang diperluas [Expanded International Military Education and Training, E-IMET]. mencabut embargo terhadap penjualan komersial barang-barang pertahanan yang tak mematikan ke Indonesia, dengan syarat setiap permintaan individual harus dipelajari kasus demi kasus, sesuai dengan praktek standar yang diberlakukan di Amerika.
Pembenaran untuk peningkatan hubungan militer ini diajukan oleh Rand Corporation [sebuah lembaga konsultan ternama di AS, ed.], yang berpendapat bahwa “hubungan dengan militer Indonesia akan meningkatkan kemampuan Amerika Serikat untuk mempromosikan model demokratik profesionalisme militer di Indonesia”. Klaim ini jelas bermasalah – jika keterlibatan AS dengan militer Indonesia memang begitu kondusif untuk tumbuhnya profesionalisme, apa hasil hubungan dekat mereka selama tiga dekade di bawah pemerintahan Orde Barunya Soeharto? Seperti yang dinyatakan dalam laporan International Crisis Group pada Juli 2001, “hubungan militer belum pernah efektif sampai saat ini dalam menghasilkan militer Indonesia yang memenuhi standar kekuatan yang modern, profesional, di bawah kendali orang sipil atau pun mendorong stabilitas jangka panjang di Indonesia.” Catatan HAM untuk Megawati pun mengandung kelemahan. Sebagai seorang nasionalis yang gigih, ia menentang referendum di Timor Lorosae yang membawa negeri itu ke kemerdekaannya. Ia berhubungan cukup dekat dengan militer, sambil memberi tempat pada empat jendral purnawirawan dalam kabinetnya. Ia sudah mengambil beberapa tindakan permulaan untuk menjawab tuntutan penentuan nasib sendiri dari penduduk Aceh dan Papua Barat. Salah satu undang-undang yang sudah ditandatangani Megawati sebagai presiden adalah Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan undang-undang serupa untuk Papua Barat sedang dipertimbangkan oleh parlemen Indonesia. Kedua usulan perundang-undangan itu dipandang tidak memadai di wilayah masing-masing, dan represi meningkat sejak Megawati menjadi presiden. Sebelum 11 September paling tidak usulan untuk memperkuat kembali hubungan militer Indonesia-AS ditentang oleh beberapa tokoh kunci di Kongres dan kelompok-kelompok HAM karena terus berlangsungnya pelanggaran HAM oleh militer Indonesia, dan bertahannya kekebalan hukum di kalangan pejabat tinggi militer Indonesia yang diduga bersepakat dengan pelanggaran HAM di Timor Lorosae dan di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya sekarang apakah semangat kerjasama antar dua negara yang menandai periode sejak serangan teroris ke AS tersebut akan meluas sampai ke upaya pemerintahan Bush memperkuat militer yang bisa menggerogoti nilai-nilai utama kebebasan dan demokrasi? Padahal perang terhadap terorisme ini konon untuk menegakkan kebebasan dan demokrasi. John Gershman <[email protected]> adalah salah satu direktur program Hubungan Global di organisasi Interhemispheric Resource Center dan editor Asia/Pacific untuk Foreign Policy in Focus.
1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Seabad Perlawanan di Filipina Dominasi AS di Filipina dipicu oleh perang melawan Spanyol sejak akhir abad ke-19. Sementara pemerintah AS mengobarkan pembebasan Filipina dari penjajahan Spanyol, rakyat melihatnya sebagai invasi baru untuk mengganti penguasa yang satu dengan yang lain. Sejak pergantian abad, ketika AS berhasil mengalahkan Spanyol dan mengambilalih kekuasaan, gerak perlawanan pun dimulai dan mencatat nama-nama seperti Bonifacio dan Hukbalahap. Di 1970-an, gerakan menentang intervensi AS semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya perlawanan terhadap kediktatoran Marcos. Seiring dengan kejatuhan Marcos, kesempatan untuk menghimpun kekuatan yang lebih luas semakin terbuka, dan menjadikan kehadiran pangkalan AS di Subic Bay dan Clark sebagai sasaran. Di 1986 gerakan itu mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan referendum tentang kehadiran pangkalan. Sekitar 25 juta orang dengan hak pilih memberikan suara dan hasilnya 76% di antaranya menolak pangkalan militer AS. Mereka juga mendukung pasal-pasal yang menjunjung perdamaian dan pernyataan Filipina sebagai daerah bebas nuklir dalam konstitusi yang baru. Momentum berikutnya adalah perundingan pemerintah AS dan Senat Filipina untuk memperpanjang kontrak pangkalan di negeri tersebut pada 1991. Sebelumnya tidak pernah ada kesulitan apa pun karena Senat Filipina sangat konservatif dan mendukung segala yang diinginkan AS dari mereka. Tapi situasi sudah berubah. Demonstrasi besar terjadi di manamana. Dalam waktu beberapa hari gerakan perdamaian berhasil menghimpun ratusan ribu orang di depan gedung Senat Filipina untuk menentang perpanjangan kontrak tersebut. Di bawah desakan yang hebat, akhirnya Senat memutuskan untuk menolak perpanjangan itu. Pemerintah Filipina memberi waktu satu tahun kepada AS untuk menarik puluhan ribu tentara beserta senjata dan peralatannya. Simbol kekuasaan AS di wilayah itu pun ditutup. Semua itu tentu membuat pemerintah AS yang selalu menganggap para penguasa di Filipina sebagai adik kami yang berkulit coklat [our brown little brothers], jengkel. Skema baru pun diluncurkan, yakni Perjanjian Kunjungan Pasukan [VFA, Visiting Forces Agreement], yang mengatur “kunjungan” pasukan AS ke Filipina lengkap dengan segala hak istimewa yang mereka peroleh di masa lalu. Seorang pejabat AS dalam laporan rahasianya tanpa ragu mengatakan, “kesepakatan itu terutama untuk melayani dan melindungi AS. Pentagon dan Kamp Aguinaldo akan membungkus itu dengan menyebut “keuntungan” bagi Angkatan Bersenjata Filipina dari kesepakatan itu, seperti pelatihan dan peralatan.” Pada 1999 kesepakatan itu diratifikasi oleh Senat dan mengundang protes dari berbagai kalangan. Para veteran gerakan anti-pangkalan bersekutu dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari gerakan buruh dan petani, perempuan, pelajar dan mahasiswa, serta kalangan intelektual membentuk Junk VFA Movement. Ada beberapa alasan yang melandasi protes ini: ●
●
●
●
●
●
VFA membiarkan militer AS menggunakan 22 pelabuhan dan semua landasan pesawat di seluruh Filipina tanpa batas. VFA menyerahkan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh personel militer AS di Filipina kepada sistem peradilan militer AS sendiri. Keputusan ini tentu akan membawa kembali perlakuan sewenang-wenang yang dihadapi rakyat Filipina, seperti kekerasan seksual dan perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak, dan bahkan pembunuhan seperti yang berulangkali terjadi ketika pangkalan AS masih berdiri. VFA melanggar prinsip kedaulatan Filipina sebagai bangsa dengan menghalangi wewenang untuk menerapkan pajak, meminta paspor dan surat izin mengemudi prajurit AS, meninjau kapal-kapal pengangkut serta fasilitas milik AS untuk memastikan bahwa segalanya dilakukan sesuai dengan hukum. VFA akan menyuburkan prostitusi, pengunaan narkoba dan berbagai persoalan sosial serta lingkungan hidup yang pernah terjadi dalam sejarah kehadiran militer AS di Filipina. VFA akan kembali menjadikan Filipina sebagai pangkalan AS untuk melancarkan perang dan serangan militer ke berbagai negara, seperti yang terjadi di masa lalu ketika AS menyerang Tiongkok, Uni Soviet, Korea, Indonesia, Kamboja dan Irak dari basis-basis mereka di Filipina. VFA akan membuka jalan bagi militer AS untuk kembali mendukung kelas penguasa yang reaksioner seperti yang terjadi di masa kediktatoran dan akan menindas gerakan rakyat demokratik.
Keputusan Senat itu dianggap melanggar konstitusi dan juga segala pencapaian setelah kediktatoran Marcos berakhir. Gerakan protes mulai menjalar ke AS sendiri yang melibatkan gerakan solidaritas dan perdamaian di negeri itu. Perjuangan terus berlanjut. (Tim Media Kerja Budaya) 1 | 2 | 3 | 4 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Organisasi ini dibentuk tahun 1994 di Marrakesh setelah negosiasi panjang mengenai perdagangan dunia yang dikenal dengan sebutan Putaran Uruguay. Beranggotakan 137 negara, organisasi ini menjadi forum untuk membicarakan kesepakatan dagang internasional, mengawasi dan menegakkan pelaksanaannya. Dalam Putaran Uruguay, negara-negara secara bertahap diminta mengurangi hambatan tarif demi kemajuan perdagangan. Pembentukan WTO memuluskan agenda perusahaan raksasa untuk menghapus semua hambatan bagi perdagangan internasional. Negara-negara dituntut menghapus semua undang-undang dan peraturan yang bersifat melindungi pasar, menghambat arus modal dan barang. Jika semula perusahaan raksasa selalu menjadikan negara Dunia Ketiga sebagai sasaran – antara lain karena dikenal korup atau mudah dibeli – maka dengan WTO sasarannya adalah semua pemerintahan dan lembaga yang melindungi buruh, konsumen, perempuan atau lingkungan hidup. Semua pertimbangan perlindungan dihapus, dan diganti dengan prinsip “keuntungan apa yang bisa didapat”. Sekarang ini WTO mulai berfungsi sebagai pengadilan internasional untuk menyelesaikan perselisihan dagang antarnegara. Masalahnya pengadilan ini jauh dari keadilan, karena doktrin neoliberal tentang perdagangan bebas adalah hukum dasarnya dan para petugas pengadilan tidak lain adalah kaum profesional yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan untuk membela kepentingan mereka. Dalam setiap kasus yang dibawa ke pengadilan ini, kepentingan perusahaan selalu menang dan pemerintahan serta rakyat menjadi korban. Misalnya dalam sengketa antara industri perikanan internasional melawan pemerintah AS yang menggunakan hukum perlindungan satwa langka, sengketa industri minyak Venezuela melawan Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat, dan banyak lainnya. Indonesia saat ini adalah anggota WTO dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melemahkan kekuatannya sendiri dan masyarakat tentu saja, demi kepentingan dagang dan cari untung. (fn) ●
Globalisasi di Internet
●
Dalam Bahasa Mereka Sendiri
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
GLOBALISASI DI INTERNET Diskusi tentang globalisasi sudah cukup lama disiarkan melalui jaringan Internet. Ratusan situs didirikan untuk bertukar pikiran, menyampaikan berita dan informasi tentang segala aspek globalisasi. Jumlahnya terus membengkak dan kadang membuat para pengguna kewalahan dan angkat tangan. Berikut beberapa situs terpilih yang berhasil dihimpun oleh redaksi MKB. Hampir semuanya adalah portal informasi (information gateway) yang menghubungkan pengguna dengan ratusan dan bermacam sumber informasi lainnya. Selamat mencoba.
Corporation Watch. Perhatian utamanya adalah perilaku perusahaan raksasa yang menguasai perekonomian dunia. Situs dibagi ke dalam beberapa topik dan ditata dengan baik. Memuat banyak artikel dan tulisan mengenai globalisasi, lembaga keuangan internasional dan masalah-masalah yang ditimbulkan. Alamat: www.corpwatch.org Focus on the South. Melihat globalisasi dari perspektif Dunia Ketiga. Situs ditata dengan menarik dan mempermudah orang mendapatkan informasi yang diinginkan. Banyak artikel dan tulisan lain dari intelektual-aktivis Dunia Ketiga seperti Vandana Shiva, Arundhati Roy dan Walden Bello. Alamat: www.focusweb.org Peoples’ Global Action. Situs aktivis Dunia Ketiga yang menentang globalisasi neoliberal dalam berbagai bahasa. Memuat berita aksi dan gerakan perlawanan di negara-negara Selatan, berikut pernyataan dan dokumen, serta link ke berbagai organisasi perlawanan. Alamat: www.agp.org Robinsón Rojas Archive. Situs ini didirikan seorang akademisi, yang memuat banyak informasi tentang globalisasi dan tata ekonomi dunia. Penataan situsnya tidak terlalu baik, karena banyak informasi yang ditampilkan langsung di halaman awal, sehingga cenderung membingungkan. Namun, koleksi tulisan, laporan dan dokumentasinya sangat berguna. Alamat: www.rrojasdatabank.org War on Want and Globalization. Melihat globalisasi dari perspektif rakyat pekerja. Banyak informasi mengenai dampak globalisasi neoliberal terhadap buruh di berbagai sektor dan negara. Link ke situs-situs organisasi rakyat pekerja lainnya sangat berguna. Alamat: www.globalworkplace.org Z-Net. Situs progresif yang sangat besar, dengan informasi mengenai berbagai masalah dari perspektif progresif. Di samping analisis tentang situasi sekarang juga memiliki seksi tentang alternatif terhadap globalisasi. Arsip artikel dan tulisannya patut dikunjungi. Alamat: www.zmag.org Bahan dalam bahasa Indonesia sementara ini masih sangat terbatas. Beberapa artikel terjemahan dan tulisan sendiri tersebar di berbagai situs dan belum ada upaya untuk mengumpulkannya. Tapi ada beberapa situs yang dapat membantu globalisasi dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Down to Earth. Memproduksi lembar fakta dan berita dalam bahasa Indonesia. Perhatian utamanya adalah lingkungan hidup, tapi dilihat dalam perspektif ekspansi globalisasi neoliberal. Lembar fakta mengenai lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan ADB sangat berguna. Ada beberapa link yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan. Alamat: www. gn.apc.org/dte E-Che’s Page. Bagian dari situs yang dikelola oleh Edi Cahyono. Memuat beberapa artikel dan pamflet dalam bahasa Indonesia mengenai lembaga keuangan internasional dan neoliberalisme. Arsip mengenai sejarah Indonesia dan masalah perburuhan juga membantu. Alamat: www.geocities. com/edicahy Indo-Marxist. Situs ini memuat tulisan mengenai neoliberalisme dan perkembangan globalisasi dari perspektif kiri. Di samping itu ada arsip besar karya klasik dalam bahasa Indonesia. Alamat: http:// members.xoom.com/indomarxist/
●
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
●
Dalam Bahasa Mereka Sendiri
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
DALAM BAHASA MEREKA SENDIRI Kadang sukar dipercaya bahwa kesengsaraan di dunia sekarang adalah hasil karya manusia. Media massa selalu menampilkan para elit penguasa sistem sebagai kumpulan manusia santun, yang ramah dan baik hati. Tapi, tidak selamanya orang bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Berikut beberapa kutipan yang dapat membuka mata untuk melihat orang seperti apa yang sesungguhnya menggerakkan dan merayakan globalisasi kesengsaraan ini. “Jika dunia seperti sebuah pasar besar, maka semua pegawai akan bersaing dengan semua orang di dunia yang mampu melakukan pekerjaannya. Kita tahu ada banyak orang seperti itu, dan umumnya mereka itu lapar.” (Andrew Grove, Presiden Intel Corp. dalam bukunya High Output Management) “Ini di antara kita saja. Apa tidak lebih baik jika Bank Dunia menganjurkan pembuangan limbah industri yang kotor lebih banyak ke negara berkembang? Dalam logika ekonomi membuang limbah beracun ke negeri berpenghasilan rendah bukan tindakan tercela dan kita harus berani menghadapinya. Saya selalu berpikir bahwa Afrika yang jarang penduduknya, tentu juga sedikit polusinya; pencemaran udara di sana masih sangat rendah dibandingkan Los Angeles atau Mexico City. Dan itu tidak efisien.” (Lawrence Summers, Wakil Sekretaris Bank Dunia, dalam sebuah memo internal, 1991) “Hanya sedikit kecenderungan yang dapat menggerogoti landasan dasar masyarakat kita yang bebas. Salah satunya adalah jika kita membiarkan para pemimpin perusahaan memikul tanggung jawab sosial lain di luar mengeruk uang sebanyak mungkin bagi para pemegang saham mereka.” (Milton Friedman, dalam bukunya Capitalism and Freedom) “Masyarakat apa yang tidak mengenal keserakahan? Masalah tata sosial sekarang adalah bagaimana menciptakan sistem di mana keserakahan tidak begitu menyakitkan; dan itulah kapitalisme.” (Milton Friedman dalam majalah Playboy, 1973) “Saya tidak tahu satu pun produk yang ditemukan oleh laboratorium atau perusahaan raksasa. Bahkan alat pencukur listrik dan tempat pemanas bukan berasal dari sana. Perusahaan raksasa selama ini hanya bergerak masuk, membeli semuanya dan menghisap para pencipta yang kecil.” (John Molloy, wakil presiden General Electrics, dalam bukunya Molloy’s Live for Success, 1983) “Kekuatan kapitalisme untuk menjembatani kesenjangan antara yang kaya dan miskin memang luar biasa. Dan saya pikir, dari tahun ke tahun, kesenjangan itu semakin kecil.” (Bill Gates, pimpinan Microsoft, 1997. Saat setengah penduduk dunia hidup dari upah $2 per hari, Gates berpenghasilan $96 setiap detik!) “Saya tidak tahu mengapa industri farmasi terus dituntut untuk berbuat [baik]. Tak seorang pun menuntut Renault memberi mobil kepada orang yang belum punya mobil.” (Bernard Lemoine, direktur asosiasi industri farmasi Perancis, Januari 2000)
●
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
●
Globalisasi di Internet
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Indymedia, Membangun Media Gerakan Media komersial adalah senjata ampuh dalam globalisasi neoliberal, khusus nya untuk membentuk citra buruk setiap usaha perlawanan. Untuk menghadapi itu dalam aksi protes di Seattle bulan November 1999, jurnalis-aktivis dan pekerja media membentuk Independent Media Center (IMC) yang lebih dikenal dengan sebutan Indymedia. Sejak saat itu jaringan ini dikelola secara kolektif oleh aktivis, jurnalis independen, teknisi dan pekerja media. “Kami membantu rakyat yang terus bekerja membuat dunia lebih baik, di tengah distorsi media komersial dan ketidakinginan mereka untuk meliput usaha-usaha pembebasan manusia,” bunyi pernyataan di situs mereka. Tugas utamanya adalah menjadi clearinghouse informasi yang menyediakan laporan dari lapangan, foto, rekaman suara dan video, yang kemudian disiarkan melalui Internet dan saluran televisi publik. Jaringan Internet adalah saluran utamanya, dan dalam waktu kurang dari setahun situs Indymedia menjadi salah satu sumber paling populer untuk mengikuti berita-berita tentang aksi anti-globalisasi di seluruh dunia. Jaringan media ini mengutamakan desentralisasi dan bersifat otonom. Setiap kota dan komunitas didorong untuk menciptakan “pusat kegiatan” sendiri, lalu menghubungkannya dengan “pusat-pusat” yang lain. Saat ini sudah ada ratusan pusat semacam itu di seluruh Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Meksiko, Cekoslowakia, Afrika Selatan, Belgia, Perancis, Italia dan setiap waktu terus bertambah seiring meningkatnya gelombang protes anti-globalisasi di seluruh dunia. Dana dan bantuan teknis untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan di masing-masing pusat diperoleh dari sumbangan pribadi dan beberapa lembaga yang bersimpati seperti Free Speech TV, Paper Tiger TV, ProtestNet, Radio for Peace International, Public Citizen, FAIR, puluhan stasiun televisi dan radio komunitas lainnya dan organisasi pekerja media. ●
2000, Tahun Perlawanan
●
Mengadili Globalisasi
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
2000, Tahun Perlawanan Peralihan milenium ini menjadi mimpi buruk bagi para penguasa dunia. Hampir semua pertemuan penting dihadang oleh gerakan protes yang melibatkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu negara. Sementara itu di negara-negara Selatan berlangsung ratusan aksi, mulai dari demonstrasi damai sampai pemogokan massal di berbagai sektor. · Sekitar seribu aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang turun ke jalan raya di kota Jakarta pada Januari, memprotes pertemuan CGI yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia. Sementara itu di Ekuador terjadi pemberontakan rakyat menentang kebijakan neoliberal. · Pada Februari di Bangkok jaringan rakyat miskin pedesaan dan aktivis perkotaan melancarkan protes terhadap pertemuan lima tahunan Konperensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). · Pada awal April, protes rakyat menentang globalisasi semakin meluas, yang bermula dari lapangan kota Cochabamba, Bolivia. Ribuan penduduk setempat memaksa perusahaan Bechtel yang akan mengambil alih (swastanisasi) pelayanan air minum untuk keluar dari negeri itu. Penguasa membalas dengan memberlakukan negara dalam keadaan bahaya. · Saat 30.000 aktivis dari seluruh dunia menyerbu Washington dan mengepung markas IMF dan Bank Dunia, aksi solidaritas dalam jumlah yang sama terjadi di berbagai negeri Dunia Ketiga, termasuk Brasil dan Afrika Selatan. Di Lusaka dan Nairobi, kelompok perempuan melancarkan aksi serupa di bawah tekanan hebat dan akhirnya dibubarkan paksa oleh polisi. · Awal Mei, pertemuan Bank Pembangunan Asia (ADB) di kota Chiang Mai diguncang demonstrasi 5.000 mahasiswa, pengangguran, aktivis lingkungan dan rakyat pedesaan yang tergusur. Polisi yang mengawal pertemuan itu sempat kewalahan. · Pada 10 Mei, gerakan serikat buruh India menyerukan pemogokan umum yang ternyata diikuti oleh separuh angkatan kerja di negeri itu. Mereka menetang kebijakan neoliberal rancangan Bank Dunia yang akan berakibat pemecatan massal. Aksi protes terjadi di berbagai kota, melibatkan sekitar 200.000 buruh. Hari berikutnya, dua puluh juta buruh India melancarkan aksi mogok. Mereka secara eksplisit memprotes penyerahan kedaulatan nasional India ke tangan IMF dan Bank Dunia. · Sekitar 80.000 orang melancarkan aksi menentang IMF di Argentina pada pertengahan Mei. Penguasa membalas dengan penggebukan massal yang menyebabkan banyak orang terluka. Di Turki pada waktu bersamaan pemerintah juga menindas demonstrasi yang menentang kebijakan “mengencangkan ikat pinggang”. · Pada Juni, ribuan orang turun ke jalan-jalan raya di Port-au-Prince, Haiti, dalam rangkaian aksi menentang hutang luar negeri. Sementara itu di Paraguay serikat-serikat buruh menyerukan pemogokan umum selama dua hari untuk menentang swastanisasi yang dipaksakan IMF. · Di Nigeria pada bulan yang sama, serikat-serikat buruh bersekutu dengan penduduk Lagos dalam pemogokan massal menentang kenaikan harga minyak yang dianjurkan IMF. Aksi itu membuat para pejabat IMF mempersingkat jadwal kunjungannya di negeri itu. · Pada Juli, serikat buruh Korea Selatan berulangkali melancarkan pemogokan dan protes menentang kebijakan “mengencangkan ikat pinggang” yang dianjurkan oleh IMF. · Sebulan kemudian, gerakan kiri di Brasil mengadakan plebisit tentang program IMF di Brasil. Lebih dari enam juta orang memberikan suara, dan mayoritas menyatakan menolak. · Pada September aksi solidaritas mendukung S-26 berlangsung di seluruh dunia. Di Afrika Selatan, ribuan aktivis turun ke jalan-jalan di Durban, berdemonstrasi di depan kedutaan besar AS di Cape Town dan membuat arak-arakan menuju markas perusahaan terbesar di Afrika (Anglo American Corp). Para petugas keamanan perusahaan itu menghadapinya dengan kekerasan dan semprotan air lada ke wajah para aktivis. · Belasan ribu buruh, mahasiswa dan aktivis gerakan sosial berkonfrontasi dengan aparat keamanan di Seoul tanggal 20 Oktober. Aksi itu diarahkan pada pertemuan antara pemimpinpemimpin Eropa dan Asia di kota itu. ●
Indymedia, Membangun Media Gerakan
●
Mengadili Globalisasi
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
PicoSearch
Cari!
Mengadili Globalisasi Pada April 2000 berlangsung pertemuan negara-negara Selatan di Havana, Kuba. Hadir di sana para pemimpin Dunia Ketiga, termasuk Abdurrahman Wahid sebagai presiden Indonesia waktu itu. Fidel Castro sebagai tuan rumah pertemuan itu, menyampaikan pidato untuk mewakili pandangan rakyat tertindas. Berikut cuplikannya, “Limapuluh tahun yang lalu kita diberi janji bahwa suatu hari takkan ada lagi kesenjangan antara negeri maju dan berkembang. Kita diberi janji roti dan keadilan; tapi saat ini kita semakin jarang makan roti dan ketidakadilan pun meningkat. Neoliberalisme bisa membuat dunia menjadi global tapi tidak bisa berkuasa atas milyaran orang yang lapar akan roti dan keadilan. Gambar-gambar ibu dan anak korban kekeringan dan bencana lainnya di seluruh Afrika mengingatkan kita pada kamp-kamp konsentrasi di Jerman semasa Nazi; gambar-gambar itu membawa kembali ingatan akan tumpukan mayat dan laki-laki, perempuan serta anak-anak yang sekarat. Kita perlu menggelar Nuremberg* lagi untuk mengadili tatanan ekonomi yang dipaksakan kepada kita sekarang. Dengan kelaparan dan penyakit yang bisa disembuhkan tatanan ini setiap tiga tahun membunuh lebih banyak laki-laki, perempuan dan anak-anak daripada jumlah korban Perang Dunia Kedua selama enam tahun. Kita perlu berdiskusi di sini tentang apa yang harus dilakukan. Di Kuba kami biasanya berkata, “Tanah Air atau Mati!” Dalam pertemuan negeri-negeri Dunia Ketiga ini kita bisa bilang: “Bersatu dan menegakkan kerjasama yang erat, atau mati bersama!” * Nuremberg adalah kota tempat pengadilan para penjahat perang Nazi Jerman digelar.
●
Indymedia, Membangun Media Gerakan
●
2000, Tahun Perlawanan
1 | 2 | 3 | >>
INDEX | ARSIP | EDISI ONLINE | HALAMAN NASKAH | LINKS Tentang MKB | Email ©2003, Media Kerjabudaya Online. http://mkb.kerjabudaya.org e-mail: [email protected] design & maintenance: nobodycorp. internationale unlimited
Related Documents

Web Media Kerjabudaya Edisi 072001
February 2021 0
Media Kerjabudaya Edisi 112003
February 2021 1
( Edisi Revisi )
January 2021 1
Media
January 2021 4
Edisi 1
January 2021 3
Tehnologii Web
January 2021 0More Documents from "BlackFlame40"

Web Media Kerjabudaya Edisi 072001
February 2021 0
Buku Kumpulan Diskusi 2000 Dbp
February 2021 1
Media Kerjabudaya Edisi 112003
February 2021 1
Perkembangan Cybercrime Di Indonesia
February 2021 1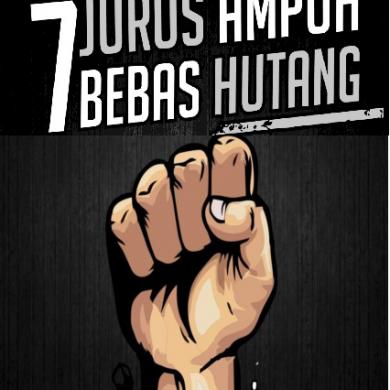
Jurus Ampuh Bebas Hutang
January 2021 1