Media Kerjabudaya Edisi 112003
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Media Kerjabudaya Edisi 112003 as PDF for free.
More details
- Words: 40,901
- Pages: 72
Loading documents preview...
edisi 11 tahun 2003
Rp 8000,http://mkb.kerjabudaya.org
ISSN: 0853-8069
MENCARI BAHASA PEMBEBASAN CERPEN SAUT SITUMORANG: BAH! KLASIK: JS FURNIVALL PAT GULIPAT: GONJANG-GANJING SISDIKNAS SISIPAN: TEMU KORBAN
DATA BICARA PENGUNGSI PARIAH PROLETARIAT DATA B I C A R A
“Dan sejarah ini, perampasan hidup mereka, tertera dalam kitab perjalanan umat manusia dengan aksara darah dan api.” (Karl Marx, Das Kapital, 1867). “Lebih dari 10.000 orang tewas dan sekitar 1,4 juta orang terusir dari tempat asalnya dalam konflik komunal di Indonesia. Banyak internally displaced persons (IDPs) yang bersesak-sesak dalam tempat penampungan sementara selama lebih dari dua tahun… membentuk kelas pariah, yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan yang sangat buruk.” “Masalah ini harus secepatnya diselesaikan sebelum mengeras dan menurun pada generasi anak-anak pengungsi.”(Laporan World Food Programme, 2002). PBB dan pemerintah melakukan survey ulang antara Desember 2002 dan April 2003, untuk mendapat angka yang lebih pasti. Pemerintah mengatakan jumlah pengungsi sekarang hanya 500.000 orang. Tapi PBB mengatakan jumlahnya jauh melebihi itu. Setelah tawar-menawar akhirnya disepakati bahwa jumlah mereka sekitar 700.000. Tentu ini belum termasuk jumlah pengungsi di Aceh yang sejak berlakunya operasi militer, menurut keterangan penguasa militer sudah mencapai 42.000 jiwa.
Miskin dan lapar dalam kegelapan Tingkat kemiskinan tiga kali lebih tinggi dibandingkan penduduk pada umumnya. Sekitar 17% anak-anak pengungsi tidak pernah menikmati bangku sekolah. Sementara, 12% lainnya terpaksa drop-out karena keluarganya tidak mampu membiayai. Sekitar 80% rumah tangga tidak punya kamar kecil atau tempat mandi, sementara 88% tidak punya tempat sampah. Di 50 daerah yang dikunjungi, sekitar 90% rumah tangga dilaporkan memiliki anggota keluarga yang sakit. Di 11 distrik, jumlah itu bahkan mencapai 100%. (Laporan World Food
Kalau pulang, bisa bikin apa? Skema pemulangan pengungsi selalu menemui kesulitan. Selama tiga tahun berlangsungnya konflik komunal, diperkirakan 57.000 bangunan rata dengan tanah, di antaranya ada 448 rumah ibadah, 241 sekolah, dan 260 kantor. Sebagian besar penghancuran ini terjadi di Maluku. Di Aceh, ada sekitar 12.000 bangunan yang hancur (Jakarta Post, 17 Juni 2001). Sementara itu, ribuan hektar tanah dan bangunan berpindah tangan yang akan menimbulkan masalah baru di masa mendatang. Pengungsi yang memilih pulang akan mendapat bantuan jatah hidup (jadup) selama tiga bulan sejumlah Rp 250.000, ditambah bantuan untuk membangun kembali rumah senilai Rp 2,5 juta. (Kompas, 22 Januari 2003). Biaya membangun rumah di daerah-daerah yang dilanda konflik biasanya sekitar Rp 300.000/m2. Artinya dengan dana itu pengungsi hanya bisa membangun rumah sekitar 8 m2, tanpa jaminan tanah yang ditinggalkan dapat diperoleh kembali.
Programme, 2002).
Uang, Perang, Damai… Ke mana kami bisa pergi? Menjadi buruh. Menurut Menakertrans Jacob Nuwawea, para pengungsi Aceh yang berjumlah 42.000 jiwa dapat disalurkan menjadi buruh di perkebunan negara maupun swasta. “Bagi pengungsi yang tidak mau, pemerintah lepas tangan dan tidak akan mengurus mereka lagi,” katanya. “Pengungsi selama ini sudah keenakan karena selama ini tanpa bekerja, pemerintah tetap mensubsidi uang lauk pauk Rp 1.500/jiwa. Itulah yang membuat saya jadi pusing,” katanya (Waspada, 28 Agustus 2001). Transmigrasi. Banyak pengungsi asal Timor Leste yang sekarang dijadikan transmigran ke Sulawesi dan Sumatera. Beberapa dari mereka mengaku tidak betah karena fasilitas yang tersedia di sana ternyata tidak sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Buruh harian. Karena lapar dan miskin, tidak sedikit pengungsi yang memilih bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di tempattempat yang banyak menampung pengungsi, barak-barak mereka adalah pusat tenaga kerja murah baru. Kontraktor, pemilik modal dan juga preman bisa merekrut tenaga yang bersedia melakukan apa saja untuk bayaran sekitar Rp 4.000-10.000 per hari. Pulang kampung. Sekitar dua pertiga dari 140.000 orang yang terusir dari Poso saat meledaknya konflik komunal di wilayah itu akhirnya pulang kampung. Di Ambon jumlah yang kembali ke tempat asal mencapai 113,000 dari sekitar 330.000 yang terusir (CCDA, 5 Maret 2003). Tapi bagi ratusan ribu orang lain yang tak punya kampung lagi, pulang ke tempat asal bukan pilihan yang menguntungkan. Karena bermacam alasan, sekitar 70% pengungsi sampai saat ini tetap memilih tinggal di tempat penampungan sementara.
Saat ini diperkirakan bantuan bagi pengungsi dari lembaga kemanusiaan internasional, pemerintah, dan LSM, mencapai US$200 juta per tahun. Pemerintah Inggris selama 2003 menyumbang sekitar US$ 1,2 juta (UN-OCHA, 11 Agustus 2003). Jumlah ini tentunya tidak seberapa dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan senjata ke Indonesia. Jumlah bantuan itu hanya separuh dari nilai sebuah tank Scorpion-90 yang sekarang dipakai untuk menghancurkan pemukiman dan gedung-gedung di Aceh.
… dan tentu saja, korupsi Sebanyak 24 aparat pemerintah dan masyarakat diperiksa oleh kejaksaan di Sumatera Utara karena menggelapkan sekitar Rp 2,07 milyar dana bantuan pengungsi (Kompas, 20 Maret 2003). Di Maluku sekitar Rp 27 milyar bantuan untuk pengungsian tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan membuat bantuan untuk daerahdaerah lainnya terhambat sampai saat ini (Kompas, 22 Maret 2003). DPRD Nusa Tenggara Timur meminta kejaksaan tinggi setempat memeriksa gubernur Piet A. Talo, lima bupati, dan walikota karena diduga menyelewengkan dana pengungsi asal Timor Leste sebesar Rp 600 milyar (Koran Tempo, 13 September 2001). Calon gubernur Maluku Utara, Thaib Armayn, diduga terlibat korupsi dana bantuan sebesar Rp 67 milyar (Koran Tempo, 16 September 2002). sumber foto: www.tempo.co.id
SURAT PEMBACA Yth. Sahabat-sahabatku di Jaringan Kerja Budaya, Entah mengapa tergerak juga hati ini untuk mengirim beberapa catatan dari saya mengenai keadaan Aceh selama sepuluh tahunan ini. Mengapa saya katakan catatan, bukan puisi? Sebab sebuah puisi, sebagaimana layaknya definisi yang terjadi selama ini di Indonesia, haruslah ditulis oleh seorang penyair besar, dan dia haruslah pula menetap tinggal di Jakarta-Jawa. Bukan yang ditulis oleh seseorang seperti saya, yang hanya berdomisili dan kebetulan lahir di Aceh. Apalah artinya orang-orang seperti itu, bukan? Tapi itu tidak begitu penting. Yang perlu saya ingin sampaikan apa saja catatan saya tentang Aceh-Indonesia, setidaknya dari kaca mata saya, yang mudahmudahan belum lagi buram. Bagi saya, yang ibu asli seseorang keturunan Aceh dan kini telah lama meninggal dunia, mendengar kata-kata Aceh sama terharunya ketika saya mendengar kalimat Allah bagi pemeluk agama Islam. Aceh adalah sebuah ironi, sekaligus malapetaka bagi nasib orangorangnya. Aceh seperti penyakir SARS yang sangat berbahaya dan harus dimusnahkan. Sepertinya saya terlalu romantis. Oya, bagaimana keadaan sahabat-sahabatku di sini? Semoga Tuhan masih memberi perlindungan kepada kita. Semoga kehidupan ini masih dapat terpelihara sebagaimana layaknya kehidupan yang baik. Bagaimana pula kabarnya sahabat, kawan dan guru saya Kakanda Hilmar Farid (Fey)? Salam hangat saya untuk beliau. Salam hangat saya untuk sahabat-sahabat di JKB. Bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang Aceh? Ini saya kirim beberapa catatan tentang Aceh, dan kalau dianggap berbahaya bagi keselamatan jiwa, mohon sekedar untuk dibaca-baca saja. Hanya kepada Allah kita memohon ampunan, kepadaNya pula kita meminta perlindungan. Amin. Salam, Din Saja, Banda Aceh
MENDAPATKAN MKB Hallooo... nama saya Rezki Hasibuan. Saya seorang wartawan dari Radio 68H Jakarta. Begitu saya membuka situs Media Kerja Budaya online anda, saya jadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kiprah Media Kerja Budaya ini. Kira-kira di mana saya bisa mendapatkan majalah Media Kerja Budaya? Apakah saya boleh mengetahui siapa-siapa saja yang membidani lahirnya Media Kerja Budaya ini?. SURAT PEMBACA
Mungkin kita bisa berdialog dan berdiskusi panjang lebar soal pengaruh media televisi dan hal-hal yang bersifat kontra-kultura lainnya. Kira-kira bolehkah saya mengirimkan tulisan mengenai kritisi media, kritisi industri musik atau soal budaya lainnya?? Soalnya saya ingin mengetahui lebih jauh tentang kiprah Jaringan Kerja Budaya beserta Media Kerja Budaya. Rezki Hasibuan
CARI INFORMASI Halo. Setelah membaca edisi 8/2002 saya ingin mencari lebih banyak informasi dari majalah anda. Saya belajar/bekerja di Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara di UGM, sedang meneliti aspek-aspek budaya dan seksualitas. Terkait dengan penelitian ini saya minta bantuan anda: 1. Dengan edisi-edisi lama, adakah artikel lain tentang pornografi, seksualitas dan seks? Ada artikel ‘dagang daging $40 milyar’ - siapa penulisnya? 2. Ada penulis dari edisi tersebut, Rika Suryanto. Dia membahas buku “Remaja dalam Cengkeraman Militer”. Minta alamat email, alamat rumah atau nomor telepon - ingin pendapat dia tentang topik yang saya teliti. terima kasih Semsar Siahaan
SURAT DARI ACEH
Thomas Barker, Bulaksumur BLok B-10B Yogyakarta, 55281.
SURAT DARI SEMSAR Gua fikir MKB mengalami kemunduran dalam pemuatan ilustrasi yang bermutu (maaf). Edisi terakhir yang gua sebut, ilustrasinya tampak dadakan dan asal isi. Di samping itu akibat dari illustrasi tersebut, membawa MKB awut-awutan secara visual. Bersama surat ini gua nyumbang dua karyakarya gua thn 2000. untuk bebas digunakan oleh MKB. Dan berjudul: 1. “Totem Millenium Tiga” I dan “ Totem Millenium Tiga” II. Keduanya tinta di atas kertas dan berukuran : 57 cm x 77 cm. Hal lain yang ingin gua kritik adalah menyangkut Keluasan Isi Berimbang atau Kesatuan Isi Kerakyatan MKB. Maksud gua, mengapa isinya dia-dia lagi yang menulis. Dan mengapa isinya melulu berupa tulisan hasil “Pengamatan/Analisa” Intelektual yang itu-itu lagi manusianya, kan begitu luas kemungkinan memuat isi MKB. SELAMAT HARI ULANG TAHUN JKB dan MKB yang KE-X.
Su r a t u n t uk Su rat Pe m baca h e n d a k nya d i l e ngk ap i d e nga n na ma d an al a ma t l e ngkap. K i r i m k an su r at an d a ke a la ma t redaksi MKB: Jalan Pinang Ranti No. 3, Jakar ta 13560 atau emai l: [email protected] rg . Reda ksi t idak mengem bali ka n surat-surat yang diterima.
OBITUARI DAN AKURASI MKB No. 10/2003 memuat obituari Agam Wispi oleh JJ Kusni. Sayang, tulisan itu tak lebih dari “sekapur sihir” yang “diramu” dari larik-larik puisi Wispi sendiri. Tak dijelaskan posisi unik Wispi di antara penyair Lekra dan arti pentingnya bagi sastra Indonesia modern. Di rubrik Resensi Buku ada tulisan Hersri yang, setelah membahas buku, bercerita tentang Buru. Di awal alinea terakhir tulisan itu Hesri menulis “... demi akurasi data.” Sayang lagi, Hersri sendiri tidak akurat. Dia mengatakan Dalang Tristuti Rachmadi tinggal di Unit IV, padahal Tristuti tinggal di Unit X. Dia bilang semua pelukis “dilokalisasi” di dekat Markas Komando Inrehab, padahal banyak pelukis yang tetap tinggal di unitnya, seperti Suhud Mardjo, Martean Sagara, dan Wiryawan. Saya minta Hersri berhenti berpikir bahwa dia paling tahu tentang Inrehab Buru. Saya harapkan juga Redaksi MKB lebih kritis dan seksama. Amarzan, Jakarta.
SALAM PELA Semoga teman-teman sehat selalu. Pertama kami memperkenalkan diri kami yaitu ALIANSI PELA ACEH yang berkududukan di Banda Aceh. Aliansi Pela Aceh merupakan kumpulan dari berbagai individu dengan kemampuan dan spesialisasi tertentu (wartawan, pengacara, guru, aktivis NGO dan lain sebagainya). Aliansi didirikan dengan dilatar-belakangi adanya keinginan berbagai individu untuk ikut terlibat dalam membela, membantu, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir Aceh serta memperjuangkan pengelolaan pesisir dan laut aceh yang berbasis rakyat dan lingkungan yang berlandaskan resolusi konflik, demokratis, dan berkeadilan gender. Sampai saat ini Aliansi telah berusia hampir dua tahun. Kami berharap melalui email ini kita bisa sharing informasi dan mudah-mudahan di masa datang kita dapat bekerja sama. Selain itu kami berharap rekan-rekan bisa mengirimkan buletin, Info Sheet dan lain sebagainya yang bisa memperkuat, mendukung maupun memberikan gambaran kegiatan lembaga rekan-rekan. Informasi ini akan sangat berguna bagi Aliansi Pela Aceh. Demikian perkenalan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dede Suhendra, Sekretaris Eksekutif Aliansi Pela Aceh.
Semsar Siahaan, Victoria, Kanada. media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
3
EDISI 11 TAHUN 2003 Sejak 1993 ISSN: 0853-8069
Mencari Bahasa Pembebasan 2 DATA BICARA 3 SURAT PEMBACA 5 EDITORIAL SAMPUL: ALIT AMBARA
Pemimpin Redaksi Razif Sidang Redaksi Agung Putri, Anom Astika, Arif Rusli, Ayu Ratih, B.I. Purwantari, Hilmar Farid, IBE Karyanto, John Roosa, M. Fauzi, Nugraha Katjasungkana, Razif, Sentot Setyosiswanto Koreksi Akhir Th. J. Erlijna Desain & Web Alit Ambara Distribusi Andre Keuangan O.H.D. Tata Usaha Mariatoen Pemimpin Umum Firman Ichsan Wakil Pemimpin Umum Dolorosa Sinaga
6
6-33 POKOK 7 Puisi JJ. Kusni 8-12 Masih Adakah Bahasa (Bangsa) Indonesia? Yang Menjadikan Bahasa Indonesia Wawancara Jus Badudu Wawancara I Gusti Ngurah Oka Ulasan Alia Swastika Ulasan Hersri Setiawan PAT tentang Bahasa Indonesia
14-18 19-21 21-24 25-27 27-29 30-33
TIM MEDIA KERJA BUDAYA
34-35 OBITUARI EDWARD SAID Media Kerja Budaya adalah terbitan berkala tentang kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Media Kerja Budaya mengangkat berbagai persoalan, gagasan dan penciptaan untuk memajukan kehidupan budaya dan intelektual di Indonesia. Redaksi menerima sumbangan berupa tulisan, foto, gambar dan seterusnya yang bisa membantu penerbitan ini. Bagi pembaca yang ingin eksemplar tambahan dapat menghubungi alamat tata usaha kami. Penerbitan ini sangat tergantung pada dukungan pembaca, kami berharap dapat menerima kritik dan saran anda. Untuk berlangganan Media Kerja Budaya kirimkan data lengkap anda (nama, alamat, no.tel/fax, e-mail) ke bagian tata usaha kami: Jl. Pinang Ranti No. 3 RT. 015/01 Jakarta 13560. Tel./Fax: 021.8095474 (Mariatoen), E-Mail: [email protected]. Biaya berlangganan per edisi Rp 8000,- (Minimum 5 Edisi) ditambah ongkos kirim menurut jarak pengiriman. Pembayaran Dilakukan Melalui Transfer BANK BCA KCP Kramat Jati, Rekening No. 165-600071-7 a.n.: I Gusti Agung Ayu Ratih. Alamat Redaksi Jalan Pinang Ranti No. 3 RT. 015/01 Jakarta Timur 13560 Indonesia Tel./Fax: 62.21.809 5474 E-Mail: [email protected] Alamat Tata Usaha PO. Box 8921/CW Jakarta 13089 Indonesia Tel./Fax: 62.21.809 5474 E-Mail: [email protected]
John Roosa
36-37 PAT GULIPAT Gonjang-Ganjing Sisdiknas
38-40 ESAI Nyanyian Perempuan Amerika Bagi Pembebasan
42
Umi Lasmina
41 PUISI DIN SAJA 42-44 KRITIK SENI Punk di Indonesia Antara Gaya dan Isi Resmi Setia M.S
45-57 SISIPAN MKB Temu Kemanusiaan Korban Orde Baru
58-60 CERPEN SAUT SITUMORANG
45
Bah!
61-63 KLASIK John Sydenham Furnivall M. Fauzi
64-66 RESENSI BUKU Penguasaan Sumber Daya Alam dan Krisis Sistem Kapitalisme Dunia Antonius T. Stevanus
67
67-70 TOKOH Subcomandante Marcos Wilson
71 BERITA PUSTAKA
http://mkb.kerjabudaya.org DAFTAR ISI
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
&2003, Milik Umum
EDITORIAL
DALAM suatu kesempatan langka, A. Latief, seorang agen penyalur buruh Indonesia, menyatakan bahwa TKW banyak menderita kekerasan di luar negeri karena kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab para pembantu ini sangat rendah. “Mereka itu kan anak-anak desa yang bodoh. Kalau dikasih perintah sama majikannya sering salah-salah karena ngga ngerti bahasanya. Ya, lama-lama jengkel majikannya.” Masih menurut si Latief, pemerintah RI harus lebih ketat mengeluarkan ijin usaha penyaluran TKW. “Kalau bisa agen yang mampu mengajarkan bahasa asing saja yang boleh beroperasi.” Tentu saja kami tak percaya begitu saja penjelasan si Latief. Penjelasannya kedengaran seperti dongeng saduran dari pernyataan pejabat pemerintah. Kejengkelan serupa apa yang sudah membenarkan seorang majikan menyiram wajah pembantunya dengan air keras? Kesalahan seberat apa yang sudah dilakukan sekian banyak perempuan desa Indonesia sehingga mereka patut diperkosa, dan tak jarang disiksa sampai mati? Tak mungkin bahasa saja yang jadi sumber soal. Ini soal daya tawar yang sangat tak berimbang. Dan, bukan hanya daya tawar buruh-buruh belia itu saja, tapi juga daya tawar negeri yang mengirim mereka. Menyambut Kongres Bahasa Indonesia VIII yang baru lalu, Kepala Pusat Bahasa, Dendy Sugono, menulis bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi “sebagai alternatif dalam mengisi perdagangan bebas” (Kompas, 13 Oktober 2003). Alasannya, jumlah penutur bahasa ini masuk dalam urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina, Inggris dan Spanyol. Kita harus menyiapkan bahan-bahan pelajaran yang baik untuk membantu orang asing belajar bahasa Indonesia. Setelah gas, minyak bumi, kayu gelondongan, nikel, tembaga, bahkan orang, sudah dijual, kini bahasa pun ditawarkan. Bahasa yang pernah jadi modal berdagang, akan diperdagangkan. Tapi, bukan cuma itu soalnya. Nilai apa yang dimiliki bahasa Indonesia sehingga orang akan tertarik membelinya? Sedangkan Jim Bob Moffet, Presiden Direktur Freeport McMoran, yang tak berbahasa Indonesia sepatah kata pun bisa menguasai tujuh puncak gunung di wilayah Pegunungan Tengah. Dan lagi, kalau kebanyakan kaum terpelajar lebih puas menjadi juru tulis atau juru bicara IMF dan Bank Dunia dari pada menulis karya ilmiah tentang Indonesia, untuk apa orang asing belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tidak akan laku dijual di dalam, apalagi di luar negeri, selama keindonesiaan yang ia wakili adalah pembantaian massal, pencurian dana proyek, penggusuran orang miskin, penggundulan dan pembakaran hutan, serta penjualan anakanak dan perempuan. Selama yang menjadi duta negeri ini adalah tersangka dan terdakwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, tukang catut bantuan untuk pengungsi, dan makelar tubuh manusia, bahasa yang berlaku adalah bahasa uang. Saat ini, satu-satunya bahasa yang menjanjikan pemulihan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat adalah Bahasa Korban. Kita perlu mendengarkan suara mereka yang menjadi korban kekerasan dan kebijakan kriminal ciptaan para petinggi yang lebih cinta uang dari pada manusia. Bahasa mereka terkadang kelewat pedih, menggigit, tapi jelas tak bersalut pemanis ketika menggugat. Seperti ucapan Bu Martini, ibu seorang korban penembakan di Semanggi yang bekerja sebagai buruh cuci, “Kalau Bu Mega ngga bisa selesaikan masalah pelanggaran HAM di masa lalu, ya lebih baik kembali saja ke dapur, masak sayur asem.” Kalau kita tak sanggup hadapi masa paling kelam dalam sejarah Indonesia, kita akan terkurung di “dapur” bangsa lain walau masih berbahasa Indonesia, walau berjumlah keempat terbesar di dunia. Selamat Idul Fitri 1424 H. Maaf sebesar-besarnya MKB edisi ini terbit sangat terlambat. Kami, Gerombolan Orang Particulier Indonesia, berjanji akan bekerja lebih keras tahun depan!
Pemimpin Redaksi
EDITORIAL
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
5
ALIT AMBARA
6
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
MASIH BISAKAH KITA BERBAHASA INDONESIA? JJ. Kusni serambut saja memang perbatasan itu merentang darimana hidup dipilah dari maut kianat terpisah dari setia benci dari cinta damai dari perang sedang hidup jadi wilayah keduanya kernanya diriku pun sering terbelah atau bagai adonan rupa-rupa ramuan — rahasia putra-putri bumi selalu menggelitik tanya tanahair begini besar ditandai warna-warni tanahair sungguh gudang rahasia di mana kita belajar berbangsa dan mendewasa kala mengurai kerunyamannya indonesia adalah keragaman keragaman adalah indonesia dan hidup memang keragaman — para leluhur pun tahu sejak bahela tapi kukira masih saja patut saban kali diulangucapkan menegur ingatan terkadang sangat sembrono yang bisa menyalakan api menghanguskan segala kita memang sering tak gampang dewasa seakan enggan melepaskan masa kanak membungkus kejahatan dengan lagak tanpa dosa kebocahan hingga tak layak digugat hingga pantas dipahami saja dan dimaafkan kitapun dengan enak tak usah lagi peduli ribuan, jutaan nyawa binasa serta miliaran kehancuran bahkan angka-angka yang berada di luar jangkauan mesin-mesin hitung maka bom demi bom dengan tenang terus diledakkan yang kian mengabur perbatasan kemudian batas semu kau sahkan lagi-lagi dengan bom yang mau lebih sadis membayonet para perempuan dan gadis-gadis usai ramai-ramai mereka diperkosa (sempatkah kita berpikir tentang nasib perempuan? sempatkah kita teringat akan ibu sendiri?) aku menanyai diri agar kesadaran tak terlambat menanggap apakah ini bahasa baru dilahirkan waktu dan di sini di indonesia kita tak lagi paham berbahasa indonesia? Perjalanan 2002 media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
7
Masih Adakah Bahasa (Bangsa) Indonesia? Kalau kita membaca sejumlah artikel yang muncul menyambut Bulan Bahasa tahun ini, bahasa Indonesia ditampilkan seperti seorang pejuang tua dan miskin yang sedang bertarung antara hidup dan mati dengan bahasabahasa lain di dunia. Salomo Simanungkalit di harian Kompas menyatakan, “Bahasa Indonesia masuk ke medan perjuangan tempat suatu bahasa saling bertarung dengan bahasa-bahasa lain.” Sialnya, perjuangan itu ternyata tidak menjanjikan apa-apa bagi bahasa kita tercinta ini. Ia diserbu habis-habisan oleh bahasa Inggris yang memasuki “medan perang” dengan persenjataan mutakhir. Bahasa Inggris dengan jumawanya menjadi pemenang bukan saja atas bahasa Indonesia, tapi atas semua bahasa di dunia, “Tentu saja tidak ada satu bahasa lain pun yang mampu memenangkan pertarungan selain bahasa Inggris.” Walaupun kelihatannya akan kalah, bahasa Indonesia tetap berjuang dengan gagah berani. Ada harapan indah terselip bahwa suatu saat bahasa kita yang sederhana dan bersahaja ini akhirnya akan memenangi pertarungan sengit di medan perang bahasa. Kiasan tentang adanya peperangan antar bahasa menunjukkan contoh yang baik bagaimana bahasa bisa mengecoh pemahaman kita. Wartawan Kompas tersebut membicarakan benda mati yang bukan manusia – dalam hal ini bahasa — dan memperlakukannya seakan-akan benda itu memiliki ciri-ciri kemanusiaan. Dalam bahasa Inggris ini disebut anthropomorphism. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sejauh ini kita belum memiliki padanan katanya selain dari personifikasi, yang diserap dari bahasa Inggris personification. Sebagai perangkat retorik, tak ada yang salah dengan personifikasi. Itu sejenis metafor yang seringkali kita pakai. Masalahnya justru ketika kita menggunakan perangkat retorik untuk membangun pemikiran rasional. Rasanya cukup jelas 8
bagi kita semua bahwa bahasa Indonesia tidak sedang berperang melawan bahasa Inggris, seperti juga nasi goreng tidak sedang mengacungacungkan bambu runcing memburu hamburger. Untuk memahami persoalan bahasa Indonesia dewasa ini, kita perlu berpikir tentang kegiatan berbahasa itu sendiri secara menyeluruh. Bagi mereka yang terperangkap dalam metafor perang bahasa, sebenarnya medan yang dibicarakan terbatas pada kosa kata. Bahasa Indonesia dianggap kalah karena semakin banyak orang menggunakan kata-kata bahasa Inggris dalam ujarannya ketimbang katakata bahasa Indonesia. Orang dengan mudah mengganti kata-kata bahasa Indonesia yang sudah cukup jelas maknanya dengan katakata asing, atau malas mencari padanan kata asing yang belum ditemukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Para pengamat khawatir bahasa Indonesia akan semakin tercemar dan tidak dihormati lagi. Kalau keadaan ini berlanjut, mungkin suatu saat kita akan berbicara dalam bahasa Inggris dengan hiasan beberapa kata Indonesia, seperti , “I have to go to the mall sayang, do you want to titip anything?” “Yes, please get me the imported wine that is really enak.” Kita akan berlaku seperti kaum ekspatriat yang hanya tahu segelintir kata-kata Indonesia, tetapi ingin memamerkan kecintaannya terhadap Indonesia dengan cara yang termudah. Menurut beberapa pengamat masalah ini timbul antara lain karena semakin tipisnya nasionalisme di kalangan orang Indonesia pada umumnya. Mereka ingin mencapai “kesuksesan” dengan jalan pintas walaupun pengetahuan dan pengalamannya tidak seberapa. Mereka tidak segan-segan meniru, melahap, bahkan menghamba pada apa pun yang berasal dari “luar negeri” (baca: Amerika Serikat dan Eropa). Jika demikian, apakah kemudian penyelesaiannya adalah pemerintah harus
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ALIT AMBARA
POKOK
menghimbau masyarakat supaya lebih nasionalistik? Menyebarkan propaganda supaya masyarakat bangga dengan bahasa sendiri dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kita semua tahu, Kegiatan serupa ini, seperti juga kampanye ‘Aku cinta rupiah’, ‘Jagalah kebersihan’, atau ‘Orang bijak taat pajak’, tak akan membawa hasil yang berarti. Kami melihat bahwa persoalan sebenarnya bukan pada membanjirnya katakata bahasa Inggris dalam ujaran bahasa Indonesia, tapi bahwa mereka yang menggunakan kata-kata atau istilah bahasa Inggris seringkali tidak tahu persis apa arti kata-kata tersebut. Memang patut disayangkan bahwa kelompok yang begitu banyak memiliki kesempatan mempelajari
POKOK
bahasa apa pun dengan baik justru menjadi salah satu agen perusak bahasa. Kaum terdidik perkotaan yang senantiasa perlu mematut-matut diri ini menggunakan kata-kata bahasa asing bukan untuk memperkaya bahasa Indonesia – bahasa yang selama berabad-abad menyerap ribuan kata dari bahasa Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, dst. – tetapi sekedar untuk memberi kesan kosmopolitan dan berpengetahuan luas. Kalau kita simak baik-baik tuturan mereka, boleh dibilang miskin gagasan orisinal. Mereka mungkin berharap istilah asing yang mereka gunakan bisa menutupi kekosongan dari segi substansi dan mempesona pendengarnya. Sebagai pembanding tuturan kaum
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
yang menyebut dirinya intelektual ini, kita perlu membaca kembali pidato-pidato Soekarno. Setiap pidato Soekarno sarat dengan kata-kata asing. Kadang-kadang ia bisa memakai kata-kata dari tujuh bahasa asing ketika berbicara. Yang menarik ia selalu menjelaskan arti kata-kata asing itu dalam bahasa Indonesia kalau dia menduga pendengarnya tidak mengerti. Kadangkadang ia bahkan menjelaskan cara mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar. Tak heran apabila pendengarnya mudah merasa terangkat derajatnya oleh pidato-pidato Soekarno. Berbeda dengan intelektual publik di masa kini. Mereka malahan ingin membedakan diri, mengambil jarak sejauh mungkin dari pendengarnya. Pendengar kerap merasa
9
10
Indonesia membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, tetapi tidak seluruhnya. Hanya satu bagian saja yang membeku, yaitu bagian yang berkaitan dengan kehidupan kolektif kita sebagai bangsa. Selebihnya dibiarkan terbengkalai, berlarian bebas seperti ayam kampung, menjadi bahasa gaul, bahasa prokem, dan bahasabahasa ‘anti-kemapanan’ lainnya. Seperti juga di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kebudayaan, pemerintahan Soeharto berbuat sangat sedikit untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Tak pelak lagi, seandainya bahasa itu bisa dijadikan komoditi, ia akan dijual murah seperti minyak bumi, tembaga, kayu dan tenaga manusia. Karena tidak memiliki apa yang disebut seorang pemikir Jerman berjenggot exchange value (nilai tukar), bahasa Indonesia diperlakukan seperti udara, sesuatu yang sekedar ada, terbuka bagi siapa saja, dan dengan demikian tersedia pula bagi penguasa untuk dicemari dengan limbah kosa kata beracun: OTB, GPK, massa mengambang, bahaya laten, ekstrim kiri-kanan-tengah, SARA, dst.
Salah satu usaha minimal pemerintah Orba untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah melakukan standarisasi. Sebuah lembaga dengan dana dan ruang gerak terbatas, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), berhasil menyusun daftar kata bahasa Indonesia yang bisa mengganti bahasa asing untuk istilah-istilah teknis. Upaya ini sendiri sesungguhnya patut dihargai. Setiap bahasa sampai tahap tertentu membutuhkan standarisasi supaya bahasa itu bisa dipakai sebagai bahasa tulisan (untuk surat kabar, jurnal, buku, dst.). Mereka yang melihat institusi semacam P3B ini sebagai bukti ambisi totalitarian rejim Orde Baru agaknya melebih-lebihkan kesewenangwenangan institusi tersebut. Bagaimana pun juga standarisasi ragam tulisan untuk tujuan tertentu, seperti penulisan karya ilmiah dan hukum sebenarnya penting dilakukan. Standarisasi di satu bidang tidak berarti standarisasi seluruh bahasa dan pengingkaran atas keragaman. Sasaran utama kritik terhadap bahasa pada masa pemerintahan Soeharto seharusnya
ALIT AMBARA
rendah diri karena mereka dibuat tidak mengerti istilah-istilah ajaib seperti good governance, stakeholder, deconstruction, postmodernism, dst. Padahal sering terjadi bahwa si pembicara sendiri tak terlalu memahami kata-kata yang ia lontarkan. Yang lebih parah lagi, kata-kata yang dipakai mewakili konsep-konsep yang pada dasarnya tidak jelas asal-usulnya dan tidak terlalu penting juga secara ilmiah. Kelompok ini juga dengan teratur dan setia mengacau bahasa Indonesia (atau, bahasa pada umumnya) sebagai penulis kolom atau editorial di surat kabar dan majalah. Kalau kita ambil koran apa saja secara acak dan membaca satu-dua artikel karya para pengamat, segera akan tampak kata-kata dalam bahasa Inggris bertebaran sia-sia dan tak tentu maksudnya. Sebagai contoh, perhatikan kutipan dari artikel yang dimuat di sebuah harian terkemuka di bawah ini: Banyak pula mantan Pati TNI yang bergabung dengan parpol yang lulus threshold. Tetapi, hal itu dapat juga berarti peringatan (warning) kepada kalangan parpol. Tampaknya persoalan dikotomi sipil-militer dalam politik di Indonesia hanyalah materi percakapan di meja perjamuan kaum scholars saja. Orang asing yang berbahasa Inggris tak bakal mengerti kalimat-kalimat di atas, sedangkan kebanyakan orang Indonesia pun hanya akan menebak-nebak. Dan, apa pula perlunya menambahkan kata warning di dalam kurung setelah kata peringatan? Tingginya frekuensi kesalahan penggunaan kata-kata bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia menunjukkan persoalan yang lebih luas dalam bahasa Indonesia sendiri. Suka atau tidak kita harus melihat kembali ke masa pemerintahan Soeharto. Wacana publik dimonopoli sedemikian rupa oleh para petinggi militer dan birokrat sehingga bahasa Indonesia luar biasa terluka dan tumbuh tersendat. Sebagai alat komunikasi sehari-hari antar-teman, bahasa Indonesia sangat kaya. Jika kita ingin menggambarkan penampilan atau kepribadian tetangga atau kenalan kita, tak ada masalah. Ratusan kata dari berbagai bahasa, bahkan dialek, mengalir lancar. Tetapi kalau kita harus berbicara tentang kemiskinan, kekerasan, dan demokrasi, kita seakan-akan kehilangan kata. Yang kita kenal baik adalah rumusan-rumusan resmi dari pemerintah atau ungkapan-ungkapan klise peninggalan para intelektual di masa Orde Baru. Seperti dinyatakan banyak kritikus, bahasa
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
diarahkan pada pembekuan wacana politik di bawah cengkeraman birokrasi dan pengabaian kebutuhan pengembangan bahasa di bidang-bidang lainnya. Bagi orang-orang yang dalam kesehariannya berurusan dengan penulisan dan penerjemahan, standarisasi bahasa tulisan akan sangat membantu kelancaran pekerjaan mereka. Kami di MKB misalnya, akan merasa beruntung kalau ada buku-buku pedoman yang terus-menerus diperbaharui seperti, Oxford English Dictionary dan Chicago Manual of Style untuk bahasa Indonesia. Buku-buku acuan tentang semantik, ejaan, dan tanda baca dalam bahasa Inggris tersebut terbukti membantu banyak penulis dan editor berbahasa Inggris. Tentunya penyusunan buku acuan yang demikian rinci dan padat membutuhkan institusi yang dibiayai dengan memadai dan dikelola orang-orang yang memang ahli dan terampil di bidang kebahasaan. Standarisasi bahasa tulisan yang kami usulkan tidak ada hubungannya dengan konservatisme politik. Justru sebaliknya. Perubahan radikal membutuhkan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Ini adalah pandangan klasik para pemikir masa Pencerahan di abad ke-18 ketika mereka menentang dogmatisme dan takhayul. Para penguasa masa kini tak jauh berbeda dengan penguasa di masa feodal; mempertahankan kekuasaannya dengan menyembunyikan tindakan-tindakan mereka dan mengelabui khalayak dengan bahasa. Tujuan utama politik radikal dengan sendirinya adalah mendobrak ilusi dan merebut kebenaran. Coba kita pertimbangkan beberapa prinsip dasar menulis yang baik: gunakan kalimat aktif yang menunjukkan apa/siapa sebagai subyek (Kamu membunuh lelaki itu. Bukan kalimat pasif: Lelaki itu dibunuh.); gunakan kata-kata yang mengundang kepekaan panca indera sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu kejadian (Kamu menembaknya di kepala dengan sebuah pistol Colt.); hindari eufemisme (Lelaki itu meninggal karena kejadian yang tragis.) Prinsipprinsip atau norma-norma ini penting karena membantu kita menulis karangan yang menggambarkan realitas. Mereka bukan norma-norma khayalan yang dibuat sembarangan. Mereka juga bukan hasil rekaan guru-guru tua nyinyir yang bernafsu membatasi imajinasi kita. Bahasa politik pada jaman Soeharto – yang dipakai dalam pidato-pidato resmi sebagai presiden, terbitan pemerintah, POKOK
begitu juga di media massa secara umum – dengan leluasa mengabaikan normanorma sederhana di atas. Bahasa Orde Baru, seperti sudah sering diungkapkan beberapa peneliti dan pengamat, penuh dengan kalimat pasif, deskripsi seadanya, dan eufemisme. Memang tidak ada pilihan lain bagi sebuah rejim yang harus menyembunyikan terlalu banyak tindakan kriminal. Misalnya, ketika kelompok Soeharto mulai melancarkan aksi kriminalnya yang pertama, teror sepanjang 1965-66, jarang dinyatakan bahwa tentara menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai ‘komunis’: tentara mengamankan mereka. (Lihat buku terbaru Hersri Setiawan, Kamus Gestok, untuk eufemisme ini dan yang lain.) Hilangnya kelugasan dalam gaya bahasa Orde Baru bisa dilihat, antara lain dalam pernyataan Departemen Luar Negeri tentang pembantaian Santa Cruz di Timor Lorosae pada 12 November 1991. Menarik, pernyataan tersebut aslinya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi dengan gaya bahasa Indonesia Orba. “Sangat disayangkan, demonstrasi tersebut tidak sepenuhnya damai dan sesungguhnya menunjukkan provokasi dan tindakan agresif yang direncanakan. Hal itu memicu reaksi spontan dari beberapa aparat keamanan, yang bertindak di luar kontrol atau komando perwira senior, dan mengakibatkan kehilangan nyawa dan sejumlah orang terluka.” Tidak jelas siapa yang membunuh siapa atau bagaimana orang terbunuh. Kata-kata pembunuhan atau pembantaian bahkan tak muncul; birokrat di Deplu menggunakan eufemisme “kehilangan nyawa”. Orang yang membaca pernyataan Deplu tidak akan tahu bahwa dalam peristiwa itu pasukan tentara berjajar rapi, menembak serentak tak berkeputusan serombongan anak muda Timor Lorosae yang tidak bersenjata, dan membunuh paling tidak 300 orang. Tetapi mungkin sebagian warga negeri ini akan menganggap kami tidak patriotik karena ingin berbahasa dengan lugas. Dengan mendorong ditetapkannya norma-norma yang lebih jelas untuk bahasa Indonesia ragam tertulis, bukan berarti kami mendukung “pembekuan” bahasa. Norma-norma yang disebutkan di atas adalah jenis norma-norma yang akan memancing kita menggunakan bahasa dengan lebih kreatif. Pada saat kita berusaha mencapai ketepatan dan menimbulkan kepekaan, kita harus mengobrak-abrik otak kita dan mencari kata sifat yang paling deskriptif, kata benda yang paling akurat, media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
POKOK
kata kerja yang paling dinamis. Mereka yang enggan berurusan dengan norma seharusnya menyadari bahwa setiap bahasa didasari oleh aturan-aturan tata bahasa yang sangat ketat. Manusia mempelajari aturan-aturan tata bahasa ini sejak ia mulai mengenal bahasa, dan menghayatinya sedemikian rupa sehingga ia tak berpikir lagi tentang bahasa secara sadar. Seperti dinyatakan ahli tata bahasa terkenal, Noam Chomsky, manusia secara tak terhingga kreatif berbahasa di tengah aturan-aturan tata bahasa yang terbatas jumlahnya. Misalnya, orang bisa menciptakan kalimat tak terhingga jumlahnya hanya dengan mengikuti rumusan sederhana subyek-kata kerja-obyek. Kalau gaya bertutur resmi bahasa Indonesia menderita penganiayaan luar biasa di tangan rejim Soeharto (perhatikan adanya personifikasi ganda dalam klausa ini), ia tidak bernasib lebih baik di lingkungan intelektual dewasa ini yang berbicara atas nama postmodernism. Ada semacam kecenderungan di kalangan intelektual – sebetulnya bukan hanya di Indonesia saja – untuk berpikir bahwa kedalaman pengetahuan diperoleh semata-mata dari ketaksaan dan kesamaran makna tuturan. Semakin kabur dan tersembunyi makna suatu tulisan, tentunya semakin pandai si Penulis. Tak terlalu mengherankan, kita hidup di dunia yang membingungkan. Kita tidak memahami banyak hal yang sedang terjadi. Keinginan kita untuk memahami realitas sering kali menuntut kita menyingkirkan pandangan-pandangan yang terasa masuk akal dan mengembangkan teori-teori yang kompleks. Tetapi teori-teori yang kompleks masih tetap bisa dipahami begitu seseorang memiliki kesabaran untuk mempelajarinya dengan baik. Yang sering terjadi di kalangan mereka yang menyebut dirinya kaum postmodernist (kami memakai ‘yang menyebut dirinya’ karena mereka tidak tahu pasti juga apa arti istilah itu) adalah menganggap tuturan yang tidak masuk akal sebagai pertanda kompleksitas. Mari kita perhatikan pernyataan seorang guru besar emeritus di bidang hukum dari Semarang: “Postmodernism telah melakukan dekonstruksi terhadap dominasi atau hegemoni negara.” Ia tidak menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan empat dari lima kata benda yang ia gunakan di dalam satu kalimat: postmodernism, dekonstruksi, dominasi, dan hegemoni. Dan, lagilagi, kalau kita baca seluruh esai dengan teliti, tampak bahwa si Penulis tidak tahu apa arti kata-kata tersebut. Misal11
nya, menurut kebanyakan literatur di bidang teori politik, dominasi, dan hegemoni merupakan istilah yang sangat berbeda artinya dan tidak bisa disandingkan seakan-akan keduanya bisa dipakai bergantian tanpa mengubah makna masing-masing kata. (Dominasi mengacu pada kekuasaan yang bertumpu di atas penggunaan kekuatan pemaksa, sedangkan hegemoni mengacu pada kekuasaan yang bergantung pada penggalangan kesepakatan.) Sementara, dekonstruksi adalah metode canggih untuk analisa sastra yang dikembangkan oleh intelektual Prancis Derrida. Tapi dalam esai ini kata dekonstruksi berarti tidak lebih dari ‘mengkritik’. Tulisan dari kalangan aktifis prodemokrasi pun tidak jauh berbeda masalahnya. Berbicara atas nama rakyat, pernyataan-pernyataan terbuka mereka sarat dengan jajaran kata hujatan, tetapi tidak mudah dirunut ujung pangkal persoalannya. Salah satu contoh mutakhir adalah kalimat berikut, “Mengamati dan mencermati eskalasi (meningkatnya) ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang merebak begitu cepat dan meluas, sebagai reaksi terhadap akumulasi berbagai kebijakan pemerintah yang tak perduli kondisi objektif dan suasana bathin rakyatnya, merupakan fakta dan realita politik Indonesia hari ini.” Tanpa permakluman yang cukup besar, pernyataan serupa ini akan melahirkan selusin pertanyaan, mulai dari siapa yang “mengamati dan mencermati” apa sampai ke keterandalan “fakta” yang disampaikan. Sulit melihat kecenderungan berbahasa serupa ini sebagai pertanda kecanggihan mengemukakan gagasan dalam abstraksi. Apa yang terjadi belakangan ini adalah bentuk obskurantisme baru atas nama anti-otoritarianisme. Intelektual yang seharusnya memberi contoh gaya bertutur yang jelas, teliti, dan mendidik asyik berceloteh atau menulis esai yang penuh dengan jargon yang mereka sendiri tidak mengerti dengan baik. Mereka kembali mengambil peran kasta brahmana di dalam masyarakat kuno: mengaburkan kenyataan untuk keuntungan penguasa dan berlaku seakan mereka memiliki bahasa rahasia untuk berhubungan dengan para dewa (yang sekarang kebanyakan mengajar di universitas-universitas ternama di Paris dan New York). Di luar kalangan intelektual yang demam bergenit-genit, ada pula yang memperlakukan bahasa Indonesia seakanakan ia memiliki kekuatan magis untuk 12
mempertahankan kesatuan bangsa ini. Mereka sudah mengelirukan akibat dengan sebab. Ketika sekelompok pemuda menyatakan pada 28 Oktober 1928 bahwa Indonesia memiliki “satu bahasa”, mereka berbicara tentang bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang dibayangkan, sebagai bahasa yang akan dikembangkan seiring dengan upaya membangun bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sedang menjadi, bukan produk siap pakai bagi seluruh orang Indonesia. Bukankah para pemuda ini menuliskan sumpah tersebut dalam bahasa Belanda? Pramoedya menulis dalam artikel yang diterbitkan dalam edisi ini juga bahwa keinginan hidup bersama sebagai suatu bangsa muncul terlebih dahulu, baru kemudian keinginan berbicara dalam bahasa yang sama. Persoalan kesatuan nasional dewasa ini sedikit hubungannya dengan bahasa. Ambil contoh rakyat Timor Lorosae yang (dipaksa) belajar bahasa Indonesia selama bertahun-tahun dan berhasil menguasainya dengan baik. Mereka toh memilih memisahkan diri dari Indonesia pada 1999. Saat ini pun setelah mereka merdeka, kaum terdidik Timor Lorosae masih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa itu sendiri bagi mereka tidak jadi persoalan. Mereka bukan ingin merdeka karena mereka tidak suka bahasa Indonesia. Masalah terbesar bagi mereka adalah keharusan hidup di tengah iklim ketakutan terus-menerus, ketidakamanan, dan kekerasan di bawah pendudukan militer Indonesia. Hal yang sama bisa dinyatakan tentang rakyat Aceh sekarang. Yang jadi persoalan utama bukan bahasa Indonesia. Tak bisa disangkal bahwa bahasa yang sama merupakan salah satu syarat bagi tegaknya suatu bangsa, tetapi ia bukan jaminan mutlak kesatuan bangsa. Kekhawatiran berlebihan sebagian orang akan nasib bangsa ini sudah melahirkan pengharapan yang tidak masuk akal akan bahasa Indonesia. Seiring dengan kecemasan akan keutuhan NKRI, tumbuh pula kecemasan akan lemahnya Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan kekuatan militer tingkat dunia. Seluruh kekhawatiran ini kemudian mereka pantulkan ke bahasa Indonesia, seperti yang terlihat pada retorik tentang perang bahasa di awal tulisan ini. Karena Indonesia secara umum dalam posisi lemah dan rentan, bahasa Indonesia juga diasumsikan sama lemah dan rentannya. Lucunya, kecemasan ini muncul dari kalangan yang secara langsung pun tidak mendukung penjualan segala aset yang dimiliki negeri ini, termasuk tenaga media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
manusia, atas nama pasar bebas, demi globalisasi. Kepala Pusat Bahasa bahkan sudah menimbang-nimbang potensi bahasa Indonesia masuk ke pasar internasional dengan bekal jumlah penutur terbesar keempat di dunia! Salah satu upaya Pusat Bahasa mengangkat kembali derajat bahasa Indonesia adalah menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia syarat bagi orang asing untuk bekerja atau belajar di Indonesia. Semua orang asing harus mempelajari bahasa Indonesia dan mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI) supaya bisa berkomunikasi lebih baik dengan orang lokal dan melakukan alih teknologi. Tak terbayangkan bagaimana aturan ini bisa berlaku ketika para pejabat pemerintah yang diutus keliling dunia selama ini merangkak di hadapan para investor asing, merengek-rengek agar mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Strategi usang memupuk kebanggaan nasional yang palsu ini tak juga berubah. Pejabat-pejabat yang berteriak-teriak mengecam “intervensi asing”, “ikut campur urusan dalam negeri Indonesia” adalah mereka yang dengan senang hati menerima kucuran dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan menyalurkan sebagian besar dana itu ke rekening-rekening pribadi mereka. Kalau benar investor asing diharapkan menguasai bahasa Indonesia, mungkin kosa kata yang perlu diketahui tak perlu terlampau banyak: jatah, pungli, komisi, biaya administrasi – semua kata yang berhubungan dengan korupsi dan pemerasan yang dilakukan tentara dan birokrat preman. Bagaimana pula kalau semua orang asing fasih berbicara dalam bahasa Indonesia? Melihat sikap umum kita yang menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa orang pandai, pasti kita akan menganggap bahasa Indonesia orang asing lebih superior dari pada cara berbahasa kita sendiri. Kita akan meniru mereka sebisa mungkin sehingga kesalahan berbahasa dan aksen mereka menjadi norma umum bahasa Indonesia yang baik dan benar! 0
POKOK
BAHASA INDONESIA TERBUKA ATAWA TERTUTUP?
Selama ratusan tahun bahasa Indonesia (BI) yang berasal dari sebuah lingua franca atau bahasa Melayu Pasar dikenal ramah dan terbuka terhadap pengaruh bahasa asing, terutama dari segi kosa kata. Jadi, kalau para pejabat sering menyerukan tanda bahaya “Hati-hati terhadap intervensi asing!”, sebetulnya percuma saja. “Basi!” kalau anak gaul Jakarta bilang. Di bawah ini ada daftar statistik “kasar2an” jumlah kata-kata asing dalam BI yang pernah dibuat ilmuwan politik jahil, tapi pintar, dari Universitas Cornell (sekarang sudah pensiun), Ben Anderson. Dengan bantuan temannya, seorang Arab, ia menghitung semua kata yang ada di Kamus “antik” Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, cetakan ke-2, tahun 1953. Jumlah kata yang diselidiki 4.120 kata. Hampir separuh (45%), atau 1.828 kata, berasal dari bahasa-bahasa non-nasional. Urutannya sebagai berikut:
Aneh juga si Ben ini tak memasukkan bahasa Sansekerta dalam daftarnya. Bayangkan kalau dimasukkan, persentase bahasa asing dalam BI mungkin jadi 75%, karena banyak sekali kata BI yang berasal dari bahasa itu. Saking sudah begitu akrabnya dengan BI, mungkin banyak yang tak sadar kata-kata yang dipakai sehari-hari itu berasal dari bahasa asing. Coba kita lihat bersama daftar kata-kata berikut, yang dikumpulkan dari berbagai sumber: Belanda:
handuk, kakus, kulkas, selai, praktek, apotek, persekot, bioskop, duit
Arab:
rakyat, masalah, masyarakat, kitab, pikir, paham, sebab, kuat, dunia
Inggris:
nasionalisme, mal, diskotik, modern, teater
Tionghoa:
taoco, kongsi, toge, tahu, tongkang, loteng
Sansekerta:
negara, putra-putri, kerja, perkasa, cinta, agama, menteri, semua
Tamil:
cukai, kedai, modal, kolam, kapal, cuma
Portugis:
sabun, gereja, meja, sepatu, bendera, serdadu, peniti, garpu
Parsi:
kertas, bebas, bandar, dewan, bedebah
Nah, sekarang coba kita ingat-ingat adakah kata dari bahasa Papua atau Timor yang kita kenal dan pakai dalam percakapan seharihari? Tentunya bukan yang dari lagu-lagu daerah. Kami sudah cari dengan cukup rajin, ternyata di kamus juga tak ada. Berarti, bahasa Indonesia sebetulnya tak terbuka-terbuka amat. Tak salah kalau orang-orang Indonesia Timur merasa dianaktirikan. Pendapat bahwa bangsa Indonesia dikuasai lingkaran elit Jawa, Sunda, Betawi dan Sumatra juga bukan asal bicara. Konon “bahasa menunjukkan bangsa”.
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
13
Yang Menjadikan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia bukan anugerah yang diturunkan dari langit. Ia adalah buah pertarungan beraneka kepentingan dalam gerak sejarah. Ia juga senjata yang dirombak dan dirakit berulang kali untuk memenuhi kebutuhan membebaskan pun menindas. Dari wacana sejarah utama, kita mendapat kesan bahwa bahasa Indonesia ditemukan begitu saja oleh sebuah Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Tak pernah diungkapkan bahwa kebanyakan peserta kongres yang berasal dari golongan menengah-atas terdidik ini ternyata tidak bisa berbahasa Melayu sehingga kongres itu sendiri terpaksa diselenggarakan sebagian besar dalam bahasa Belanda. Kalau mereka bersepakat menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu bukanlah karena mereka beroleh wangsit di tengah mimpi. Ada kenyataan sejarah yang tak bisa mereka pungkiri, yaitu bahasa yang dipakai secara meluas di wilayah Hindia Belanda adalah bahasa Melayu. Lagi pula, gerakan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan kolonial yang mendahului kongres tersebut sudah menggunakan bahasa Melayu – walau dengan gaya yang berbeda — sebagai bahasa politik. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pergerakan nasional tak bisa dipisahkan dari posisi-posisi politik yang berkembang di paruh awal abad ke-20. Di satu sisi, politik kebudayaan pemerintah kolonial Belanda – berbeda dengan pemerintah kolonial Inggris dan Prancis – membatasi penyebaran bahasa Belanda di tanah jajahannya. Di lain sisi, gerakan perlawanan yang berkembang di masa itu membayangkan suatu nasion yang mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda dan melibatkan kalangan rakyat biasa. Seandainya Indonesia yang dibayangkan itu sebatas tanah (priyayi) Jawa, bahasa nasional yang akan dipilih kemungkinan bahasa Jawa, atau malahan bahasa Belanda. 14
Bahasa Segala Bangsa Selama ratusan tahun sebelum bahasa Melayu menjadi bahasa nasional yang ‘rapi’ dan ‘sopan’, ia sudah berkembang sebagai bahasa khalayak ramai (lingua franca) dari berbagai ras dan suku bangsa terutama di bandar-bandar perniagaan sepanjang pesisir Nusantara. Bahasa Melayu Pasar ini – Pramoedya Ananta Toer menyebutnya sebagai bahasa Melayu Kerja atau bahasa pra-Indonesia — berbeda dengan bahasa yang dipakai kalangan istana di pantai timur Sumatra dan Semenanjung Malaya untuk menulis karya sastra dan dokumen administrasi pemerintahan. Seperti lingua franca pada umumnya, bahasa ini sangat terbuka terhadap dialek dan kosa kata lokal. Struktur tata bahasanya sederhana, tidak memiliki standar yang baku, tapi cukup jelas untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Kalau bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Jawa, Bali, Madura, Sunda, atau Belanda, bermuatan nilai-nilai kebudayaan tradisional, bahasa Melayu Pasar seakan tumbuh ‘liar’ menjadi bahasa segala bangsa. Ia dengan mudah menyerap kata-kata Arab, Portugis, Cina, dsb., tanpa mengganggu kesalingterpahaman antar-pembicaranya. Dominasi kultur perdagangan kepulauan sudah membuat lingua franca ini bertahan selama ratusan tahun. Lepas dari segala keterbatasannya, ia praktis sebagai bahasa transaksi dan fleksibel sebagai alat komunikasi antar (suku) bangsa. Sampai awal abad ke-19 hampir-hampir tak ada upaya untuk menstandarkan atau membakukan bahasa tersebut. Kebutuhan mengendalikan ‘kekacauan’ praktek berbahasa ini mulai muncul setelah Gubernur Jendral Inggris, T. Stamford Raffles, datang ke Hindia Belanda sekitar 1810an. Ia terperanjat melihat kesantaian orang-orang Belanda, termasuk para pegawai birokrasi kolonial, bergaul dengan kaum pribumi. Walaupun secara resmi pemerintah kolonial yang mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik, di wilayah sosial-budaya Belanda tidak memimpin sehingga nilai-nilai peradaban Eropa
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ALIT AMBARA
POKOK
dianggap meluntur. Raffles khawatir kekuasaan Belanda di tanah jajahan akan mudah tergerogoti tanpa ada hegemoni budaya. Ia juga gusar dengan tercemarnya keeropaan orang-orang Belanda yang sudah bertahun-tahun hidup di Hindia Belanda dan mengadopsi cara hidup masyarakat lokal. Bahasa Belanda mereka makin buruk karena bercampur kosa kata Melayu Pasar. Kedekatan mereka dengan penguasa lokal membuat birokrasi kolonial tidak efisien laiknya sistem Eropa. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat, ia bertekad mendesakkan pembedaan budaya yang jelas antara birokrat Belanda dan kaum ‘inlander’. Penggunaan bahasa menjadi salah satu sasaran utama operasi penertiban budaya ini. Ada dua hal yang menjadi tujuan. Pertama, pegawai pemerintah harus menjadi model keteraturan yang ditunjukkan dengan penguasaan bahasa Belanda dan bahasa lokal yang sempurna, secara lisan pun tulisan. Kedua, pemerintah perlu menyebarkan aturan main kolonial dengan bahasa yang ajeg struktur dan ragamnya agar tidak mengundang perbedaan pemahaman dan pendapat di kalangan masyarakat umum. Sepeninggal Raffles, penguasa-penguasa berikutnya melanjutkan kebijakan ini. Sejak 1820an ahli-ahli bahasa dari universitas-universitas ternama di Belanda dikerahkan untuk melakukan penelitian tentang POKOK
bahasa-bahasa lokal yang dominan dan mengusulkan cara penataan bahasa yang paling menguntungkan pemerintah. Pejabat pemerintah yang merasa dirinya mengenal koloni lebih baik ikut pula bersuara. Perdebatan sengit tak terelakkan. Ada pihak yang beranggapan bahasa Jawa lebih tepat dipakai karena mayoritas penduduk Hindia Belanda dan pusat kekuasaan pemerintah berada di Jawa. Pihak lain melihat bahwa bahasa Melayu lebih tepat karena pemerintah berniat memperkokoh kekuasaannya di luar Jawa dan memerlukan bahasa pengantar yang sudah lazim dipakai penguasa lokal non-Jawa. Tidak berhenti di perdebatan, para ahli bahasa ini berlomba-lomba menerbitkan hasil-hasil penelitian mereka. Dr. Pieter Roorda van Eizinga misalnya menyusun kamus besar Melayu/Jawa-Belanda dan Belanda-Melayu/Jawa. Sedangkan ahli lain, Dr. Pijnnappel, malah menerbitkan sejumlah buku pegangan bahasa Melayu dalam berbagai versi untuk mengatasi variasi dialek yang hidup di masyarakat Hindia Belanda. Namun, satu hal yang mereka sepakati adalah sulitnya mengendalikan bahasa Melayu Pasar karena begitu lentur dan beragamnya dialek yang berkembang di pelbagai daerah di Nusantara. Pemerintah sendiri dihadapkan pada kenyataan
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
yang rumit: harus ada bahasa yang mampu mendukung kepentingan pemusatan kekuasaan, tapi bahasa lokal yang paling dominan, bahasa Melayu Pasar, sama sekali tidak memadai untuk menjawab kebutuhan ini. Menarik diperhatikan bahwa misi pemberadaban koloni melalui bahasa ini bukannya menghasilkan kebijakan penggunaan bahasa Belanda, tapi malah mendorong penataan bahasa-bahasa lokal. Tampaknya keterbatasan sumber daya pemerintah kolonial melatarbelakangi keputusan ini. Lebih murah menyewa beberapa intelektual Belanda untuk melakukan penelitian daripada menyelenggarakan pendidikan massal bagi seluruh penghuni Hindia Belanda dalam bahasa Belanda. Bisa jadi ini terkait pula dengan politik kolonial yang ingin mempertahankan penguasa-penguasa lokal sebagai kakitangan pemerintah daripada mendatangkan dan menggaji ribuan pegawai dari negeri Belanda. Setelah sekian uji coba dan perdebatan selama berpuluh-puluh tahun, pendukung penggunaan bahasa Melayu beroleh posisi lebih kuat. Hanya saja, mereka sejak dini sudah menetapkan bahwa acuan utama untuk kerja penataan bahasa ini adalah bahasa Melayu tulisan yang digunakan di pusat kebudayaan Melayu, yaitu Riau dan Selat Malaka. Lepas dari hasil penelitian mereka yang menunjukkan kepo15
puleran bahasa Melayu Pasar, mereka berpendapat bahasa Melayu Riau lah yang lebih murni dan nyata. Dari Bahasa Dagang ke Bahasa Pergerakan Penertiban bahasa Melayu berlangsung paling sistematis menjelang akhir abad ke19 sejalan dengan ambisi pemerintah kolonial memantapkan kekuasaannya di se-antero Nusantara. Dua intelektual yang berperan penting dalam operasi ini adalah Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah untuk urusan kebudayaan, dan J. van Ophuysen, guru besar bahasa Melayu dari Universitas Leiden. Atas usulan Snouck, van Ophuysen menyusun dua buku yang berisi daftar kata-kata Melayu dengan sistem ejaan Eropa dan aturan tata bahasa Melayu. Kedua buku ini menjadi buku pegangan utama bagi pegawai pemerintah dan pendidik di Hindia Belanda maupun di Belanda sendiri. Bahasa Melayu ala Van Ophuysen segera ditahbiskan sebagai bahasa resmi dan disebarluaskan melalui institusi pendidikan pribumi. Di kalangan pemerintah kolonial dan intelektual pendukungnya mulai dikenal istilah bahasa Melayu ‘Tinggi’ dan ‘Rendah’. Semua varian bahasa Melayu yang tidak mengikuti versi Van Ophuysen, diberi cap ‘rendah’ atau ‘kacau’ dan hanya pantas dipakai untuk berkomunikasi dengan babu dan jongos. Selain menyebarkan bahasa Melayu Tinggi melalui pengajaran, pada 1908 pemerintah Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat, atau lebih dikenal dengan Balai Pustaka (BP), untuk memproduksi bacaan Melayu bagi kaum bumiputra. Badan yang dikepalai D.A. Rinkes ini bertugas menyeleksi naskah-naskah yang masuk dan memastikan bahwa isinya tidak bertentangan dengan kepentingan politik pemerintah. Karena syarat awal yang ditetapkan adalah penggunaan bahasa Melayu Tinggi, sudah barang tentu karyakarya yang diterbitkan sebagian besar ditulis oleh pengarang dari Sumatra. Kelak, para penulis Melayu ini berperan cukup penting dalam pelibasan karya-karya bumiputra yang dianggap ‘tidak bermutu’, dan menentukan batasan khazanah sastra modern Indonesia (untuk pembahasan lebih mendalam tentang BP, lihat MKB edisi 03/2000). Di tengah kesibukan pemerintah kolonial menata bahasa Melayu, golongan masyarakat Tionghoa peranakan dan IndoEropa justru mendorong berkembangnya bahasa Melayu Pasar dari sebuah lingua 16
franca menjadi bahasa pers dan bahasa sastra. Sejak paruh akhir abad ke-19 mereka sudah menerjemahkan karya-karya ternama dari Tiongkok dan Eropa ke dalam bahasa Melayu Pasar. Dari pengalaman ini, muncullah keberanian untuk menulis novel yang menggambarkan suasana Hindia Belanda dan menerbitkan koran dalam bahasa Melayu Pasar. Terbitan lokal ini ternyata mendapat sambutan luar biasa, terutama karena bahasa yang dipakai akrab dengan khalayak jajahan. Misalnya saja, dalam waktu beberapa puluh tahun jumlah novel Melayu-Tionghoa yang diproduksi, menurut perhitungan peneliti sastra Claudine Salmon, mencapai tidak kurang dari 3.000 karya. Terbitan kaum Tionghoa peranakan dan Indo-Eropa ini dimungkinkan karena mereka memiliki usaha penerbitan dan percetakan mandiri yang tidak bergantung pada subsidi pemerintah kolonial. Bukubuku yang mereka terbitkan biasanya diproduksi dengan harga yang sangat murah supaya bisa dibeli pegawai rendahan dan kaum yang disebut orang partikelier – mereka yang tidak bekerja tetap di kantor pemerintah atau perusahaan swasta. Berbeda dengan penerbitan milik Belanda yang mempekerjakan kaum bumiputra sebagai buruh kasar, usaha penerbitan dan percetakan ini membuka ruang bagi kaum bumiputra untuk magang sebagai penyunting dan penulis. Banyak tokoh-tokoh pers pergerakan 1920an, seperti R.M. Tirtoadhisoerjo, Mas Marco Kartodikromo, dan Mohammad Sanoesi yang mengawali karirnya di perusahaan serupa ini. Menjamurnya percetakan dan penerbitan golongan Tionghoa peranakan dan Indo-Eropa mengancam dominasi bacaan resmi pemerintah kolonial. Laporan penyelidikan tentang skandal-skandal perkebunan, roman percintaan yang berlawanan dengan nilai-nilai priyayi/kolonial, sampai berita kemenangan Jepang atas Rusia dan kisah-kisah perlawanan lain di negeri seberang bersaing dengan teks-teks dingin dan membosankan yang melulu berisi laporan-laporan pemerintah. Lebih jauh lagi, bahan-bahan bacaan tak resmi yang berhasil meraih kelas-kelas rendahan ini lambat-laun membuka cakrawala pemikiran yang berbeda di kalangan bumiputra. Ketidakadilan yang diciptakan sistem kolonial harus dilawan dengan caracara baru. Dan, pewartaan yang mampu mengungkap kebobrokan sistem tersebut menjadi pilihan pertama. Pemuda-pemuda pribumi yang semula media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
menjadi tenaga magang mulai membuka penerbitan dan percetakannya sendiri. Pada 1907, Tirtoadhisoerjo membuka percetakan dan penerbitan Medan Prijaji yang menerbitkan surat kabar dengan nama yang sama. Di Solo, HM Misbach mendirikan penerbit Insulinde yang berperan besar dalam produksi bacaan selama kurun 1910an. Serikat buruh kereta api, VSTP, yang bermarkas di Semarang kemudian juga mendirikan percetakannya sendiri dan menerbitkan surat kabar dengan tiras terbesar sepanjang sejarah pergerakan, Si Tetap. Dengan basis yang relatif independen dari kekuasaan kolonial, para penulis dan pengelola surat kabar segera memulai ‘perang suara’ dengan penguasa kolonial dengan gaya tulisan yang militan dan memikat. Dengan sengaja para jurnalis ini memilih bahasa Melayu Pasar sebagai alat komunikasi lisan pun tertulis. Mereka melihat bahwa usaha pemerintah menertibkan bahasa Melayu berkaitan dengan niat pemerintah mengendalikan pola pikir rakyat jajahan. Di samping itu, secara praktis mereka merasa bahwa bahasa Melayu Pasar jauh lebih lugas dan bebas dari tata krama feodal ketimbang bahasa Jawa atau bahasa Melayu-Belanda. Upaya pemerintah memberadabkan kaum bumiputra dengan buku-buku keluaran BP dihadapi dengan koran, pamflet, majalah, syair, novel bagi kelas-kelas rendahan untuk mempelajari, mengkritik, dan sekaligus menyerang kekuasaan kolonial. Sementara bacaan dalam bahasa Belanda dan Melayu Tinggi yang dikuasai pemerintah kolonial mengajar kaum bumiputra tentang hukum, aturan, dan tatanan kolonial yang membungkus ketimpangan, bacaan pergerakan justru mulai dengan melihat ketimpangan dan menggunakan pengertian-pengertian baru yang diperoleh dari berbagai sumber: tradisi perlawanan rakyat Jawa, Revolusi Tiongkok, dan Rusia, dan gagasan sosial-demokrat Belanda. Militansi dan radikalisme semakin meningkat ketika para jurnalis, penulis, dan penerbit mulai terlibat dalam organisasi pergerakan nasionalis seperti Sarekat Islam, Insulinde, dan serikat-serikat buruh. Tulisan mereka semakin terarah pada persoalan konkret yang dihadapi organisasi, perseteruan dengan pemerintah kolonial, dan ketimpangan serta ketidakadilan yang dihadapi mayoritas pembacanya. Pada paruh kedua 1910an, ratusan buku dan puluhan surat kabar sudah diterbitkan dan menjadi bagian penting dari pergerakan
kannya untuk menjelaskan gagasan abstrak, seperti sosialisme dan marxisme, atau kaitan antara Islam dan komunisme. Sedangkan Mas Marco Kartodikromo berupaya menyusun ulang Babad Tanah Jawa, untuk “mengambil kembali masa lalu orang Jawa yang selama ini berada di tangan orang Belanda”. Maraknya terbitan politik yang berjalan seiring dengan gelombang pasang gerakan massa anti-kolonial ini dengan sendirinya menimbulkan kegusaran di pihak pemerintah. Melalui BP, pemerintah menetapkan bacaan berbahasa Melayu rendah dan Melayu Tionghoa sebagai “bacaan liar” yang rendah mutunya dan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban koloni. Rinkes secara khusus menuding tokoh-tokoh pergerakan, seperti Mas Marco Kartodikromo, Semaoen, dan Moeso sebagai provokator
ALIT AMBARA
nasionalis. “Perang suara” tidak hanya dilakukan terhadap penguasa kolonial dan pendukungnya, tapi juga di antara aktifis pergerakan sendiri. Polemik dan perdebatan mengenai persoalan sehari-hari atau kebijakan pemerintah mengisi halaman surat kabar atau pamflet, dan menjadi unsur penting dalam pembentukan wacana mengenai bangsa. Kali ini golongan bumiputra rendahan membuktikan bahwa bahasa Melayu Pasar cukup memadai, bukan saja untuk mengungkapkan perasaan terdalam mereka sebagai kaum terjajah, tetapi juga untuk mengembangkan imajinasi mereka tentang kehidupan yang lebih baik. Perkembangan yang tidak kalah menarik, bahasa ini juga dipakai untuk membangun wacana ilmiah di kalangan pergerakan. H.M. Misbach, seorang aktifis Sarekat Rakyat, mengguna-
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
POKOK
yang menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Akibatnya, para jurnalis dan aktifis ini berulangkali ditangkap dan terbitan yang mereka pimpin dibredel. Namun, tekanan ini tidak menyurutkan penerbitan bacaan liar, sampai pemberontakan rakyat yang diorganisir PKI dan Sarekat Rakyat meletus pada November dan Desember 1926 di Jawa dan Sumatra Barat. Gempuran telak pemerintah kolonial terhadap pemberontakan 1926 boleh dikatakan mengakhiri kemeriahan penyebaran bahasa Melayu ‘liar’, dan menandai perubahan karakter gerakan nasionalis itu sendiri. Barisan penulis-aktifis dari kelaskelas rendahan yang mendominasi gerakan sebagian besar dipenjarakan dan dibuang ke Boven Digul. Beberapa dari mereka meninggal di pembuangan, sedangkan yang masih hidup tidak lagi memegang peranan penting pada periode-periode selanjutnya. Jaringan percetakan, penerbitan, distribusi, dan pembaca yang menopang produksi bacaan liar selama 15 tahun porak-poranda. Dan, yang berkaitan langsung dengan bahasa, kelugasan, spontanitas, dan ketajaman wacana politik dalam Melayu Pasar berganti dengan kalimat terselubung, tidak konfrontatif, bernada petuah, dalam bahasa yang lebih dekat ke gaya Melayu Istana. Memenangkan (Bahasa) Indonesia Memasuki periode 1930an, perkembangan bahasa Melayu Pasar sebagai bahasa politik boleh dibilang tersendat, kalau tidak terhenti sama sekali. Dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada 1938, salah satu pemrasaran yang juga anggota Dewan Redaktur Balai Pustaka, St. Takdir Alisjahbana, secara terbuka menyatakan bahwa bahasa Melayu Pasar adalah bahasa yang belum mengenal peradaban dan tidak memadai untuk mengungkapkan gagasan dalam tulisan. Kongres yang dipimpin kaum terpelajar golongan menengah-atas ini – Sanoesi Pane, St. Pamuntjak, Muh. Yamin, Adinegoro, Poerbatjaraka — memutuskan untuk memakai ejaan Van Ophuysen sebagai acuan resmi bagi seluruh orang Indonesia. Keputusan konservatif serupa ini seakan tak terelakkan. Di satu sisi, represi luar biasa terhadap gerakan massa radikal sudah membuat aktifis gerakan nasionalis 1930an lebih berhati-hati berhadapan dengan pemerintah. Di lain sisi, sebagian besar dari mereka yang muncul dalam periode ini, seperti Hatta dan Sjahrir, memang tidak menguasai bahasa 17
Melayu dengan baik. Jangankan bahasa Melayu Pasar, bahasa Melayu Tinggi pun tak mereka pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih banyak berpikir dan berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Selain itu, mereka juga tidak punya pengalaman membangun organisasi massa dari bawah seperti aktifis 1920an, sehingga tak terlalu mengherankan kalau gagasan kebangsaan yang mereka coba rumuskan sangat dipengaruhi ide-ide pemberadaban politik etis. Selama hampir seabad, melalui tiga generasi ilmuwan dan birokrat, pemerintah kolonial berusaha keras menertibkan bahasa Melayu Pasar. Ternyata kaum cerdikcendekia yang cukup beroleh keuntungan dari kolonialisme yang akhirnya berhasil memenuhi ambisi tersebut. Seperti halnya isi putusan Kongres Pemuda 1928 yang menekankan kesatuan, bahasa Melayu-Belanda yang dikembangkan sejak 1930an membawa serta nilai-nilai kolonial yang menekankan ketertiban, keseragaman, dan kepatutan. Alhasil, wacana nasionalisme yang berkembang di masa itu sangat dihantui keinginan untuk menjadi bangsa yang ‘maju’ menurut ukuran Eropa, sederajat dengan bangsa-bangsa Eropa. Yang menjadi pokok soal adalah perbedaan warna kulit atau kesenjangan antara kultur ‘barat’ dan ‘timur’, bukan perbedaan kelas. Memang, kebangkitan kembali pergerakan massa sejak Revolusi Agustus 1945 seakan membuka jalan bagi rakyat untuk memberi makna pembebasan dalam bahasa Indonesia rakitan kolonial ini. Kata-kata yang mencerminkan pengalaman paling penting pembicaranya, seperti merdeka, perjuangan, kebangsaan, muncul tanpa kendali. Harus diakui pula kemampuan Soekarno sebagai pimpinan nasional pergerakan dalam menggunakan bahasa yang rancak dan menimbulkan semangat berpengaruh luar biasa terhadap pemerkayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa politik. Dalam banyak hal Soekarno mengadopsi cara-cara berbahasa tokoh-tokoh pergerakan 1920an, yang mungkin ia pelajari dari pengalamannya sebagai pemuda di masa itu dan kedekatannya dengan HOS Tjokroaminoto, pimpinan Sarekat Islam dan orator handal di jamannya. Sayangnya masa kebebasan bahasa Indonesia tidak berlangsung lama. Menjelang akhir 1950an persaingan politik antar partai dan ancaman ekspansi modal internasional yang beberapa kali diwujudkan dalam provokasi militer melahirkan seruan-seruan yang sarat slogan untuk ke18
pentingan mobilisasi dan konsolidasi massa. Para pimpinan kekuatan-kekuatan politik yang bertarung — yang paling revolusioner sekali pun – seperti kehilangan kemampuan menciptakan adagium yang mencerminkan pemahaman mereka akan permasalahan sosial masyarakat. Mereka melakukan “perang suara” di antara mereka sendiri. Di sisi lain, dominannya pemimpinpemimpin dari kalangan priyayi Jawa mendorong apa yang disebut ilmuwan Ben Anderson “kramanisasi bahasa publik Indonesia”, yaitu munculnya kata-kata Sansekerta atau Jawa Kuno baik untuk merumuskan konsep-konsep politik, maupun untuk memberi nama institusi publik yang bernilai politis tinggi. Misalnya, di masa itu bermunculan istilah-istilah seperti Tri Ubaya Çakti, Sapta Marga, Operasi Mandala, Praja Muda Karana, Cakrabhirawa, dst. Soekarno, dalam usahanya menggalang solidaritas dan mempertahankan persatuan nasional, asyik menciptakan lusinan akronim yang terdengar revolusioner, seperti Jarek (Jalannya Revolusi Kita), Resopim (Revolusi Sosialisme Pimpinan), Manipol-Usdek (Manifesto Politik- UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Nasional), tapi belakangan justru menjadi mantra-mantra yang menghalangi pemahaman rakyat tentang revolusi itu sendiri. Kemana bahasa politik Indonesia? Ketegangan politik yang berlarut-larut akhirnya memuncak pada peristiwa G30S 1965, yang diikuti dengan tragedi paling berdarah sepanjang sejarah modern Indonesia. Operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di bawah komando Mayjen. Soeharto membersihkan jagad politik Indonesia dari seluruh elemen yang dianggap kiri, komunis, termasuk Soekarno. Bahasa Indonesia tidak luput dari operasi pembersihan ini. Kata-kata yang sepanjang sejarah pergerakan nasional menjadi kendaraan pembebas, seperti buruh, rakyat, revolusi, sosialisme, bahkan kata pergerakan itu sendiri, dihilangkan atau diganti dengan kata-kata yang tidak mengundang ingatan akan perlawanan di masa lalu. Kontrol ketat terhadap media massa dan terbitan umum menghasilkan bahasa yang sopan, berlikuliku, dan tak berpendapat. Wacana publik dipenuhi oleh bahasa birokrasi negara. Orde Baru memang jauh lebih berhasil dari pemerintah kolonial Belanda dalam menertibkan dan memaksakan pemakaian bahasa Indonesia yang ‘baik dan benar’ ke media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
seluruh Nusantara, bahkan ke negeri tetangga, Timor Lorosae. Sumber kekuatan utamanya tak lain dari ratusan ribu tentara yang diperintahkan terus-menerus mengawasi tingkah laku, kalau perlu membunuh dan memperkosa, warga negeri ini. Tapi, yang tidak kalah pentingnya adalah keberhasilan rejim ini meyakinkan sebagian warganya bahwa ketertiban dan kepatutan yang dijamin dengan kepatuhan terhadap pemerintah akan membawa kemajuan bagi kehidupan mereka. Meskipun rejim Soeharto akhirnya tumbang pada 1998, merebut kembali bahasa Indonesia sebagai bahasa pembebasan ternyata tidak mudah. Kita jelas tak bisa kembali ke bahasa Melayu Pasar yang berkembang meriah bersama gerakan sosial 1920an; kita tak mungkin menghapus 80 tahun perjalanan bahasa Indonesia. Tapi, kita harus bisa merubuhkan temboktembok pembatas bahasa ala Orba. Salah satu tembok yang cukup kokoh adalah keangkuhan kalangan terdidik di Jawa dan Jakarta yang berpikir bahwa merekalah yang paling menguasai bahasa Indonesia secara sempurna dan merasa seakan-akan merekalah yang bertanggung-jawab mengangkat derajat seluruh bangsa. Kita perlu memperluas ruang berbincang bagi orangorang dari berbagai ras dan suku bangsa sehingga bahasa Indonesia mencerminkan keragaman logat dan dialek yang hidup di segala penjuru kepulauan ini. Kebutuhan akan bahasa yang sama tidak harus dipenuhi dengan standarisasi bahasa di tingkat pusat dan pemaksaan penggunaan di tingkat daerah. Bahasa Indonesia bukan amunisi senjata tentara yang perlu diagung-agungkan sebagai pengikat utama kesatuan republik ini. Seperti kisah kelahirannya, ia seharusnya tumbuh dari percakapan terbuka antar warga bangsa; ia selayaknya pulang asal sebagai alat pendobrak milik kaum mardika. 0
BINCANG-BINCANG
Jus Badudu: “Tidak ada bahasa Indonesia standar.”
kadang-kadang orang tambahkan Indonesia, padahal bukan. Dia tidak hanya mengurus bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah dan bahasa asing yang berhubungan dengan bahasa Indonesia.
ALIT AMBARA
Bagi penonton TVRI di akhir 1970an, nama Jus Badudu tentunya tak asing di telinga. Pemerhati dan praktisi bahasa Indonesia yang terlahir dengan nama Sjarief Jus Badudu ini pernah mengasuh acara mingguan Pembinaan Bahasa Indonesia antara 1977-1980. Jus Badudu menghabiskan masa kecil sampai tamat pendidikan menengah dengan berpindah-pindah ke berbagai kota di Sulawesi. Lahir di Gorontalo pada 1926, ia kemudian bersekolah di Poso, Luwuk, Tomohon dan Makassar. Pada 1952, ia pindah ke Bandung untuk kursus B1 Bahasa Indonesia. Setelah itu, ia masuk Fakultas Sastra Universitas Padjajaran dan mendapat gelar kesarjanaan pada 1963. Pendidikan Magister ditempuhnya di Post-Graduate Linguistics Rijksuniversiteit Leiden, Belanda (197173) dan meraih gelar doktor ilmu-ilmu sastra dengan pengkhususan di bidang Linguistik di Universitas Indonesia (1975). Sebagian besar hidup Jus Badudu dicurahkan untuk dunia pendidikan, yakni menjadi guru SD, SMP, dan SLTA selama 23 tahun sejak 1941 sampai 1964. Ia kemudian menjadi dosen di perguruan tinggi selama 26 tahun sejak 1965, dan akhirnya pensiun pada 1991 di umur 65 tahun. Kini, Guru Besar Emeritus Bahasa Indonesia ini memberikan kuliah dan membimbing tesis serta disertasi mahasiswa program S-2 dan S-3 di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Jus Badudu dikenal sebagai penulis buku yang produktif. Sejak 1957, ia telah menulis dan menerbitkan sekitar 50 buku. Buku terakhirnya yang terbit pada 2003 berjudul Kamus Indonesia Serapan Bahasa Asing. Redaktur Media Kerja Budaya B.I. Purwantari mewancarai Jus Badudu, di rumahnya, di Bandung. Di bawah ini petikan hasil wawancara tersebut. Di masa Orde Baru ada banyak kritik ditujukan kepada Pusat Bahasa Nasional karena lembaga ini dianggap terlalu otoriter terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Apa sebenarnya tugas lembaga ini? Apa pendapat Bapak tentang lembaga ini? Saya tidak pernah bekerja di Pusat Bahasa. Saya pada waktu di televisi itu hanya bekerja sama dengan Pusat Bahasa. Jadi, acara itu adalah acara Pusat Bahasa. Sekarang namanya Pusat Bahasa, sudah disingkatkan. Dulu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), malah
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
19
Tugas lembaga ini sebenarnya memperhatikan bahasa, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan bahasa. Selain itu, lembaga ini bertugas meluaskan kata-kata baru yang dipakai orang. Tetapi sayangnya, dia tidak punya alat penyebar untuk temuan-temuannya, seperti brosur untuk kata-kata baru atau majalah. Orang-orang yang bekerja di Pusat Bahasa mengeluh, katanya, “Lebih banyak mengurusi bahasa daerah dari pada bahasa Indonesia.” Memang bahasa daerah itu perlu diangkat, perlu difasihkan, supaya jangan hilang. Itu juga salah satu tugas Pusat Bahasa. Dia betul-betul lembaga pemerintah, tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk memberikan ketentuan-ketentuan. Silakan dia membuat rumusan-rumusan sampai diperlukan, kalau orang merasa perlu. Kalau tidak diperlukan, ya sudah. Apakah Pusat Bahasa juga melakukan standarisasi terhadap bahasa Indonesia? Tidak ada bahasa Indonesia standar. Sebenarnya yang dijadikan standar itu adalah yang sudah tertulis dan sudah terpakai. Dan kalau orang patuh pada aturan yang tertulis berarti mereka mematuhi bahasa standar dan mematuhi bahasa baku. Saya berbicara bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yang aturannya saya ketahui, yang saya pelajari. Apalagi mereka itu adalah suatu lembaga yang berada di bawah Direktorat Kebudayaan, tepatnya kementerian, Direktorat Pusat Bahasa. Jadi, di bawah sekali pada tingkat-tingkat di kementerian. Mereka tidak dapat, misalnya, mengambil tindakan pada ketidakbenaran pada bahasa. Kurang wibawa. Maksud Bapak seharusnya Pusat Bahasa mempunyai wewenang yang lebih besar? Tentunya wewenang besar yang dapat menentukan sesuatu mengenai bahasa, misalkan untuk dipergunakan dalam membuat undang-undang. Kalau ia melihat bahwa bahasanya kurang berkembang, ia bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang membuat undang-undang itu. Tetapi, Pusat Bahasa tidak mempunyai wewenang seperti itu. Kalau begitu standarisasi dalam bahasa Indonesia tidak ada? Tidak ada! Standarisasi itu seharusnya kita menetapkan muatan bahasa yang sudah 20
ditetapkan. Kalau standarisasi, itu berarti dikatakan apa yang kita pelajari dari buku-buku tatabahasa. Standarisasi kata itu berlangsung; kata baru masuk dalam kamus dan ia menjadi baku. Kalau belum masuk dalam kamus, berarti belum baku kata itu. Sedangkan struktur biasanya bertahan dalam tata bahasa. Anda membuat kalimat kan ada objek, predikat, kata keterangan. Begitu-begitu saja terus, tidak ada yang baru. Kecuali misalnya dikatakan: “pakaian yang disimpannya dalam lemari”, atau “lemari yang di dalamnya disimpan pakaian”. Nah, itu bahasa Indonesia. Tetapi sekarang orang menjadikan “lemari di dalam mana disimpan pakaian”. Itu kan pengaruh bahasa asing di dalam mana berasal dari bahasa Inggris wherein, atau bahasa Belanda waar in. Bahasa Indonesia sebetulnya tidak mengenal bentuk seperti itu. Ada beberapa contoh lagi: “buku yang di atasnya”, atau “meja yang di atasnya ada kamus”. Itu bahasa Indonesia, bukan, “meja di atas mana terletak kamus”. Begitu juga dengan “rumah di mana dia tinggal”. Dalam bahasa Indonesia asli kita menggunakan “rumah yang ditinggalinya”, atau “rumah yang didiaminya”. Biasanya, tata bahasa yang tidak sesuai kita tolak, termasuk juga dari bahasa Jawa, misalnya, “kakinya meja”, “atapnya rumah”. Kita anggap tidak baku dan kita tentukan saja “kaki meja”, tidak perlu menggunakan “nya”. Juga, kalimat seperti “Omanya datang”, atau “Rumahnya siapa?”, itu bukan bahasa Indonesia. Jadi, Bapak masih menganggap perlu standarisasi bahasa Indonesia? Bisa saja. Namun, kenyataannya Pusat Bahasa ini tugasnya apa? Kalau sebagai lembaga pemerintah, setaraf dengan apa? Standarisasi itu perlu. Biasanya, standarisasi itu berlangsung tidak lagi secara resmi. Jadi, sebetulnya penulispenulis buku itulah yang menstandarkan bahasa, memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana bahasa Indonesia dipakai, bagaimana bentuknya yang benar. Penulis buku mengenai tata bahasa itu adalah orang-orang yang menstandarisasi bahasa. Seharusnya lembaga seperti Pusat Bahasa yang melakukannya, tetapi mereka harus punya alat, yaitu majalah yang keluar, kalau tidak setiap minggu, sekurangkurangnya satu bulan sekali, seperti dulu media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
Pak Takdir Ali [Sutan Takdir Alisjahbana – red.] dengan majalahnya, Pembina Bahasa Indonesia itu. Tapi dia kan bukan orang pemerintah. Wah, wibawa majalah itu hebat sekali! Ada juga majalah Bahasa dan Budaya yang dikendalikan oleh sebagian lembaga pemerintah, semacam pusat bahasa di Yogyakarta. Ada lagi majalah Medan Bahasa yang diterbitkan pemerintah. Tapi yang paling berwibawa, ya, Pembina Bahasa Indonesia itu. Apa yang ditulis diperhatikan orang. Bagaimana dengan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri? Perkembangan bahasa Indonesia terutama dari segi pertambahan kosa kata, perbendaharaan kata. Kalau dari segi struktur, perkembangannya sangat lambat, hampir tidak ada. Kata-kata baru banyak sekali masuk dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah. Ada yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak mampu menciptakan kata-kata baru dan hanya mampu mengadopsi kata asing. Bagaimana menurut Bapak? Umumnya ada empat macam aturan kalau kita menerima kata baru. Kita terima kata baru dari bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu misalnya. Kalau tidak ada, kita ambil dari bahasa Indonesia yang sudah mati, dari kata-kata lama. Orang tidak sadar kata-kata seperti kelola, pantau, itu bukan kata baru, tetapi kata lama yang diangkat kembali, karena dari dulu ada di dalam kamus. Kalau tidak ada di bahasa Melayu, orang lari ke bahasa daerah, bahasa daerah yang hidup. Kalau tidak ada kata daerah yang hidup, orang akan cari pada bahasa daerah yang lama. Kalau empat hal ini tidak bisa, lalu kata asing itu orang Indonesia-kan. Misalkan, kita pakai kata superior. Itu kan kata asing yang diindonesiakan karena kalau diterjemahkan terlalu panjang. Juga struktur, kita ambil dari bahasa Belanda. Perkembangan kosa kata dalam bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya bahasa seseorang yang dapat mempengaruhi gaya bahasa orang lain. Misalnya, kalau orang sudah pernah membaca bahasa Takdir, ia mengenal gaya Takdir tersendiri; bagaimana dia menyusun kata-kata dalam kalimat sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang senang memakai kata-kata lama seperti Amir Hamzah dulu. Dengan puisinya, ia sering mencari kata-kata Melayu lama karena Amir Hamzah kan orang Sumatra
daerah rawan”, padahal di sana banyak terjadi kejahatan, terdapat pemberontakan, kerusuhan. Bahasa pejabat biasanya menghindari hal yang memalukan pemerintah, misalkan di Timor sekarang ada kelaparan. Pemerintah harus mengatur supaya tidak terjadi kelaparan. Bukankah itu pembohongan? Yah, bagaimana masyarakat menggunakannyalah. Bahasa seperti itu akan mati kalau masyarakat maju. Mereka membutuhkan banyak pengungkapan. Sebelumnya tidak dipakai, lalu mencari ungkapan baru. Kadang-kadang kita anggap sebagai manipulasi bahasa, tetapi dipergunakan dengan sengaja. Mereka berusaha menghindari pengertian yang keras. 0
POKOK
ALIT AMBARA
Timur, orang Langsa, ya. Jadi, orang Melayu bisa berbicara bahasa Melayu. Kata-kata yang dipakai itu kata-kata Melayu lama. Dia mengenal bahasa Melayu, tetapi orang di luar Melayu tidak tahu. Kata-kata yang dipakai Amir Hamzah ini ada yang bisa kita temukan di kamus, ada yang tidak. Bagaimana dengan manipulasi bahasa, seperti yang dipakai oleh kalangan birokrat, misalnya, menyatakan “kenaikan harga” dengan “terjadi penyesuaian harga”? Membuat ungkapan baru untuk menghindari arti yang dianggap merugikan itu adalah manipulasi bahasa. Di tempat-tempat yang minim akan kesehatan, dikatakan sebagai “daerah-
BINCANG-BINCANG
I Gusti Ngurah Oka: “Kalau pembina bahasa dituruti semua keinginannya, maka ia bunuh semua ragam bahasa dan gunakan satu bahasa baku.” I Gusti Ngurah Oka adalah salah satu tenaga ahli yang terlibat dalam perumusan Politik Bahasa Nasional di dekade awal pemerintahan Orde Baru. Berbekal pengetahuan dan pengalaman sebagai dosen bahasa Indonesia di almamaternya, IKIP Malang, ia diminta menangani bidang pengajaran bahasa di Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (P3B) dan Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama paling tidak 10 tahun sejak 1973. Lahir di Denpasar pada 15 Juli 1937, Pak Oka – demikian ia biasa dipanggil – menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Denpasar dan Singaraja sebelum ia memutuskan untuk hijrah ke Jawa pada 1958. Ia lulus dari Jurusan Bahasa Indonesia IKIP Malang pada 1964 dan sejak saat itu memusatkan perhatiannya pada masalah pengembangan pendidikan bahasa. Sebagai asisten pakar pendidikan, Dr. Soepartinah Pakasi (alm.), ia membantu mendirikan SD Laboratorium IKIP POKOK
Malang. Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu dalam mata kuliah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Kuno di University of Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat selama 1972-1973. Di sela-sela kesibukannya mengajar dan bekerja untuk P3B, Pak Oka sempat menulis sejumlah buku dan artikel mengenai pengajaran bahasa Indonesia dan retorika. Sejak pertengahan 1980an ia lebih banyak menghabiskan waktunya mengajar di beberapa kampus di Malang dan kota-kota sekitarnya. Walaupun ia sudah pensiun pada 2001, perhatiannya pada masalah kebahasaan tidak surut. Untuk mengetahui lebih lanjut soal penanganan bahasa nasional di masa Orde Baru, Tim Redaksi MKB mewawancarai Pak Oka di kediamannya di Malang. Kapan P3B didirikan dan mengapa P3B perlu didirikan? P3B itu perlu didirikan untuk menggariskan kebijakan kebahasaan nasional yang akan mengatur pembinaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia. Sebelum P3B didirikan tidak ada badan yang secara
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
formal melakukan kebijakan serupa itu. Tugasnya pertama-tama menggariskan kebijakan nasional yang akan memecahkan masalah kebahasaan di Indonesia. Masalah kebahasaan dibagi tiga, yaitu masalah bahasa nasional atau bahasa Indonesia, masalah bahasa daerah, dan masalah bahasa asing. Masalahmasalahnya, misalnya, pendidikan bahasa, penyebaran bahasa, pengembangan bahasa, pemakaian bahasa, antara lain seperti itu. Apakah ada panduan tertentu bagi P3B dari pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya? Ada. Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 70an, saya jadi sekretarisnya. Keputusan seminar inilah yang kemudian menggariskan pola kebijaksanaan bahasa nasional, sebagai pedoman. Yang datang ke seminar itu bukan hanya orang-orang P3B, tapi juga tokoh-tokoh bahasa di perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia, pokoknya lengkaplah pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap masalah kebahasaan di Indonesia, termasuk juga Menteri Pendidik-
21
an dan Kebudayaan sebagai sponsornya. Apa prinsip-prinsip utama yang diacu P3B dalam melakukan pembakuan bahasa Indonesia? Dalam pembakuan bahasa, prinsip utamanya adalah pemakaian bahasa yang hidup di masyarakat. Kemudian, pemakaian bahasa di kalangan intelektual, kalangan terpelajar, di dalam karya-karya budaya yang bernilai tinggi. Itulah yang dipakai sebagai pedoman. Maksudnya dibakukan di sini bagaimana? Apakah ada aturan tertentu? Oh, ada. Sudah keluar pedomanpedoman tertentu, seperti misalnya, di dalam penulisan, keluar Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, dalam peristilahan, keluar Pedoman Istilah, di dalam pemakaian makna kata, keluar Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam tata bahasa, keluar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Bagaimana hubungan antara pengembangan bahasa nasional dan pengembangan bahasa daerah? Maksudnya, apakah dalam proses pengembangan bahasa nasional dipertimbangkan juga pentingnya pengembangan bahasa daerah?
22
Pembinaan bahasa nasional itu kan komprehensif. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia saja, bahasa daerah juga, bahasa asing juga. Yang namanya masalah bahasa nasional adalah masalah bahasa di Indonesia yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Jadi ketiga-tiganya ditangani oleh Pusat Bahasa. Termasuk di dalamnya adalah memberi pedoman bagaimana menyerap kata-kata asing. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, apakah ada upaya untuk memelihara segala kekayaan kata, warna, dan ekspresi paling baik dan paling dinamik dari unsur-unsur bahasa maupun logat suku bangsa dan/atau daerah? Atau, yang ditekankan justru penghilangan sifatsifat khusus bahasa daerah dalam bahasa nasional? Tidak, justru sangat dipelihara itu. Cuma, caranya begini, dipersilakan orang berkompetisi memasukkan nilai-nilai bahasa daerah, lewat menulis, lewat berkarya bahasa apa pun. Nanti, yang bernilai tinggi, akan diangkat sebagai milik bahasa nasional. Tidak ada halangan. Sehingga sebenarnya dibuka kompetisi fair antar tiap daerah. Nah, bahwa sekarang masuk bahasa Jawa banyak, ya karena orang Jawanya banyak, orang Jawanya lebih pinter. Sebenarnya semua dipersilakan menulis di koran, menulis di majalah, memasukkan kata-kata daerah. Yang paling banyak frekuensinya diangkat menjadi bahasa Indonesia. Terus, selain kompetisi, apa usaha lain untuk mengintegrasikan bahasa daerah? Yah, kalangan terpelajar dari berbagai daerah diberi kesempatan seluas-luasnya mengusulkan materi bahasa yang
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
belum ada dalam bahasa Indonesia untuk dipertimbangkan di level nasional, apakah itu bisa dipakai atau tidak sebagai peristilahan ilmiah, misalnya. Nanti dicoba disebarkan di pusat, lewat media massa, lewat televisi. Kembali ke soal orang Jawa yang banyak tadi, apakah masyarakat dari suku lain belum punya perhatian yang besar terhadap bahasa Indonesia? Bukan belum punya perhatian besar. Mereka itu kurang berkarya, mengemukakan buah pikirannya, kurang mengemukakan karya-karyanya di media massa. Jadi kan tidak terserap kata-kata daerah itu. Yang banyak menulis itu orang Jawa, sehingga timbul memang suatu gejala kepekaan dari daerah-daerah lain yang selalu mengisukan adanya Jawanisasi dalam bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya semua pihak dipersilakan mengajukan usulan, karena kata-kata, atau hal-hal yang dibakukan, dalam bahasa Indonesia pertimbangannya frekuensi pakai. Katakata mana yang paling banyak dipakai. Bagaimana P3B menyebarluaskan hasil kerja yang dilakukan? Apakah ada kebijakan khusus dari pemerintah yang mengharuskan penggunaan bahan-bahan dari P3B di dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah? Mengharuskan sih tidak, tapi memberikan pedoman iya. Karena dalam pembinaan bahasa, keharusan itu tidak ada. Pedoman-pedoman itu dimasyarakatkan, seperti pedoman ejaan, kamus, tata bahasa baku, pedoman istilah disebarkan. Masalahnya sekarang, masyarakat mau ngga mengikuti pedoman itu? Ada juga penataran untuk guru-guru. Tapi, tetap saja ada kesalahan, ada pelanggaran, tetap juga tidak ditaati. Itulah kesulitan pembinaan bahasa. Bagaimana hubungan P3B dengan media massa? Secara tidak langsung dilakukan, karena redaksi media massa antara lain disarankan mengoreksi bahasa yang akan dikeluarkan media massa. Seperti misalnya, kata-kata daerah yang masuk dalam media massa selalu dicetak miring. Itu hasil-hasil editing dari media massa yang bekerja sama dengan Pusat Bahasa. Selain itu, ada juga semacam penataran untuk para editor. Tapi harus diingat, bahasa surat kabar dengan bahasa pemerintahan itu dua hal yang berbeda.
Apakah ada perbedaan besar antara bahasa Indonesia yang dipakai sebelum dan sesudah pemerintah Orde Baru, terutama dari segi kekayaan wacana dan gaya berbahasa? Oh, sangat banyak perbedaannya, karena bahasa Indonesia ini kan tergolong bahasa yang masih muda. Perkembangannya pesat sekali. Tiap era membentuk ragamnya sendiri. Seperti misalnya, ragam bahasa Indonesia Orde Baru itu sangat kuat Jawanya karena pemerintah pusat mencoba memasukkan konsep-konsep Jawa ke dalam sistem pemerintahan. Akibatnya, kata-kata Jawa banyak sekali. Secara tidak langsung itu menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Sebelum Orde Baru, misalnya, jaman Orde Lama, kata-kata yang membenci imperialisme itu sangat besar. Tapi, perbedaan dalam gaya bahasanya yang paling menonjol. Seperti misalnya, gaya romantis terdapat pada Orde Lama. Gaya metaforik sangat kuat dalam Orde Baru, berputar-putar juga, sehingga makna sebuah ungkapan itu tidak sama dengan makna katanya, harus ditafsirkan dalam konteks, siapa yang bicara dan untuk tujuan apa. Banyak orang yang melihat almarhum Presiden Soekarno mempunyai kemampuan berbahasa yang luar biasa baik dan cerdas. Apa pendapat Anda tentang bahasa yang digunakan Soekarno? Saya kira itu benar, ya, karena Soekarno itu mempunyai retorik yang sangat kuat, retorik untuk mempersuasi pendengarnya, gaya bahasa yang persuasif sekali, terutama untuk lisannya. Dia menggunakan keberulangan ungkapanungkapan, memberi tekanan yang sangat kuat pada kata-kata tertentu sehingga gaya Soekarno itu sudah monumental. Banyak politikus belakangan ini mencoba meniru. Cuma kesulitannya sering menggunakan bahasa Belanda, bahasa asing. Tapi yang dianggap sebagai ahli retorik di Indonesia, retorik aplikatif, ya Soekarno itu. Dia sudah punya paten sendiri sehingga ada gaya bahasa Soekarno kalau dari segi bahasa. Cepat sekali bisa diidentifikasi kalau ada orang yang meniru “Ah, itu kayak Soekarno!” Kalau dibandingkan dengan gaya berdakwah bagaimana? Sangat lain gaya dakwah dengan gaya Soekarno itu. Gaya dakwah itu kan seperti
POKOK
menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti dengan menjanjikan sesuatu setelah mati. Sedangkan gaya Soekarno itu membuat orang itu menjadi besar, merasa diri berharga, merasa diri hebat. Jadi, walaupun rakyat waktu itu miskin, kalau Soekarno sudah ngomong, bisa merasa kaya, bisa merasa hebat. Itu kan retorik saja. Ada pihak yang beranggapan bahwa bahasa hanyalah sekedar instrumen untuk menyampaikan gagasan, tapi ada pula yang berpendapat bahasa tidak bisa dipisahkan dari perubahan struktur sosial. Bagaimana menurut Anda? Kedua-duanya benar. Sebagai alat, ya, tapi alat apa? Alat untuk mewadahi, mengungkapkan, memetakan, menyimbolkan, mewakili sesuatu yang ingin dikomunikasikan? Sedangkan bahasa sebagai struktur, oh, itu sudah lama diungkapkan bangsa Melayu, “Bahasa menunjukkan bangsa”. Jadi, struktur kebudayaan, struktur nilai suatu bangsa, tampak pada bahasa. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat bagi perkembangan bahasa? Bagaimana mengatasinya? Yang paling kuat saya lihat adalah sikap terhadap bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia boleh dikatakan belum positif. Sikap positif itu kalau orang menghormati bahasa itu, kalau orang bersedia menggunakan bahasa itu, kalau orang bangga menggunakan bahasa itu, kalau orang prihatin terhadap bahasa itu. Ini yang sangat lemah di Indonesia sehingga sikap bahasa yang positif ke bahasa asing. Bahasa Indonesia dianggap tidak berharga, tidak patut dibanggakan, ini yang merupakan hambatan utama. Itu juga saya kira karena kesalahan pemerintah tidak memberikan himbauan, atau memberikan ganjaran kepada pemakai bahasa Indonesia yang baik dan tidak mendukung yang menggunakan bahasa Indonesia yang jelek. Seperti misalnya, kalau seseorang mencari pegawai, bukan penguasaan bahasa Indonesianya yang diperiksa, tapi penguasaan bahasa Inggrisnya. Kalau orang ingin naik pangkat, mestinya kan penguasaan bahasa Indonesianya dipertimbangkan, sehingga orang mau belajar bahasa Indonesia. Selain itu, saya kira karena masalah ekonomi. Dana untuk pembinaan bahasa itu sangat kecil dan SDM tidak tertarik terjun ke bidang itu.
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
POKOK
Ada hambatan politiknya juga. Yang dinamakan Pusat Bahasa itu kan saya kira semacam bendera saja yang diadakan supaya ada begitu, kelengkapan saja, tapi ngga pernah diberikan fasilitas yang memadai. Apakah ada nilai-nilai tertentu yang patut ditanamkan dalam pengajaran bahasa, baik bahasa nasional maupun bahasa daerah? Ya, ada. Kan selalu orang kembali pada Sumpah Pemuda dan nyanyian Satu Nusa Satu Bangsa itu, lalu nilai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai nilai formal sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya. Itu nilai-nilai yang sebenarnya merupakan das solen, yang das sein-nya jarang dilakukan. Dengan semakin terbukanya media massa Indonesia muncul gaya berbahasa yang campur baur antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahasa resmi dan bahasa “gaul”, di berbagai medium komunikasi, terutama di acara-acara televisi. Apa pendapat Anda tentang gaya bahasa seperti ini? Apakah itu menunjukkan semakin demokratisnya bahasa Indonesia, atau justru sebaliknya, semakin miskin? Televisi itu media komunikasi massa yang melayani banyak kepentingan. Jadi, ada kepentingan formal, kepentingan bisnis, kepentingan politik. Dia harus bisa melayani dengan baik, menyediakan media untuk masing-masing kepentingan itu. Lalu, mereka yang di bidang institusi resmi, menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia resmi. Seperti misalnya, pidato kenegaraan, ceramah-ceramah atau informasi yang disampaikan oleh seorang pejabat menteri misalnya, mesti bahasa Indonesia yang resmi, bahasa Indonesia yang baku, tidak akan menggunakan terlalu banyak campur-campur. Sekarang, kepentingan bisnis yang menggunakan bahasa. Bisnis yang bisa menarik keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang ada juga kalangan generasi muda. TV itu akan menarik kalau mereka diberi kesempatan untuk berbahasa seperti kelompok mereka. Jadi sulit sekali diatur televisi, misalnya harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Konyol nanti itu, ndak laku nanti TV itu, karena TV melayani kepentingan banyak pihak. Sehingga fakta menunjukkan TVRI kurang
23
laku karena tidak disukai oleh generasi muda, oleh kalangan bisnis, itulah fakta. Jadi, sekali lagi, TV tak bisa diatur seperti itu. Gaya bahasa seperti contohnya: “Sebetulnya kalau cuma ngomong sih kita fine-fine aja” itu kan bahasa gaul. Itu bagus untuk sinetron, untuk anak-anak muda, atau pejabat yang sedang santai. “Kita sudah di-recommend untuk jalanin kerjaan yang ada dulu”, jelas ini bahasa generasi muda Jakarta sekarang. Ngga apa-apa, wajar-wajar saja. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia di masa Orba sangat memungkinkan terjadinya miskomunikasi karena cenderung bermakna ganda, membingungkan, dan penuh tata krama. Di wilayah politik terutama, banyak sekali konsep-konsep abstrak, seperti “demokrasi”, “partisipasi rakyat”, yang tidak pernah dijabarkan dengan baik. Bagaimana menurut Anda? Di masa Orba terjadi miskomunikasi, bermakna begitu. Barangkali ada kesalahan antara harapan dan fakta, ya? Orba harus dipahami sebagai kebudayaan Jawa. Budaya Jawa itu berlapis lapis, tidak langsung. Yang bisa memahami, yang bisa berkomunikasi dengan baik, ya, yang persepsi budaya Jawanya bagus. Jadi antara Soeharto dengan kelompoknya itu tidak akan ada miskomunikasi, karena mereka itu sudah biasa berputar dahulu atau secara tidak langsung menyampaikan apa yang mereka maksudkan sebenarnya. Bagi yang non-Jawa, ya, agak sulit itu, bermakna ganda, membingungkan. Itu sering tidak berani diungkapkan. Di dalam budaya Orba itu Jawanisasi. Orang harus bisa menangkap yang tersirat, yang tersorot, bukan hanya yang tersurat saja. Malahan dari segi seni berbahasa, itu sangat tinggi, karena selalu diungkapkan secara tidak langsung. Bagi mereka yang bukan orang Jawa, wong Jawa itu dianggap membingungkan, bermakna ganda. Karena suatu kata dalam konteks Jawa itu bisa macammacam artinya. Demokrasi bisa berarti kekuasaan pejabat. Partisipasi rakyat bisa berarti partisipasi anaknya pejabat. Itu kontekstual sekali. Ndak bisa dicari di kamus itu. Itu memang salah satu perkembangan bahasa di dalam perjalanan sejarah. Dalam kondisi sosial politik yang kacaubalau dewasa ini, apakah bahasa Indonesia masih punya peran yang signifikan? Apakah bahasa Indonesia masih punya
24
daya membebaskan dan mempersatukan berbagai kekuatan politik dan suku bangsa yang ada di negeri ini, seperti yang dicita-citakan para pendiri republik? Saya kira itu jelas, karena suatu bangsa yang mempunyai bahasa, betapa pun brengseknya keadaannya, dalam sejarahnya selalu signifikan. Bahasa itulah sebagai penanda eksistensi bangsa itu. Nah sekarang, bangsa Indonesia salah satu ciri keindonesiaannya itu bahasa Indonesia, yang bisa mempersatukan semua etnik di Indonesia, bisa memberikan pembebasan-pembebasan di dalam berkomunikasi antar etnik. Cuma sekarang, karena bahasa Indonesia masih merupakan bahasa kedua, masing-masing masih menafsirkan dengan konsep bahasa pertama. Sering terjadi salah paham. Masih sulit dikatakan mempersatukan. Tetapi, sebagai suatu sarana nasional pasti itu sangat diperlukan. Itulah dahulu sejarahnya kenapa bahasa Indonesia itu dipakai oleh generasi pendiri bangsa itu. Jadi secara kenyataan, misalnya, kita lihat signifikansi bahasa Indonesia itu kalau kita sudah pergi ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan bahasa Indonesia-lah kita membuat diri seperti orang Indonesia. Mengapa perlu dibuat kebijakan nasional untuk pembinaan dan pengembangan bahasa? Untuk apa kebijakan nasional itu? Namanya saja kebijakan nasional. Itu karena bahasa ini selalu berkembang dan selalu berubah, maka dikhawatirkan terjadi perubahan yang divergen. Seperti misalnya, pecahnya bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu, Brunei, Malaysia, itu perkembangan yang divergen. Supaya bahasa di Indonesia ini tetap bahasa Indonesia, maka dibuatlah kebijakan nasional sehingga perkembangannya itu konvergen. Nah, itu salah satu latar belakang filosofisnya. Terus kemudian, latar belakang praktisnya, menghadapi berbagai ragam bahasa Indonesia yang berada di bumi Indonesia begitu luasnya; ada ragam lokal, ada ragam etnik, ada ragam profesional, macam-macam ragam, sekarang diperlukan satu ragam baku. Sebagai rujukan, ya, sebagai tolok ukur. Setidak-tidaknya bisa ditemukan sesuatu yang bisa dipakai untuk menentukan benar-salah. Itu kebijakan nasional bahasa. Bisa mengatur bahasa itu. Apakah itu akan menjadi suatu yang satu bahasa media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
atau tidak itu soal lain. Ini sebenarnya meniru Perancis, Academie Francais. Nah itu sebuah akademi yang membina bahasa Perancis sehingga ada satu pedoman yang bisa ditoleh bersama. Contoh yang riil adalah perlunya kebijaksanaan bahasa nasional untuk EYD. Ejaan Yang Disempurnakan itu sudah diikuti keputusan kebijaksanaan nasional. Begitu juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku. Itu hasil kebijaksanaan nasional. Bagaimana realisasinya di masyarakat itu kan ada prakteknya. Masing-masing orang punya disiplin. Sehubungan dengan itu, sekaligus menjawab sangat perlu pembakuan bahasa. Setidak-tidaknya ada yang dilihat, dibayangkan adanya bahasa Indonesia baku. Untuk menentukan salah-benar, bukan baik-buruk lho, salah dan benar secara kebahasaan. Baik-buruk itu masalah lain lagi di dalam berbahasa. Karena baik-buruk itu tergantung pada siapa yang diajak omong, tentang apa, dalam situasi apa. Kalau bahasa baku, itu soal benar-salah. Yang penting itu ada pembakuan dalam bahasa resmi, bahasa birokrasi, kemudian dalam sekolah. Kalau sekolah tidak punya bahasa baku, ya repot, apa yang mau diajarkan? Itu perlunya pembakuan bahasa. Mengapa perlu ada pembakuan bahasa? Ada penelitian tentang bahasa Indonesia Tionghoa yang mengatakan bahwa bahasa kelompok khusus seperti ini malah perlu dilestarikan. Bagaimana menurut Anda? Bahwa bahasa Indo-Tionghoa itu perlu dilestarikan, ya itu mesti saja toh. Kalau itu dihilangkan, ya Indo-Tionghoanya hilang juga. Penanda atau indikator keberadaan Indo-Tionghoa adalah bahasa Indo-Tionghoa. Kalau ingin mempertahankannya sebagai kelompok, bahasanya harus dipertahankan. Sama saja misalnya dengan kelompokkelompok lain. Itu kan pandangan seorang linguis, bukan pandangan seorang pembina bahasa. Kalau pembina bahasa dituruti semua keinginannya, maka ia bunuh semua ragam bahasa dan gunakan satu bahasa baku. Ya itu tidak mungkin toh, karena bahasa itu konvensi. Tiap kelompok mempunyai konvensinya masing-masing. Tapi ada satu pedoman pokok yang diacu yang disebut bahasa baku, dan siapa yang mengurusi bahasa baku itu, ya kebijakan nasional itu. 0
ULASAN
Memplesetkan Bahasa, Memplesetkan Bangsa
Alia Swastika Plesetan bukanlah sekadar humor atau bahan lawakan. Ia adalah sisi lain dari politik negara terhadap bahasa nasional yang telah begitu lama menjelajah dalam kehidupan sehari-hari warga biasa. Dalam plesetan, kita akan menemukan cara pandang rakyat biasa terhadap persoalan sosial politik di sekitarnya, yang mereka ungkapkan dalam bentuk permainan bahasa. Tulisan ini akan mengambil kasus bagaimana masyarakat Yogyakarta, dan mungkin akan melebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, memposisikan plesetan sebagai permainan bahasa yang punya makna politis dan kebudayaan tertentu. Sebuah resistensi terhadap bahasa Indonesia—dalam kasus ini, juga terhadap bahasa Indonesia ala Jakarta—yang harus mereka lahap sehari-hari di sekolah, di kantor-kantor, dan dalam artikel-artikel di media massa. Segala hal yang berbau plesetan pernah sangat populer pada pertengahan 1990an, tahun-tahun ketika isu politik— khususnya isu tentang suksesi—mulai memanas, tahun-tahun menjelang jatuhnya rezim totaliter. Beberapa tayangan humor dan lawak yang ditayangkan di televisi tak lagi mengandalkan slapstick, melainkan mulai menggunakan gaya plesetan. Pada saat itu, tentu saja yang banyak menjadi sasaran plesetan adalah isu-isu politik, meski ini dilakukan dengan begitu kabur dan diam-diam. Dalam plesetan inilah kita dapat menemui ungkapan ketidakpuasan dan frustasi masyarakat terhadap kekuasaan yang sifatnya sangat kontekstual. Yogyakarta dan Kecenderungan Plesetan Di Yogyakarta, plesetan bukanlah sesuatu yang baru. Permainan bahasa ini sudah diakrabi masyarakat sejak mereka masih kecil. Sangat sulit untuk dapat menyebutkan kurun waktu, karena seperti biasanya, tak banyak data-data yang bisa digali untuk melihat sejak kapan permainan bahasa ini muncul dalam tradisi masyarakat Jawa. Yang jelas, generasi pelawak asal Yogyakarta yang kini telah berusia senja, masih saja fasih melontarkan plesetan dalam dialog-dialog mereka. Begitu juga anak-anak kelas lima SD yang mulai menggunakan plesetan sebagai cara baru untuk menjalin ikatan pertemanan yang lebih luas dan lebih akrab. Plesetan selalu menjadi cara masyarakat menciptakan suasana yang penuh tawa, sejenak melepaskan mereka dari tekanan hidup sehari-hari. Bahkan sampai kini, ketika Yogyakarta sudah semakin dipadati mahasiswa dari luar daerah, plesetan masih bertahan di sela gempuran bahasa Indonesia ala Jakarta yang nyaris terdengar setiap hari di radio-radio. Malah menariknya, mahasiswa “pendatang” ini memerlukan kemampuan untuk bisa bermain plesetan agar dapat diterima di kalangan mahasiswa “tuan rumah”. Tanpa mengetahui arti kata-kata yang terlontar selama
permainan plesetan berlangsung, seseorang tidak akan dapat masuk ke dalam suasana akrab yang tercipta pada waktu itu. Di sini terlihat bahwa seiring dengan perkembangan berbagai pola interaksi antar-warga, kemahiran dalam permainan bunyi kemudian menjadi salah satu modal yang penting bagi masyarakat Jawa dan para pendatang untuk tetap menjaga kedekatan dan keakraban satu sama lain. Beberapa orang pengamat linguistik meyakini bahwa kemahiran orang Yogya bermain plesetan ini disebabkan karena budaya mereka yang senang berdebat, senang tampil unik (berbeda dibandingkan yang lain), juga kesenangan masyarakat untuk mengobrol dan melepas humor. Di Yogyakarta, kebiasaan bersantai dengan lingkungan sepergaulan diwujudkan dengan kegiatan kumpul-kumpul sambil berbincangbincang tentang banyak hal (dalam istilah Jawa, ngobrol ngalor ngidul). Dari situlah kemudian muncul dialog yang beragam, cara menyampaikan ujaran-ujaran yang beragam, sampai lahir plesetan. Selain itu, ada karakter khas yang selama ini selalu dilekatkan pada orang Jawa yang agaknya turut mempengaruhi kebiasaan plesetan mereka. Orang Jawa dianggap tidak konfrontatif, tidak suka berterus terang, dan menjaga harmoni. Jika tidak setuju atau tidak suka akan sesuatu, orang Jawa cenderung menyampaikannya dengan bahasa yang halus untuk menghindari perseteruan dan rusaknya harmoni. Karenanya, kritik kemudian disampaikan dengan kemasan lain, yang diharapkan tidak membuat pihak yang dikritik tersinggung. Humor adalah salah satu bentuk yang dianggap paling efektif. Bagi orang Jawa, permainan bahasa menjadi salah satu cara wong cilik menyikapi zaman Edan—suatu zaman yang diramalkan oleh pujangga Ronggowarsito ketika keteraturan, norma-norma, keamanan, atau harapan mengalami gangguan dan mungkin melenyap. Permainan ini diwujudkan dengan melakukan othak-athik kata-kata sehingga gathuk (cocok). Plesetan dan Bahasa yang Militeristik Ketimbang merunut kedekatan masyarakat sehari-hari dengan plesetan, tampaknya lebih mudah menelusuri sejarah keterlibatan plesetan di panggung-panggung dagelan rakyat. Mbah Guno, seorang seniman senior di Yogyakarta, melihat bahwa di panggung hiburan, plesetan sebagai bahan dagelan muncul dari kebiasaan guyon (bercanda) dan ngomong waton (berbicara seenaknya) di grup musik milik Kodam Diponegoro, “Tunas Kasih”, yang populer di 1970an. Baru setelah itu, plesetan ini menjadi permainan bahasa yang populer di kalangan seniman Yogyakarta. Dari sumber ini, penulis melihat bahwa kebiasaan yang tidak disiplin dan melenceng dari ketertiban berbahasa pada umumnya justru muncul dalam sebuah institusi yang dikenal memegang teguh
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
25
kedisiplinan, mengindoktrinasi anggotaanggotanya untuk menjadi sosok-sosok yang tertib, tegas, dan tampil angker. Disiplin militer dalam kehidupan sehari-hari ini tampak juga dalam bahasa. Kata-kata semacam “Hormat, grak!” atau “Siap!” selalu diucapkan dengan sikap tubuh tertentu yang menunjukkan kedisiplinan dan kesigapan. Bahasa yang hidup dalam barak-barak militer adalah bahasa yang tertata, tegas dan—menurut pengamatan penulis—‘patuh’ terhadap atasan (yang karenanya menjadi mapan dan tidak terbuka). Kepenatan dan frustasi menghadapi tata-tertib bahasa semacam itulah yang memunculkan perlawanan dalam bentuk permainan kata, meskipun saat itu hanya ditampilkan terbatas pada panggung hiburan. Plesetan selalu mencoba mengusik kata-kata yang sudah terlanjur mapan, atau bahkan dengan terang-terangan menjadikan hal-hal yang berkesan serius menjadi lelucon. Misalnya saja, di Yogyakarta ada kelompok lawak yang menamakan dirinya LBH. Kalau dalam pengertian umum, LBH adalah singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum, bagi kelompok ini LBH menjadi kependekan dari Lembaga Bantuan Humor. Saat kelompok ini mengisi acara HUT TVRI Yogyakarta yang diselenggarakan di Monumen Yogya Kembali (Monjali), mereka memelesetkan slogan TVRI yang berbunyi: “TVRI Menjalin Persatuan dan Kesatuan” menjadi: “TVRI Monjali Persatuan dan Kesatuan”. Dalam percakapan sehari-hari di kalangan mahasiswa, misalnya, penulis mendapati istilah-istilah semacam DOM (Daerah Operasi Militer)”, polisi, ataupun Primus biasa digunakan dalam percakapan antar-kawan dengan memberikan makna baru untuk kata-kata itu yang bermaksud menyindir makna aslinya. Kata DOM mereka gunakan untuk menyebut tindakan yang kejam atau untuk menyampaikan 26
ancaman (“Kalau kamu terus membantah, ku-DOM kamu nanti!”). Singkatan ini mereka pakai ketika keadaan di Aceh mulai memanas, dan pemerintah berencana menetapkan wilayah tersebut sebagai Daerah Operasi Militer (sebuah tindakan yang mereka bayangkan bisa melahirkan tragedi kemanusiaan atau pembunuhan massal). Sementara polisi mereka plesetkan menjadi akronim dari “Pokoknya Lihat Situasi”, karena menurut mereka, polisi, terutama polisi lalu lintas, selalu berusaha mendapatkan uang tambahan dengan mencari-cari kesalahan para pengendara sepeda motor. Sedangkan Primus sesungguhnya adalah nama seorang aktor idola remaja berwajah tampan. Dalam guyonan sehari-hari, Primus menjadi akronim dari “Pria Mushola”, sebuah identitas yang dilekatkan pada remaja-remaja pria yang alim. Dari contoh-contoh di atas kita mendapati bahwa orang-orang yang terbiasa melakukan plesetan harus punya modal pengetahuan yang luas dan mengikuti perkembangan wacana yang beredar di kalangan masyarakat umum. Jika masih menggunakan isu lama yang tidak lagi populer, plesetan yang dilontarkannya akan dianggap ketinggalan zaman. Di sini tampak bagaimana plesetan menjadi representasi respons masyarakat awam terhadap isu-isu sosial-politik-kebudayaan yang kompleks yang sifatnya aktual. Dagadu dan Basa Walikan Pada 1994, di Yogyakarta muncul fenomena baru dalam hal plesetan. Sekelompok mahasiswa UGM mendirikan perusahaan kaus oblong kecil-kecilan yang mereka tawarkan sebagai cinderamata alternatif dari Yogyakarta. Oblong yang mereka produksi kemudian dinamai “Dagadu” dengan logo mata. Kata dagadu sebenarnya adalah makian khas masyarakat Yogya yang berarti ma-ta-mu. Rumus mengganti kata matamu dengan dagadu adalah rumus basa walikan—salah satu variasi plesetan khas Yogyakarta. Bagi orang luar Yogya, untuk dapat mengerti basa walikan ini tidak cukup dengan mengerti bahasa Jawa saja, melainkan ia harus menguasai 20 karakter dasar huruf Jawa. Seperti halnya permainan bahasa yang lainnya, basa walikan ini adalah perayaan kelas bawah terhadap identitas mereka. Lewat bahasa mereka mengukuhkan keberadaan mereka—karena di luar wilayah itu, mereka tidak pernah diakui media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
keberadaannya. Mereka menggenggam sesuatu yang benar-benar mereka miliki, dan keluar dari disiplin-disiplin yang dibangun kelas yang lebih mapan. Dahulu, basa walikan menjadi bahasa yang digunakan preman-preman untuk melakukan komunikasi antar mereka dan menyampaikan informasi-informasi penting yang tidak boleh diketahui pihak lain, demi melindungi mereka dari para penegak hukum. Karenanya bahasa ini sering juga disebut basa maling (bahasa pencuri), basa sacilad (bahasa bajingan) atau basa gali (bahasa preman). Meski ada banyak desakan dan bahkan pemusnahan yang dilakukan aparat terhadap preman, salah satunya peristiwa Penembakan Misterius pada 1983, bahasa yang mereka gunakan ini justru terus berkembang dan meluas. Masyarakat awam mulai mengambil bahasa ini untuk mencari nuansa yang lain, untuk menemukan cara yang berbeda dalam menyampaikan kritik dan ekspresi perasaan mereka. Basa walikan tiba-tiba menjadi bahasa yang enak saja digunakan dalam kehidupan seharihari dengan lingkungan yang sudah diakrabi. Dan keputusan menjadikan “Dagadu” merek kaus oblong ternyata menjadi satu politik berbahasa tersendiri yang mengangkat citra bahasa kelas bawah ini menjadi bahasa yang bisa masuk ke pusat perbelanjaan ber-AC, atau melekat pada punggung orang-orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Semenjak popularitas kaus oblong Dagadu meningkat, banyak orang yang awalnya tidak memahami basa walikan jadi tertarik untuk bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Plesetan, termasuk juga basa walikan, memang akhirnya menjadi komoditi. Ia hadir dalam budaya massa yang lebih luas, dan menjadi ikon dalam budaya pop khas Yogyakarta. Panggung-panggung lawak di Yogyakarta selalu digarap dengan konsep plesetan, diberi tajuk acara yang berbau plesetan, misalnya, “Gerr satu kita teguh, Gerr cerai kita runtuh”. Beberapa kelompok musik menggunakan basa walikan dalam syair lagu-lagu mereka, misalnya salah satu grup beraliran rap menciptakan lagu berjudul “Pabu Sacilat” (Asu Bajingan). Selain Dagadu, muncul pula beberapa perusahaan kaus oblong yang menggunakan formula yang sama. Warung-warung makan di pinggir jalan menggunakan formula plesetan yang terasa ‘mengejek’ halhal yang lebih mapan (“Kentuku Fried Chicken”, atau “Kenchick” [dibalik
chicken]). Bahasa yang lahir dari kelompok bawah ini justru mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan bahasa Jawa yang adiluhung. Buktinya, bahasa Jawa yang dikatakan sebagai budaya tinggi itu kini justru ditinggalkan, dilupakan, dan cuma menjadi rujukan sejarah. Resistensi dan Eksistensi Apakah kemunculan bahasa pinggiran ke kalangan yang lebih luas pada akhirnya menghilangkan nilai-nilai awal yang melahirkan bahasa ini? Jawabannya bisa jadi ya, jika kita hanya melihat persoalan ini dari satu sudut pandang. Bahasa menjadi alat untuk mengkomunikasikan maknamakna tertentu dalam lingkup masyarakat yang tercakup dalam sebuah konvensi sosial tentang simbol-simbol verbal. Makna itu tentu saja hilang saat bahasa yang digunakan oleh satu kelompok tertentu diadopsi dan digunakan oleh kelompok lain. Namun dengan menggunakan sudut pandang yang lain, kita bisa melihat bahwa bahasa (pinggiran) sebagai resistensi akan selalu hidup selama ada kelompok yang melakukan hegemoni dan menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Jadi, meskipun ia berada di dalam wilayah budaya populer yang penuh dengan eksploitasi kaum kapitalis sekali pun, bahasa-bahasa pinggiran ini menunjukkan perlawanan terhadap sesuatu. Entah kebosanan mereka akan kehidupan yang semakin sulit dan menekan, harapan-harapan yang semakin sukar diwujudkan, ataupun hilangnya ruang-ruang bagi mereka untuk berinteraksi dengan hangat. Bahasa menjadi cara bagi orang biasa untuk menunjukkan eksistensinya dalam pelbagai perangkat aturan yang ditetapkan kelompok penguasa. Semakin bahasa di-disiplinkan, akan semakin besar kemungkinan adanya resistensi terhadap pendisiplinan itu. 0 Bahan Bacaan: Latif, Yudi dan Ibrahim, Idy Subandi. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. (Bandung: Mizan, 1996) Majalah Balairung, “Membaca Ekspresi Yogya”, edisi 30/th. XIV/1999 Majalah PRISMA, No. 1, 1996 Wijana, I Dewa Putu. Wacana Dagadu, Permainan Bahasa, dan Ilmu Bahasa. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2003
Alia Swastika, editor KUNCI Cultural Studies Center
POKOK
POKOK
ULASAN
Catatan Kecil
Budaya dan Olahraga Bahasa Sport Tidak Sportif in memoriam Njoto, penasihat PSSI
Hersri Setiawan Dunia “sport” dengan dunia “budaya” dalam arti sempit, lebih sempit lagi bahkan dunia “seni”, sungguhnya memang berbatasan tipis saja. Ketika masih di dalam “jaman Lekra” dulu, tentu saja di “daerahku sendiri” Yogyakarta dan Jawa Tengah (di daerah lain tentu saja aku tidak tahu!), kami sering dihadapkan pada pertanyaan yang sulit dijawab, misalnya, pencak silat itu termasuk olah raga murni atau seni olah raga? Kalau olah raga murni, mengapa sering disebut sebagai “seni bela diri”? Juga karate, yang jelas-jemelas adukuat (katakanlah kuatnya tenaga dalam). Mengapa di atas pintu tempat latihannya dipasang papan bertuliskan: Seni Bela Diri Karate, Yudo, Yuyitsu? Begitu juga permainan kartu “bridge” dan permainan catur, olah raga otak — otak kok berolah raga? — atau salah satu cabang seni dalam ilmu? Bisa saja orang menjawab — ya, “bisa saja”! Maka dicobanya memisah antara “art” (seni) dari “ars” (kiat). Apakah ini bukan soal dimensi nuansa saja? Dahulu kala, konon kata sahibulhikayat, tatkala “olimpiade” pertama diselenggarakan di Yunani tahun 776 SM, tontonannya hanya satu saja, yaitu lomba lari sepanjang satu arah di dalam stadion, namanya dromos (lihatlah Chamber’s Twentieth Century Dictionary). Puluhan tahun kemudian, 724 SM, selain lomba tunggal itu ditambah lagi dengan “dromos bolakbalik”, namanya diaulos — konon sekitar sama panjang dengan lomba lari 400 meter sekarang. Empat tahun kemudian (olimpiade itu diadakan sekali tiap 4 tahun) ditambah lagi dengan dolichos, lomba lari jauh, kira-kira sama dengan 1.500 meter atau bahkan sampai 5.000 meter sekarang. Tahun 708 SM ditambah lagi dengan acara adu gulat dan pancalomba. “Seni adu gulat” tentu saja sejenis “seni pencak silat” pada kita, karena janganlah
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
lupa bahwa peradaban Yunani dan Romawi Kuno selain ditandai dengan pengembangan seni murni dan filsafat, juga pengembangan ilmu-ilmu kiat “jaya kawijayan”. Melatih uletnya kulit kerasnya ulang, menjadikan diri menjadi jawara yang “dugdeng”. Maka, dalam nomor-nomor pancalomba pertama itu pun terdiri dari lompat jauh, lempar tombak atau lembing, lempar cakra(m), jalan cepat, dan adu gulat. Aku teringat pada seorang Jawa yang “komunis dari sononya”, juga penulis Jawa baik gancaran maupun geguritan yang sangat subur, dan anggota pimpinan Lekra cabang Yogya. Ia bernama Darsono alias Mbah Dar alias Pak Ireng alias Ki Wungkul alias Pakdhe Dar, yang juga seorang pendekar dan guru pencak silat “Wetan Kali”, yaitu daerah Yogyakarta sebelah timur aliran Kali Code. Suatu hari akhir 50an di rumahnya di kampung Nyutran, berkata kepadaku: “Aku masih mampu (keconggah) lho, Nak, kalau kepepet mencelat naik ke bubungan, seperti yang ‘Nak kenal dari cerita-cerita silat itu!” Ujung jarinya menunjuk ke atas. Sampai olimpiade ke-77 (472 SM) semua pertandingan berlangsung dalam satu hari. Belakangan kemudian diperpanjang menjadi empat hari, dan malah di tambah satu hari lagi untuk upacara penutupan, pemberian hadiah, dan jamuan pesta bagi para pemenang. Sampai saat ini perempuan tidak boleh hadir, apalagi ikut bertanding, selain pendeta perempuan, Demeter, itu pun hadir sebagai penonton. Selain hanya laki-laki, semula peserta olimpiade juga terbatas untuk orang Yunani merdeka (dalam arti bukan budak), termasuk yang lahir di kawasan taklukannya. Para peserta lomba adalah atlet-atlet amatir, dalam arti hadiahnya “cuma” karangan bunga. Kemudian demi perolehan prestasi, sifat profesionalisme lalu menjadi menonjol. Para olah ragawan caloncalon peserta olimpiade lalu hidup-mati dari berolah raga (barangkali bisa dibandingkan dengan yang disebut “pekerja 27
olah raga” di negeri-negeri (pernah) sosialis seperti Uni Soviet dan RRT. Atlet menjadi lapangan kerja khusus, yang menuntut “pengabdian” penuh seperti halnya lapangan kerja yang lain-lain, bukan sekedar lapangan bersantai pengisi waktu kosong. Pada saat inilah sejarah profesionalisme di bidang olah raga bermula. Sementara itu, di jaman Yunani baheula ini ada upacara keagamaan yang berlangsung di kota Delphi, dipersembahkan bagi pendeta perempuan Apollo bernama Pythia, yang pernah mewartakan dakwahdakwahnya di kota ini (lihat kamus di atas). Dalam upacara ini juga disertai dengan lomba olah raga, delapan tahun sekali dan kemudian menjadi empat tahun sekali (sejak 582 SM), pada tahun ketiga sesudah setiap olimpiade tersebut di atas. Namun kekhususan “Olimpiade Phytia”, di sini dimasukkan lomba acara yang non-olah raga. Misalnya, mulailah masuk dalam olimpiade versi Pythia ini lomba menyanyi, memainkan alat musik, dan berdeklamasi. Hadiah bagi para jawara berupa mahkota daun salam — daun perdamaian! Sekarang olimpiade modern abad kita, konon sudah sejak empat olimpiade terakhir, IOC (Panitia Olimpiade Sedunia) telah mengembalikan peristiwa pesta olah raga ini pada “khitah” olimpiade Phytia: memasukkan nomor-nomor budaya dan seni khususnya dalam acara, walaupun tidak semuanya dipertandingkan, melainkan “sekedar” dipamerkan — misalnya dalam hal benda-benda bersejarah, adatistiadat, penerbitan buku, dsb. Perihal yang patut disambut oleh Indonesia, yang untuk ini tidak ada kata “terlambat”. Tidak hanya mengirim olah ragawan untuk memburu medali. Tapi juga mengirim “pelangi budaya” sebagai titian Dewi Perdamaian antar-manusia sesama. Semoga! Dalam hubungan dengan tulisan singkat di atas itulah, aku lalu tertarik memperhatikan “dunia kebahasaan” dalam tulisan-tulisan tentang “dunia keolah ragaan”, baik yang berupa sekedar berita liputan peristiwa atau pun yang berupa komentar atau analisis jalannya peristiwa, atau peristiwanya itu sendiri. Tidak seorang bisa membantah sumbangan besar pers terhadap perkembangan bahasa — pada bangsa mana pun. Sumbangannya itu tidak saja di bidang penggunaan bahasa, atau dalam hal berbahasa secara efisien, tapi juga dalam hal penciptaan peristilahan baru. Tentu saja ada akibat ikutannya yang tidak positif, yang di satu 28
pihak bisa menjurus menjadi merusak bahasa dan di lain pihak bahkan merusak citra pers itu sendiri. Timbulnya apa yang disebut “koran got” atau “pers kuning”, juga terjadi dalam sejarah pers bangsa mana saja, bukan saja disebabkan oleh materi atau isi pesan yang (pinjam ungkapan Njoto) menggunakan adagium “anjing menggigit manusia” bukanlah berita, tapi sebaliknya “manusia menggigit anjing” itulah berita. Tapi selain oleh materi beritanya, juga oleh cara bagaimana berita itu disampaikan. Dalam hal ini tentu saja berarti, bagaimana si wartawan “memainkan” perbendaharaan katanya, sehingga ia berhasil menyajikan sebuah berita yang “mencekam” calon pembacanya. Contoh sangat banyak, dari yang masih tetap “dingin”, walaupun menyentak, sampai kepada yang terasa “panas” sensasional. Misalnya kalimat-kalimat begini: “Pangdam tanda tangani …” tidak usah “menandatangani”; atau: “toko Mas Jaya ludes disikat …” bukannya “toko Mas Jaya bius dicuri …” dsb., dll. Suatu ketika dalam paroh pertama tahun 60an di Kolombo (aku sungguh pernah di sana lho, walau pun mungkin sebagai pesuruh saja, untuk menggantikan Rivai Apin yang sibuk sebagai anggota BPH Jakarta Raya) berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan nasional Sri Langka melawan PSSI Banteng (karena ada tim PSSI lain, yaitu PSSI Harimau dan PSSI Garuda, saking banyaknya bintang lapangan hijau ketika itu). Duta Besar Asa Bafagih bersama Letkol. Gatot Soewagio (pimpinan rombongan) menjemput aku untuk ikut duduk di bangku suporter masyarakat Indonesia yang (ditambah saudara-saudara kita beberapa tokoh dari Perhimpunan Masyarakat Melayu Sri Langka; Ceylon Malay Association.) hanya berjumlah belasan orang itu. PSSI menang besar: 7-0! Pulang dari stadion kutulis reportase yang kuberi judul “Banteng Indonesia Tanduk Singa Singhala 7 : 0.” Coba, bayangkanlah itu! Tidak ada sepertinya dua kesebelasan sepak bola yang bertanding, melainkan dua ekor binatang hutan yang berlaga. Yang satu, Sang Banteng Indonesia, mendongak ke langit berjaya, dan yang lain, Si Singa Singhala, berdarah-darah dan perut jebol di sanasini. Reportase itu kukirim ke Sdr. Hardjito, redaktur Harian Rakyat “Sport dan Film” ketika itu. Tapi, sehabis itu, membaca kembali duplikat reportase itu, aku thengerthenger sendiri: “Mengerikan amat fantasiku!” media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
Yang terlukis pada angan-anganku ketika itu ialah tentang hewan banteng yang seakan diangkat sebagai binatang mitologi, lambang semangat bangsa Indonesia, berhadapan dengan singa, binatang mitologi bangsa Singhala. Dulu, dan dulu ini belum sangat lama, di empat sudut persada Monas yang berbentuk bujur sangkar itu, dipasang patung Banteng Merah yang besar dan gagah. Juga dalam lirik lagu “Jempol Indonesia”, yang bernada-nada “Di Timur Matahari”, ada satu barisnya yang berbunyi “Banteng Indonesia …” Jadi begitulah banteng dalam angan-anganku. Sedangkan hewan singa merupakan lambang resmi negara dan bangsa Sri Langka yang bermayoritas penduduk suku Singhala, konon satu bangsa yang diturunkan oleh Sing(h)a, binatang mitologi bangsa Singhala. Ia menjadi me-Manusia setelah menerima ajaran pencerahan dari Sang Sidharta Gautama (tentang ini pernah ditulis dan dipentaskan dalam bentuk drama panggung oleh Wickramasinghe, penulis terkemuka tahun 60an di negeri ini). Aku tidak tahu bagaimana “bahasa pers” di dunia olah raga ketika itu, lebih khusus lagi dunia olah raga sepak bola. Apakah kata-kata perbandingan yang kupakai di sana masih “sportif” atau tidak, justru sebagai perbandingan dalam tulisan untuk melaporkan tentang peristiwa “sport”. Tapi peristilahan itu kuajukan memang dengan sadar atas dasar simbolsimbol kemuliaan dan demi pemuliaaan bangsa yang bersangkutan. Bukankah Bung Karno juga pernah gegap gempita meramalkan: “Kelak apabila Banteng Indonesia telah bersatu dengan Gajah Putih dari Campa, Barongsai dari Tiongkok, Lembu Nandi dari India … ketika itulah fajar kemerdekaan negeri-negeri Asia akan terbit!” (silakan temukan dalam Mentjapai Indonesia Merdeka). “Sport” ialah “olah raga”. Tapi “sportif” tidak cukup diartikan sebagai “bersifat keolah ragaan”, karena di sana terkandung makna “sifat jujur”, “sifat kesatria”, fair, dan semacamnya. Bagaimanakah praktek kebahasaan dunia sport pada pers kita sekarang? Banyak peristilahan yang sama sekali tidak sportif sekarang ini bertaburan di dalam pemberitaan atau serba tulisan tentang dunia sport! Apakah ini gejala produk kebudayaan Orde Baru di bidang linguistik atau kebahasaan, khususnya kebahasaan dunia olah raga? Kalau begitu halnya, apakah dengan ini bisa diartikan
bahwa, “sifat jujur” atau “sifat kesatria” atau fairness (dengan segala maknanya: kejujuran, keadilan, kewajaran) di jaman Orde Baru sudah bergeser maknanya? Bayangkanlah! Bagaimana bisa terjadi, justru dari dunia sport lahir seribu satu peristilahan yang sama sekali tidak sportif? Bagaimana harus masuk di penalaranku, bahwa ada akronim “bonek”, dari kepanjangan bondho nekat (kata-kata Jawa untuk “bermodalkan nekat”), lahir dari dunia sport yang mestinya serba tidak nekat itu? Apalagi perbuatan mereka memang nekat. Apabila klub yang dijagokannya kalah, etalase toko akan hancur, gerbong-gerbong kereta api, tawuran antara kelompok sana dan kelompok sini terjadi! Istilah-istilah yang serba tidak sportif itu terdapat di dalam rubrik olah raga, khususnya sepak bola, pada hampir semua media massa, cetak maupun sibernetika. Inilah beberapa contoh, perhatikan katakata dalam bold, misalnya: “Bungkam Venus, Serena juara” (satusport); “Angie tekuk
unggulan keempat” (detiksport); “Spurs jungkalkan Pistons” (Astaga.com.sport); “Barcelona menelikung R. Huelva”, dan tentu banyak lagi (Barangkali juga bisa kita baca dalam Kompas, Suara Pembaruan, Pos Kota dan lain-lain?) Bukan hanya mencari hingar-bingar dalam kata-kata yang tidak sportif demikian, tapi adakalanya juga mencari “wah” dengan menggunakan kata-kata asing yang tidak kumengerti. Misalnya, dari reportase sepak bola, antara lain kutemukan begini: “umpan lambung dari rusuk kiri dikonversikan menjadi sebuah gol”. Tentu saja maksudnya jelas: “diubah”. Tapi manfaat apa, kata “ubah” yang sederhana dan pendek dirasa perlu diganti dengan “konversi” — seperti layaknya hak guna tanah saja?! Padahal akan lebih bagus, karena ini reportase sepak bola, kalau dilukiskan dengan gerak apa si Pemain itu berhasil “mengkonversikan” umpan lambung itu menjadi gol: “ditanduk”, dipotong setengah lutut, atau dengan tendangan akrobatik
POKOK
dan lain-lain? Apakah masalah kebahasaan ini perihal “sepele”? Kalau jawabannya “ya”, aku ingin bertanya lagi: kalau dunia sport dipenuhi peristilahan yang tidak sportif, bagaimana makna peristalahan dalam dunia lain-lain? Kata “korup”, misalnya, apakah mungkin sekarang sudah bukan lagi “korup” di “Jaman Sukarno”? Kata “vonis”, umpamanya, apakah sekarang tinggal sepatah wacana dunia “pengadilan”, notabene yang bukan lagi “pengadilan” di “Jaman Normal”? Lha, kalau memang sudah begitu, pantes aja amburadul seperti tidak ada wasit lagi di lapangan hijau kita yang bernama Republik Indonesia! Mari kita renung bersama-sama! 0 Kockengen, 26 Januari 2003. Hersri Setiawan, penulis menetap di Negeri Belanda
ROEPA-ROEPA BASA MARDIKA Mas Marco Kartodikromo: Dan semangkin tambah pengatahoean saja, bertambah berani saja bergerak dimedan kemadjoean. Sebab semoea kepandaian itoe hanja saja pandang seperti perkakas jang bisa menjampaikan toedjoean saja goena kebangsaan. Tetapi ada banjak orang jang berkepandaian mendjilat kotorannja orang-orang jang merampok kita. Kasian!! (“Dorongan oentoek Si Pendjilat”, Sinar Hindia, 28 Agoestoes 1918)
Moesso: Volksalmanak-volksalmanak dan almanak-almanak tani itoe soedah tentoe memoeat hal-hal wetenschappenlijk (scientific), jang kelihatannja tidak bersangkoetan dengan politik. Tetapi orang jang mengerti sedikit tentang politik mengerti djoega, bahwa boekoe-boekoe dan almanak-almanak itoe nomer satoe dibikin tidak memboeat mendidik Rakjat, tetapi boeat menjesatkan pikiran Rakjat. Sistematis, dengan cara jang haloes sekali boeah-boeah pikiran pihak sana dimasoekkan dalam kepala Rakjat. Soedah waktoenja kewadjiban kita melawan pengaroeh Balai Poestaka. Kita haroes menerbitkan boekoe jang perloe, boekoe tjerita sendiri, agar Rakjat tidak lepas dari pergerakan. Rakjat tidak terikoet aroes nasehatnasehat baik dalam boekoe dari Volkslectoeoer, karena batjaan terseboet tidak baik bagi rakjat djadjahan. (Api, 25 Djoeli 1925)
Rangsang dalam Kaoem Merah: Sebab moelai djaman doeloe sampai sekarang kita kaoem perempoean dipandang seperti perhiasan roemah tangga, dan mendjadi kepalanja koki. Tetapi boeat ini djaman itoe atoeran haroes dioebah. Boeat kaoem kita perempoean jang memang ada kewadjiban roemah tangga dan lelaki boleh melakoekan itoe pekerdjaan, tetapi boeat kaoem perempoean jang tidak mempoenyai itoe kewadjiban, haroes sekali menolong pekerdjaan kaoem lelaki jang menoedjoe kegoenaan oemoem. Kita tahoe ada banjak orang perempoean jang memilih doedoek diam sambil makan angin, meski perempoean jang terpeladjar djoega, ada jang soeka melakoekan itoe tabiat. Sekarang kita kira soedah waktoenja kita orang toeroet bergerak bersama-sama dengan saoedara kita kaoem lelaki. Kita tahoe djoega, bangsa kaoem kolot tentoe mesem mendengar perkataan ini. Baiklah kaoem jang tidak menjetoedjoei itoe kita sisihkan sadja.
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
29
PENGANTAR Didesak oleh keprihatinan terhadap kurangnya penghargaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia, Pramoedya Ananta Toer meluncurkan 11 tulisan berseri tentang sejarah bahasa Indonesia dan kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan negeri ini. Seri tulisan berjudul “Basa Indonesia sebagai Basa Revolusi Indonesia” ini dimuat di Lembaran Kebudajaan harian Bintang Timur, Lentera, hampir setiap minggu dari 22 September 1963 sampai 5 April 1964. Di tulisan paling awal Pramoedya menekankan, “Basa Indonesia merupakan bagian jang integral dari Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia tak bakal ada tanpa basa Indonesia. Sebaliknya basa Indonesia pun takkan mungkin ada tanpa adanja Revolusi.” Dalam edisi MKB kali ini, Tim Redaksi menerbitkan kembali 2 tulisan yang paling berkaitan dengan tema yang ingin kami angkat, yaitu hubungan antara bahasa Indonesia dengan gerakan nasionalis di sepanjang paruh pertama abad ke-20. Sengaja kami tidak mengubah ejaan yang digunakan dalam tulisan-tulisan di bawah agar pembaca bisa mengamati sendiri perubahan yang dilalui bahasa Indonesia sejak 20 tahun yang lalu.
Basa Indonesia Sebagai Basa Revolusi Indonesia Pramoedya Ananta Toer 20 Oktober 1963+ Apakah faktor2 jang menjebabkan basa pra-Indonesia dipilih oleh pers pra-Indonesia? Mengapa pada umumnja bukan basa daerah jang dipergunakan atau bukan basa Belanda? Beberapa faktor jang menentukan pemilihan ini jalah: a. Keadaan Sosial Ekonomi dimana Rakjat djelata pada umumnya tidak membatja ____ karena butahuruf. ____ jang membatja adalah bordjuis, jang karena kondisi sosial ekonomi mendapat keberuntungan pendidikan sekolah.* b. Politik Kolonial Dibidang Basa, dimana Belanda tidak rela disebarkannja basa Belanda di Indonesia, terutama Indo, akan terantjam hegemoninja dilapangan ilmu dan pengetahuan, serta dilapangan penghidupan. c. Watak Basa Pra-Indonesia jang terusmenerus demokratik jang memudahkan seseorang menempatkan dirinja dihadapan orang jang dilawannja bitjara, djadi tidak seperti halnja bila orang dari rumpun kebudajaan Djawa mem-
pergunakan basa-ibunja. Watak basa ini segera akan muntjul bila orang dari rumpun kebudajaan Djawa terpaksa mempergunakan basa pra-Indonesia . d. Politik Pintu Terbuka Hindia Belanda melahirkan sumber2 kehidupan baru diluar kampung halaman sendiri. Perpindahan tenaga kerdja jang berhimpun dipusat2 pekerdjaan melahirkan perkampungan2 baru dimana orang dari berbagai daerah bertemu dan hidup bersama. Sedang pertemuan antara orang2 dari provinsi2 kebudajaan jang berlainan membutuhkan lahirnja lingua-franca. Dalam pada itu golongan Indo jang tidak mendapatkan tempat dikantor2 pemerintah, serta bekas serdadu, pada bekerdja dipabrik2, jang djuga timbul disebabkan karena politik pintu terbuka tsb. Mereka adalah dari berbagai matjam daerah di Indonesia, jang dalam pekerdjaannja sehari2 djuga dipaksa dan menerima basa pra-Indonesia sebagai linguafranca. Pabrik2 ini pada umumnja adalah pabrik gula, teh, kopi, tembakau dan pabrik pengolahan barang pelikan. Politik pintu terbuka menjebabkan ramainja lalulintas perdagangan dan pada gilirannja menimbulkan perusahaan2 djasa: perhotelan, perbengkelan, binatu dsb. jang djuga menjebabkan semakin meratanja basa pra-Indonesia. e. Wudjut Dari Basa Pra-Indonesia itu sendiri jang dalam penggunaannja tidak meminta sjarat jang tinggi, sehingga siapapun bisa mempergunakannja asalkan berani. f. Sifat Basa Pra-Indonesia jang selalu mema’afkan penggunanja jang miskin perbendaharaannja, serta besarnja daja hisap serta dajakajal basa ini jang selalu mau menerima kata2 baru dari manapun djuga datangnja sehingga memudahkan para penggunanja dimanapun ia berada. Sifat ini hampir sama dengan jang dimiliki oleh basa Esperanto, hanja saja basa jang achir ini melakukan seleksi setjara terpimpin, sedang basa pra-Indonesia bukan sadja tidak terpimpin, bahkan setjara liberal. Perbedaan lain jalah daerah basa jang dipergunakan sebagai sumber. g. Kondisi Pers Pra-Indonesia sendiri pada pertengahan kedua abad jl.[jang lalu – ed.] itu jang kebanjakan dibiajai oleh perusahaan2 monopoli besar seperti gula, tebu, karet dan tembakau untuk memberikan pengertian kepada pedjabat2 pribumi — jang waktu itu belum mengenal basa Belanda — tentang berkah jang diberikan oleh perusahaan tsb. kepada penduduk dan dengan demikian antipati dapat ditumpahkan pada pemberontakan2 petani, jang pada waktu itu selalu timbul disebabkan perebutan tanah2 subur antara para petani kontra perusahaan2 monopoli besar. Kelak pemberontakan2 tani ini banjak djuga dilaporkan oleh sastra assimilatif sebagai kelandjutan daripada pemberitaan2 pers. Perusahaan monopoli terbesar didaerah2 perkebunan penting inilah jang mendjawab mengapa sudah dalam dekenla keenam abad jl.itu pers pra-Indonesia terbesar di Djakarta, Semarang, Surabaja, Jogjakarta dan Medan dan tidak hanja di Djakarta sebagai pusat pemerintahan. Dari situasi ini dapat pula difahami mengapa pembantu2 sk2 [surat kabar – ed.]. begitu meluas sampai didusun2 (perkebunan) jang sangat ketjil. Sebaliknja sk2 itupun disebarkan keperkebunan2, per-
+
Tulisan yang dimuat pada 20 Oktober 1963 ini sebenarnya dimulai dengan poin c. Watak Basa Pra-Indonesia Poin-poin sebelumnya dibahas pada tulisan yang dimuat pada 13 Oktober 1963. Tapi untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembicaraan, Tim Redaksi memasukkan 2 poin yang disebut terlebih dahulu. * Di teks asli yang disalin dari microfilm ada beberapa kata yang tidak jelas. Tim Redaksi mengosongkan bagianbagian yang memang sama sekali tidak terbaca.
30
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ISTIMEWA
POKOK
tambangan, pabrik2, dan sebagainja, dan tidak djarang pihak perusahaan membagikan kepada buruhnja jang bisa batja tulis untuk dibatjakan kepada sesama buruh. Djuga pers pra-Indonesia ini dalam komposisi pemberitaannja sangat sedikit menjoroti kedjadian luarnegeri, walaupun difahami karena belum adanja kantorberita pada waktu itu, tetapi peperangan2 kolonial selalu dihidangkan sedemikian rupa sehingga memberikan kesan jang tak meragukan lagi tentang keuangan balatentara keradjaan Belanda. Pergerakan Rakjat, apabila tidak diberitakan, maka ditafsirkan sebagai kerusuhan. Pada tengah kedua abad jl. ini, sekalipun banjaknja butahuruf, pers pra-Indonesia praktis telah mendjadi barang peradaban jang sangat biasa dipusat2 perusahaan monopoli ini. Pada pihak lain amanat jang dibawa oleh pers ini dibidang basa pra-Indonesia, ialah meningkatkan perbendaharaan kata pembatjanja, serta memberikan kesempatan untuk membatja, sehingga lambatlaun pers jang dimulai oleh kaum geredja kemudian oleh golongan Indo ini dianggap sebagai basa pra-Indonesia jang sempurna. Bukankah orang2 Indo (Belanda) jang mengendalikannja? Bukankah mereka “lebih pintar” dan “lebih tahu” daripada Pribumi? Dalam pada itu basa pra-Indonesia jang sebenarnja senjawa dengan basa pers praIndonesia, dan senjawa pula dengan pers pra-Indonesia sendiri dalam penggunaannja. Djurnalistik dalam perkembangan apapun, biasanja memerlukan ketjepatan bekerdja, sedang sjarat jang terpenting adalah ketertiban dlm. mengemukakan facts. Tidak ada waktu tjukup untuk memikirkan salahtidaknja menurut ilmubasa, sedang basa pra-Indonesia sendiri tidak meminta sjarat ilmubasa jang tinggi.
POKOK
Disamping adanja bantu-membantu antara pers dan sifat basa pra-Indonesia sendiri, pada masa itu kondisi pertjetakan belumlah sebaik sekarang, sehingga waktu mentjetak adalah lebih lama dan lebih meminta waktu daripada sekarang. Para redaktur biasanja djuga merangkap sebagai korektor, bahkan mengedar, bahkan djuga ikut mentjetak, sehingga segi2 ilmu basa praktis ditinggalkan samasekali. Ada sementara tulisan jang menilai basa pra-Indonesia sebagai basa Melaju Indo, dan nampaknja, melihat dari latarbelakang historik ini penilaian demikian tidak terlalu keliru. Bahkan Medan Prijaji jang terbit pada tahun 1907 masih mempergunakan “Melaju Indo” ini. Demikian faktor2 jang menentukan mengapa basa pra-Indonesia setjara “alamiah” mendjadi basa pers pra-Indonesia. Pers jang menggunakan basa daerah, terutama pers organisasi2 politik kooperatif, dalam perkembangan selandjutnja ternjata tidak bisa membawa kemadjuan pers pra-Indonesia, baik dalam peredaran umum maupun tirasnja, dan tetap mendjadi pers daerah. Sesuai dengan kedaerahannja, maka djarang sekali terdapat pers daerah jg mempunjai pengaruh didalam masjarakat. Dan sudah dalam dekenla keenam abad jang lalu basa pers Indonesia, sekalipun didalam pers dipelopori oleh golongan Indo, telah menundjukkan mempunjai dajadjangkau dan dajatjakup jang lebih luas daripada basa daerah. Basa Djawa jang pada waktu dipergunakan oleh hampir 40 djuta manusia, jakni djumlah terbesar suku bangsa Indonesia, didalam kehidupan pers tidak mampu mengambil peranan penting, karena hampir 40 djuta suku Djawa adalah bagian termiskin dari penduduk Indonesia waktu itu sedang harga surat kabar adalah terlalu tinggi
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
dibandingkan dgn di djaman kemerdekaan. Perlawanan Terhadap Pers PraIndonesia Tidak Pernah Berhasil. Apabila disini disebut pers Indonesia artinja tidak lain daripada pers jang menggunakan pra-Indonesia, bukan basa Melaju atau basa Belanda ataupun basa daerah. Dalam istilah ini tidak dibedakan apakah pers itu ikut bergabung ataupun menentang gerakan kemerdekaan nasional, karena jang djadi pegangan hanjalah basa jang dipergunakannja. Bisa djadi pers itu mendukung pendjadjahan Belanda, boleh djadi menentangnja, hal ini adalah kontradiksi2 jang terdapat dalam pers praIndonesia dan tidak mempengaruhi wudjut dari pers pra-Indonesia itu sendiri. Baik sebelum, terutama selama gerakan kemerdekaan nasional, pers pra-Indonesia setjara periodik terus-menerus mendapat serangan. Serangan ini terutama berasal dari pers Melaju, jaitu pers jang menggunakan basa Melaju sebagaimana ditentukan oleh politik basa Hindia Belanda. Apakah pers pra-Indonesia adalah pers borjuasi pra-Indonesia, maka pers Melaju adalah pers pegawai negeri atau tjalon pegawai negeri, jang disekolahkan, mendapat didikan basa Melaju sebagaimana dikehendaki oleh politik kolonial Hindia Belanda. Pers Melaju biasanja dipimpin oleh “ahli2” basa Melaju, artinja: guru atau bekas guru. Sudah sedjak disekolah mereka diadjarkan menghinakan basa pra-Indonesia tanpa diadjarkan kepada mereka untuk memahami alasan2 sosial daripadanja. Pers Melaju kebanjakan berbentuk madjalah mingguan, sedang jang pertamakali dihidangkan setjara Barat adalah Bintang Hindia jang diasuh oleh dr. Abdul Rivai dan Letnan Clackoner Broussen. Betapa pentingnja pers birokrat ini untuk menghadapi pers bordjuis pra-Indonesia dapat dilihat dari tjara penjebarannja jang meluas di kalangan para pegawai negeri, dengan pemerintah Hindia Belanda dibelakangnja jg membebaskan peredaran madjalah ini dari pembajaran porto pos. Madjalah ini diterbitkan dalam rangka usaha Hindia Belanda untuk melakukan “pasifikasi Atjeh”, sedang para pengarangnja terketjuali, Mara Sutan, adalah djago2 tua jang kelak merajai Balai Pustaka. Terdapat diantara pengarangnja tokoh pers Melaju Sumatera Timur Dja Endar Muda, dsb. Salim jang kelak terkenal sebagai “the grand old man” Hadji Agus Salim. Majalah ini djuga menjediakan ruangan untuk karangan-karangan berbasa Belanda, 31
diantara penjumbangnja terdapat djuga nama Kartini. Adanja perpisahan jang menentukan antara basa Melaju dari basa pra-Indonesia, ditambah dengan pemihakan jang berkuasa pada Basa Melaju untuk masa sepandjang penjajahan Belanda, menimbulkan komplikasi2 dan pertentangan2 didalam masjarakat hanja karena tjara menggunakan kedua matjam basa tersebut. Sekitar awal abad ini, apa jang disebut kaum terpelajar Pribumi adalah senjawa dengan kaum guru. Berbagai sektor kemadjuan praktis dirintis oleh kaum guru. Mereka ini adalah pendukung politik ethik Hindia Belanda jang menempatkan pengajaran pada tempat terpenting sebagai garapan utama dalam usaha mentjiptakan kemadjuan. Djuga dibidang pers, terutama di Sumatra—djadi berbeda dari di Jawa— mereka djuga mendjadi pelopor pers Melaju, diantaranja Dja Endar Muda dengan Pertja Baratnja, Mangaradja Salamabut dengan Pertja Timurnja jang terbit pada tahun 1905. 5 April 1964 Dimanakah rasia kekuatan basa pra-Indonesia ini? Bila diperhatikan bangun basa itu sendiri, akan nampaklah bahsa ia tidak meminta sjarat-sjarat jang biasanja dituntut dari kaum feodal, jakni pengkastaan, penghormatan wadjib dan formalisme. Pendeknja ia tidak meminta sjarat2 feodal, jang memisahkan seseorang dari seseorang jang lain hanja karena asal kelahirannja. Sebaliknja, ia digunakan dengan sebebasnja untuk mendapatkan effek persaudaraan dan persatuan jang sekokoh2nja serta seluas-luasnja dan sebanjak-banjaknja. Maka sebagai pegangan untuk dapat mengingat perkembangan jang luar biasa dalam sedjarah basa2 ini jalah bahwa praIndonesia telah terpilih oleh gerakan nasional sebagai basa persatuan karena itu sendiri memikul kodrat persatuan. Kalau Multatuli pernah mengatakan, bahwa basa Melaju adalah Italianja Asia Tenggara, mungkin asosiasinja terpaut pada perkembangan basa Italia jang hampir2 menjerupai basa pra-Indonesia. Persamaan itu terletak pada kenjataan bahwa basa Italia adalah sebuah dialek Latin jang berkembang sedemikian luas dan tjepatnja dan mendorong induk basa kesudut dan mendjadi steril, sedjak abad ke XIV, sedang basa pra-Indonesia jang tadinja sebuah dialek basa Melaju djuga berkem32
bang dengan luas dan tjepat sedjak abad keXVI dan mendorong induk basanja, jakni Melaju, ke sudut dan mendjadi steril. Tetapi Multatuli melupakan atau terlupa pada kodrat2 persatuan jang terkandung didalam wudjud basa pra-Indonesia. Sedjak penolakan sajap kiri Sarekat Islam sedjak tahun 1916, basa pra-Indonesia mengalami perkembangan extensif. Praktis seluruh madjalah daerah memberikan ruangan pra-Indonesia apalagi iklan jang hampir selamanja tertulis dalam basa praIndonesia. Dalam basa daerah serta Belanda tertulis hanja iklan jang bersifat kultural, misalnja buku2 dan penawaran djasa jang bersifat kebudajaan. Pada tahun 1923 bukan hanja sajap kiri Sarekat Islam jang menolak koperasi, djuga seluruh organisasi Sarekat Islam sendiri dengan penolakan Tjokroaminoto terhadap pengangkatannja sebagai wakil organisasi didalam Volksraad. Tindakan ini setjara politik membenarkan sajap kiri. Ini merupakan putusan didalam Kongres tahun 1923 itu, dimana nama Sarekat Islam diubah mendjadi Partai Sarekat Islam (PSI), dan dengan menggunakan sebutan “partai”, setjara resmi basa pra-Indonesia sebagai basa organisasi mulai mendjadi basa politik. Setahun sebelum itu Studenten Vereeniging di Amsterdam telah mengubah namanja djadi Perhimpoenan Indonesia. Djadi apabila pada tahun 1922 kata Indonesia telah mendjadi istilah politik. Perubahan nama ini — bagaimanapun kurangnja penilaian orang sampai dewasa ini, tidak dapat mengurangi makna politik jang hidup didalam pernjataan itu. Madjalahnja — Hindia Putera, diubah pula namanja mendjadi Indonesia Berdjuang. Bahwa jang memelopori penggunaan nama Indonesia adalah organisasi mahasiswa diluarnegeri, tidak lain daripada suatu perlambang, bahwa gerakan nasional dikodratkan untuk dipelopori oleh angkatan muda, sedang peristiwa sedjarah ini terdjadi di Nederland sendiri tidak lain daripada suatu perlambang, bahwa perlawanan terhadap imperialisme dipelopori justru didalam sarang imperialis sendiri. Djuga dalam madjalah tsb. lebih separoh daripada halaman2 jang tersedia dipergunakan untuk memuat tulisan2 berbasa praIndonesia. Sajang sekali bahwa madjalah jang patriotik ini hampir2 tak dapat ditemukan lagi di Indonesia. Padahal pada masanja, ia selalu berhasil dalam menerobos sidangsidang Dewan Rakjat, Dewan Hindia, Algemeene Secretaris, dan pers pra-Indomedia kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
nesia pada umumnja. Dengan digunakannja nama Indonesia oleh gerakan mahasiswa kita di Nederland tsb. sedjarah basa Indonesia sebenarnja telah bermula dan istilah pra-Indonesia, telah dapat dihapuskan. Tetapi karena penggunaan itu baru oleh satu organisasi sadja dan belum mendapat pengakuan dari semua organisasi jang punja kedudukan, basa pra-Indonesia sebagai basa Indonesia masih merupakan de facto. Setelah terdjadi perkisaran dalam kehidupan organisasi mahasiswa dan sekaligus menjetudjui politik non-koperasi, demikian pula halnja dengan Partai Sarekat Islam, hubungan “kekeluargaan” dengan imperialisme Belanda digunting putus, dan kedua organisasi tersebut mulailah setjara terang-terangan menghadapi imperialis Belanda sebagai musuh pokok. Pihak imperialis mempergunakan basa Belanda, pihak Nasionalis nonkoperatif dengan basa Indonesia, dan keadaan darurat sadja menggunakan basa Belanda. Pendeknja, publikasi2 mulai babak ini menggunakan basa Indonesia, karena ditudjukan kepada gerakan nasional, djadi tidak lagi seperti Budi Utomo, Indische Partij ataupun Insulinde jang menggunakan basa Belanda untuk mendapatkan perhatian dari imperialis Belanda, dan samasekali telah meninggalkan Sosrokardono, Casajangan, Iskandar, Kartini, Notosuroto dll. jg dapat dikatakan mutlak menggunakan basa Belanda untuk meminta perhatian. Perpindahan Sarekat Islam mendjadi Partai dan sekaligus menanggalkan politik koperasi, disebabkan karena perkembangan intern dimana sajap kiri makin lama makin berpengaruh dan menentukan. VSTP jang pada mulanja djuga menggunakan basa Belanda, pada tahun itu praktis telah menggunakan basa pra-Indonesia. Pada tahun 1924 organisasi2 kiri jang mutlak menggunakan basa pra Indonesia, VSTP, petjahan Sarekat Islam, Partai Komunis Hindia — terlebur mendjadi organisasi kiri jang terbesar dalam sedjarah, jaitu Partai Komunis Indonesia. Dengan demikian untuk kedua kalinja nama Indonesia mendjadi nama organisasi nonkoperatif. Dibawah pimpinan Partai Komunis Indonesia, politik non koperatif mendapatkan kemenangan jang gilang-gemilang, sekalipun sedjarah belum memberikan kemenangan mutlak. Tapi dibidang basa kemenangan golongan kiri berarti kemenangan mutlak basa Indonesia. Organisasi2 kedaerahan jang pada mulanja memilih
sosial dan kebudajaan sebagai garapannja, dengan gelumbang mulai bergerak tanpa ragu dan dengan terang2an dibidang politik: Budi Utomo, Pasundan, Tirtajasa, Sarekat Ambon, Sarekat Madura, Kaum Betawi, jang sebelum itu bernama Daja Upaja dan Betawi Berichtiar. Dengan sendirinja basa pra-Indonesialah jang djadi basa organisasi dan djuga antar organisasi. Kampanje2 politik, surat2 selebaran, plakat2 dari golongan non menggunakan basa pra-Indonesia ini sampai ketengah2 pabrik dan perkebunan2 dan mentjapai puntjaknja pada tahun 1926. Maka adalah suatu keteledoran untuk tidak mengetahui, bahwa sk Proletar terbitan Surabaja ikut
mendjiwai basa pra-Indonesia sebagai basa perdjuangan, perkelahian dan pertarungan melawan imperialisme. Pada waktu terdjadi penjitaan atas 2 toko buku terbitan penerbit2 kiri di Surabaja, seluruhnja tertulis dalam basa pra-Indonesia. Ali Archam dalam pembelaan terhadap kekuasaan imperialis sebelum dibuang ke Irian Barat pada tanggal 24 Desember 1925, djuga menggunakan basa pra-Indonesia sebagai alat pembelaannja, ja sekalipun basa ini tidak diakui sebagai basa hukum. SBBM, jaitu serikat buruh marine, jang hidup ditengah2 alat pembunuh imperialis bukan saja menggunakan basa pra-Indonesia, djuga menghimpun seluruh buruh
POKOK
merah dari berbagai keturunan dengan basa itu. Ada suatu keteledoran pula untuk tidak mengetahui, bahwa politik pertamatama dalam sedjarah Indonesia, jaitu pemberontakan 1926, dalam penjerangan2nja di Glodok, Tanah Abang, Pal Merah, menggunakan komando basa pra-Indonesia. Dalam pemeriksaan militer dan polisi, mereka jang tertangkappun menggunakan basa ini dan mereka jang menguasai basa Belanda djuga menolak basa imperialis tsb. Malah seorang komunis Belanda, Lassen, dalam pemeriksaan polisi pada bulan Djanuari 1926 tidak menggunakan basa ibunja sendiri, tapi basa pra-Indonesia. 0
ALIT AMBARA
TIM MEDIA KERJA BUDAYA: Anom Astika, Ayu Ratih, John Roosa, Purwantari, Razif
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
33
Edward Said (1935-2003) John Roosa Dalam menimbang kehidupan Edward Said, kekaguman sulit dihindari: penulis yang produktif, pemain piano ulung, aktifis politik tak kenal lelah untuk hak-hak orang Palestina, ilmuwan sastra yang fasih berbahasa Inggris, Perancis dan Arab. Bahkan ketika ia sakit leukemia parah di dasawarsa terakhir hidupnya, masuk keluar rumah sakit untuk transfusi darah, ia tetap bergerak dengan laju mencengangkan dalam menulis dan memberi ceramah – gerak yang seharusnya luar biasa meletihkan kebanyakan manusia sehat. Kematiannya pada 25 September 2003 memutus kehidupan seorang intelektual yang bergairah dan tekun, setelah perjalanan penuh pencapaian, masih memiliki begitu banyak untuk disumbangkan. Latar belakang pengasuhan dari keluarga Palestina yang cukup berada sudah memungkinkan Said memperoleh sifat-sifat yang menonjol: keterpelajaran, pandangan kosmopolitan, rasa percaya diri yang kuat, dan kesadaran akan pengalaman menjadi korban. Lahir di Jerusalem, ia menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya di Kairo dan Lebanon, tempat ia belajar di sekolah swasta untuk kaum elit. Said berangkat ke Amerika Serikat pada 1951 untuk melanjutkan studi ke Universitas Princeton. Pada saat itu keluarganya sudah tersebar bersama dengan kelompokkelompok perantau Palestina lainnya ke segala penjuru dunia. Pembentukan negara Israel pada 1948 merupakan bencana bukan saja bagi keluarganya, tapi juga bagi seluruh bangsa Palestina. Ia mengenang kemudian bahwa “sejak musim semi 1948 tak seorang pun dari sanak-saudaraku yang masih tinggal di Palestina. Semuanya telah dibersihkan dengan sentimen etnis kekuatan Zionis.” Ketika ia belajar di program paska sarjana Universitas Columbia pada 1960an, Said tenggelam dalam studi tentang kesusatraan klasik. Seorang kawan lamanya, Michael Wood, mengungkapkan bahwa Said adalah “ilmuwan ketinggalan jaman” yang dengan ‘keningratannya’ berjarak dari
OBITUARI 34
budaya populer. Ia memainkan musik klasik dengan piano (komposer favoritnya Brahms) dan menulis tentang Joseph Conrad (subyek buku pertamanya pada 1966). Bayangan ideal Said tentang sosok yang berbudaya dan humanis memiliki kebaikan tersendiri. Ia meruntuhkan seluruh stereotip yang dipercayai orang Amerika tentang orang Arab. Di Amerika tak ada kelompok etnis yang lebih dizalimi daripada orang Arab. Perhatikan saja filmfilm produksi Hollywood. Dalam imajinasi populer, orang Arab digambarkan kalau tidak sebagai sultan yang dekaden, masyarakat suku terbelakang yang menggembalakan unta di padang pasir, atau teroris. Said seakan tampil sebagai suatu keajaiban bagi kebanyakan orang Amerika: seorang Arab yang bukan hanya kritikus sastra, tetapi juga kritikus sastra yang melejit sampai ke puncak pencapaian profesinya – guru besar dengan jabatan abadi dan gaji yang tinggi di sebuah universitas Ivy League [kumpulan 8 universitas swasta terpandang di pantai timur AS, red.] di kota New York. Bahwa ia seorang Nasrani menghancurkan lagi streotip yang lain – orang Amerika berpikir bahwa semua orang Arab itu Muslim. Dengan perspektif kosmopolitannya, Said berhasil menghindari perangkap fanatisme berlebihan terhadap etnisitas atau agama. Kebanyakan karya tulisnya memang dirancang untuk membujuk orang supaya menolak prasangka terhadap ‘yang [dianggap] lain’. Ia menulis kata pengantar baru untuk bukunya yang paling terkenal, Orientalism (pertama kali diterbitkan pada 1978), yang akan diterbitkan ulang, bahwa ia adalah pembela “humanisme” dan itu maksudnya “menggunakan otak secara historis dan rasional untuk tujuan pemahaman yang reflektif.” Disiplin keilmuan tua tentang interpretasi (seperti dalam filologi dan hermeneutika) baginya tampak sebagai model hubungan sosial yang ideal. Dalam memahami teks dari budaya asing atau periode sejarah yang berada jauh dari masa kini, seorang kritikus
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
sastra harus “ s e c a r a simpatik dan s u b y e k t i f memasuki kehidupan teks tertulis seperti yang tampak dalam perspektif waktu dan penulis teks.” Said mendorong kita untuk memiliki “keramahan dan keterbukaan” terhadap apa yang awalnya tampak asing bagi kita dan untuk “menyediakan tempat” bagi keasingan itu di benak kita. Ia melihat sastrawan seperti Goethe dan Erich Aurbach sebagai pahlawan dalam upayanya mencapai pemahaman lintas budaya. Said mengerti bahwa penggusuran brutal bangsa Palestina bukan disebabkan oleh semacam permusuhan kuno antara kaum Yahudi dan Muslim. Tidak seperti mereka yang ingin menjadi pendukung kepentingan bangsa Palestina di luar Palestina, ia tidak pernah mengkritik agama Yahudi. Ia tahu bahwa masalahnya bersumber dari kebijakan negara Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin negara Israel boleh saja berbicara atas nama Judaisme, tapi pada akhirnya sebuah negarabangsa berbeda dengan sebuah agama. Beberapa orang Yahudi, di dalam dan di luar Palestina, juga memahami hal yang sama dan mereka tidak keberatan bergandengan tangan dengan orang-orang Palestina. Said adalah sahabat karib dirigen orkestra dan pianis Yahudi ternama Daniel Barenboim. Karena bertemu Said pada pertengahan 1990an lah, Barenboim mulai mengunjungi Tepi Barat dan menyelenggarakan konser musik di tengah masyarakat Palestina. Dalam pernyataan-pernyataan publiknya, Barenboim mengutuk pendudukan Israel dan mengusulkan penyelesaian dua-negara. Mereka berdua mengajak musisi Barat dan Timur Tengah untuk membentuk sebuah orkestra bernama East-West Divan pada 1999 (nama ini mengacu pada satu kiasan dalam puisi Goethe). Konser terakhir orkestra ini diadakan di London hanya sebulan sebelum kematian Said. Sebetulnya Said bisa memilih untuk
OBITUARI 34
diam, sekedar menjadi dosen yang rajin, seperti beberapa dari pahlawan kesusastraan yang ia kagumi. Tapi, ia justru memilih menceburkan diri ke tengah pekatnya salah satu soal politik paling kontroversial di AS. Ia tidak melarikan diri dari dunia politik dengan permakluman bahwa ia hanyalah seorang ilmuwan sastra. Ia abdikan sebagian besar waktunya untuk menulis analisa politik dan berceramah tentang perjuangan bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ia menjadi juru bicara bangsa Palestina yang paling ternama karena ia penulis yang demikian cerdas dan pembicara yang mengesankan. Bahkan esai-esai politiknya yang ditulis cepat pun senantiasa tampil anggun. Said berhak memperoleh penghormatan besar untuk keberaniannya menghadapi kampanye pelecehan dirinya yang diluncurkan golongan Zionis sayap kanan. Dalam pandangan picik orang-orang yang disebut “pendukung” Israel di AS (kadang-kadang pandangan mereka lebih ekstrim daripada opini publik di Israel sendiri), siapa pun yang berbicara atas nama bangsa Palestina sama dengan mendukung terorisme. Sebuah jurnal sayap kanan menerbitkan artikel tentang Said yang berjudul “Dosen Teror”. Jurnal yang sama, Commentary, menerbitkan satu karangan penuh fitnah lagi pada 1999 yang menuduh bahwa Said ternyata bukan orang Palestina! Bahwa penulisnya menghabiskan tiga tahun meneliti kehidupan Said (dan memperoleh sebagian besar fakta yang salah) menunjukkan betapa besar kebencian kaum Zionis terhadap Said. Mereka menyadari bahwa pria rasional dan terdidik yang fasih berbicara tentang masalah Palestina ini adalah musuh terburuk mereka. Said memupuk keberanian dari keyakinan kuatnya. Ia tidak ragu-ragu mengkritik pemimpin-pemimpin Arab dan Palestina. Kritiknya terhadap Arafat dan Perjanjian Oslo 1993 membuat tulisan-tulisannya dilarang oleh Penguasa Palestina yang berumur pendek. Argumen Said belakangan terbukti benar: Perjanjian Oslo adalah kesalahan yang tragis dan mengkhianati perjuangan massa kaum Intifada. Dari seluruh karya Said, buku yang paling saya gemari adalah After the Last Sky (1986). Teks dan foto-foto hasil bidikan Jean Mohr yang menghiasinya secara sensitif mengangkat kehidupan orang Palestina dalam seluruh keberagaman dan tragedinya. Bagi suatu bangsa yang secara rutin ditidakmanusiakan dalam media massa utama, buku ini merupakan penggambaran OBITUARI
cemerlang kemanusiaan mereka. Di ekstrim yang lain, buku yang paling tidak saya senangi justru buku yang membuatnya terkenal, Orientalism. Pandangan dasar Said (atau pandangan dasar yang saya tarik dari buku itu) benar – pengetahuan Barat tentang Timur Tengah cenderung membangun imej tentang “masyarakat Islam” yang kasar, ahistoris, dan monolitik. Tapi sanggahan pendukungnya di banyak bagian tidak konsisten, membingungkan, dan salah. Said membuka lahan pemikiran baru dengan Orientalism sehingga tak terlalu mengherankan kalau argumennya tidak sepenuhnya mantap. Yang lebih penting adalah buku ini memancing pengkajian ulang — yang memang sangat dibutuhkan — tujuan studi kebudayaan di Barat dan kaitannya dengan imperialisme. Dalam tulisan-tulisan berikutnya, Said mengolah kembali dan mempertajam argumenargumennya. Dalam salah satu esai yang ia tulis menjelang akhir hayatnya,“Dignity, Solidarity and the Penal Colony” (2003), Said mencoba, seperti yang ia lakukan berulangkali sebelumnya, memperbaiki kesalahpahaman Barat terhadap orang Palestina sebagai agresor dan teroris: “Di Barat, ada perhatian berlebihan dan tidak mendidik terhadap bom bunuh diri oleh orang Palestina sehingga distorsi parah terhadap realitas telah mengaburkan apa yang lebih buruk: kejahatan resmi Israel, dan mungkin juga khas [Ariel] Sharon, yang sudah ditimpakan secara sengaja dan terarah pada rakyat Palestina. Bom bunuh diri itu salah tapi menurut pendapat saya tindakan itu merupakan akibat langsung dan terprogram, yang secara sadar dilakukan, dari tahun-tahun penuh perlakuan buruk, ketidakberdayaan dan keputusasaan.” Sejak menguasai Jalur Gaza dan Tepi Barat secara militer pada 1967, Israel sudah membiarkan penduduk wilayah tersebut dalam ketidakpastian: mereka bukan warga negeri mereka sendiri juga bukan warga negara Israel. Saat ini, dengan pagar dan pos penjagaan di sekeliling mereka, mereka sudah menjadi tawanan di sebuah penjara besar yang terbuka. Said menulis: “Sesekali kita perlu ambil jeda dan menyatakan dalam kemarahan bahwa hanya ada satu sisi dengan tentara dan negara: di sisi yang lain adalah penduduk tak bernegara, terampas hartanya, tanpa hak atau cara apa pun untuk melindungi diri mereka.” Pemerintahan Jendral Sharon menginginkan“tak lebih dari pemusnahan seluruh masyarakat dengan cara penyekapan, pembunuhan langsung, media mediakerjabudaya. kerjabudaya.edisi edisi1111tahun tahun2003 2003
dan mencekik kehidupan sehari-hari secara pelahan-lahan dan sistematik.” Said mengakui bahwa masa depan bangsa Palestina suram. Sedikit sekali perlawanan di Israel, “yang jiwanya sudah terperangkap kegilaan terhadap tindakan menghukum yang lemah, demokrasi yang dengan setia mencerminkan mentalitas psikopat penguasanya, Jendral Sharon.” Sedikit sekali perlawanan di wilayah pemberi dana bagi Israel, Amerika Serikat. Dan sedikit sekali dukungan dari pemimpin-pemimpin negara Arab yang, menurut Said, tidak mewakili masyarakat Arab: “mereka begitu hebatnya meremehkan kemampuan mereka sendiri dan kemampuan rakyatnya sehingga membuat mereka tertutup, intoleran dan takut perubahan.” Pemimpin-pemimpin Palestina sendiri, Arafat dan lingkarannya, sudah sedemikian mengecewakan rakyatnya, dan, dalam ambisi mereka meraih kekuasaan, lupa bahwa mereka mewakili perjuangan popular. Mereka sudah direndahkan menjadi “gabungan antara penolakan kekanakkanakan yang salah tempat dan permohonan menghiba yang tak berdaya.” Tetapi Said melihat secercah harapan justru dari kenyataan bahwa gerakan perlawanan rakyat Palestina tetap bersikukuh. Bangsa ini terus menerus menghadapi bencana sejak 1948 dan selalu menemukan cara untuk bertahan. Bagaimana pun mengenaskannya situasi mereka, tidak ada pilihan lain kecuali melanjutkan perlawanan. Bagi mereka di luar Palestina, tak ada pilihan lain pula kecuali melanjutkan tindakan-tindakan solidaritas yang konstruktif,“Secara khusus orang seharusnya menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk keadilan, bukan melempar kritik melelahkan dan berkepanjangan, komentar mengecilkan hati yang membuat frustrasi, atau tindakan memecahbelah yang melumpuhkan. Ingatlah solidaritas di sini [di AS, red.] dan di berbagai tempat di Amerika Latin, Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Dan ingatlah juga akan kerja bersama yang menjadi tumpuan komitmen begitu banyak orang walaupun ada kesulitan dan halangan yang mengerikan. Mengapa? Karena perjuangan rakyat Palestina berjalan dengan prinsip yang adil, cita-cita yang luhur, tuntutan moral untuk kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.” 0 John Roosa, dosen sejarah Asia di Universitas British Columbia, Vancouver, Kanada
35 35
36
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
PAT GULIPAT
PAT GULIPAT
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
37
Nyanyian Perempuan Amerika bagi Pembebasan
Umi Lasmina
L
agu adalah ramuan melodimusik dan lirik yang melahir kan kemenyatuan antara mereka yang mendengarkan dengan “apa” yang didengarkan. Seperti halnya media lain yang menjembatani satu atau beberapa orang dengan orang-orang lainnya, lagu sejak dulu menjadi media yang lebih banyak merepresentasikan suara, pengalaman, dan sejarah laki-laki. Apa boleh buat, faktanya perempuan bisa secara bebas bersentuhan dengan media ini secara massal (ada interaksi antara perempuanmusik-perempuan-musik-perempuan banyak) baru-baru ini saja. Berarti suara, pengalaman, rasanya pun sudah merepresentasikan perempuan. Perempuan, karena seksualitasnya, memiliki ciri yang berbeda dari laki-laki. Salah satu diantara ciri-ciri tersebut berwujud fungsi biologis: perempuan memiliki rahim, maka ia harus melahirkan, mengurus anak, dan menjaga keseluruhan tubuhnya agar laki-laki tidak tergoda padanya. Karena laki-laki tidak melahirkan, maka ia harus bekerja mencari nafkah. Ia tidak harus mengurus anak dan rumah tangga. Harus-harus inilah yang membelenggu manusia. Padahal manusia hidup dalam pilihan bebas untuk menuju kebahagiaan masing-masing.
38
Perempuan tentunya tidak tinggal diam. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mendobrak kungkungan terhadap dirinya, antara lain melalui gerakan sosial yang berideologi feminisme. Perempuan yang ikut dalam gerakan ini memakai berbagai media untuk menyebarkan gagasan pembebasan. Lagu adalah salah satu media pembebasan, sekaligus media perlawanan. Karena lagu seperti media lainnya yang ada di bumi, seringkali juga menyuarakan nilai yang menyudutkan perempuan. Maka lagu, selain menjadi teman dalam gerakan yang mengiringi semangat perempuan, juga menjadi alat perlawanan terhadap lagu-lagu yang diciptakan laki-laki untuk merendahkan perempuan. Lagu-lagu ini biasanya lahir secara kolektif, bersamaan dengan jalannya gerakan perempuan, dan dinyanyikan pada saat aksi. Lagu inilah yang bisa disebut sebagai musik perempuan. Margie Adams, musisi peraih Award dari National Women’s Music Festival, menyatakan, “Musik perempuan adalah musik yang mengafirmasi dan memberdayakan perempuan, dibuat oleh perempuan untuk siapa saja, terutama perempuan dan laki-laki pro-feminis.” Bagi saya pribadi, musik perempuan memiliki melodi yang menenangkan dan memiliki mayoritas nilai feminin (kelembutan, media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
kedamaian, berbicara cinta, dan berbicara dengan hati). Tak heran melodi yang lahir pun bernuansa jazz, terutama mainstream jazz dari New Orleans, folk, dan orkestra. Lagu-lagu yang lahir dari gerakan antara lain dinyanyikan pada saat Konvensi Perempuan I di Seneca Falls, Amerika, di 1840an. Lagu yang dilantunkan mencerminkan harapan dan perubahan posisi dan peran perempuan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan untuk bersuara. Seperti yang diciptakan D. Estabrook, Keep Woman in Her Sphere [Biarkan Perempuan di Ruangnya]: Aku bertanya padanya, “Bagaimana dengan hak-hak perempuan?”/Ia menjawab dengan nada serius/”Pandanganku tentang hal itu sudah mantap,/Biarkan perempuan di ruangnya.”/Aku melihat seorang lelaki berpakaian compang-camping/Keluar dari toko kelontong/Ia habiskan seluruh uangnya untuk minuman keras/dan biarkan istrinya kelaparan di rumah/Aku bertanya padanya “Tidakkah perempuan seharusnya memilih”/Sambil menyeringai ia menjawab—/”Aku sudah mengajar istriku agar tahu tempatnya,/Biarkan perempuan di ruangnya.”/Aku bertemu seorang lelaki yang tulus dan penuh perhatian/Beberapa hari yang lalu/Yang berpikir dalam tentang segala hukum ESAI
ISTIMEWA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Tracy Chapman dan Suzanne Vega
manusia/Kebenaran paling jujur yang perlu diketahui/Aku bertanya padanya “Bagaimana dengan kepentingan perempuan?”/Jawabannya sungguh-sungguh — /”Hak-hak mereka sama dengan hak-hak ku,/Biarkan perempuan memilih ruangnya.” Lagu lain muncul saat gerakan perempuan 1960an muncul dengan deklarasi Blue Stocking Manifestonya. Beginilah lirik lagu yang dinyanyikan: Pembebasan perempuan sudah tiba/laki-laki tak lagi bisa putuskan segala/tentang jika dan bagaimana dan di mana dan kapan/di akhir hari yang melelahkan.// Karena perempuan pun inginkan bagiannya yang adil/dalam kesenangan pun upah /tapi ia tetap ingin menjadi majikan/maka ia pun balikkan badan// Lirik ini mencerminkan perjuangan persamaan upah dan kesenangan. Diangkat pula soal seksualitas …/ketika tiba saatnya bermain cinta di akhir hari yang melelahkan.//Ia akan bergerak tanpa pedulikan perasaan yang mungkin ia simpan/ sampai dalam perlawanannya ia katakan/sakit kepala yang jadi bahan tertawaan semua orang.// Dan/Ya.Tidak/ Ya.Tidak/Maaf aku sakit kepala// Pada masa ini pula digelar Michigan Womyn Music Festival 1974, yaitu per-
ESAI
tunjukan musik tahunan untuk perempuan oleh perempuan yang dilakukan di alam terbuka di atas tanah seluas 23 hektar yang dibeli 3 pendirinya. Festival musik ini diprakarsai oleh feminis radikal. Awalnya festival ini dimulai oleh feminis radikal hanya untuk perempuan yang mayoritas lesbian. Kini semakin banyak transgender (laki-laki menjadi perempuan) serta keluarga heteroseksual turut serta. Perencanaan akomodasi festival ini mencerminkan nilai-nilai feminin, misalnya dengan disediakannya akomodasi penginapan bagi mereka yang punya anak, membawa suami, dan hewan peliharaan. Selain pertunjukan musik, ada pula lokakarya mengenai berbagai topik musik dan sosial-budaya. Festival musik perempuan seperti ini tidak hanya ada di Michigan, tetapi juga di beberapa negara bagian lain di AS. Tetapi Michigan Womyn Music Festival yang paling kontroversial dan cukup bertahan lama. Pada 1990an lahir lagi festival musik yang diprakarsai penyanyi Sarah McLachan, yaitu Lilith Fair yang menggelar pertunjukan dari satu kota ke kota lain. Berbeda dengan festival musik perempuan 1960an-1970an, Lilith Fair ini memiliki keterkaitan langsung dengan dunia industri rekaman. Festival ini juga
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
bekerja sama dengan berbagai perusahaan, mulai dari sabun hingga celana jeans. Meskipun begitu, saya menganggap festival ini sebagai bagian dari gerakan karena memiliki konsep pemberdayaan perempuan, pembebasan, dan persaudaraan. Apalagi Lilith Fair hadir untuk melawan Lollapoloza, sebuah festival musik rock yang didominasi penyanyi laki-laki yang macho, sehinga tak memberi ruang bagi perempuan. Lilith Fair Festival juga mengadakan lomba menyanyi dan bermusik bagi perempuan. Pemenangnya tampil dalam festival bersama musisi perempuan terkenal. Dana yang didapat dari penjualan tiket disalurkan bagi Rape, Abuse, & Incest National Network (RAINN), layanan hotline nasional bagi korban perkosaan, incest, dan kekerasan domestik; LIFEbeat, sebuah organisasi penelitian dan peningkatan kesadaran tentang HIV/ AIDS; dan Rumah Suaka perempuan di tingkat lokal. Penyanyi yang turut dalam festival ini penyanyi 1980-1990an seperti Jewel, Nathalie Merchant, Tori Amos, Sheryl Crow, Nelly Furtado, serta penyanyi veteran seperti Bonnie Raitt, Joan Baez, dan lain-lain. Penyanyi Indonesia, Anggun C. Sasmi, juga pernah ikut menyanyi di Lilith Fair Festival.
39
Disini lagu-lagu untuk pembebasan perempuan dilantunkan, dengan penuh suka cita, kesadaran, dan kesyahduan sehingga para penonton perempuan yang hadir pun merasa bahagia karena mendapatkan kepercayaan diri yang lebih kuat sebagai perempuan. Musik perempuan sejak 1970an adalah upaya mengembalikan kontrol atas diri perempuan, mendefinisikan serta menampilkannya melalui musik. Ada pula tujuan memberdayakan perempuan dengan mendirikan sendiri perusahaan rekaman, melatih perempuan menjadi teknisi, atau pekerja ahli di media massa. Musik tidak hanya memberi inspirasi, tapi juga memberi ruang bagi potensi perempuan. Perusaan rekaman yang dirintis penyanyi perempuan, seperti Ani Di Franco, Carole King, dan Madonna, semakin banyak. Suara-suara Individu Musisi dan penyanyi perempuan sebagai individu juga telah menyumbangkan suara dan bunyi yang menceritakan pengalaman pribadi, teman, saudara, atau orang lain. Kemampuan mereka menyerap, kemudian memuntahkan kembali apa yang diserap melalui lagu luar biasa. Apalagi lagu tersebut mampu menyentuh nurani jutaan orang di dunia. Di sinilah musisi perempuan memiliki kesadaran untuk menciptakan lagu yang selain menjadi ekspresi pribadi, juga ekspresi perempuan lain. Ini menunjukkan fakta yang tak dapat dipungkiri: perempuan memiliki banyak persamaan oleh sebab seksualitasnya. Keserupaan pengalaman ini, misalnya, dituturkan dalam lagu yang ditulis Suzanne Vega dan Tracy Chapman tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam lagunya Luka, Suzanne Vega mengungkapkan “/Jika kamu mendengar sesuatu saat larut malam/Seperti ada masalah seperti ada perkelahian/Jangan tanya padaku apa itu/ Mereka hanya memukul sampai kamu menangis/ Dan setelah itu jangan kamu bertanya kenapa/Kamu tak berdebat lagi/…Tracy Chapman dengan Behind the Walls [Di Balik Dinding]: Tadi malam aku mendengar teriakan/Suara-suara keras di balik dinding../Dan ketika mereka tiba/Mereka bilang mereka tak bisa ikut campur/Dalam urusan domestik/Antara lelaki dan istrinya/Dan ketika mereka berjalan keluar/Air mata mengembang di pelupuknya.// Kedua lagu tersebut mencerminkan interaksi perempuan (penulis lagu dan 40
penyanyi) dengan dunia yang penuh dengan kekerasan bagi perempuan dan anak-anak. Tori Amos, penulis lagu dan penyanyi yang pernah mengalami perkosaan menuliskan pengalamannya dalam lagu Me and A Gun [Aku dan Pistol]: Jumat pagi jam lima/Adalah Aku dan Pistol dan Lelaki di belakangku/Aku nyanyikan Holy.Holy/Saat ia membuka ritsleting celananya .. aku dan pistol/ .Tapi aku belum melihat Barbados jadi aku harus lolos dari ini/Kukenakan barang merah yang lembut/ tak berarti aku harus mengangkang, untukmu dan teman-temanmu, bapakmu Mr. Ed//Lagu ini dilantunkan dengan hymne acapella tanpa musik, bagi seorang perempuan yang pernah mengalami percobaan perkosaan atau perkosaan pasti bisa merasakan apa yang dirasakan Tori. Ada banyak kisah kegetiran dan kegalauan hidup sebagai perempuan yang dilantunkan dalam nyanyian yang diciptakan perempuan termasuk juga oleh Madonna. Tak banyak media mengungkap sisi lain penyanyi ini. Mungkin karena kita terperangkap oleh penampilannya yang eksploitatif, hingga tak mau tahu bahwa ia pernah mencipta lagu What it Feels Like for A Girl [Bagaimana Rasanya bagi Seorang Gadis]: ”Dan memotong pendek rambutnya / Memakai kemeja dan sepatu bot/Karena tak apa menjadi laki-laki/Tapi bagi lakilaki kelihatan seperti gadis itu merendahkan/Karena kamu berpikir menjadi gadis itu memalukan/Tapi di dalam hati kamu ingin tahu bagaimana rasanya/Bukankah begitu/Bagaimana rasanya bagi seorang gadis/. Atau lagunya Love Makes The World Go Round [Cinta Membuat Dunia Berputar] yang ditulis bersama Pat Leonard:Kita bilang main cinta bukan perang/Mudah diulang/Tapi tak berarti apa-apa/Kecuali kalau kita akan bertarung/Tapi bukan dengan pistol dan pisau/Kita harus selamatkan hidup/ Setiap anak lelaki dan perempuan/Yang tumbuh besar di dunia ini. Masih soal pengalaman sebagai perempuan, Sinead O’Connor dan Nathalie Merchant menulis lagu tentang menjadi ibu. Sinead dalam All Babies [Semua Bayi]: Semua bayi lahir dari kesakitan luar biasa/Semua bayi lahir sambil ucapkan nama Tuhan/ Ia dengarkan jeritan mereka ia adalah ibu dan ayah// Semua bayi menangis/. Sedangkan Nathalie dalam lagunya Eat For Two [Makan untuk Dua Nyawa] bahkan juga media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
bercerita bagaimana konsepsi terjadi, Baiklah, lelaki telur jatuh dari rak/Lelaki para raja terbaik dengan bantuan mereka berjuang mati-matian demi sebuah cangkang yang tak bisa mereka rekatkan kembali/Kamu tahu kemana ini akan berlanjut, ke buaian di ruang bayi/ke tendangan di dalam tubuhku/Kebodohanku tumbuh di dalam aku/Aku makan untuk dua nyawa, berjalan untuk dua nyawa, bernafas untuk dua nyawa sekarang/Kebanggaan untuk lelaki, sedangkan gadis muda harus berlari dan sembunyi/Ambil resiko permainan dengan berani katakan “ya”. Lagu-lagu yang dilahirkan perempuan selain mengenai kegalauan tentunya juga membawa harapan dan semangat untuk perjuangan, seperti lagu Jewel, Life Uncommon [Hidup yang Tak Biasa], yang diciptakan khusus untuk tantenya Jacqie, seorang aktivis feminis dan lingkungan hidup: Jangan khawatir ibu, semua akan baik-baik saja/jangan khawatir saudariku tidur lelap/Kita dipersenjatai dengan keyakinan/Kita lelah kita khawatir tapi kita tidak aus// Penyanyi provokatif lainnya yang sering menyuarakan pembebasan kemanusiaan dan perempuan adalah Michelle Shocked, yang pernah dipenjara karena protes menentang pemerintah. Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan perempuan bukan tanpa kaitan dengan lagu yang diciptakan laki-laki. Meskipun media popular tak begitu memperhatikan perkembangan lagu perempuan, kenyataannya semakin banyak penyanyi dan pencipta lagu perempuan yang lahir dan terus berkembang dengan inspirasi dari penyanyi, lagu, dan festival. Penyanyi perempuan semakin mampu memberi inspirasi bagi kepercayaan diri banyak perempuan dan memberi ruang bagi pembebasan perempuan. Tak heran MTV menghadirkan MTV Fan-Atic. Tentunya selain ada bumbu komersil dan industri, kehadiran penyanyi dan pencipta lagu perempuan dibutuhkan untuk penghargaan diri dan panutan bagi perempuan muda. 0 19 April 2003 Umi Lasmina, aktifis feminis, tinggal di Jakarta
ESAI
omongkosong apalagi dimainkan dalam perjanjian, kesepakatan; damaikah hati?
mengucap fatwa dari telepon genggam: tiada siapa dapat membunuh siapa tidak diri menjadi tanpa adaptasi inilah warkah sebuah negeri yang hancur terombangambing laut malaka
mae dan isteri melaok eungkot payeh menjaja sepanjang bibir-bibir
Banda Aceh, 29 September 2002
dodaidi meninabobokan** mimpi omongkosong apalagi dimainkan tersebab hukom bak syiahkuala qanun bak putroe phang adat bak potomeureuhom resam bak bentara mae dan isteri menjaja sampai jauh ke dalam mae dan isteri hilang SEMSAR SIAHAAN
PUISI DIN SAJA
FRAGMENTASI OPERA EUNGKOT PAYEH*
eungkot payeh terbungkus rapi atas jembatan Banda Aceh, 21 Desember 2002 *eungkot payeh = ikan pepes **dodaidi = lagu menidurkan anak di Aceh
KEPADA “R” YANG TERCINTA
WARKAH SEBUAH NEGERI YANG HANCUR inilah secarik warkah sebuah negeri yang hancur belantara yang sunyi dikirim melalui selat malaka, entah berlabuh di mana
untuk sementara kita pisah dulu sambil segarkan kenangan yang kita tak pernah ada didalamnya sambil merebahkan diri ditikarpandan dihalaman rumah dibawah pohon jambu sambil dengarkan kicau burung-burung jerit anak-anak dikejauhan tidakkah kau dengar lenguh kerbau ngingatkan untuk sebuah kehidupan dengkur kuda bermimpi melintas padang-padang baris berbaris semut memacu waktu
dihempasan ombak warkah bawa pesan sebuah negeri yang hancur kampung halaman, identitas tercabik darah kebencian mendendam
karena perpisahan merupakan harapan untuk mastikan hidup bukan tujuan
semalam lakseumana keumalahayati memberi pesan lewat sms: biarkan bibir pantai perahu amatrhangmanyang melaut samudera kapal-kapal berlayar arung kehidupan
dengan hati sabar rindu mendendam kita ulur waktu dalam kehidupan
waktu bersamaan tjoet nyak dhien menyampai kesal melalui faksimil: mengapa iskandarmuda memimpin negeri lilawangsa dan teuku umar jadi pecundangnya
mari kita pisah putih hitam dulu Banda Aceh, 10 September 2002
dalam pula itu abu beureueh Din Saja, penyair menetap di Banda Aceh media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
41
KRITIK SENI
PUNK DI INDONEI
S I N A D A Y A ANTARA G SIA Resmi Setia M.S
Sekilas Sejarah Perkembangan Punk Inggris dan Amerika Pengertian punk seringkali diartikan secara berbeda-beda, dari mulai anak muda hingga para manejer perusahaan yang sering nongkrong di pub. Lebih jauh punk juga diartikan sebagai orang yang ceroboh, sembrono, dan ugal-ugalan hingga sekelompok pemuda bergerak menentang masyarakat mapan dengan menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang khas. Craig O’Hara dalam The Philosophy of Punk (1999) mendefinisikan punk lebih luas, yaitu sebagai perlawanan “hebat” melalui musik, gaya hidup, komuniti dan mereka menciptakan kebudayaan sendiri. Di Indonesia media massa memberikan definisi awal begitu umum dan memberikan deskripsi populer terhadap punk. Sedangkan definisi terakhir mungkin lebih mampu menggambarkan punk sesungguhnya walaupun terasa berat jika disandang oleh punkers di Indonesia yang sebagian besar masih memahami punk sebatas sensasi bukan esensi. Terdapat berbagai perdebatan mengenai masalah waktu dan tempat lahirnya punk. Apakah dari New York Scene pada akhir tahun 1960an/awal tahun 1970an atau di Inggris tahun 1975-1976? Namun tidak ada satu pun dapat melacak lebih jauh sebagai suatu bentuk gerakan politik sampai akhir tahun 1970an. Pada
42
Anarchism, the revolutionary idea that no one is more qualified than you are to decide what your life will be (Days of War Nights of Love)
musim panas tahun 1976 di Inggris muncul suatu bentuk “budaya” baru mengingatkan pada mods dan rockers di tahun 1960an. Ini adalah punk rocker berasal dari punk rock, sejenis dengan musik new wave yang berkembang di Amerika Serikat. Majalah Melody Maker mendefinisikan punk (Inggris) tidak begitu perduli dengan penataan musik, namun cenderung pada musik pemberontak. New wave adalah jenis musik lebih kurang hampir mirip dengan irama lebih meyakinkan. Hal ini mencerminkan perbedaan antara musik rock Inggris dan Amerika. Di Inggris, musisi-musisi amatirnya bersemangat dan kurang memiliki teknik bermusik tapi memiliki keberanian tampil di panggung. Sedangkan musisi Amerika lebih memiliki keahlian dalam bermusik tapi tidak berani tampil seperti halnya musisi amatir Inggris. Grup-grup pengusung musik punk rock berkembang di pub-pub dengan berbagai gaya rambut dicat dengan warna-warna mencolok dan gaya berpakaian yang didasari oleh ide perbudakan dan seksual fetisisme (Lihat Brake, 1980: 80). Para grup musik pengikut punk menciptakan suatu penampilan yang liar dan menyerukan bahwa tidak ada masa depan, pekerjaan, dan prospek yang suram (Brake, 1980: 81). Tricia Henry melalui bukunya Break All Rules (dalam O’Hara, 1999: 26-27) mempertegas hal ini dengan
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
menyatakan bahwa pengangguran dan kondisi sosial begitu buruk membangkitkan kemarahan dan sikap frustasi. Perasaan-perasaan ini diekspresikan dengan berbagai cara. Kejahatan merupakan tanggapan yang paling populer dilakukan. Hubungan antara fenomena punk dan ketidakseimbangan ekonomi-sosial di Inggris menegaskan kesahihan filosofi pendukung gerakan punk. Pada dasarnya gerakan punk di Inggris muncul dari serba kekurangan yang dirasakan oleh kelas pekerja. Banyak dari mereka menggunakan punk sebagai media untuk mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuasan. Sejak akhir tahun 1970-an, punk telah berkembang menjadi suatu gerakan politik dan tidak hanya menekankan pada gaya berpakaian dan musiknya saja. Punk lebih menjadi gaya hidup dengan salah satu filosofinya, do-it-yourself (DIY). Mark Andersen dalam bukunya Positive Force Handout (dalam O’Hara, 1999: 36) menyatakan : “...Punk bukan sekedar fashion, gaya berpakaian, masa pemberontakan pada orang tua, trend atau jenis musik terbaru. Punk adalah gagasan yang dapat menuntun dan memotivasi hidup. Apa itu gagasan? Berpikir untuk diri sendiri, menjadi diri sendiri, menciptakan aturan sendiri dan hidup untuk diri sendiri”. Konsep DIY erat kaitannya dengan
KRITIK SENI
filosofi punk memudar dan bahkan menghilang. Punk dianggap fashion dan musik saja. Band-band yang mengklaim sebagai pengusung punk rock, seperti Green Day, Offspring, Helmet, Sum 41, dsb., semakin mempercepat pergeseran makna punk dari anti-kapitalis menjadi pro-kapitalis. Hal ini tampak dari lirik-lirik lagunya sama sekali tidak mencerminkan makna punk dan bergabungnya band tersebut dengan perusahaan-perusahaan rekaman multinasional dan dikenal dengan istilah sell out semakin menegaskan jauhnya mereka dari filosofi punk.
Masuk, Berkembang dan Memudarnya Punk di Indonesia Musik punk rock mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-an, namun belum dikenal secara meluas karena pemasaran kasetnya masih terbatas. Pada tahuntahun berikutnya peredaran kaset punk rock mulai meluas, diawali dengan saling meng-copy kaset di antara para penggemar musik punk rock sampai akhirnya beredar secara bebas dipasaran. Hingga awal tahun 1990an penggemar musik punk rock semakin bertambah terutama di kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Berawal dari sekedar mengikuti fashion band punk rock idolanya, seperti The Sex Pistols, The Exploited, The Clash, The Varukers, sampai lebih mendalami makna punk. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang pelopor punk/hardcore di Bandung, “berawal dari seorang poser atau orang yang ikut-ikutan hingga lebih mendalami sub-kultur punk”. Terdapat dua jenis poser. Pertama mereka senantiasa tertinggal informasi terbaru tentang
punk, sedangkan poser yang kedua mencari informasi lebih terperinci dan tidak lagi menjadi ikut-ikutan (Wardiman, 1999). Perkembangan komunitas punk di Indonesia sangat didukung oleh terbukanya media informasi, seperti internet, televisi dan majalah, pertumbuhan industri musik, kelonggaran perijinan penyelenggaraan pertunjukan musik, dan munculnya pusat-pusat interaksi perbelanjaan, seperti mall dan tempat kumpul gratis lainnya. Hingga 1996 punk masih dimaknai sebatas musik dan fashion karena merupakan unsur paling mudah diterima. Di Indonesia, punk tidak lahir dari suatu kondisi ekonomi dan sosial yang timpang tapi lebih sebagai sebuah trend musik dan fashion baru bagi remaja. Mereka hanya menjadikan punk sebagai sebuah sensasi dengan melengkapi masa perkembangan hidupnya. Masuknya punk ke Indonesia diikuti dengan bermunculannya berbagai band punk rock dan gaya ala punk rocker. Rambut yang dicat warna-warna mencolok dengan model mohawk, model paku, dsb. Berbagai atribut menghiasi pakaian serta tubuh seperti spike atau paku, rantai serta peniti dikenakan di telinga, bibir semakin menegaskan perbedaan gaya penampilan remaja penggemar musik punk rock dengan remaja pada umumnya. Gaya penampilan punkers di Indonesia tidak berbeda dengan negara asalnya, Inggris dan Amerika. Demikian pula dengan musik dan liriknya, pengusung musik punk rock di Indonesia terutama di Bandung lebih mendekati musisi punk
sumber foto: www.thescriptorium.net
anarkisme. Kondisi pendorong utama munculnya anarkisme dalam gerakan punk adalah iklim pemerintahan dan sistem hirarki yang mengakibatkan tekanan dan eksploitasi terhadap orang-orang di dalamnya. Sistem Kapitalisme dan berbagai masalah terangkat kepermukaan, seperti ketimpangan ekonomi semakin mendorong munculnya anarkisme menjadi dasar pijakan gerakan punk. Grup band pertama dengan mengusung paham anarki adalah band punk Inggris, Crass. Menurut mereka anarki adalah bentuk pemikiran dengan initisari tidak mencoba mengontrol orang melalui pemaksaan dan kekuatan. Anarki juga merupakan penolakan terhadap kontrol negara dan melambangkan tuntutan individu untuk hidup dan bebas menentukan pilihan. Anarki dirumuskan bukan sebagai kerusuhan dimana semua orang keluar dari diri mereka sendiri, tapi bagaimana individu hidup dengan orang lain dalam suatu kepercayaan dan toleransi (lihat Crass dalam O’Hara, 1999). Gerakan punk tidak terlepas dari bermunculannya berbagai fanzines, seperti Maximum Rock N’ Roll, Flipside, dsb. Mereka termotivasi oleh fanzines muncul tahun 1970an, yaitu Sniffin Glue dari Inggris dan Punk dari New York. Kedua fanzines ini dapat menghubungkan jaringan punk di seluruh dunia (O’Hara, 1999). Fanzines merupakan salah satu media komunikasi punk yang menegaskan budaya dan filosofi punk. Dalam perkembangannya saat ini, banyak terjadi pergeseran dalam gerakan punk. Banyak band punk rock membuat
KRITIK SENI
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
43
rock Inggris yang kurang menguasai teknik bermusik tapi memiliki keberanian tampil di atas pentas. Meskipun punk di Indonesia tidak lahir dari kondisi tertentu tapi lirik-liriknya tetap mengekspresikan kepedulian terhadap kondisi politik, sosial, dan lingkungan. Seperti lirik lagu sebuah band asal Bandung yang berjudul “Berontak”: “Seperti kita ketahui, yang nyata telah memperlihatkan tanda-tanda usang dan koyak. Anda berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan kini baru, segar tak tertandingi. Anda dapat menjadi pahlawan buruk rupa atau penjahat berhati mulia. Orang besar sering bersikap seperti raksasa dan terlalu ingin dihormati, hidup rakus, tamak, kalau bisa merampas. Meski berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Sungguh itu suatu kebodohan. Apabila mereka yang berkedudukan dan terhormat mencuri kau diamkan saja, tetapi ketika rakyat kecil yang melakukannya dijatuhi hukuman yang semestinya. Namun kebijakan ternyata agak berseberangan. Sebagai kaum minoritas jangan biarkan para penjilat itu menindas kita, lawan, lawan, bangkit, hancurkan mereka.” Kemunculan band punk rock, didukung oleh maraknya pertunjukan musik underground, mulai mendapat tempat lebih luas dikalangan remaja. Di Bandung dapat diidentifikasi beberapa pelopor acara musik underground seperti Hullaballoo yang diadakan selama tiga tahun berturut-turut kemudian diikuti oleh acara musik lainnya seperti Gorong-gorong, Campur Aduk, Bandung Underground, dsb. Motivasi awal diadakannya acara musik ini adalah keinginan untuk memiliki sarana bermusik bagi para pengusung musik underground. Biaya penyelenggaraan diperoleh dari iuran atau sumbangan panitia penyelenggara, biasanya berasal dari kelompok pertemanan serta mempunyai kegemaran terhadap musik underground. Hasil penjualan tiket biasanya dibagikan kepada seluruh panitia atau dijadikan modal untuk membuat acara serupa. Pada 1997-2000, di Bandung hampir setiap minggu diadakan acara musik underground dan motivasi penyelenggaraan acara musik itu sendiri menjadi bergeser ke arah lebih komersial. Semakin bertambahnya penggemar musik underground dianggap sebagai peluang cukup menguntungkan oleh enterprise dan sengaja mencari keuntungan materi melalui penyelenggaraan acara musik underground. Hal ini mulai mendapat
44
tanggapan cukup keras dari komunitas punk/hardcore di Bandung yang ditulis dalam newsletter “Submissive Riot” (1998); “...fuck off! Mereka tidak lain adalah enterprise yang menyelenggarakan acara komersil/kapitalistik yang berkedok musik-musik antikomersial. Kenapa mereka memasang tiket dengan harga tinggi padahal musik yang ditampilkan adalah musik-musik kaum working class… Kenapa mereka tidak menyelenggarakan saja konser musik pop?… kenapa mereka menolak membayar band-band yang ingin tampil dengan bayaran yang pantas? Mungkin karena mereka ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya…” Pertengahan hingga akhir tahun 1990an merupakan puncak kejayaan musik underground Bandung, termasuk punk rock. Kehadiran mereka sangat mencolok di pusat-pusat keramaian dari mulai pertunjukan musik, pusat pertokoan, hingga jalanan. Masyarakat menanggapinya secara berbeda-beda mulai dari merasa terganggu hingga menganggap tidak ada bedanya dengan remaja lainnya kecuali fashion-nya saja. Pro dan kontra terhadap kehadiran mereka tidak membuat mereka surut. Jaringan mereka meluas ke daerah lain bahkan negara lain. Yogyakarta, Malang merupakan daerah komunitas punk-nya cukup berkembang dan memiliki hubungan cukup erat dengan komunitas punk di Bandung. Pertukaran informasi terjadi melalui internet, fanzines/ newsletter dan kaset yang diproduksi oleh individu maupun kelompok. Tigabelas zines dan Submissive Riot merupakan fanzines/newsletter, generasi pertama di Bandung. Fanzines/newsletter tersebut memuat masalah sosial, politik, lingkungan hidup, protes terhadap MNC’s, wawancara dengan band-band lokal hingga filosofi punk. Fanzines/newsletter dikemas dalam bentuk fotokopi, disisipi dengan berbagai macam foto, karikatur, dan informasi seputar band punk rock/hardcore. Fanzines/newsletter merupakan media informasi yang cukup efektif di kalangan komunitas punk. Sejak 2002, pertunjukan musik underground sudah mulai ditinggalkan karena penggemarnya yang mengalami kejenuhan. Musik undeground benar-benar kehilangan pamornya. Hal ini didorong oleh perubahan haluan musik para pendukungnya ke jenis musik lain yang sedang berkembang saat itu. Kelompok punk, biasanya tampak di pusat-pusat keramaian sudah mulai menghilang digantikan oleh kelompok-kelompok remaja lainnya. Baru-baru ini ada upaya
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
untuk memunculkan kembali acara musik tersebut, namun penggemarnya sudah semakin berkurang dan hanya berasal dari daerah-daerah pinggiran Kota Bandung. Penurunan pamor musik underground tidak serta merta menyurutkan kemunculan distro-distro yang menjadi tempat penjualan barang-barang komunitas underground, dari mulai aksesoris, t-shirt, kaset band underground lokal maupun luar negeri, hingga fanzines/ newsletter. Distro tersebut masih tetap eksis namun lebih berorientasi profit dan menjangkau pasar lebih luas. Bagaimana pun distro masih mempunyai keistimewaan sendiri karena menjadi media alternatif dari produk-produk kapitalis. Sebagian besar anggota komunitas underground tidak memahami inti dari gerakan underground, khususnya punk yang memerlukan konsistensi pendukungnya agar tetap eksis. Dari sisi kuantitas pendukung gerakan punk di Bandung mengalami penurunan. Tetapi dari kualitas pendalaman terhadap filosofi, punk mengalami kemajuan sangat berarti dari masa-masa sebelumnya. Namun, arah gerakannya lebih bersifat politis. Dinamika punk di Indonesia, khususnya Bandung, belum mewujudkan suatu bentuk perlawanan yang sesungguhnya, namun telah keburu memudar. Hal ini disebabkan gaya hidup punk senantiasa mensyaratkan kemandirian total, terlalu berat bagi sebagian besar anggotanya yang kehidupan sehari-harinya masih tergantung pada banyak pihak. Jalur masuknya gaya hidup punk melalui musik bagi sebagian besar remaja lebih dianggap sebagai hiburan daripada pedoman hidup, maka yang diadopsi unsurunsur luarnya saja. Lets making punk a threat again (profane existence). 0 Daftar rujukan: Brake, Mike. 1980. The sociology of youth culture and youth subcultures. London, dll: Routledge & Kegan Paul. O’Hara, Craig. 1999. The Philosophy Of Punk: more than noise. London, dll: AK Press. Resmi Setia. 2001. Punk sebagai Gaya Hidup Remaja: studi kasus pada kelompok punk di kota Bandung. Jatinangor: Jurusan Antropologi FISIP UNPAD. Wardiman, A. Arifin. 1999. Subkultur punk: sebuah tinjauan gaya dan pengembangannya terhadap produk jewelry. Bandung: FSRD ITB.
Submissive Riot. Edisi 3. 1998. Bandung.
Resmi Setia M.S., penulis menetap di Bandung
KRITIK SENI
sisipan 0
edisi 11 tahun 2003
MENGAJAK KORBAN BERKESENIAN? MENGAPA TIDAK?
P
ada 9-11 Mei 2003 telah berlangsung pertemu an antar korban kekerasan Orde Baru di Wisma Hijau, Cimanggis, Jawa Barat. Dihadiri sekitar 100 orang korban dari berbagai kasus dan wilayah, serta pengamat dari organisasi-organisasi yang berminat terhadap masalah pelanggaran HAM di masa lalu, pertemuan ini membicarakan persoalanpersoalan yang berkaitan dengan pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan bagi para korban. Karena tujuan utama pertemuan ini adalah memberi ruang bagi korban untuk menggali pemikiran mereka tentang langkah yang harus diambil untuk mencapai kebenaran dan keadilan, yang menjadi narasumber utama adalah para korban sendiri. Sedangkan aktifis pembela HAM yang terlibat dalam kepanitiaan semata-mata berfungsi sebagai fasilitator untuk melancarkan jalannya proses diskusi. Gagasan untuk menyelenggarakan temu korban yang melibatkan wilayah demikian luas sebenarnya sudah muncul sejak April 2001. Lewat sejumlah pertemuan awal di Bali, Jawa, Sulawesi dan Sumatra, korban dari peristiwa kekerasan yang berbeda-beda, seperti Tragedi 1965, Tanjung Priok, Lampung, 27 Juli 1996, Penculikan, Mei, dan Semanggi I dan II, berkesempatan untuk bertemu muka dan bertukar pikiran tentang langkah-langkah yang pernah dan perlu diambil untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Sedangkan keputusan untuk mengadakannya pada Mei 2003 berkaitan dengan rencana organisasi pendamping korban Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) bersama dengan Paguyuban Keluarga Korban Mei memperingati 5 tahun Tragedi Mei 1998. Dalam rapat-rapat persiapan acara disimpulkan bahwa Mei 1998 bukan hanya melahirkan korban, tetapi juga mengawali terbentuknya gerakan kemanusiaan yang menempatkan korban sebagai poros kekuatan utama. Dari sini lah muncul usulan agar acara Temu Korban dirangkai dengan sebuah Sarasehan Gerakan Kemanusiaan pada 12 Mei 2003 yang akan memberi kesempatan pada korban untuk menyampaikan hasil-hasil pertemuan mereka ke publik dan berdialog dengan kalangan masyarakat yang lebih luas. Dan, sebagai puncak acara adalah Peringatan 5 tahun Tragedi Mei 1998 pada 13 Mei 2003 di salah satu lokasi terjadinya pembakaran massal kaum miskin kota, yaitu Mal Citra (d/h Yogya Plaza), Klender. Panitia acara sejak awal menyadari bahwa tidak mudah menyelenggarakan serangkaian acara yang melibatkan ratusan orang selama 5 hari berturut-turut. Walaupun acara-acara tersebut sama dalam substansi, tapi mereka
berbeda dalam bentuk. Namun, munculnya tanggapan positif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kelompok-kelompok korban sendiri, pelahan-lahan mengurangi kekhawatiran panitia dan membuat langkah puluhan relawan yang terlibat dalam persiapan acara selama sebulan penuh semakin ringan. Satu hal yang tidak lazim dilakukan tapi kemudian cukup berpengaruh dalam membangun rasa setiakawan sepanjang acara Temu Korban dan acara-acara yang mengikutinya adalah mengajak para korban dan pendamping korban terlibat dalam kegiatan kesenian. Awalnya, panitia berencana mengundang seniman-seniman ternama untuk menghibur korban setelah lelah seharian berdiskusi tentang masalah-masalah yang pelik.Tapi, kemudian seniman PM TOH Agus Nuramal dan pekerja kebudayaan Erlijna mengusulkan agar kegiatan lepas malam ini dimeriahkan oleh korban sendiri. Mereka yakin bahwa jika diberi ruang dan waktu yang leluasa, para korban akan mampu mengungkapkan ekspresi artistiknya berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, Agus dan Erlijn mengusulkan agar korban tampil dalam sebuah pertunjukan untuk memperingati 5 tahun Tragedi Mei 1998. *** Pada hari per tama acara Temu Korban terasa ada kecanggungan dan kebingungan di kalangan peserta. Sebagian besar dari mereka sudah berusia lanjut, sementara anggota panitia bersama tampak masih muda dan bukan tokoh-tokoh publik ternama. Memang acara dibuka oleh Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara.Tapi setelah itu, praktis acara berlangsung tanpa kehadiran “yang dituakan”. Kemudian, dalam proses diskusi, semua korban harus belajar mendengarkan kisah dan pendapat sesama korban dari kasus yang berbeda-beda dan berusaha mencari rumusan bersama yang tidak lagi bertumpu pada kepentingan penyelesaian satu-dua kasus. Dan, mungkin yang paling membingungkan adalah ketika tim acara kesenian muncul di sore hari dan mengajak peserta menyanyi, membaca puisi dan menari. Salah satu peserta sempat bertanya pada panitia, “Mau dibawa kemana kita ini?” Toh, kebingungan ini tidak berlangsung lama. Dari percakapan di dalam dan di luar acara pokok korban mulai melihat bahwa di atas perbedaan masing-masing kasus kekerasan yang mereka alami ada persamaan dalam hal “nasib”: bahwa mereka teraniaya oleh kebijakan negara yang salah dan bahwa orang-orang yang bertanggungjawab atas kesalahan itu masih bebas berkeliaran. Disamping itu, kesigapan dan ketelatenan petugas penghubung/LO membantu peserta memenuhi kebutuhan apa saja, dari mencari wartel, obat sakit kepala, sampai membeli sandal jepit, membuat peserta terharu. Beberapa peserta yang sudah mengenal baik panitia juga memainkan peran tak kalah pentingnya. Seusai acara “resmi” mereka habiskan waktu untuk berbincang-bincang, bahkan curhat mengenai pengalaman pahitnya sebagai korban, dengan para LO. Yang juga menarik, peserta yang memang senang menyanyi dan bermain drama dengan semangat mengikuti “perintah” sutradara pertunjukan, Agus Nuramal, untuk 45
sisipan0 11-2003
mengerahkan segala kemampuannya sebagai seniman dadakan. Lewat perbincangan santai dan riuh rendah korban memberi usulan berbagai tema untuk Peringatan Tragedi Mei. Lalu disepakati acara pertunjukan akan diberi judul Malam Seribu Lilin, Seribu Kisah: Di Klender Kita Berjanji. Mereka juga secara spontan mengajak semua menyanyikan berbagai lagu rakyat, seperti “Aceh lon Sayang”, “Akai Bi Pamere” dari Papua, “Hai Jengki Agresor” dari Minahasa, “Genjer-genjer” dari Jawa Timur, dan lagu-lagu perjuangan seperti “Padamu Negeri”, “Maju Tak Gentar”, sampai lagu kebangsaan nasional “Indonesia Raya”. Beberapa dari mereka membacakan syair “P’rang Sabi”, puisi untuk kawan-kawan muda yang menjadi panitia, “Para Muda yang Berdaya”, dan “Balada Senyum Sang Jendral”. Kegiatan berkesenian yang diadakan setiap hari sehabis makan malam di lapangan bulutangkis terbuka berjalan menyenangkan, tapi tidak mudah. Skenario gerak, lagu dan puisi yang dirancang sutradara bersama para korban berulang kali berubah sesuai dengan kemampuan korban. Para pemusik dari kelompok Jentera Muda Jakarta (JMJ) dan pelatih gerak, Aidal, dari kelompok seniman Aceh, Sajak, sebelumnya tidak pernah mempersiapkan pertunjukan dengan orang-orang amatir.Tak heran jika di sela-sela latihan terjadi ketegangan diantara para seniman “profesional” akibat kecanggungan pemain melakukan perannya yang berbuntut pada penggantian satu-dua adegan berkali-kali. Untungnya, semua pihak yang terlibat dalam acara ini dikaruniai kesabaran luar biasa sehingga ketegangan tidak meledak menjadi “pemutusan hubungan kerja”. Di akhir malam yang panjang selalu ada rapat kecil tim acara untuk membicarakan kekesalan dan usulan perbaikan untuk malam berikutnya. Kehadiran Mbak Sipon, istri penyair hilang Widji Thukul, yang berpengalaman dalam melatih drama sedikit banyak memudahkan kerja Agus Nuramal. Ia memberi kepercayaan kepada korban yang ragu-ragu berekspresi untuk bergerak dan bersuara bebas. Tak bisa dilupakan pula ketekunan Aidal dan Bang Jaya, seniman Aceh yang pernah mengalami kekerasan militer, dalam mengajarkan lagulagu Aceh dan gerak Seudati sederhana.Tentunya muncul adegan-adegan menggelikan yang bersumber dari ketidaktahuan satu-dua korban tentang pengalaman korban lainnya. Misalnya, para korban dari daerah DOM, Aceh dan Papua, paling senang bila diminta jadi tentara atau intel yang bertindak kasar terhadap rakyat sipil. Mereka mengira semua korban mengalami kekerasan serupa.
46
Ketika giliran Ibu Darwin dari Paguyuban Korban Mei mendramatisasi pengalamannya, tanpa komando dari sutradara, pasukan “tentara” gadungan ini masuk ke tengah panggung dan beramai-ramai mengeroyoknya. Padahal Ibu Darwin tidak pernah berhadapan langsung dengan tentara. Ia harus berteriak-teriak untuk menghentikan “serbuan” kawan-kawannya sendiri. Ada saatnya korban tak kuasa menahan pilu ketika mereka diminta mengucapkan nama-nama korban meninggal yang mereka kenal baik secara beruntun seperti orang berzikir. Suasana menjadi hening. Korban yang selama ini berbentuk angka belaka, bernama. Ketika beberapa korban mulai terisak, latihan mau tak mau dihentikan. Semua yang berada di sekitar tempat latihan – petugas penghubung, pemain musik, pelatih gerak, anggota panitia lainnya – meluangkan waktu sejenak untuk mengenang korban yang gugur. Nama dan angka ternyata menguji pemahaman korban tentang nilai sebuah tragedi dan kaitannya dengan kerja pengungkapan kebenaran. Dalam skenario korban hanya diminta menyebutkan nama korban.Tapi beberapa korban berkali-kali menyebutkan nama diikuti dengan jumlah korban yang mereka percayai benar, seperti “Parto, Sri, dan 3 juta korban lain yang dibantai Orde Baru!”Yang menarik bukan hanya sutradara, tetapi juga korban lain, berusaha mengingatkan bahwa jumlah tidak penting, karena dengan menyebut satu nama saja kita sudah menunjukkan penghormatan terhadap kawan atau kerabat yang telah mendahului kita. Di sisi lain, ketika panitia meminta korban untuk mengumpulkan daftar nama korban meninggal yang mereka kenal untuk dituliskan pada kain putih panjang, ternyata nama yang terkumpul dari 100 korban hanya 491 orang. Bisa dibayangkan berapa banyak korban yang harus terlibat dalam kerja pengumpulan fakta untuk membuktikan bahwa Orde Baru telah membunuh jutaan warganya! Menjelang hari pertunjukan, 13 Mei 2003, latihan bersama ini berlangsung semakin ketat dan melelahkan. Kesibukan di luar latihan kesenian juga meningkat. Anggota panitia yang tidak terlibat per tunjukan tiap malam menuliskan ratusan nama di lembar-lembar kain putih yang akan digantungkan di sekeliling areal Mal Citra. Ada yang mengajak kawan-kawan dari organisasi lain untuk menyumbang bunga. Yang lain meminta ibu-ibu dari SIP menjadi perangkai bunga, pembawa acara dan pembaca puisi. Sementara itu, tim kesenian sendiri masih sibuk melengkapi narasi skenario dan mencari lagu yang akan
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
membawa tema persatuan korban. Sumbangan berbagai bentuk mengalir dari segala kalangan. Ada sumbangan puisi yang indah dari penyair Hersri Setiawan, “Seruan kepada Sesama Korban”, tapi terlalu panjang untuk dijadikan lirik lagu. Dengan desakan dan bujukan yang kukuh akhirnya Ibe Karyanto dari Sanggar Akar bersedia menggubah sebuah lagu dengan inspirasi dari puisi Hersri. Lahirlah Mars Suara Korban dua hari sebelum acara puncak. Korban segera belajar melantunkan mars tersebut dan menjadikannya bagian dari keseluruhan pertunjukan. Pada hari yang dinanti-nanti timbul masalah baru. Pihak Mal Citra ragu-ragu memberi ijin pemakaian tempat karena khawatir akan mengganggu kenyamanan pengunjung yang akan berbelanja.Tim dekorasi yang seharusnya sudah mulai bekerja sejak pagi hari terpaksa berfungsi juga sebagai juru runding.Tanpa diduga dukungan justru diberikan oleh seorang pemilik apotik di kompleks pertokoan tersebut yang mengalami kebakaran pada peristiwa Mei. Dalam waktu kurang dari 3 jam pelataran kosong di sisi apotik tersebut disulap menjadi panggung terbuka. Bebungaan sumbangan dari Komnas Perempuan, Huma, Suara Ibu Peduli, dan masyarakat umum segera ditebar untuk mengharumi panggung dan sekitarnya. Ratusan lilin ditegakkan mulai dari jalan masuk ke lingkar luar panggung. Tepat pukul enam sore gebrakan perkusi Sanggar Akar membuka acara. Pelataran sempit tak menghalangi berkumpulnya ratusan orang – peserta dan panitia Temu Korban, keluarga korban Mei, aktifis LSM, dan masyarakat umum. Para pemain mulai tampak gugup, tapi tetap bersemangat tampil. Kawan-kawan muda petugas penghubung dengan setia menemani pemain dan membantu mereka menghafal lirik dan narasi. Setelah musik pembuka, Ita Fatia Nadia dari Komnas Perempuan membacakan Refleksi Kemanusiaan yang menggugah. Kemudian, pertunjukan dimulai. Diantara penonton tampak sejumlah orang berlinangan airmatanya. Kekhusyukan acara sempat terganggu oleh ulah wartawan yang berebut mencari posisi sedekat mungkin ke panggung, melanggar deretan lilin yang menyala, dan menghalangi pandangan penonton. Di pojok lain ada wartawan yang terus berusaha mewawancarai seorang korban Mei, Pak Iwan, yang cacat akibat luka bakar. Panitia jadi dibuat sibuk menertibkan para wartawan yang tak tahu aturan. Pertunjukan berlangsung kurang lebih 1 jam dan berakhir dengan gerak bersama yang tak terduga. Begitu para pemain menyanyikan Mars Suara Korban sambil mengacungkan lilin, seluruh penonton, bahkan manajer Mal Citra yang awalnya hanya mengamati dari jauh, ikut berdiri melambaikan bunga, mengacungkan lilin, dan berderap merapat bersama korban. Di tengah kerumunan itu lah, Musa, wakil korban dari Aceh membacakan Deklarasi Korban dengan suara lantang. 0
SISIPAN
Hersri Setiawan
seruan pada sesama korban [dari tanah persinggahan] menyongsong temukorban orba saudara, mari kita songsong bersama di atas dataran tanah bersama di bawah kolong langit bersama diterangi matahari yang sama diselubungi gelap malam yang sama saudara, mari kita bicara bersama dalam satu bahasa, bahasa pembebasan dan itu bukan bahasa kebenaran dan itu bukan bahasa keadilan bahasa manusia dan bahasa hidup dan dalam hidup, saudara yang satu jadi berganda-ganda dan pada manusia, saudara yang satu jadi berganda-ganda dalam bahasa manusia tidak ada kata satu dalam bahasa hidup yang satu jadi beribu saudara, mari kita bicara bersama dalam satu bahasa persaudaraan karena di situ rahim kebenaran karena di situ janin keadilan saudara, mari kita pandang ke atas dalam satu semangat, perlawanan pada mata-air kepalsuan pada mata-air kezaliman akhiri kekuasaan zalim dan palsu! mari akhiri nafsu antara sesama dalam satu bahasa korban, kerukunan karena kita bukan bersaing penderitaan karena kita bukan berebut pampasan saudara, ini pertarungan, pertarungan vertikal bukan pertarungan sesama horisontal akhiri kekuasaan zalim dan palsu kita buka lahan persaudaraan kita bangun gubuk kerukunan di sana rahim kebenaran di sana janin keadilan kockengen, 5 mei 03
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
47
sisipan0 11-2003
Sekilas Temu Korban Kekerasan Orde Baru Wisma Hijau, Cimanggis, 9-12 Mei 2003
GALANG SOLIDARITAS TUNTUT TANGGUNG JAWAB NEGARA PULIHKAN KORBAN Mengikuti tergulingnya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998 suara korban penindasan rejim Orde Baru yang menuntut keadilan bermunculan dan menjadi semakin kuat. Dimulai dengan kesaksian para janda korban DOM dan korban perkosaan militer di Aceh, para korban dari kasus-kasus lain bergerak mengungkapkan kepedihan dan kemarahan mereka. Sejak akhir 1998 mereka secara aktif membangun kelompok-kelompok korban, dan menggalang dukungan dari masyarakat luas dengan berbicara di pertemuan-pertemuan publik yang diliput media massa cetak pun elektronik. Mereka juga melangsungkan aksi demonstrasi di berbagai instansi pemerintahan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang baru. Diantara korban adalah mereka yang langsung terkena represi dari negara, terutama aparat militer, dan keluarga mereka, seperti orang tua, istri, suami atau anak-anaknya. Suara-suara dari korban ini sampai batas tertentu sudah memaksa pemerintah dan parlemen untuk menetapkan mekanisme keadilan yang layak bagi para korban pemerintahan Soeharto. Parlemen menetapkan UU no. 39 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang diikuti dengan UU No. 26 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc yang mendirikan pengadilan HAM di
48
lima kota: Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Semarang dan Makassar. Sejumlah tim investigasi juga dibentuk untuk Kerusuhan Mei 1998, DOM di Aceh, dan pembunuhan pimpinan Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran berat HAM di Timor Timur sudah berjalan, sedangkan pengadilan serupa untuk kasus Tanjung Priok sedang berjalan. Selain itu Komnas HAM sudah mendirikan sejumlah Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus-kasus Timor Timur, Abepura, Trisakti-Semanggi I dan II, dan terakhir Kerusuhan Mei 1998. Namun, seperti diketahui hampir semua usaha itu belum memuaskan rasa keadilan korban. Kebanyakan hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhenti di Kejaksaan Agung. Sedangkan kasus-kasus lain masih menunggu tanggapan dari negara, misalnya pembunuhan massal di desa Talangsari, Lampung pada 1986 dan serangkaian tindak kekerasan, termasuk pembunuhan, yang terjadi setelah Peristiwa G30S 1965. Keputusan yang dikeluarkan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur pun ternyata mengecewakan karena kebanyakan terdakwa yang menurut hasil investigasi KPP HAM bertanggungjawab terhadap pelanggaran berat HAM dibebaskan. Kejutan lain adalah ketika Pansus Trisakti-Semanggi DPR RI menyatakan bahwa penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti dan daerah Semanggi bukan pelanggaran HAM berat sehingga tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM Ad Hoc. Sementara itu para pelaku, yakni para penguasa di masa Orde Baru, dalam masa perubahan ini secara bergerilya mengangkat diri menjadi bagian dari gerakan “reformasi”, dan berusaha melepaskan tanggung jawab atas kejahatan mereka di masa lalu. Persekongkolan politik baru yang melibatkan elit Orde Baru dan elit “reformasi” membuat kasus-kasus keke-
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
rasan kembali tenggelam di balik hirukpikuk politik partai dan pergantian presiden. Para pelaku juga berusaha menjinakkan korban dengan menawarkan jalan “penyelesaian” secara damai, seperti tawaran ishlah kepada korban peristiwa Talangsari, Lampung dan Tanjung Priok. Sebagian lainnya memanfaatkan kesulitan hidup para korban dan menawarkan “bantuan kemanusiaan” dengan imbalan bahwa kasus-kasus yang dialami tidak dibicarakan lagi apalagi diproses menurut hukum yang berlaku. Lembaga-lembaga dan organisasi yang bekerja mendampingi korban dan berusaha mendorong proses penyelesaian menyadari bahwa gerakan untuk mengungkapkan kebenaran ternyata amat sulit dan lamban, apalagi untuk menegakkan keadilan. Masalahnya bukan hanya karena lawan yang dihadapi begitu besar dan kuat dalam segala hal, tapi juga karena banyaknya masalah di kalangan korban sendiri, baik sebagai perorangan, maupun sebagai kelompok. Persoalan yang cukup berat adalah kebanyakan korban itu miskin sehingga perjuangan mencapai keadilan seperti sebuah kemewahan bagi mereka. Kondisi sosial-ekonomi yang buruk juga membuat komunitas korban menjadi rentan terhadap bermacam bentuk infiltrasi yang bertujuan melemahkan gerakan mereka. Disamping itu, banyak korban yang memahami persoalan ketidakadilan semata-mata berkaitan dengan pengalaman yang mereka alami secara pribadi, sedangkan pemahaman lebih luas tentang persoalan politik dan hukum yang menyebabkan pelanggaran HAM kurang. Salah satu keberhasilan Orde Baru dalam membungkam perjuangan mengungkap kebenaran adalah dengan menghalangi persatuan di antara korban. Hal ini tampak jelas misalnya dari pengalaman korban peristiwa 1965 yang sampai saat ini masih dianggap sebagai “warga kelas dua”, “komunis” karena
SISIPAN
dituduh terlibat gerakan makar, antiPancasila. Atau korban peristiwa Mei 1998 dituduh “penjarah” oleh pemerintah dengan restu sebagian masyarakat. Penguasa secara aktif memecah-belah komunitas korban dengan merangkul sebagian dan menyingkirkan yang lain. Berangkat dari persoalan di atas, sejumlah kelompok korban dan organisasi pendamping korban sepakat untuk mengadakan lokakarya korban dan organisasi advokasi HAM di Wisma Hijau, Cimanggis pada akhir April 2001. Dalam pertemuan itu peserta lokakarya berbagi pengalaman dan meninjau kembali upaya-upaya penyelesaian kasus yang telah dilakukan selama ini. Dari hasil perbincangan ini dirasakan adanya kebutuhan membangun wadah bagi para korban kekerasan Orde Baru, yang bisa berfungsi sebagai wahana sekaligus kendaraan untuk secara bersama-sama membicarakan dan memperjuangkan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang mereka alami. Kemudian disepakati bahwa salah satu upaya yang harus dilakukanuntuk mencapai wadah bersama itu adalah dengan mempertemukan dan membangun jaringan antar korban di berbagai wilayah dan kasus di Indonesia dalam sebuah pertemuan korban tingkat nasional. Diputuskan pula bahwa pertemuan yang belum dipastikan waktunya akan bernama “Temu Korban Kekerasan Orde Baru” dan akan dibentuk panitia persiapan untuk menyebarkan gagasan ini ke kelompok-kelompok korban di daerah lain. Hasil pertemuan Cimanggis dirumuskan menjadi Materi Sosialisasi Temu Korban yang disebarkan ke berbagai organisasi pembela HAM, pendamping korban, dan kelompok korban di seluruh Indonesia. Secara garis besar bahan acuan ini berisi analisis korban terhadap kebijakan-kebijakan represif pemerintah Orde Baru yang telah mengakibatkan ribuan kasus pelanggaran HAM, strategi perjuangan korban untuk mencari keadilan dan membangun jaringan kerjasama antar korban, dan dengan organisasi HAM yang lebih luas. Selama setahun setelah lokakarya di Cimanggis panitia persiapan Temu Korban berkeliling ke berbagai kota di Indonesia, yaitu Padang, Lampung, Tasikmalaya, Garut, Jakarta, Solo, SISIPAN
Denpasar, Manado dan Palu untuk mengadakan pertemuan formal pun informal dengan berbagai kelompok korban dan organisasi HAM. Materi pembahasan mengalami banyak perkembangan dengan adanya masukan berharga dari kelompok-kelompok korban di luar Jakarta. Perbedaan-perbedaan yang awalnya tampak sulit dijembatani, seperti ketegangan antara korbankorban yang diberi label “ekstrim kiri” (Tragedi 1965) dan “ekstrim kanan” (Tragedi Talangsari dan Tanjung Priok), berhasil diatasi melalui kunjungankunjungan silaturahmi dan percakapan santai antar korban. Dari serangkaian pertemuan di tingkat lokal ini panitia persiapan Temu Korban berusaha merumuskan beberapa soal mendasar yang menjadi pokok perhatian korban. Berikut paparan singkatnya: 1. Siapakah korban? Rejim Orde Baru dibangun dengan pembunuhan massal dan tindak kekerasan yang tiada tandingannya dalam sejarah modern Indonesia. Sekitar 500.000 sampai tiga juta orang diperkirakan tewas dalam pembantaian yang berlangsung sejak Oktober 1965 sampai 1969. Sementara itu jutaan lainnya ditangkap, disiksa, diperkosa, ditahan tanpa proses pengadilan, dibuang ke kamp-kamp kerja paksa selama belasan tahun. Sanak keluarga mereka yang dianggap terlibat “G30S/PKI” diperlakukan sebagai “warga negara kelas dua” dan dijadikan sasaran diskriminasi selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Kekerasan politik yang bersifat sistematis dan meluas ini menjadi langkah pembuka para perwira militer, elit birokrasi dan pemegang modal besar untuk membuat sebuah sistem pemerintahan yang militeristik dan mengabdi pada kepentingan ekonomi segolongan orang saja. Penindasan terhadap mereka yang dianggap melawan kebijakan negara berlanjut di segala penjuru negeri ini sehingga melahirkan ratusan ribu korban baru dari masa ke masa. Mereka yang dianggap melawan, tapi berhasil lolos dari kebrutalan rejim ini menyandang “cacat sosial-politik” dengan cap-cap paten seperti “PKI”, “komunis”, “gerakan pengacau keamanan”, “subversif ”, “penjarah”, dan berbagai sebutan lainnya. Pemberian cap-cap ini bukan saja media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
melumpuhkan korban, tapi juga melindungi para pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Dalam banyak hal ribuan kasus kekerasan yang terjadi sejak 1965 memiliki kesamaan yang cukup kasat mata. Para pelaku semuanya adalah bagian dari rejim Orde Baru dan mereka melakukan tindak kekerasan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah ini. Sedangkan para korban adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mengkritik, melawan, dan ingin mengubah tatanan sosial-politik yang diciptakan rejim Orde Baru. Karena itulah kasus-kasus kekerasan yang menimpa mereka lazim disebut “kekerasan politik”. 2. Pengakuan bagi korban Sejak awal perjuangannya, tuntutan utama korban kekerasan politik Orde Baru adalah keadilan. Namun, setelah pergantian pemerintahan yang kesekian kali negara belum pernah memberikan pengakuan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal, pengakuan merupakan bentuk awal dari keadilan yang diharapkan korban, sebelum bisa sampai pada bentuk-bentuk keadilan yang lebih kompleks, seperti pemulihan, rehabilitasi, dan kompensasi. Pengakuan bagi korban bukan sekedar pernyataan lisan dari pemerintah yang berkuasa. Pengakuan membutuhkan pernyataan yang lebih menyeluruh dan bersifat publik. Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah pengakuan harus dapat menjelaskan latar belakang, pelaku, dan institusi yang terlibat dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM. Bersifat publik artinya pengakuan itu harus merupakan pernyataan resmi dari pemerintah yang ditujukan kepada seluruh warga negara republik ini. Hanya dengan pengakuan serupa inilah paling tidak penerimaan korban sebagai bagian dari warga masyarakat lebih dimungkinkan. Pengakuan bagi korban mencakup beberapa dimensi yaitu: A. Pengungkapan Kebenaran 1. Adanya institusi negara yang secara resmi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM, termasuk menetapkan kebijakan-kebijakan negara yang memfasilitasi kekerasan/pelanggaran HAM 2. Adanya institusi negara yang secara 49
sisipan0 11-2003
resmi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM, termasuk menetapkan institusi-pelaku yang bertanggungjawab 3. Adanya institusi negara yang secara resmi melakukan penyelidikan pelanggaran HAM dan mengakui terjadinya berbagai bentuk kekerasan, seperti pembunuhan massal yang disponsori negara, pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan institusi negara, keberadaan orang hilang, perkosaan sebagai metode kekerasan yang sistematis untuk melumpuhkan masyarakat, penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan 4. Adanya pengakuan terhadap keberadaan korban dan keluarga korban beserta akibat-akibat yang dideritanya B. Pengadilan 1. Pengadilan di luar pengadilan HAM dan pengadilan sipil —> pengadilan militer, pengadilan koneksitas 2. Pengadilan berdasarkan gugatan korban 3. Pengadilan sebagai mandat negara —> pengadilan HAM Ad Hoc C. Kompensasi dan Rehabilitasi 1. Korban hanya menerima ishlah yang didahului oleh pengakuan secara publik 2. Adanya instansi-instansi pemerintah yang menangani korban, bahkan sebelum adanya pengakuan resmi 3. Rehabilitasi terhadap nama baik korban 3. Posisi Korban dalam Masyarakat Tindak kekerasan yang dilancarkan terhadap korban telah menimbulkan kerusakan material dan non-material di pihak korban maupun keluarganya. Kerusakan awal yang diderita korban pelanggaran HAM adalah: a. penderitaan fisik, seperti cacat tubuh, gangguan jiwa, rasa ketakutan berlebihan yang melanda korban tanpa melihat latar belakang kejadian, bentuk kekerasan, atau ideologi korban b. penderitaan sosial, ketika pemerintah menempelkan cap-cap yang membuat masyarakat segan berhubungan dengan korban. c. kerugian material, seperti kehilangan rumah, mata pencaharian, kehilangan akses ke perekonomian. Kesulitan sosial dan ekonomi semakin menghambat gerak korban yang sebagian besar dari kalangan menengah ke 50
bawah. Peristiwa kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa mereka hanya menambah beban bagi kehidupan mereka yang sudah sulit. Korban kekerasan di desa Talangsari, Lampung umumnya adalah para santri dari keluarga petani miskin, korban kekerasan di Tanjung Priok juga para santri yang terpuruk dalam kemiskinan di pantai utara Jakarta, korban kekerasan Tragedi 1965 kebanyakan adalah petani yang tak bertanah, korban kekerasan di Aceh pada umumnya adalah keluarga petani pula. Keterbatasan ekonomi korban adalah salah satu faktor penting yang menjadi kendala bagi korban untuk melanjutkan tuntutan atas keadilan. Tak jarang kepasrahan muncul dalam aneka bentuk ketidakberdayaan. Misalnya, salah satu alasan sebagian korban pembantaian Tanjung Priok menerima ishlah yang ditawarkan pihak pelaku adalah tekanan ekonomi yang tak tertahankan lagi. Terlibat dalam organisasi korban dengan berbagai kegiatan membutuhkan tenaga, waktu dan biaya tak sedikit. 3. Problem Internal Organisasi Korban Semenjak pertengahan 1998 bentuk dan jumlah organisasi korban semakin berkembang. Bahkan untuk kasus 1965 terdapat lebih dari satu organisasi korban dengan kegiatan yang tak terlalu berbeda. Tidak hanya berkumpul, korban bersama dengan organisasi pendamping atau dengan kelompok lainnya dengan berani mengungkapkan kisah mereka kepada publik dan mengajukan tuntutan terbuka kepada institusi-institusi pemerintah yang berwenang. Organisasi korban juga berhasil membangun kerjasama yang baik dengan berbagai LSM dan organisasi mahasiswa. Di balik kemajuan yang cukup pesat ini, organisasi korban sangat rentan terhadap perpecahan, baik yang disebabkan oleh faktor dari luar – penawaran dana untuk melakukan ishlah – maupun oleh ketidakmampuan organisasi mengatasi konflik yang terjadi diantara para anggotanya. Perpecahan ini membuat organisasi korban kesulitan mempertahankan kesinambungan aktifitas mereka. Alhasil, korban seringkali tidak siap merumuskan sikap dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi sosial, ekonomi, atau politik yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika pengadilan ad media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
hoc yang pertama berlangsung, yaitu untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, tidak ada persiapan sama sekali dari korban untuk mengamati jalannya pengadilan tersebut. Padahal, pengadilan ini menjadi tolok ukur pengadilan HAM berikutnya. Demikian juga dengan terbentuknya dan kinerja macam-macam panitia penyelidik yang tak mendapat pengawasan yang terencana dan seksama dari kelompok-kelompok korban. Gerak organisasi korban masih sangat ditentukan oleh momentum-momentum yang tercipta di luar kemampuan mereka. 4. Peran Lembaga HAM Lembaga HAM, termasuk Komnas HAM, selama ini cukup terlibat dengan korban dalam menangani penyelesaian kasus-kasus yang mereka alami. Namun, korban belum pernah merumuskan apa sebetulnya peran lembaga ini bagi korban sehingga bisa terjadi kerjasama untuk mendorong perwujudan pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Para korban berharap bahwa: - organisasi korban memiliki kemandirian dalam menentukan visi dan program kerjanya, - peran lembaga HAM dirumuskan dalam rangka memperkuat upaya perjuangan memperoleh keadilan, baik dalam upaya mendapatkan pengakuan, pemulihan hak-hak korban, maupun penguatan organisasi korban 5. Tujuan Temu Korban Tuntutan terhadap keadilan tidak sesederhana pengadilan. Ada kompleksitas yang harus dihadapi korban. Oleh karenanya penyelesaian kasus, perjuangan memperoleh keadilan, membutuhkan daya tahan organisasi korban dan kerjasama yang luas dengan lembaga HAM dan masyarakat. Temu Korban Kekerasan Orde Baru bertujuan untuk: a. merumuskan pandangan korban tentang keadilan b. meningkatkan kesadaran korban tentang kekuatannya c. merumuskan platform perjuangan korban d. membangun jaringan organisasi dan kelompok korban 0
SISIPAN
DEKLARASI ALIANSI KEMANUSIAAN KORBAN KEKERASAN NEGARA Kekerasan yang terjadi di Indonesia sejak awal Orde Baru hingga sekarang sesungguhnya dilatarbelakangi oleh perubahan kekuasaan negara yang terjadi pada 1965. Untuk mempertahankan kekuasaannya, rezim Orde Baru melakukan penyimpangan terhadap konstitusi negara dengan membuat produk hukum dan lembaga untuk membenarkan penggunaan kekerasan secara sistematis terhadap rakyat. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun dapat kita lihat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965, Peristiwa Malari, Komando Jihad, Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari Lampung, pemberlakuan operasi-operasi militer di Aceh dan Papua, Peristiwa 27 Juli, penculikan aktivis pro-demokrasi, Tragedi Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, dan di dalam setiap peristiwa konflik sosial & politik tersebut perempuan menjadi bagian dari korban, termasuk menjadi korban kekerasan seksual. Kenyataan dari peristiwa tersebut membuktikan bahwa kekerasan negara bukanlah sesuatu yang bersifat kasuistis tapi adalah mata rantai untuk mempertahankan kekuasaan. Akibat perbuatan kekerasan tersebut berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan membekaskan luka-luka badan dan hati. Semua derita yang masih ditambah dengan diskriminasi yang dilakukan oleh dan atas nama negara ini tersimpan dalam hati para korban dan masyarakat, tidak bermuara pada dendam tapi pada kehendak luhur bagi negara dan bangsa. Mengingat kekerasan-kekerasan tersebut maka Aliansi Kemanusiaan yang menjadi korban kekerasan tersebut bersamasama masyarakat secara luas mengajukan: 1. KEPADA PENYELENGGARA NEGARA a. Mengambil langkah untuk menghentikan tindakan kekerasan negara b. Menyelenggarakan proses pengadilan yang sehat dan tidak memihak dengan memperbaiki sistem, prosedur dan mekanisme Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan peradilan pada umumnya, dengan menempatkan warga negara yang memiliki independensi, integritas dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia. 2. KEPADA KELOMPOK KORBAN a. Membangun Aliansi dengan mengukuhkan kerjasama antara sesama korban serta menumbuhkan solidaratis b. Menumbuhkan solidaritas antar kasus c. Membangun jaringan komunikasi antar kelompok korban d. Mengkoordinasikan kerjasama untuk pengungkapan kebenaran dan pemulihan e. Melanjutkan kegiatan formal dan legal terhadap penyelenggara negara f. Menggalang perjuangan Aliansi dengan berbagai organisasi masyarakat, seperti partai politik, NGO, di tingkat lokal, nasional dan internasional 3. KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT a. Aliansi mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan pencapaian keadilan, yang meliputi pengungkapan kebenaran, pengadilan, pemulihan dan pencegahan keberulangan kekerasan b. Aliansi mengajak masyarakat membangun kerjasama dan persatuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Maka Aliansi berpendapat perlunya melakukan: 1. Supaya penyelenggara negara mentaati dan menghormati dan SISIPAN
melaksanakan dengan sungguh-sungguh Konstitusi Negara 2. Menjadi perlu untuk mereview semua produk hukum dan lembaganya, sehingga yang tidak sesuai atau berlawanan dengan Konstitusi secara bertahap dapat dilakukan 3. Menghentikan segera tindakan-tindakan diskriminatif dari kalangan penyelenggara negara, baik terhadap para korban kekerasan maupun masyarakat pada umumnya 4. Mensosialisasikan informasi-informasi yang benar mengenai semua peristiwa kekerasan yang terjadi Cimanggis Minggu, 11 Mei 2003 Aliansi Kemanusian Korban Kekerasan Negara
Resolusi Temu Kemanusiaan Korban Orde Baru Wisma Hijau, 9 – 11 Mei 2003 I. PERADILAN A. untuk kasus-kasus yang sedang dalam proses pengadilan (kasus Abepura dan Tanjung Priok): 1. segera menjalankan proses persidangan dengan menunjuk hakim dan jaksa yang berkemampuan dan memiliki integritas terhadap penegakan HAM 2. selama proses persidangan terdakwa harus ditahan 3. terdakwa tidak boleh dan atau di nonaktifkan dari jabatan publik B. untuk kasus-kasus yang sedang dalam proses penyelidikan (Trisakti-Semanggi I,II): 1. cabut rekomendasi DPR 2. mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan 3. mendesak pemerintah untuk menerbitkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc II. ACEH 1. mendesak pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan menarik mundur seluruh pasukan militer 2. melanjutkan proses damai dengan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat sipil 3. membubarkan milisi-milisi di Aceh III. PAPUA 1. mendesak pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan menarik mundur seluruh pasukan militer pasca penyerangan markas Kodim Jayawijaya 2. melanjutkan proses damai dengan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat sipil 3. membubarkan milisi-milisi di Aceh IV. PEMULIHAN 1. mencabut seluruh produk hukum yang mendiskriminasikan korban pelanggaran (berat) HAM 2. memberikan rehabilitasi kepada seluruh korban pelanggaran (berat) HAM
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
51
sisipan0 11-2003
Narator (Agus Nur Amal) Mengapa kami yang mereka pilih untuk dijadikan korban? Sutradara: Agus Nur Amal Sebab hanya dengan cara mengorbankan kami, mereka bisa mendapatkan dan memperkuat kedudukan. Sebab bagi mereka, mengorbankan kami adalah cara untuk SERIBU LILIN, SERIBU KISAH mempersatukan diri mereka sendiri. Sebab mengorbankan kami berarti memperkaya mereka. Di Klender Kita Berjanji Selama puluhan tahun kami berada dalam kesunyian dan penderitaan. OPENING Namun, selama puluhan tahun pula kami bertahan untuk MC (Ani Rukmainah) kebenaran dan keadilan. Selamat malam, Di tahun ’65…. Panitia Temu Korban mengucapkan terima kasih atas Wakil ’65 (mengkisahkan pengalaman pribadinya) kesediaan Bapak dan Ibu menghadiri acara Peringatan Mei Narator (Agung Ayu) 2003 ini. Sejak 1989 hingga 1998, Di Aceh…. Selama beberapa hari kemarin, kami beserta sahabatsahabat kami, para korban dari Paguyuban Keluarga Wakil Aceh (mengkisahkan pengalaman pribadinya) Korban Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Aceh, Papua, Narator (Agus Nur Amal) Talang Sari, Tanjung Priok, ’65, 27 Juli, Penculikan telah Di Tanjung Priok…. berkumpul bersama untuk saling berdiskusi dan membahas Wakil Tanjung Priok berbagai agenda pekerjaan. Yang aku tahu masyarakat di kampungku kesulitan Di tengah-tengah kesibukan selama empat hari kemarin itu, memperoleh air bersih, tak punya cukup uang untuk makan kawan-kawan korban menyempatkan diri berlatih untuk sehari-hari, apalagi menyekolahkan anak. Tak kudengar mempersembahkan sebuah pertunjukan kesenian. Seribu rencana mendirikan negara Islam. Orang-orang kampungku Lilin, Seribu Kisah: Di Klender Kita Berjanji, adalah judul marah karena teman-teman kami ditangkapi begitu saja. pertunjukan kami di malam hari ini. Sesudah itu mesjid kami dilecehkan. Padahal, di mesjid-lah Harapan kita semua, pertunjukan malam ini akan kami peroleh keteduhan. memperkuat semangat kita, untuk bersama korban, Orang-orang kampungku cuma menuntut keadilan. Kami memperjuangkan keadilan dan mencegah terulangnya sudah tahankan kemiskinan. Orang-orang kampungku kekerasan. cuma berbekal kepercayaan kepada Allah SWT. Tapi, Bapak, Ibu, dan Kawan-kawan semua, selamat seruan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” tak cegah pasukan menyaksikan. bersenjata muntahkan ratusan, mungkin ribuan pelor panas, tembusi tubuh anak, kekasih hati, dan orang tua Musik: “Nyanyian Para Saksi”1 (Sanggar Akar) kami. Tak selamanya kami akan diam Aku sungguh tak tahu apa kesalahan kami sehingga harus Tak selamanya kami merunduk dimusnahkan begitu rupa. Segala yang hidup ada batasnya Narator (Agung Ayu) Kami yang lemah pun kini bangkit Di Talang Sari, Lampung….. Wakil Talang Sari Terlalu lama diri kami disingkirkan Pukul menunjukkan jam 04.30 pagi. Terdengar azan subuh Terlalu lama luka pun menganga memecah hening di pagi itu. Para jemaah berkemas untuk Terlalu banyak milik kami yang dirampas bersiap menghadap Ilahi dengan menunaikan sholat subuh. Sekarang saat bagi kami untuk bergerak Tidak ada firasat sama sekali kalau sholat subuh saat itu adalah sholat subuh terakhir kali, karena tepat jam 05.30, Satukan niat ayunkan langkah bersama kita maju tiba-tiba terdengar desingan suara peluru di mana-mana Bersatu padu meretas tuntas segala pembodohan menerjang kesunyian di pagi itu. Kami kan bangun dunia baru tanpa darah dan luka Tak lama terdengar kumandang “Allahu Akbar, Allahu Akbar”, pekik Jemaah Warsidi menyongsong peluru yang Pada saat lagu dikumandangkan, pemain bangkit dari datang. antara penonton menuju Lilin Keadilan. Satu per satu Satu per satu tubuh bergelimpangan diterjang oleh timah pemain meletakkan bunga di dekat Lilin Keadilan, kemudian panas para tentara. duduk membentuk lingkaran di sekelilingnya. Setelah itu hening timbul kembali dan tak lama terdengar derap langkah tentara memasuki halaman Pondok BABAK I Pesantren Warsidi…. Di situlah ratusan manusia bergelimpangan sudah tak MENGAPA KITA MENJADI KORBAN? bernyawa lagi. Narator (Agus Nur Amal) Refleksi Kemanusiaan (Ita F. Nadia)
Acara Peringatan Mei, 13 Mei 2003
52
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
Pada tanggal 27 Juli 1996…. Wakil 27 Juli 1996 Minggu pagi buta, aku dan ratusan kawan lainnya sudah berjaga-jaga akan kemungkinan diserang Kami menyebar di sekeliling markas pusat PDI, juga di atas wuwungan gedung, berbekal tongkat, benda pemukul apa saja, dan keyakinan bahwa kami benar. Dari kejauhan tampak ratusan orang mendekati markas, diantar tentara, membawa obor dan jerigen bensin. Begitu mereka sampai di depan pagar, mereka mulai melempari kami dengan batu bertubi-tubi. Hubungan telpon terputus. Tak lama kemudian terlihat empat buah panser, dan sepenggal jalan Diponegoro sampai Megaria diblokade. Lemparan batu tak berhenti, gerbang diguncang-guncang sampai rubuh. Kami coba bertahan dengan kursi sebagai tameng. Tapi, serbuan ratusan orang bersama tentara ke dalam markas tak tertahankan. Aku bersembunyi gemetaran di bawah meja, menyaksikan bagaimana gerombolan berkaus merah PDI dan bertutup kepala seperti ninja mengayun-ayunkan kelewang, samurai, menghancurkan harta benda partai, menghilangkan kehidupan kawan-kawanku sambil berteriak-teriak beringas. Mereka seperti pemburu binatang buas, padahal tak seorang pun dari kami bersenjata. Darah menggenang di mana-mana Yang tersisa dari kami segera digiring ke mobil tahanan seperti penjahat. Jasad-jasad kaku dilemparkan ke truk, dibawa pergi, entah ke mana. Markas disembur air pemadam kebakaran. Darah kawan-kawanku sirna tersedot bumi bersama air. Narator (Agung Ayu) Di Surabaya, Lampung, Solo, Jakarta…. Wakil Penculikan Biasanya paling tidak seminggu sekali Bimo akan telpon, sekadar berkabar kepada kami orang tuanya. Sejak ia bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik, Kami memang selalu mengkhawatirkan keselamatannya. Memang kami selalu berdiskusi dengan Bimo tentang persoalan-persoalan rakyat yang mengganggu pikirannya. Tapi, di jaman Orde Baru itu bicara tentang persoalan rakyat kan resikonya besar. Nah, kami tak lagi mendengar kabar darinya sejak Maret 1998. Kami tak tahu apa kesalahannya. Setahu kami, dia orang yang keras hati, tapi sebetulnya dia orang yang mudah tersentuh dan selalu mau mendengarkan orang lain. Sahabat-sahabatnya menyampaikan pada kami bahwa dia sangat setia menemani kawan-kawannya, ia tak bisa meninggalkan kawan dalam kesendirian. Bimo pandai bermusik dan menulis lagu; dia membentuk kelompok band di kampusnya Bimo juga suka menulis dan membuat desain grafis.
SISIPAN
Kami benar-benar tak paham mengapa pemuda dengan kemampuan dan talenta sekaya itu harus dihilangkan? Narator (Agus Nur Amal) ’98 Mei di berbagai kota…. Wakil Mei ’98 (membacakan puisi) Narator (Agung Ayu) Di kampus Trisakti dan Semanggi… Wakil Trisakti dan Semanggi Apakah aku pejuang atau pahlawan reformasi? Aku tak tahu itu hanya ungkapan orang Aku bosan dilecehkan ketika Kau bercerita perjuangan Seakan aku seorang pelawak Aku bukan pelawak, aku hanya mencoba Aku mencoba kata hati nurani Aku berusaha untuk orang lain Aku tak peduli pada balas budi Aku hanya bisa berusaha agar semua orang bisa tersenyum Aku hanya ingin semua orang bisa bebas Aku hanya ingin mencintai Terlalu besar yang aku korbankan Kuliah, jodoh, dan kedamaian Berbulan-bulan aku dicekam rasa takut disiksa Berbulan-bulan aku lari dari hidup normal Tapi perjuangan yang hampir selesai musnah Reformasi kini hanya kedok penguasa Aku masih ingin berjuang, tapi itu tidak mungkin Kiri kananku jurang, depan belakangku tembok Aku sendiri, haruskah aku lari keluar seperti yang lain? Belum, aku masih punya nyawa, dan itu pengorbanan terakhirku2 Narator (Agus Nur Amal) Dari Papua…. Wakil Papua (mengkisahkan pengalaman masyarakat) Lagu: “Kepada yang Hilang”3 (Sri Wulan-diiringi koor) Pergi, pergilah dengan tenang Jangan sisakan jerit rontamu Pada daun, musim, bumi, dan langit Kami yang tinggal di sini Selalu memanjatkan doa-doa Semoga perjalananmu abadi Menuju arasnya Ilahi. MC (Ani Rukmainah) Sahabat dan keluarga kita yang menjadi korban… Litani Nama Korban (Arswendi Nasution dan Vien) Narator secara bergiliran membacakan 491 nama korban. Beberapa saat nama-nama korban dibacakan, seluruh pemain secara serentak dengan suara pelahan mengucapkan nama-nama korban seperti sedang berzikir,
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
53
sisipan0 11-2003
dan berakhir ketika dua narator selesai membacakan nama-nama korban. Setelah nama korban terakhir dibacakan (Widji Thukul) langsung dibacakan puisi. Puisi: Bunga dan Tembok4 (Sipon-musik ilustrasi) Seumpama bunga kami adalah bunga yang tak Kau kehendaki tumbuh Engkau lebih suka membangun Rumah dan merampas tanah Seumpama bunga Kami adalah bunga yang tak Kau kehendaki adanya Engkau lebih suka membangun Jalan raya dan pagar besi Seumpama bunga Kami adalah bunga yang Dirontokkan di bumi kami sendiri Jika kami bunga Engkau adalah tembok Tapi di tubuh tembok itu Telah kami sebar biji-biji Suatu saat kami akan tumbuh bersama Dengan keyakinan: engkau harus hancur! Dalam keyakinan kami di mana pun-tirani harus tumbang! BABAK II TANTANGAN-TANTANGAN MENCAPAI TUNTUTAN KORBAN Musik Ilustrasi Drama “Tantangan dalam Perjuangan Korban” SINOPSIS DRAMA Korban berjuang di mana–mana masing-masing menuntut keadilan atas kasus yang menimpanya. Ke sana-ke mari selalu menghadapi kegagalan, kekecewaan, penolakan, bahkan kekerasan. Korban 27 Juli, Aceh, Mei, ’65, Papua, Tanjung Priok, Talang Sari, Trisakti-Semanggi, Penculikan. Para korban yang menuntut keadilan hampir putus harapan hingga suatu saat mereka saling bertemu, bertukar pikiran. Mereka semua menginginkan hal yang sama: terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan.
Para pemain drama maju satu per satu, berkumpul di dekat altar, berbincang-bincang, kemudian menyalakan keadilan. BABAK III SOLIDARITAS MENGHADAPI TANTANGAN Puisi: “Seruan Sesama Korban”5 (Katmi-SIP)
54
Pemain Drama Aceh (beat lambat) Daerah Aceh, tanoh loen sayang Nibak tempat nyan, loen udeep matee…. Seluruh pemain (beat cepat, menari) Daerah Aceh, tanoh loen sayang Nibak tempat nyan, loen udeep matee… Tanoh keunebah, indatu moyang Lampoh dengon blang, luah bukon lee…2x Ureung jak u glee, na so peuseunang Na so peutimang, keureja matee…. Hatee yang susah, loen rasa senang Aceh loen sayang, sampo’an matee….2x Pemain Drama Papua (beat lambat) Iriani sup iriani….2x Seluruh Pemain (beat cepat-menari) Iriani sup iriani2x Yembe mawa yembe pioper Yafa fnakro Yaswar epna, yaswar epna Isof fioro-fioro…2x
Lagu diakhiri dengan teriakan: FIORO! Pemain sudah membentuk barisan beberapa saaf di kirikanan menghadap lilin keadilan. Pidato: “Melangkah ke Depan” (Ibe Karyanto) Lagu Mars: “Suara Korban”6 (Seluruh pemain) Semua yang terluka, marilah satukan s’luruh daya Di atas tanah kelahiran, di kolong langit kehidupan Mari kita bicara, di dalam bahasa para korban Yang tak kenal perseteruan atas penderitaan Akhiri s’gala bentuk kezaliman, tumpas segala kepalsuan Tegakkan jiwa persaudaraan sebagai rahim keadilan Meski dalam derita, marilah bergerak kita maju Lintasi batas ketakutan, arungi batas perbedaan Dalam duka yang sama bersatu menyusun langkah baru Merebut semua hak kita, merebut kehidupan Patahkan rasa ‘tuk saling curiga, merengkuh saudara yang lemah Satulah kita sebagai pertanda penjaga setia kebenaran
Empat pemain di barisan terpinggir maju ke arah lilin keadilan dan menyalakan lilin yang dipegangnya. Mereka membagi api lilin tersebut kepada pemain lain. Deklarasi Aliansi Kemanusiaan Korban Kekerasan Negara (Wakil pemain) Lagu Mars: “Suara Korban” (Seluruh pemain dan hadirin)
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
Setelah lagu selesai dinyanyikan, pemain secara berurutan berjalan kembali ke arah penonton dan berbaur kembali. CLOSING MC (Ani Rukmainah) Bapak, Ibu, yang terhormat Demikianlah pertunjukkan singkat kami di malam ini Semoga semangat solidaritas dan cinta akan kebenaran dan keadilan Yang dikumandangkan para korban menjadi panduan bagi kita semua Dalam mendukung perjuangan para korban Seluruh kepanitiaan Peringatan Lima Tahun Tragedi Mei 1998 Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada kawankawan seniman Aceh dari SAJAK dan kawan-kawan Jentera Muda Jakarta (JMJ) yang tak kenal lelah dan bosan melatih para pemain. Kepada Ibe Karyanto yang bersedia memenuhi permintaan panitia menciptakan lagu mars ‘Suara Korban” hanya dalam waktu dua hari. Teman-teman Sanggar Akar yang telah menyempatkan diri mengiringi musik. Terima kasih juga kami hunjukkan kepada kawankawan aktivis perempuan dari berbagai organisasi, khususnya Suara Ibu Peduli, atas sumbangan bebungaan yang mengharumi dan memberi warna tersendiri pada acara ini.
Badan Pekerja Temu Kemanusiaan Korban Orde Baru Penanggung Jawab: Agung Putri Keuangan: Erine Ismayani Sie Kepesertaan: Dyah Wara, Fatima Astuti, E. Rini Pratsnawati,Taat Ujianto Sie Akomodasi: Amos Sembiring, Dr. Eko (medis) Sie Konsumsi: Etty, Ipah, Mariatun, Mona Sie Transportasi: Diana, Hanna, Kokom,Victor da Costa Sie Acara: Agnes Diana, Atnike Sigiro, Esti Kristanti, Bp. Sasmoyo Sie Kesenian: Agung Ayu, Agus Nuramal,Th. J. Erlijna Sie Dekorasi: Alit Ambara, Anna HP, Elly Sie Dokumentasi: Andre Susanto, Anton Stevanus,Yayan Wiludiharto, Sandy Therodelita,Wibowo Sie Publikasi dan Humas: Ibu Sumarsih, Herman Wikoco, Nining Sie Keamanan: Adi Prasetyo, Isnu Handono, Bp. Effendi, Lefidus Malau Sie Peringatan Mei: Ibu Darwin, Syaldi Pembantu Umum: Eka, Dewi
Tim Fasilitator: Amiruddin, Atnike Sigiro, Benny Biki, Hilmar Farid, Indriaswati Saptaningrum, Ita F. Nadia, Kamala Chandrakirana, Ori Rahman, Rinto Trihasworo, Ruth Indiah Rahayu, Rudi Rizki, Sentot Setyosiswanto,Wayan Santa Tim Notulis: Aquino, Eka, Grace, Razif, Reza, Suluh, Syaldi,Winda Tim Petugas Penghubung/LO : Asih, Benny, Etty, Iwan, Lili, Liza, Mona, Peri,Tigor Tim Pengemudi: Cecep, Untung
Penyerahan empat rangkaian bunga kepada wakil SAJAK, JMJ, Komnas Perempuan, dan SIP. Sebagai penutup acara malam ini, kami minta kesediaan bapak Direktur Mal Citra untuk memberikan ungkapan perasaan atas peristiwa malam ini. Kami persilakan
Sambutan Manajer Mal Citra MC (Ani Rukmainah) Pemberian karangan bunga pada Manajer Mal Citra dari Temu Korban Nasional
Tim Penasehat: Amiruddin, Hilmar Farid, Rm. I. Sandyawan S., SJ, Ifdhal Kasim, Ita F Nadia, Kamala Chandrakirana, Lily Hasanuddin, M. Habib Chirzin, Ruth Indah Rahayu, Salahudin Wahid, Saparinah Sadli. Lembaga Pendukung: ELSAM, Kalyanamitra, Keluarga Korban Priok, Keluarga Korban Talangsari, Komite S’malam, Komnas Perempuan, KontraS, Paguyuban Keluarga Korban dan Korban Mei’98, Paguyuban Keluarga Korban Semanggi I-II, Pakorba, SHMI,TRuK,Yappika.
Pemberian karangan bunga diberikan oleh seorang wakil pemain. MC (Ani Rukmainah) Bapak-Ibu yang budiman, terima kasih, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak-Ibu menghadiri acara Peringatan Mei pada 2003 ini. 1 Cipt.: Ibe Karyanto | 2 Puisi berjudul “Reformasi”, cipt. BR. Norma Irmawan | 3 Cipt. Rahmad Sanjaya | 4 Cipt. Widji Thukul | 5 Cipt.: Hersri Setiawan | 6 Cipt.: Ibe Karyanto
SISIPAN
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
55
sisipan0 11-2003
MARS SUARA KORBAN cipt.: IBE Karyanto
56
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
SISIPAN
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
57
CERITA PENDEK
Bah! Saut Situmorang
M
alam itu aku datang lagi ke situ. Aku sudah sangat rindu pada perempuanku. Perempuanku yang manis, perempuanku yang pandai menghibur. Aku mempercepat langkahku, membelok ke gang terakhir menuju gerbang masuk perkampungan kecil di mana perempuanku itu tinggal. Perkampungan itu sangat sunyi. Hanya beberapa anak kecil nampak sedang main kejar-kejaran dan dua-tiga perempuan berpapasan denganku. Mereka menyapaku dan kubalas dengan anggukan kepala. Rumah perempuanku terletak agak di tepi perkampungan kecil itu. Rumah itu juga kecil. Hanya punya sebuah kamar tidur dan kamar mandi saja. Tak ada dapur dan perempuanku membeli makanannya di rumah makan di luar perkampungan atau pada para penjual bakso atau sate yang sering masuk ke situ. Mengingat perempuanku yang manis itu, tanpa sadar aku mempercepat langkahku. Tinggal seratusan meter dari rumah perempuanku, tibatiba kuhentikan langkahku. Aku lihat seorang laki-laki muncul dari dalam rumah itu. Laki-laki itu berdiri sebentar di ambang pintu, sepertinya sedang mengawasi sesuatu, lalu kembali menutup pintu rumah perempuanku. Aku jadi heran. Bukankah perempuanku sudah berjanji akan memberikan malam ini sepenuhnya untukku? Bukankah dia bilang tak akan ada orang yang akan mengganggu? Aku masih termangu-mangu di tempatku itu sambil mencoba mengingat-ingat perkataan perempuanku seminggu lalu waktu pintu rumahnya terbuka lagi dan laki-laki tadi muncul kembali di ambang pintu. Kembali dia bersikap seperti sedang mengawasi sesuatu di luar rumah sebelum menutup pintu. Rasa penasaranku makin menjadi-jadi hingga kuputuskan untuk mendatangi saja rumah perempuanku itu. Mulanya aku hendak masuk lewat pintu depan di mana laki-laki tadi berdiri, tapi segera kubatalkan. Aku ingin menyelidiki dulu siapa laki-laki itu dan kenapa tingkahnya aneh begitu. Untuk itu aku harus mengintip apa yang dilakukannya di dalam rumah perempuanku. Aku juga heran kenapa perempuanku
58
sedari tadi tak pernah muncul-muncul. Apa dia tak ada di rumah hingga laki-laki tadi harus menunggunya? Mungkin laki-laki itu tak sabar menunggu begitu lama… Baru saja tanganku meraba dinding rumah perempuanku, tiba-tiba aku dengar suara laki-laki dari dalamnya. Aku yakin suara itu pasti punya si laki-laki yang kulihat di pintu tadi. Suara itu agak berat dan kasar. Kayaknya dia sedang marah. Tapi, marah pada siapa? Akhirnya aku berhasil memergoki sebuah lobang kecil dekat jendela. Kudekatkan mataku ke lobang itu dan coba melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Mataku langsung melihat laki-laki tadi. Dia sedang duduk di atas ranjang perempuanku dan wajahnya menghadap ke arahku. Rasa-rasanya aku seperti mengenali laki-laki setengah baya yang sedang marah itu. Kucoba mengingat-ingat, tapi aku lupa. Kuamati lagi wajahnya yang bulat dan gempal itu, aku yakin aku mengenalnya. Tapi aku tetap lupa siapa namanya. Sekarang kucoba cari perempuanku. Aku lihat kursi dekat cermin yang tergantung di dinding, kosong. Biasanya dia suka duduk di kursi itu sambil menyisir rambutnya. Aku jadi tambah heran. Aku lalu kembali ke tempat tidur. Laki-laki itu masih duduk di situ. Tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berjalan ke arah pintu. Pada waktu itulah perempuanku nampak padaku. Dia telungkup di atas ranjang. Wajahnya terbenam di bantal. Kulihat punggungnya bergerak-gerak tak teratur. Dia sedang menangis. Tapi, kenapa? Kenapa dia menangis dan kenapa laki-laki tadi kelihatan marah dan resah? Siapa lakilaki itu dan apa yang sedang terjadi di sini? Laki-laki itu kembali menutup pintu dan berjalan ke arah tempat tidur di mana perempuanku sedang menelungkup menangis. Wajah laki-laki itu mengerikan sekali. Kemarahan yang sangat dahsyat memancar di matanya. Begitu sampai di tepi ranjang, tangan kanannya langsung bergerak ke kepala perempuanku. Dengan kasar dijambaknya rambut perempuanku yang panjang itu. Perempuanku menjerit kesakitan tapi berusaha
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ALIT AMBARA
CERITA PENDEK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
59
menahannya agar tak terdengar ke luar. Wajahnya basah airmata. Tiba-tiba kurasakan api kemarahan muncul dalam diriku. Aku mulai panas. Aku ingin mendobrak masuk dan menghajar laki-laki yang menyakiti perempuanku itu. Kurasakan badanku mulai gemetar. Sambil melepaskan jambakannya, laki-laki itu mulai memaki-maki perempuanku yang sekarang duduk di atas ranjang dan menangis terisak-isak. Dia memakinya “lonte tak tahu diri”, “pelacur jorok”, “perempuan tukang serong,” dan kata-kata kasar lainnya yang tak pantas diucapkan pada seorang perempuan, apalagi perempuan seperti perempuanku itu yang begitu manis dan pandai menghibur hati. Perempuanku tak menjawab sepatah kata pun dan hanya menangis di atas ranjang sambil menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Setelah puas memaki-maki, laki-laki itu lalu membentak perempuanku supaya berhenti menangis, melihat padanya, dan menjawab pertanyaannya. Perempuanku menurut. Dihentikannya tangisnya dan mengangkat wajahnya memandang ke arah laki-laki itu. Wajah itu basah dan nampak bengkak. Dia bertanya tentang “siapa lelaki itu” dan minta perempuanku menjawabnya dengan jujur. Perempuanku cuma diam. Tak ada satu bunyi pun keluar dari mulutnya. Lakilaki itu mengulang pertanyaannya. Perempuanku tetap tak menjawab. Lalu diulanginya lagi pertanyaannya tadi. Karena tetap tak mendapat jawaban, tangan kanannya yang besar dan kasar melayang ke pipi kiri perempuanku. Plak! Perempuanku terjungkal ke belakang dan jeritan kecil keluar dari mulutnya. Laki-laki itu lalu menarik rambutnya hingga dia kembali ke posisinya semula duduk di atas ranjang. Kemudian kembali tangannya melayang berkali-kali ke wajah perempuanku yang mulai berdarah itu. Kulihat bibirnya pecah dan darah ada di wajahnya, baju tidurnya, seprei, dan di tangan kanan laki-laki itu. Laki-laki itu lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Sebuah pistol kecil! Kaget sekali aku melihatnya. Pistol kecil itu ditodongkannya ke dada perempuanku yang kini 60
cerita pendek
memandangnya dengan mata terbelalak ketakutan. Sekarang aku tak tahu harus berbuat apa. Keinginanku untuk melabrak masuk terpaksa aku tunda. Dari lobang dekat jendela itu kulihat laki-laki itu mulai tersenyum! Bangsat, apa orang ini sudah gila! Dia bisa tersenyum dengan pistol di tangannya ditodongkan ke dada seorang perempuan yang memandangnya ketakutan! Laki-laki ini benar-benar bajingan! Seekor binatang gila! Dia malah mengancam akan menembak perempuanku kalau tetap tak mau menjawab pertanyaannya itu. Katanya perempuanku lebih baik mampus daripada jabatannya sebagai walikota hancur. Walikota! Ah, aku ingat sekarang. Ya, aku ingat laki-laki ini adalah walikota kotaku yang sering kubaca beritanya di koran lokal dan sering muncul di tv lokal. Dia juga sering hadir di seminarseminar yang diadakan di kampusku. Aku ingat siapa dia sekarang. Laki-laki bajingan yang sekarang kupanggil si Walikota itu mengulurkan tangan kirinya ke arah dada perempuanku dan mulai meremasremas kedua buah dadanya sambil tersenyum. Dia meremas-remasnya dengan kuat hingga perempuanku meringis kesakitan dan menggeliatgeliatkankan badannya. Kembali walikota itu mengulangi pertanyaannya. Tapi tetap saja perempuanku tidak menjawabnya. Merasa kalau perempuanku tidak akan pernah menjawab pertanyaannya itu walau disakiti sekalipun, walikota itu mulai hilang kesabarannya. Dengan kasar dirobeknya baju perempuanku. Dirobek dan dirobeknya terus hingga perempuanku hampir telanjang bulat duduk di atas ranjang di depannya. Hanya kutang dan celana dalamnya saja yang tinggal. Lalu dipaksanya perempuanku membuka keduanya. Karena sangat ketakutan, perempuanku menuruti perintah walikota yang sekarang juga mulai membukai pakaiannya sendiri itu. Lalu walikota itu memperkosa perempuanku sementara pistol kecilnya ditodongkannya ke kepalanya. Aku memejamkan mataku. Tangis perempuanku dan kemarahanku memukul-mukul kepalaku. Aku berusaha tenang. Aku berusaha mengendalikan amarahku karena kalau media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
aku mendobrak pintu dan membuat walikota bangsat itu gugup, terancamlah nyawa perempuanku. Aku tak mau perempuanku mati terbunuh setelah disiksa dan diperkosa. Walikota itu mesti mempertanggungjawabkan perbuatan biadabnya itu. Aku juga ingin tahu siapa laki-laki yang membuat walikota itu begitu marah hingga membuatnya melakukan perbuatan gilanya terhadap perempuanku. Aku tak boleh kalap, aku tak boleh membuat keselamatan perempuanku terancam… Aku tak tahu entah berapa lama berlalu ketika tiba-tiba kudengar suara “tep”, “tep” yang sangat halus dari dalam rumah. Lalu suara orang melangkah tergesa-gesa, pintu dibuka, dan suara langkah di halaman. Lalu sunyi. Aku tak mendengar apa-apa lagi. Aku coba melihat ke dalam rumah lewat lobang kecil tadi. Perempuanku ada di atas ranjang, telanjang bulat. Walikota itu tak ada di dekatnya. Juga tidak di kursi dekat cermin. Walikota itu sudah tak ada di dalam rumah. Aku beranjak ke pintu, kucoba dan terbuka. Sekarang dengan jelas kulihat darah di mana-mana dalam rumah perempuanku itu! Di atas ranjang kudapati perempuanku sudah tak bernyawa lagi, matanya terbelalak lebar, dan di dekat kepalanya yang penuh darah tergeletak sebuah pistol kecil yang juga berlumuran darah. Aku meraung keras. Baru saja aku membalikkan badanku hendak mengejar walikota itu, kulihat di ambang pintu sudah berdiri kepala kampung, seorang polisi, dan walikota itu sendiri. Lalu kudengar suara ribut-ribut di luar rumah dan… “Tok! Tok! Tok!!! Dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara kepada terdakwa yang didakwa membunuh seorang wanita dengan cara menembaknya dua kali di bagian kepala dengan…” Di antara para pengunjung sidang pengadilan kulihat walikota itu tersenyum mengejek padaku. 0 Saut Situmorang, penyair dan pencinta cersil Kho Ping Hoo, tinggal di Bantul
CERITA PENDEK
KLASIK
JOHN SYDENHAM FURNIVALL: Pembanding Kolonialisme Inggris dengan Belanda
Kali Besar - Jakarta Kota, Foto: Hervé Dangla
M. Fauzi
D
alam sebuah buku yang berisi kumpulan esai dari mereka yang pernah aktif dalam politik kolonial di Hindia Belanda, Balans van Beleid: Terugblik op de Laatste Halve eeuw van Nederlandsch Indie (dialihbahasakan Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan), editornya, yaitu H. Baudet menulis tentang salah seorang sosok administratur kolonial asal Inggris, John Sydenham Furnivall. Dalam kesan-kesannya, Baudet mengungkapkan kekecewaannya dengan kalimat sebagai berikut, “Sayangnya, ada seorang, yang kita hormati, tidak hadir. Ketidakhadirannya tidak saja merupakan suatu kekurangan dalam mendiskusikan buku ini [Balans van Beleid], tetapi juga sebagai suatu kerugian yang tidak dapat diganti untuk bidang sejarah di masa penjajahan.” Seberapa pentingkah Furnivall, dan di mana sesungguhnya KLASIK
posisinya dalam studi-studi kolonialisme di Asia Tenggara? Semula, Furnival merencanakan menulis sebuah esai tentang pengalamannya sebagai administratur kolonial dan pengetahuannya tentang kolonialisme. Namun, sebelum rencana itu terwujud, ia meninggal pada 7 Juli 1960 dalam usia 82 tahun. Tentunya Baudet sangat kecewa atas meninggalnya Furnivall, sekaligus “suatu kerugian yang tidak dapat diganti” bagi publik ilmiah telaah tentang Asia Tenggara, khususnya Burma dan Hindia Belanda. Kekecewaannya itu juga bisa dipahami sebagai suatu bentuk pengakuan Baudet atau para “Indolog” terhadap otoritas keilmuwan Furnivall. Dalam kajian tentang kolonialisme Belanda, Furnivall memang termasuk salah seorang figur yang menonjol di antara puluhan Indolog alumni Universiteit Leiden dan Utrecht, dua perguruan tinggi terke-
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
61
muka di Belanda yang banyak menelurkan Indolog. Ia termasuk segelintir ilmuwan Inggris yang menaruh minat pada studi perbandingan negeri-negeri di Asia Tenggara, terutama Burma dan Hindia Belanda. Dua negeri yang banyak dikaji oleh Furnivall. Studi Furnivall tentang Hindia Belanda yang terkenal adalah Netherlands India: A Study of Plural Economy, terbit pada 1939, dan menjadi salah satu bacaan wajib di berbagai universitas dan kajian-kajian mengenai sistem kolonial. Furnivall menulis dan menyelesaikan Netherlands India saat menjadi pengajar bidang hukum, sejarah, dan bahasa Burma di Cambridge University, Inggris. Ia memang fasih berbicara tentang Burma. Minat dan kajiannya tentang Burma di bawah kolonial Inggris sama menarik dengan kajiannya tentang Hindia Belanda di bawah kolonial Belanda. Mungkin karena alasan itulah, ia secara intensif mendalami dan membandingkan antara kolonialisme Inggris di Burma dan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Salah satu karyanya yang menyoroti tentang perbandingan kolonialisme di kedua negeri tersebut adalah Colonial Policy and Practice, terbit pada 1948. Di Burma, pemerintah kolonial Inggris telah menghapuskan sistem monarki dan menyingkirkan para penguasa tradisional. Sementara pemerintah kolonial Belanda justru berbuat sebaliknya. Pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan sistem monarki dan penguasa tradisional, dan menjadikan yang terakhir sebagai kepanjangan tangannya dalam urusan-urusan publik dan bahkan ekonomi, khususnya meningkatkan pendapatan dari tanaman ekspor penghasil devisa terbesar seperti kopi, gula, teh, dan nila. Memang, latar belakang bercokolnya kolonialisme di kedua negeri itu berbeda. Jika Inggris menguasai Burma melalui jalan penaklukan secara fisik dan militer, Belanda justru menancapkan kekuasaannya melalui serangkaian perundingan dan kontrak-kontrak perjanjian dengan keraton dan penguasa-penguasa lokal. Seorang nasionalis dan sastrawan, Sanoesi Pane, menyebut cara dan taktik Belanda dalam menaklukan kepulauan Nusantara ini dengan jalan berunding sebagai “soeatoe tipoe moeslihat”. Dalam uraiannya tentang sistem pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda, Furnivall juga membahas tentang bagaimana Belanda mengatur jajahannya dengan aparat-aparat kolonialnya. Di Hindia Belanda, di samping gubernur jenderal, residen, asisten residen, kontrolir, ada pula 62
jajaran birokrasi pribumi yang terdiri dari para bupati, patih, wedana, asisten wedana. Maka, dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda yang terjadi adalah berlangsungnya suatu sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dari aparat kolonial kepada rakyatnya melalui birokrat pribumi, atau lebih dikenal sebagai pangreh praja (penguasa kerajaan). Sebagai suatu istilah, pangreh praja, menurut Heather Sutherland, yang meneliti secara mendalam topik ini, mungkin lebih tepat ditujukan bagi pribumi. Namun, tidak demikian halnya di mata pemerintah kolonial. Bagi pemerintah kolonial, aparat pribumi yang disebut sebagai “penguasa-penguasa kerajaan” itu tak lebih dari semacam inlandsch bestuur (pemerintah pribumi) yang kedudukannya lebih rendah dari pemerintah lokal. Tumpang tindih atau“pemborosan birokrasi” dalam sistem pemerintahan kolonial ini terus berlanjut bahkan setelah Indonesia merdeka, dengan aktor dan peran yang berbeda. Meskipun begitu, dari segi keuangan, pemerintahan tak langsung yang memanfaatkan aparat pribumi dalam sistem kolonial ini memang jauh lebih murah ketimbang harus mengimpor langsung atau menggaji aparat dari Belanda. Selain itu, pemerintah kolonial juga melihat penduduk tampaknya lebih patuh kepada penguasa-penguasa lokal dari pada kepada pemerintah kolonial. Indirect rule, di sisi lain, memang menjadi “pesona” tersendiri dalam telaah tentang kolonialisme di Hindia Belanda. Tak terkecuali juga bagi Furnivall dalam Netherlands India. Kendati kajian Furnivall tentang Hindia Belanda banyak menyoroti perkembangan yang terjadi sejak awal abad ke-19 hingga menjelang tahun-tahun terakhir runtuhnya Hindia Belanda, ia juga membahas beberapa segi kebijakan politik dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Hongitochten, misalnya, menyebut kebijakan memotong pohon-pohon rempah di Maluku yang tidak dapat diatur oleh VOC ini sebagai suatu bentuk penyamunan untuk menghancurkan seluruh produksi yang melebihi kebutuhan Belanda. Cara VOC untuk menguasai melalui jalan kekerasan pada akhirnya dilakukan jika kontrak-kontrak gagal disepakati. Ini pula yang terjadi di Kepulauan Banda dalam soal pala. Sejak dimulainya hongitochten, perusakan, perlawanan, hukuman adalah sejarah yang kerap silih berganti dan melekat di wilayah Kepulauan Maluku. Masa Tanam Paksa (cultuur stelsel) yang berlangsung sepanjang 1830-1870 juga tak luput dari perhatian Furnivall. Sejak beramedia kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
khirnya sistem itu pada 1870, penyerahan paksa hanya diwajibkan untuk gula dan kopi. Serah paksa kopi sendiri baru berakhir pada 1919, dan tanaman jenis ini menjadi penyumbang devisa terbesar bagi kas kolonial Belanda. Tentang UU Agraria 1870, Furnivall menyatakan pendapatnya sebagai berikut,“Dengan sesuatu yang didasarkan atas prinsip bahwa keuntungan hendaknya jatuh ke tangan perorangan-perorangan swasta dari pada ke sektor umum.” Jelas di sini adanya upaya segelintir orang, pemilik modal atau para tuan kebun, untuk menggeser kepentingan umum menjadi kepentingan perorangan swasta belaka. UU ini juga menghapuskan monopoli negara atas penanaman gula dan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta melakukan sewa jangka panjang atas “tanah-tanah telantar”, dan sewa jangka pendek atas tanah-tanah yang sedang ditanami. Furnivall menyadari betul bahwa semua hubungan kolonial, tak terkecuali di Burma dan Hindia Belanda, sesungguhnya ditentukan oleh ekonomi. Di Hindia Belanda termasuk di dalamnya “tiga serangkai”, yaitu era cultuur stelsel, liberal, dan Politik Etis. Kontroversi yang terus-menerus tentang kolonialisme Belanda sejak cultuur stelsel hingga era liberal terus berlanjut ke masa Politik Etis. Kebijakan baru ini dicanangkan sejak awal abad ke-20 sekaligus menandai berakhirnya ekspansi horisontal negara yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mata Furnivall juga memiliki tujuan ekonomis. Dan, awal serta akhir kebijakan itu juga ditentukan oleh ekonomi. Sejak Politik Etis dilaksanakan, terjadi perluasan aparat kolonial yang sangat besar dan mendalam hingga masyarakat pribumi, dan fungsinya pun berkembang. Pendidikan, irigasi, pertanian, kesehatan, eksploitasi mineral, pengawasan politik semuanya menjadi urusan kepegawaian yang kian meluas karena desakan dari dalam ketimbang dari luar negara. Tak lama setelah pemberlakuan Politik Etis, pada 1910 negara kolonial mulai bertindak melalui kekuatan bersenjatanya (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger, KNIL) dan berhasil menerapkan rust en orde (ketentraman dan ketertiban) di wilayah kekuasaannya. Suatu sistem kontrol yang tidak mendapatkan kendala serius hingga pembubarannya beberapa pekan menjelang invasi Jepang pada 1942. Kajian Furnivall tentang Hindia Belanda mungkin tak sebanyak kajiannya tentang Burma. Setidaknya Wealth in Burma (1937), Political Economy of Burma (1951), The GovKLASIK
ernment of Modern Burma (1958) adalah beberapa contoh di antaranya. Di Indonesia, studi tentang Burma, khususnya waktu di bawah kolonial Inggris, sedikit mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Padahal, membandingkan kedua corak sistem kolonialisme di kedua negeri di Asia Tenggara ini tentulah sangat menarik. Inggris memang pernah berkuasa di Indonesia, tetapi itu pun berlangsung singkat, yakni pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816). Setidaknya perbandingan itu membawa kepada suatu pemahaman tentang watak kolonialisme Inggris dan Belanda di masing-masing negeri jajahannya. Adakah perbedaan antara keduanya di masing-masing negeri? Ataukah setiap negeri diterapkan kebijakan yang sama? Dari telaah Furnivall, banyak hal yang sebenarnya berbeda dan perbedaan itu dipengaruhi oleh kondisi di masing-masing negeri. Dalam kasus Hindia Belanda, perbedaan dan hasilhasil apa saja yang telah dilakukan baik oleh kolonial Inggris – saat Gubernur Jenderal Raffles berkuasa – maupun kolonial Belanda tentunya menjadi suatu kajian yang menarik. Tentang Hindia Belanda, pendapatnya yang cukup menarik adalah mengenai masyarakat majemuk (plural society). Setiap kelompok dalam masyarakat ini cenderung menjalankan kehidupan sosial yang mandiri dan diatur oleh pemimpinnya masingmasing. Mereka hidup dalam unit politik yang sama. Dalam kerangka ini pula, hukum di Hindia Belanda sesungguhnya bagi macam-macam kelompok berlain-lainan. Begitu pula halnya dalam hal aturan kemasyarakatan.
Dalam masyarakat Tionghoa misalnya, mereka mengenal sistem opsir, atau para kepala masyarakat Tionghoa. Hingga abad ke-19 para opsir ini terdiri dari kapitan, letnan, mayor, dan kepala kampung (wijkmeester). Suatu kedudukan yang kemudian menjadi turun-temurun. Mereka bukan hanya penimbun modal, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat Tionghoa. Para opsir ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepangkatan dalam militer kolonial. Mereka adalah pedagang kaya atau cabang atas dalam masyarakat Tionghoa. Nah, para opsir ini lah yang menjadi penghubung antara masyarakat Tionghoa dan pemerintah kolonial. Pacht atau monopoli pajak yang dijual kepada orang Tionghoa dalam pelelangan terbuka menjadi inti hubungan ekonomi-politik antara opsir dan pemerintah kolonial. Perbedaan lain dalam masyarakat majemuk juga terlihat di bidang hukum. Sistem peradilan di Hindia Belanda misalnya menganut azas yang berbeda-beda untuk berbagai masyarakat: pribumi, Tionghoa/Timur Asing, dan Eropa. Dan, kesenjangan ini pula yang dimanfaatkan oleh Sukarno ketika membacakan pembelaannya yang terkenal “Indonesia Menggugat” di Landraad Bandung. Bagi Sukarno, hukum kolonial tak mungkin membenarkan tindakannya beserta kawan-kawannya dalam PNI dan karena itu kesempatan membela diri dipergunakannya untuk “membongkar” sistem kolonial yang destruktif dan eksploitatif. Tindakan serupa dalam menguliti sistem kolonial juga dilakukan oleh Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, Semaoen, Darsono, Mas Marco, dan Hadji Misbach.
klasik
Sistem pemerintahan bertingkat dan tak langsung yang diterapkan Belanda di koloni Hindia Belanda melalui penguasa-penguasa tradisional pribumi dan para opsir dalam masyarakat Tionghoa dari segi keuangan mungkin efisien dan hemat. Tetapi, hal ini bisa mengundang kerawanan bila rakyat ternyata lebih mematuhi bupati atau kapitannya ketimbang pemerintah kolonial. “Persekutuan” antara pemerintah kolonial dengan aparat pribumi atau dengan para opsir Tionghoa tentunya bisa saja berubah menjadi permusuhan antara keduanya. Ujian mengenai sejauh mana kelanggengan hubungan itu terlihat, misalnya, saat pergerakan memasuki zaman baru di permulaan abad ke-20. Beberapa pangreh praja terlibat aktif dalam organisasi Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan organisasi kerakyatan lainnya, sembari tak melepaskan jabatannya dalam pemerintah Hindia Belanda. Maka, memetik pelajaran dari telaah Furnivall tentang Burma dan Hindia Belanda, kolonialisme sebagai sebuah sistem eksploitasi politik, ekonomi, dan sosial dampaknya masih bisa disaksikan sampai sekarang. Pengkotak-kotakan masyarakat, pembagian masyarakat dalam kelas, kasta, dan wilayah, dan perbedaan di bidang hukum adalah “warisan” kolonialisme yang tersisa hingga kini. Kontribusi Furnivall adalah mengingatkan kita untuk tidak mengulangi pembelahan rakyat dalam sistem kolonial yang destruktif dan eksploitatif. 0 M. Fauzi adalah Kepala Pustaka Kerja Budaya
MUAK DENGAN ARUS UTAmA?
http://arus.kerjabudaya.org
KLASIK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
63
® RESENSI BUKU
& ©
Penguasaan Sumber Daya Alam™ Krisis Sistem Kapitalisme Dunia
Antonius T. Stevanus
Milyaran warga dunia dewasa ini didorong untuk mempercayai dan memahami bahwa GLOBALISASI adalah sinyal masa depan untuk kesejahteraan umat manusia. Sementara para penentang globalisasi membeberkan bahwa globalisasi adalah sebuah sistem kapitalisme lama yang diperbaharui. Tiga buku yang akan saya bahas di bawah ini memandang globalisasi akan menghancurkan peradaban manusia dan memaksa kelas pekerja, perempuan masuk ke dalam proses proletarianisasi. Buku pertama, Imperialisme Abad 21, karya James Petras dan Henry Veltmeyer, merupakan terjemahan dari Globalization Unmasked: Imperialism in the 21 st Century yang ingin menanggalkan berbagai selubung indah penutup ide globalisasi selama ini, sehingga kita bisa menentukan sikap apakah globalisasi itu sebuah sistem bagi kesejahteraan atau ketidakadilan. Namun sungguh sayang bahasa buku terjemahan ini kurang populer, sehingga agak sulit untuk memahami isinya. Di lain sisi, buku ini mendorong pembacanya berpikir lebih keras untuk memahami analisa kelas yang tak lazim dipakai di Indonesia. Dalam buku Imperialisme Abad 21 , Petras dan Veltmeyer sejak awal
64
menantang klaim-klaim keniscayaan kaum globalis bahwa sistem kapitalisme merupakan satu-satunya pilihan tata dunia. Menyandingkan globalisasi dengan konsep imbangannya, yaitu imperialisme, penulis menggunakan analisa kelas untuk mengurai kembali dasar-dasar pemikiran dan praktek kapitalisme. Menarik bahwa teori Marxisme yang sudah banyak ditinggalkan orang justru memberikan kekuatan penjelas yang akurat bagi situasi yang tengah berlangsung seperti diperlihatkan buku ini. Petras dan Veltmeyer membawa kembali dimensi pemikiran ilmiah dengan unsur-unsur yang bertentangan, bahkan dengan intelektual sepikiran, yang mampu memberikan pemahaman dasar gerak globalisasi pada kalangan yang lebih luas. Tidak hanya itu, buku ini juga memberi aktivis penentang globalisasi perangkat teoretik yang akan memperkuat aksi perlawanan. Selama ini pembahasan mengenai globalisasi begitu kompleks sehingga menjadi wacana ekonomi dan sosial-politik yang membingungkan. Jika globalisasi dipahami sebagai penguatan dan perluasan ekonomi ‘pasar bebas’ dengan menghapuskan segala aturan pembatas
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
©
gerak modal internasional, imperialisme meraih bidang yang jauh lebih strategis, yaitu proyek-proyek politik yang mengkondisikan perdagangan global berkelanjutan. Bukannya tanpa alasan globalisasi hadir dengan mitos-mitos kemajuan dan kesejahteraan yang menyelubungi ideologi kepentingan kelas kapitalis internasional. Sistem ini secara dinamis terus melakukan penyempurnaan strategi untuk menaklukkan segala aspek kehidupan manusia di bawah kekuasaannya, dan lewat promosi ‘pasar bebas’, ia mengubah tatanan dunia untuk menciptakan sistem perekonomian tunggal. Untuk melancarkan perluasan modal internasional dalam jumlah yang semakin besar, selain menggunakan teknologi dan sistem informasi yang canggih, perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara industri maju, seperti Amerika Serikat, beberapa negara yang bergabung dengan Uni Eropa, dan Jepang, melibatkan lembaga keuangan dan perencanaan internasional seperti IMF, Bank Dunia. Negara-negara inilah yang menjadi pusat penggerak proyekproyek perubahan di seluruh dunia dan mewujudkan sistem pemerintahan global. Perubahan dilakukan berdasarkan
KLASIK
James Petras dan Henry Veltmeyer, Imperialisme Abad 21, Jakarta, 2001
Hira Jhamtani, Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan, Jakarta, 2001
Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan, Jakarta, 2002
keputusan sekelompok manusia yang sepenuhnya sadar untuk menundukkan manusia lain di bawah kekuasaannya. Bayangan tentang tatanan dunia baru menjadi sebuah keniscayaan, dan kita semua harus melakukan penyesuaian terhadapnya. Negara-negara di luar kelompok negara imperial yang mengalami perubahan politik secara drastis, seperti di Indonesia, menjadi sasaran proyek ‘pembaharuan’ ini. Setelah rejim diktator dan militeristik tergusur, pemerintahan sipil yang baru didorong untuk melaksanakan program-program etiket seperti “good governance” (tata kelola pemerintahan yang baik) dan mengadopsi “Structural Adjustment Programme” (program penyesuaian struktural) untuk membangun kinerja institusi dan melahirkan kebijakan negara yang sepenuhnya mendukung rejim “pasar bebas”. Pendukung pasar bebas melihat kepatuhan negara-negara miskin untuk menandatangani nota kesepakatan dan mengikuti kursus-kursus menjalankan pemerintahan yang baik sebagai upaya membangun sistem yang lebih “demokratis” bagi rakyat. Padahal, ini semua tak lain dari strategi untuk melancarkan
RESENSI BUKU
perputaran modal internasional. Pemerintah lokal tidak pernah mempunyai peran untuk menentukan kebijakan nasional maupun internasional yang lebih baik bagi rakyatnya karena mereka membutuhkan bantuan dana dan investasi dari negara-negara imperial. Program-program pembaharuan pada gilirannya menciptakan krisis berkepanjangan di segala bidang kehidupan masyarakat. Investasi asing yang membanjir memicu krisis pada perusahaan-perusahaan milik negara yang mengelola kebutuhan mendasar rakyat. Privatisasi menjadi jalan keluar walaupun itu berarti meniadakan sumber-sumber keuntungan pemerintah dan menyerahkan pengelolaan sumber daya hidup rakyat ke tangan swasta. Sedangkan pemasukan untuk pemerintah diusahakan dari kebijakan menaikkan pajak, memotong anggaran publik, dan mengurangi subsidi sosial. Satu hal menarik yang diungkap oleh buku ini adalah bagaimana rejim globalisasi menaklukkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang diciptakan sistem kapitalisme internasional. Dalam propagandanya, rejim ini menggunakan katakata populer, seperti demokrasi, pembangunan , solidaritas , civil society , atau pluralisme , untuk membingungkan dan mengacaukan gerakan-gerakan oposisi. Definisi kata-kata ini sudah ditentukan oleh kelas yang berkepentingan dengan perluasan modal internasional sebelum ditawarkan ke seluruh dunia lewat proyek-proyek yang disebut “penguatan masyarakat sipil”. Ornop atau LSM seringkali terjebak dalam mantra-mantra ini dan menjadi jurkam kekuatan imperial untuk menjinakkan perlawanan rakyat. Misalnya, istilah ‘masyarakat sipil’ sudah mengabaikan perbedaan kelas dalam masyarakat; kata ‘solidaritas’ berarti ‘pemberian bantuan’ dan penyelenggaraan ‘pelatihan’. Ada jarak antara para penyuluh dengan rakyat. Secara umum, buku ini menarik karena di setiap akhir pembahasan suatu tema, penulis memberikan kesimpulan penjelas dibalik uraian ilmiah tentang ekonomi dan sosial-politik yang rumit. Walaupun fokus pembahasan buku ini pada dampak dan praktek globalisasi di Amerika Latin, dari paparan penulis menjadi jelas bahwa globalisasi menimbulkan masalah yang serupa di segala penjuru dunia. Misalnya untuk memahami persoalan di Indonesia, kita bisa
mencermati kaitan antara praktekpraktek yang dijalankan perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis menegaskan buku ini bukan semacam panduan untuk mengatasi globalisasi walau pun buku ini diakhiri dengan solusi dan strategi sosialisme. Penulis justru ingin menunjukkan kepada kita bahwa pengamatan yang teliti terhadap realitas adalah pisau bedah yang penting untuk menguliti konsep globalisasi dan membantu kita menemukan kembali pilihan-pilihan alternatif tatanan hidup yang beragam dalam situasi globalisasi. Buku berikutnya, Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan, merupakan rangkuman pengalaman Hira Jhamtani sebagai aktifis LSM lingkungan yang menangani soal bioteknologi. Disusun sebagai catatan awal untuk berbagai kalangan yang peduli dengan lingkungan, buku ini memaparkan bagaimana globalisasi membuat posisi dunia ketiga semakin dikungkung oleh ketidaksetaraan di bidang ekonomi, teknologi dan kesejahteraan sosial. Ada beberapa tema dalam buku ini yang menarik. Pertama adalah bagaimana keanekaragaman hayati menjadi sumber “emas hijau” globalisasi. Sumber-sumber alam telah dipaksa pertumbuhan alamiahnya untuk memenuhi kebutuhan globalisasi dengan dukungan kemajuan teknologi di bidang biologi dan informasi. Dalam konteks Indonesia, bioteknologi dalam globalisasi adalah ancaman serius, baik bagi keberlanjutan alam, maupun bagi pemenuhan kebutuhan manusia akan kesehatan dan pangan. Tema kedua adalah paten atas segala bentuk kehidupan untuk dijadikan hak milik perseorangan atau perusahaan berbadan hukum. Ini adalah strategi untuk menguasai sumber-sumber alam dengan menarik keuntungan sebesarbesarnya dari penggunaan paten melalui royalti. Susunan genetika yang terdapat pada masing-masing mahluk hidup menjadi sumber daya penting untuk direkayasa. Praktek ini kemudian memicu krisis ilmu pengetahuan dan tersingkirkannya, bahkan punah, kearifan-kearifan lokal masyarakat. Keikutsertaan penulis dalam perundingan-perundingan konvensi antar negara dalam lembaga internasio-
™ media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
65
nal banyak memberikan pemahaman kepada kita bagaimana proses perumusan kesepakatan tentang globalisasi dilakukan melalui jalan parlementer. Jelas bahwa yang dirumuskan pada perundingan lingkungan internasional pada umumnya hanya menghasilkan suatu kesepakatan untuk menanggulangi dampak globalisasi pada lingkungan, tapi bukan pada perubahan drastis menuju perbaikan lingkungan. Kesepakatan ini justru membawa dampak yang lebih merusak lingkungan dalam bentuk bujuk rayu investasi asing, janji alih teknologi dan pembagian keuntungan. Jhamtani menyatakan bahwa sejak pemberlakuan WTO, pemerintah Indonesia menderita kerugian sekitar US$ 1,9 milyar. Sayangnya, ia tidak merinci cara penghitungannya. Yang berperan kunci dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan globalisasi lingkungan adalah WTO dan Bank Dunia, bersama dengan kebijakan ‘pasar bebas’ AS yang didukung perusahaan multinasional. Mereka, misalnya, menetapkan kebijakan TRIP’s (Trade-Related Intellectual Property Rights – Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Perdagangan) untuk mematenkan bentuk kehidupan secara legal. Belum lagi kebijakan perdagangan AS ‘Super 301’yang mengancam pemberlakuan sanksi perdagangan bagi negara-negara yang tidak sepaham. Seperti yang diungkapkan penulis, utusan negara-negara dunia ketiga biasanya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk bernegosiasi dan membahas persoalan ini. Ini sebenarnya bukan karena utusan pemerintah negara-negara maju lebih kuat dalam bernegosiasi seperti sering diutarakan banyak pengamat. Tapi, pemerintah memang tidak punya itikad baik memperjuangkan kepentingan rakyatnya di tingkat internasional sehingga mereka tidak berusaha mencari atau mendidik utusan yang lebih menguasai soal. Posisi LSM, dalam pandangan penulis, oportunis, baik di tingkat internasional, nasional, maupun di akar rumput. Setelah tegas-tegas mengutuk globalisasi, mereka menyarankan kepada pemerintah agar membuat kebijakan lingkungan yang tidak melanggar perjanjian internasional (WTO). Mereka menyarankan pemerintah untuk mendengar66
kan aspirasi dari masyarakat, tapi di lain waktu juga menyalahkan masyarakat atas kerusakan alam. Mereka juga mendesak pemerintah untuk bekerja sesuai dengan tata tertib “good governance”, kemudian menciptakan paradigma lingkungan baru yang jauh kaitannya dengan praktek pelestarian lingkungan yang hidup di masyarakat. Beberapa solusi yang ditawarkan penulis anehnya membawa kita berharap akan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian internasional dan bersifat normatif. Contohnya, penulis mengusulkan penanganan bioteknologi dengan kasih, yang menjunjung etika dan moral; transparansi kebijakan pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat yang didasari atas kejujuran. Penulis bahkan berharap pada doa sebagai alternatif terakhir jika kebakaran hutan tak teratasi. Jadi, saran-saran yang ia ajukan juga tidak berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dari praktekpraktek masyarakat pelestari lingkungan, dan tidak akan bisa diserap pembuat kebijakan. Sebagai sebuah catatan awal, informasi dan data yang disampaikan dalam buku ini tidak begitu banyak, khususnya mengenai dampak globalisasi lingkungan di Indonesia. Dua artikel pertama dan selanjutnya membahas tema keanekaragaman hayati berulang-ulang dengan penggunaan kata yang berbeda-beda. Ada kesan pembahasan ditekankan pada kerangka teori, bukan realita kerusakan lingkungan itu sendiri. Bagaimana pun buku ini tetap melengkapi pemahaman kita mengenai globalisasi itu sendiri. Dengan membaca tentang proses perundingan tingkat internasional, pembaca bisa melihat bahwa yang mendominasi pembuatan kebijakan adalah kelas kapitalis. Mereka juga bisa menyerap praktek kultural yang berlaku di belahan dunia tertentu untuk menciptakan perubahan nilai sesuai dengan kepentingan kelas mereka. Hal ini juga menggambarkan bahwa perjuangan parlementer tidak selamanya berjalan dengan hasil memuaskan. Buku Globalisasi dan Monopoli Ilmu Pengetahuan-Telaah Tentang TRIP’s dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia merupakan buku hasil studi yang dilakukan Hira Jhamtani bersama Lutfiyah Hanim. Mungkin buku ini hendak meneruskan buku sebelumnya media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
karena masih berkaitan dengan isu lingkungan, tapi dengan pembahasan lebih spesifik pada TRIP’s atau Hak atas Kekayaan Intelektual. Sejak awal dirumuskan TRIP’s mengundang sejumlah pertentangan, baik antar negara perumus, antara negara perumus dengan negara anggota WTO lain, maupun dengan hasil perundingan lingkungan tingkat internasional lainnya. TRIP’s telah menjadi pusat kebijakan yang melemahkan hasil perundingan lain sehingga perumusan TRIPs tidak juga menguntungkan penggunanya. Namun, negara anggota WTO tetap saja mengadaptasi aturan main ini dalam kebijakan nasional masing-masing. Kerancuan ini berlanjut ketika di tingkat nasional ternyata tidak ada pemahaman bersama tentang hak paten, bahkan di kalangan pemerintah sendiri. Maka tak heran jika soal paten memicu banyak sekali korban. Kebijakan yang ada tidak mampu menjembatani perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Misalnya, hak paten ini menghancurkan proses dan hasil praktek kultural yang hidup dalam masyarakat tradisional. Bagi para pengusaha rekaman kebijakan soal paten berguna untuk melindungi hak cipta. Tapi bagi pengrajin atau petani, aturan ini janggal, karena ketrampilan yang mereka miliki adalah warisan turun temurun komunitas yang tidak perlu diberi paten oleh negara. Lepas dari kelemahannya di sana-sini, ketiga buku ini memberikan sumbangan besar untuk pemahaman neoliberalisme. Dari ketiganya tampak bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat berkait kelindan dengan globalisasi. Setiap orang tidak bisa mengabaikannya begitu saja karena ia hidup didalam sistem ini. 0
Antonius T. Stevanus adalah anggota Tim Relawan Untuk Kemanusiaan
® RESENSI BUKU
TOKOH
Dunia Dongeng dan Kata-Kata
SUBCOMANDANTE MARCOS Adalah kata-kata yang menciptakan kita. mereka yang membentuk kita, Dan membentangkan Garis-garisnya Untuk mengontrol kita. (Subcomandante Marcos)
Wilson
B
TOKOH
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
sumber foto: www.ezln.org
iasanya membaca tulisan para tokoh revolusioner, kepala kita jadi mudah berdenyut-denyut, dipenuhi kata-kata teknis tradisional kaum revolusioner yang menggebu-gebu disanasini, dan tentu saja provokatif. Sampai suatu hari, dunia dikejutkan oleh aksi para gerilyawan Zapatista di Chiapas, Mexico. Dari model gerakan, mungkin itu adalah plot klasik kaum revolusioner di berbagai tempat: sebuah insureksi yang dipersiapkan matang terhadap kekuasaan negara. Tidak ada yang baru dari plot 1 Januari 1994. Hal baru yang dibawa para gerilyawan bertopeng “yang tanpa suara/tanpa wajah/tanpa nama” tersebut adalah ‘gaya kepemimpinan’ yang unik dari Subcomandante Marcos. Membaca dokumen dan seruan dari Subcomandante Marcos, kita seperti sedang membaca sebuah karya sastra. Kutipan puisi, dongeng, kata-kata indah bertaburan bagaikan kristal—kata-kata seperti berubah wujud menjadi sinar yang terang benderang. Salah satu contoh yang paling luar biasa adalah pidato pembukaannya dalam Konferensi Internasional Anti Neoliberalisme di Juli 1996. Berbeda dengan para peserta yang mengungkapkan pendapatnya dalam bahasa teoritis, data-data ekonomi yang pelik tentang penindasan pasar bebas, Subcomandante Marcos membawa suasana lebih cair dan teduh. Ia membuka acara dengan kata sambutan berbentuk puisi panjang. Sesuatu yang sukar kita bayangkan akan dilakukan Fidel Castro atau Lenin, atau para pimpinan gerakan revolusioner di berbagai belahan dunia. Dengan indah ia mengenalkan diri:
67
Inilah siapa kami Tentara pembebasan nasional Zapatista Suara-suara yang mempersenjatai diri agar bisa didengar Wajah-wajah yang disembunyikan agar tidak terlihat Nama-nama yang tidak mau diberi nama Ekspresi politik dalam bentuk puisi, drama, dongeng, dan foklore memang memenuhi berbagai pernyataan politik Subcomandante Marcos. Semua ekspresi estetik tersebut memberikan suatu roh baru dalam pernyataan-pernyataan politik kaum revolusioner— keindahan. Sesuatu yang ‘agak baru’ dalam tradisi politik kiri, yang selama ini dipenuhi dengan bahasa teoritis, sloganistik, provokatif dan polemis. Beberapa pemimpin gerakan kiri seperti Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Aidit, atau Xanana (yang saya kenal) juga menulis puisi. Namun puisi-puisi mereka adalah ‘dunia lain’, tidak menjadi bagian langsung dari ‘perang propaganda politik’. Sementara Subcomadante Marcos tidak membagi ‘dunia estetik’ dan ‘dunia politik’ sebagai dua wilayah yang berbeda—keduanya hadir dalam saat yang bersamaan, saling memperkuat dan saling memberi isi. Permainan kata-kata memang mendapatkan perhatian serius dari Subcomandante Marcos. Kata-katanya beri roh perjuangan dan harapan, menjadi suatu alat yang hidup, bahkan senjata yang paling utama: “Adalah kata-kata yang memberi bentuk pada sesuatu yang masuk dan keluar dari diri kita. Adalah kata-kata yang menjadi jembatan untuk menyeberang ke tempat lain ketika kita diam, kita akan tetap sendirian. Berbicara, kita mengobati rasa sakit. Berbicara kita membangun persahabatan dengan yang lain. Para penguasa menggunakan kata-kata untuk menata imperium diam. Kita menggunakan kata-kata untuk memperbaharui diri kita… Inilah senjata kita saudara-saudaraku.” (12 Oktober 1995)
Di Chiapas, Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) menciptakan suatu ‘tradisi’ unik, di mana proses kreatif dan kualitas estetik muncul dari kawah perjuangan itu sendiri. Dari perjuangan tersebut lahir puisi, dongeng, dan kata-kata indah yang ditujukan kepada pendukung, sahabat, anak-anak, perempuan, kaum buruh, kaum tani, masyarakat adat, dan juga musuh-musuh rakyat. Perjuangan Subcomandante Marcos dkk. telah meningkatkan kualitas keindahan dari alat kontemplasi, apresiasi, perenungan, menjadi suatu ‘roh’ yang menjadi satu kesatuan dengan kehidupan revolusioner. Jadi kita tidak mungkin bisa membayangkan kerja estetis Subcomadante tanpa perjuangan revolusioner, dan begitu pula sebaliknya. Tentu saja, pemahaman “kata-kata adalah senjata” harus ditempatkan dalam konteks perjuangan, bukan dalam kamar kaum seniman soliter, jurkam, atau tukang obat. Bisa jadi, kalau kata-kata ini dicabut dari konteksnya, dunia ini akan dipenuhi para pengikut NATO (no action talking only – tak ada aksi bicara melulu, red.). Kata-kata menjadi senjata bila ia menjadi bagian dari perjuangan pembebasan; kata-kata tidak menjadi apa-apa bila ia hanya sekedar kata-kata. Dan memahami kata-kata sebagai senjata harus dimulai dari perjuangan Tentara Pembebasan Naional Zapatista. Perjuangan rakyat Chiapas yang monumental dan menjadi titik balik penting adalah di malam tahun baru 1994, tepat di hari pertama implementasi NAFTA (North American Free Trade Agreement —
68
Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, red.) Bagaikan kisah dongeng, ribuan gerilyawan tentara EZLN, di bawah pimpinan seorang laki-laki dengan topeng ski dan pipa cangklong terselip di bibir, menguasai kota San Cristobal de las Casas dan kota-kota kecil sekitarnya. Pesan politik dari aksi tersebut cukup jelas, yaitu mengingatkan pemerintah Meksiko dan dunia tentang nasib masyarakat adat yang disengsarakan, ditindas, terusir, dan dilupakan. Namun yang lebih penting lagi, hari itu adalah sebuah pembaptisan, sebuah permulaan ‘perang global’, menentang neo-liberalisme. Dan gerakan tersebut dipimpin oleh seorang tokoh misterius dengan mata hijau yang bersinar dari balik topeng skinya. Ketika para jurnalis bertanya “Siapakah Anda ?”, laki-laki bertopeng itu menjawab, “Saya adalah Subcomandante Marcos”. Penampilannya yang misterius menimbulkan berbagai spekulasi tentang siapa sebenarnya pria karismatik ini? Sesuatu yang serba misterius memang mengundang keingintahuan orang, apalagi para jurnalis. Tidak heran, nama Subcomandante Marcos menjadi suatu daya tarik, semacam teka-teki, di mana semua orang ikut bermain, dan dengan bersahaja mencoba menebak-nebak wajahnya, atau sekedar membagi kerinduan dan impian. Pokoknya, tidak ada suatu penafsiran tunggal tentang sosok misterius di balik topeng tersebut. Setiap orang bebas membangun impiannya sendiri, bahkan setiap orang juga bebas menjadi Subcomandante Marcos itu sendiri. EZLN berbeda dengan berbagai perjuangan revolusioner lainnya dengan wajah para pimpinannya yang sangat dikenal publik. Subcomandante Marcos berhasil membangun semacam tradisi baru, di mana identitas pimpinan adalah sesuatu yang anonim; sosok yang ada, tapi seperti tidak ada; hadir, tapi seperti tidak hadir; dikenal, tapi orang tidak mengenalnya; bersembunyi, tapi semua orang dapat melihatnya. Identitas anonim Marcos mungkin ingin menjelaskan suatu prinsip, bahwa rakyat yang utama, rakyat yang nyata, rakyat tidak anonim, rakyat yang punya sejarah, rakyat yang memiliki penderitaan, dan rakyat pula yang memiliki perjuangan, bukan para pimpinannya. Karena itu biarlah para pimpinan dikenal sebagai sesuatu yang anonim, sebab mereka bukanlah hal yang paling penting dalam perubahan atau sebuah perjuangan. Nama sebagai sesuatu identitas pribadi atau individu baginya adalah omong kosong, sebab”sekarang kita mempunyai nama kolektif”. Pada musim panas 1994, para pejuang Zapatista mengundang pers nasional dan internasional, para aktivis dan orang-orang yang sekedar ingin tahu, untuk menghadiri pertemuan di hutan Chiapas. Sekitar 600 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Kebanyakan yang datang ingin tahu “Mengapa ia bersembunyi di balik topeng? Mengapa ia takut menunjukkan wajahnya?” Merespon keingintahuan tersebut, Marcos melakukan gerakan seperti hendak membuka topengnya. Kesunyian terasa di tengah hutan. Semua orang seperti menahan nafas, penasaran siapa di balik topeng tersebut. Tiba-tiba kesunyian terpecah dengan teriakan “Jangan.. jangan.. jangan!”. Dan topeng tersebut tidak jadi dibuka. Topeng tersebut, bukan hanya penting untuk menghapuskan identitas dirinya sebagai individu, tapi sebagai identitas komunal dari penduduk asli Chiapas yang telah dilupakan, menderita, tapi tidak kehilangan harga diri; sebagai identitas komunal yang baru— komune perjuangan. Sejak itu, Marcos, melalui internet, mengeluarkan berbagai pernyataan, surat seruan, puisi, dongeng, solidaritas kepada dunia. Tulisan-tulisannya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menyebar dengan cepat melalui jaringan internet. Dari cara Subcomandante Marcos bermain dengan kata-kata, perjuangan revolusioner menjadi suatu medium estetik, proses kreatif, yang mungkin tidak lazim dari perspektif teori seni arus
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
TOKOH
sumber foto: www.ezln.org
utama. Yang paling menarik adalah kisah-kisah dongengnya. Dongeng-dongeng tersebut adalah bentuk foklore yang terus hidup dari satu generasi ke generasi. Karena itu dongeng dapat diartikan sebagai suatu penelusuran ke masa lalu guna memberikan ‘identitas historis’ kepada masyarakat “bahwa mereka sudah ada, sebelum para penindas ada. Dan akan terus ada, ketika para penindas menjadi tidak ada”. Marcos sudah menggunakan cara bertutur seperti mendongeng sejak awal terlibat dalam perjuangan bersenjata, sekitar 1984. Dongeng pertama ia kisahkan pada suatu senja di Agustus 1984 berjudul “Menanam Pohon Masa Depan”. Dengan dongeng itu menyampaikan “apa yang ingin dilakukan oleh Zapatista”: “Untuk menanam pohon masa depan, itulah yang kita akan lakukan… Pohon masa depan adalah ruang bagi semua orang, tempat setiap orang saling menghormati yang lain… Jika anda memaksa saya untuk mengatakannya dengan lebih persis, Saya akan katakan pada kalian itu adalah sebuah tempat dengan demokrasi, kebebasan dan keadilan; itulah yang dimaksud dengan pohon masa depan. “ Marcos selalu berpesan ‘rakyat yang tidak mempunyai masa lalu tidak akan mempunyai masa depan.” Kalimat ini keluar untuk
TOKOH
merespon politik penguasa yang menganggap ‘penduduk asli’ (baca: kaum tertindas) tidak pernah ada, baik di masa kini, di masa lalu dan masa depan. Karena itu mereka selalu diabaikan, tidak pernah diajak bicara, berembug, atau menentukan nasib mereka sendiri. Pokoknya dianggap tidak pernah ada. Dengan dongeng, Marcos seperti membuktikan bahwa “kami ada”; “kami mempunyai sejarah kami sendiri”; sejarah yang telah dikisahkan selama ratusan tahun oleh para nenek moyang. Dan keberadaan itu sekarang juga hadir dalam bentuk perjuangan. Perjuangan yang membuat penduduk asli mempunyai masa lalu, masa kini, dan tentu saja masa depan. Masa lalu adalah suatu yang hidup dalam masa kini, hadir dalam berbagai dongeng yang kreatif, penuh dengan ajaran moral, didaktis, nilai-nilai pengorbanan, harapan, dan perjuangan. Uniknya, masa lalu itu sebetulnya sudah dikenal baik oleh semua orang, karena sudah dikisahkan sejak kecil. Dan ketika si kecil sudah dewasa, dia mengisahkan kembali kepada anak-anaknya. Demikianlah ‘sebuah rantai sejarah’ direkam dalam kepala setiap orang. Inilah salah satu kekuatan bahasa tutur, sebuah dongeng, ketimbang teks sejarah akademis. “Sejarah dunia yang menciptakan dunia ini datang dari tempat yang sangat jauh sekali. Kalian tidak bisa menemukannya tertera di dalam buku atau terlukis di atas pohon. Juga tidak ada dalam aliran sungai
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
69
atau awan-awan yang beterbangan. Kalian tidak akan dapat membaca sejarah tentang dunia di dalam kalender. Sejarah tentang bagaimana kita lahir dan bagaimana kita diciptakan tidak tersembunyi di balik tulisan atau di dalamnya.” (21 Oktober 1999)
Dalam Catatan editor buku kumpulan tulisan Marcos Our Word is Our Weapon, Juana Ponce de Leon mengatakan bahwa “Buku tersebut adalah sebuah kesaksian tentang kekuatan bahasa.” Dengan tulisan-tulisannya, Subcomandante Marcos telah menjadikan Chiapas sebagai jendela bagi semua orang. Bahkan menurut Juana Ponce, “Kata-kata berbicara lebih banyak daripada revolusi”. Apa yang dilakukan Marcos persis seperti yang dilakukan para penulis besar Amerika Latin, seperti Pablo Neruda, Miguel Angel Asturias, atau Gabriel Garcia Marquez. Marcos mungkin agak mirip seperti sastrawan, “Ia memadukan keyakinan politik dan keindahan sastra untuk menciptakan keindahan bagi pandangan-pandangannya.” Salah satu hal yang menarik perhatian saya dari dongeng Marcos adalah penggunaan ‘kata kecil” dengan makna yang ‘besar’. Terdapat lima dongeng dengan protagonis utama adalah ‘si Kecil”. Intisarinya mungkin bahwa yang kecil belum tentu kalah; bahwa yang kecil belum tentu tidak berarti; bahwa yang kecil justru menjadi awal dari suatu yang besar; bahwa kecil itu juga sebuah kekuatan. Pemaknaan baru atas hal-hal yang dianggap kecil, merupakan suatu dekonstruksi terhadap kesalahpahaman dominan, atau kealpaan banyak orang, yang selalu mengidentikkan, menafsirkan sesuatu yang kecil dengan kelemahan, ketakberdayaan, kekalahan, marjinal, dan sesuatu yang tidak berarti. Sebuah dongeng tentang “Seonggok Awan Kecil” menjadi contoh bagaimana Marcos memberi makna yang dalam pada sesuatu yang kecil. Mahluk yang tadinya rendah diri, merasa tidak berguna, dan dilecehkan oleh awan-awan yang lebih besar, menemukan jati dirinya, kebanggaan diri, ketika ia menjadi pelopor menyirami sebuah padang pasir dengan hujan rintik-rintik. Ketika dia menjadi berguna bagi yang lain, maka si Awan Kecil sesungguhnya sudah melakukan sesuatu yang besar.
Salemba, 24 April 2003 Wilson, peneliti di Praxis Institute, Jakarta
sumber foto: www.ezln.org
Pada suatu masa, terdapat sebongkah awan yang sangat kurus, sendirian, dan selalu menjauh dari awan yang besar. Dia sangat kecil, hanya seonggok awan. Ketika awan-awan yang besar mengubah dirinya menjadi hujan yang melumuri gunung-gunung yang hijau, si Awan Kecil hanya dapat melayang-layang di atasnya. Tapi mereka mengejeknya karena dia begitu kecil. “Kau tidak memberikan apapun,” begitulah yang selalu diucapkan awan besar kepadanya.”Kamu terlalu kecil.” Awan-awan yang lebih besar selalu membuat gurauan lucu tentang dirinya. Lalu, karena begitu sedihnya, si Awan Kecil mencoba pergi ke tempat lain untuk mengubah dirinya menjadi hujan, tapi ke mana pun ia pergi, para awan besar selalu mendorongya keluar. Sehingga si Awan Kecil tidak pernah berubah. Hingga suatu hari, dia datang ke sebuah tempat yang sangat kering, begitu keringnya sehingga tidak ada satu
tokoh
pun yang dapat tumbuh. Dan si Awan Kecil berkata kepada cerminnya. (Aku lupa mengatakan kepada kalian bahwa si Awan Kecil ini membawa sebuah cermin, jadi dia dapat berkata kepada dirinya sendiri ketika sedang sendirian): “Ini tempat yang pas untuk mengubah diriku menjadi hujan sebab tak ada seorang pun yang pernah datang kemari.” Si Awan Kecil melakukan berbagai upaya agar dirinya menjadi hujan, dan akhirnya rintik-rintik kecil berjatuhan. Si Awan Kecil pun lenyap dan mengubah dirinya menjadi hujan rintik-rintik. Sedikit demi sedikit, si Awan Kecil yang sekarang menjadi hujan rintik-rintik mulai berjatuhan. Sepenuhnya dalam kesendirian, dia merasakan dan merasakannya, tapi tidak ada satu pun yang menantinya di bawah sana. Akhirnya, rintik hujan memecah seluruh dirinya. Saat itu, padang pasir masih sangat sunyi, hujan rintik-rintik membuat sedikit kegaduhan ketika dia jatuh tepat di atas bebatuan. Kegaduhan Itu telah membangunkan Bumi yang berujar: “Suara ribut apa ini?” “Wah turun hujan? Ini berarti akan turun hujan! Hayo, semuanya bangun! Hari akan hujan!” dia berteriak pada tetumbuhan yang bersembunyi di bawah batu, menghindar dari sinar mentari. Sang tetumbuhan segera bangun dan menggeliat. Dalam sekejap seluruh guruh menjadi kehijauan, dan Awan-awan besar melihat seluruh kehijauan tersebut dari jauh dan berujar: “Lihatlah! Di sana tampak banyak warna hijau. Mari mengubah diri kita menjadi hujan di sana. Kok kita tidak pernah tahu di sana ada yang begitu hijau.” Mereka pun mengubah dirinya menjadi hujan di sebuah tempat yang dulunya padang pasir. Mereka terus menurunkan hujan tanpa henti dan pepohonan mulai tumbuh membuat semuanya tampak hijau. “Sangat mujur sekali bahwa kita ada di sekitar sini,” kata si awan besar. “Tanpa kita, pastilah tidak mungkin akan sehijau ini”. Tampaknya tidak seorang pun mengingat bahwa seonggok Awan Kecil yang berubah menjadi rintik-rintik hujan telah membangunkan semuanya. Boleh saja tak seorang pun pernah mengingat, tapi bebatuan tetap menjaga rahasia hujan rintik-rintik itu. Waktu pun terus berlalu, awan besar pertama sudah menghilang dan pohon-pohon pertama sudah beranjak mati. Tinggallah bebatuan yang tidak pernah mati, selalu menceritakan kisah tentang seonggok Awan Kecil yang berubah menjadi hujan rintik-rintik pada tumbuh-tumbuhan yang baru muncul dan pada awan-awan yang baru tiba. (“ Dongeng Tentang Seonggok Awan Kecil”7 November 1997) 0
70
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
TOKOH
Lébur! Seni Musik dan Pertunjukan Dalam Masyarakat Madura Penulis: Helene Bouvier Kata Pengantar: Georges Condominas Penerjemah: Rahayu S. Hidayat dan Jean Couteau Penyunting terjemahan: Daniel Perret dan Rahayu S. Hidayat Penerbit: Forum Jakarta Paris, Ecole Francais d’Extreme-Orient, Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan dan Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2002
Buku ini menyoroti suatu aspek masyarakat Madura yang kurang dikenal, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu kegiatan keseniannya. Metode penelitian etnografis yang dipergunakan penulis memungkinkan ia mengamati kesenian dari segi estetika maupun segi sosial. Ia juga menyoroti proses penciptaan yang nyata sampai ke sumber materialnya, sehingga ia bisa mengungkapkan kaitan struktural bentuk kesenian di bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Dari pengamatannya, karena setiap kegiatan kesenian melibatkan satu segmen masyarakat pada berbagai macam tingkatan, konsep kesenian tradisional dan identitas budaya meliputi keadaan yang sangat bervariasi di Madura. Muncullah pertanyaan, “Apa yang akan terjadi dengan stereotip tentang “Kebudayaan Madura”? Buku ini meraih penghargaan Jeanne Cuisinier (buku Prancis terbaik tentang Indonesia) pada 1992 dan Penghargaan Georges Jamati (buku Prancis terbaik tentang estetika seni pentas) pada 1994. 0
Transcending Borders: Arabs, Politics, Trade and Islam in Southeast Asia Editor: Huub De Jonge and Nico Kaptein Penerbit: KITLV Press, Leiden 2002
Imigran Arab ke Asia Tenggara dan anak cucu mereka tidak banyak menerima perhatian peneliti jika dibandingkan dengan imigran-imigran dari belahan dunia lain, seperti Cina, India, dan Eropa. Secara jumlah, orang-orang Arab sering dianggap tidak penting di sisi minoritas asing lainnya, tapi mereka mempunyai pengaruh besar di bidang ekonomi, politik, sosial, dan perkembangan agama di wilayah berpulau-pulau ini selama berabad-abad. Buku ini memuat 10 artikel dari berbagai perspektif disiplin: sejarah, sosiologi, antropologi, dan Islamologi. Esaiesai ini membahas hubungan di dalam berbagai komunitas Arab, dan antara kalangan masyarakat Arab dengan masyarakat yang lebih luas; dalam bidang politik, perdagangan dan Islam. Huub de Jonge adalah dosen senior dalam ekonomi antropologi di University of Nijmegen, Belanda, sedangkan Nico J.G. Kaptein adalah koordinator dan dosen dalam kerjasama Indonesia-Belanda untuk Studi Islam di Leiden University. 0
The Thugs, The Curtain Thief, And The Sugar Lord: Power, Politics, and Culture in Colonial Java Penulis: Onghokham Penerbit: Metafor Publishing, Jakarta 2003
Kehidupan di Jawa pada zaman Hindia Belanda tidak pernah tampak sesederhana lukisan kuno. Dalam kumpulan tulisan ini, Onghokham, sejarawan terkemuka Indonesia, membeberkan kompleksitas kehidupan Jawa pada masa kolonial. Terperinci dalam penjelasan, penuh simpati, dan melemparkan kemeriahan anekdot, kumpulan esai ini memperlihatkan kelincahan interaksi antara penguasa kolonial dengan pribumi yang cerdik, dan bagaimana interaksi ini secara bertahap menciptakan sistem politik dan kebudayaan baru. Dalam satu esainya, Ong menggambarkan bagaimana usaha menyingkap sebuah pencurian sudah mendesak pemerintah Hindia Belanda ke dalam sebuah kesulitan. Di bagian lain, Ong menggambarkan bagaimana canggihnya lapisan kriminal tumbuh di luar sistem kepemimpinan tradisional Jawa. Membaca kumpulan karangan ini membantu kita melihat bagaimana Indonesia masa kini sebagai sebuah produk sejarah yang panjang. 0
http://tkkorba.kerjabudaya.org KAMPANYE INI DIPERSEMBAHKAN OLEH X-Y BEKERJA SAMA DENGAN MKB
Rp 8000,http://mkb.kerjabudaya.org
ISSN: 0853-8069
MENCARI BAHASA PEMBEBASAN CERPEN SAUT SITUMORANG: BAH! KLASIK: JS FURNIVALL PAT GULIPAT: GONJANG-GANJING SISDIKNAS SISIPAN: TEMU KORBAN
DATA BICARA PENGUNGSI PARIAH PROLETARIAT DATA B I C A R A
“Dan sejarah ini, perampasan hidup mereka, tertera dalam kitab perjalanan umat manusia dengan aksara darah dan api.” (Karl Marx, Das Kapital, 1867). “Lebih dari 10.000 orang tewas dan sekitar 1,4 juta orang terusir dari tempat asalnya dalam konflik komunal di Indonesia. Banyak internally displaced persons (IDPs) yang bersesak-sesak dalam tempat penampungan sementara selama lebih dari dua tahun… membentuk kelas pariah, yang menderita karena kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan yang sangat buruk.” “Masalah ini harus secepatnya diselesaikan sebelum mengeras dan menurun pada generasi anak-anak pengungsi.”(Laporan World Food Programme, 2002). PBB dan pemerintah melakukan survey ulang antara Desember 2002 dan April 2003, untuk mendapat angka yang lebih pasti. Pemerintah mengatakan jumlah pengungsi sekarang hanya 500.000 orang. Tapi PBB mengatakan jumlahnya jauh melebihi itu. Setelah tawar-menawar akhirnya disepakati bahwa jumlah mereka sekitar 700.000. Tentu ini belum termasuk jumlah pengungsi di Aceh yang sejak berlakunya operasi militer, menurut keterangan penguasa militer sudah mencapai 42.000 jiwa.
Miskin dan lapar dalam kegelapan Tingkat kemiskinan tiga kali lebih tinggi dibandingkan penduduk pada umumnya. Sekitar 17% anak-anak pengungsi tidak pernah menikmati bangku sekolah. Sementara, 12% lainnya terpaksa drop-out karena keluarganya tidak mampu membiayai. Sekitar 80% rumah tangga tidak punya kamar kecil atau tempat mandi, sementara 88% tidak punya tempat sampah. Di 50 daerah yang dikunjungi, sekitar 90% rumah tangga dilaporkan memiliki anggota keluarga yang sakit. Di 11 distrik, jumlah itu bahkan mencapai 100%. (Laporan World Food
Kalau pulang, bisa bikin apa? Skema pemulangan pengungsi selalu menemui kesulitan. Selama tiga tahun berlangsungnya konflik komunal, diperkirakan 57.000 bangunan rata dengan tanah, di antaranya ada 448 rumah ibadah, 241 sekolah, dan 260 kantor. Sebagian besar penghancuran ini terjadi di Maluku. Di Aceh, ada sekitar 12.000 bangunan yang hancur (Jakarta Post, 17 Juni 2001). Sementara itu, ribuan hektar tanah dan bangunan berpindah tangan yang akan menimbulkan masalah baru di masa mendatang. Pengungsi yang memilih pulang akan mendapat bantuan jatah hidup (jadup) selama tiga bulan sejumlah Rp 250.000, ditambah bantuan untuk membangun kembali rumah senilai Rp 2,5 juta. (Kompas, 22 Januari 2003). Biaya membangun rumah di daerah-daerah yang dilanda konflik biasanya sekitar Rp 300.000/m2. Artinya dengan dana itu pengungsi hanya bisa membangun rumah sekitar 8 m2, tanpa jaminan tanah yang ditinggalkan dapat diperoleh kembali.
Programme, 2002).
Uang, Perang, Damai… Ke mana kami bisa pergi? Menjadi buruh. Menurut Menakertrans Jacob Nuwawea, para pengungsi Aceh yang berjumlah 42.000 jiwa dapat disalurkan menjadi buruh di perkebunan negara maupun swasta. “Bagi pengungsi yang tidak mau, pemerintah lepas tangan dan tidak akan mengurus mereka lagi,” katanya. “Pengungsi selama ini sudah keenakan karena selama ini tanpa bekerja, pemerintah tetap mensubsidi uang lauk pauk Rp 1.500/jiwa. Itulah yang membuat saya jadi pusing,” katanya (Waspada, 28 Agustus 2001). Transmigrasi. Banyak pengungsi asal Timor Leste yang sekarang dijadikan transmigran ke Sulawesi dan Sumatera. Beberapa dari mereka mengaku tidak betah karena fasilitas yang tersedia di sana ternyata tidak sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Buruh harian. Karena lapar dan miskin, tidak sedikit pengungsi yang memilih bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di tempattempat yang banyak menampung pengungsi, barak-barak mereka adalah pusat tenaga kerja murah baru. Kontraktor, pemilik modal dan juga preman bisa merekrut tenaga yang bersedia melakukan apa saja untuk bayaran sekitar Rp 4.000-10.000 per hari. Pulang kampung. Sekitar dua pertiga dari 140.000 orang yang terusir dari Poso saat meledaknya konflik komunal di wilayah itu akhirnya pulang kampung. Di Ambon jumlah yang kembali ke tempat asal mencapai 113,000 dari sekitar 330.000 yang terusir (CCDA, 5 Maret 2003). Tapi bagi ratusan ribu orang lain yang tak punya kampung lagi, pulang ke tempat asal bukan pilihan yang menguntungkan. Karena bermacam alasan, sekitar 70% pengungsi sampai saat ini tetap memilih tinggal di tempat penampungan sementara.
Saat ini diperkirakan bantuan bagi pengungsi dari lembaga kemanusiaan internasional, pemerintah, dan LSM, mencapai US$200 juta per tahun. Pemerintah Inggris selama 2003 menyumbang sekitar US$ 1,2 juta (UN-OCHA, 11 Agustus 2003). Jumlah ini tentunya tidak seberapa dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan senjata ke Indonesia. Jumlah bantuan itu hanya separuh dari nilai sebuah tank Scorpion-90 yang sekarang dipakai untuk menghancurkan pemukiman dan gedung-gedung di Aceh.
… dan tentu saja, korupsi Sebanyak 24 aparat pemerintah dan masyarakat diperiksa oleh kejaksaan di Sumatera Utara karena menggelapkan sekitar Rp 2,07 milyar dana bantuan pengungsi (Kompas, 20 Maret 2003). Di Maluku sekitar Rp 27 milyar bantuan untuk pengungsian tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan membuat bantuan untuk daerahdaerah lainnya terhambat sampai saat ini (Kompas, 22 Maret 2003). DPRD Nusa Tenggara Timur meminta kejaksaan tinggi setempat memeriksa gubernur Piet A. Talo, lima bupati, dan walikota karena diduga menyelewengkan dana pengungsi asal Timor Leste sebesar Rp 600 milyar (Koran Tempo, 13 September 2001). Calon gubernur Maluku Utara, Thaib Armayn, diduga terlibat korupsi dana bantuan sebesar Rp 67 milyar (Koran Tempo, 16 September 2002). sumber foto: www.tempo.co.id
SURAT PEMBACA Yth. Sahabat-sahabatku di Jaringan Kerja Budaya, Entah mengapa tergerak juga hati ini untuk mengirim beberapa catatan dari saya mengenai keadaan Aceh selama sepuluh tahunan ini. Mengapa saya katakan catatan, bukan puisi? Sebab sebuah puisi, sebagaimana layaknya definisi yang terjadi selama ini di Indonesia, haruslah ditulis oleh seorang penyair besar, dan dia haruslah pula menetap tinggal di Jakarta-Jawa. Bukan yang ditulis oleh seseorang seperti saya, yang hanya berdomisili dan kebetulan lahir di Aceh. Apalah artinya orang-orang seperti itu, bukan? Tapi itu tidak begitu penting. Yang perlu saya ingin sampaikan apa saja catatan saya tentang Aceh-Indonesia, setidaknya dari kaca mata saya, yang mudahmudahan belum lagi buram. Bagi saya, yang ibu asli seseorang keturunan Aceh dan kini telah lama meninggal dunia, mendengar kata-kata Aceh sama terharunya ketika saya mendengar kalimat Allah bagi pemeluk agama Islam. Aceh adalah sebuah ironi, sekaligus malapetaka bagi nasib orangorangnya. Aceh seperti penyakir SARS yang sangat berbahaya dan harus dimusnahkan. Sepertinya saya terlalu romantis. Oya, bagaimana keadaan sahabat-sahabatku di sini? Semoga Tuhan masih memberi perlindungan kepada kita. Semoga kehidupan ini masih dapat terpelihara sebagaimana layaknya kehidupan yang baik. Bagaimana pula kabarnya sahabat, kawan dan guru saya Kakanda Hilmar Farid (Fey)? Salam hangat saya untuk beliau. Salam hangat saya untuk sahabat-sahabat di JKB. Bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang Aceh? Ini saya kirim beberapa catatan tentang Aceh, dan kalau dianggap berbahaya bagi keselamatan jiwa, mohon sekedar untuk dibaca-baca saja. Hanya kepada Allah kita memohon ampunan, kepadaNya pula kita meminta perlindungan. Amin. Salam, Din Saja, Banda Aceh
MENDAPATKAN MKB Hallooo... nama saya Rezki Hasibuan. Saya seorang wartawan dari Radio 68H Jakarta. Begitu saya membuka situs Media Kerja Budaya online anda, saya jadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kiprah Media Kerja Budaya ini. Kira-kira di mana saya bisa mendapatkan majalah Media Kerja Budaya? Apakah saya boleh mengetahui siapa-siapa saja yang membidani lahirnya Media Kerja Budaya ini?. SURAT PEMBACA
Mungkin kita bisa berdialog dan berdiskusi panjang lebar soal pengaruh media televisi dan hal-hal yang bersifat kontra-kultura lainnya. Kira-kira bolehkah saya mengirimkan tulisan mengenai kritisi media, kritisi industri musik atau soal budaya lainnya?? Soalnya saya ingin mengetahui lebih jauh tentang kiprah Jaringan Kerja Budaya beserta Media Kerja Budaya. Rezki Hasibuan
CARI INFORMASI Halo. Setelah membaca edisi 8/2002 saya ingin mencari lebih banyak informasi dari majalah anda. Saya belajar/bekerja di Pusat Studi Sosial dan Asia Tenggara di UGM, sedang meneliti aspek-aspek budaya dan seksualitas. Terkait dengan penelitian ini saya minta bantuan anda: 1. Dengan edisi-edisi lama, adakah artikel lain tentang pornografi, seksualitas dan seks? Ada artikel ‘dagang daging $40 milyar’ - siapa penulisnya? 2. Ada penulis dari edisi tersebut, Rika Suryanto. Dia membahas buku “Remaja dalam Cengkeraman Militer”. Minta alamat email, alamat rumah atau nomor telepon - ingin pendapat dia tentang topik yang saya teliti. terima kasih Semsar Siahaan
SURAT DARI ACEH
Thomas Barker, Bulaksumur BLok B-10B Yogyakarta, 55281.
SURAT DARI SEMSAR Gua fikir MKB mengalami kemunduran dalam pemuatan ilustrasi yang bermutu (maaf). Edisi terakhir yang gua sebut, ilustrasinya tampak dadakan dan asal isi. Di samping itu akibat dari illustrasi tersebut, membawa MKB awut-awutan secara visual. Bersama surat ini gua nyumbang dua karyakarya gua thn 2000. untuk bebas digunakan oleh MKB. Dan berjudul: 1. “Totem Millenium Tiga” I dan “ Totem Millenium Tiga” II. Keduanya tinta di atas kertas dan berukuran : 57 cm x 77 cm. Hal lain yang ingin gua kritik adalah menyangkut Keluasan Isi Berimbang atau Kesatuan Isi Kerakyatan MKB. Maksud gua, mengapa isinya dia-dia lagi yang menulis. Dan mengapa isinya melulu berupa tulisan hasil “Pengamatan/Analisa” Intelektual yang itu-itu lagi manusianya, kan begitu luas kemungkinan memuat isi MKB. SELAMAT HARI ULANG TAHUN JKB dan MKB yang KE-X.
Su r a t u n t uk Su rat Pe m baca h e n d a k nya d i l e ngk ap i d e nga n na ma d an al a ma t l e ngkap. K i r i m k an su r at an d a ke a la ma t redaksi MKB: Jalan Pinang Ranti No. 3, Jakar ta 13560 atau emai l: [email protected] rg . Reda ksi t idak mengem bali ka n surat-surat yang diterima.
OBITUARI DAN AKURASI MKB No. 10/2003 memuat obituari Agam Wispi oleh JJ Kusni. Sayang, tulisan itu tak lebih dari “sekapur sihir” yang “diramu” dari larik-larik puisi Wispi sendiri. Tak dijelaskan posisi unik Wispi di antara penyair Lekra dan arti pentingnya bagi sastra Indonesia modern. Di rubrik Resensi Buku ada tulisan Hersri yang, setelah membahas buku, bercerita tentang Buru. Di awal alinea terakhir tulisan itu Hesri menulis “... demi akurasi data.” Sayang lagi, Hersri sendiri tidak akurat. Dia mengatakan Dalang Tristuti Rachmadi tinggal di Unit IV, padahal Tristuti tinggal di Unit X. Dia bilang semua pelukis “dilokalisasi” di dekat Markas Komando Inrehab, padahal banyak pelukis yang tetap tinggal di unitnya, seperti Suhud Mardjo, Martean Sagara, dan Wiryawan. Saya minta Hersri berhenti berpikir bahwa dia paling tahu tentang Inrehab Buru. Saya harapkan juga Redaksi MKB lebih kritis dan seksama. Amarzan, Jakarta.
SALAM PELA Semoga teman-teman sehat selalu. Pertama kami memperkenalkan diri kami yaitu ALIANSI PELA ACEH yang berkududukan di Banda Aceh. Aliansi Pela Aceh merupakan kumpulan dari berbagai individu dengan kemampuan dan spesialisasi tertentu (wartawan, pengacara, guru, aktivis NGO dan lain sebagainya). Aliansi didirikan dengan dilatar-belakangi adanya keinginan berbagai individu untuk ikut terlibat dalam membela, membantu, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir Aceh serta memperjuangkan pengelolaan pesisir dan laut aceh yang berbasis rakyat dan lingkungan yang berlandaskan resolusi konflik, demokratis, dan berkeadilan gender. Sampai saat ini Aliansi telah berusia hampir dua tahun. Kami berharap melalui email ini kita bisa sharing informasi dan mudah-mudahan di masa datang kita dapat bekerja sama. Selain itu kami berharap rekan-rekan bisa mengirimkan buletin, Info Sheet dan lain sebagainya yang bisa memperkuat, mendukung maupun memberikan gambaran kegiatan lembaga rekan-rekan. Informasi ini akan sangat berguna bagi Aliansi Pela Aceh. Demikian perkenalan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dede Suhendra, Sekretaris Eksekutif Aliansi Pela Aceh.
Semsar Siahaan, Victoria, Kanada. media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
3
EDISI 11 TAHUN 2003 Sejak 1993 ISSN: 0853-8069
Mencari Bahasa Pembebasan 2 DATA BICARA 3 SURAT PEMBACA 5 EDITORIAL SAMPUL: ALIT AMBARA
Pemimpin Redaksi Razif Sidang Redaksi Agung Putri, Anom Astika, Arif Rusli, Ayu Ratih, B.I. Purwantari, Hilmar Farid, IBE Karyanto, John Roosa, M. Fauzi, Nugraha Katjasungkana, Razif, Sentot Setyosiswanto Koreksi Akhir Th. J. Erlijna Desain & Web Alit Ambara Distribusi Andre Keuangan O.H.D. Tata Usaha Mariatoen Pemimpin Umum Firman Ichsan Wakil Pemimpin Umum Dolorosa Sinaga
6
6-33 POKOK 7 Puisi JJ. Kusni 8-12 Masih Adakah Bahasa (Bangsa) Indonesia? Yang Menjadikan Bahasa Indonesia Wawancara Jus Badudu Wawancara I Gusti Ngurah Oka Ulasan Alia Swastika Ulasan Hersri Setiawan PAT tentang Bahasa Indonesia
14-18 19-21 21-24 25-27 27-29 30-33
TIM MEDIA KERJA BUDAYA
34-35 OBITUARI EDWARD SAID Media Kerja Budaya adalah terbitan berkala tentang kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Media Kerja Budaya mengangkat berbagai persoalan, gagasan dan penciptaan untuk memajukan kehidupan budaya dan intelektual di Indonesia. Redaksi menerima sumbangan berupa tulisan, foto, gambar dan seterusnya yang bisa membantu penerbitan ini. Bagi pembaca yang ingin eksemplar tambahan dapat menghubungi alamat tata usaha kami. Penerbitan ini sangat tergantung pada dukungan pembaca, kami berharap dapat menerima kritik dan saran anda. Untuk berlangganan Media Kerja Budaya kirimkan data lengkap anda (nama, alamat, no.tel/fax, e-mail) ke bagian tata usaha kami: Jl. Pinang Ranti No. 3 RT. 015/01 Jakarta 13560. Tel./Fax: 021.8095474 (Mariatoen), E-Mail: [email protected]. Biaya berlangganan per edisi Rp 8000,- (Minimum 5 Edisi) ditambah ongkos kirim menurut jarak pengiriman. Pembayaran Dilakukan Melalui Transfer BANK BCA KCP Kramat Jati, Rekening No. 165-600071-7 a.n.: I Gusti Agung Ayu Ratih. Alamat Redaksi Jalan Pinang Ranti No. 3 RT. 015/01 Jakarta Timur 13560 Indonesia Tel./Fax: 62.21.809 5474 E-Mail: [email protected] Alamat Tata Usaha PO. Box 8921/CW Jakarta 13089 Indonesia Tel./Fax: 62.21.809 5474 E-Mail: [email protected]
John Roosa
36-37 PAT GULIPAT Gonjang-Ganjing Sisdiknas
38-40 ESAI Nyanyian Perempuan Amerika Bagi Pembebasan
42
Umi Lasmina
41 PUISI DIN SAJA 42-44 KRITIK SENI Punk di Indonesia Antara Gaya dan Isi Resmi Setia M.S
45-57 SISIPAN MKB Temu Kemanusiaan Korban Orde Baru
58-60 CERPEN SAUT SITUMORANG
45
Bah!
61-63 KLASIK John Sydenham Furnivall M. Fauzi
64-66 RESENSI BUKU Penguasaan Sumber Daya Alam dan Krisis Sistem Kapitalisme Dunia Antonius T. Stevanus
67
67-70 TOKOH Subcomandante Marcos Wilson
71 BERITA PUSTAKA
http://mkb.kerjabudaya.org DAFTAR ISI
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
&2003, Milik Umum
EDITORIAL
DALAM suatu kesempatan langka, A. Latief, seorang agen penyalur buruh Indonesia, menyatakan bahwa TKW banyak menderita kekerasan di luar negeri karena kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab para pembantu ini sangat rendah. “Mereka itu kan anak-anak desa yang bodoh. Kalau dikasih perintah sama majikannya sering salah-salah karena ngga ngerti bahasanya. Ya, lama-lama jengkel majikannya.” Masih menurut si Latief, pemerintah RI harus lebih ketat mengeluarkan ijin usaha penyaluran TKW. “Kalau bisa agen yang mampu mengajarkan bahasa asing saja yang boleh beroperasi.” Tentu saja kami tak percaya begitu saja penjelasan si Latief. Penjelasannya kedengaran seperti dongeng saduran dari pernyataan pejabat pemerintah. Kejengkelan serupa apa yang sudah membenarkan seorang majikan menyiram wajah pembantunya dengan air keras? Kesalahan seberat apa yang sudah dilakukan sekian banyak perempuan desa Indonesia sehingga mereka patut diperkosa, dan tak jarang disiksa sampai mati? Tak mungkin bahasa saja yang jadi sumber soal. Ini soal daya tawar yang sangat tak berimbang. Dan, bukan hanya daya tawar buruh-buruh belia itu saja, tapi juga daya tawar negeri yang mengirim mereka. Menyambut Kongres Bahasa Indonesia VIII yang baru lalu, Kepala Pusat Bahasa, Dendy Sugono, menulis bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi “sebagai alternatif dalam mengisi perdagangan bebas” (Kompas, 13 Oktober 2003). Alasannya, jumlah penutur bahasa ini masuk dalam urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina, Inggris dan Spanyol. Kita harus menyiapkan bahan-bahan pelajaran yang baik untuk membantu orang asing belajar bahasa Indonesia. Setelah gas, minyak bumi, kayu gelondongan, nikel, tembaga, bahkan orang, sudah dijual, kini bahasa pun ditawarkan. Bahasa yang pernah jadi modal berdagang, akan diperdagangkan. Tapi, bukan cuma itu soalnya. Nilai apa yang dimiliki bahasa Indonesia sehingga orang akan tertarik membelinya? Sedangkan Jim Bob Moffet, Presiden Direktur Freeport McMoran, yang tak berbahasa Indonesia sepatah kata pun bisa menguasai tujuh puncak gunung di wilayah Pegunungan Tengah. Dan lagi, kalau kebanyakan kaum terpelajar lebih puas menjadi juru tulis atau juru bicara IMF dan Bank Dunia dari pada menulis karya ilmiah tentang Indonesia, untuk apa orang asing belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tidak akan laku dijual di dalam, apalagi di luar negeri, selama keindonesiaan yang ia wakili adalah pembantaian massal, pencurian dana proyek, penggusuran orang miskin, penggundulan dan pembakaran hutan, serta penjualan anakanak dan perempuan. Selama yang menjadi duta negeri ini adalah tersangka dan terdakwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, tukang catut bantuan untuk pengungsi, dan makelar tubuh manusia, bahasa yang berlaku adalah bahasa uang. Saat ini, satu-satunya bahasa yang menjanjikan pemulihan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat adalah Bahasa Korban. Kita perlu mendengarkan suara mereka yang menjadi korban kekerasan dan kebijakan kriminal ciptaan para petinggi yang lebih cinta uang dari pada manusia. Bahasa mereka terkadang kelewat pedih, menggigit, tapi jelas tak bersalut pemanis ketika menggugat. Seperti ucapan Bu Martini, ibu seorang korban penembakan di Semanggi yang bekerja sebagai buruh cuci, “Kalau Bu Mega ngga bisa selesaikan masalah pelanggaran HAM di masa lalu, ya lebih baik kembali saja ke dapur, masak sayur asem.” Kalau kita tak sanggup hadapi masa paling kelam dalam sejarah Indonesia, kita akan terkurung di “dapur” bangsa lain walau masih berbahasa Indonesia, walau berjumlah keempat terbesar di dunia. Selamat Idul Fitri 1424 H. Maaf sebesar-besarnya MKB edisi ini terbit sangat terlambat. Kami, Gerombolan Orang Particulier Indonesia, berjanji akan bekerja lebih keras tahun depan!
Pemimpin Redaksi
EDITORIAL
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
5
ALIT AMBARA
6
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
MASIH BISAKAH KITA BERBAHASA INDONESIA? JJ. Kusni serambut saja memang perbatasan itu merentang darimana hidup dipilah dari maut kianat terpisah dari setia benci dari cinta damai dari perang sedang hidup jadi wilayah keduanya kernanya diriku pun sering terbelah atau bagai adonan rupa-rupa ramuan — rahasia putra-putri bumi selalu menggelitik tanya tanahair begini besar ditandai warna-warni tanahair sungguh gudang rahasia di mana kita belajar berbangsa dan mendewasa kala mengurai kerunyamannya indonesia adalah keragaman keragaman adalah indonesia dan hidup memang keragaman — para leluhur pun tahu sejak bahela tapi kukira masih saja patut saban kali diulangucapkan menegur ingatan terkadang sangat sembrono yang bisa menyalakan api menghanguskan segala kita memang sering tak gampang dewasa seakan enggan melepaskan masa kanak membungkus kejahatan dengan lagak tanpa dosa kebocahan hingga tak layak digugat hingga pantas dipahami saja dan dimaafkan kitapun dengan enak tak usah lagi peduli ribuan, jutaan nyawa binasa serta miliaran kehancuran bahkan angka-angka yang berada di luar jangkauan mesin-mesin hitung maka bom demi bom dengan tenang terus diledakkan yang kian mengabur perbatasan kemudian batas semu kau sahkan lagi-lagi dengan bom yang mau lebih sadis membayonet para perempuan dan gadis-gadis usai ramai-ramai mereka diperkosa (sempatkah kita berpikir tentang nasib perempuan? sempatkah kita teringat akan ibu sendiri?) aku menanyai diri agar kesadaran tak terlambat menanggap apakah ini bahasa baru dilahirkan waktu dan di sini di indonesia kita tak lagi paham berbahasa indonesia? Perjalanan 2002 media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
7
Masih Adakah Bahasa (Bangsa) Indonesia? Kalau kita membaca sejumlah artikel yang muncul menyambut Bulan Bahasa tahun ini, bahasa Indonesia ditampilkan seperti seorang pejuang tua dan miskin yang sedang bertarung antara hidup dan mati dengan bahasabahasa lain di dunia. Salomo Simanungkalit di harian Kompas menyatakan, “Bahasa Indonesia masuk ke medan perjuangan tempat suatu bahasa saling bertarung dengan bahasa-bahasa lain.” Sialnya, perjuangan itu ternyata tidak menjanjikan apa-apa bagi bahasa kita tercinta ini. Ia diserbu habis-habisan oleh bahasa Inggris yang memasuki “medan perang” dengan persenjataan mutakhir. Bahasa Inggris dengan jumawanya menjadi pemenang bukan saja atas bahasa Indonesia, tapi atas semua bahasa di dunia, “Tentu saja tidak ada satu bahasa lain pun yang mampu memenangkan pertarungan selain bahasa Inggris.” Walaupun kelihatannya akan kalah, bahasa Indonesia tetap berjuang dengan gagah berani. Ada harapan indah terselip bahwa suatu saat bahasa kita yang sederhana dan bersahaja ini akhirnya akan memenangi pertarungan sengit di medan perang bahasa. Kiasan tentang adanya peperangan antar bahasa menunjukkan contoh yang baik bagaimana bahasa bisa mengecoh pemahaman kita. Wartawan Kompas tersebut membicarakan benda mati yang bukan manusia – dalam hal ini bahasa — dan memperlakukannya seakan-akan benda itu memiliki ciri-ciri kemanusiaan. Dalam bahasa Inggris ini disebut anthropomorphism. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sejauh ini kita belum memiliki padanan katanya selain dari personifikasi, yang diserap dari bahasa Inggris personification. Sebagai perangkat retorik, tak ada yang salah dengan personifikasi. Itu sejenis metafor yang seringkali kita pakai. Masalahnya justru ketika kita menggunakan perangkat retorik untuk membangun pemikiran rasional. Rasanya cukup jelas 8
bagi kita semua bahwa bahasa Indonesia tidak sedang berperang melawan bahasa Inggris, seperti juga nasi goreng tidak sedang mengacungacungkan bambu runcing memburu hamburger. Untuk memahami persoalan bahasa Indonesia dewasa ini, kita perlu berpikir tentang kegiatan berbahasa itu sendiri secara menyeluruh. Bagi mereka yang terperangkap dalam metafor perang bahasa, sebenarnya medan yang dibicarakan terbatas pada kosa kata. Bahasa Indonesia dianggap kalah karena semakin banyak orang menggunakan kata-kata bahasa Inggris dalam ujarannya ketimbang katakata bahasa Indonesia. Orang dengan mudah mengganti kata-kata bahasa Indonesia yang sudah cukup jelas maknanya dengan katakata asing, atau malas mencari padanan kata asing yang belum ditemukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Para pengamat khawatir bahasa Indonesia akan semakin tercemar dan tidak dihormati lagi. Kalau keadaan ini berlanjut, mungkin suatu saat kita akan berbicara dalam bahasa Inggris dengan hiasan beberapa kata Indonesia, seperti , “I have to go to the mall sayang, do you want to titip anything?” “Yes, please get me the imported wine that is really enak.” Kita akan berlaku seperti kaum ekspatriat yang hanya tahu segelintir kata-kata Indonesia, tetapi ingin memamerkan kecintaannya terhadap Indonesia dengan cara yang termudah. Menurut beberapa pengamat masalah ini timbul antara lain karena semakin tipisnya nasionalisme di kalangan orang Indonesia pada umumnya. Mereka ingin mencapai “kesuksesan” dengan jalan pintas walaupun pengetahuan dan pengalamannya tidak seberapa. Mereka tidak segan-segan meniru, melahap, bahkan menghamba pada apa pun yang berasal dari “luar negeri” (baca: Amerika Serikat dan Eropa). Jika demikian, apakah kemudian penyelesaiannya adalah pemerintah harus
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ALIT AMBARA
POKOK
menghimbau masyarakat supaya lebih nasionalistik? Menyebarkan propaganda supaya masyarakat bangga dengan bahasa sendiri dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kita semua tahu, Kegiatan serupa ini, seperti juga kampanye ‘Aku cinta rupiah’, ‘Jagalah kebersihan’, atau ‘Orang bijak taat pajak’, tak akan membawa hasil yang berarti. Kami melihat bahwa persoalan sebenarnya bukan pada membanjirnya katakata bahasa Inggris dalam ujaran bahasa Indonesia, tapi bahwa mereka yang menggunakan kata-kata atau istilah bahasa Inggris seringkali tidak tahu persis apa arti kata-kata tersebut. Memang patut disayangkan bahwa kelompok yang begitu banyak memiliki kesempatan mempelajari
POKOK
bahasa apa pun dengan baik justru menjadi salah satu agen perusak bahasa. Kaum terdidik perkotaan yang senantiasa perlu mematut-matut diri ini menggunakan kata-kata bahasa asing bukan untuk memperkaya bahasa Indonesia – bahasa yang selama berabad-abad menyerap ribuan kata dari bahasa Sansekerta, Arab, Portugis, Belanda, dst. – tetapi sekedar untuk memberi kesan kosmopolitan dan berpengetahuan luas. Kalau kita simak baik-baik tuturan mereka, boleh dibilang miskin gagasan orisinal. Mereka mungkin berharap istilah asing yang mereka gunakan bisa menutupi kekosongan dari segi substansi dan mempesona pendengarnya. Sebagai pembanding tuturan kaum
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
yang menyebut dirinya intelektual ini, kita perlu membaca kembali pidato-pidato Soekarno. Setiap pidato Soekarno sarat dengan kata-kata asing. Kadang-kadang ia bisa memakai kata-kata dari tujuh bahasa asing ketika berbicara. Yang menarik ia selalu menjelaskan arti kata-kata asing itu dalam bahasa Indonesia kalau dia menduga pendengarnya tidak mengerti. Kadangkadang ia bahkan menjelaskan cara mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar. Tak heran apabila pendengarnya mudah merasa terangkat derajatnya oleh pidato-pidato Soekarno. Berbeda dengan intelektual publik di masa kini. Mereka malahan ingin membedakan diri, mengambil jarak sejauh mungkin dari pendengarnya. Pendengar kerap merasa
9
10
Indonesia membeku sepanjang pemerintahan Orde Baru, tetapi tidak seluruhnya. Hanya satu bagian saja yang membeku, yaitu bagian yang berkaitan dengan kehidupan kolektif kita sebagai bangsa. Selebihnya dibiarkan terbengkalai, berlarian bebas seperti ayam kampung, menjadi bahasa gaul, bahasa prokem, dan bahasabahasa ‘anti-kemapanan’ lainnya. Seperti juga di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kebudayaan, pemerintahan Soeharto berbuat sangat sedikit untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Tak pelak lagi, seandainya bahasa itu bisa dijadikan komoditi, ia akan dijual murah seperti minyak bumi, tembaga, kayu dan tenaga manusia. Karena tidak memiliki apa yang disebut seorang pemikir Jerman berjenggot exchange value (nilai tukar), bahasa Indonesia diperlakukan seperti udara, sesuatu yang sekedar ada, terbuka bagi siapa saja, dan dengan demikian tersedia pula bagi penguasa untuk dicemari dengan limbah kosa kata beracun: OTB, GPK, massa mengambang, bahaya laten, ekstrim kiri-kanan-tengah, SARA, dst.
Salah satu usaha minimal pemerintah Orba untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah melakukan standarisasi. Sebuah lembaga dengan dana dan ruang gerak terbatas, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), berhasil menyusun daftar kata bahasa Indonesia yang bisa mengganti bahasa asing untuk istilah-istilah teknis. Upaya ini sendiri sesungguhnya patut dihargai. Setiap bahasa sampai tahap tertentu membutuhkan standarisasi supaya bahasa itu bisa dipakai sebagai bahasa tulisan (untuk surat kabar, jurnal, buku, dst.). Mereka yang melihat institusi semacam P3B ini sebagai bukti ambisi totalitarian rejim Orde Baru agaknya melebih-lebihkan kesewenangwenangan institusi tersebut. Bagaimana pun juga standarisasi ragam tulisan untuk tujuan tertentu, seperti penulisan karya ilmiah dan hukum sebenarnya penting dilakukan. Standarisasi di satu bidang tidak berarti standarisasi seluruh bahasa dan pengingkaran atas keragaman. Sasaran utama kritik terhadap bahasa pada masa pemerintahan Soeharto seharusnya
ALIT AMBARA
rendah diri karena mereka dibuat tidak mengerti istilah-istilah ajaib seperti good governance, stakeholder, deconstruction, postmodernism, dst. Padahal sering terjadi bahwa si pembicara sendiri tak terlalu memahami kata-kata yang ia lontarkan. Yang lebih parah lagi, kata-kata yang dipakai mewakili konsep-konsep yang pada dasarnya tidak jelas asal-usulnya dan tidak terlalu penting juga secara ilmiah. Kelompok ini juga dengan teratur dan setia mengacau bahasa Indonesia (atau, bahasa pada umumnya) sebagai penulis kolom atau editorial di surat kabar dan majalah. Kalau kita ambil koran apa saja secara acak dan membaca satu-dua artikel karya para pengamat, segera akan tampak kata-kata dalam bahasa Inggris bertebaran sia-sia dan tak tentu maksudnya. Sebagai contoh, perhatikan kutipan dari artikel yang dimuat di sebuah harian terkemuka di bawah ini: Banyak pula mantan Pati TNI yang bergabung dengan parpol yang lulus threshold. Tetapi, hal itu dapat juga berarti peringatan (warning) kepada kalangan parpol. Tampaknya persoalan dikotomi sipil-militer dalam politik di Indonesia hanyalah materi percakapan di meja perjamuan kaum scholars saja. Orang asing yang berbahasa Inggris tak bakal mengerti kalimat-kalimat di atas, sedangkan kebanyakan orang Indonesia pun hanya akan menebak-nebak. Dan, apa pula perlunya menambahkan kata warning di dalam kurung setelah kata peringatan? Tingginya frekuensi kesalahan penggunaan kata-kata bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia menunjukkan persoalan yang lebih luas dalam bahasa Indonesia sendiri. Suka atau tidak kita harus melihat kembali ke masa pemerintahan Soeharto. Wacana publik dimonopoli sedemikian rupa oleh para petinggi militer dan birokrat sehingga bahasa Indonesia luar biasa terluka dan tumbuh tersendat. Sebagai alat komunikasi sehari-hari antar-teman, bahasa Indonesia sangat kaya. Jika kita ingin menggambarkan penampilan atau kepribadian tetangga atau kenalan kita, tak ada masalah. Ratusan kata dari berbagai bahasa, bahkan dialek, mengalir lancar. Tetapi kalau kita harus berbicara tentang kemiskinan, kekerasan, dan demokrasi, kita seakan-akan kehilangan kata. Yang kita kenal baik adalah rumusan-rumusan resmi dari pemerintah atau ungkapan-ungkapan klise peninggalan para intelektual di masa Orde Baru. Seperti dinyatakan banyak kritikus, bahasa
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
diarahkan pada pembekuan wacana politik di bawah cengkeraman birokrasi dan pengabaian kebutuhan pengembangan bahasa di bidang-bidang lainnya. Bagi orang-orang yang dalam kesehariannya berurusan dengan penulisan dan penerjemahan, standarisasi bahasa tulisan akan sangat membantu kelancaran pekerjaan mereka. Kami di MKB misalnya, akan merasa beruntung kalau ada buku-buku pedoman yang terus-menerus diperbaharui seperti, Oxford English Dictionary dan Chicago Manual of Style untuk bahasa Indonesia. Buku-buku acuan tentang semantik, ejaan, dan tanda baca dalam bahasa Inggris tersebut terbukti membantu banyak penulis dan editor berbahasa Inggris. Tentunya penyusunan buku acuan yang demikian rinci dan padat membutuhkan institusi yang dibiayai dengan memadai dan dikelola orang-orang yang memang ahli dan terampil di bidang kebahasaan. Standarisasi bahasa tulisan yang kami usulkan tidak ada hubungannya dengan konservatisme politik. Justru sebaliknya. Perubahan radikal membutuhkan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Ini adalah pandangan klasik para pemikir masa Pencerahan di abad ke-18 ketika mereka menentang dogmatisme dan takhayul. Para penguasa masa kini tak jauh berbeda dengan penguasa di masa feodal; mempertahankan kekuasaannya dengan menyembunyikan tindakan-tindakan mereka dan mengelabui khalayak dengan bahasa. Tujuan utama politik radikal dengan sendirinya adalah mendobrak ilusi dan merebut kebenaran. Coba kita pertimbangkan beberapa prinsip dasar menulis yang baik: gunakan kalimat aktif yang menunjukkan apa/siapa sebagai subyek (Kamu membunuh lelaki itu. Bukan kalimat pasif: Lelaki itu dibunuh.); gunakan kata-kata yang mengundang kepekaan panca indera sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu kejadian (Kamu menembaknya di kepala dengan sebuah pistol Colt.); hindari eufemisme (Lelaki itu meninggal karena kejadian yang tragis.) Prinsipprinsip atau norma-norma ini penting karena membantu kita menulis karangan yang menggambarkan realitas. Mereka bukan norma-norma khayalan yang dibuat sembarangan. Mereka juga bukan hasil rekaan guru-guru tua nyinyir yang bernafsu membatasi imajinasi kita. Bahasa politik pada jaman Soeharto – yang dipakai dalam pidato-pidato resmi sebagai presiden, terbitan pemerintah, POKOK
begitu juga di media massa secara umum – dengan leluasa mengabaikan normanorma sederhana di atas. Bahasa Orde Baru, seperti sudah sering diungkapkan beberapa peneliti dan pengamat, penuh dengan kalimat pasif, deskripsi seadanya, dan eufemisme. Memang tidak ada pilihan lain bagi sebuah rejim yang harus menyembunyikan terlalu banyak tindakan kriminal. Misalnya, ketika kelompok Soeharto mulai melancarkan aksi kriminalnya yang pertama, teror sepanjang 1965-66, jarang dinyatakan bahwa tentara menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai ‘komunis’: tentara mengamankan mereka. (Lihat buku terbaru Hersri Setiawan, Kamus Gestok, untuk eufemisme ini dan yang lain.) Hilangnya kelugasan dalam gaya bahasa Orde Baru bisa dilihat, antara lain dalam pernyataan Departemen Luar Negeri tentang pembantaian Santa Cruz di Timor Lorosae pada 12 November 1991. Menarik, pernyataan tersebut aslinya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi dengan gaya bahasa Indonesia Orba. “Sangat disayangkan, demonstrasi tersebut tidak sepenuhnya damai dan sesungguhnya menunjukkan provokasi dan tindakan agresif yang direncanakan. Hal itu memicu reaksi spontan dari beberapa aparat keamanan, yang bertindak di luar kontrol atau komando perwira senior, dan mengakibatkan kehilangan nyawa dan sejumlah orang terluka.” Tidak jelas siapa yang membunuh siapa atau bagaimana orang terbunuh. Kata-kata pembunuhan atau pembantaian bahkan tak muncul; birokrat di Deplu menggunakan eufemisme “kehilangan nyawa”. Orang yang membaca pernyataan Deplu tidak akan tahu bahwa dalam peristiwa itu pasukan tentara berjajar rapi, menembak serentak tak berkeputusan serombongan anak muda Timor Lorosae yang tidak bersenjata, dan membunuh paling tidak 300 orang. Tetapi mungkin sebagian warga negeri ini akan menganggap kami tidak patriotik karena ingin berbahasa dengan lugas. Dengan mendorong ditetapkannya norma-norma yang lebih jelas untuk bahasa Indonesia ragam tertulis, bukan berarti kami mendukung “pembekuan” bahasa. Norma-norma yang disebutkan di atas adalah jenis norma-norma yang akan memancing kita menggunakan bahasa dengan lebih kreatif. Pada saat kita berusaha mencapai ketepatan dan menimbulkan kepekaan, kita harus mengobrak-abrik otak kita dan mencari kata sifat yang paling deskriptif, kata benda yang paling akurat, media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
POKOK
kata kerja yang paling dinamis. Mereka yang enggan berurusan dengan norma seharusnya menyadari bahwa setiap bahasa didasari oleh aturan-aturan tata bahasa yang sangat ketat. Manusia mempelajari aturan-aturan tata bahasa ini sejak ia mulai mengenal bahasa, dan menghayatinya sedemikian rupa sehingga ia tak berpikir lagi tentang bahasa secara sadar. Seperti dinyatakan ahli tata bahasa terkenal, Noam Chomsky, manusia secara tak terhingga kreatif berbahasa di tengah aturan-aturan tata bahasa yang terbatas jumlahnya. Misalnya, orang bisa menciptakan kalimat tak terhingga jumlahnya hanya dengan mengikuti rumusan sederhana subyek-kata kerja-obyek. Kalau gaya bertutur resmi bahasa Indonesia menderita penganiayaan luar biasa di tangan rejim Soeharto (perhatikan adanya personifikasi ganda dalam klausa ini), ia tidak bernasib lebih baik di lingkungan intelektual dewasa ini yang berbicara atas nama postmodernism. Ada semacam kecenderungan di kalangan intelektual – sebetulnya bukan hanya di Indonesia saja – untuk berpikir bahwa kedalaman pengetahuan diperoleh semata-mata dari ketaksaan dan kesamaran makna tuturan. Semakin kabur dan tersembunyi makna suatu tulisan, tentunya semakin pandai si Penulis. Tak terlalu mengherankan, kita hidup di dunia yang membingungkan. Kita tidak memahami banyak hal yang sedang terjadi. Keinginan kita untuk memahami realitas sering kali menuntut kita menyingkirkan pandangan-pandangan yang terasa masuk akal dan mengembangkan teori-teori yang kompleks. Tetapi teori-teori yang kompleks masih tetap bisa dipahami begitu seseorang memiliki kesabaran untuk mempelajarinya dengan baik. Yang sering terjadi di kalangan mereka yang menyebut dirinya kaum postmodernist (kami memakai ‘yang menyebut dirinya’ karena mereka tidak tahu pasti juga apa arti istilah itu) adalah menganggap tuturan yang tidak masuk akal sebagai pertanda kompleksitas. Mari kita perhatikan pernyataan seorang guru besar emeritus di bidang hukum dari Semarang: “Postmodernism telah melakukan dekonstruksi terhadap dominasi atau hegemoni negara.” Ia tidak menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan empat dari lima kata benda yang ia gunakan di dalam satu kalimat: postmodernism, dekonstruksi, dominasi, dan hegemoni. Dan, lagilagi, kalau kita baca seluruh esai dengan teliti, tampak bahwa si Penulis tidak tahu apa arti kata-kata tersebut. Misal11
nya, menurut kebanyakan literatur di bidang teori politik, dominasi, dan hegemoni merupakan istilah yang sangat berbeda artinya dan tidak bisa disandingkan seakan-akan keduanya bisa dipakai bergantian tanpa mengubah makna masing-masing kata. (Dominasi mengacu pada kekuasaan yang bertumpu di atas penggunaan kekuatan pemaksa, sedangkan hegemoni mengacu pada kekuasaan yang bergantung pada penggalangan kesepakatan.) Sementara, dekonstruksi adalah metode canggih untuk analisa sastra yang dikembangkan oleh intelektual Prancis Derrida. Tapi dalam esai ini kata dekonstruksi berarti tidak lebih dari ‘mengkritik’. Tulisan dari kalangan aktifis prodemokrasi pun tidak jauh berbeda masalahnya. Berbicara atas nama rakyat, pernyataan-pernyataan terbuka mereka sarat dengan jajaran kata hujatan, tetapi tidak mudah dirunut ujung pangkal persoalannya. Salah satu contoh mutakhir adalah kalimat berikut, “Mengamati dan mencermati eskalasi (meningkatnya) ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang merebak begitu cepat dan meluas, sebagai reaksi terhadap akumulasi berbagai kebijakan pemerintah yang tak perduli kondisi objektif dan suasana bathin rakyatnya, merupakan fakta dan realita politik Indonesia hari ini.” Tanpa permakluman yang cukup besar, pernyataan serupa ini akan melahirkan selusin pertanyaan, mulai dari siapa yang “mengamati dan mencermati” apa sampai ke keterandalan “fakta” yang disampaikan. Sulit melihat kecenderungan berbahasa serupa ini sebagai pertanda kecanggihan mengemukakan gagasan dalam abstraksi. Apa yang terjadi belakangan ini adalah bentuk obskurantisme baru atas nama anti-otoritarianisme. Intelektual yang seharusnya memberi contoh gaya bertutur yang jelas, teliti, dan mendidik asyik berceloteh atau menulis esai yang penuh dengan jargon yang mereka sendiri tidak mengerti dengan baik. Mereka kembali mengambil peran kasta brahmana di dalam masyarakat kuno: mengaburkan kenyataan untuk keuntungan penguasa dan berlaku seakan mereka memiliki bahasa rahasia untuk berhubungan dengan para dewa (yang sekarang kebanyakan mengajar di universitas-universitas ternama di Paris dan New York). Di luar kalangan intelektual yang demam bergenit-genit, ada pula yang memperlakukan bahasa Indonesia seakanakan ia memiliki kekuatan magis untuk 12
mempertahankan kesatuan bangsa ini. Mereka sudah mengelirukan akibat dengan sebab. Ketika sekelompok pemuda menyatakan pada 28 Oktober 1928 bahwa Indonesia memiliki “satu bahasa”, mereka berbicara tentang bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang dibayangkan, sebagai bahasa yang akan dikembangkan seiring dengan upaya membangun bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sedang menjadi, bukan produk siap pakai bagi seluruh orang Indonesia. Bukankah para pemuda ini menuliskan sumpah tersebut dalam bahasa Belanda? Pramoedya menulis dalam artikel yang diterbitkan dalam edisi ini juga bahwa keinginan hidup bersama sebagai suatu bangsa muncul terlebih dahulu, baru kemudian keinginan berbicara dalam bahasa yang sama. Persoalan kesatuan nasional dewasa ini sedikit hubungannya dengan bahasa. Ambil contoh rakyat Timor Lorosae yang (dipaksa) belajar bahasa Indonesia selama bertahun-tahun dan berhasil menguasainya dengan baik. Mereka toh memilih memisahkan diri dari Indonesia pada 1999. Saat ini pun setelah mereka merdeka, kaum terdidik Timor Lorosae masih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa itu sendiri bagi mereka tidak jadi persoalan. Mereka bukan ingin merdeka karena mereka tidak suka bahasa Indonesia. Masalah terbesar bagi mereka adalah keharusan hidup di tengah iklim ketakutan terus-menerus, ketidakamanan, dan kekerasan di bawah pendudukan militer Indonesia. Hal yang sama bisa dinyatakan tentang rakyat Aceh sekarang. Yang jadi persoalan utama bukan bahasa Indonesia. Tak bisa disangkal bahwa bahasa yang sama merupakan salah satu syarat bagi tegaknya suatu bangsa, tetapi ia bukan jaminan mutlak kesatuan bangsa. Kekhawatiran berlebihan sebagian orang akan nasib bangsa ini sudah melahirkan pengharapan yang tidak masuk akal akan bahasa Indonesia. Seiring dengan kecemasan akan keutuhan NKRI, tumbuh pula kecemasan akan lemahnya Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan kekuatan militer tingkat dunia. Seluruh kekhawatiran ini kemudian mereka pantulkan ke bahasa Indonesia, seperti yang terlihat pada retorik tentang perang bahasa di awal tulisan ini. Karena Indonesia secara umum dalam posisi lemah dan rentan, bahasa Indonesia juga diasumsikan sama lemah dan rentannya. Lucunya, kecemasan ini muncul dari kalangan yang secara langsung pun tidak mendukung penjualan segala aset yang dimiliki negeri ini, termasuk tenaga media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
manusia, atas nama pasar bebas, demi globalisasi. Kepala Pusat Bahasa bahkan sudah menimbang-nimbang potensi bahasa Indonesia masuk ke pasar internasional dengan bekal jumlah penutur terbesar keempat di dunia! Salah satu upaya Pusat Bahasa mengangkat kembali derajat bahasa Indonesia adalah menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia syarat bagi orang asing untuk bekerja atau belajar di Indonesia. Semua orang asing harus mempelajari bahasa Indonesia dan mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI) supaya bisa berkomunikasi lebih baik dengan orang lokal dan melakukan alih teknologi. Tak terbayangkan bagaimana aturan ini bisa berlaku ketika para pejabat pemerintah yang diutus keliling dunia selama ini merangkak di hadapan para investor asing, merengek-rengek agar mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Strategi usang memupuk kebanggaan nasional yang palsu ini tak juga berubah. Pejabat-pejabat yang berteriak-teriak mengecam “intervensi asing”, “ikut campur urusan dalam negeri Indonesia” adalah mereka yang dengan senang hati menerima kucuran dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan menyalurkan sebagian besar dana itu ke rekening-rekening pribadi mereka. Kalau benar investor asing diharapkan menguasai bahasa Indonesia, mungkin kosa kata yang perlu diketahui tak perlu terlampau banyak: jatah, pungli, komisi, biaya administrasi – semua kata yang berhubungan dengan korupsi dan pemerasan yang dilakukan tentara dan birokrat preman. Bagaimana pula kalau semua orang asing fasih berbicara dalam bahasa Indonesia? Melihat sikap umum kita yang menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa orang pandai, pasti kita akan menganggap bahasa Indonesia orang asing lebih superior dari pada cara berbahasa kita sendiri. Kita akan meniru mereka sebisa mungkin sehingga kesalahan berbahasa dan aksen mereka menjadi norma umum bahasa Indonesia yang baik dan benar! 0
POKOK
BAHASA INDONESIA TERBUKA ATAWA TERTUTUP?
Selama ratusan tahun bahasa Indonesia (BI) yang berasal dari sebuah lingua franca atau bahasa Melayu Pasar dikenal ramah dan terbuka terhadap pengaruh bahasa asing, terutama dari segi kosa kata. Jadi, kalau para pejabat sering menyerukan tanda bahaya “Hati-hati terhadap intervensi asing!”, sebetulnya percuma saja. “Basi!” kalau anak gaul Jakarta bilang. Di bawah ini ada daftar statistik “kasar2an” jumlah kata-kata asing dalam BI yang pernah dibuat ilmuwan politik jahil, tapi pintar, dari Universitas Cornell (sekarang sudah pensiun), Ben Anderson. Dengan bantuan temannya, seorang Arab, ia menghitung semua kata yang ada di Kamus “antik” Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, cetakan ke-2, tahun 1953. Jumlah kata yang diselidiki 4.120 kata. Hampir separuh (45%), atau 1.828 kata, berasal dari bahasa-bahasa non-nasional. Urutannya sebagai berikut:
Aneh juga si Ben ini tak memasukkan bahasa Sansekerta dalam daftarnya. Bayangkan kalau dimasukkan, persentase bahasa asing dalam BI mungkin jadi 75%, karena banyak sekali kata BI yang berasal dari bahasa itu. Saking sudah begitu akrabnya dengan BI, mungkin banyak yang tak sadar kata-kata yang dipakai sehari-hari itu berasal dari bahasa asing. Coba kita lihat bersama daftar kata-kata berikut, yang dikumpulkan dari berbagai sumber: Belanda:
handuk, kakus, kulkas, selai, praktek, apotek, persekot, bioskop, duit
Arab:
rakyat, masalah, masyarakat, kitab, pikir, paham, sebab, kuat, dunia
Inggris:
nasionalisme, mal, diskotik, modern, teater
Tionghoa:
taoco, kongsi, toge, tahu, tongkang, loteng
Sansekerta:
negara, putra-putri, kerja, perkasa, cinta, agama, menteri, semua
Tamil:
cukai, kedai, modal, kolam, kapal, cuma
Portugis:
sabun, gereja, meja, sepatu, bendera, serdadu, peniti, garpu
Parsi:
kertas, bebas, bandar, dewan, bedebah
Nah, sekarang coba kita ingat-ingat adakah kata dari bahasa Papua atau Timor yang kita kenal dan pakai dalam percakapan seharihari? Tentunya bukan yang dari lagu-lagu daerah. Kami sudah cari dengan cukup rajin, ternyata di kamus juga tak ada. Berarti, bahasa Indonesia sebetulnya tak terbuka-terbuka amat. Tak salah kalau orang-orang Indonesia Timur merasa dianaktirikan. Pendapat bahwa bangsa Indonesia dikuasai lingkaran elit Jawa, Sunda, Betawi dan Sumatra juga bukan asal bicara. Konon “bahasa menunjukkan bangsa”.
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
13
Yang Menjadikan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia bukan anugerah yang diturunkan dari langit. Ia adalah buah pertarungan beraneka kepentingan dalam gerak sejarah. Ia juga senjata yang dirombak dan dirakit berulang kali untuk memenuhi kebutuhan membebaskan pun menindas. Dari wacana sejarah utama, kita mendapat kesan bahwa bahasa Indonesia ditemukan begitu saja oleh sebuah Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Tak pernah diungkapkan bahwa kebanyakan peserta kongres yang berasal dari golongan menengah-atas terdidik ini ternyata tidak bisa berbahasa Melayu sehingga kongres itu sendiri terpaksa diselenggarakan sebagian besar dalam bahasa Belanda. Kalau mereka bersepakat menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu bukanlah karena mereka beroleh wangsit di tengah mimpi. Ada kenyataan sejarah yang tak bisa mereka pungkiri, yaitu bahasa yang dipakai secara meluas di wilayah Hindia Belanda adalah bahasa Melayu. Lagi pula, gerakan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan kolonial yang mendahului kongres tersebut sudah menggunakan bahasa Melayu – walau dengan gaya yang berbeda — sebagai bahasa politik. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pergerakan nasional tak bisa dipisahkan dari posisi-posisi politik yang berkembang di paruh awal abad ke-20. Di satu sisi, politik kebudayaan pemerintah kolonial Belanda – berbeda dengan pemerintah kolonial Inggris dan Prancis – membatasi penyebaran bahasa Belanda di tanah jajahannya. Di lain sisi, gerakan perlawanan yang berkembang di masa itu membayangkan suatu nasion yang mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda dan melibatkan kalangan rakyat biasa. Seandainya Indonesia yang dibayangkan itu sebatas tanah (priyayi) Jawa, bahasa nasional yang akan dipilih kemungkinan bahasa Jawa, atau malahan bahasa Belanda. 14
Bahasa Segala Bangsa Selama ratusan tahun sebelum bahasa Melayu menjadi bahasa nasional yang ‘rapi’ dan ‘sopan’, ia sudah berkembang sebagai bahasa khalayak ramai (lingua franca) dari berbagai ras dan suku bangsa terutama di bandar-bandar perniagaan sepanjang pesisir Nusantara. Bahasa Melayu Pasar ini – Pramoedya Ananta Toer menyebutnya sebagai bahasa Melayu Kerja atau bahasa pra-Indonesia — berbeda dengan bahasa yang dipakai kalangan istana di pantai timur Sumatra dan Semenanjung Malaya untuk menulis karya sastra dan dokumen administrasi pemerintahan. Seperti lingua franca pada umumnya, bahasa ini sangat terbuka terhadap dialek dan kosa kata lokal. Struktur tata bahasanya sederhana, tidak memiliki standar yang baku, tapi cukup jelas untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Kalau bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Jawa, Bali, Madura, Sunda, atau Belanda, bermuatan nilai-nilai kebudayaan tradisional, bahasa Melayu Pasar seakan tumbuh ‘liar’ menjadi bahasa segala bangsa. Ia dengan mudah menyerap kata-kata Arab, Portugis, Cina, dsb., tanpa mengganggu kesalingterpahaman antar-pembicaranya. Dominasi kultur perdagangan kepulauan sudah membuat lingua franca ini bertahan selama ratusan tahun. Lepas dari segala keterbatasannya, ia praktis sebagai bahasa transaksi dan fleksibel sebagai alat komunikasi antar (suku) bangsa. Sampai awal abad ke-19 hampir-hampir tak ada upaya untuk menstandarkan atau membakukan bahasa tersebut. Kebutuhan mengendalikan ‘kekacauan’ praktek berbahasa ini mulai muncul setelah Gubernur Jendral Inggris, T. Stamford Raffles, datang ke Hindia Belanda sekitar 1810an. Ia terperanjat melihat kesantaian orang-orang Belanda, termasuk para pegawai birokrasi kolonial, bergaul dengan kaum pribumi. Walaupun secara resmi pemerintah kolonial yang mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik, di wilayah sosial-budaya Belanda tidak memimpin sehingga nilai-nilai peradaban Eropa
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ALIT AMBARA
POKOK
dianggap meluntur. Raffles khawatir kekuasaan Belanda di tanah jajahan akan mudah tergerogoti tanpa ada hegemoni budaya. Ia juga gusar dengan tercemarnya keeropaan orang-orang Belanda yang sudah bertahun-tahun hidup di Hindia Belanda dan mengadopsi cara hidup masyarakat lokal. Bahasa Belanda mereka makin buruk karena bercampur kosa kata Melayu Pasar. Kedekatan mereka dengan penguasa lokal membuat birokrasi kolonial tidak efisien laiknya sistem Eropa. Dalam masa kepemimpinannya yang singkat, ia bertekad mendesakkan pembedaan budaya yang jelas antara birokrat Belanda dan kaum ‘inlander’. Penggunaan bahasa menjadi salah satu sasaran utama operasi penertiban budaya ini. Ada dua hal yang menjadi tujuan. Pertama, pegawai pemerintah harus menjadi model keteraturan yang ditunjukkan dengan penguasaan bahasa Belanda dan bahasa lokal yang sempurna, secara lisan pun tulisan. Kedua, pemerintah perlu menyebarkan aturan main kolonial dengan bahasa yang ajeg struktur dan ragamnya agar tidak mengundang perbedaan pemahaman dan pendapat di kalangan masyarakat umum. Sepeninggal Raffles, penguasa-penguasa berikutnya melanjutkan kebijakan ini. Sejak 1820an ahli-ahli bahasa dari universitas-universitas ternama di Belanda dikerahkan untuk melakukan penelitian tentang POKOK
bahasa-bahasa lokal yang dominan dan mengusulkan cara penataan bahasa yang paling menguntungkan pemerintah. Pejabat pemerintah yang merasa dirinya mengenal koloni lebih baik ikut pula bersuara. Perdebatan sengit tak terelakkan. Ada pihak yang beranggapan bahasa Jawa lebih tepat dipakai karena mayoritas penduduk Hindia Belanda dan pusat kekuasaan pemerintah berada di Jawa. Pihak lain melihat bahwa bahasa Melayu lebih tepat karena pemerintah berniat memperkokoh kekuasaannya di luar Jawa dan memerlukan bahasa pengantar yang sudah lazim dipakai penguasa lokal non-Jawa. Tidak berhenti di perdebatan, para ahli bahasa ini berlomba-lomba menerbitkan hasil-hasil penelitian mereka. Dr. Pieter Roorda van Eizinga misalnya menyusun kamus besar Melayu/Jawa-Belanda dan Belanda-Melayu/Jawa. Sedangkan ahli lain, Dr. Pijnnappel, malah menerbitkan sejumlah buku pegangan bahasa Melayu dalam berbagai versi untuk mengatasi variasi dialek yang hidup di masyarakat Hindia Belanda. Namun, satu hal yang mereka sepakati adalah sulitnya mengendalikan bahasa Melayu Pasar karena begitu lentur dan beragamnya dialek yang berkembang di pelbagai daerah di Nusantara. Pemerintah sendiri dihadapkan pada kenyataan
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
yang rumit: harus ada bahasa yang mampu mendukung kepentingan pemusatan kekuasaan, tapi bahasa lokal yang paling dominan, bahasa Melayu Pasar, sama sekali tidak memadai untuk menjawab kebutuhan ini. Menarik diperhatikan bahwa misi pemberadaban koloni melalui bahasa ini bukannya menghasilkan kebijakan penggunaan bahasa Belanda, tapi malah mendorong penataan bahasa-bahasa lokal. Tampaknya keterbatasan sumber daya pemerintah kolonial melatarbelakangi keputusan ini. Lebih murah menyewa beberapa intelektual Belanda untuk melakukan penelitian daripada menyelenggarakan pendidikan massal bagi seluruh penghuni Hindia Belanda dalam bahasa Belanda. Bisa jadi ini terkait pula dengan politik kolonial yang ingin mempertahankan penguasa-penguasa lokal sebagai kakitangan pemerintah daripada mendatangkan dan menggaji ribuan pegawai dari negeri Belanda. Setelah sekian uji coba dan perdebatan selama berpuluh-puluh tahun, pendukung penggunaan bahasa Melayu beroleh posisi lebih kuat. Hanya saja, mereka sejak dini sudah menetapkan bahwa acuan utama untuk kerja penataan bahasa ini adalah bahasa Melayu tulisan yang digunakan di pusat kebudayaan Melayu, yaitu Riau dan Selat Malaka. Lepas dari hasil penelitian mereka yang menunjukkan kepo15
puleran bahasa Melayu Pasar, mereka berpendapat bahasa Melayu Riau lah yang lebih murni dan nyata. Dari Bahasa Dagang ke Bahasa Pergerakan Penertiban bahasa Melayu berlangsung paling sistematis menjelang akhir abad ke19 sejalan dengan ambisi pemerintah kolonial memantapkan kekuasaannya di se-antero Nusantara. Dua intelektual yang berperan penting dalam operasi ini adalah Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah untuk urusan kebudayaan, dan J. van Ophuysen, guru besar bahasa Melayu dari Universitas Leiden. Atas usulan Snouck, van Ophuysen menyusun dua buku yang berisi daftar kata-kata Melayu dengan sistem ejaan Eropa dan aturan tata bahasa Melayu. Kedua buku ini menjadi buku pegangan utama bagi pegawai pemerintah dan pendidik di Hindia Belanda maupun di Belanda sendiri. Bahasa Melayu ala Van Ophuysen segera ditahbiskan sebagai bahasa resmi dan disebarluaskan melalui institusi pendidikan pribumi. Di kalangan pemerintah kolonial dan intelektual pendukungnya mulai dikenal istilah bahasa Melayu ‘Tinggi’ dan ‘Rendah’. Semua varian bahasa Melayu yang tidak mengikuti versi Van Ophuysen, diberi cap ‘rendah’ atau ‘kacau’ dan hanya pantas dipakai untuk berkomunikasi dengan babu dan jongos. Selain menyebarkan bahasa Melayu Tinggi melalui pengajaran, pada 1908 pemerintah Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat, atau lebih dikenal dengan Balai Pustaka (BP), untuk memproduksi bacaan Melayu bagi kaum bumiputra. Badan yang dikepalai D.A. Rinkes ini bertugas menyeleksi naskah-naskah yang masuk dan memastikan bahwa isinya tidak bertentangan dengan kepentingan politik pemerintah. Karena syarat awal yang ditetapkan adalah penggunaan bahasa Melayu Tinggi, sudah barang tentu karyakarya yang diterbitkan sebagian besar ditulis oleh pengarang dari Sumatra. Kelak, para penulis Melayu ini berperan cukup penting dalam pelibasan karya-karya bumiputra yang dianggap ‘tidak bermutu’, dan menentukan batasan khazanah sastra modern Indonesia (untuk pembahasan lebih mendalam tentang BP, lihat MKB edisi 03/2000). Di tengah kesibukan pemerintah kolonial menata bahasa Melayu, golongan masyarakat Tionghoa peranakan dan IndoEropa justru mendorong berkembangnya bahasa Melayu Pasar dari sebuah lingua 16
franca menjadi bahasa pers dan bahasa sastra. Sejak paruh akhir abad ke-19 mereka sudah menerjemahkan karya-karya ternama dari Tiongkok dan Eropa ke dalam bahasa Melayu Pasar. Dari pengalaman ini, muncullah keberanian untuk menulis novel yang menggambarkan suasana Hindia Belanda dan menerbitkan koran dalam bahasa Melayu Pasar. Terbitan lokal ini ternyata mendapat sambutan luar biasa, terutama karena bahasa yang dipakai akrab dengan khalayak jajahan. Misalnya saja, dalam waktu beberapa puluh tahun jumlah novel Melayu-Tionghoa yang diproduksi, menurut perhitungan peneliti sastra Claudine Salmon, mencapai tidak kurang dari 3.000 karya. Terbitan kaum Tionghoa peranakan dan Indo-Eropa ini dimungkinkan karena mereka memiliki usaha penerbitan dan percetakan mandiri yang tidak bergantung pada subsidi pemerintah kolonial. Bukubuku yang mereka terbitkan biasanya diproduksi dengan harga yang sangat murah supaya bisa dibeli pegawai rendahan dan kaum yang disebut orang partikelier – mereka yang tidak bekerja tetap di kantor pemerintah atau perusahaan swasta. Berbeda dengan penerbitan milik Belanda yang mempekerjakan kaum bumiputra sebagai buruh kasar, usaha penerbitan dan percetakan ini membuka ruang bagi kaum bumiputra untuk magang sebagai penyunting dan penulis. Banyak tokoh-tokoh pers pergerakan 1920an, seperti R.M. Tirtoadhisoerjo, Mas Marco Kartodikromo, dan Mohammad Sanoesi yang mengawali karirnya di perusahaan serupa ini. Menjamurnya percetakan dan penerbitan golongan Tionghoa peranakan dan Indo-Eropa mengancam dominasi bacaan resmi pemerintah kolonial. Laporan penyelidikan tentang skandal-skandal perkebunan, roman percintaan yang berlawanan dengan nilai-nilai priyayi/kolonial, sampai berita kemenangan Jepang atas Rusia dan kisah-kisah perlawanan lain di negeri seberang bersaing dengan teks-teks dingin dan membosankan yang melulu berisi laporan-laporan pemerintah. Lebih jauh lagi, bahan-bahan bacaan tak resmi yang berhasil meraih kelas-kelas rendahan ini lambat-laun membuka cakrawala pemikiran yang berbeda di kalangan bumiputra. Ketidakadilan yang diciptakan sistem kolonial harus dilawan dengan caracara baru. Dan, pewartaan yang mampu mengungkap kebobrokan sistem tersebut menjadi pilihan pertama. Pemuda-pemuda pribumi yang semula media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
menjadi tenaga magang mulai membuka penerbitan dan percetakannya sendiri. Pada 1907, Tirtoadhisoerjo membuka percetakan dan penerbitan Medan Prijaji yang menerbitkan surat kabar dengan nama yang sama. Di Solo, HM Misbach mendirikan penerbit Insulinde yang berperan besar dalam produksi bacaan selama kurun 1910an. Serikat buruh kereta api, VSTP, yang bermarkas di Semarang kemudian juga mendirikan percetakannya sendiri dan menerbitkan surat kabar dengan tiras terbesar sepanjang sejarah pergerakan, Si Tetap. Dengan basis yang relatif independen dari kekuasaan kolonial, para penulis dan pengelola surat kabar segera memulai ‘perang suara’ dengan penguasa kolonial dengan gaya tulisan yang militan dan memikat. Dengan sengaja para jurnalis ini memilih bahasa Melayu Pasar sebagai alat komunikasi lisan pun tertulis. Mereka melihat bahwa usaha pemerintah menertibkan bahasa Melayu berkaitan dengan niat pemerintah mengendalikan pola pikir rakyat jajahan. Di samping itu, secara praktis mereka merasa bahwa bahasa Melayu Pasar jauh lebih lugas dan bebas dari tata krama feodal ketimbang bahasa Jawa atau bahasa Melayu-Belanda. Upaya pemerintah memberadabkan kaum bumiputra dengan buku-buku keluaran BP dihadapi dengan koran, pamflet, majalah, syair, novel bagi kelas-kelas rendahan untuk mempelajari, mengkritik, dan sekaligus menyerang kekuasaan kolonial. Sementara bacaan dalam bahasa Belanda dan Melayu Tinggi yang dikuasai pemerintah kolonial mengajar kaum bumiputra tentang hukum, aturan, dan tatanan kolonial yang membungkus ketimpangan, bacaan pergerakan justru mulai dengan melihat ketimpangan dan menggunakan pengertian-pengertian baru yang diperoleh dari berbagai sumber: tradisi perlawanan rakyat Jawa, Revolusi Tiongkok, dan Rusia, dan gagasan sosial-demokrat Belanda. Militansi dan radikalisme semakin meningkat ketika para jurnalis, penulis, dan penerbit mulai terlibat dalam organisasi pergerakan nasionalis seperti Sarekat Islam, Insulinde, dan serikat-serikat buruh. Tulisan mereka semakin terarah pada persoalan konkret yang dihadapi organisasi, perseteruan dengan pemerintah kolonial, dan ketimpangan serta ketidakadilan yang dihadapi mayoritas pembacanya. Pada paruh kedua 1910an, ratusan buku dan puluhan surat kabar sudah diterbitkan dan menjadi bagian penting dari pergerakan
kannya untuk menjelaskan gagasan abstrak, seperti sosialisme dan marxisme, atau kaitan antara Islam dan komunisme. Sedangkan Mas Marco Kartodikromo berupaya menyusun ulang Babad Tanah Jawa, untuk “mengambil kembali masa lalu orang Jawa yang selama ini berada di tangan orang Belanda”. Maraknya terbitan politik yang berjalan seiring dengan gelombang pasang gerakan massa anti-kolonial ini dengan sendirinya menimbulkan kegusaran di pihak pemerintah. Melalui BP, pemerintah menetapkan bacaan berbahasa Melayu rendah dan Melayu Tionghoa sebagai “bacaan liar” yang rendah mutunya dan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban koloni. Rinkes secara khusus menuding tokoh-tokoh pergerakan, seperti Mas Marco Kartodikromo, Semaoen, dan Moeso sebagai provokator
ALIT AMBARA
nasionalis. “Perang suara” tidak hanya dilakukan terhadap penguasa kolonial dan pendukungnya, tapi juga di antara aktifis pergerakan sendiri. Polemik dan perdebatan mengenai persoalan sehari-hari atau kebijakan pemerintah mengisi halaman surat kabar atau pamflet, dan menjadi unsur penting dalam pembentukan wacana mengenai bangsa. Kali ini golongan bumiputra rendahan membuktikan bahwa bahasa Melayu Pasar cukup memadai, bukan saja untuk mengungkapkan perasaan terdalam mereka sebagai kaum terjajah, tetapi juga untuk mengembangkan imajinasi mereka tentang kehidupan yang lebih baik. Perkembangan yang tidak kalah menarik, bahasa ini juga dipakai untuk membangun wacana ilmiah di kalangan pergerakan. H.M. Misbach, seorang aktifis Sarekat Rakyat, mengguna-
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
POKOK
yang menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Akibatnya, para jurnalis dan aktifis ini berulangkali ditangkap dan terbitan yang mereka pimpin dibredel. Namun, tekanan ini tidak menyurutkan penerbitan bacaan liar, sampai pemberontakan rakyat yang diorganisir PKI dan Sarekat Rakyat meletus pada November dan Desember 1926 di Jawa dan Sumatra Barat. Gempuran telak pemerintah kolonial terhadap pemberontakan 1926 boleh dikatakan mengakhiri kemeriahan penyebaran bahasa Melayu ‘liar’, dan menandai perubahan karakter gerakan nasionalis itu sendiri. Barisan penulis-aktifis dari kelaskelas rendahan yang mendominasi gerakan sebagian besar dipenjarakan dan dibuang ke Boven Digul. Beberapa dari mereka meninggal di pembuangan, sedangkan yang masih hidup tidak lagi memegang peranan penting pada periode-periode selanjutnya. Jaringan percetakan, penerbitan, distribusi, dan pembaca yang menopang produksi bacaan liar selama 15 tahun porak-poranda. Dan, yang berkaitan langsung dengan bahasa, kelugasan, spontanitas, dan ketajaman wacana politik dalam Melayu Pasar berganti dengan kalimat terselubung, tidak konfrontatif, bernada petuah, dalam bahasa yang lebih dekat ke gaya Melayu Istana. Memenangkan (Bahasa) Indonesia Memasuki periode 1930an, perkembangan bahasa Melayu Pasar sebagai bahasa politik boleh dibilang tersendat, kalau tidak terhenti sama sekali. Dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada 1938, salah satu pemrasaran yang juga anggota Dewan Redaktur Balai Pustaka, St. Takdir Alisjahbana, secara terbuka menyatakan bahwa bahasa Melayu Pasar adalah bahasa yang belum mengenal peradaban dan tidak memadai untuk mengungkapkan gagasan dalam tulisan. Kongres yang dipimpin kaum terpelajar golongan menengah-atas ini – Sanoesi Pane, St. Pamuntjak, Muh. Yamin, Adinegoro, Poerbatjaraka — memutuskan untuk memakai ejaan Van Ophuysen sebagai acuan resmi bagi seluruh orang Indonesia. Keputusan konservatif serupa ini seakan tak terelakkan. Di satu sisi, represi luar biasa terhadap gerakan massa radikal sudah membuat aktifis gerakan nasionalis 1930an lebih berhati-hati berhadapan dengan pemerintah. Di lain sisi, sebagian besar dari mereka yang muncul dalam periode ini, seperti Hatta dan Sjahrir, memang tidak menguasai bahasa 17
Melayu dengan baik. Jangankan bahasa Melayu Pasar, bahasa Melayu Tinggi pun tak mereka pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih banyak berpikir dan berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Selain itu, mereka juga tidak punya pengalaman membangun organisasi massa dari bawah seperti aktifis 1920an, sehingga tak terlalu mengherankan kalau gagasan kebangsaan yang mereka coba rumuskan sangat dipengaruhi ide-ide pemberadaban politik etis. Selama hampir seabad, melalui tiga generasi ilmuwan dan birokrat, pemerintah kolonial berusaha keras menertibkan bahasa Melayu Pasar. Ternyata kaum cerdikcendekia yang cukup beroleh keuntungan dari kolonialisme yang akhirnya berhasil memenuhi ambisi tersebut. Seperti halnya isi putusan Kongres Pemuda 1928 yang menekankan kesatuan, bahasa Melayu-Belanda yang dikembangkan sejak 1930an membawa serta nilai-nilai kolonial yang menekankan ketertiban, keseragaman, dan kepatutan. Alhasil, wacana nasionalisme yang berkembang di masa itu sangat dihantui keinginan untuk menjadi bangsa yang ‘maju’ menurut ukuran Eropa, sederajat dengan bangsa-bangsa Eropa. Yang menjadi pokok soal adalah perbedaan warna kulit atau kesenjangan antara kultur ‘barat’ dan ‘timur’, bukan perbedaan kelas. Memang, kebangkitan kembali pergerakan massa sejak Revolusi Agustus 1945 seakan membuka jalan bagi rakyat untuk memberi makna pembebasan dalam bahasa Indonesia rakitan kolonial ini. Kata-kata yang mencerminkan pengalaman paling penting pembicaranya, seperti merdeka, perjuangan, kebangsaan, muncul tanpa kendali. Harus diakui pula kemampuan Soekarno sebagai pimpinan nasional pergerakan dalam menggunakan bahasa yang rancak dan menimbulkan semangat berpengaruh luar biasa terhadap pemerkayaan bahasa Indonesia sebagai bahasa politik. Dalam banyak hal Soekarno mengadopsi cara-cara berbahasa tokoh-tokoh pergerakan 1920an, yang mungkin ia pelajari dari pengalamannya sebagai pemuda di masa itu dan kedekatannya dengan HOS Tjokroaminoto, pimpinan Sarekat Islam dan orator handal di jamannya. Sayangnya masa kebebasan bahasa Indonesia tidak berlangsung lama. Menjelang akhir 1950an persaingan politik antar partai dan ancaman ekspansi modal internasional yang beberapa kali diwujudkan dalam provokasi militer melahirkan seruan-seruan yang sarat slogan untuk ke18
pentingan mobilisasi dan konsolidasi massa. Para pimpinan kekuatan-kekuatan politik yang bertarung — yang paling revolusioner sekali pun – seperti kehilangan kemampuan menciptakan adagium yang mencerminkan pemahaman mereka akan permasalahan sosial masyarakat. Mereka melakukan “perang suara” di antara mereka sendiri. Di sisi lain, dominannya pemimpinpemimpin dari kalangan priyayi Jawa mendorong apa yang disebut ilmuwan Ben Anderson “kramanisasi bahasa publik Indonesia”, yaitu munculnya kata-kata Sansekerta atau Jawa Kuno baik untuk merumuskan konsep-konsep politik, maupun untuk memberi nama institusi publik yang bernilai politis tinggi. Misalnya, di masa itu bermunculan istilah-istilah seperti Tri Ubaya Çakti, Sapta Marga, Operasi Mandala, Praja Muda Karana, Cakrabhirawa, dst. Soekarno, dalam usahanya menggalang solidaritas dan mempertahankan persatuan nasional, asyik menciptakan lusinan akronim yang terdengar revolusioner, seperti Jarek (Jalannya Revolusi Kita), Resopim (Revolusi Sosialisme Pimpinan), Manipol-Usdek (Manifesto Politik- UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Nasional), tapi belakangan justru menjadi mantra-mantra yang menghalangi pemahaman rakyat tentang revolusi itu sendiri. Kemana bahasa politik Indonesia? Ketegangan politik yang berlarut-larut akhirnya memuncak pada peristiwa G30S 1965, yang diikuti dengan tragedi paling berdarah sepanjang sejarah modern Indonesia. Operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di bawah komando Mayjen. Soeharto membersihkan jagad politik Indonesia dari seluruh elemen yang dianggap kiri, komunis, termasuk Soekarno. Bahasa Indonesia tidak luput dari operasi pembersihan ini. Kata-kata yang sepanjang sejarah pergerakan nasional menjadi kendaraan pembebas, seperti buruh, rakyat, revolusi, sosialisme, bahkan kata pergerakan itu sendiri, dihilangkan atau diganti dengan kata-kata yang tidak mengundang ingatan akan perlawanan di masa lalu. Kontrol ketat terhadap media massa dan terbitan umum menghasilkan bahasa yang sopan, berlikuliku, dan tak berpendapat. Wacana publik dipenuhi oleh bahasa birokrasi negara. Orde Baru memang jauh lebih berhasil dari pemerintah kolonial Belanda dalam menertibkan dan memaksakan pemakaian bahasa Indonesia yang ‘baik dan benar’ ke media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
seluruh Nusantara, bahkan ke negeri tetangga, Timor Lorosae. Sumber kekuatan utamanya tak lain dari ratusan ribu tentara yang diperintahkan terus-menerus mengawasi tingkah laku, kalau perlu membunuh dan memperkosa, warga negeri ini. Tapi, yang tidak kalah pentingnya adalah keberhasilan rejim ini meyakinkan sebagian warganya bahwa ketertiban dan kepatutan yang dijamin dengan kepatuhan terhadap pemerintah akan membawa kemajuan bagi kehidupan mereka. Meskipun rejim Soeharto akhirnya tumbang pada 1998, merebut kembali bahasa Indonesia sebagai bahasa pembebasan ternyata tidak mudah. Kita jelas tak bisa kembali ke bahasa Melayu Pasar yang berkembang meriah bersama gerakan sosial 1920an; kita tak mungkin menghapus 80 tahun perjalanan bahasa Indonesia. Tapi, kita harus bisa merubuhkan temboktembok pembatas bahasa ala Orba. Salah satu tembok yang cukup kokoh adalah keangkuhan kalangan terdidik di Jawa dan Jakarta yang berpikir bahwa merekalah yang paling menguasai bahasa Indonesia secara sempurna dan merasa seakan-akan merekalah yang bertanggung-jawab mengangkat derajat seluruh bangsa. Kita perlu memperluas ruang berbincang bagi orangorang dari berbagai ras dan suku bangsa sehingga bahasa Indonesia mencerminkan keragaman logat dan dialek yang hidup di segala penjuru kepulauan ini. Kebutuhan akan bahasa yang sama tidak harus dipenuhi dengan standarisasi bahasa di tingkat pusat dan pemaksaan penggunaan di tingkat daerah. Bahasa Indonesia bukan amunisi senjata tentara yang perlu diagung-agungkan sebagai pengikat utama kesatuan republik ini. Seperti kisah kelahirannya, ia seharusnya tumbuh dari percakapan terbuka antar warga bangsa; ia selayaknya pulang asal sebagai alat pendobrak milik kaum mardika. 0
BINCANG-BINCANG
Jus Badudu: “Tidak ada bahasa Indonesia standar.”
kadang-kadang orang tambahkan Indonesia, padahal bukan. Dia tidak hanya mengurus bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah dan bahasa asing yang berhubungan dengan bahasa Indonesia.
ALIT AMBARA
Bagi penonton TVRI di akhir 1970an, nama Jus Badudu tentunya tak asing di telinga. Pemerhati dan praktisi bahasa Indonesia yang terlahir dengan nama Sjarief Jus Badudu ini pernah mengasuh acara mingguan Pembinaan Bahasa Indonesia antara 1977-1980. Jus Badudu menghabiskan masa kecil sampai tamat pendidikan menengah dengan berpindah-pindah ke berbagai kota di Sulawesi. Lahir di Gorontalo pada 1926, ia kemudian bersekolah di Poso, Luwuk, Tomohon dan Makassar. Pada 1952, ia pindah ke Bandung untuk kursus B1 Bahasa Indonesia. Setelah itu, ia masuk Fakultas Sastra Universitas Padjajaran dan mendapat gelar kesarjanaan pada 1963. Pendidikan Magister ditempuhnya di Post-Graduate Linguistics Rijksuniversiteit Leiden, Belanda (197173) dan meraih gelar doktor ilmu-ilmu sastra dengan pengkhususan di bidang Linguistik di Universitas Indonesia (1975). Sebagian besar hidup Jus Badudu dicurahkan untuk dunia pendidikan, yakni menjadi guru SD, SMP, dan SLTA selama 23 tahun sejak 1941 sampai 1964. Ia kemudian menjadi dosen di perguruan tinggi selama 26 tahun sejak 1965, dan akhirnya pensiun pada 1991 di umur 65 tahun. Kini, Guru Besar Emeritus Bahasa Indonesia ini memberikan kuliah dan membimbing tesis serta disertasi mahasiswa program S-2 dan S-3 di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Jus Badudu dikenal sebagai penulis buku yang produktif. Sejak 1957, ia telah menulis dan menerbitkan sekitar 50 buku. Buku terakhirnya yang terbit pada 2003 berjudul Kamus Indonesia Serapan Bahasa Asing. Redaktur Media Kerja Budaya B.I. Purwantari mewancarai Jus Badudu, di rumahnya, di Bandung. Di bawah ini petikan hasil wawancara tersebut. Di masa Orde Baru ada banyak kritik ditujukan kepada Pusat Bahasa Nasional karena lembaga ini dianggap terlalu otoriter terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Apa sebenarnya tugas lembaga ini? Apa pendapat Bapak tentang lembaga ini? Saya tidak pernah bekerja di Pusat Bahasa. Saya pada waktu di televisi itu hanya bekerja sama dengan Pusat Bahasa. Jadi, acara itu adalah acara Pusat Bahasa. Sekarang namanya Pusat Bahasa, sudah disingkatkan. Dulu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), malah
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
19
Tugas lembaga ini sebenarnya memperhatikan bahasa, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan bahasa. Selain itu, lembaga ini bertugas meluaskan kata-kata baru yang dipakai orang. Tetapi sayangnya, dia tidak punya alat penyebar untuk temuan-temuannya, seperti brosur untuk kata-kata baru atau majalah. Orang-orang yang bekerja di Pusat Bahasa mengeluh, katanya, “Lebih banyak mengurusi bahasa daerah dari pada bahasa Indonesia.” Memang bahasa daerah itu perlu diangkat, perlu difasihkan, supaya jangan hilang. Itu juga salah satu tugas Pusat Bahasa. Dia betul-betul lembaga pemerintah, tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk memberikan ketentuan-ketentuan. Silakan dia membuat rumusan-rumusan sampai diperlukan, kalau orang merasa perlu. Kalau tidak diperlukan, ya sudah. Apakah Pusat Bahasa juga melakukan standarisasi terhadap bahasa Indonesia? Tidak ada bahasa Indonesia standar. Sebenarnya yang dijadikan standar itu adalah yang sudah tertulis dan sudah terpakai. Dan kalau orang patuh pada aturan yang tertulis berarti mereka mematuhi bahasa standar dan mematuhi bahasa baku. Saya berbicara bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yang aturannya saya ketahui, yang saya pelajari. Apalagi mereka itu adalah suatu lembaga yang berada di bawah Direktorat Kebudayaan, tepatnya kementerian, Direktorat Pusat Bahasa. Jadi, di bawah sekali pada tingkat-tingkat di kementerian. Mereka tidak dapat, misalnya, mengambil tindakan pada ketidakbenaran pada bahasa. Kurang wibawa. Maksud Bapak seharusnya Pusat Bahasa mempunyai wewenang yang lebih besar? Tentunya wewenang besar yang dapat menentukan sesuatu mengenai bahasa, misalkan untuk dipergunakan dalam membuat undang-undang. Kalau ia melihat bahwa bahasanya kurang berkembang, ia bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang membuat undang-undang itu. Tetapi, Pusat Bahasa tidak mempunyai wewenang seperti itu. Kalau begitu standarisasi dalam bahasa Indonesia tidak ada? Tidak ada! Standarisasi itu seharusnya kita menetapkan muatan bahasa yang sudah 20
ditetapkan. Kalau standarisasi, itu berarti dikatakan apa yang kita pelajari dari buku-buku tatabahasa. Standarisasi kata itu berlangsung; kata baru masuk dalam kamus dan ia menjadi baku. Kalau belum masuk dalam kamus, berarti belum baku kata itu. Sedangkan struktur biasanya bertahan dalam tata bahasa. Anda membuat kalimat kan ada objek, predikat, kata keterangan. Begitu-begitu saja terus, tidak ada yang baru. Kecuali misalnya dikatakan: “pakaian yang disimpannya dalam lemari”, atau “lemari yang di dalamnya disimpan pakaian”. Nah, itu bahasa Indonesia. Tetapi sekarang orang menjadikan “lemari di dalam mana disimpan pakaian”. Itu kan pengaruh bahasa asing di dalam mana berasal dari bahasa Inggris wherein, atau bahasa Belanda waar in. Bahasa Indonesia sebetulnya tidak mengenal bentuk seperti itu. Ada beberapa contoh lagi: “buku yang di atasnya”, atau “meja yang di atasnya ada kamus”. Itu bahasa Indonesia, bukan, “meja di atas mana terletak kamus”. Begitu juga dengan “rumah di mana dia tinggal”. Dalam bahasa Indonesia asli kita menggunakan “rumah yang ditinggalinya”, atau “rumah yang didiaminya”. Biasanya, tata bahasa yang tidak sesuai kita tolak, termasuk juga dari bahasa Jawa, misalnya, “kakinya meja”, “atapnya rumah”. Kita anggap tidak baku dan kita tentukan saja “kaki meja”, tidak perlu menggunakan “nya”. Juga, kalimat seperti “Omanya datang”, atau “Rumahnya siapa?”, itu bukan bahasa Indonesia. Jadi, Bapak masih menganggap perlu standarisasi bahasa Indonesia? Bisa saja. Namun, kenyataannya Pusat Bahasa ini tugasnya apa? Kalau sebagai lembaga pemerintah, setaraf dengan apa? Standarisasi itu perlu. Biasanya, standarisasi itu berlangsung tidak lagi secara resmi. Jadi, sebetulnya penulispenulis buku itulah yang menstandarkan bahasa, memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana bahasa Indonesia dipakai, bagaimana bentuknya yang benar. Penulis buku mengenai tata bahasa itu adalah orang-orang yang menstandarisasi bahasa. Seharusnya lembaga seperti Pusat Bahasa yang melakukannya, tetapi mereka harus punya alat, yaitu majalah yang keluar, kalau tidak setiap minggu, sekurangkurangnya satu bulan sekali, seperti dulu media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
Pak Takdir Ali [Sutan Takdir Alisjahbana – red.] dengan majalahnya, Pembina Bahasa Indonesia itu. Tapi dia kan bukan orang pemerintah. Wah, wibawa majalah itu hebat sekali! Ada juga majalah Bahasa dan Budaya yang dikendalikan oleh sebagian lembaga pemerintah, semacam pusat bahasa di Yogyakarta. Ada lagi majalah Medan Bahasa yang diterbitkan pemerintah. Tapi yang paling berwibawa, ya, Pembina Bahasa Indonesia itu. Apa yang ditulis diperhatikan orang. Bagaimana dengan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri? Perkembangan bahasa Indonesia terutama dari segi pertambahan kosa kata, perbendaharaan kata. Kalau dari segi struktur, perkembangannya sangat lambat, hampir tidak ada. Kata-kata baru banyak sekali masuk dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah. Ada yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak mampu menciptakan kata-kata baru dan hanya mampu mengadopsi kata asing. Bagaimana menurut Bapak? Umumnya ada empat macam aturan kalau kita menerima kata baru. Kita terima kata baru dari bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu misalnya. Kalau tidak ada, kita ambil dari bahasa Indonesia yang sudah mati, dari kata-kata lama. Orang tidak sadar kata-kata seperti kelola, pantau, itu bukan kata baru, tetapi kata lama yang diangkat kembali, karena dari dulu ada di dalam kamus. Kalau tidak ada di bahasa Melayu, orang lari ke bahasa daerah, bahasa daerah yang hidup. Kalau tidak ada kata daerah yang hidup, orang akan cari pada bahasa daerah yang lama. Kalau empat hal ini tidak bisa, lalu kata asing itu orang Indonesia-kan. Misalkan, kita pakai kata superior. Itu kan kata asing yang diindonesiakan karena kalau diterjemahkan terlalu panjang. Juga struktur, kita ambil dari bahasa Belanda. Perkembangan kosa kata dalam bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya bahasa seseorang yang dapat mempengaruhi gaya bahasa orang lain. Misalnya, kalau orang sudah pernah membaca bahasa Takdir, ia mengenal gaya Takdir tersendiri; bagaimana dia menyusun kata-kata dalam kalimat sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang senang memakai kata-kata lama seperti Amir Hamzah dulu. Dengan puisinya, ia sering mencari kata-kata Melayu lama karena Amir Hamzah kan orang Sumatra
daerah rawan”, padahal di sana banyak terjadi kejahatan, terdapat pemberontakan, kerusuhan. Bahasa pejabat biasanya menghindari hal yang memalukan pemerintah, misalkan di Timor sekarang ada kelaparan. Pemerintah harus mengatur supaya tidak terjadi kelaparan. Bukankah itu pembohongan? Yah, bagaimana masyarakat menggunakannyalah. Bahasa seperti itu akan mati kalau masyarakat maju. Mereka membutuhkan banyak pengungkapan. Sebelumnya tidak dipakai, lalu mencari ungkapan baru. Kadang-kadang kita anggap sebagai manipulasi bahasa, tetapi dipergunakan dengan sengaja. Mereka berusaha menghindari pengertian yang keras. 0
POKOK
ALIT AMBARA
Timur, orang Langsa, ya. Jadi, orang Melayu bisa berbicara bahasa Melayu. Kata-kata yang dipakai itu kata-kata Melayu lama. Dia mengenal bahasa Melayu, tetapi orang di luar Melayu tidak tahu. Kata-kata yang dipakai Amir Hamzah ini ada yang bisa kita temukan di kamus, ada yang tidak. Bagaimana dengan manipulasi bahasa, seperti yang dipakai oleh kalangan birokrat, misalnya, menyatakan “kenaikan harga” dengan “terjadi penyesuaian harga”? Membuat ungkapan baru untuk menghindari arti yang dianggap merugikan itu adalah manipulasi bahasa. Di tempat-tempat yang minim akan kesehatan, dikatakan sebagai “daerah-
BINCANG-BINCANG
I Gusti Ngurah Oka: “Kalau pembina bahasa dituruti semua keinginannya, maka ia bunuh semua ragam bahasa dan gunakan satu bahasa baku.” I Gusti Ngurah Oka adalah salah satu tenaga ahli yang terlibat dalam perumusan Politik Bahasa Nasional di dekade awal pemerintahan Orde Baru. Berbekal pengetahuan dan pengalaman sebagai dosen bahasa Indonesia di almamaternya, IKIP Malang, ia diminta menangani bidang pengajaran bahasa di Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (P3B) dan Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama paling tidak 10 tahun sejak 1973. Lahir di Denpasar pada 15 Juli 1937, Pak Oka – demikian ia biasa dipanggil – menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Denpasar dan Singaraja sebelum ia memutuskan untuk hijrah ke Jawa pada 1958. Ia lulus dari Jurusan Bahasa Indonesia IKIP Malang pada 1964 dan sejak saat itu memusatkan perhatiannya pada masalah pengembangan pendidikan bahasa. Sebagai asisten pakar pendidikan, Dr. Soepartinah Pakasi (alm.), ia membantu mendirikan SD Laboratorium IKIP POKOK
Malang. Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu dalam mata kuliah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Kuno di University of Michigan, Ann Arbor, Amerika Serikat selama 1972-1973. Di sela-sela kesibukannya mengajar dan bekerja untuk P3B, Pak Oka sempat menulis sejumlah buku dan artikel mengenai pengajaran bahasa Indonesia dan retorika. Sejak pertengahan 1980an ia lebih banyak menghabiskan waktunya mengajar di beberapa kampus di Malang dan kota-kota sekitarnya. Walaupun ia sudah pensiun pada 2001, perhatiannya pada masalah kebahasaan tidak surut. Untuk mengetahui lebih lanjut soal penanganan bahasa nasional di masa Orde Baru, Tim Redaksi MKB mewawancarai Pak Oka di kediamannya di Malang. Kapan P3B didirikan dan mengapa P3B perlu didirikan? P3B itu perlu didirikan untuk menggariskan kebijakan kebahasaan nasional yang akan mengatur pembinaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia. Sebelum P3B didirikan tidak ada badan yang secara
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
formal melakukan kebijakan serupa itu. Tugasnya pertama-tama menggariskan kebijakan nasional yang akan memecahkan masalah kebahasaan di Indonesia. Masalah kebahasaan dibagi tiga, yaitu masalah bahasa nasional atau bahasa Indonesia, masalah bahasa daerah, dan masalah bahasa asing. Masalahmasalahnya, misalnya, pendidikan bahasa, penyebaran bahasa, pengembangan bahasa, pemakaian bahasa, antara lain seperti itu. Apakah ada panduan tertentu bagi P3B dari pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya? Ada. Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 70an, saya jadi sekretarisnya. Keputusan seminar inilah yang kemudian menggariskan pola kebijaksanaan bahasa nasional, sebagai pedoman. Yang datang ke seminar itu bukan hanya orang-orang P3B, tapi juga tokoh-tokoh bahasa di perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dari seluruh Indonesia, pokoknya lengkaplah pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap masalah kebahasaan di Indonesia, termasuk juga Menteri Pendidik-
21
an dan Kebudayaan sebagai sponsornya. Apa prinsip-prinsip utama yang diacu P3B dalam melakukan pembakuan bahasa Indonesia? Dalam pembakuan bahasa, prinsip utamanya adalah pemakaian bahasa yang hidup di masyarakat. Kemudian, pemakaian bahasa di kalangan intelektual, kalangan terpelajar, di dalam karya-karya budaya yang bernilai tinggi. Itulah yang dipakai sebagai pedoman. Maksudnya dibakukan di sini bagaimana? Apakah ada aturan tertentu? Oh, ada. Sudah keluar pedomanpedoman tertentu, seperti misalnya, di dalam penulisan, keluar Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, dalam peristilahan, keluar Pedoman Istilah, di dalam pemakaian makna kata, keluar Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam tata bahasa, keluar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Bagaimana hubungan antara pengembangan bahasa nasional dan pengembangan bahasa daerah? Maksudnya, apakah dalam proses pengembangan bahasa nasional dipertimbangkan juga pentingnya pengembangan bahasa daerah?
22
Pembinaan bahasa nasional itu kan komprehensif. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia saja, bahasa daerah juga, bahasa asing juga. Yang namanya masalah bahasa nasional adalah masalah bahasa di Indonesia yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Jadi ketiga-tiganya ditangani oleh Pusat Bahasa. Termasuk di dalamnya adalah memberi pedoman bagaimana menyerap kata-kata asing. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, apakah ada upaya untuk memelihara segala kekayaan kata, warna, dan ekspresi paling baik dan paling dinamik dari unsur-unsur bahasa maupun logat suku bangsa dan/atau daerah? Atau, yang ditekankan justru penghilangan sifatsifat khusus bahasa daerah dalam bahasa nasional? Tidak, justru sangat dipelihara itu. Cuma, caranya begini, dipersilakan orang berkompetisi memasukkan nilai-nilai bahasa daerah, lewat menulis, lewat berkarya bahasa apa pun. Nanti, yang bernilai tinggi, akan diangkat sebagai milik bahasa nasional. Tidak ada halangan. Sehingga sebenarnya dibuka kompetisi fair antar tiap daerah. Nah, bahwa sekarang masuk bahasa Jawa banyak, ya karena orang Jawanya banyak, orang Jawanya lebih pinter. Sebenarnya semua dipersilakan menulis di koran, menulis di majalah, memasukkan kata-kata daerah. Yang paling banyak frekuensinya diangkat menjadi bahasa Indonesia. Terus, selain kompetisi, apa usaha lain untuk mengintegrasikan bahasa daerah? Yah, kalangan terpelajar dari berbagai daerah diberi kesempatan seluas-luasnya mengusulkan materi bahasa yang
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
belum ada dalam bahasa Indonesia untuk dipertimbangkan di level nasional, apakah itu bisa dipakai atau tidak sebagai peristilahan ilmiah, misalnya. Nanti dicoba disebarkan di pusat, lewat media massa, lewat televisi. Kembali ke soal orang Jawa yang banyak tadi, apakah masyarakat dari suku lain belum punya perhatian yang besar terhadap bahasa Indonesia? Bukan belum punya perhatian besar. Mereka itu kurang berkarya, mengemukakan buah pikirannya, kurang mengemukakan karya-karyanya di media massa. Jadi kan tidak terserap kata-kata daerah itu. Yang banyak menulis itu orang Jawa, sehingga timbul memang suatu gejala kepekaan dari daerah-daerah lain yang selalu mengisukan adanya Jawanisasi dalam bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya semua pihak dipersilakan mengajukan usulan, karena kata-kata, atau hal-hal yang dibakukan, dalam bahasa Indonesia pertimbangannya frekuensi pakai. Katakata mana yang paling banyak dipakai. Bagaimana P3B menyebarluaskan hasil kerja yang dilakukan? Apakah ada kebijakan khusus dari pemerintah yang mengharuskan penggunaan bahan-bahan dari P3B di dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah? Mengharuskan sih tidak, tapi memberikan pedoman iya. Karena dalam pembinaan bahasa, keharusan itu tidak ada. Pedoman-pedoman itu dimasyarakatkan, seperti pedoman ejaan, kamus, tata bahasa baku, pedoman istilah disebarkan. Masalahnya sekarang, masyarakat mau ngga mengikuti pedoman itu? Ada juga penataran untuk guru-guru. Tapi, tetap saja ada kesalahan, ada pelanggaran, tetap juga tidak ditaati. Itulah kesulitan pembinaan bahasa. Bagaimana hubungan P3B dengan media massa? Secara tidak langsung dilakukan, karena redaksi media massa antara lain disarankan mengoreksi bahasa yang akan dikeluarkan media massa. Seperti misalnya, kata-kata daerah yang masuk dalam media massa selalu dicetak miring. Itu hasil-hasil editing dari media massa yang bekerja sama dengan Pusat Bahasa. Selain itu, ada juga semacam penataran untuk para editor. Tapi harus diingat, bahasa surat kabar dengan bahasa pemerintahan itu dua hal yang berbeda.
Apakah ada perbedaan besar antara bahasa Indonesia yang dipakai sebelum dan sesudah pemerintah Orde Baru, terutama dari segi kekayaan wacana dan gaya berbahasa? Oh, sangat banyak perbedaannya, karena bahasa Indonesia ini kan tergolong bahasa yang masih muda. Perkembangannya pesat sekali. Tiap era membentuk ragamnya sendiri. Seperti misalnya, ragam bahasa Indonesia Orde Baru itu sangat kuat Jawanya karena pemerintah pusat mencoba memasukkan konsep-konsep Jawa ke dalam sistem pemerintahan. Akibatnya, kata-kata Jawa banyak sekali. Secara tidak langsung itu menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Sebelum Orde Baru, misalnya, jaman Orde Lama, kata-kata yang membenci imperialisme itu sangat besar. Tapi, perbedaan dalam gaya bahasanya yang paling menonjol. Seperti misalnya, gaya romantis terdapat pada Orde Lama. Gaya metaforik sangat kuat dalam Orde Baru, berputar-putar juga, sehingga makna sebuah ungkapan itu tidak sama dengan makna katanya, harus ditafsirkan dalam konteks, siapa yang bicara dan untuk tujuan apa. Banyak orang yang melihat almarhum Presiden Soekarno mempunyai kemampuan berbahasa yang luar biasa baik dan cerdas. Apa pendapat Anda tentang bahasa yang digunakan Soekarno? Saya kira itu benar, ya, karena Soekarno itu mempunyai retorik yang sangat kuat, retorik untuk mempersuasi pendengarnya, gaya bahasa yang persuasif sekali, terutama untuk lisannya. Dia menggunakan keberulangan ungkapanungkapan, memberi tekanan yang sangat kuat pada kata-kata tertentu sehingga gaya Soekarno itu sudah monumental. Banyak politikus belakangan ini mencoba meniru. Cuma kesulitannya sering menggunakan bahasa Belanda, bahasa asing. Tapi yang dianggap sebagai ahli retorik di Indonesia, retorik aplikatif, ya Soekarno itu. Dia sudah punya paten sendiri sehingga ada gaya bahasa Soekarno kalau dari segi bahasa. Cepat sekali bisa diidentifikasi kalau ada orang yang meniru “Ah, itu kayak Soekarno!” Kalau dibandingkan dengan gaya berdakwah bagaimana? Sangat lain gaya dakwah dengan gaya Soekarno itu. Gaya dakwah itu kan seperti
POKOK
menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti dengan menjanjikan sesuatu setelah mati. Sedangkan gaya Soekarno itu membuat orang itu menjadi besar, merasa diri berharga, merasa diri hebat. Jadi, walaupun rakyat waktu itu miskin, kalau Soekarno sudah ngomong, bisa merasa kaya, bisa merasa hebat. Itu kan retorik saja. Ada pihak yang beranggapan bahwa bahasa hanyalah sekedar instrumen untuk menyampaikan gagasan, tapi ada pula yang berpendapat bahasa tidak bisa dipisahkan dari perubahan struktur sosial. Bagaimana menurut Anda? Kedua-duanya benar. Sebagai alat, ya, tapi alat apa? Alat untuk mewadahi, mengungkapkan, memetakan, menyimbolkan, mewakili sesuatu yang ingin dikomunikasikan? Sedangkan bahasa sebagai struktur, oh, itu sudah lama diungkapkan bangsa Melayu, “Bahasa menunjukkan bangsa”. Jadi, struktur kebudayaan, struktur nilai suatu bangsa, tampak pada bahasa. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat bagi perkembangan bahasa? Bagaimana mengatasinya? Yang paling kuat saya lihat adalah sikap terhadap bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia boleh dikatakan belum positif. Sikap positif itu kalau orang menghormati bahasa itu, kalau orang bersedia menggunakan bahasa itu, kalau orang bangga menggunakan bahasa itu, kalau orang prihatin terhadap bahasa itu. Ini yang sangat lemah di Indonesia sehingga sikap bahasa yang positif ke bahasa asing. Bahasa Indonesia dianggap tidak berharga, tidak patut dibanggakan, ini yang merupakan hambatan utama. Itu juga saya kira karena kesalahan pemerintah tidak memberikan himbauan, atau memberikan ganjaran kepada pemakai bahasa Indonesia yang baik dan tidak mendukung yang menggunakan bahasa Indonesia yang jelek. Seperti misalnya, kalau seseorang mencari pegawai, bukan penguasaan bahasa Indonesianya yang diperiksa, tapi penguasaan bahasa Inggrisnya. Kalau orang ingin naik pangkat, mestinya kan penguasaan bahasa Indonesianya dipertimbangkan, sehingga orang mau belajar bahasa Indonesia. Selain itu, saya kira karena masalah ekonomi. Dana untuk pembinaan bahasa itu sangat kecil dan SDM tidak tertarik terjun ke bidang itu.
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
POKOK
Ada hambatan politiknya juga. Yang dinamakan Pusat Bahasa itu kan saya kira semacam bendera saja yang diadakan supaya ada begitu, kelengkapan saja, tapi ngga pernah diberikan fasilitas yang memadai. Apakah ada nilai-nilai tertentu yang patut ditanamkan dalam pengajaran bahasa, baik bahasa nasional maupun bahasa daerah? Ya, ada. Kan selalu orang kembali pada Sumpah Pemuda dan nyanyian Satu Nusa Satu Bangsa itu, lalu nilai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai nilai formal sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya. Itu nilai-nilai yang sebenarnya merupakan das solen, yang das sein-nya jarang dilakukan. Dengan semakin terbukanya media massa Indonesia muncul gaya berbahasa yang campur baur antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahasa resmi dan bahasa “gaul”, di berbagai medium komunikasi, terutama di acara-acara televisi. Apa pendapat Anda tentang gaya bahasa seperti ini? Apakah itu menunjukkan semakin demokratisnya bahasa Indonesia, atau justru sebaliknya, semakin miskin? Televisi itu media komunikasi massa yang melayani banyak kepentingan. Jadi, ada kepentingan formal, kepentingan bisnis, kepentingan politik. Dia harus bisa melayani dengan baik, menyediakan media untuk masing-masing kepentingan itu. Lalu, mereka yang di bidang institusi resmi, menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia resmi. Seperti misalnya, pidato kenegaraan, ceramah-ceramah atau informasi yang disampaikan oleh seorang pejabat menteri misalnya, mesti bahasa Indonesia yang resmi, bahasa Indonesia yang baku, tidak akan menggunakan terlalu banyak campur-campur. Sekarang, kepentingan bisnis yang menggunakan bahasa. Bisnis yang bisa menarik keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang ada juga kalangan generasi muda. TV itu akan menarik kalau mereka diberi kesempatan untuk berbahasa seperti kelompok mereka. Jadi sulit sekali diatur televisi, misalnya harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Konyol nanti itu, ndak laku nanti TV itu, karena TV melayani kepentingan banyak pihak. Sehingga fakta menunjukkan TVRI kurang
23
laku karena tidak disukai oleh generasi muda, oleh kalangan bisnis, itulah fakta. Jadi, sekali lagi, TV tak bisa diatur seperti itu. Gaya bahasa seperti contohnya: “Sebetulnya kalau cuma ngomong sih kita fine-fine aja” itu kan bahasa gaul. Itu bagus untuk sinetron, untuk anak-anak muda, atau pejabat yang sedang santai. “Kita sudah di-recommend untuk jalanin kerjaan yang ada dulu”, jelas ini bahasa generasi muda Jakarta sekarang. Ngga apa-apa, wajar-wajar saja. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia di masa Orba sangat memungkinkan terjadinya miskomunikasi karena cenderung bermakna ganda, membingungkan, dan penuh tata krama. Di wilayah politik terutama, banyak sekali konsep-konsep abstrak, seperti “demokrasi”, “partisipasi rakyat”, yang tidak pernah dijabarkan dengan baik. Bagaimana menurut Anda? Di masa Orba terjadi miskomunikasi, bermakna begitu. Barangkali ada kesalahan antara harapan dan fakta, ya? Orba harus dipahami sebagai kebudayaan Jawa. Budaya Jawa itu berlapis lapis, tidak langsung. Yang bisa memahami, yang bisa berkomunikasi dengan baik, ya, yang persepsi budaya Jawanya bagus. Jadi antara Soeharto dengan kelompoknya itu tidak akan ada miskomunikasi, karena mereka itu sudah biasa berputar dahulu atau secara tidak langsung menyampaikan apa yang mereka maksudkan sebenarnya. Bagi yang non-Jawa, ya, agak sulit itu, bermakna ganda, membingungkan. Itu sering tidak berani diungkapkan. Di dalam budaya Orba itu Jawanisasi. Orang harus bisa menangkap yang tersirat, yang tersorot, bukan hanya yang tersurat saja. Malahan dari segi seni berbahasa, itu sangat tinggi, karena selalu diungkapkan secara tidak langsung. Bagi mereka yang bukan orang Jawa, wong Jawa itu dianggap membingungkan, bermakna ganda. Karena suatu kata dalam konteks Jawa itu bisa macammacam artinya. Demokrasi bisa berarti kekuasaan pejabat. Partisipasi rakyat bisa berarti partisipasi anaknya pejabat. Itu kontekstual sekali. Ndak bisa dicari di kamus itu. Itu memang salah satu perkembangan bahasa di dalam perjalanan sejarah. Dalam kondisi sosial politik yang kacaubalau dewasa ini, apakah bahasa Indonesia masih punya peran yang signifikan? Apakah bahasa Indonesia masih punya
24
daya membebaskan dan mempersatukan berbagai kekuatan politik dan suku bangsa yang ada di negeri ini, seperti yang dicita-citakan para pendiri republik? Saya kira itu jelas, karena suatu bangsa yang mempunyai bahasa, betapa pun brengseknya keadaannya, dalam sejarahnya selalu signifikan. Bahasa itulah sebagai penanda eksistensi bangsa itu. Nah sekarang, bangsa Indonesia salah satu ciri keindonesiaannya itu bahasa Indonesia, yang bisa mempersatukan semua etnik di Indonesia, bisa memberikan pembebasan-pembebasan di dalam berkomunikasi antar etnik. Cuma sekarang, karena bahasa Indonesia masih merupakan bahasa kedua, masing-masing masih menafsirkan dengan konsep bahasa pertama. Sering terjadi salah paham. Masih sulit dikatakan mempersatukan. Tetapi, sebagai suatu sarana nasional pasti itu sangat diperlukan. Itulah dahulu sejarahnya kenapa bahasa Indonesia itu dipakai oleh generasi pendiri bangsa itu. Jadi secara kenyataan, misalnya, kita lihat signifikansi bahasa Indonesia itu kalau kita sudah pergi ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan bahasa Indonesia-lah kita membuat diri seperti orang Indonesia. Mengapa perlu dibuat kebijakan nasional untuk pembinaan dan pengembangan bahasa? Untuk apa kebijakan nasional itu? Namanya saja kebijakan nasional. Itu karena bahasa ini selalu berkembang dan selalu berubah, maka dikhawatirkan terjadi perubahan yang divergen. Seperti misalnya, pecahnya bahasa Melayu menjadi bahasa Melayu, Brunei, Malaysia, itu perkembangan yang divergen. Supaya bahasa di Indonesia ini tetap bahasa Indonesia, maka dibuatlah kebijakan nasional sehingga perkembangannya itu konvergen. Nah, itu salah satu latar belakang filosofisnya. Terus kemudian, latar belakang praktisnya, menghadapi berbagai ragam bahasa Indonesia yang berada di bumi Indonesia begitu luasnya; ada ragam lokal, ada ragam etnik, ada ragam profesional, macam-macam ragam, sekarang diperlukan satu ragam baku. Sebagai rujukan, ya, sebagai tolok ukur. Setidak-tidaknya bisa ditemukan sesuatu yang bisa dipakai untuk menentukan benar-salah. Itu kebijakan nasional bahasa. Bisa mengatur bahasa itu. Apakah itu akan menjadi suatu yang satu bahasa media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
atau tidak itu soal lain. Ini sebenarnya meniru Perancis, Academie Francais. Nah itu sebuah akademi yang membina bahasa Perancis sehingga ada satu pedoman yang bisa ditoleh bersama. Contoh yang riil adalah perlunya kebijaksanaan bahasa nasional untuk EYD. Ejaan Yang Disempurnakan itu sudah diikuti keputusan kebijaksanaan nasional. Begitu juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku. Itu hasil kebijaksanaan nasional. Bagaimana realisasinya di masyarakat itu kan ada prakteknya. Masing-masing orang punya disiplin. Sehubungan dengan itu, sekaligus menjawab sangat perlu pembakuan bahasa. Setidak-tidaknya ada yang dilihat, dibayangkan adanya bahasa Indonesia baku. Untuk menentukan salah-benar, bukan baik-buruk lho, salah dan benar secara kebahasaan. Baik-buruk itu masalah lain lagi di dalam berbahasa. Karena baik-buruk itu tergantung pada siapa yang diajak omong, tentang apa, dalam situasi apa. Kalau bahasa baku, itu soal benar-salah. Yang penting itu ada pembakuan dalam bahasa resmi, bahasa birokrasi, kemudian dalam sekolah. Kalau sekolah tidak punya bahasa baku, ya repot, apa yang mau diajarkan? Itu perlunya pembakuan bahasa. Mengapa perlu ada pembakuan bahasa? Ada penelitian tentang bahasa Indonesia Tionghoa yang mengatakan bahwa bahasa kelompok khusus seperti ini malah perlu dilestarikan. Bagaimana menurut Anda? Bahwa bahasa Indo-Tionghoa itu perlu dilestarikan, ya itu mesti saja toh. Kalau itu dihilangkan, ya Indo-Tionghoanya hilang juga. Penanda atau indikator keberadaan Indo-Tionghoa adalah bahasa Indo-Tionghoa. Kalau ingin mempertahankannya sebagai kelompok, bahasanya harus dipertahankan. Sama saja misalnya dengan kelompokkelompok lain. Itu kan pandangan seorang linguis, bukan pandangan seorang pembina bahasa. Kalau pembina bahasa dituruti semua keinginannya, maka ia bunuh semua ragam bahasa dan gunakan satu bahasa baku. Ya itu tidak mungkin toh, karena bahasa itu konvensi. Tiap kelompok mempunyai konvensinya masing-masing. Tapi ada satu pedoman pokok yang diacu yang disebut bahasa baku, dan siapa yang mengurusi bahasa baku itu, ya kebijakan nasional itu. 0
ULASAN
Memplesetkan Bahasa, Memplesetkan Bangsa
Alia Swastika Plesetan bukanlah sekadar humor atau bahan lawakan. Ia adalah sisi lain dari politik negara terhadap bahasa nasional yang telah begitu lama menjelajah dalam kehidupan sehari-hari warga biasa. Dalam plesetan, kita akan menemukan cara pandang rakyat biasa terhadap persoalan sosial politik di sekitarnya, yang mereka ungkapkan dalam bentuk permainan bahasa. Tulisan ini akan mengambil kasus bagaimana masyarakat Yogyakarta, dan mungkin akan melebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, memposisikan plesetan sebagai permainan bahasa yang punya makna politis dan kebudayaan tertentu. Sebuah resistensi terhadap bahasa Indonesia—dalam kasus ini, juga terhadap bahasa Indonesia ala Jakarta—yang harus mereka lahap sehari-hari di sekolah, di kantor-kantor, dan dalam artikel-artikel di media massa. Segala hal yang berbau plesetan pernah sangat populer pada pertengahan 1990an, tahun-tahun ketika isu politik— khususnya isu tentang suksesi—mulai memanas, tahun-tahun menjelang jatuhnya rezim totaliter. Beberapa tayangan humor dan lawak yang ditayangkan di televisi tak lagi mengandalkan slapstick, melainkan mulai menggunakan gaya plesetan. Pada saat itu, tentu saja yang banyak menjadi sasaran plesetan adalah isu-isu politik, meski ini dilakukan dengan begitu kabur dan diam-diam. Dalam plesetan inilah kita dapat menemui ungkapan ketidakpuasan dan frustasi masyarakat terhadap kekuasaan yang sifatnya sangat kontekstual. Yogyakarta dan Kecenderungan Plesetan Di Yogyakarta, plesetan bukanlah sesuatu yang baru. Permainan bahasa ini sudah diakrabi masyarakat sejak mereka masih kecil. Sangat sulit untuk dapat menyebutkan kurun waktu, karena seperti biasanya, tak banyak data-data yang bisa digali untuk melihat sejak kapan permainan bahasa ini muncul dalam tradisi masyarakat Jawa. Yang jelas, generasi pelawak asal Yogyakarta yang kini telah berusia senja, masih saja fasih melontarkan plesetan dalam dialog-dialog mereka. Begitu juga anak-anak kelas lima SD yang mulai menggunakan plesetan sebagai cara baru untuk menjalin ikatan pertemanan yang lebih luas dan lebih akrab. Plesetan selalu menjadi cara masyarakat menciptakan suasana yang penuh tawa, sejenak melepaskan mereka dari tekanan hidup sehari-hari. Bahkan sampai kini, ketika Yogyakarta sudah semakin dipadati mahasiswa dari luar daerah, plesetan masih bertahan di sela gempuran bahasa Indonesia ala Jakarta yang nyaris terdengar setiap hari di radio-radio. Malah menariknya, mahasiswa “pendatang” ini memerlukan kemampuan untuk bisa bermain plesetan agar dapat diterima di kalangan mahasiswa “tuan rumah”. Tanpa mengetahui arti kata-kata yang terlontar selama
permainan plesetan berlangsung, seseorang tidak akan dapat masuk ke dalam suasana akrab yang tercipta pada waktu itu. Di sini terlihat bahwa seiring dengan perkembangan berbagai pola interaksi antar-warga, kemahiran dalam permainan bunyi kemudian menjadi salah satu modal yang penting bagi masyarakat Jawa dan para pendatang untuk tetap menjaga kedekatan dan keakraban satu sama lain. Beberapa orang pengamat linguistik meyakini bahwa kemahiran orang Yogya bermain plesetan ini disebabkan karena budaya mereka yang senang berdebat, senang tampil unik (berbeda dibandingkan yang lain), juga kesenangan masyarakat untuk mengobrol dan melepas humor. Di Yogyakarta, kebiasaan bersantai dengan lingkungan sepergaulan diwujudkan dengan kegiatan kumpul-kumpul sambil berbincangbincang tentang banyak hal (dalam istilah Jawa, ngobrol ngalor ngidul). Dari situlah kemudian muncul dialog yang beragam, cara menyampaikan ujaran-ujaran yang beragam, sampai lahir plesetan. Selain itu, ada karakter khas yang selama ini selalu dilekatkan pada orang Jawa yang agaknya turut mempengaruhi kebiasaan plesetan mereka. Orang Jawa dianggap tidak konfrontatif, tidak suka berterus terang, dan menjaga harmoni. Jika tidak setuju atau tidak suka akan sesuatu, orang Jawa cenderung menyampaikannya dengan bahasa yang halus untuk menghindari perseteruan dan rusaknya harmoni. Karenanya, kritik kemudian disampaikan dengan kemasan lain, yang diharapkan tidak membuat pihak yang dikritik tersinggung. Humor adalah salah satu bentuk yang dianggap paling efektif. Bagi orang Jawa, permainan bahasa menjadi salah satu cara wong cilik menyikapi zaman Edan—suatu zaman yang diramalkan oleh pujangga Ronggowarsito ketika keteraturan, norma-norma, keamanan, atau harapan mengalami gangguan dan mungkin melenyap. Permainan ini diwujudkan dengan melakukan othak-athik kata-kata sehingga gathuk (cocok). Plesetan dan Bahasa yang Militeristik Ketimbang merunut kedekatan masyarakat sehari-hari dengan plesetan, tampaknya lebih mudah menelusuri sejarah keterlibatan plesetan di panggung-panggung dagelan rakyat. Mbah Guno, seorang seniman senior di Yogyakarta, melihat bahwa di panggung hiburan, plesetan sebagai bahan dagelan muncul dari kebiasaan guyon (bercanda) dan ngomong waton (berbicara seenaknya) di grup musik milik Kodam Diponegoro, “Tunas Kasih”, yang populer di 1970an. Baru setelah itu, plesetan ini menjadi permainan bahasa yang populer di kalangan seniman Yogyakarta. Dari sumber ini, penulis melihat bahwa kebiasaan yang tidak disiplin dan melenceng dari ketertiban berbahasa pada umumnya justru muncul dalam sebuah institusi yang dikenal memegang teguh
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
25
kedisiplinan, mengindoktrinasi anggotaanggotanya untuk menjadi sosok-sosok yang tertib, tegas, dan tampil angker. Disiplin militer dalam kehidupan sehari-hari ini tampak juga dalam bahasa. Kata-kata semacam “Hormat, grak!” atau “Siap!” selalu diucapkan dengan sikap tubuh tertentu yang menunjukkan kedisiplinan dan kesigapan. Bahasa yang hidup dalam barak-barak militer adalah bahasa yang tertata, tegas dan—menurut pengamatan penulis—‘patuh’ terhadap atasan (yang karenanya menjadi mapan dan tidak terbuka). Kepenatan dan frustasi menghadapi tata-tertib bahasa semacam itulah yang memunculkan perlawanan dalam bentuk permainan kata, meskipun saat itu hanya ditampilkan terbatas pada panggung hiburan. Plesetan selalu mencoba mengusik kata-kata yang sudah terlanjur mapan, atau bahkan dengan terang-terangan menjadikan hal-hal yang berkesan serius menjadi lelucon. Misalnya saja, di Yogyakarta ada kelompok lawak yang menamakan dirinya LBH. Kalau dalam pengertian umum, LBH adalah singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum, bagi kelompok ini LBH menjadi kependekan dari Lembaga Bantuan Humor. Saat kelompok ini mengisi acara HUT TVRI Yogyakarta yang diselenggarakan di Monumen Yogya Kembali (Monjali), mereka memelesetkan slogan TVRI yang berbunyi: “TVRI Menjalin Persatuan dan Kesatuan” menjadi: “TVRI Monjali Persatuan dan Kesatuan”. Dalam percakapan sehari-hari di kalangan mahasiswa, misalnya, penulis mendapati istilah-istilah semacam DOM (Daerah Operasi Militer)”, polisi, ataupun Primus biasa digunakan dalam percakapan antar-kawan dengan memberikan makna baru untuk kata-kata itu yang bermaksud menyindir makna aslinya. Kata DOM mereka gunakan untuk menyebut tindakan yang kejam atau untuk menyampaikan 26
ancaman (“Kalau kamu terus membantah, ku-DOM kamu nanti!”). Singkatan ini mereka pakai ketika keadaan di Aceh mulai memanas, dan pemerintah berencana menetapkan wilayah tersebut sebagai Daerah Operasi Militer (sebuah tindakan yang mereka bayangkan bisa melahirkan tragedi kemanusiaan atau pembunuhan massal). Sementara polisi mereka plesetkan menjadi akronim dari “Pokoknya Lihat Situasi”, karena menurut mereka, polisi, terutama polisi lalu lintas, selalu berusaha mendapatkan uang tambahan dengan mencari-cari kesalahan para pengendara sepeda motor. Sedangkan Primus sesungguhnya adalah nama seorang aktor idola remaja berwajah tampan. Dalam guyonan sehari-hari, Primus menjadi akronim dari “Pria Mushola”, sebuah identitas yang dilekatkan pada remaja-remaja pria yang alim. Dari contoh-contoh di atas kita mendapati bahwa orang-orang yang terbiasa melakukan plesetan harus punya modal pengetahuan yang luas dan mengikuti perkembangan wacana yang beredar di kalangan masyarakat umum. Jika masih menggunakan isu lama yang tidak lagi populer, plesetan yang dilontarkannya akan dianggap ketinggalan zaman. Di sini tampak bagaimana plesetan menjadi representasi respons masyarakat awam terhadap isu-isu sosial-politik-kebudayaan yang kompleks yang sifatnya aktual. Dagadu dan Basa Walikan Pada 1994, di Yogyakarta muncul fenomena baru dalam hal plesetan. Sekelompok mahasiswa UGM mendirikan perusahaan kaus oblong kecil-kecilan yang mereka tawarkan sebagai cinderamata alternatif dari Yogyakarta. Oblong yang mereka produksi kemudian dinamai “Dagadu” dengan logo mata. Kata dagadu sebenarnya adalah makian khas masyarakat Yogya yang berarti ma-ta-mu. Rumus mengganti kata matamu dengan dagadu adalah rumus basa walikan—salah satu variasi plesetan khas Yogyakarta. Bagi orang luar Yogya, untuk dapat mengerti basa walikan ini tidak cukup dengan mengerti bahasa Jawa saja, melainkan ia harus menguasai 20 karakter dasar huruf Jawa. Seperti halnya permainan bahasa yang lainnya, basa walikan ini adalah perayaan kelas bawah terhadap identitas mereka. Lewat bahasa mereka mengukuhkan keberadaan mereka—karena di luar wilayah itu, mereka tidak pernah diakui media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
keberadaannya. Mereka menggenggam sesuatu yang benar-benar mereka miliki, dan keluar dari disiplin-disiplin yang dibangun kelas yang lebih mapan. Dahulu, basa walikan menjadi bahasa yang digunakan preman-preman untuk melakukan komunikasi antar mereka dan menyampaikan informasi-informasi penting yang tidak boleh diketahui pihak lain, demi melindungi mereka dari para penegak hukum. Karenanya bahasa ini sering juga disebut basa maling (bahasa pencuri), basa sacilad (bahasa bajingan) atau basa gali (bahasa preman). Meski ada banyak desakan dan bahkan pemusnahan yang dilakukan aparat terhadap preman, salah satunya peristiwa Penembakan Misterius pada 1983, bahasa yang mereka gunakan ini justru terus berkembang dan meluas. Masyarakat awam mulai mengambil bahasa ini untuk mencari nuansa yang lain, untuk menemukan cara yang berbeda dalam menyampaikan kritik dan ekspresi perasaan mereka. Basa walikan tiba-tiba menjadi bahasa yang enak saja digunakan dalam kehidupan seharihari dengan lingkungan yang sudah diakrabi. Dan keputusan menjadikan “Dagadu” merek kaus oblong ternyata menjadi satu politik berbahasa tersendiri yang mengangkat citra bahasa kelas bawah ini menjadi bahasa yang bisa masuk ke pusat perbelanjaan ber-AC, atau melekat pada punggung orang-orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Semenjak popularitas kaus oblong Dagadu meningkat, banyak orang yang awalnya tidak memahami basa walikan jadi tertarik untuk bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Plesetan, termasuk juga basa walikan, memang akhirnya menjadi komoditi. Ia hadir dalam budaya massa yang lebih luas, dan menjadi ikon dalam budaya pop khas Yogyakarta. Panggung-panggung lawak di Yogyakarta selalu digarap dengan konsep plesetan, diberi tajuk acara yang berbau plesetan, misalnya, “Gerr satu kita teguh, Gerr cerai kita runtuh”. Beberapa kelompok musik menggunakan basa walikan dalam syair lagu-lagu mereka, misalnya salah satu grup beraliran rap menciptakan lagu berjudul “Pabu Sacilat” (Asu Bajingan). Selain Dagadu, muncul pula beberapa perusahaan kaus oblong yang menggunakan formula yang sama. Warung-warung makan di pinggir jalan menggunakan formula plesetan yang terasa ‘mengejek’ halhal yang lebih mapan (“Kentuku Fried Chicken”, atau “Kenchick” [dibalik
chicken]). Bahasa yang lahir dari kelompok bawah ini justru mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan bahasa Jawa yang adiluhung. Buktinya, bahasa Jawa yang dikatakan sebagai budaya tinggi itu kini justru ditinggalkan, dilupakan, dan cuma menjadi rujukan sejarah. Resistensi dan Eksistensi Apakah kemunculan bahasa pinggiran ke kalangan yang lebih luas pada akhirnya menghilangkan nilai-nilai awal yang melahirkan bahasa ini? Jawabannya bisa jadi ya, jika kita hanya melihat persoalan ini dari satu sudut pandang. Bahasa menjadi alat untuk mengkomunikasikan maknamakna tertentu dalam lingkup masyarakat yang tercakup dalam sebuah konvensi sosial tentang simbol-simbol verbal. Makna itu tentu saja hilang saat bahasa yang digunakan oleh satu kelompok tertentu diadopsi dan digunakan oleh kelompok lain. Namun dengan menggunakan sudut pandang yang lain, kita bisa melihat bahwa bahasa (pinggiran) sebagai resistensi akan selalu hidup selama ada kelompok yang melakukan hegemoni dan menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Jadi, meskipun ia berada di dalam wilayah budaya populer yang penuh dengan eksploitasi kaum kapitalis sekali pun, bahasa-bahasa pinggiran ini menunjukkan perlawanan terhadap sesuatu. Entah kebosanan mereka akan kehidupan yang semakin sulit dan menekan, harapan-harapan yang semakin sukar diwujudkan, ataupun hilangnya ruang-ruang bagi mereka untuk berinteraksi dengan hangat. Bahasa menjadi cara bagi orang biasa untuk menunjukkan eksistensinya dalam pelbagai perangkat aturan yang ditetapkan kelompok penguasa. Semakin bahasa di-disiplinkan, akan semakin besar kemungkinan adanya resistensi terhadap pendisiplinan itu. 0 Bahan Bacaan: Latif, Yudi dan Ibrahim, Idy Subandi. Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru. (Bandung: Mizan, 1996) Majalah Balairung, “Membaca Ekspresi Yogya”, edisi 30/th. XIV/1999 Majalah PRISMA, No. 1, 1996 Wijana, I Dewa Putu. Wacana Dagadu, Permainan Bahasa, dan Ilmu Bahasa. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2003
Alia Swastika, editor KUNCI Cultural Studies Center
POKOK
POKOK
ULASAN
Catatan Kecil
Budaya dan Olahraga Bahasa Sport Tidak Sportif in memoriam Njoto, penasihat PSSI
Hersri Setiawan Dunia “sport” dengan dunia “budaya” dalam arti sempit, lebih sempit lagi bahkan dunia “seni”, sungguhnya memang berbatasan tipis saja. Ketika masih di dalam “jaman Lekra” dulu, tentu saja di “daerahku sendiri” Yogyakarta dan Jawa Tengah (di daerah lain tentu saja aku tidak tahu!), kami sering dihadapkan pada pertanyaan yang sulit dijawab, misalnya, pencak silat itu termasuk olah raga murni atau seni olah raga? Kalau olah raga murni, mengapa sering disebut sebagai “seni bela diri”? Juga karate, yang jelas-jemelas adukuat (katakanlah kuatnya tenaga dalam). Mengapa di atas pintu tempat latihannya dipasang papan bertuliskan: Seni Bela Diri Karate, Yudo, Yuyitsu? Begitu juga permainan kartu “bridge” dan permainan catur, olah raga otak — otak kok berolah raga? — atau salah satu cabang seni dalam ilmu? Bisa saja orang menjawab — ya, “bisa saja”! Maka dicobanya memisah antara “art” (seni) dari “ars” (kiat). Apakah ini bukan soal dimensi nuansa saja? Dahulu kala, konon kata sahibulhikayat, tatkala “olimpiade” pertama diselenggarakan di Yunani tahun 776 SM, tontonannya hanya satu saja, yaitu lomba lari sepanjang satu arah di dalam stadion, namanya dromos (lihatlah Chamber’s Twentieth Century Dictionary). Puluhan tahun kemudian, 724 SM, selain lomba tunggal itu ditambah lagi dengan “dromos bolakbalik”, namanya diaulos — konon sekitar sama panjang dengan lomba lari 400 meter sekarang. Empat tahun kemudian (olimpiade itu diadakan sekali tiap 4 tahun) ditambah lagi dengan dolichos, lomba lari jauh, kira-kira sama dengan 1.500 meter atau bahkan sampai 5.000 meter sekarang. Tahun 708 SM ditambah lagi dengan acara adu gulat dan pancalomba. “Seni adu gulat” tentu saja sejenis “seni pencak silat” pada kita, karena janganlah
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
lupa bahwa peradaban Yunani dan Romawi Kuno selain ditandai dengan pengembangan seni murni dan filsafat, juga pengembangan ilmu-ilmu kiat “jaya kawijayan”. Melatih uletnya kulit kerasnya ulang, menjadikan diri menjadi jawara yang “dugdeng”. Maka, dalam nomor-nomor pancalomba pertama itu pun terdiri dari lompat jauh, lempar tombak atau lembing, lempar cakra(m), jalan cepat, dan adu gulat. Aku teringat pada seorang Jawa yang “komunis dari sononya”, juga penulis Jawa baik gancaran maupun geguritan yang sangat subur, dan anggota pimpinan Lekra cabang Yogya. Ia bernama Darsono alias Mbah Dar alias Pak Ireng alias Ki Wungkul alias Pakdhe Dar, yang juga seorang pendekar dan guru pencak silat “Wetan Kali”, yaitu daerah Yogyakarta sebelah timur aliran Kali Code. Suatu hari akhir 50an di rumahnya di kampung Nyutran, berkata kepadaku: “Aku masih mampu (keconggah) lho, Nak, kalau kepepet mencelat naik ke bubungan, seperti yang ‘Nak kenal dari cerita-cerita silat itu!” Ujung jarinya menunjuk ke atas. Sampai olimpiade ke-77 (472 SM) semua pertandingan berlangsung dalam satu hari. Belakangan kemudian diperpanjang menjadi empat hari, dan malah di tambah satu hari lagi untuk upacara penutupan, pemberian hadiah, dan jamuan pesta bagi para pemenang. Sampai saat ini perempuan tidak boleh hadir, apalagi ikut bertanding, selain pendeta perempuan, Demeter, itu pun hadir sebagai penonton. Selain hanya laki-laki, semula peserta olimpiade juga terbatas untuk orang Yunani merdeka (dalam arti bukan budak), termasuk yang lahir di kawasan taklukannya. Para peserta lomba adalah atlet-atlet amatir, dalam arti hadiahnya “cuma” karangan bunga. Kemudian demi perolehan prestasi, sifat profesionalisme lalu menjadi menonjol. Para olah ragawan caloncalon peserta olimpiade lalu hidup-mati dari berolah raga (barangkali bisa dibandingkan dengan yang disebut “pekerja 27
olah raga” di negeri-negeri (pernah) sosialis seperti Uni Soviet dan RRT. Atlet menjadi lapangan kerja khusus, yang menuntut “pengabdian” penuh seperti halnya lapangan kerja yang lain-lain, bukan sekedar lapangan bersantai pengisi waktu kosong. Pada saat inilah sejarah profesionalisme di bidang olah raga bermula. Sementara itu, di jaman Yunani baheula ini ada upacara keagamaan yang berlangsung di kota Delphi, dipersembahkan bagi pendeta perempuan Apollo bernama Pythia, yang pernah mewartakan dakwahdakwahnya di kota ini (lihat kamus di atas). Dalam upacara ini juga disertai dengan lomba olah raga, delapan tahun sekali dan kemudian menjadi empat tahun sekali (sejak 582 SM), pada tahun ketiga sesudah setiap olimpiade tersebut di atas. Namun kekhususan “Olimpiade Phytia”, di sini dimasukkan lomba acara yang non-olah raga. Misalnya, mulailah masuk dalam olimpiade versi Pythia ini lomba menyanyi, memainkan alat musik, dan berdeklamasi. Hadiah bagi para jawara berupa mahkota daun salam — daun perdamaian! Sekarang olimpiade modern abad kita, konon sudah sejak empat olimpiade terakhir, IOC (Panitia Olimpiade Sedunia) telah mengembalikan peristiwa pesta olah raga ini pada “khitah” olimpiade Phytia: memasukkan nomor-nomor budaya dan seni khususnya dalam acara, walaupun tidak semuanya dipertandingkan, melainkan “sekedar” dipamerkan — misalnya dalam hal benda-benda bersejarah, adatistiadat, penerbitan buku, dsb. Perihal yang patut disambut oleh Indonesia, yang untuk ini tidak ada kata “terlambat”. Tidak hanya mengirim olah ragawan untuk memburu medali. Tapi juga mengirim “pelangi budaya” sebagai titian Dewi Perdamaian antar-manusia sesama. Semoga! Dalam hubungan dengan tulisan singkat di atas itulah, aku lalu tertarik memperhatikan “dunia kebahasaan” dalam tulisan-tulisan tentang “dunia keolah ragaan”, baik yang berupa sekedar berita liputan peristiwa atau pun yang berupa komentar atau analisis jalannya peristiwa, atau peristiwanya itu sendiri. Tidak seorang bisa membantah sumbangan besar pers terhadap perkembangan bahasa — pada bangsa mana pun. Sumbangannya itu tidak saja di bidang penggunaan bahasa, atau dalam hal berbahasa secara efisien, tapi juga dalam hal penciptaan peristilahan baru. Tentu saja ada akibat ikutannya yang tidak positif, yang di satu 28
pihak bisa menjurus menjadi merusak bahasa dan di lain pihak bahkan merusak citra pers itu sendiri. Timbulnya apa yang disebut “koran got” atau “pers kuning”, juga terjadi dalam sejarah pers bangsa mana saja, bukan saja disebabkan oleh materi atau isi pesan yang (pinjam ungkapan Njoto) menggunakan adagium “anjing menggigit manusia” bukanlah berita, tapi sebaliknya “manusia menggigit anjing” itulah berita. Tapi selain oleh materi beritanya, juga oleh cara bagaimana berita itu disampaikan. Dalam hal ini tentu saja berarti, bagaimana si wartawan “memainkan” perbendaharaan katanya, sehingga ia berhasil menyajikan sebuah berita yang “mencekam” calon pembacanya. Contoh sangat banyak, dari yang masih tetap “dingin”, walaupun menyentak, sampai kepada yang terasa “panas” sensasional. Misalnya kalimat-kalimat begini: “Pangdam tanda tangani …” tidak usah “menandatangani”; atau: “toko Mas Jaya ludes disikat …” bukannya “toko Mas Jaya bius dicuri …” dsb., dll. Suatu ketika dalam paroh pertama tahun 60an di Kolombo (aku sungguh pernah di sana lho, walau pun mungkin sebagai pesuruh saja, untuk menggantikan Rivai Apin yang sibuk sebagai anggota BPH Jakarta Raya) berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan nasional Sri Langka melawan PSSI Banteng (karena ada tim PSSI lain, yaitu PSSI Harimau dan PSSI Garuda, saking banyaknya bintang lapangan hijau ketika itu). Duta Besar Asa Bafagih bersama Letkol. Gatot Soewagio (pimpinan rombongan) menjemput aku untuk ikut duduk di bangku suporter masyarakat Indonesia yang (ditambah saudara-saudara kita beberapa tokoh dari Perhimpunan Masyarakat Melayu Sri Langka; Ceylon Malay Association.) hanya berjumlah belasan orang itu. PSSI menang besar: 7-0! Pulang dari stadion kutulis reportase yang kuberi judul “Banteng Indonesia Tanduk Singa Singhala 7 : 0.” Coba, bayangkanlah itu! Tidak ada sepertinya dua kesebelasan sepak bola yang bertanding, melainkan dua ekor binatang hutan yang berlaga. Yang satu, Sang Banteng Indonesia, mendongak ke langit berjaya, dan yang lain, Si Singa Singhala, berdarah-darah dan perut jebol di sanasini. Reportase itu kukirim ke Sdr. Hardjito, redaktur Harian Rakyat “Sport dan Film” ketika itu. Tapi, sehabis itu, membaca kembali duplikat reportase itu, aku thengerthenger sendiri: “Mengerikan amat fantasiku!” media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
Yang terlukis pada angan-anganku ketika itu ialah tentang hewan banteng yang seakan diangkat sebagai binatang mitologi, lambang semangat bangsa Indonesia, berhadapan dengan singa, binatang mitologi bangsa Singhala. Dulu, dan dulu ini belum sangat lama, di empat sudut persada Monas yang berbentuk bujur sangkar itu, dipasang patung Banteng Merah yang besar dan gagah. Juga dalam lirik lagu “Jempol Indonesia”, yang bernada-nada “Di Timur Matahari”, ada satu barisnya yang berbunyi “Banteng Indonesia …” Jadi begitulah banteng dalam angan-anganku. Sedangkan hewan singa merupakan lambang resmi negara dan bangsa Sri Langka yang bermayoritas penduduk suku Singhala, konon satu bangsa yang diturunkan oleh Sing(h)a, binatang mitologi bangsa Singhala. Ia menjadi me-Manusia setelah menerima ajaran pencerahan dari Sang Sidharta Gautama (tentang ini pernah ditulis dan dipentaskan dalam bentuk drama panggung oleh Wickramasinghe, penulis terkemuka tahun 60an di negeri ini). Aku tidak tahu bagaimana “bahasa pers” di dunia olah raga ketika itu, lebih khusus lagi dunia olah raga sepak bola. Apakah kata-kata perbandingan yang kupakai di sana masih “sportif” atau tidak, justru sebagai perbandingan dalam tulisan untuk melaporkan tentang peristiwa “sport”. Tapi peristilahan itu kuajukan memang dengan sadar atas dasar simbolsimbol kemuliaan dan demi pemuliaaan bangsa yang bersangkutan. Bukankah Bung Karno juga pernah gegap gempita meramalkan: “Kelak apabila Banteng Indonesia telah bersatu dengan Gajah Putih dari Campa, Barongsai dari Tiongkok, Lembu Nandi dari India … ketika itulah fajar kemerdekaan negeri-negeri Asia akan terbit!” (silakan temukan dalam Mentjapai Indonesia Merdeka). “Sport” ialah “olah raga”. Tapi “sportif” tidak cukup diartikan sebagai “bersifat keolah ragaan”, karena di sana terkandung makna “sifat jujur”, “sifat kesatria”, fair, dan semacamnya. Bagaimanakah praktek kebahasaan dunia sport pada pers kita sekarang? Banyak peristilahan yang sama sekali tidak sportif sekarang ini bertaburan di dalam pemberitaan atau serba tulisan tentang dunia sport! Apakah ini gejala produk kebudayaan Orde Baru di bidang linguistik atau kebahasaan, khususnya kebahasaan dunia olah raga? Kalau begitu halnya, apakah dengan ini bisa diartikan
bahwa, “sifat jujur” atau “sifat kesatria” atau fairness (dengan segala maknanya: kejujuran, keadilan, kewajaran) di jaman Orde Baru sudah bergeser maknanya? Bayangkanlah! Bagaimana bisa terjadi, justru dari dunia sport lahir seribu satu peristilahan yang sama sekali tidak sportif? Bagaimana harus masuk di penalaranku, bahwa ada akronim “bonek”, dari kepanjangan bondho nekat (kata-kata Jawa untuk “bermodalkan nekat”), lahir dari dunia sport yang mestinya serba tidak nekat itu? Apalagi perbuatan mereka memang nekat. Apabila klub yang dijagokannya kalah, etalase toko akan hancur, gerbong-gerbong kereta api, tawuran antara kelompok sana dan kelompok sini terjadi! Istilah-istilah yang serba tidak sportif itu terdapat di dalam rubrik olah raga, khususnya sepak bola, pada hampir semua media massa, cetak maupun sibernetika. Inilah beberapa contoh, perhatikan katakata dalam bold, misalnya: “Bungkam Venus, Serena juara” (satusport); “Angie tekuk
unggulan keempat” (detiksport); “Spurs jungkalkan Pistons” (Astaga.com.sport); “Barcelona menelikung R. Huelva”, dan tentu banyak lagi (Barangkali juga bisa kita baca dalam Kompas, Suara Pembaruan, Pos Kota dan lain-lain?) Bukan hanya mencari hingar-bingar dalam kata-kata yang tidak sportif demikian, tapi adakalanya juga mencari “wah” dengan menggunakan kata-kata asing yang tidak kumengerti. Misalnya, dari reportase sepak bola, antara lain kutemukan begini: “umpan lambung dari rusuk kiri dikonversikan menjadi sebuah gol”. Tentu saja maksudnya jelas: “diubah”. Tapi manfaat apa, kata “ubah” yang sederhana dan pendek dirasa perlu diganti dengan “konversi” — seperti layaknya hak guna tanah saja?! Padahal akan lebih bagus, karena ini reportase sepak bola, kalau dilukiskan dengan gerak apa si Pemain itu berhasil “mengkonversikan” umpan lambung itu menjadi gol: “ditanduk”, dipotong setengah lutut, atau dengan tendangan akrobatik
POKOK
dan lain-lain? Apakah masalah kebahasaan ini perihal “sepele”? Kalau jawabannya “ya”, aku ingin bertanya lagi: kalau dunia sport dipenuhi peristilahan yang tidak sportif, bagaimana makna peristalahan dalam dunia lain-lain? Kata “korup”, misalnya, apakah mungkin sekarang sudah bukan lagi “korup” di “Jaman Sukarno”? Kata “vonis”, umpamanya, apakah sekarang tinggal sepatah wacana dunia “pengadilan”, notabene yang bukan lagi “pengadilan” di “Jaman Normal”? Lha, kalau memang sudah begitu, pantes aja amburadul seperti tidak ada wasit lagi di lapangan hijau kita yang bernama Republik Indonesia! Mari kita renung bersama-sama! 0 Kockengen, 26 Januari 2003. Hersri Setiawan, penulis menetap di Negeri Belanda
ROEPA-ROEPA BASA MARDIKA Mas Marco Kartodikromo: Dan semangkin tambah pengatahoean saja, bertambah berani saja bergerak dimedan kemadjoean. Sebab semoea kepandaian itoe hanja saja pandang seperti perkakas jang bisa menjampaikan toedjoean saja goena kebangsaan. Tetapi ada banjak orang jang berkepandaian mendjilat kotorannja orang-orang jang merampok kita. Kasian!! (“Dorongan oentoek Si Pendjilat”, Sinar Hindia, 28 Agoestoes 1918)
Moesso: Volksalmanak-volksalmanak dan almanak-almanak tani itoe soedah tentoe memoeat hal-hal wetenschappenlijk (scientific), jang kelihatannja tidak bersangkoetan dengan politik. Tetapi orang jang mengerti sedikit tentang politik mengerti djoega, bahwa boekoe-boekoe dan almanak-almanak itoe nomer satoe dibikin tidak memboeat mendidik Rakjat, tetapi boeat menjesatkan pikiran Rakjat. Sistematis, dengan cara jang haloes sekali boeah-boeah pikiran pihak sana dimasoekkan dalam kepala Rakjat. Soedah waktoenja kewadjiban kita melawan pengaroeh Balai Poestaka. Kita haroes menerbitkan boekoe jang perloe, boekoe tjerita sendiri, agar Rakjat tidak lepas dari pergerakan. Rakjat tidak terikoet aroes nasehatnasehat baik dalam boekoe dari Volkslectoeoer, karena batjaan terseboet tidak baik bagi rakjat djadjahan. (Api, 25 Djoeli 1925)
Rangsang dalam Kaoem Merah: Sebab moelai djaman doeloe sampai sekarang kita kaoem perempoean dipandang seperti perhiasan roemah tangga, dan mendjadi kepalanja koki. Tetapi boeat ini djaman itoe atoeran haroes dioebah. Boeat kaoem kita perempoean jang memang ada kewadjiban roemah tangga dan lelaki boleh melakoekan itoe pekerdjaan, tetapi boeat kaoem perempoean jang tidak mempoenyai itoe kewadjiban, haroes sekali menolong pekerdjaan kaoem lelaki jang menoedjoe kegoenaan oemoem. Kita tahoe ada banjak orang perempoean jang memilih doedoek diam sambil makan angin, meski perempoean jang terpeladjar djoega, ada jang soeka melakoekan itoe tabiat. Sekarang kita kira soedah waktoenja kita orang toeroet bergerak bersama-sama dengan saoedara kita kaoem lelaki. Kita tahoe djoega, bangsa kaoem kolot tentoe mesem mendengar perkataan ini. Baiklah kaoem jang tidak menjetoedjoei itoe kita sisihkan sadja.
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
29
PENGANTAR Didesak oleh keprihatinan terhadap kurangnya penghargaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia, Pramoedya Ananta Toer meluncurkan 11 tulisan berseri tentang sejarah bahasa Indonesia dan kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan negeri ini. Seri tulisan berjudul “Basa Indonesia sebagai Basa Revolusi Indonesia” ini dimuat di Lembaran Kebudajaan harian Bintang Timur, Lentera, hampir setiap minggu dari 22 September 1963 sampai 5 April 1964. Di tulisan paling awal Pramoedya menekankan, “Basa Indonesia merupakan bagian jang integral dari Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia tak bakal ada tanpa basa Indonesia. Sebaliknya basa Indonesia pun takkan mungkin ada tanpa adanja Revolusi.” Dalam edisi MKB kali ini, Tim Redaksi menerbitkan kembali 2 tulisan yang paling berkaitan dengan tema yang ingin kami angkat, yaitu hubungan antara bahasa Indonesia dengan gerakan nasionalis di sepanjang paruh pertama abad ke-20. Sengaja kami tidak mengubah ejaan yang digunakan dalam tulisan-tulisan di bawah agar pembaca bisa mengamati sendiri perubahan yang dilalui bahasa Indonesia sejak 20 tahun yang lalu.
Basa Indonesia Sebagai Basa Revolusi Indonesia Pramoedya Ananta Toer 20 Oktober 1963+ Apakah faktor2 jang menjebabkan basa pra-Indonesia dipilih oleh pers pra-Indonesia? Mengapa pada umumnja bukan basa daerah jang dipergunakan atau bukan basa Belanda? Beberapa faktor jang menentukan pemilihan ini jalah: a. Keadaan Sosial Ekonomi dimana Rakjat djelata pada umumnya tidak membatja ____ karena butahuruf. ____ jang membatja adalah bordjuis, jang karena kondisi sosial ekonomi mendapat keberuntungan pendidikan sekolah.* b. Politik Kolonial Dibidang Basa, dimana Belanda tidak rela disebarkannja basa Belanda di Indonesia, terutama Indo, akan terantjam hegemoninja dilapangan ilmu dan pengetahuan, serta dilapangan penghidupan. c. Watak Basa Pra-Indonesia jang terusmenerus demokratik jang memudahkan seseorang menempatkan dirinja dihadapan orang jang dilawannja bitjara, djadi tidak seperti halnja bila orang dari rumpun kebudajaan Djawa mem-
pergunakan basa-ibunja. Watak basa ini segera akan muntjul bila orang dari rumpun kebudajaan Djawa terpaksa mempergunakan basa pra-Indonesia . d. Politik Pintu Terbuka Hindia Belanda melahirkan sumber2 kehidupan baru diluar kampung halaman sendiri. Perpindahan tenaga kerdja jang berhimpun dipusat2 pekerdjaan melahirkan perkampungan2 baru dimana orang dari berbagai daerah bertemu dan hidup bersama. Sedang pertemuan antara orang2 dari provinsi2 kebudajaan jang berlainan membutuhkan lahirnja lingua-franca. Dalam pada itu golongan Indo jang tidak mendapatkan tempat dikantor2 pemerintah, serta bekas serdadu, pada bekerdja dipabrik2, jang djuga timbul disebabkan karena politik pintu terbuka tsb. Mereka adalah dari berbagai matjam daerah di Indonesia, jang dalam pekerdjaannja sehari2 djuga dipaksa dan menerima basa pra-Indonesia sebagai linguafranca. Pabrik2 ini pada umumnja adalah pabrik gula, teh, kopi, tembakau dan pabrik pengolahan barang pelikan. Politik pintu terbuka menjebabkan ramainja lalulintas perdagangan dan pada gilirannja menimbulkan perusahaan2 djasa: perhotelan, perbengkelan, binatu dsb. jang djuga menjebabkan semakin meratanja basa pra-Indonesia. e. Wudjut Dari Basa Pra-Indonesia itu sendiri jang dalam penggunaannja tidak meminta sjarat jang tinggi, sehingga siapapun bisa mempergunakannja asalkan berani. f. Sifat Basa Pra-Indonesia jang selalu mema’afkan penggunanja jang miskin perbendaharaannja, serta besarnja daja hisap serta dajakajal basa ini jang selalu mau menerima kata2 baru dari manapun djuga datangnja sehingga memudahkan para penggunanja dimanapun ia berada. Sifat ini hampir sama dengan jang dimiliki oleh basa Esperanto, hanja saja basa jang achir ini melakukan seleksi setjara terpimpin, sedang basa pra-Indonesia bukan sadja tidak terpimpin, bahkan setjara liberal. Perbedaan lain jalah daerah basa jang dipergunakan sebagai sumber. g. Kondisi Pers Pra-Indonesia sendiri pada pertengahan kedua abad jl.[jang lalu – ed.] itu jang kebanjakan dibiajai oleh perusahaan2 monopoli besar seperti gula, tebu, karet dan tembakau untuk memberikan pengertian kepada pedjabat2 pribumi — jang waktu itu belum mengenal basa Belanda — tentang berkah jang diberikan oleh perusahaan tsb. kepada penduduk dan dengan demikian antipati dapat ditumpahkan pada pemberontakan2 petani, jang pada waktu itu selalu timbul disebabkan perebutan tanah2 subur antara para petani kontra perusahaan2 monopoli besar. Kelak pemberontakan2 tani ini banjak djuga dilaporkan oleh sastra assimilatif sebagai kelandjutan daripada pemberitaan2 pers. Perusahaan monopoli terbesar didaerah2 perkebunan penting inilah jang mendjawab mengapa sudah dalam dekenla keenam abad jl.itu pers pra-Indonesia terbesar di Djakarta, Semarang, Surabaja, Jogjakarta dan Medan dan tidak hanja di Djakarta sebagai pusat pemerintahan. Dari situasi ini dapat pula difahami mengapa pembantu2 sk2 [surat kabar – ed.]. begitu meluas sampai didusun2 (perkebunan) jang sangat ketjil. Sebaliknja sk2 itupun disebarkan keperkebunan2, per-
+
Tulisan yang dimuat pada 20 Oktober 1963 ini sebenarnya dimulai dengan poin c. Watak Basa Pra-Indonesia Poin-poin sebelumnya dibahas pada tulisan yang dimuat pada 13 Oktober 1963. Tapi untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembicaraan, Tim Redaksi memasukkan 2 poin yang disebut terlebih dahulu. * Di teks asli yang disalin dari microfilm ada beberapa kata yang tidak jelas. Tim Redaksi mengosongkan bagianbagian yang memang sama sekali tidak terbaca.
30
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ISTIMEWA
POKOK
tambangan, pabrik2, dan sebagainja, dan tidak djarang pihak perusahaan membagikan kepada buruhnja jang bisa batja tulis untuk dibatjakan kepada sesama buruh. Djuga pers pra-Indonesia ini dalam komposisi pemberitaannja sangat sedikit menjoroti kedjadian luarnegeri, walaupun difahami karena belum adanja kantorberita pada waktu itu, tetapi peperangan2 kolonial selalu dihidangkan sedemikian rupa sehingga memberikan kesan jang tak meragukan lagi tentang keuangan balatentara keradjaan Belanda. Pergerakan Rakjat, apabila tidak diberitakan, maka ditafsirkan sebagai kerusuhan. Pada tengah kedua abad jl. ini, sekalipun banjaknja butahuruf, pers pra-Indonesia praktis telah mendjadi barang peradaban jang sangat biasa dipusat2 perusahaan monopoli ini. Pada pihak lain amanat jang dibawa oleh pers ini dibidang basa pra-Indonesia, ialah meningkatkan perbendaharaan kata pembatjanja, serta memberikan kesempatan untuk membatja, sehingga lambatlaun pers jang dimulai oleh kaum geredja kemudian oleh golongan Indo ini dianggap sebagai basa pra-Indonesia jang sempurna. Bukankah orang2 Indo (Belanda) jang mengendalikannja? Bukankah mereka “lebih pintar” dan “lebih tahu” daripada Pribumi? Dalam pada itu basa pra-Indonesia jang sebenarnja senjawa dengan basa pers praIndonesia, dan senjawa pula dengan pers pra-Indonesia sendiri dalam penggunaannja. Djurnalistik dalam perkembangan apapun, biasanja memerlukan ketjepatan bekerdja, sedang sjarat jang terpenting adalah ketertiban dlm. mengemukakan facts. Tidak ada waktu tjukup untuk memikirkan salahtidaknja menurut ilmubasa, sedang basa pra-Indonesia sendiri tidak meminta sjarat ilmubasa jang tinggi.
POKOK
Disamping adanja bantu-membantu antara pers dan sifat basa pra-Indonesia sendiri, pada masa itu kondisi pertjetakan belumlah sebaik sekarang, sehingga waktu mentjetak adalah lebih lama dan lebih meminta waktu daripada sekarang. Para redaktur biasanja djuga merangkap sebagai korektor, bahkan mengedar, bahkan djuga ikut mentjetak, sehingga segi2 ilmu basa praktis ditinggalkan samasekali. Ada sementara tulisan jang menilai basa pra-Indonesia sebagai basa Melaju Indo, dan nampaknja, melihat dari latarbelakang historik ini penilaian demikian tidak terlalu keliru. Bahkan Medan Prijaji jang terbit pada tahun 1907 masih mempergunakan “Melaju Indo” ini. Demikian faktor2 jang menentukan mengapa basa pra-Indonesia setjara “alamiah” mendjadi basa pers pra-Indonesia. Pers jang menggunakan basa daerah, terutama pers organisasi2 politik kooperatif, dalam perkembangan selandjutnja ternjata tidak bisa membawa kemadjuan pers pra-Indonesia, baik dalam peredaran umum maupun tirasnja, dan tetap mendjadi pers daerah. Sesuai dengan kedaerahannja, maka djarang sekali terdapat pers daerah jg mempunjai pengaruh didalam masjarakat. Dan sudah dalam dekenla keenam abad jang lalu basa pers Indonesia, sekalipun didalam pers dipelopori oleh golongan Indo, telah menundjukkan mempunjai dajadjangkau dan dajatjakup jang lebih luas daripada basa daerah. Basa Djawa jang pada waktu dipergunakan oleh hampir 40 djuta manusia, jakni djumlah terbesar suku bangsa Indonesia, didalam kehidupan pers tidak mampu mengambil peranan penting, karena hampir 40 djuta suku Djawa adalah bagian termiskin dari penduduk Indonesia waktu itu sedang harga surat kabar adalah terlalu tinggi
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
dibandingkan dgn di djaman kemerdekaan. Perlawanan Terhadap Pers PraIndonesia Tidak Pernah Berhasil. Apabila disini disebut pers Indonesia artinja tidak lain daripada pers jang menggunakan pra-Indonesia, bukan basa Melaju atau basa Belanda ataupun basa daerah. Dalam istilah ini tidak dibedakan apakah pers itu ikut bergabung ataupun menentang gerakan kemerdekaan nasional, karena jang djadi pegangan hanjalah basa jang dipergunakannja. Bisa djadi pers itu mendukung pendjadjahan Belanda, boleh djadi menentangnja, hal ini adalah kontradiksi2 jang terdapat dalam pers praIndonesia dan tidak mempengaruhi wudjut dari pers pra-Indonesia itu sendiri. Baik sebelum, terutama selama gerakan kemerdekaan nasional, pers pra-Indonesia setjara periodik terus-menerus mendapat serangan. Serangan ini terutama berasal dari pers Melaju, jaitu pers jang menggunakan basa Melaju sebagaimana ditentukan oleh politik basa Hindia Belanda. Apakah pers pra-Indonesia adalah pers borjuasi pra-Indonesia, maka pers Melaju adalah pers pegawai negeri atau tjalon pegawai negeri, jang disekolahkan, mendapat didikan basa Melaju sebagaimana dikehendaki oleh politik kolonial Hindia Belanda. Pers Melaju biasanja dipimpin oleh “ahli2” basa Melaju, artinja: guru atau bekas guru. Sudah sedjak disekolah mereka diadjarkan menghinakan basa pra-Indonesia tanpa diadjarkan kepada mereka untuk memahami alasan2 sosial daripadanja. Pers Melaju kebanjakan berbentuk madjalah mingguan, sedang jang pertamakali dihidangkan setjara Barat adalah Bintang Hindia jang diasuh oleh dr. Abdul Rivai dan Letnan Clackoner Broussen. Betapa pentingnja pers birokrat ini untuk menghadapi pers bordjuis pra-Indonesia dapat dilihat dari tjara penjebarannja jang meluas di kalangan para pegawai negeri, dengan pemerintah Hindia Belanda dibelakangnja jg membebaskan peredaran madjalah ini dari pembajaran porto pos. Madjalah ini diterbitkan dalam rangka usaha Hindia Belanda untuk melakukan “pasifikasi Atjeh”, sedang para pengarangnja terketjuali, Mara Sutan, adalah djago2 tua jang kelak merajai Balai Pustaka. Terdapat diantara pengarangnja tokoh pers Melaju Sumatera Timur Dja Endar Muda, dsb. Salim jang kelak terkenal sebagai “the grand old man” Hadji Agus Salim. Majalah ini djuga menjediakan ruangan untuk karangan-karangan berbasa Belanda, 31
diantara penjumbangnja terdapat djuga nama Kartini. Adanja perpisahan jang menentukan antara basa Melaju dari basa pra-Indonesia, ditambah dengan pemihakan jang berkuasa pada Basa Melaju untuk masa sepandjang penjajahan Belanda, menimbulkan komplikasi2 dan pertentangan2 didalam masjarakat hanja karena tjara menggunakan kedua matjam basa tersebut. Sekitar awal abad ini, apa jang disebut kaum terpelajar Pribumi adalah senjawa dengan kaum guru. Berbagai sektor kemadjuan praktis dirintis oleh kaum guru. Mereka ini adalah pendukung politik ethik Hindia Belanda jang menempatkan pengajaran pada tempat terpenting sebagai garapan utama dalam usaha mentjiptakan kemadjuan. Djuga dibidang pers, terutama di Sumatra—djadi berbeda dari di Jawa— mereka djuga mendjadi pelopor pers Melaju, diantaranja Dja Endar Muda dengan Pertja Baratnja, Mangaradja Salamabut dengan Pertja Timurnja jang terbit pada tahun 1905. 5 April 1964 Dimanakah rasia kekuatan basa pra-Indonesia ini? Bila diperhatikan bangun basa itu sendiri, akan nampaklah bahsa ia tidak meminta sjarat-sjarat jang biasanja dituntut dari kaum feodal, jakni pengkastaan, penghormatan wadjib dan formalisme. Pendeknja ia tidak meminta sjarat2 feodal, jang memisahkan seseorang dari seseorang jang lain hanja karena asal kelahirannja. Sebaliknja, ia digunakan dengan sebebasnja untuk mendapatkan effek persaudaraan dan persatuan jang sekokoh2nja serta seluas-luasnja dan sebanjak-banjaknja. Maka sebagai pegangan untuk dapat mengingat perkembangan jang luar biasa dalam sedjarah basa2 ini jalah bahwa praIndonesia telah terpilih oleh gerakan nasional sebagai basa persatuan karena itu sendiri memikul kodrat persatuan. Kalau Multatuli pernah mengatakan, bahwa basa Melaju adalah Italianja Asia Tenggara, mungkin asosiasinja terpaut pada perkembangan basa Italia jang hampir2 menjerupai basa pra-Indonesia. Persamaan itu terletak pada kenjataan bahwa basa Italia adalah sebuah dialek Latin jang berkembang sedemikian luas dan tjepatnja dan mendorong induk basa kesudut dan mendjadi steril, sedjak abad ke XIV, sedang basa pra-Indonesia jang tadinja sebuah dialek basa Melaju djuga berkem32
bang dengan luas dan tjepat sedjak abad keXVI dan mendorong induk basanja, jakni Melaju, ke sudut dan mendjadi steril. Tetapi Multatuli melupakan atau terlupa pada kodrat2 persatuan jang terkandung didalam wudjud basa pra-Indonesia. Sedjak penolakan sajap kiri Sarekat Islam sedjak tahun 1916, basa pra-Indonesia mengalami perkembangan extensif. Praktis seluruh madjalah daerah memberikan ruangan pra-Indonesia apalagi iklan jang hampir selamanja tertulis dalam basa praIndonesia. Dalam basa daerah serta Belanda tertulis hanja iklan jang bersifat kultural, misalnja buku2 dan penawaran djasa jang bersifat kebudajaan. Pada tahun 1923 bukan hanja sajap kiri Sarekat Islam jang menolak koperasi, djuga seluruh organisasi Sarekat Islam sendiri dengan penolakan Tjokroaminoto terhadap pengangkatannja sebagai wakil organisasi didalam Volksraad. Tindakan ini setjara politik membenarkan sajap kiri. Ini merupakan putusan didalam Kongres tahun 1923 itu, dimana nama Sarekat Islam diubah mendjadi Partai Sarekat Islam (PSI), dan dengan menggunakan sebutan “partai”, setjara resmi basa pra-Indonesia sebagai basa organisasi mulai mendjadi basa politik. Setahun sebelum itu Studenten Vereeniging di Amsterdam telah mengubah namanja djadi Perhimpoenan Indonesia. Djadi apabila pada tahun 1922 kata Indonesia telah mendjadi istilah politik. Perubahan nama ini — bagaimanapun kurangnja penilaian orang sampai dewasa ini, tidak dapat mengurangi makna politik jang hidup didalam pernjataan itu. Madjalahnja — Hindia Putera, diubah pula namanja mendjadi Indonesia Berdjuang. Bahwa jang memelopori penggunaan nama Indonesia adalah organisasi mahasiswa diluarnegeri, tidak lain daripada suatu perlambang, bahwa gerakan nasional dikodratkan untuk dipelopori oleh angkatan muda, sedang peristiwa sedjarah ini terdjadi di Nederland sendiri tidak lain daripada suatu perlambang, bahwa perlawanan terhadap imperialisme dipelopori justru didalam sarang imperialis sendiri. Djuga dalam madjalah tsb. lebih separoh daripada halaman2 jang tersedia dipergunakan untuk memuat tulisan2 berbasa praIndonesia. Sajang sekali bahwa madjalah jang patriotik ini hampir2 tak dapat ditemukan lagi di Indonesia. Padahal pada masanja, ia selalu berhasil dalam menerobos sidangsidang Dewan Rakjat, Dewan Hindia, Algemeene Secretaris, dan pers pra-Indomedia kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
nesia pada umumnja. Dengan digunakannja nama Indonesia oleh gerakan mahasiswa kita di Nederland tsb. sedjarah basa Indonesia sebenarnja telah bermula dan istilah pra-Indonesia, telah dapat dihapuskan. Tetapi karena penggunaan itu baru oleh satu organisasi sadja dan belum mendapat pengakuan dari semua organisasi jang punja kedudukan, basa pra-Indonesia sebagai basa Indonesia masih merupakan de facto. Setelah terdjadi perkisaran dalam kehidupan organisasi mahasiswa dan sekaligus menjetudjui politik non-koperasi, demikian pula halnja dengan Partai Sarekat Islam, hubungan “kekeluargaan” dengan imperialisme Belanda digunting putus, dan kedua organisasi tersebut mulailah setjara terang-terangan menghadapi imperialis Belanda sebagai musuh pokok. Pihak imperialis mempergunakan basa Belanda, pihak Nasionalis nonkoperatif dengan basa Indonesia, dan keadaan darurat sadja menggunakan basa Belanda. Pendeknja, publikasi2 mulai babak ini menggunakan basa Indonesia, karena ditudjukan kepada gerakan nasional, djadi tidak lagi seperti Budi Utomo, Indische Partij ataupun Insulinde jang menggunakan basa Belanda untuk mendapatkan perhatian dari imperialis Belanda, dan samasekali telah meninggalkan Sosrokardono, Casajangan, Iskandar, Kartini, Notosuroto dll. jg dapat dikatakan mutlak menggunakan basa Belanda untuk meminta perhatian. Perpindahan Sarekat Islam mendjadi Partai dan sekaligus menanggalkan politik koperasi, disebabkan karena perkembangan intern dimana sajap kiri makin lama makin berpengaruh dan menentukan. VSTP jang pada mulanja djuga menggunakan basa Belanda, pada tahun itu praktis telah menggunakan basa pra-Indonesia. Pada tahun 1924 organisasi2 kiri jang mutlak menggunakan basa pra Indonesia, VSTP, petjahan Sarekat Islam, Partai Komunis Hindia — terlebur mendjadi organisasi kiri jang terbesar dalam sedjarah, jaitu Partai Komunis Indonesia. Dengan demikian untuk kedua kalinja nama Indonesia mendjadi nama organisasi nonkoperatif. Dibawah pimpinan Partai Komunis Indonesia, politik non koperatif mendapatkan kemenangan jang gilang-gemilang, sekalipun sedjarah belum memberikan kemenangan mutlak. Tapi dibidang basa kemenangan golongan kiri berarti kemenangan mutlak basa Indonesia. Organisasi2 kedaerahan jang pada mulanja memilih
sosial dan kebudajaan sebagai garapannja, dengan gelumbang mulai bergerak tanpa ragu dan dengan terang2an dibidang politik: Budi Utomo, Pasundan, Tirtajasa, Sarekat Ambon, Sarekat Madura, Kaum Betawi, jang sebelum itu bernama Daja Upaja dan Betawi Berichtiar. Dengan sendirinja basa pra-Indonesialah jang djadi basa organisasi dan djuga antar organisasi. Kampanje2 politik, surat2 selebaran, plakat2 dari golongan non menggunakan basa pra-Indonesia ini sampai ketengah2 pabrik dan perkebunan2 dan mentjapai puntjaknja pada tahun 1926. Maka adalah suatu keteledoran untuk tidak mengetahui, bahwa sk Proletar terbitan Surabaja ikut
mendjiwai basa pra-Indonesia sebagai basa perdjuangan, perkelahian dan pertarungan melawan imperialisme. Pada waktu terdjadi penjitaan atas 2 toko buku terbitan penerbit2 kiri di Surabaja, seluruhnja tertulis dalam basa pra-Indonesia. Ali Archam dalam pembelaan terhadap kekuasaan imperialis sebelum dibuang ke Irian Barat pada tanggal 24 Desember 1925, djuga menggunakan basa pra-Indonesia sebagai alat pembelaannja, ja sekalipun basa ini tidak diakui sebagai basa hukum. SBBM, jaitu serikat buruh marine, jang hidup ditengah2 alat pembunuh imperialis bukan saja menggunakan basa pra-Indonesia, djuga menghimpun seluruh buruh
POKOK
merah dari berbagai keturunan dengan basa itu. Ada suatu keteledoran pula untuk tidak mengetahui, bahwa politik pertamatama dalam sedjarah Indonesia, jaitu pemberontakan 1926, dalam penjerangan2nja di Glodok, Tanah Abang, Pal Merah, menggunakan komando basa pra-Indonesia. Dalam pemeriksaan militer dan polisi, mereka jang tertangkappun menggunakan basa ini dan mereka jang menguasai basa Belanda djuga menolak basa imperialis tsb. Malah seorang komunis Belanda, Lassen, dalam pemeriksaan polisi pada bulan Djanuari 1926 tidak menggunakan basa ibunja sendiri, tapi basa pra-Indonesia. 0
ALIT AMBARA
TIM MEDIA KERJA BUDAYA: Anom Astika, Ayu Ratih, John Roosa, Purwantari, Razif
POKOK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
33
Edward Said (1935-2003) John Roosa Dalam menimbang kehidupan Edward Said, kekaguman sulit dihindari: penulis yang produktif, pemain piano ulung, aktifis politik tak kenal lelah untuk hak-hak orang Palestina, ilmuwan sastra yang fasih berbahasa Inggris, Perancis dan Arab. Bahkan ketika ia sakit leukemia parah di dasawarsa terakhir hidupnya, masuk keluar rumah sakit untuk transfusi darah, ia tetap bergerak dengan laju mencengangkan dalam menulis dan memberi ceramah – gerak yang seharusnya luar biasa meletihkan kebanyakan manusia sehat. Kematiannya pada 25 September 2003 memutus kehidupan seorang intelektual yang bergairah dan tekun, setelah perjalanan penuh pencapaian, masih memiliki begitu banyak untuk disumbangkan. Latar belakang pengasuhan dari keluarga Palestina yang cukup berada sudah memungkinkan Said memperoleh sifat-sifat yang menonjol: keterpelajaran, pandangan kosmopolitan, rasa percaya diri yang kuat, dan kesadaran akan pengalaman menjadi korban. Lahir di Jerusalem, ia menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya di Kairo dan Lebanon, tempat ia belajar di sekolah swasta untuk kaum elit. Said berangkat ke Amerika Serikat pada 1951 untuk melanjutkan studi ke Universitas Princeton. Pada saat itu keluarganya sudah tersebar bersama dengan kelompokkelompok perantau Palestina lainnya ke segala penjuru dunia. Pembentukan negara Israel pada 1948 merupakan bencana bukan saja bagi keluarganya, tapi juga bagi seluruh bangsa Palestina. Ia mengenang kemudian bahwa “sejak musim semi 1948 tak seorang pun dari sanak-saudaraku yang masih tinggal di Palestina. Semuanya telah dibersihkan dengan sentimen etnis kekuatan Zionis.” Ketika ia belajar di program paska sarjana Universitas Columbia pada 1960an, Said tenggelam dalam studi tentang kesusatraan klasik. Seorang kawan lamanya, Michael Wood, mengungkapkan bahwa Said adalah “ilmuwan ketinggalan jaman” yang dengan ‘keningratannya’ berjarak dari
OBITUARI 34
budaya populer. Ia memainkan musik klasik dengan piano (komposer favoritnya Brahms) dan menulis tentang Joseph Conrad (subyek buku pertamanya pada 1966). Bayangan ideal Said tentang sosok yang berbudaya dan humanis memiliki kebaikan tersendiri. Ia meruntuhkan seluruh stereotip yang dipercayai orang Amerika tentang orang Arab. Di Amerika tak ada kelompok etnis yang lebih dizalimi daripada orang Arab. Perhatikan saja filmfilm produksi Hollywood. Dalam imajinasi populer, orang Arab digambarkan kalau tidak sebagai sultan yang dekaden, masyarakat suku terbelakang yang menggembalakan unta di padang pasir, atau teroris. Said seakan tampil sebagai suatu keajaiban bagi kebanyakan orang Amerika: seorang Arab yang bukan hanya kritikus sastra, tetapi juga kritikus sastra yang melejit sampai ke puncak pencapaian profesinya – guru besar dengan jabatan abadi dan gaji yang tinggi di sebuah universitas Ivy League [kumpulan 8 universitas swasta terpandang di pantai timur AS, red.] di kota New York. Bahwa ia seorang Nasrani menghancurkan lagi streotip yang lain – orang Amerika berpikir bahwa semua orang Arab itu Muslim. Dengan perspektif kosmopolitannya, Said berhasil menghindari perangkap fanatisme berlebihan terhadap etnisitas atau agama. Kebanyakan karya tulisnya memang dirancang untuk membujuk orang supaya menolak prasangka terhadap ‘yang [dianggap] lain’. Ia menulis kata pengantar baru untuk bukunya yang paling terkenal, Orientalism (pertama kali diterbitkan pada 1978), yang akan diterbitkan ulang, bahwa ia adalah pembela “humanisme” dan itu maksudnya “menggunakan otak secara historis dan rasional untuk tujuan pemahaman yang reflektif.” Disiplin keilmuan tua tentang interpretasi (seperti dalam filologi dan hermeneutika) baginya tampak sebagai model hubungan sosial yang ideal. Dalam memahami teks dari budaya asing atau periode sejarah yang berada jauh dari masa kini, seorang kritikus
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
sastra harus “ s e c a r a simpatik dan s u b y e k t i f memasuki kehidupan teks tertulis seperti yang tampak dalam perspektif waktu dan penulis teks.” Said mendorong kita untuk memiliki “keramahan dan keterbukaan” terhadap apa yang awalnya tampak asing bagi kita dan untuk “menyediakan tempat” bagi keasingan itu di benak kita. Ia melihat sastrawan seperti Goethe dan Erich Aurbach sebagai pahlawan dalam upayanya mencapai pemahaman lintas budaya. Said mengerti bahwa penggusuran brutal bangsa Palestina bukan disebabkan oleh semacam permusuhan kuno antara kaum Yahudi dan Muslim. Tidak seperti mereka yang ingin menjadi pendukung kepentingan bangsa Palestina di luar Palestina, ia tidak pernah mengkritik agama Yahudi. Ia tahu bahwa masalahnya bersumber dari kebijakan negara Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin negara Israel boleh saja berbicara atas nama Judaisme, tapi pada akhirnya sebuah negarabangsa berbeda dengan sebuah agama. Beberapa orang Yahudi, di dalam dan di luar Palestina, juga memahami hal yang sama dan mereka tidak keberatan bergandengan tangan dengan orang-orang Palestina. Said adalah sahabat karib dirigen orkestra dan pianis Yahudi ternama Daniel Barenboim. Karena bertemu Said pada pertengahan 1990an lah, Barenboim mulai mengunjungi Tepi Barat dan menyelenggarakan konser musik di tengah masyarakat Palestina. Dalam pernyataan-pernyataan publiknya, Barenboim mengutuk pendudukan Israel dan mengusulkan penyelesaian dua-negara. Mereka berdua mengajak musisi Barat dan Timur Tengah untuk membentuk sebuah orkestra bernama East-West Divan pada 1999 (nama ini mengacu pada satu kiasan dalam puisi Goethe). Konser terakhir orkestra ini diadakan di London hanya sebulan sebelum kematian Said. Sebetulnya Said bisa memilih untuk
OBITUARI 34
diam, sekedar menjadi dosen yang rajin, seperti beberapa dari pahlawan kesusastraan yang ia kagumi. Tapi, ia justru memilih menceburkan diri ke tengah pekatnya salah satu soal politik paling kontroversial di AS. Ia tidak melarikan diri dari dunia politik dengan permakluman bahwa ia hanyalah seorang ilmuwan sastra. Ia abdikan sebagian besar waktunya untuk menulis analisa politik dan berceramah tentang perjuangan bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ia menjadi juru bicara bangsa Palestina yang paling ternama karena ia penulis yang demikian cerdas dan pembicara yang mengesankan. Bahkan esai-esai politiknya yang ditulis cepat pun senantiasa tampil anggun. Said berhak memperoleh penghormatan besar untuk keberaniannya menghadapi kampanye pelecehan dirinya yang diluncurkan golongan Zionis sayap kanan. Dalam pandangan picik orang-orang yang disebut “pendukung” Israel di AS (kadang-kadang pandangan mereka lebih ekstrim daripada opini publik di Israel sendiri), siapa pun yang berbicara atas nama bangsa Palestina sama dengan mendukung terorisme. Sebuah jurnal sayap kanan menerbitkan artikel tentang Said yang berjudul “Dosen Teror”. Jurnal yang sama, Commentary, menerbitkan satu karangan penuh fitnah lagi pada 1999 yang menuduh bahwa Said ternyata bukan orang Palestina! Bahwa penulisnya menghabiskan tiga tahun meneliti kehidupan Said (dan memperoleh sebagian besar fakta yang salah) menunjukkan betapa besar kebencian kaum Zionis terhadap Said. Mereka menyadari bahwa pria rasional dan terdidik yang fasih berbicara tentang masalah Palestina ini adalah musuh terburuk mereka. Said memupuk keberanian dari keyakinan kuatnya. Ia tidak ragu-ragu mengkritik pemimpin-pemimpin Arab dan Palestina. Kritiknya terhadap Arafat dan Perjanjian Oslo 1993 membuat tulisan-tulisannya dilarang oleh Penguasa Palestina yang berumur pendek. Argumen Said belakangan terbukti benar: Perjanjian Oslo adalah kesalahan yang tragis dan mengkhianati perjuangan massa kaum Intifada. Dari seluruh karya Said, buku yang paling saya gemari adalah After the Last Sky (1986). Teks dan foto-foto hasil bidikan Jean Mohr yang menghiasinya secara sensitif mengangkat kehidupan orang Palestina dalam seluruh keberagaman dan tragedinya. Bagi suatu bangsa yang secara rutin ditidakmanusiakan dalam media massa utama, buku ini merupakan penggambaran OBITUARI
cemerlang kemanusiaan mereka. Di ekstrim yang lain, buku yang paling tidak saya senangi justru buku yang membuatnya terkenal, Orientalism. Pandangan dasar Said (atau pandangan dasar yang saya tarik dari buku itu) benar – pengetahuan Barat tentang Timur Tengah cenderung membangun imej tentang “masyarakat Islam” yang kasar, ahistoris, dan monolitik. Tapi sanggahan pendukungnya di banyak bagian tidak konsisten, membingungkan, dan salah. Said membuka lahan pemikiran baru dengan Orientalism sehingga tak terlalu mengherankan kalau argumennya tidak sepenuhnya mantap. Yang lebih penting adalah buku ini memancing pengkajian ulang — yang memang sangat dibutuhkan — tujuan studi kebudayaan di Barat dan kaitannya dengan imperialisme. Dalam tulisan-tulisan berikutnya, Said mengolah kembali dan mempertajam argumenargumennya. Dalam salah satu esai yang ia tulis menjelang akhir hayatnya,“Dignity, Solidarity and the Penal Colony” (2003), Said mencoba, seperti yang ia lakukan berulangkali sebelumnya, memperbaiki kesalahpahaman Barat terhadap orang Palestina sebagai agresor dan teroris: “Di Barat, ada perhatian berlebihan dan tidak mendidik terhadap bom bunuh diri oleh orang Palestina sehingga distorsi parah terhadap realitas telah mengaburkan apa yang lebih buruk: kejahatan resmi Israel, dan mungkin juga khas [Ariel] Sharon, yang sudah ditimpakan secara sengaja dan terarah pada rakyat Palestina. Bom bunuh diri itu salah tapi menurut pendapat saya tindakan itu merupakan akibat langsung dan terprogram, yang secara sadar dilakukan, dari tahun-tahun penuh perlakuan buruk, ketidakberdayaan dan keputusasaan.” Sejak menguasai Jalur Gaza dan Tepi Barat secara militer pada 1967, Israel sudah membiarkan penduduk wilayah tersebut dalam ketidakpastian: mereka bukan warga negeri mereka sendiri juga bukan warga negara Israel. Saat ini, dengan pagar dan pos penjagaan di sekeliling mereka, mereka sudah menjadi tawanan di sebuah penjara besar yang terbuka. Said menulis: “Sesekali kita perlu ambil jeda dan menyatakan dalam kemarahan bahwa hanya ada satu sisi dengan tentara dan negara: di sisi yang lain adalah penduduk tak bernegara, terampas hartanya, tanpa hak atau cara apa pun untuk melindungi diri mereka.” Pemerintahan Jendral Sharon menginginkan“tak lebih dari pemusnahan seluruh masyarakat dengan cara penyekapan, pembunuhan langsung, media mediakerjabudaya. kerjabudaya.edisi edisi1111tahun tahun2003 2003
dan mencekik kehidupan sehari-hari secara pelahan-lahan dan sistematik.” Said mengakui bahwa masa depan bangsa Palestina suram. Sedikit sekali perlawanan di Israel, “yang jiwanya sudah terperangkap kegilaan terhadap tindakan menghukum yang lemah, demokrasi yang dengan setia mencerminkan mentalitas psikopat penguasanya, Jendral Sharon.” Sedikit sekali perlawanan di wilayah pemberi dana bagi Israel, Amerika Serikat. Dan sedikit sekali dukungan dari pemimpin-pemimpin negara Arab yang, menurut Said, tidak mewakili masyarakat Arab: “mereka begitu hebatnya meremehkan kemampuan mereka sendiri dan kemampuan rakyatnya sehingga membuat mereka tertutup, intoleran dan takut perubahan.” Pemimpin-pemimpin Palestina sendiri, Arafat dan lingkarannya, sudah sedemikian mengecewakan rakyatnya, dan, dalam ambisi mereka meraih kekuasaan, lupa bahwa mereka mewakili perjuangan popular. Mereka sudah direndahkan menjadi “gabungan antara penolakan kekanakkanakan yang salah tempat dan permohonan menghiba yang tak berdaya.” Tetapi Said melihat secercah harapan justru dari kenyataan bahwa gerakan perlawanan rakyat Palestina tetap bersikukuh. Bangsa ini terus menerus menghadapi bencana sejak 1948 dan selalu menemukan cara untuk bertahan. Bagaimana pun mengenaskannya situasi mereka, tidak ada pilihan lain kecuali melanjutkan perlawanan. Bagi mereka di luar Palestina, tak ada pilihan lain pula kecuali melanjutkan tindakan-tindakan solidaritas yang konstruktif,“Secara khusus orang seharusnya menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk keadilan, bukan melempar kritik melelahkan dan berkepanjangan, komentar mengecilkan hati yang membuat frustrasi, atau tindakan memecahbelah yang melumpuhkan. Ingatlah solidaritas di sini [di AS, red.] dan di berbagai tempat di Amerika Latin, Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Dan ingatlah juga akan kerja bersama yang menjadi tumpuan komitmen begitu banyak orang walaupun ada kesulitan dan halangan yang mengerikan. Mengapa? Karena perjuangan rakyat Palestina berjalan dengan prinsip yang adil, cita-cita yang luhur, tuntutan moral untuk kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.” 0 John Roosa, dosen sejarah Asia di Universitas British Columbia, Vancouver, Kanada
35 35
36
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
PAT GULIPAT
PAT GULIPAT
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
37
Nyanyian Perempuan Amerika bagi Pembebasan
Umi Lasmina
L
agu adalah ramuan melodimusik dan lirik yang melahir kan kemenyatuan antara mereka yang mendengarkan dengan “apa” yang didengarkan. Seperti halnya media lain yang menjembatani satu atau beberapa orang dengan orang-orang lainnya, lagu sejak dulu menjadi media yang lebih banyak merepresentasikan suara, pengalaman, dan sejarah laki-laki. Apa boleh buat, faktanya perempuan bisa secara bebas bersentuhan dengan media ini secara massal (ada interaksi antara perempuanmusik-perempuan-musik-perempuan banyak) baru-baru ini saja. Berarti suara, pengalaman, rasanya pun sudah merepresentasikan perempuan. Perempuan, karena seksualitasnya, memiliki ciri yang berbeda dari laki-laki. Salah satu diantara ciri-ciri tersebut berwujud fungsi biologis: perempuan memiliki rahim, maka ia harus melahirkan, mengurus anak, dan menjaga keseluruhan tubuhnya agar laki-laki tidak tergoda padanya. Karena laki-laki tidak melahirkan, maka ia harus bekerja mencari nafkah. Ia tidak harus mengurus anak dan rumah tangga. Harus-harus inilah yang membelenggu manusia. Padahal manusia hidup dalam pilihan bebas untuk menuju kebahagiaan masing-masing.
38
Perempuan tentunya tidak tinggal diam. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mendobrak kungkungan terhadap dirinya, antara lain melalui gerakan sosial yang berideologi feminisme. Perempuan yang ikut dalam gerakan ini memakai berbagai media untuk menyebarkan gagasan pembebasan. Lagu adalah salah satu media pembebasan, sekaligus media perlawanan. Karena lagu seperti media lainnya yang ada di bumi, seringkali juga menyuarakan nilai yang menyudutkan perempuan. Maka lagu, selain menjadi teman dalam gerakan yang mengiringi semangat perempuan, juga menjadi alat perlawanan terhadap lagu-lagu yang diciptakan laki-laki untuk merendahkan perempuan. Lagu-lagu ini biasanya lahir secara kolektif, bersamaan dengan jalannya gerakan perempuan, dan dinyanyikan pada saat aksi. Lagu inilah yang bisa disebut sebagai musik perempuan. Margie Adams, musisi peraih Award dari National Women’s Music Festival, menyatakan, “Musik perempuan adalah musik yang mengafirmasi dan memberdayakan perempuan, dibuat oleh perempuan untuk siapa saja, terutama perempuan dan laki-laki pro-feminis.” Bagi saya pribadi, musik perempuan memiliki melodi yang menenangkan dan memiliki mayoritas nilai feminin (kelembutan, media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
kedamaian, berbicara cinta, dan berbicara dengan hati). Tak heran melodi yang lahir pun bernuansa jazz, terutama mainstream jazz dari New Orleans, folk, dan orkestra. Lagu-lagu yang lahir dari gerakan antara lain dinyanyikan pada saat Konvensi Perempuan I di Seneca Falls, Amerika, di 1840an. Lagu yang dilantunkan mencerminkan harapan dan perubahan posisi dan peran perempuan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan untuk bersuara. Seperti yang diciptakan D. Estabrook, Keep Woman in Her Sphere [Biarkan Perempuan di Ruangnya]: Aku bertanya padanya, “Bagaimana dengan hak-hak perempuan?”/Ia menjawab dengan nada serius/”Pandanganku tentang hal itu sudah mantap,/Biarkan perempuan di ruangnya.”/Aku melihat seorang lelaki berpakaian compang-camping/Keluar dari toko kelontong/Ia habiskan seluruh uangnya untuk minuman keras/dan biarkan istrinya kelaparan di rumah/Aku bertanya padanya “Tidakkah perempuan seharusnya memilih”/Sambil menyeringai ia menjawab—/”Aku sudah mengajar istriku agar tahu tempatnya,/Biarkan perempuan di ruangnya.”/Aku bertemu seorang lelaki yang tulus dan penuh perhatian/Beberapa hari yang lalu/Yang berpikir dalam tentang segala hukum ESAI
ISTIMEWA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Tracy Chapman dan Suzanne Vega
manusia/Kebenaran paling jujur yang perlu diketahui/Aku bertanya padanya “Bagaimana dengan kepentingan perempuan?”/Jawabannya sungguh-sungguh — /”Hak-hak mereka sama dengan hak-hak ku,/Biarkan perempuan memilih ruangnya.” Lagu lain muncul saat gerakan perempuan 1960an muncul dengan deklarasi Blue Stocking Manifestonya. Beginilah lirik lagu yang dinyanyikan: Pembebasan perempuan sudah tiba/laki-laki tak lagi bisa putuskan segala/tentang jika dan bagaimana dan di mana dan kapan/di akhir hari yang melelahkan.// Karena perempuan pun inginkan bagiannya yang adil/dalam kesenangan pun upah /tapi ia tetap ingin menjadi majikan/maka ia pun balikkan badan// Lirik ini mencerminkan perjuangan persamaan upah dan kesenangan. Diangkat pula soal seksualitas …/ketika tiba saatnya bermain cinta di akhir hari yang melelahkan.//Ia akan bergerak tanpa pedulikan perasaan yang mungkin ia simpan/ sampai dalam perlawanannya ia katakan/sakit kepala yang jadi bahan tertawaan semua orang.// Dan/Ya.Tidak/ Ya.Tidak/Maaf aku sakit kepala// Pada masa ini pula digelar Michigan Womyn Music Festival 1974, yaitu per-
ESAI
tunjukan musik tahunan untuk perempuan oleh perempuan yang dilakukan di alam terbuka di atas tanah seluas 23 hektar yang dibeli 3 pendirinya. Festival musik ini diprakarsai oleh feminis radikal. Awalnya festival ini dimulai oleh feminis radikal hanya untuk perempuan yang mayoritas lesbian. Kini semakin banyak transgender (laki-laki menjadi perempuan) serta keluarga heteroseksual turut serta. Perencanaan akomodasi festival ini mencerminkan nilai-nilai feminin, misalnya dengan disediakannya akomodasi penginapan bagi mereka yang punya anak, membawa suami, dan hewan peliharaan. Selain pertunjukan musik, ada pula lokakarya mengenai berbagai topik musik dan sosial-budaya. Festival musik perempuan seperti ini tidak hanya ada di Michigan, tetapi juga di beberapa negara bagian lain di AS. Tetapi Michigan Womyn Music Festival yang paling kontroversial dan cukup bertahan lama. Pada 1990an lahir lagi festival musik yang diprakarsai penyanyi Sarah McLachan, yaitu Lilith Fair yang menggelar pertunjukan dari satu kota ke kota lain. Berbeda dengan festival musik perempuan 1960an-1970an, Lilith Fair ini memiliki keterkaitan langsung dengan dunia industri rekaman. Festival ini juga
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
bekerja sama dengan berbagai perusahaan, mulai dari sabun hingga celana jeans. Meskipun begitu, saya menganggap festival ini sebagai bagian dari gerakan karena memiliki konsep pemberdayaan perempuan, pembebasan, dan persaudaraan. Apalagi Lilith Fair hadir untuk melawan Lollapoloza, sebuah festival musik rock yang didominasi penyanyi laki-laki yang macho, sehinga tak memberi ruang bagi perempuan. Lilith Fair Festival juga mengadakan lomba menyanyi dan bermusik bagi perempuan. Pemenangnya tampil dalam festival bersama musisi perempuan terkenal. Dana yang didapat dari penjualan tiket disalurkan bagi Rape, Abuse, & Incest National Network (RAINN), layanan hotline nasional bagi korban perkosaan, incest, dan kekerasan domestik; LIFEbeat, sebuah organisasi penelitian dan peningkatan kesadaran tentang HIV/ AIDS; dan Rumah Suaka perempuan di tingkat lokal. Penyanyi yang turut dalam festival ini penyanyi 1980-1990an seperti Jewel, Nathalie Merchant, Tori Amos, Sheryl Crow, Nelly Furtado, serta penyanyi veteran seperti Bonnie Raitt, Joan Baez, dan lain-lain. Penyanyi Indonesia, Anggun C. Sasmi, juga pernah ikut menyanyi di Lilith Fair Festival.
39
Disini lagu-lagu untuk pembebasan perempuan dilantunkan, dengan penuh suka cita, kesadaran, dan kesyahduan sehingga para penonton perempuan yang hadir pun merasa bahagia karena mendapatkan kepercayaan diri yang lebih kuat sebagai perempuan. Musik perempuan sejak 1970an adalah upaya mengembalikan kontrol atas diri perempuan, mendefinisikan serta menampilkannya melalui musik. Ada pula tujuan memberdayakan perempuan dengan mendirikan sendiri perusahaan rekaman, melatih perempuan menjadi teknisi, atau pekerja ahli di media massa. Musik tidak hanya memberi inspirasi, tapi juga memberi ruang bagi potensi perempuan. Perusaan rekaman yang dirintis penyanyi perempuan, seperti Ani Di Franco, Carole King, dan Madonna, semakin banyak. Suara-suara Individu Musisi dan penyanyi perempuan sebagai individu juga telah menyumbangkan suara dan bunyi yang menceritakan pengalaman pribadi, teman, saudara, atau orang lain. Kemampuan mereka menyerap, kemudian memuntahkan kembali apa yang diserap melalui lagu luar biasa. Apalagi lagu tersebut mampu menyentuh nurani jutaan orang di dunia. Di sinilah musisi perempuan memiliki kesadaran untuk menciptakan lagu yang selain menjadi ekspresi pribadi, juga ekspresi perempuan lain. Ini menunjukkan fakta yang tak dapat dipungkiri: perempuan memiliki banyak persamaan oleh sebab seksualitasnya. Keserupaan pengalaman ini, misalnya, dituturkan dalam lagu yang ditulis Suzanne Vega dan Tracy Chapman tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam lagunya Luka, Suzanne Vega mengungkapkan “/Jika kamu mendengar sesuatu saat larut malam/Seperti ada masalah seperti ada perkelahian/Jangan tanya padaku apa itu/ Mereka hanya memukul sampai kamu menangis/ Dan setelah itu jangan kamu bertanya kenapa/Kamu tak berdebat lagi/…Tracy Chapman dengan Behind the Walls [Di Balik Dinding]: Tadi malam aku mendengar teriakan/Suara-suara keras di balik dinding../Dan ketika mereka tiba/Mereka bilang mereka tak bisa ikut campur/Dalam urusan domestik/Antara lelaki dan istrinya/Dan ketika mereka berjalan keluar/Air mata mengembang di pelupuknya.// Kedua lagu tersebut mencerminkan interaksi perempuan (penulis lagu dan 40
penyanyi) dengan dunia yang penuh dengan kekerasan bagi perempuan dan anak-anak. Tori Amos, penulis lagu dan penyanyi yang pernah mengalami perkosaan menuliskan pengalamannya dalam lagu Me and A Gun [Aku dan Pistol]: Jumat pagi jam lima/Adalah Aku dan Pistol dan Lelaki di belakangku/Aku nyanyikan Holy.Holy/Saat ia membuka ritsleting celananya .. aku dan pistol/ .Tapi aku belum melihat Barbados jadi aku harus lolos dari ini/Kukenakan barang merah yang lembut/ tak berarti aku harus mengangkang, untukmu dan teman-temanmu, bapakmu Mr. Ed//Lagu ini dilantunkan dengan hymne acapella tanpa musik, bagi seorang perempuan yang pernah mengalami percobaan perkosaan atau perkosaan pasti bisa merasakan apa yang dirasakan Tori. Ada banyak kisah kegetiran dan kegalauan hidup sebagai perempuan yang dilantunkan dalam nyanyian yang diciptakan perempuan termasuk juga oleh Madonna. Tak banyak media mengungkap sisi lain penyanyi ini. Mungkin karena kita terperangkap oleh penampilannya yang eksploitatif, hingga tak mau tahu bahwa ia pernah mencipta lagu What it Feels Like for A Girl [Bagaimana Rasanya bagi Seorang Gadis]: ”Dan memotong pendek rambutnya / Memakai kemeja dan sepatu bot/Karena tak apa menjadi laki-laki/Tapi bagi lakilaki kelihatan seperti gadis itu merendahkan/Karena kamu berpikir menjadi gadis itu memalukan/Tapi di dalam hati kamu ingin tahu bagaimana rasanya/Bukankah begitu/Bagaimana rasanya bagi seorang gadis/. Atau lagunya Love Makes The World Go Round [Cinta Membuat Dunia Berputar] yang ditulis bersama Pat Leonard:Kita bilang main cinta bukan perang/Mudah diulang/Tapi tak berarti apa-apa/Kecuali kalau kita akan bertarung/Tapi bukan dengan pistol dan pisau/Kita harus selamatkan hidup/ Setiap anak lelaki dan perempuan/Yang tumbuh besar di dunia ini. Masih soal pengalaman sebagai perempuan, Sinead O’Connor dan Nathalie Merchant menulis lagu tentang menjadi ibu. Sinead dalam All Babies [Semua Bayi]: Semua bayi lahir dari kesakitan luar biasa/Semua bayi lahir sambil ucapkan nama Tuhan/ Ia dengarkan jeritan mereka ia adalah ibu dan ayah// Semua bayi menangis/. Sedangkan Nathalie dalam lagunya Eat For Two [Makan untuk Dua Nyawa] bahkan juga media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
bercerita bagaimana konsepsi terjadi, Baiklah, lelaki telur jatuh dari rak/Lelaki para raja terbaik dengan bantuan mereka berjuang mati-matian demi sebuah cangkang yang tak bisa mereka rekatkan kembali/Kamu tahu kemana ini akan berlanjut, ke buaian di ruang bayi/ke tendangan di dalam tubuhku/Kebodohanku tumbuh di dalam aku/Aku makan untuk dua nyawa, berjalan untuk dua nyawa, bernafas untuk dua nyawa sekarang/Kebanggaan untuk lelaki, sedangkan gadis muda harus berlari dan sembunyi/Ambil resiko permainan dengan berani katakan “ya”. Lagu-lagu yang dilahirkan perempuan selain mengenai kegalauan tentunya juga membawa harapan dan semangat untuk perjuangan, seperti lagu Jewel, Life Uncommon [Hidup yang Tak Biasa], yang diciptakan khusus untuk tantenya Jacqie, seorang aktivis feminis dan lingkungan hidup: Jangan khawatir ibu, semua akan baik-baik saja/jangan khawatir saudariku tidur lelap/Kita dipersenjatai dengan keyakinan/Kita lelah kita khawatir tapi kita tidak aus// Penyanyi provokatif lainnya yang sering menyuarakan pembebasan kemanusiaan dan perempuan adalah Michelle Shocked, yang pernah dipenjara karena protes menentang pemerintah. Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan perempuan bukan tanpa kaitan dengan lagu yang diciptakan laki-laki. Meskipun media popular tak begitu memperhatikan perkembangan lagu perempuan, kenyataannya semakin banyak penyanyi dan pencipta lagu perempuan yang lahir dan terus berkembang dengan inspirasi dari penyanyi, lagu, dan festival. Penyanyi perempuan semakin mampu memberi inspirasi bagi kepercayaan diri banyak perempuan dan memberi ruang bagi pembebasan perempuan. Tak heran MTV menghadirkan MTV Fan-Atic. Tentunya selain ada bumbu komersil dan industri, kehadiran penyanyi dan pencipta lagu perempuan dibutuhkan untuk penghargaan diri dan panutan bagi perempuan muda. 0 19 April 2003 Umi Lasmina, aktifis feminis, tinggal di Jakarta
ESAI
omongkosong apalagi dimainkan dalam perjanjian, kesepakatan; damaikah hati?
mengucap fatwa dari telepon genggam: tiada siapa dapat membunuh siapa tidak diri menjadi tanpa adaptasi inilah warkah sebuah negeri yang hancur terombangambing laut malaka
mae dan isteri melaok eungkot payeh menjaja sepanjang bibir-bibir
Banda Aceh, 29 September 2002
dodaidi meninabobokan** mimpi omongkosong apalagi dimainkan tersebab hukom bak syiahkuala qanun bak putroe phang adat bak potomeureuhom resam bak bentara mae dan isteri menjaja sampai jauh ke dalam mae dan isteri hilang SEMSAR SIAHAAN
PUISI DIN SAJA
FRAGMENTASI OPERA EUNGKOT PAYEH*
eungkot payeh terbungkus rapi atas jembatan Banda Aceh, 21 Desember 2002 *eungkot payeh = ikan pepes **dodaidi = lagu menidurkan anak di Aceh
KEPADA “R” YANG TERCINTA
WARKAH SEBUAH NEGERI YANG HANCUR inilah secarik warkah sebuah negeri yang hancur belantara yang sunyi dikirim melalui selat malaka, entah berlabuh di mana
untuk sementara kita pisah dulu sambil segarkan kenangan yang kita tak pernah ada didalamnya sambil merebahkan diri ditikarpandan dihalaman rumah dibawah pohon jambu sambil dengarkan kicau burung-burung jerit anak-anak dikejauhan tidakkah kau dengar lenguh kerbau ngingatkan untuk sebuah kehidupan dengkur kuda bermimpi melintas padang-padang baris berbaris semut memacu waktu
dihempasan ombak warkah bawa pesan sebuah negeri yang hancur kampung halaman, identitas tercabik darah kebencian mendendam
karena perpisahan merupakan harapan untuk mastikan hidup bukan tujuan
semalam lakseumana keumalahayati memberi pesan lewat sms: biarkan bibir pantai perahu amatrhangmanyang melaut samudera kapal-kapal berlayar arung kehidupan
dengan hati sabar rindu mendendam kita ulur waktu dalam kehidupan
waktu bersamaan tjoet nyak dhien menyampai kesal melalui faksimil: mengapa iskandarmuda memimpin negeri lilawangsa dan teuku umar jadi pecundangnya
mari kita pisah putih hitam dulu Banda Aceh, 10 September 2002
dalam pula itu abu beureueh Din Saja, penyair menetap di Banda Aceh media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
41
KRITIK SENI
PUNK DI INDONEI
S I N A D A Y A ANTARA G SIA Resmi Setia M.S
Sekilas Sejarah Perkembangan Punk Inggris dan Amerika Pengertian punk seringkali diartikan secara berbeda-beda, dari mulai anak muda hingga para manejer perusahaan yang sering nongkrong di pub. Lebih jauh punk juga diartikan sebagai orang yang ceroboh, sembrono, dan ugal-ugalan hingga sekelompok pemuda bergerak menentang masyarakat mapan dengan menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang khas. Craig O’Hara dalam The Philosophy of Punk (1999) mendefinisikan punk lebih luas, yaitu sebagai perlawanan “hebat” melalui musik, gaya hidup, komuniti dan mereka menciptakan kebudayaan sendiri. Di Indonesia media massa memberikan definisi awal begitu umum dan memberikan deskripsi populer terhadap punk. Sedangkan definisi terakhir mungkin lebih mampu menggambarkan punk sesungguhnya walaupun terasa berat jika disandang oleh punkers di Indonesia yang sebagian besar masih memahami punk sebatas sensasi bukan esensi. Terdapat berbagai perdebatan mengenai masalah waktu dan tempat lahirnya punk. Apakah dari New York Scene pada akhir tahun 1960an/awal tahun 1970an atau di Inggris tahun 1975-1976? Namun tidak ada satu pun dapat melacak lebih jauh sebagai suatu bentuk gerakan politik sampai akhir tahun 1970an. Pada
42
Anarchism, the revolutionary idea that no one is more qualified than you are to decide what your life will be (Days of War Nights of Love)
musim panas tahun 1976 di Inggris muncul suatu bentuk “budaya” baru mengingatkan pada mods dan rockers di tahun 1960an. Ini adalah punk rocker berasal dari punk rock, sejenis dengan musik new wave yang berkembang di Amerika Serikat. Majalah Melody Maker mendefinisikan punk (Inggris) tidak begitu perduli dengan penataan musik, namun cenderung pada musik pemberontak. New wave adalah jenis musik lebih kurang hampir mirip dengan irama lebih meyakinkan. Hal ini mencerminkan perbedaan antara musik rock Inggris dan Amerika. Di Inggris, musisi-musisi amatirnya bersemangat dan kurang memiliki teknik bermusik tapi memiliki keberanian tampil di panggung. Sedangkan musisi Amerika lebih memiliki keahlian dalam bermusik tapi tidak berani tampil seperti halnya musisi amatir Inggris. Grup-grup pengusung musik punk rock berkembang di pub-pub dengan berbagai gaya rambut dicat dengan warna-warna mencolok dan gaya berpakaian yang didasari oleh ide perbudakan dan seksual fetisisme (Lihat Brake, 1980: 80). Para grup musik pengikut punk menciptakan suatu penampilan yang liar dan menyerukan bahwa tidak ada masa depan, pekerjaan, dan prospek yang suram (Brake, 1980: 81). Tricia Henry melalui bukunya Break All Rules (dalam O’Hara, 1999: 26-27) mempertegas hal ini dengan
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
menyatakan bahwa pengangguran dan kondisi sosial begitu buruk membangkitkan kemarahan dan sikap frustasi. Perasaan-perasaan ini diekspresikan dengan berbagai cara. Kejahatan merupakan tanggapan yang paling populer dilakukan. Hubungan antara fenomena punk dan ketidakseimbangan ekonomi-sosial di Inggris menegaskan kesahihan filosofi pendukung gerakan punk. Pada dasarnya gerakan punk di Inggris muncul dari serba kekurangan yang dirasakan oleh kelas pekerja. Banyak dari mereka menggunakan punk sebagai media untuk mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuasan. Sejak akhir tahun 1970-an, punk telah berkembang menjadi suatu gerakan politik dan tidak hanya menekankan pada gaya berpakaian dan musiknya saja. Punk lebih menjadi gaya hidup dengan salah satu filosofinya, do-it-yourself (DIY). Mark Andersen dalam bukunya Positive Force Handout (dalam O’Hara, 1999: 36) menyatakan : “...Punk bukan sekedar fashion, gaya berpakaian, masa pemberontakan pada orang tua, trend atau jenis musik terbaru. Punk adalah gagasan yang dapat menuntun dan memotivasi hidup. Apa itu gagasan? Berpikir untuk diri sendiri, menjadi diri sendiri, menciptakan aturan sendiri dan hidup untuk diri sendiri”. Konsep DIY erat kaitannya dengan
KRITIK SENI
filosofi punk memudar dan bahkan menghilang. Punk dianggap fashion dan musik saja. Band-band yang mengklaim sebagai pengusung punk rock, seperti Green Day, Offspring, Helmet, Sum 41, dsb., semakin mempercepat pergeseran makna punk dari anti-kapitalis menjadi pro-kapitalis. Hal ini tampak dari lirik-lirik lagunya sama sekali tidak mencerminkan makna punk dan bergabungnya band tersebut dengan perusahaan-perusahaan rekaman multinasional dan dikenal dengan istilah sell out semakin menegaskan jauhnya mereka dari filosofi punk.
Masuk, Berkembang dan Memudarnya Punk di Indonesia Musik punk rock mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-an, namun belum dikenal secara meluas karena pemasaran kasetnya masih terbatas. Pada tahuntahun berikutnya peredaran kaset punk rock mulai meluas, diawali dengan saling meng-copy kaset di antara para penggemar musik punk rock sampai akhirnya beredar secara bebas dipasaran. Hingga awal tahun 1990an penggemar musik punk rock semakin bertambah terutama di kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Berawal dari sekedar mengikuti fashion band punk rock idolanya, seperti The Sex Pistols, The Exploited, The Clash, The Varukers, sampai lebih mendalami makna punk. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang pelopor punk/hardcore di Bandung, “berawal dari seorang poser atau orang yang ikut-ikutan hingga lebih mendalami sub-kultur punk”. Terdapat dua jenis poser. Pertama mereka senantiasa tertinggal informasi terbaru tentang
punk, sedangkan poser yang kedua mencari informasi lebih terperinci dan tidak lagi menjadi ikut-ikutan (Wardiman, 1999). Perkembangan komunitas punk di Indonesia sangat didukung oleh terbukanya media informasi, seperti internet, televisi dan majalah, pertumbuhan industri musik, kelonggaran perijinan penyelenggaraan pertunjukan musik, dan munculnya pusat-pusat interaksi perbelanjaan, seperti mall dan tempat kumpul gratis lainnya. Hingga 1996 punk masih dimaknai sebatas musik dan fashion karena merupakan unsur paling mudah diterima. Di Indonesia, punk tidak lahir dari suatu kondisi ekonomi dan sosial yang timpang tapi lebih sebagai sebuah trend musik dan fashion baru bagi remaja. Mereka hanya menjadikan punk sebagai sebuah sensasi dengan melengkapi masa perkembangan hidupnya. Masuknya punk ke Indonesia diikuti dengan bermunculannya berbagai band punk rock dan gaya ala punk rocker. Rambut yang dicat warna-warna mencolok dengan model mohawk, model paku, dsb. Berbagai atribut menghiasi pakaian serta tubuh seperti spike atau paku, rantai serta peniti dikenakan di telinga, bibir semakin menegaskan perbedaan gaya penampilan remaja penggemar musik punk rock dengan remaja pada umumnya. Gaya penampilan punkers di Indonesia tidak berbeda dengan negara asalnya, Inggris dan Amerika. Demikian pula dengan musik dan liriknya, pengusung musik punk rock di Indonesia terutama di Bandung lebih mendekati musisi punk
sumber foto: www.thescriptorium.net
anarkisme. Kondisi pendorong utama munculnya anarkisme dalam gerakan punk adalah iklim pemerintahan dan sistem hirarki yang mengakibatkan tekanan dan eksploitasi terhadap orang-orang di dalamnya. Sistem Kapitalisme dan berbagai masalah terangkat kepermukaan, seperti ketimpangan ekonomi semakin mendorong munculnya anarkisme menjadi dasar pijakan gerakan punk. Grup band pertama dengan mengusung paham anarki adalah band punk Inggris, Crass. Menurut mereka anarki adalah bentuk pemikiran dengan initisari tidak mencoba mengontrol orang melalui pemaksaan dan kekuatan. Anarki juga merupakan penolakan terhadap kontrol negara dan melambangkan tuntutan individu untuk hidup dan bebas menentukan pilihan. Anarki dirumuskan bukan sebagai kerusuhan dimana semua orang keluar dari diri mereka sendiri, tapi bagaimana individu hidup dengan orang lain dalam suatu kepercayaan dan toleransi (lihat Crass dalam O’Hara, 1999). Gerakan punk tidak terlepas dari bermunculannya berbagai fanzines, seperti Maximum Rock N’ Roll, Flipside, dsb. Mereka termotivasi oleh fanzines muncul tahun 1970an, yaitu Sniffin Glue dari Inggris dan Punk dari New York. Kedua fanzines ini dapat menghubungkan jaringan punk di seluruh dunia (O’Hara, 1999). Fanzines merupakan salah satu media komunikasi punk yang menegaskan budaya dan filosofi punk. Dalam perkembangannya saat ini, banyak terjadi pergeseran dalam gerakan punk. Banyak band punk rock membuat
KRITIK SENI
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
43
rock Inggris yang kurang menguasai teknik bermusik tapi memiliki keberanian tampil di atas pentas. Meskipun punk di Indonesia tidak lahir dari kondisi tertentu tapi lirik-liriknya tetap mengekspresikan kepedulian terhadap kondisi politik, sosial, dan lingkungan. Seperti lirik lagu sebuah band asal Bandung yang berjudul “Berontak”: “Seperti kita ketahui, yang nyata telah memperlihatkan tanda-tanda usang dan koyak. Anda berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan kini baru, segar tak tertandingi. Anda dapat menjadi pahlawan buruk rupa atau penjahat berhati mulia. Orang besar sering bersikap seperti raksasa dan terlalu ingin dihormati, hidup rakus, tamak, kalau bisa merampas. Meski berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Sungguh itu suatu kebodohan. Apabila mereka yang berkedudukan dan terhormat mencuri kau diamkan saja, tetapi ketika rakyat kecil yang melakukannya dijatuhi hukuman yang semestinya. Namun kebijakan ternyata agak berseberangan. Sebagai kaum minoritas jangan biarkan para penjilat itu menindas kita, lawan, lawan, bangkit, hancurkan mereka.” Kemunculan band punk rock, didukung oleh maraknya pertunjukan musik underground, mulai mendapat tempat lebih luas dikalangan remaja. Di Bandung dapat diidentifikasi beberapa pelopor acara musik underground seperti Hullaballoo yang diadakan selama tiga tahun berturut-turut kemudian diikuti oleh acara musik lainnya seperti Gorong-gorong, Campur Aduk, Bandung Underground, dsb. Motivasi awal diadakannya acara musik ini adalah keinginan untuk memiliki sarana bermusik bagi para pengusung musik underground. Biaya penyelenggaraan diperoleh dari iuran atau sumbangan panitia penyelenggara, biasanya berasal dari kelompok pertemanan serta mempunyai kegemaran terhadap musik underground. Hasil penjualan tiket biasanya dibagikan kepada seluruh panitia atau dijadikan modal untuk membuat acara serupa. Pada 1997-2000, di Bandung hampir setiap minggu diadakan acara musik underground dan motivasi penyelenggaraan acara musik itu sendiri menjadi bergeser ke arah lebih komersial. Semakin bertambahnya penggemar musik underground dianggap sebagai peluang cukup menguntungkan oleh enterprise dan sengaja mencari keuntungan materi melalui penyelenggaraan acara musik underground. Hal ini mulai mendapat
44
tanggapan cukup keras dari komunitas punk/hardcore di Bandung yang ditulis dalam newsletter “Submissive Riot” (1998); “...fuck off! Mereka tidak lain adalah enterprise yang menyelenggarakan acara komersil/kapitalistik yang berkedok musik-musik antikomersial. Kenapa mereka memasang tiket dengan harga tinggi padahal musik yang ditampilkan adalah musik-musik kaum working class… Kenapa mereka tidak menyelenggarakan saja konser musik pop?… kenapa mereka menolak membayar band-band yang ingin tampil dengan bayaran yang pantas? Mungkin karena mereka ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya…” Pertengahan hingga akhir tahun 1990an merupakan puncak kejayaan musik underground Bandung, termasuk punk rock. Kehadiran mereka sangat mencolok di pusat-pusat keramaian dari mulai pertunjukan musik, pusat pertokoan, hingga jalanan. Masyarakat menanggapinya secara berbeda-beda mulai dari merasa terganggu hingga menganggap tidak ada bedanya dengan remaja lainnya kecuali fashion-nya saja. Pro dan kontra terhadap kehadiran mereka tidak membuat mereka surut. Jaringan mereka meluas ke daerah lain bahkan negara lain. Yogyakarta, Malang merupakan daerah komunitas punk-nya cukup berkembang dan memiliki hubungan cukup erat dengan komunitas punk di Bandung. Pertukaran informasi terjadi melalui internet, fanzines/ newsletter dan kaset yang diproduksi oleh individu maupun kelompok. Tigabelas zines dan Submissive Riot merupakan fanzines/newsletter, generasi pertama di Bandung. Fanzines/newsletter tersebut memuat masalah sosial, politik, lingkungan hidup, protes terhadap MNC’s, wawancara dengan band-band lokal hingga filosofi punk. Fanzines/newsletter dikemas dalam bentuk fotokopi, disisipi dengan berbagai macam foto, karikatur, dan informasi seputar band punk rock/hardcore. Fanzines/newsletter merupakan media informasi yang cukup efektif di kalangan komunitas punk. Sejak 2002, pertunjukan musik underground sudah mulai ditinggalkan karena penggemarnya yang mengalami kejenuhan. Musik undeground benar-benar kehilangan pamornya. Hal ini didorong oleh perubahan haluan musik para pendukungnya ke jenis musik lain yang sedang berkembang saat itu. Kelompok punk, biasanya tampak di pusat-pusat keramaian sudah mulai menghilang digantikan oleh kelompok-kelompok remaja lainnya. Baru-baru ini ada upaya
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
untuk memunculkan kembali acara musik tersebut, namun penggemarnya sudah semakin berkurang dan hanya berasal dari daerah-daerah pinggiran Kota Bandung. Penurunan pamor musik underground tidak serta merta menyurutkan kemunculan distro-distro yang menjadi tempat penjualan barang-barang komunitas underground, dari mulai aksesoris, t-shirt, kaset band underground lokal maupun luar negeri, hingga fanzines/ newsletter. Distro tersebut masih tetap eksis namun lebih berorientasi profit dan menjangkau pasar lebih luas. Bagaimana pun distro masih mempunyai keistimewaan sendiri karena menjadi media alternatif dari produk-produk kapitalis. Sebagian besar anggota komunitas underground tidak memahami inti dari gerakan underground, khususnya punk yang memerlukan konsistensi pendukungnya agar tetap eksis. Dari sisi kuantitas pendukung gerakan punk di Bandung mengalami penurunan. Tetapi dari kualitas pendalaman terhadap filosofi, punk mengalami kemajuan sangat berarti dari masa-masa sebelumnya. Namun, arah gerakannya lebih bersifat politis. Dinamika punk di Indonesia, khususnya Bandung, belum mewujudkan suatu bentuk perlawanan yang sesungguhnya, namun telah keburu memudar. Hal ini disebabkan gaya hidup punk senantiasa mensyaratkan kemandirian total, terlalu berat bagi sebagian besar anggotanya yang kehidupan sehari-harinya masih tergantung pada banyak pihak. Jalur masuknya gaya hidup punk melalui musik bagi sebagian besar remaja lebih dianggap sebagai hiburan daripada pedoman hidup, maka yang diadopsi unsurunsur luarnya saja. Lets making punk a threat again (profane existence). 0 Daftar rujukan: Brake, Mike. 1980. The sociology of youth culture and youth subcultures. London, dll: Routledge & Kegan Paul. O’Hara, Craig. 1999. The Philosophy Of Punk: more than noise. London, dll: AK Press. Resmi Setia. 2001. Punk sebagai Gaya Hidup Remaja: studi kasus pada kelompok punk di kota Bandung. Jatinangor: Jurusan Antropologi FISIP UNPAD. Wardiman, A. Arifin. 1999. Subkultur punk: sebuah tinjauan gaya dan pengembangannya terhadap produk jewelry. Bandung: FSRD ITB.
Submissive Riot. Edisi 3. 1998. Bandung.
Resmi Setia M.S., penulis menetap di Bandung
KRITIK SENI
sisipan 0
edisi 11 tahun 2003
MENGAJAK KORBAN BERKESENIAN? MENGAPA TIDAK?
P
ada 9-11 Mei 2003 telah berlangsung pertemu an antar korban kekerasan Orde Baru di Wisma Hijau, Cimanggis, Jawa Barat. Dihadiri sekitar 100 orang korban dari berbagai kasus dan wilayah, serta pengamat dari organisasi-organisasi yang berminat terhadap masalah pelanggaran HAM di masa lalu, pertemuan ini membicarakan persoalanpersoalan yang berkaitan dengan pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan bagi para korban. Karena tujuan utama pertemuan ini adalah memberi ruang bagi korban untuk menggali pemikiran mereka tentang langkah yang harus diambil untuk mencapai kebenaran dan keadilan, yang menjadi narasumber utama adalah para korban sendiri. Sedangkan aktifis pembela HAM yang terlibat dalam kepanitiaan semata-mata berfungsi sebagai fasilitator untuk melancarkan jalannya proses diskusi. Gagasan untuk menyelenggarakan temu korban yang melibatkan wilayah demikian luas sebenarnya sudah muncul sejak April 2001. Lewat sejumlah pertemuan awal di Bali, Jawa, Sulawesi dan Sumatra, korban dari peristiwa kekerasan yang berbeda-beda, seperti Tragedi 1965, Tanjung Priok, Lampung, 27 Juli 1996, Penculikan, Mei, dan Semanggi I dan II, berkesempatan untuk bertemu muka dan bertukar pikiran tentang langkah-langkah yang pernah dan perlu diambil untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Sedangkan keputusan untuk mengadakannya pada Mei 2003 berkaitan dengan rencana organisasi pendamping korban Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) bersama dengan Paguyuban Keluarga Korban Mei memperingati 5 tahun Tragedi Mei 1998. Dalam rapat-rapat persiapan acara disimpulkan bahwa Mei 1998 bukan hanya melahirkan korban, tetapi juga mengawali terbentuknya gerakan kemanusiaan yang menempatkan korban sebagai poros kekuatan utama. Dari sini lah muncul usulan agar acara Temu Korban dirangkai dengan sebuah Sarasehan Gerakan Kemanusiaan pada 12 Mei 2003 yang akan memberi kesempatan pada korban untuk menyampaikan hasil-hasil pertemuan mereka ke publik dan berdialog dengan kalangan masyarakat yang lebih luas. Dan, sebagai puncak acara adalah Peringatan 5 tahun Tragedi Mei 1998 pada 13 Mei 2003 di salah satu lokasi terjadinya pembakaran massal kaum miskin kota, yaitu Mal Citra (d/h Yogya Plaza), Klender. Panitia acara sejak awal menyadari bahwa tidak mudah menyelenggarakan serangkaian acara yang melibatkan ratusan orang selama 5 hari berturut-turut. Walaupun acara-acara tersebut sama dalam substansi, tapi mereka
berbeda dalam bentuk. Namun, munculnya tanggapan positif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kelompok-kelompok korban sendiri, pelahan-lahan mengurangi kekhawatiran panitia dan membuat langkah puluhan relawan yang terlibat dalam persiapan acara selama sebulan penuh semakin ringan. Satu hal yang tidak lazim dilakukan tapi kemudian cukup berpengaruh dalam membangun rasa setiakawan sepanjang acara Temu Korban dan acara-acara yang mengikutinya adalah mengajak para korban dan pendamping korban terlibat dalam kegiatan kesenian. Awalnya, panitia berencana mengundang seniman-seniman ternama untuk menghibur korban setelah lelah seharian berdiskusi tentang masalah-masalah yang pelik.Tapi, kemudian seniman PM TOH Agus Nuramal dan pekerja kebudayaan Erlijna mengusulkan agar kegiatan lepas malam ini dimeriahkan oleh korban sendiri. Mereka yakin bahwa jika diberi ruang dan waktu yang leluasa, para korban akan mampu mengungkapkan ekspresi artistiknya berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, Agus dan Erlijn mengusulkan agar korban tampil dalam sebuah pertunjukan untuk memperingati 5 tahun Tragedi Mei 1998. *** Pada hari per tama acara Temu Korban terasa ada kecanggungan dan kebingungan di kalangan peserta. Sebagian besar dari mereka sudah berusia lanjut, sementara anggota panitia bersama tampak masih muda dan bukan tokoh-tokoh publik ternama. Memang acara dibuka oleh Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara.Tapi setelah itu, praktis acara berlangsung tanpa kehadiran “yang dituakan”. Kemudian, dalam proses diskusi, semua korban harus belajar mendengarkan kisah dan pendapat sesama korban dari kasus yang berbeda-beda dan berusaha mencari rumusan bersama yang tidak lagi bertumpu pada kepentingan penyelesaian satu-dua kasus. Dan, mungkin yang paling membingungkan adalah ketika tim acara kesenian muncul di sore hari dan mengajak peserta menyanyi, membaca puisi dan menari. Salah satu peserta sempat bertanya pada panitia, “Mau dibawa kemana kita ini?” Toh, kebingungan ini tidak berlangsung lama. Dari percakapan di dalam dan di luar acara pokok korban mulai melihat bahwa di atas perbedaan masing-masing kasus kekerasan yang mereka alami ada persamaan dalam hal “nasib”: bahwa mereka teraniaya oleh kebijakan negara yang salah dan bahwa orang-orang yang bertanggungjawab atas kesalahan itu masih bebas berkeliaran. Disamping itu, kesigapan dan ketelatenan petugas penghubung/LO membantu peserta memenuhi kebutuhan apa saja, dari mencari wartel, obat sakit kepala, sampai membeli sandal jepit, membuat peserta terharu. Beberapa peserta yang sudah mengenal baik panitia juga memainkan peran tak kalah pentingnya. Seusai acara “resmi” mereka habiskan waktu untuk berbincang-bincang, bahkan curhat mengenai pengalaman pahitnya sebagai korban, dengan para LO. Yang juga menarik, peserta yang memang senang menyanyi dan bermain drama dengan semangat mengikuti “perintah” sutradara pertunjukan, Agus Nuramal, untuk 45
sisipan0 11-2003
mengerahkan segala kemampuannya sebagai seniman dadakan. Lewat perbincangan santai dan riuh rendah korban memberi usulan berbagai tema untuk Peringatan Tragedi Mei. Lalu disepakati acara pertunjukan akan diberi judul Malam Seribu Lilin, Seribu Kisah: Di Klender Kita Berjanji. Mereka juga secara spontan mengajak semua menyanyikan berbagai lagu rakyat, seperti “Aceh lon Sayang”, “Akai Bi Pamere” dari Papua, “Hai Jengki Agresor” dari Minahasa, “Genjer-genjer” dari Jawa Timur, dan lagu-lagu perjuangan seperti “Padamu Negeri”, “Maju Tak Gentar”, sampai lagu kebangsaan nasional “Indonesia Raya”. Beberapa dari mereka membacakan syair “P’rang Sabi”, puisi untuk kawan-kawan muda yang menjadi panitia, “Para Muda yang Berdaya”, dan “Balada Senyum Sang Jendral”. Kegiatan berkesenian yang diadakan setiap hari sehabis makan malam di lapangan bulutangkis terbuka berjalan menyenangkan, tapi tidak mudah. Skenario gerak, lagu dan puisi yang dirancang sutradara bersama para korban berulang kali berubah sesuai dengan kemampuan korban. Para pemusik dari kelompok Jentera Muda Jakarta (JMJ) dan pelatih gerak, Aidal, dari kelompok seniman Aceh, Sajak, sebelumnya tidak pernah mempersiapkan pertunjukan dengan orang-orang amatir.Tak heran jika di sela-sela latihan terjadi ketegangan diantara para seniman “profesional” akibat kecanggungan pemain melakukan perannya yang berbuntut pada penggantian satu-dua adegan berkali-kali. Untungnya, semua pihak yang terlibat dalam acara ini dikaruniai kesabaran luar biasa sehingga ketegangan tidak meledak menjadi “pemutusan hubungan kerja”. Di akhir malam yang panjang selalu ada rapat kecil tim acara untuk membicarakan kekesalan dan usulan perbaikan untuk malam berikutnya. Kehadiran Mbak Sipon, istri penyair hilang Widji Thukul, yang berpengalaman dalam melatih drama sedikit banyak memudahkan kerja Agus Nuramal. Ia memberi kepercayaan kepada korban yang ragu-ragu berekspresi untuk bergerak dan bersuara bebas. Tak bisa dilupakan pula ketekunan Aidal dan Bang Jaya, seniman Aceh yang pernah mengalami kekerasan militer, dalam mengajarkan lagulagu Aceh dan gerak Seudati sederhana.Tentunya muncul adegan-adegan menggelikan yang bersumber dari ketidaktahuan satu-dua korban tentang pengalaman korban lainnya. Misalnya, para korban dari daerah DOM, Aceh dan Papua, paling senang bila diminta jadi tentara atau intel yang bertindak kasar terhadap rakyat sipil. Mereka mengira semua korban mengalami kekerasan serupa.
46
Ketika giliran Ibu Darwin dari Paguyuban Korban Mei mendramatisasi pengalamannya, tanpa komando dari sutradara, pasukan “tentara” gadungan ini masuk ke tengah panggung dan beramai-ramai mengeroyoknya. Padahal Ibu Darwin tidak pernah berhadapan langsung dengan tentara. Ia harus berteriak-teriak untuk menghentikan “serbuan” kawan-kawannya sendiri. Ada saatnya korban tak kuasa menahan pilu ketika mereka diminta mengucapkan nama-nama korban meninggal yang mereka kenal baik secara beruntun seperti orang berzikir. Suasana menjadi hening. Korban yang selama ini berbentuk angka belaka, bernama. Ketika beberapa korban mulai terisak, latihan mau tak mau dihentikan. Semua yang berada di sekitar tempat latihan – petugas penghubung, pemain musik, pelatih gerak, anggota panitia lainnya – meluangkan waktu sejenak untuk mengenang korban yang gugur. Nama dan angka ternyata menguji pemahaman korban tentang nilai sebuah tragedi dan kaitannya dengan kerja pengungkapan kebenaran. Dalam skenario korban hanya diminta menyebutkan nama korban.Tapi beberapa korban berkali-kali menyebutkan nama diikuti dengan jumlah korban yang mereka percayai benar, seperti “Parto, Sri, dan 3 juta korban lain yang dibantai Orde Baru!”Yang menarik bukan hanya sutradara, tetapi juga korban lain, berusaha mengingatkan bahwa jumlah tidak penting, karena dengan menyebut satu nama saja kita sudah menunjukkan penghormatan terhadap kawan atau kerabat yang telah mendahului kita. Di sisi lain, ketika panitia meminta korban untuk mengumpulkan daftar nama korban meninggal yang mereka kenal untuk dituliskan pada kain putih panjang, ternyata nama yang terkumpul dari 100 korban hanya 491 orang. Bisa dibayangkan berapa banyak korban yang harus terlibat dalam kerja pengumpulan fakta untuk membuktikan bahwa Orde Baru telah membunuh jutaan warganya! Menjelang hari pertunjukan, 13 Mei 2003, latihan bersama ini berlangsung semakin ketat dan melelahkan. Kesibukan di luar latihan kesenian juga meningkat. Anggota panitia yang tidak terlibat per tunjukan tiap malam menuliskan ratusan nama di lembar-lembar kain putih yang akan digantungkan di sekeliling areal Mal Citra. Ada yang mengajak kawan-kawan dari organisasi lain untuk menyumbang bunga. Yang lain meminta ibu-ibu dari SIP menjadi perangkai bunga, pembawa acara dan pembaca puisi. Sementara itu, tim kesenian sendiri masih sibuk melengkapi narasi skenario dan mencari lagu yang akan
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
membawa tema persatuan korban. Sumbangan berbagai bentuk mengalir dari segala kalangan. Ada sumbangan puisi yang indah dari penyair Hersri Setiawan, “Seruan kepada Sesama Korban”, tapi terlalu panjang untuk dijadikan lirik lagu. Dengan desakan dan bujukan yang kukuh akhirnya Ibe Karyanto dari Sanggar Akar bersedia menggubah sebuah lagu dengan inspirasi dari puisi Hersri. Lahirlah Mars Suara Korban dua hari sebelum acara puncak. Korban segera belajar melantunkan mars tersebut dan menjadikannya bagian dari keseluruhan pertunjukan. Pada hari yang dinanti-nanti timbul masalah baru. Pihak Mal Citra ragu-ragu memberi ijin pemakaian tempat karena khawatir akan mengganggu kenyamanan pengunjung yang akan berbelanja.Tim dekorasi yang seharusnya sudah mulai bekerja sejak pagi hari terpaksa berfungsi juga sebagai juru runding.Tanpa diduga dukungan justru diberikan oleh seorang pemilik apotik di kompleks pertokoan tersebut yang mengalami kebakaran pada peristiwa Mei. Dalam waktu kurang dari 3 jam pelataran kosong di sisi apotik tersebut disulap menjadi panggung terbuka. Bebungaan sumbangan dari Komnas Perempuan, Huma, Suara Ibu Peduli, dan masyarakat umum segera ditebar untuk mengharumi panggung dan sekitarnya. Ratusan lilin ditegakkan mulai dari jalan masuk ke lingkar luar panggung. Tepat pukul enam sore gebrakan perkusi Sanggar Akar membuka acara. Pelataran sempit tak menghalangi berkumpulnya ratusan orang – peserta dan panitia Temu Korban, keluarga korban Mei, aktifis LSM, dan masyarakat umum. Para pemain mulai tampak gugup, tapi tetap bersemangat tampil. Kawan-kawan muda petugas penghubung dengan setia menemani pemain dan membantu mereka menghafal lirik dan narasi. Setelah musik pembuka, Ita Fatia Nadia dari Komnas Perempuan membacakan Refleksi Kemanusiaan yang menggugah. Kemudian, pertunjukan dimulai. Diantara penonton tampak sejumlah orang berlinangan airmatanya. Kekhusyukan acara sempat terganggu oleh ulah wartawan yang berebut mencari posisi sedekat mungkin ke panggung, melanggar deretan lilin yang menyala, dan menghalangi pandangan penonton. Di pojok lain ada wartawan yang terus berusaha mewawancarai seorang korban Mei, Pak Iwan, yang cacat akibat luka bakar. Panitia jadi dibuat sibuk menertibkan para wartawan yang tak tahu aturan. Pertunjukan berlangsung kurang lebih 1 jam dan berakhir dengan gerak bersama yang tak terduga. Begitu para pemain menyanyikan Mars Suara Korban sambil mengacungkan lilin, seluruh penonton, bahkan manajer Mal Citra yang awalnya hanya mengamati dari jauh, ikut berdiri melambaikan bunga, mengacungkan lilin, dan berderap merapat bersama korban. Di tengah kerumunan itu lah, Musa, wakil korban dari Aceh membacakan Deklarasi Korban dengan suara lantang. 0
SISIPAN
Hersri Setiawan
seruan pada sesama korban [dari tanah persinggahan] menyongsong temukorban orba saudara, mari kita songsong bersama di atas dataran tanah bersama di bawah kolong langit bersama diterangi matahari yang sama diselubungi gelap malam yang sama saudara, mari kita bicara bersama dalam satu bahasa, bahasa pembebasan dan itu bukan bahasa kebenaran dan itu bukan bahasa keadilan bahasa manusia dan bahasa hidup dan dalam hidup, saudara yang satu jadi berganda-ganda dan pada manusia, saudara yang satu jadi berganda-ganda dalam bahasa manusia tidak ada kata satu dalam bahasa hidup yang satu jadi beribu saudara, mari kita bicara bersama dalam satu bahasa persaudaraan karena di situ rahim kebenaran karena di situ janin keadilan saudara, mari kita pandang ke atas dalam satu semangat, perlawanan pada mata-air kepalsuan pada mata-air kezaliman akhiri kekuasaan zalim dan palsu! mari akhiri nafsu antara sesama dalam satu bahasa korban, kerukunan karena kita bukan bersaing penderitaan karena kita bukan berebut pampasan saudara, ini pertarungan, pertarungan vertikal bukan pertarungan sesama horisontal akhiri kekuasaan zalim dan palsu kita buka lahan persaudaraan kita bangun gubuk kerukunan di sana rahim kebenaran di sana janin keadilan kockengen, 5 mei 03
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
47
sisipan0 11-2003
Sekilas Temu Korban Kekerasan Orde Baru Wisma Hijau, Cimanggis, 9-12 Mei 2003
GALANG SOLIDARITAS TUNTUT TANGGUNG JAWAB NEGARA PULIHKAN KORBAN Mengikuti tergulingnya kekuasaan Soeharto pada 21 Mei 1998 suara korban penindasan rejim Orde Baru yang menuntut keadilan bermunculan dan menjadi semakin kuat. Dimulai dengan kesaksian para janda korban DOM dan korban perkosaan militer di Aceh, para korban dari kasus-kasus lain bergerak mengungkapkan kepedihan dan kemarahan mereka. Sejak akhir 1998 mereka secara aktif membangun kelompok-kelompok korban, dan menggalang dukungan dari masyarakat luas dengan berbicara di pertemuan-pertemuan publik yang diliput media massa cetak pun elektronik. Mereka juga melangsungkan aksi demonstrasi di berbagai instansi pemerintahan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang baru. Diantara korban adalah mereka yang langsung terkena represi dari negara, terutama aparat militer, dan keluarga mereka, seperti orang tua, istri, suami atau anak-anaknya. Suara-suara dari korban ini sampai batas tertentu sudah memaksa pemerintah dan parlemen untuk menetapkan mekanisme keadilan yang layak bagi para korban pemerintahan Soeharto. Parlemen menetapkan UU no. 39 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang diikuti dengan UU No. 26 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc yang mendirikan pengadilan HAM di
48
lima kota: Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Semarang dan Makassar. Sejumlah tim investigasi juga dibentuk untuk Kerusuhan Mei 1998, DOM di Aceh, dan pembunuhan pimpinan Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran berat HAM di Timor Timur sudah berjalan, sedangkan pengadilan serupa untuk kasus Tanjung Priok sedang berjalan. Selain itu Komnas HAM sudah mendirikan sejumlah Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk kasus-kasus Timor Timur, Abepura, Trisakti-Semanggi I dan II, dan terakhir Kerusuhan Mei 1998. Namun, seperti diketahui hampir semua usaha itu belum memuaskan rasa keadilan korban. Kebanyakan hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhenti di Kejaksaan Agung. Sedangkan kasus-kasus lain masih menunggu tanggapan dari negara, misalnya pembunuhan massal di desa Talangsari, Lampung pada 1986 dan serangkaian tindak kekerasan, termasuk pembunuhan, yang terjadi setelah Peristiwa G30S 1965. Keputusan yang dikeluarkan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur pun ternyata mengecewakan karena kebanyakan terdakwa yang menurut hasil investigasi KPP HAM bertanggungjawab terhadap pelanggaran berat HAM dibebaskan. Kejutan lain adalah ketika Pansus Trisakti-Semanggi DPR RI menyatakan bahwa penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti dan daerah Semanggi bukan pelanggaran HAM berat sehingga tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM Ad Hoc. Sementara itu para pelaku, yakni para penguasa di masa Orde Baru, dalam masa perubahan ini secara bergerilya mengangkat diri menjadi bagian dari gerakan “reformasi”, dan berusaha melepaskan tanggung jawab atas kejahatan mereka di masa lalu. Persekongkolan politik baru yang melibatkan elit Orde Baru dan elit “reformasi” membuat kasus-kasus keke-
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
rasan kembali tenggelam di balik hirukpikuk politik partai dan pergantian presiden. Para pelaku juga berusaha menjinakkan korban dengan menawarkan jalan “penyelesaian” secara damai, seperti tawaran ishlah kepada korban peristiwa Talangsari, Lampung dan Tanjung Priok. Sebagian lainnya memanfaatkan kesulitan hidup para korban dan menawarkan “bantuan kemanusiaan” dengan imbalan bahwa kasus-kasus yang dialami tidak dibicarakan lagi apalagi diproses menurut hukum yang berlaku. Lembaga-lembaga dan organisasi yang bekerja mendampingi korban dan berusaha mendorong proses penyelesaian menyadari bahwa gerakan untuk mengungkapkan kebenaran ternyata amat sulit dan lamban, apalagi untuk menegakkan keadilan. Masalahnya bukan hanya karena lawan yang dihadapi begitu besar dan kuat dalam segala hal, tapi juga karena banyaknya masalah di kalangan korban sendiri, baik sebagai perorangan, maupun sebagai kelompok. Persoalan yang cukup berat adalah kebanyakan korban itu miskin sehingga perjuangan mencapai keadilan seperti sebuah kemewahan bagi mereka. Kondisi sosial-ekonomi yang buruk juga membuat komunitas korban menjadi rentan terhadap bermacam bentuk infiltrasi yang bertujuan melemahkan gerakan mereka. Disamping itu, banyak korban yang memahami persoalan ketidakadilan semata-mata berkaitan dengan pengalaman yang mereka alami secara pribadi, sedangkan pemahaman lebih luas tentang persoalan politik dan hukum yang menyebabkan pelanggaran HAM kurang. Salah satu keberhasilan Orde Baru dalam membungkam perjuangan mengungkap kebenaran adalah dengan menghalangi persatuan di antara korban. Hal ini tampak jelas misalnya dari pengalaman korban peristiwa 1965 yang sampai saat ini masih dianggap sebagai “warga kelas dua”, “komunis” karena
SISIPAN
dituduh terlibat gerakan makar, antiPancasila. Atau korban peristiwa Mei 1998 dituduh “penjarah” oleh pemerintah dengan restu sebagian masyarakat. Penguasa secara aktif memecah-belah komunitas korban dengan merangkul sebagian dan menyingkirkan yang lain. Berangkat dari persoalan di atas, sejumlah kelompok korban dan organisasi pendamping korban sepakat untuk mengadakan lokakarya korban dan organisasi advokasi HAM di Wisma Hijau, Cimanggis pada akhir April 2001. Dalam pertemuan itu peserta lokakarya berbagi pengalaman dan meninjau kembali upaya-upaya penyelesaian kasus yang telah dilakukan selama ini. Dari hasil perbincangan ini dirasakan adanya kebutuhan membangun wadah bagi para korban kekerasan Orde Baru, yang bisa berfungsi sebagai wahana sekaligus kendaraan untuk secara bersama-sama membicarakan dan memperjuangkan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang mereka alami. Kemudian disepakati bahwa salah satu upaya yang harus dilakukanuntuk mencapai wadah bersama itu adalah dengan mempertemukan dan membangun jaringan antar korban di berbagai wilayah dan kasus di Indonesia dalam sebuah pertemuan korban tingkat nasional. Diputuskan pula bahwa pertemuan yang belum dipastikan waktunya akan bernama “Temu Korban Kekerasan Orde Baru” dan akan dibentuk panitia persiapan untuk menyebarkan gagasan ini ke kelompok-kelompok korban di daerah lain. Hasil pertemuan Cimanggis dirumuskan menjadi Materi Sosialisasi Temu Korban yang disebarkan ke berbagai organisasi pembela HAM, pendamping korban, dan kelompok korban di seluruh Indonesia. Secara garis besar bahan acuan ini berisi analisis korban terhadap kebijakan-kebijakan represif pemerintah Orde Baru yang telah mengakibatkan ribuan kasus pelanggaran HAM, strategi perjuangan korban untuk mencari keadilan dan membangun jaringan kerjasama antar korban, dan dengan organisasi HAM yang lebih luas. Selama setahun setelah lokakarya di Cimanggis panitia persiapan Temu Korban berkeliling ke berbagai kota di Indonesia, yaitu Padang, Lampung, Tasikmalaya, Garut, Jakarta, Solo, SISIPAN
Denpasar, Manado dan Palu untuk mengadakan pertemuan formal pun informal dengan berbagai kelompok korban dan organisasi HAM. Materi pembahasan mengalami banyak perkembangan dengan adanya masukan berharga dari kelompok-kelompok korban di luar Jakarta. Perbedaan-perbedaan yang awalnya tampak sulit dijembatani, seperti ketegangan antara korbankorban yang diberi label “ekstrim kiri” (Tragedi 1965) dan “ekstrim kanan” (Tragedi Talangsari dan Tanjung Priok), berhasil diatasi melalui kunjungankunjungan silaturahmi dan percakapan santai antar korban. Dari serangkaian pertemuan di tingkat lokal ini panitia persiapan Temu Korban berusaha merumuskan beberapa soal mendasar yang menjadi pokok perhatian korban. Berikut paparan singkatnya: 1. Siapakah korban? Rejim Orde Baru dibangun dengan pembunuhan massal dan tindak kekerasan yang tiada tandingannya dalam sejarah modern Indonesia. Sekitar 500.000 sampai tiga juta orang diperkirakan tewas dalam pembantaian yang berlangsung sejak Oktober 1965 sampai 1969. Sementara itu jutaan lainnya ditangkap, disiksa, diperkosa, ditahan tanpa proses pengadilan, dibuang ke kamp-kamp kerja paksa selama belasan tahun. Sanak keluarga mereka yang dianggap terlibat “G30S/PKI” diperlakukan sebagai “warga negara kelas dua” dan dijadikan sasaran diskriminasi selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Kekerasan politik yang bersifat sistematis dan meluas ini menjadi langkah pembuka para perwira militer, elit birokrasi dan pemegang modal besar untuk membuat sebuah sistem pemerintahan yang militeristik dan mengabdi pada kepentingan ekonomi segolongan orang saja. Penindasan terhadap mereka yang dianggap melawan kebijakan negara berlanjut di segala penjuru negeri ini sehingga melahirkan ratusan ribu korban baru dari masa ke masa. Mereka yang dianggap melawan, tapi berhasil lolos dari kebrutalan rejim ini menyandang “cacat sosial-politik” dengan cap-cap paten seperti “PKI”, “komunis”, “gerakan pengacau keamanan”, “subversif ”, “penjarah”, dan berbagai sebutan lainnya. Pemberian cap-cap ini bukan saja media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
melumpuhkan korban, tapi juga melindungi para pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Dalam banyak hal ribuan kasus kekerasan yang terjadi sejak 1965 memiliki kesamaan yang cukup kasat mata. Para pelaku semuanya adalah bagian dari rejim Orde Baru dan mereka melakukan tindak kekerasan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah ini. Sedangkan para korban adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mengkritik, melawan, dan ingin mengubah tatanan sosial-politik yang diciptakan rejim Orde Baru. Karena itulah kasus-kasus kekerasan yang menimpa mereka lazim disebut “kekerasan politik”. 2. Pengakuan bagi korban Sejak awal perjuangannya, tuntutan utama korban kekerasan politik Orde Baru adalah keadilan. Namun, setelah pergantian pemerintahan yang kesekian kali negara belum pernah memberikan pengakuan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal, pengakuan merupakan bentuk awal dari keadilan yang diharapkan korban, sebelum bisa sampai pada bentuk-bentuk keadilan yang lebih kompleks, seperti pemulihan, rehabilitasi, dan kompensasi. Pengakuan bagi korban bukan sekedar pernyataan lisan dari pemerintah yang berkuasa. Pengakuan membutuhkan pernyataan yang lebih menyeluruh dan bersifat publik. Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah pengakuan harus dapat menjelaskan latar belakang, pelaku, dan institusi yang terlibat dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM. Bersifat publik artinya pengakuan itu harus merupakan pernyataan resmi dari pemerintah yang ditujukan kepada seluruh warga negara republik ini. Hanya dengan pengakuan serupa inilah paling tidak penerimaan korban sebagai bagian dari warga masyarakat lebih dimungkinkan. Pengakuan bagi korban mencakup beberapa dimensi yaitu: A. Pengungkapan Kebenaran 1. Adanya institusi negara yang secara resmi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM, termasuk menetapkan kebijakan-kebijakan negara yang memfasilitasi kekerasan/pelanggaran HAM 2. Adanya institusi negara yang secara 49
sisipan0 11-2003
resmi melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM, termasuk menetapkan institusi-pelaku yang bertanggungjawab 3. Adanya institusi negara yang secara resmi melakukan penyelidikan pelanggaran HAM dan mengakui terjadinya berbagai bentuk kekerasan, seperti pembunuhan massal yang disponsori negara, pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan institusi negara, keberadaan orang hilang, perkosaan sebagai metode kekerasan yang sistematis untuk melumpuhkan masyarakat, penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan 4. Adanya pengakuan terhadap keberadaan korban dan keluarga korban beserta akibat-akibat yang dideritanya B. Pengadilan 1. Pengadilan di luar pengadilan HAM dan pengadilan sipil —> pengadilan militer, pengadilan koneksitas 2. Pengadilan berdasarkan gugatan korban 3. Pengadilan sebagai mandat negara —> pengadilan HAM Ad Hoc C. Kompensasi dan Rehabilitasi 1. Korban hanya menerima ishlah yang didahului oleh pengakuan secara publik 2. Adanya instansi-instansi pemerintah yang menangani korban, bahkan sebelum adanya pengakuan resmi 3. Rehabilitasi terhadap nama baik korban 3. Posisi Korban dalam Masyarakat Tindak kekerasan yang dilancarkan terhadap korban telah menimbulkan kerusakan material dan non-material di pihak korban maupun keluarganya. Kerusakan awal yang diderita korban pelanggaran HAM adalah: a. penderitaan fisik, seperti cacat tubuh, gangguan jiwa, rasa ketakutan berlebihan yang melanda korban tanpa melihat latar belakang kejadian, bentuk kekerasan, atau ideologi korban b. penderitaan sosial, ketika pemerintah menempelkan cap-cap yang membuat masyarakat segan berhubungan dengan korban. c. kerugian material, seperti kehilangan rumah, mata pencaharian, kehilangan akses ke perekonomian. Kesulitan sosial dan ekonomi semakin menghambat gerak korban yang sebagian besar dari kalangan menengah ke 50
bawah. Peristiwa kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa mereka hanya menambah beban bagi kehidupan mereka yang sudah sulit. Korban kekerasan di desa Talangsari, Lampung umumnya adalah para santri dari keluarga petani miskin, korban kekerasan di Tanjung Priok juga para santri yang terpuruk dalam kemiskinan di pantai utara Jakarta, korban kekerasan Tragedi 1965 kebanyakan adalah petani yang tak bertanah, korban kekerasan di Aceh pada umumnya adalah keluarga petani pula. Keterbatasan ekonomi korban adalah salah satu faktor penting yang menjadi kendala bagi korban untuk melanjutkan tuntutan atas keadilan. Tak jarang kepasrahan muncul dalam aneka bentuk ketidakberdayaan. Misalnya, salah satu alasan sebagian korban pembantaian Tanjung Priok menerima ishlah yang ditawarkan pihak pelaku adalah tekanan ekonomi yang tak tertahankan lagi. Terlibat dalam organisasi korban dengan berbagai kegiatan membutuhkan tenaga, waktu dan biaya tak sedikit. 3. Problem Internal Organisasi Korban Semenjak pertengahan 1998 bentuk dan jumlah organisasi korban semakin berkembang. Bahkan untuk kasus 1965 terdapat lebih dari satu organisasi korban dengan kegiatan yang tak terlalu berbeda. Tidak hanya berkumpul, korban bersama dengan organisasi pendamping atau dengan kelompok lainnya dengan berani mengungkapkan kisah mereka kepada publik dan mengajukan tuntutan terbuka kepada institusi-institusi pemerintah yang berwenang. Organisasi korban juga berhasil membangun kerjasama yang baik dengan berbagai LSM dan organisasi mahasiswa. Di balik kemajuan yang cukup pesat ini, organisasi korban sangat rentan terhadap perpecahan, baik yang disebabkan oleh faktor dari luar – penawaran dana untuk melakukan ishlah – maupun oleh ketidakmampuan organisasi mengatasi konflik yang terjadi diantara para anggotanya. Perpecahan ini membuat organisasi korban kesulitan mempertahankan kesinambungan aktifitas mereka. Alhasil, korban seringkali tidak siap merumuskan sikap dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi sosial, ekonomi, atau politik yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika pengadilan ad media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
hoc yang pertama berlangsung, yaitu untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, tidak ada persiapan sama sekali dari korban untuk mengamati jalannya pengadilan tersebut. Padahal, pengadilan ini menjadi tolok ukur pengadilan HAM berikutnya. Demikian juga dengan terbentuknya dan kinerja macam-macam panitia penyelidik yang tak mendapat pengawasan yang terencana dan seksama dari kelompok-kelompok korban. Gerak organisasi korban masih sangat ditentukan oleh momentum-momentum yang tercipta di luar kemampuan mereka. 4. Peran Lembaga HAM Lembaga HAM, termasuk Komnas HAM, selama ini cukup terlibat dengan korban dalam menangani penyelesaian kasus-kasus yang mereka alami. Namun, korban belum pernah merumuskan apa sebetulnya peran lembaga ini bagi korban sehingga bisa terjadi kerjasama untuk mendorong perwujudan pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Para korban berharap bahwa: - organisasi korban memiliki kemandirian dalam menentukan visi dan program kerjanya, - peran lembaga HAM dirumuskan dalam rangka memperkuat upaya perjuangan memperoleh keadilan, baik dalam upaya mendapatkan pengakuan, pemulihan hak-hak korban, maupun penguatan organisasi korban 5. Tujuan Temu Korban Tuntutan terhadap keadilan tidak sesederhana pengadilan. Ada kompleksitas yang harus dihadapi korban. Oleh karenanya penyelesaian kasus, perjuangan memperoleh keadilan, membutuhkan daya tahan organisasi korban dan kerjasama yang luas dengan lembaga HAM dan masyarakat. Temu Korban Kekerasan Orde Baru bertujuan untuk: a. merumuskan pandangan korban tentang keadilan b. meningkatkan kesadaran korban tentang kekuatannya c. merumuskan platform perjuangan korban d. membangun jaringan organisasi dan kelompok korban 0
SISIPAN
DEKLARASI ALIANSI KEMANUSIAAN KORBAN KEKERASAN NEGARA Kekerasan yang terjadi di Indonesia sejak awal Orde Baru hingga sekarang sesungguhnya dilatarbelakangi oleh perubahan kekuasaan negara yang terjadi pada 1965. Untuk mempertahankan kekuasaannya, rezim Orde Baru melakukan penyimpangan terhadap konstitusi negara dengan membuat produk hukum dan lembaga untuk membenarkan penggunaan kekerasan secara sistematis terhadap rakyat. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun dapat kita lihat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965, Peristiwa Malari, Komando Jihad, Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari Lampung, pemberlakuan operasi-operasi militer di Aceh dan Papua, Peristiwa 27 Juli, penculikan aktivis pro-demokrasi, Tragedi Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, dan di dalam setiap peristiwa konflik sosial & politik tersebut perempuan menjadi bagian dari korban, termasuk menjadi korban kekerasan seksual. Kenyataan dari peristiwa tersebut membuktikan bahwa kekerasan negara bukanlah sesuatu yang bersifat kasuistis tapi adalah mata rantai untuk mempertahankan kekuasaan. Akibat perbuatan kekerasan tersebut berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan membekaskan luka-luka badan dan hati. Semua derita yang masih ditambah dengan diskriminasi yang dilakukan oleh dan atas nama negara ini tersimpan dalam hati para korban dan masyarakat, tidak bermuara pada dendam tapi pada kehendak luhur bagi negara dan bangsa. Mengingat kekerasan-kekerasan tersebut maka Aliansi Kemanusiaan yang menjadi korban kekerasan tersebut bersamasama masyarakat secara luas mengajukan: 1. KEPADA PENYELENGGARA NEGARA a. Mengambil langkah untuk menghentikan tindakan kekerasan negara b. Menyelenggarakan proses pengadilan yang sehat dan tidak memihak dengan memperbaiki sistem, prosedur dan mekanisme Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan peradilan pada umumnya, dengan menempatkan warga negara yang memiliki independensi, integritas dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia. 2. KEPADA KELOMPOK KORBAN a. Membangun Aliansi dengan mengukuhkan kerjasama antara sesama korban serta menumbuhkan solidaratis b. Menumbuhkan solidaritas antar kasus c. Membangun jaringan komunikasi antar kelompok korban d. Mengkoordinasikan kerjasama untuk pengungkapan kebenaran dan pemulihan e. Melanjutkan kegiatan formal dan legal terhadap penyelenggara negara f. Menggalang perjuangan Aliansi dengan berbagai organisasi masyarakat, seperti partai politik, NGO, di tingkat lokal, nasional dan internasional 3. KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT a. Aliansi mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan pencapaian keadilan, yang meliputi pengungkapan kebenaran, pengadilan, pemulihan dan pencegahan keberulangan kekerasan b. Aliansi mengajak masyarakat membangun kerjasama dan persatuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Maka Aliansi berpendapat perlunya melakukan: 1. Supaya penyelenggara negara mentaati dan menghormati dan SISIPAN
melaksanakan dengan sungguh-sungguh Konstitusi Negara 2. Menjadi perlu untuk mereview semua produk hukum dan lembaganya, sehingga yang tidak sesuai atau berlawanan dengan Konstitusi secara bertahap dapat dilakukan 3. Menghentikan segera tindakan-tindakan diskriminatif dari kalangan penyelenggara negara, baik terhadap para korban kekerasan maupun masyarakat pada umumnya 4. Mensosialisasikan informasi-informasi yang benar mengenai semua peristiwa kekerasan yang terjadi Cimanggis Minggu, 11 Mei 2003 Aliansi Kemanusian Korban Kekerasan Negara
Resolusi Temu Kemanusiaan Korban Orde Baru Wisma Hijau, 9 – 11 Mei 2003 I. PERADILAN A. untuk kasus-kasus yang sedang dalam proses pengadilan (kasus Abepura dan Tanjung Priok): 1. segera menjalankan proses persidangan dengan menunjuk hakim dan jaksa yang berkemampuan dan memiliki integritas terhadap penegakan HAM 2. selama proses persidangan terdakwa harus ditahan 3. terdakwa tidak boleh dan atau di nonaktifkan dari jabatan publik B. untuk kasus-kasus yang sedang dalam proses penyelidikan (Trisakti-Semanggi I,II): 1. cabut rekomendasi DPR 2. mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan 3. mendesak pemerintah untuk menerbitkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc II. ACEH 1. mendesak pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan menarik mundur seluruh pasukan militer 2. melanjutkan proses damai dengan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat sipil 3. membubarkan milisi-milisi di Aceh III. PAPUA 1. mendesak pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan menarik mundur seluruh pasukan militer pasca penyerangan markas Kodim Jayawijaya 2. melanjutkan proses damai dengan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat sipil 3. membubarkan milisi-milisi di Aceh IV. PEMULIHAN 1. mencabut seluruh produk hukum yang mendiskriminasikan korban pelanggaran (berat) HAM 2. memberikan rehabilitasi kepada seluruh korban pelanggaran (berat) HAM
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
51
sisipan0 11-2003
Narator (Agus Nur Amal) Mengapa kami yang mereka pilih untuk dijadikan korban? Sutradara: Agus Nur Amal Sebab hanya dengan cara mengorbankan kami, mereka bisa mendapatkan dan memperkuat kedudukan. Sebab bagi mereka, mengorbankan kami adalah cara untuk SERIBU LILIN, SERIBU KISAH mempersatukan diri mereka sendiri. Sebab mengorbankan kami berarti memperkaya mereka. Di Klender Kita Berjanji Selama puluhan tahun kami berada dalam kesunyian dan penderitaan. OPENING Namun, selama puluhan tahun pula kami bertahan untuk MC (Ani Rukmainah) kebenaran dan keadilan. Selamat malam, Di tahun ’65…. Panitia Temu Korban mengucapkan terima kasih atas Wakil ’65 (mengkisahkan pengalaman pribadinya) kesediaan Bapak dan Ibu menghadiri acara Peringatan Mei Narator (Agung Ayu) 2003 ini. Sejak 1989 hingga 1998, Di Aceh…. Selama beberapa hari kemarin, kami beserta sahabatsahabat kami, para korban dari Paguyuban Keluarga Wakil Aceh (mengkisahkan pengalaman pribadinya) Korban Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Aceh, Papua, Narator (Agus Nur Amal) Talang Sari, Tanjung Priok, ’65, 27 Juli, Penculikan telah Di Tanjung Priok…. berkumpul bersama untuk saling berdiskusi dan membahas Wakil Tanjung Priok berbagai agenda pekerjaan. Yang aku tahu masyarakat di kampungku kesulitan Di tengah-tengah kesibukan selama empat hari kemarin itu, memperoleh air bersih, tak punya cukup uang untuk makan kawan-kawan korban menyempatkan diri berlatih untuk sehari-hari, apalagi menyekolahkan anak. Tak kudengar mempersembahkan sebuah pertunjukan kesenian. Seribu rencana mendirikan negara Islam. Orang-orang kampungku Lilin, Seribu Kisah: Di Klender Kita Berjanji, adalah judul marah karena teman-teman kami ditangkapi begitu saja. pertunjukan kami di malam hari ini. Sesudah itu mesjid kami dilecehkan. Padahal, di mesjid-lah Harapan kita semua, pertunjukan malam ini akan kami peroleh keteduhan. memperkuat semangat kita, untuk bersama korban, Orang-orang kampungku cuma menuntut keadilan. Kami memperjuangkan keadilan dan mencegah terulangnya sudah tahankan kemiskinan. Orang-orang kampungku kekerasan. cuma berbekal kepercayaan kepada Allah SWT. Tapi, Bapak, Ibu, dan Kawan-kawan semua, selamat seruan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” tak cegah pasukan menyaksikan. bersenjata muntahkan ratusan, mungkin ribuan pelor panas, tembusi tubuh anak, kekasih hati, dan orang tua Musik: “Nyanyian Para Saksi”1 (Sanggar Akar) kami. Tak selamanya kami akan diam Aku sungguh tak tahu apa kesalahan kami sehingga harus Tak selamanya kami merunduk dimusnahkan begitu rupa. Segala yang hidup ada batasnya Narator (Agung Ayu) Kami yang lemah pun kini bangkit Di Talang Sari, Lampung….. Wakil Talang Sari Terlalu lama diri kami disingkirkan Pukul menunjukkan jam 04.30 pagi. Terdengar azan subuh Terlalu lama luka pun menganga memecah hening di pagi itu. Para jemaah berkemas untuk Terlalu banyak milik kami yang dirampas bersiap menghadap Ilahi dengan menunaikan sholat subuh. Sekarang saat bagi kami untuk bergerak Tidak ada firasat sama sekali kalau sholat subuh saat itu adalah sholat subuh terakhir kali, karena tepat jam 05.30, Satukan niat ayunkan langkah bersama kita maju tiba-tiba terdengar desingan suara peluru di mana-mana Bersatu padu meretas tuntas segala pembodohan menerjang kesunyian di pagi itu. Kami kan bangun dunia baru tanpa darah dan luka Tak lama terdengar kumandang “Allahu Akbar, Allahu Akbar”, pekik Jemaah Warsidi menyongsong peluru yang Pada saat lagu dikumandangkan, pemain bangkit dari datang. antara penonton menuju Lilin Keadilan. Satu per satu Satu per satu tubuh bergelimpangan diterjang oleh timah pemain meletakkan bunga di dekat Lilin Keadilan, kemudian panas para tentara. duduk membentuk lingkaran di sekelilingnya. Setelah itu hening timbul kembali dan tak lama terdengar derap langkah tentara memasuki halaman Pondok BABAK I Pesantren Warsidi…. Di situlah ratusan manusia bergelimpangan sudah tak MENGAPA KITA MENJADI KORBAN? bernyawa lagi. Narator (Agus Nur Amal) Refleksi Kemanusiaan (Ita F. Nadia)
Acara Peringatan Mei, 13 Mei 2003
52
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
Pada tanggal 27 Juli 1996…. Wakil 27 Juli 1996 Minggu pagi buta, aku dan ratusan kawan lainnya sudah berjaga-jaga akan kemungkinan diserang Kami menyebar di sekeliling markas pusat PDI, juga di atas wuwungan gedung, berbekal tongkat, benda pemukul apa saja, dan keyakinan bahwa kami benar. Dari kejauhan tampak ratusan orang mendekati markas, diantar tentara, membawa obor dan jerigen bensin. Begitu mereka sampai di depan pagar, mereka mulai melempari kami dengan batu bertubi-tubi. Hubungan telpon terputus. Tak lama kemudian terlihat empat buah panser, dan sepenggal jalan Diponegoro sampai Megaria diblokade. Lemparan batu tak berhenti, gerbang diguncang-guncang sampai rubuh. Kami coba bertahan dengan kursi sebagai tameng. Tapi, serbuan ratusan orang bersama tentara ke dalam markas tak tertahankan. Aku bersembunyi gemetaran di bawah meja, menyaksikan bagaimana gerombolan berkaus merah PDI dan bertutup kepala seperti ninja mengayun-ayunkan kelewang, samurai, menghancurkan harta benda partai, menghilangkan kehidupan kawan-kawanku sambil berteriak-teriak beringas. Mereka seperti pemburu binatang buas, padahal tak seorang pun dari kami bersenjata. Darah menggenang di mana-mana Yang tersisa dari kami segera digiring ke mobil tahanan seperti penjahat. Jasad-jasad kaku dilemparkan ke truk, dibawa pergi, entah ke mana. Markas disembur air pemadam kebakaran. Darah kawan-kawanku sirna tersedot bumi bersama air. Narator (Agung Ayu) Di Surabaya, Lampung, Solo, Jakarta…. Wakil Penculikan Biasanya paling tidak seminggu sekali Bimo akan telpon, sekadar berkabar kepada kami orang tuanya. Sejak ia bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik, Kami memang selalu mengkhawatirkan keselamatannya. Memang kami selalu berdiskusi dengan Bimo tentang persoalan-persoalan rakyat yang mengganggu pikirannya. Tapi, di jaman Orde Baru itu bicara tentang persoalan rakyat kan resikonya besar. Nah, kami tak lagi mendengar kabar darinya sejak Maret 1998. Kami tak tahu apa kesalahannya. Setahu kami, dia orang yang keras hati, tapi sebetulnya dia orang yang mudah tersentuh dan selalu mau mendengarkan orang lain. Sahabat-sahabatnya menyampaikan pada kami bahwa dia sangat setia menemani kawan-kawannya, ia tak bisa meninggalkan kawan dalam kesendirian. Bimo pandai bermusik dan menulis lagu; dia membentuk kelompok band di kampusnya Bimo juga suka menulis dan membuat desain grafis.
SISIPAN
Kami benar-benar tak paham mengapa pemuda dengan kemampuan dan talenta sekaya itu harus dihilangkan? Narator (Agus Nur Amal) ’98 Mei di berbagai kota…. Wakil Mei ’98 (membacakan puisi) Narator (Agung Ayu) Di kampus Trisakti dan Semanggi… Wakil Trisakti dan Semanggi Apakah aku pejuang atau pahlawan reformasi? Aku tak tahu itu hanya ungkapan orang Aku bosan dilecehkan ketika Kau bercerita perjuangan Seakan aku seorang pelawak Aku bukan pelawak, aku hanya mencoba Aku mencoba kata hati nurani Aku berusaha untuk orang lain Aku tak peduli pada balas budi Aku hanya bisa berusaha agar semua orang bisa tersenyum Aku hanya ingin semua orang bisa bebas Aku hanya ingin mencintai Terlalu besar yang aku korbankan Kuliah, jodoh, dan kedamaian Berbulan-bulan aku dicekam rasa takut disiksa Berbulan-bulan aku lari dari hidup normal Tapi perjuangan yang hampir selesai musnah Reformasi kini hanya kedok penguasa Aku masih ingin berjuang, tapi itu tidak mungkin Kiri kananku jurang, depan belakangku tembok Aku sendiri, haruskah aku lari keluar seperti yang lain? Belum, aku masih punya nyawa, dan itu pengorbanan terakhirku2 Narator (Agus Nur Amal) Dari Papua…. Wakil Papua (mengkisahkan pengalaman masyarakat) Lagu: “Kepada yang Hilang”3 (Sri Wulan-diiringi koor) Pergi, pergilah dengan tenang Jangan sisakan jerit rontamu Pada daun, musim, bumi, dan langit Kami yang tinggal di sini Selalu memanjatkan doa-doa Semoga perjalananmu abadi Menuju arasnya Ilahi. MC (Ani Rukmainah) Sahabat dan keluarga kita yang menjadi korban… Litani Nama Korban (Arswendi Nasution dan Vien) Narator secara bergiliran membacakan 491 nama korban. Beberapa saat nama-nama korban dibacakan, seluruh pemain secara serentak dengan suara pelahan mengucapkan nama-nama korban seperti sedang berzikir,
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
53
sisipan0 11-2003
dan berakhir ketika dua narator selesai membacakan nama-nama korban. Setelah nama korban terakhir dibacakan (Widji Thukul) langsung dibacakan puisi. Puisi: Bunga dan Tembok4 (Sipon-musik ilustrasi) Seumpama bunga kami adalah bunga yang tak Kau kehendaki tumbuh Engkau lebih suka membangun Rumah dan merampas tanah Seumpama bunga Kami adalah bunga yang tak Kau kehendaki adanya Engkau lebih suka membangun Jalan raya dan pagar besi Seumpama bunga Kami adalah bunga yang Dirontokkan di bumi kami sendiri Jika kami bunga Engkau adalah tembok Tapi di tubuh tembok itu Telah kami sebar biji-biji Suatu saat kami akan tumbuh bersama Dengan keyakinan: engkau harus hancur! Dalam keyakinan kami di mana pun-tirani harus tumbang! BABAK II TANTANGAN-TANTANGAN MENCAPAI TUNTUTAN KORBAN Musik Ilustrasi Drama “Tantangan dalam Perjuangan Korban” SINOPSIS DRAMA Korban berjuang di mana–mana masing-masing menuntut keadilan atas kasus yang menimpanya. Ke sana-ke mari selalu menghadapi kegagalan, kekecewaan, penolakan, bahkan kekerasan. Korban 27 Juli, Aceh, Mei, ’65, Papua, Tanjung Priok, Talang Sari, Trisakti-Semanggi, Penculikan. Para korban yang menuntut keadilan hampir putus harapan hingga suatu saat mereka saling bertemu, bertukar pikiran. Mereka semua menginginkan hal yang sama: terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan.
Para pemain drama maju satu per satu, berkumpul di dekat altar, berbincang-bincang, kemudian menyalakan keadilan. BABAK III SOLIDARITAS MENGHADAPI TANTANGAN Puisi: “Seruan Sesama Korban”5 (Katmi-SIP)
54
Pemain Drama Aceh (beat lambat) Daerah Aceh, tanoh loen sayang Nibak tempat nyan, loen udeep matee…. Seluruh pemain (beat cepat, menari) Daerah Aceh, tanoh loen sayang Nibak tempat nyan, loen udeep matee… Tanoh keunebah, indatu moyang Lampoh dengon blang, luah bukon lee…2x Ureung jak u glee, na so peuseunang Na so peutimang, keureja matee…. Hatee yang susah, loen rasa senang Aceh loen sayang, sampo’an matee….2x Pemain Drama Papua (beat lambat) Iriani sup iriani….2x Seluruh Pemain (beat cepat-menari) Iriani sup iriani2x Yembe mawa yembe pioper Yafa fnakro Yaswar epna, yaswar epna Isof fioro-fioro…2x
Lagu diakhiri dengan teriakan: FIORO! Pemain sudah membentuk barisan beberapa saaf di kirikanan menghadap lilin keadilan. Pidato: “Melangkah ke Depan” (Ibe Karyanto) Lagu Mars: “Suara Korban”6 (Seluruh pemain) Semua yang terluka, marilah satukan s’luruh daya Di atas tanah kelahiran, di kolong langit kehidupan Mari kita bicara, di dalam bahasa para korban Yang tak kenal perseteruan atas penderitaan Akhiri s’gala bentuk kezaliman, tumpas segala kepalsuan Tegakkan jiwa persaudaraan sebagai rahim keadilan Meski dalam derita, marilah bergerak kita maju Lintasi batas ketakutan, arungi batas perbedaan Dalam duka yang sama bersatu menyusun langkah baru Merebut semua hak kita, merebut kehidupan Patahkan rasa ‘tuk saling curiga, merengkuh saudara yang lemah Satulah kita sebagai pertanda penjaga setia kebenaran
Empat pemain di barisan terpinggir maju ke arah lilin keadilan dan menyalakan lilin yang dipegangnya. Mereka membagi api lilin tersebut kepada pemain lain. Deklarasi Aliansi Kemanusiaan Korban Kekerasan Negara (Wakil pemain) Lagu Mars: “Suara Korban” (Seluruh pemain dan hadirin)
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
Setelah lagu selesai dinyanyikan, pemain secara berurutan berjalan kembali ke arah penonton dan berbaur kembali. CLOSING MC (Ani Rukmainah) Bapak, Ibu, yang terhormat Demikianlah pertunjukkan singkat kami di malam ini Semoga semangat solidaritas dan cinta akan kebenaran dan keadilan Yang dikumandangkan para korban menjadi panduan bagi kita semua Dalam mendukung perjuangan para korban Seluruh kepanitiaan Peringatan Lima Tahun Tragedi Mei 1998 Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada kawankawan seniman Aceh dari SAJAK dan kawan-kawan Jentera Muda Jakarta (JMJ) yang tak kenal lelah dan bosan melatih para pemain. Kepada Ibe Karyanto yang bersedia memenuhi permintaan panitia menciptakan lagu mars ‘Suara Korban” hanya dalam waktu dua hari. Teman-teman Sanggar Akar yang telah menyempatkan diri mengiringi musik. Terima kasih juga kami hunjukkan kepada kawankawan aktivis perempuan dari berbagai organisasi, khususnya Suara Ibu Peduli, atas sumbangan bebungaan yang mengharumi dan memberi warna tersendiri pada acara ini.
Badan Pekerja Temu Kemanusiaan Korban Orde Baru Penanggung Jawab: Agung Putri Keuangan: Erine Ismayani Sie Kepesertaan: Dyah Wara, Fatima Astuti, E. Rini Pratsnawati,Taat Ujianto Sie Akomodasi: Amos Sembiring, Dr. Eko (medis) Sie Konsumsi: Etty, Ipah, Mariatun, Mona Sie Transportasi: Diana, Hanna, Kokom,Victor da Costa Sie Acara: Agnes Diana, Atnike Sigiro, Esti Kristanti, Bp. Sasmoyo Sie Kesenian: Agung Ayu, Agus Nuramal,Th. J. Erlijna Sie Dekorasi: Alit Ambara, Anna HP, Elly Sie Dokumentasi: Andre Susanto, Anton Stevanus,Yayan Wiludiharto, Sandy Therodelita,Wibowo Sie Publikasi dan Humas: Ibu Sumarsih, Herman Wikoco, Nining Sie Keamanan: Adi Prasetyo, Isnu Handono, Bp. Effendi, Lefidus Malau Sie Peringatan Mei: Ibu Darwin, Syaldi Pembantu Umum: Eka, Dewi
Tim Fasilitator: Amiruddin, Atnike Sigiro, Benny Biki, Hilmar Farid, Indriaswati Saptaningrum, Ita F. Nadia, Kamala Chandrakirana, Ori Rahman, Rinto Trihasworo, Ruth Indiah Rahayu, Rudi Rizki, Sentot Setyosiswanto,Wayan Santa Tim Notulis: Aquino, Eka, Grace, Razif, Reza, Suluh, Syaldi,Winda Tim Petugas Penghubung/LO : Asih, Benny, Etty, Iwan, Lili, Liza, Mona, Peri,Tigor Tim Pengemudi: Cecep, Untung
Penyerahan empat rangkaian bunga kepada wakil SAJAK, JMJ, Komnas Perempuan, dan SIP. Sebagai penutup acara malam ini, kami minta kesediaan bapak Direktur Mal Citra untuk memberikan ungkapan perasaan atas peristiwa malam ini. Kami persilakan
Sambutan Manajer Mal Citra MC (Ani Rukmainah) Pemberian karangan bunga pada Manajer Mal Citra dari Temu Korban Nasional
Tim Penasehat: Amiruddin, Hilmar Farid, Rm. I. Sandyawan S., SJ, Ifdhal Kasim, Ita F Nadia, Kamala Chandrakirana, Lily Hasanuddin, M. Habib Chirzin, Ruth Indah Rahayu, Salahudin Wahid, Saparinah Sadli. Lembaga Pendukung: ELSAM, Kalyanamitra, Keluarga Korban Priok, Keluarga Korban Talangsari, Komite S’malam, Komnas Perempuan, KontraS, Paguyuban Keluarga Korban dan Korban Mei’98, Paguyuban Keluarga Korban Semanggi I-II, Pakorba, SHMI,TRuK,Yappika.
Pemberian karangan bunga diberikan oleh seorang wakil pemain. MC (Ani Rukmainah) Bapak-Ibu yang budiman, terima kasih, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak-Ibu menghadiri acara Peringatan Mei pada 2003 ini. 1 Cipt.: Ibe Karyanto | 2 Puisi berjudul “Reformasi”, cipt. BR. Norma Irmawan | 3 Cipt. Rahmad Sanjaya | 4 Cipt. Widji Thukul | 5 Cipt.: Hersri Setiawan | 6 Cipt.: Ibe Karyanto
SISIPAN
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
55
sisipan0 11-2003
MARS SUARA KORBAN cipt.: IBE Karyanto
56
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
SISIPAN
SISIPAN
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
57
CERITA PENDEK
Bah! Saut Situmorang
M
alam itu aku datang lagi ke situ. Aku sudah sangat rindu pada perempuanku. Perempuanku yang manis, perempuanku yang pandai menghibur. Aku mempercepat langkahku, membelok ke gang terakhir menuju gerbang masuk perkampungan kecil di mana perempuanku itu tinggal. Perkampungan itu sangat sunyi. Hanya beberapa anak kecil nampak sedang main kejar-kejaran dan dua-tiga perempuan berpapasan denganku. Mereka menyapaku dan kubalas dengan anggukan kepala. Rumah perempuanku terletak agak di tepi perkampungan kecil itu. Rumah itu juga kecil. Hanya punya sebuah kamar tidur dan kamar mandi saja. Tak ada dapur dan perempuanku membeli makanannya di rumah makan di luar perkampungan atau pada para penjual bakso atau sate yang sering masuk ke situ. Mengingat perempuanku yang manis itu, tanpa sadar aku mempercepat langkahku. Tinggal seratusan meter dari rumah perempuanku, tibatiba kuhentikan langkahku. Aku lihat seorang laki-laki muncul dari dalam rumah itu. Laki-laki itu berdiri sebentar di ambang pintu, sepertinya sedang mengawasi sesuatu, lalu kembali menutup pintu rumah perempuanku. Aku jadi heran. Bukankah perempuanku sudah berjanji akan memberikan malam ini sepenuhnya untukku? Bukankah dia bilang tak akan ada orang yang akan mengganggu? Aku masih termangu-mangu di tempatku itu sambil mencoba mengingat-ingat perkataan perempuanku seminggu lalu waktu pintu rumahnya terbuka lagi dan laki-laki tadi muncul kembali di ambang pintu. Kembali dia bersikap seperti sedang mengawasi sesuatu di luar rumah sebelum menutup pintu. Rasa penasaranku makin menjadi-jadi hingga kuputuskan untuk mendatangi saja rumah perempuanku itu. Mulanya aku hendak masuk lewat pintu depan di mana laki-laki tadi berdiri, tapi segera kubatalkan. Aku ingin menyelidiki dulu siapa laki-laki itu dan kenapa tingkahnya aneh begitu. Untuk itu aku harus mengintip apa yang dilakukannya di dalam rumah perempuanku. Aku juga heran kenapa perempuanku
58
sedari tadi tak pernah muncul-muncul. Apa dia tak ada di rumah hingga laki-laki tadi harus menunggunya? Mungkin laki-laki itu tak sabar menunggu begitu lama… Baru saja tanganku meraba dinding rumah perempuanku, tiba-tiba aku dengar suara laki-laki dari dalamnya. Aku yakin suara itu pasti punya si laki-laki yang kulihat di pintu tadi. Suara itu agak berat dan kasar. Kayaknya dia sedang marah. Tapi, marah pada siapa? Akhirnya aku berhasil memergoki sebuah lobang kecil dekat jendela. Kudekatkan mataku ke lobang itu dan coba melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Mataku langsung melihat laki-laki tadi. Dia sedang duduk di atas ranjang perempuanku dan wajahnya menghadap ke arahku. Rasa-rasanya aku seperti mengenali laki-laki setengah baya yang sedang marah itu. Kucoba mengingat-ingat, tapi aku lupa. Kuamati lagi wajahnya yang bulat dan gempal itu, aku yakin aku mengenalnya. Tapi aku tetap lupa siapa namanya. Sekarang kucoba cari perempuanku. Aku lihat kursi dekat cermin yang tergantung di dinding, kosong. Biasanya dia suka duduk di kursi itu sambil menyisir rambutnya. Aku jadi tambah heran. Aku lalu kembali ke tempat tidur. Laki-laki itu masih duduk di situ. Tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berjalan ke arah pintu. Pada waktu itulah perempuanku nampak padaku. Dia telungkup di atas ranjang. Wajahnya terbenam di bantal. Kulihat punggungnya bergerak-gerak tak teratur. Dia sedang menangis. Tapi, kenapa? Kenapa dia menangis dan kenapa laki-laki tadi kelihatan marah dan resah? Siapa lakilaki itu dan apa yang sedang terjadi di sini? Laki-laki itu kembali menutup pintu dan berjalan ke arah tempat tidur di mana perempuanku sedang menelungkup menangis. Wajah laki-laki itu mengerikan sekali. Kemarahan yang sangat dahsyat memancar di matanya. Begitu sampai di tepi ranjang, tangan kanannya langsung bergerak ke kepala perempuanku. Dengan kasar dijambaknya rambut perempuanku yang panjang itu. Perempuanku menjerit kesakitan tapi berusaha
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
ALIT AMBARA
CERITA PENDEK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
59
menahannya agar tak terdengar ke luar. Wajahnya basah airmata. Tiba-tiba kurasakan api kemarahan muncul dalam diriku. Aku mulai panas. Aku ingin mendobrak masuk dan menghajar laki-laki yang menyakiti perempuanku itu. Kurasakan badanku mulai gemetar. Sambil melepaskan jambakannya, laki-laki itu mulai memaki-maki perempuanku yang sekarang duduk di atas ranjang dan menangis terisak-isak. Dia memakinya “lonte tak tahu diri”, “pelacur jorok”, “perempuan tukang serong,” dan kata-kata kasar lainnya yang tak pantas diucapkan pada seorang perempuan, apalagi perempuan seperti perempuanku itu yang begitu manis dan pandai menghibur hati. Perempuanku tak menjawab sepatah kata pun dan hanya menangis di atas ranjang sambil menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Setelah puas memaki-maki, laki-laki itu lalu membentak perempuanku supaya berhenti menangis, melihat padanya, dan menjawab pertanyaannya. Perempuanku menurut. Dihentikannya tangisnya dan mengangkat wajahnya memandang ke arah laki-laki itu. Wajah itu basah dan nampak bengkak. Dia bertanya tentang “siapa lelaki itu” dan minta perempuanku menjawabnya dengan jujur. Perempuanku cuma diam. Tak ada satu bunyi pun keluar dari mulutnya. Lakilaki itu mengulang pertanyaannya. Perempuanku tetap tak menjawab. Lalu diulanginya lagi pertanyaannya tadi. Karena tetap tak mendapat jawaban, tangan kanannya yang besar dan kasar melayang ke pipi kiri perempuanku. Plak! Perempuanku terjungkal ke belakang dan jeritan kecil keluar dari mulutnya. Laki-laki itu lalu menarik rambutnya hingga dia kembali ke posisinya semula duduk di atas ranjang. Kemudian kembali tangannya melayang berkali-kali ke wajah perempuanku yang mulai berdarah itu. Kulihat bibirnya pecah dan darah ada di wajahnya, baju tidurnya, seprei, dan di tangan kanan laki-laki itu. Laki-laki itu lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Sebuah pistol kecil! Kaget sekali aku melihatnya. Pistol kecil itu ditodongkannya ke dada perempuanku yang kini 60
cerita pendek
memandangnya dengan mata terbelalak ketakutan. Sekarang aku tak tahu harus berbuat apa. Keinginanku untuk melabrak masuk terpaksa aku tunda. Dari lobang dekat jendela itu kulihat laki-laki itu mulai tersenyum! Bangsat, apa orang ini sudah gila! Dia bisa tersenyum dengan pistol di tangannya ditodongkan ke dada seorang perempuan yang memandangnya ketakutan! Laki-laki ini benar-benar bajingan! Seekor binatang gila! Dia malah mengancam akan menembak perempuanku kalau tetap tak mau menjawab pertanyaannya itu. Katanya perempuanku lebih baik mampus daripada jabatannya sebagai walikota hancur. Walikota! Ah, aku ingat sekarang. Ya, aku ingat laki-laki ini adalah walikota kotaku yang sering kubaca beritanya di koran lokal dan sering muncul di tv lokal. Dia juga sering hadir di seminarseminar yang diadakan di kampusku. Aku ingat siapa dia sekarang. Laki-laki bajingan yang sekarang kupanggil si Walikota itu mengulurkan tangan kirinya ke arah dada perempuanku dan mulai meremasremas kedua buah dadanya sambil tersenyum. Dia meremas-remasnya dengan kuat hingga perempuanku meringis kesakitan dan menggeliatgeliatkankan badannya. Kembali walikota itu mengulangi pertanyaannya. Tapi tetap saja perempuanku tidak menjawabnya. Merasa kalau perempuanku tidak akan pernah menjawab pertanyaannya itu walau disakiti sekalipun, walikota itu mulai hilang kesabarannya. Dengan kasar dirobeknya baju perempuanku. Dirobek dan dirobeknya terus hingga perempuanku hampir telanjang bulat duduk di atas ranjang di depannya. Hanya kutang dan celana dalamnya saja yang tinggal. Lalu dipaksanya perempuanku membuka keduanya. Karena sangat ketakutan, perempuanku menuruti perintah walikota yang sekarang juga mulai membukai pakaiannya sendiri itu. Lalu walikota itu memperkosa perempuanku sementara pistol kecilnya ditodongkannya ke kepalanya. Aku memejamkan mataku. Tangis perempuanku dan kemarahanku memukul-mukul kepalaku. Aku berusaha tenang. Aku berusaha mengendalikan amarahku karena kalau media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
aku mendobrak pintu dan membuat walikota bangsat itu gugup, terancamlah nyawa perempuanku. Aku tak mau perempuanku mati terbunuh setelah disiksa dan diperkosa. Walikota itu mesti mempertanggungjawabkan perbuatan biadabnya itu. Aku juga ingin tahu siapa laki-laki yang membuat walikota itu begitu marah hingga membuatnya melakukan perbuatan gilanya terhadap perempuanku. Aku tak boleh kalap, aku tak boleh membuat keselamatan perempuanku terancam… Aku tak tahu entah berapa lama berlalu ketika tiba-tiba kudengar suara “tep”, “tep” yang sangat halus dari dalam rumah. Lalu suara orang melangkah tergesa-gesa, pintu dibuka, dan suara langkah di halaman. Lalu sunyi. Aku tak mendengar apa-apa lagi. Aku coba melihat ke dalam rumah lewat lobang kecil tadi. Perempuanku ada di atas ranjang, telanjang bulat. Walikota itu tak ada di dekatnya. Juga tidak di kursi dekat cermin. Walikota itu sudah tak ada di dalam rumah. Aku beranjak ke pintu, kucoba dan terbuka. Sekarang dengan jelas kulihat darah di mana-mana dalam rumah perempuanku itu! Di atas ranjang kudapati perempuanku sudah tak bernyawa lagi, matanya terbelalak lebar, dan di dekat kepalanya yang penuh darah tergeletak sebuah pistol kecil yang juga berlumuran darah. Aku meraung keras. Baru saja aku membalikkan badanku hendak mengejar walikota itu, kulihat di ambang pintu sudah berdiri kepala kampung, seorang polisi, dan walikota itu sendiri. Lalu kudengar suara ribut-ribut di luar rumah dan… “Tok! Tok! Tok!!! Dengan ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara kepada terdakwa yang didakwa membunuh seorang wanita dengan cara menembaknya dua kali di bagian kepala dengan…” Di antara para pengunjung sidang pengadilan kulihat walikota itu tersenyum mengejek padaku. 0 Saut Situmorang, penyair dan pencinta cersil Kho Ping Hoo, tinggal di Bantul
CERITA PENDEK
KLASIK
JOHN SYDENHAM FURNIVALL: Pembanding Kolonialisme Inggris dengan Belanda
Kali Besar - Jakarta Kota, Foto: Hervé Dangla
M. Fauzi
D
alam sebuah buku yang berisi kumpulan esai dari mereka yang pernah aktif dalam politik kolonial di Hindia Belanda, Balans van Beleid: Terugblik op de Laatste Halve eeuw van Nederlandsch Indie (dialihbahasakan Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan), editornya, yaitu H. Baudet menulis tentang salah seorang sosok administratur kolonial asal Inggris, John Sydenham Furnivall. Dalam kesan-kesannya, Baudet mengungkapkan kekecewaannya dengan kalimat sebagai berikut, “Sayangnya, ada seorang, yang kita hormati, tidak hadir. Ketidakhadirannya tidak saja merupakan suatu kekurangan dalam mendiskusikan buku ini [Balans van Beleid], tetapi juga sebagai suatu kerugian yang tidak dapat diganti untuk bidang sejarah di masa penjajahan.” Seberapa pentingkah Furnivall, dan di mana sesungguhnya KLASIK
posisinya dalam studi-studi kolonialisme di Asia Tenggara? Semula, Furnival merencanakan menulis sebuah esai tentang pengalamannya sebagai administratur kolonial dan pengetahuannya tentang kolonialisme. Namun, sebelum rencana itu terwujud, ia meninggal pada 7 Juli 1960 dalam usia 82 tahun. Tentunya Baudet sangat kecewa atas meninggalnya Furnivall, sekaligus “suatu kerugian yang tidak dapat diganti” bagi publik ilmiah telaah tentang Asia Tenggara, khususnya Burma dan Hindia Belanda. Kekecewaannya itu juga bisa dipahami sebagai suatu bentuk pengakuan Baudet atau para “Indolog” terhadap otoritas keilmuwan Furnivall. Dalam kajian tentang kolonialisme Belanda, Furnivall memang termasuk salah seorang figur yang menonjol di antara puluhan Indolog alumni Universiteit Leiden dan Utrecht, dua perguruan tinggi terke-
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
61
muka di Belanda yang banyak menelurkan Indolog. Ia termasuk segelintir ilmuwan Inggris yang menaruh minat pada studi perbandingan negeri-negeri di Asia Tenggara, terutama Burma dan Hindia Belanda. Dua negeri yang banyak dikaji oleh Furnivall. Studi Furnivall tentang Hindia Belanda yang terkenal adalah Netherlands India: A Study of Plural Economy, terbit pada 1939, dan menjadi salah satu bacaan wajib di berbagai universitas dan kajian-kajian mengenai sistem kolonial. Furnivall menulis dan menyelesaikan Netherlands India saat menjadi pengajar bidang hukum, sejarah, dan bahasa Burma di Cambridge University, Inggris. Ia memang fasih berbicara tentang Burma. Minat dan kajiannya tentang Burma di bawah kolonial Inggris sama menarik dengan kajiannya tentang Hindia Belanda di bawah kolonial Belanda. Mungkin karena alasan itulah, ia secara intensif mendalami dan membandingkan antara kolonialisme Inggris di Burma dan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Salah satu karyanya yang menyoroti tentang perbandingan kolonialisme di kedua negeri tersebut adalah Colonial Policy and Practice, terbit pada 1948. Di Burma, pemerintah kolonial Inggris telah menghapuskan sistem monarki dan menyingkirkan para penguasa tradisional. Sementara pemerintah kolonial Belanda justru berbuat sebaliknya. Pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan sistem monarki dan penguasa tradisional, dan menjadikan yang terakhir sebagai kepanjangan tangannya dalam urusan-urusan publik dan bahkan ekonomi, khususnya meningkatkan pendapatan dari tanaman ekspor penghasil devisa terbesar seperti kopi, gula, teh, dan nila. Memang, latar belakang bercokolnya kolonialisme di kedua negeri itu berbeda. Jika Inggris menguasai Burma melalui jalan penaklukan secara fisik dan militer, Belanda justru menancapkan kekuasaannya melalui serangkaian perundingan dan kontrak-kontrak perjanjian dengan keraton dan penguasa-penguasa lokal. Seorang nasionalis dan sastrawan, Sanoesi Pane, menyebut cara dan taktik Belanda dalam menaklukan kepulauan Nusantara ini dengan jalan berunding sebagai “soeatoe tipoe moeslihat”. Dalam uraiannya tentang sistem pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda, Furnivall juga membahas tentang bagaimana Belanda mengatur jajahannya dengan aparat-aparat kolonialnya. Di Hindia Belanda, di samping gubernur jenderal, residen, asisten residen, kontrolir, ada pula 62
jajaran birokrasi pribumi yang terdiri dari para bupati, patih, wedana, asisten wedana. Maka, dalam sistem pemerintahan di Hindia Belanda yang terjadi adalah berlangsungnya suatu sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dari aparat kolonial kepada rakyatnya melalui birokrat pribumi, atau lebih dikenal sebagai pangreh praja (penguasa kerajaan). Sebagai suatu istilah, pangreh praja, menurut Heather Sutherland, yang meneliti secara mendalam topik ini, mungkin lebih tepat ditujukan bagi pribumi. Namun, tidak demikian halnya di mata pemerintah kolonial. Bagi pemerintah kolonial, aparat pribumi yang disebut sebagai “penguasa-penguasa kerajaan” itu tak lebih dari semacam inlandsch bestuur (pemerintah pribumi) yang kedudukannya lebih rendah dari pemerintah lokal. Tumpang tindih atau“pemborosan birokrasi” dalam sistem pemerintahan kolonial ini terus berlanjut bahkan setelah Indonesia merdeka, dengan aktor dan peran yang berbeda. Meskipun begitu, dari segi keuangan, pemerintahan tak langsung yang memanfaatkan aparat pribumi dalam sistem kolonial ini memang jauh lebih murah ketimbang harus mengimpor langsung atau menggaji aparat dari Belanda. Selain itu, pemerintah kolonial juga melihat penduduk tampaknya lebih patuh kepada penguasa-penguasa lokal dari pada kepada pemerintah kolonial. Indirect rule, di sisi lain, memang menjadi “pesona” tersendiri dalam telaah tentang kolonialisme di Hindia Belanda. Tak terkecuali juga bagi Furnivall dalam Netherlands India. Kendati kajian Furnivall tentang Hindia Belanda banyak menyoroti perkembangan yang terjadi sejak awal abad ke-19 hingga menjelang tahun-tahun terakhir runtuhnya Hindia Belanda, ia juga membahas beberapa segi kebijakan politik dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Hongitochten, misalnya, menyebut kebijakan memotong pohon-pohon rempah di Maluku yang tidak dapat diatur oleh VOC ini sebagai suatu bentuk penyamunan untuk menghancurkan seluruh produksi yang melebihi kebutuhan Belanda. Cara VOC untuk menguasai melalui jalan kekerasan pada akhirnya dilakukan jika kontrak-kontrak gagal disepakati. Ini pula yang terjadi di Kepulauan Banda dalam soal pala. Sejak dimulainya hongitochten, perusakan, perlawanan, hukuman adalah sejarah yang kerap silih berganti dan melekat di wilayah Kepulauan Maluku. Masa Tanam Paksa (cultuur stelsel) yang berlangsung sepanjang 1830-1870 juga tak luput dari perhatian Furnivall. Sejak beramedia kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
khirnya sistem itu pada 1870, penyerahan paksa hanya diwajibkan untuk gula dan kopi. Serah paksa kopi sendiri baru berakhir pada 1919, dan tanaman jenis ini menjadi penyumbang devisa terbesar bagi kas kolonial Belanda. Tentang UU Agraria 1870, Furnivall menyatakan pendapatnya sebagai berikut,“Dengan sesuatu yang didasarkan atas prinsip bahwa keuntungan hendaknya jatuh ke tangan perorangan-perorangan swasta dari pada ke sektor umum.” Jelas di sini adanya upaya segelintir orang, pemilik modal atau para tuan kebun, untuk menggeser kepentingan umum menjadi kepentingan perorangan swasta belaka. UU ini juga menghapuskan monopoli negara atas penanaman gula dan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta melakukan sewa jangka panjang atas “tanah-tanah telantar”, dan sewa jangka pendek atas tanah-tanah yang sedang ditanami. Furnivall menyadari betul bahwa semua hubungan kolonial, tak terkecuali di Burma dan Hindia Belanda, sesungguhnya ditentukan oleh ekonomi. Di Hindia Belanda termasuk di dalamnya “tiga serangkai”, yaitu era cultuur stelsel, liberal, dan Politik Etis. Kontroversi yang terus-menerus tentang kolonialisme Belanda sejak cultuur stelsel hingga era liberal terus berlanjut ke masa Politik Etis. Kebijakan baru ini dicanangkan sejak awal abad ke-20 sekaligus menandai berakhirnya ekspansi horisontal negara yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mata Furnivall juga memiliki tujuan ekonomis. Dan, awal serta akhir kebijakan itu juga ditentukan oleh ekonomi. Sejak Politik Etis dilaksanakan, terjadi perluasan aparat kolonial yang sangat besar dan mendalam hingga masyarakat pribumi, dan fungsinya pun berkembang. Pendidikan, irigasi, pertanian, kesehatan, eksploitasi mineral, pengawasan politik semuanya menjadi urusan kepegawaian yang kian meluas karena desakan dari dalam ketimbang dari luar negara. Tak lama setelah pemberlakuan Politik Etis, pada 1910 negara kolonial mulai bertindak melalui kekuatan bersenjatanya (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger, KNIL) dan berhasil menerapkan rust en orde (ketentraman dan ketertiban) di wilayah kekuasaannya. Suatu sistem kontrol yang tidak mendapatkan kendala serius hingga pembubarannya beberapa pekan menjelang invasi Jepang pada 1942. Kajian Furnivall tentang Hindia Belanda mungkin tak sebanyak kajiannya tentang Burma. Setidaknya Wealth in Burma (1937), Political Economy of Burma (1951), The GovKLASIK
ernment of Modern Burma (1958) adalah beberapa contoh di antaranya. Di Indonesia, studi tentang Burma, khususnya waktu di bawah kolonial Inggris, sedikit mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Padahal, membandingkan kedua corak sistem kolonialisme di kedua negeri di Asia Tenggara ini tentulah sangat menarik. Inggris memang pernah berkuasa di Indonesia, tetapi itu pun berlangsung singkat, yakni pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816). Setidaknya perbandingan itu membawa kepada suatu pemahaman tentang watak kolonialisme Inggris dan Belanda di masing-masing negeri jajahannya. Adakah perbedaan antara keduanya di masing-masing negeri? Ataukah setiap negeri diterapkan kebijakan yang sama? Dari telaah Furnivall, banyak hal yang sebenarnya berbeda dan perbedaan itu dipengaruhi oleh kondisi di masing-masing negeri. Dalam kasus Hindia Belanda, perbedaan dan hasilhasil apa saja yang telah dilakukan baik oleh kolonial Inggris – saat Gubernur Jenderal Raffles berkuasa – maupun kolonial Belanda tentunya menjadi suatu kajian yang menarik. Tentang Hindia Belanda, pendapatnya yang cukup menarik adalah mengenai masyarakat majemuk (plural society). Setiap kelompok dalam masyarakat ini cenderung menjalankan kehidupan sosial yang mandiri dan diatur oleh pemimpinnya masingmasing. Mereka hidup dalam unit politik yang sama. Dalam kerangka ini pula, hukum di Hindia Belanda sesungguhnya bagi macam-macam kelompok berlain-lainan. Begitu pula halnya dalam hal aturan kemasyarakatan.
Dalam masyarakat Tionghoa misalnya, mereka mengenal sistem opsir, atau para kepala masyarakat Tionghoa. Hingga abad ke-19 para opsir ini terdiri dari kapitan, letnan, mayor, dan kepala kampung (wijkmeester). Suatu kedudukan yang kemudian menjadi turun-temurun. Mereka bukan hanya penimbun modal, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat Tionghoa. Para opsir ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepangkatan dalam militer kolonial. Mereka adalah pedagang kaya atau cabang atas dalam masyarakat Tionghoa. Nah, para opsir ini lah yang menjadi penghubung antara masyarakat Tionghoa dan pemerintah kolonial. Pacht atau monopoli pajak yang dijual kepada orang Tionghoa dalam pelelangan terbuka menjadi inti hubungan ekonomi-politik antara opsir dan pemerintah kolonial. Perbedaan lain dalam masyarakat majemuk juga terlihat di bidang hukum. Sistem peradilan di Hindia Belanda misalnya menganut azas yang berbeda-beda untuk berbagai masyarakat: pribumi, Tionghoa/Timur Asing, dan Eropa. Dan, kesenjangan ini pula yang dimanfaatkan oleh Sukarno ketika membacakan pembelaannya yang terkenal “Indonesia Menggugat” di Landraad Bandung. Bagi Sukarno, hukum kolonial tak mungkin membenarkan tindakannya beserta kawan-kawannya dalam PNI dan karena itu kesempatan membela diri dipergunakannya untuk “membongkar” sistem kolonial yang destruktif dan eksploitatif. Tindakan serupa dalam menguliti sistem kolonial juga dilakukan oleh Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, Semaoen, Darsono, Mas Marco, dan Hadji Misbach.
klasik
Sistem pemerintahan bertingkat dan tak langsung yang diterapkan Belanda di koloni Hindia Belanda melalui penguasa-penguasa tradisional pribumi dan para opsir dalam masyarakat Tionghoa dari segi keuangan mungkin efisien dan hemat. Tetapi, hal ini bisa mengundang kerawanan bila rakyat ternyata lebih mematuhi bupati atau kapitannya ketimbang pemerintah kolonial. “Persekutuan” antara pemerintah kolonial dengan aparat pribumi atau dengan para opsir Tionghoa tentunya bisa saja berubah menjadi permusuhan antara keduanya. Ujian mengenai sejauh mana kelanggengan hubungan itu terlihat, misalnya, saat pergerakan memasuki zaman baru di permulaan abad ke-20. Beberapa pangreh praja terlibat aktif dalam organisasi Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan organisasi kerakyatan lainnya, sembari tak melepaskan jabatannya dalam pemerintah Hindia Belanda. Maka, memetik pelajaran dari telaah Furnivall tentang Burma dan Hindia Belanda, kolonialisme sebagai sebuah sistem eksploitasi politik, ekonomi, dan sosial dampaknya masih bisa disaksikan sampai sekarang. Pengkotak-kotakan masyarakat, pembagian masyarakat dalam kelas, kasta, dan wilayah, dan perbedaan di bidang hukum adalah “warisan” kolonialisme yang tersisa hingga kini. Kontribusi Furnivall adalah mengingatkan kita untuk tidak mengulangi pembelahan rakyat dalam sistem kolonial yang destruktif dan eksploitatif. 0 M. Fauzi adalah Kepala Pustaka Kerja Budaya
MUAK DENGAN ARUS UTAmA?
http://arus.kerjabudaya.org
KLASIK
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
63
® RESENSI BUKU
& ©
Penguasaan Sumber Daya Alam™ Krisis Sistem Kapitalisme Dunia
Antonius T. Stevanus
Milyaran warga dunia dewasa ini didorong untuk mempercayai dan memahami bahwa GLOBALISASI adalah sinyal masa depan untuk kesejahteraan umat manusia. Sementara para penentang globalisasi membeberkan bahwa globalisasi adalah sebuah sistem kapitalisme lama yang diperbaharui. Tiga buku yang akan saya bahas di bawah ini memandang globalisasi akan menghancurkan peradaban manusia dan memaksa kelas pekerja, perempuan masuk ke dalam proses proletarianisasi. Buku pertama, Imperialisme Abad 21, karya James Petras dan Henry Veltmeyer, merupakan terjemahan dari Globalization Unmasked: Imperialism in the 21 st Century yang ingin menanggalkan berbagai selubung indah penutup ide globalisasi selama ini, sehingga kita bisa menentukan sikap apakah globalisasi itu sebuah sistem bagi kesejahteraan atau ketidakadilan. Namun sungguh sayang bahasa buku terjemahan ini kurang populer, sehingga agak sulit untuk memahami isinya. Di lain sisi, buku ini mendorong pembacanya berpikir lebih keras untuk memahami analisa kelas yang tak lazim dipakai di Indonesia. Dalam buku Imperialisme Abad 21 , Petras dan Veltmeyer sejak awal
64
menantang klaim-klaim keniscayaan kaum globalis bahwa sistem kapitalisme merupakan satu-satunya pilihan tata dunia. Menyandingkan globalisasi dengan konsep imbangannya, yaitu imperialisme, penulis menggunakan analisa kelas untuk mengurai kembali dasar-dasar pemikiran dan praktek kapitalisme. Menarik bahwa teori Marxisme yang sudah banyak ditinggalkan orang justru memberikan kekuatan penjelas yang akurat bagi situasi yang tengah berlangsung seperti diperlihatkan buku ini. Petras dan Veltmeyer membawa kembali dimensi pemikiran ilmiah dengan unsur-unsur yang bertentangan, bahkan dengan intelektual sepikiran, yang mampu memberikan pemahaman dasar gerak globalisasi pada kalangan yang lebih luas. Tidak hanya itu, buku ini juga memberi aktivis penentang globalisasi perangkat teoretik yang akan memperkuat aksi perlawanan. Selama ini pembahasan mengenai globalisasi begitu kompleks sehingga menjadi wacana ekonomi dan sosial-politik yang membingungkan. Jika globalisasi dipahami sebagai penguatan dan perluasan ekonomi ‘pasar bebas’ dengan menghapuskan segala aturan pembatas
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
©
gerak modal internasional, imperialisme meraih bidang yang jauh lebih strategis, yaitu proyek-proyek politik yang mengkondisikan perdagangan global berkelanjutan. Bukannya tanpa alasan globalisasi hadir dengan mitos-mitos kemajuan dan kesejahteraan yang menyelubungi ideologi kepentingan kelas kapitalis internasional. Sistem ini secara dinamis terus melakukan penyempurnaan strategi untuk menaklukkan segala aspek kehidupan manusia di bawah kekuasaannya, dan lewat promosi ‘pasar bebas’, ia mengubah tatanan dunia untuk menciptakan sistem perekonomian tunggal. Untuk melancarkan perluasan modal internasional dalam jumlah yang semakin besar, selain menggunakan teknologi dan sistem informasi yang canggih, perusahaan multinasional yang berbasis di negara-negara industri maju, seperti Amerika Serikat, beberapa negara yang bergabung dengan Uni Eropa, dan Jepang, melibatkan lembaga keuangan dan perencanaan internasional seperti IMF, Bank Dunia. Negara-negara inilah yang menjadi pusat penggerak proyekproyek perubahan di seluruh dunia dan mewujudkan sistem pemerintahan global. Perubahan dilakukan berdasarkan
KLASIK
James Petras dan Henry Veltmeyer, Imperialisme Abad 21, Jakarta, 2001
Hira Jhamtani, Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan, Jakarta, 2001
Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan, Jakarta, 2002
keputusan sekelompok manusia yang sepenuhnya sadar untuk menundukkan manusia lain di bawah kekuasaannya. Bayangan tentang tatanan dunia baru menjadi sebuah keniscayaan, dan kita semua harus melakukan penyesuaian terhadapnya. Negara-negara di luar kelompok negara imperial yang mengalami perubahan politik secara drastis, seperti di Indonesia, menjadi sasaran proyek ‘pembaharuan’ ini. Setelah rejim diktator dan militeristik tergusur, pemerintahan sipil yang baru didorong untuk melaksanakan program-program etiket seperti “good governance” (tata kelola pemerintahan yang baik) dan mengadopsi “Structural Adjustment Programme” (program penyesuaian struktural) untuk membangun kinerja institusi dan melahirkan kebijakan negara yang sepenuhnya mendukung rejim “pasar bebas”. Pendukung pasar bebas melihat kepatuhan negara-negara miskin untuk menandatangani nota kesepakatan dan mengikuti kursus-kursus menjalankan pemerintahan yang baik sebagai upaya membangun sistem yang lebih “demokratis” bagi rakyat. Padahal, ini semua tak lain dari strategi untuk melancarkan
RESENSI BUKU
perputaran modal internasional. Pemerintah lokal tidak pernah mempunyai peran untuk menentukan kebijakan nasional maupun internasional yang lebih baik bagi rakyatnya karena mereka membutuhkan bantuan dana dan investasi dari negara-negara imperial. Program-program pembaharuan pada gilirannya menciptakan krisis berkepanjangan di segala bidang kehidupan masyarakat. Investasi asing yang membanjir memicu krisis pada perusahaan-perusahaan milik negara yang mengelola kebutuhan mendasar rakyat. Privatisasi menjadi jalan keluar walaupun itu berarti meniadakan sumber-sumber keuntungan pemerintah dan menyerahkan pengelolaan sumber daya hidup rakyat ke tangan swasta. Sedangkan pemasukan untuk pemerintah diusahakan dari kebijakan menaikkan pajak, memotong anggaran publik, dan mengurangi subsidi sosial. Satu hal menarik yang diungkap oleh buku ini adalah bagaimana rejim globalisasi menaklukkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang diciptakan sistem kapitalisme internasional. Dalam propagandanya, rejim ini menggunakan katakata populer, seperti demokrasi, pembangunan , solidaritas , civil society , atau pluralisme , untuk membingungkan dan mengacaukan gerakan-gerakan oposisi. Definisi kata-kata ini sudah ditentukan oleh kelas yang berkepentingan dengan perluasan modal internasional sebelum ditawarkan ke seluruh dunia lewat proyek-proyek yang disebut “penguatan masyarakat sipil”. Ornop atau LSM seringkali terjebak dalam mantra-mantra ini dan menjadi jurkam kekuatan imperial untuk menjinakkan perlawanan rakyat. Misalnya, istilah ‘masyarakat sipil’ sudah mengabaikan perbedaan kelas dalam masyarakat; kata ‘solidaritas’ berarti ‘pemberian bantuan’ dan penyelenggaraan ‘pelatihan’. Ada jarak antara para penyuluh dengan rakyat. Secara umum, buku ini menarik karena di setiap akhir pembahasan suatu tema, penulis memberikan kesimpulan penjelas dibalik uraian ilmiah tentang ekonomi dan sosial-politik yang rumit. Walaupun fokus pembahasan buku ini pada dampak dan praktek globalisasi di Amerika Latin, dari paparan penulis menjadi jelas bahwa globalisasi menimbulkan masalah yang serupa di segala penjuru dunia. Misalnya untuk memahami persoalan di Indonesia, kita bisa
mencermati kaitan antara praktekpraktek yang dijalankan perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis menegaskan buku ini bukan semacam panduan untuk mengatasi globalisasi walau pun buku ini diakhiri dengan solusi dan strategi sosialisme. Penulis justru ingin menunjukkan kepada kita bahwa pengamatan yang teliti terhadap realitas adalah pisau bedah yang penting untuk menguliti konsep globalisasi dan membantu kita menemukan kembali pilihan-pilihan alternatif tatanan hidup yang beragam dalam situasi globalisasi. Buku berikutnya, Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan, merupakan rangkuman pengalaman Hira Jhamtani sebagai aktifis LSM lingkungan yang menangani soal bioteknologi. Disusun sebagai catatan awal untuk berbagai kalangan yang peduli dengan lingkungan, buku ini memaparkan bagaimana globalisasi membuat posisi dunia ketiga semakin dikungkung oleh ketidaksetaraan di bidang ekonomi, teknologi dan kesejahteraan sosial. Ada beberapa tema dalam buku ini yang menarik. Pertama adalah bagaimana keanekaragaman hayati menjadi sumber “emas hijau” globalisasi. Sumber-sumber alam telah dipaksa pertumbuhan alamiahnya untuk memenuhi kebutuhan globalisasi dengan dukungan kemajuan teknologi di bidang biologi dan informasi. Dalam konteks Indonesia, bioteknologi dalam globalisasi adalah ancaman serius, baik bagi keberlanjutan alam, maupun bagi pemenuhan kebutuhan manusia akan kesehatan dan pangan. Tema kedua adalah paten atas segala bentuk kehidupan untuk dijadikan hak milik perseorangan atau perusahaan berbadan hukum. Ini adalah strategi untuk menguasai sumber-sumber alam dengan menarik keuntungan sebesarbesarnya dari penggunaan paten melalui royalti. Susunan genetika yang terdapat pada masing-masing mahluk hidup menjadi sumber daya penting untuk direkayasa. Praktek ini kemudian memicu krisis ilmu pengetahuan dan tersingkirkannya, bahkan punah, kearifan-kearifan lokal masyarakat. Keikutsertaan penulis dalam perundingan-perundingan konvensi antar negara dalam lembaga internasio-
™ media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
65
nal banyak memberikan pemahaman kepada kita bagaimana proses perumusan kesepakatan tentang globalisasi dilakukan melalui jalan parlementer. Jelas bahwa yang dirumuskan pada perundingan lingkungan internasional pada umumnya hanya menghasilkan suatu kesepakatan untuk menanggulangi dampak globalisasi pada lingkungan, tapi bukan pada perubahan drastis menuju perbaikan lingkungan. Kesepakatan ini justru membawa dampak yang lebih merusak lingkungan dalam bentuk bujuk rayu investasi asing, janji alih teknologi dan pembagian keuntungan. Jhamtani menyatakan bahwa sejak pemberlakuan WTO, pemerintah Indonesia menderita kerugian sekitar US$ 1,9 milyar. Sayangnya, ia tidak merinci cara penghitungannya. Yang berperan kunci dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan globalisasi lingkungan adalah WTO dan Bank Dunia, bersama dengan kebijakan ‘pasar bebas’ AS yang didukung perusahaan multinasional. Mereka, misalnya, menetapkan kebijakan TRIP’s (Trade-Related Intellectual Property Rights – Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Perdagangan) untuk mematenkan bentuk kehidupan secara legal. Belum lagi kebijakan perdagangan AS ‘Super 301’yang mengancam pemberlakuan sanksi perdagangan bagi negara-negara yang tidak sepaham. Seperti yang diungkapkan penulis, utusan negara-negara dunia ketiga biasanya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk bernegosiasi dan membahas persoalan ini. Ini sebenarnya bukan karena utusan pemerintah negara-negara maju lebih kuat dalam bernegosiasi seperti sering diutarakan banyak pengamat. Tapi, pemerintah memang tidak punya itikad baik memperjuangkan kepentingan rakyatnya di tingkat internasional sehingga mereka tidak berusaha mencari atau mendidik utusan yang lebih menguasai soal. Posisi LSM, dalam pandangan penulis, oportunis, baik di tingkat internasional, nasional, maupun di akar rumput. Setelah tegas-tegas mengutuk globalisasi, mereka menyarankan kepada pemerintah agar membuat kebijakan lingkungan yang tidak melanggar perjanjian internasional (WTO). Mereka menyarankan pemerintah untuk mendengar66
kan aspirasi dari masyarakat, tapi di lain waktu juga menyalahkan masyarakat atas kerusakan alam. Mereka juga mendesak pemerintah untuk bekerja sesuai dengan tata tertib “good governance”, kemudian menciptakan paradigma lingkungan baru yang jauh kaitannya dengan praktek pelestarian lingkungan yang hidup di masyarakat. Beberapa solusi yang ditawarkan penulis anehnya membawa kita berharap akan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian internasional dan bersifat normatif. Contohnya, penulis mengusulkan penanganan bioteknologi dengan kasih, yang menjunjung etika dan moral; transparansi kebijakan pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat yang didasari atas kejujuran. Penulis bahkan berharap pada doa sebagai alternatif terakhir jika kebakaran hutan tak teratasi. Jadi, saran-saran yang ia ajukan juga tidak berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dari praktekpraktek masyarakat pelestari lingkungan, dan tidak akan bisa diserap pembuat kebijakan. Sebagai sebuah catatan awal, informasi dan data yang disampaikan dalam buku ini tidak begitu banyak, khususnya mengenai dampak globalisasi lingkungan di Indonesia. Dua artikel pertama dan selanjutnya membahas tema keanekaragaman hayati berulang-ulang dengan penggunaan kata yang berbeda-beda. Ada kesan pembahasan ditekankan pada kerangka teori, bukan realita kerusakan lingkungan itu sendiri. Bagaimana pun buku ini tetap melengkapi pemahaman kita mengenai globalisasi itu sendiri. Dengan membaca tentang proses perundingan tingkat internasional, pembaca bisa melihat bahwa yang mendominasi pembuatan kebijakan adalah kelas kapitalis. Mereka juga bisa menyerap praktek kultural yang berlaku di belahan dunia tertentu untuk menciptakan perubahan nilai sesuai dengan kepentingan kelas mereka. Hal ini juga menggambarkan bahwa perjuangan parlementer tidak selamanya berjalan dengan hasil memuaskan. Buku Globalisasi dan Monopoli Ilmu Pengetahuan-Telaah Tentang TRIP’s dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia merupakan buku hasil studi yang dilakukan Hira Jhamtani bersama Lutfiyah Hanim. Mungkin buku ini hendak meneruskan buku sebelumnya media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
karena masih berkaitan dengan isu lingkungan, tapi dengan pembahasan lebih spesifik pada TRIP’s atau Hak atas Kekayaan Intelektual. Sejak awal dirumuskan TRIP’s mengundang sejumlah pertentangan, baik antar negara perumus, antara negara perumus dengan negara anggota WTO lain, maupun dengan hasil perundingan lingkungan tingkat internasional lainnya. TRIP’s telah menjadi pusat kebijakan yang melemahkan hasil perundingan lain sehingga perumusan TRIPs tidak juga menguntungkan penggunanya. Namun, negara anggota WTO tetap saja mengadaptasi aturan main ini dalam kebijakan nasional masing-masing. Kerancuan ini berlanjut ketika di tingkat nasional ternyata tidak ada pemahaman bersama tentang hak paten, bahkan di kalangan pemerintah sendiri. Maka tak heran jika soal paten memicu banyak sekali korban. Kebijakan yang ada tidak mampu menjembatani perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Misalnya, hak paten ini menghancurkan proses dan hasil praktek kultural yang hidup dalam masyarakat tradisional. Bagi para pengusaha rekaman kebijakan soal paten berguna untuk melindungi hak cipta. Tapi bagi pengrajin atau petani, aturan ini janggal, karena ketrampilan yang mereka miliki adalah warisan turun temurun komunitas yang tidak perlu diberi paten oleh negara. Lepas dari kelemahannya di sana-sini, ketiga buku ini memberikan sumbangan besar untuk pemahaman neoliberalisme. Dari ketiganya tampak bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat berkait kelindan dengan globalisasi. Setiap orang tidak bisa mengabaikannya begitu saja karena ia hidup didalam sistem ini. 0
Antonius T. Stevanus adalah anggota Tim Relawan Untuk Kemanusiaan
® RESENSI BUKU
TOKOH
Dunia Dongeng dan Kata-Kata
SUBCOMANDANTE MARCOS Adalah kata-kata yang menciptakan kita. mereka yang membentuk kita, Dan membentangkan Garis-garisnya Untuk mengontrol kita. (Subcomandante Marcos)
Wilson
B
TOKOH
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
sumber foto: www.ezln.org
iasanya membaca tulisan para tokoh revolusioner, kepala kita jadi mudah berdenyut-denyut, dipenuhi kata-kata teknis tradisional kaum revolusioner yang menggebu-gebu disanasini, dan tentu saja provokatif. Sampai suatu hari, dunia dikejutkan oleh aksi para gerilyawan Zapatista di Chiapas, Mexico. Dari model gerakan, mungkin itu adalah plot klasik kaum revolusioner di berbagai tempat: sebuah insureksi yang dipersiapkan matang terhadap kekuasaan negara. Tidak ada yang baru dari plot 1 Januari 1994. Hal baru yang dibawa para gerilyawan bertopeng “yang tanpa suara/tanpa wajah/tanpa nama” tersebut adalah ‘gaya kepemimpinan’ yang unik dari Subcomandante Marcos. Membaca dokumen dan seruan dari Subcomandante Marcos, kita seperti sedang membaca sebuah karya sastra. Kutipan puisi, dongeng, kata-kata indah bertaburan bagaikan kristal—kata-kata seperti berubah wujud menjadi sinar yang terang benderang. Salah satu contoh yang paling luar biasa adalah pidato pembukaannya dalam Konferensi Internasional Anti Neoliberalisme di Juli 1996. Berbeda dengan para peserta yang mengungkapkan pendapatnya dalam bahasa teoritis, data-data ekonomi yang pelik tentang penindasan pasar bebas, Subcomandante Marcos membawa suasana lebih cair dan teduh. Ia membuka acara dengan kata sambutan berbentuk puisi panjang. Sesuatu yang sukar kita bayangkan akan dilakukan Fidel Castro atau Lenin, atau para pimpinan gerakan revolusioner di berbagai belahan dunia. Dengan indah ia mengenalkan diri:
67
Inilah siapa kami Tentara pembebasan nasional Zapatista Suara-suara yang mempersenjatai diri agar bisa didengar Wajah-wajah yang disembunyikan agar tidak terlihat Nama-nama yang tidak mau diberi nama Ekspresi politik dalam bentuk puisi, drama, dongeng, dan foklore memang memenuhi berbagai pernyataan politik Subcomandante Marcos. Semua ekspresi estetik tersebut memberikan suatu roh baru dalam pernyataan-pernyataan politik kaum revolusioner— keindahan. Sesuatu yang ‘agak baru’ dalam tradisi politik kiri, yang selama ini dipenuhi dengan bahasa teoritis, sloganistik, provokatif dan polemis. Beberapa pemimpin gerakan kiri seperti Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Aidit, atau Xanana (yang saya kenal) juga menulis puisi. Namun puisi-puisi mereka adalah ‘dunia lain’, tidak menjadi bagian langsung dari ‘perang propaganda politik’. Sementara Subcomadante Marcos tidak membagi ‘dunia estetik’ dan ‘dunia politik’ sebagai dua wilayah yang berbeda—keduanya hadir dalam saat yang bersamaan, saling memperkuat dan saling memberi isi. Permainan kata-kata memang mendapatkan perhatian serius dari Subcomandante Marcos. Kata-katanya beri roh perjuangan dan harapan, menjadi suatu alat yang hidup, bahkan senjata yang paling utama: “Adalah kata-kata yang memberi bentuk pada sesuatu yang masuk dan keluar dari diri kita. Adalah kata-kata yang menjadi jembatan untuk menyeberang ke tempat lain ketika kita diam, kita akan tetap sendirian. Berbicara, kita mengobati rasa sakit. Berbicara kita membangun persahabatan dengan yang lain. Para penguasa menggunakan kata-kata untuk menata imperium diam. Kita menggunakan kata-kata untuk memperbaharui diri kita… Inilah senjata kita saudara-saudaraku.” (12 Oktober 1995)
Di Chiapas, Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) menciptakan suatu ‘tradisi’ unik, di mana proses kreatif dan kualitas estetik muncul dari kawah perjuangan itu sendiri. Dari perjuangan tersebut lahir puisi, dongeng, dan kata-kata indah yang ditujukan kepada pendukung, sahabat, anak-anak, perempuan, kaum buruh, kaum tani, masyarakat adat, dan juga musuh-musuh rakyat. Perjuangan Subcomandante Marcos dkk. telah meningkatkan kualitas keindahan dari alat kontemplasi, apresiasi, perenungan, menjadi suatu ‘roh’ yang menjadi satu kesatuan dengan kehidupan revolusioner. Jadi kita tidak mungkin bisa membayangkan kerja estetis Subcomadante tanpa perjuangan revolusioner, dan begitu pula sebaliknya. Tentu saja, pemahaman “kata-kata adalah senjata” harus ditempatkan dalam konteks perjuangan, bukan dalam kamar kaum seniman soliter, jurkam, atau tukang obat. Bisa jadi, kalau kata-kata ini dicabut dari konteksnya, dunia ini akan dipenuhi para pengikut NATO (no action talking only – tak ada aksi bicara melulu, red.). Kata-kata menjadi senjata bila ia menjadi bagian dari perjuangan pembebasan; kata-kata tidak menjadi apa-apa bila ia hanya sekedar kata-kata. Dan memahami kata-kata sebagai senjata harus dimulai dari perjuangan Tentara Pembebasan Naional Zapatista. Perjuangan rakyat Chiapas yang monumental dan menjadi titik balik penting adalah di malam tahun baru 1994, tepat di hari pertama implementasi NAFTA (North American Free Trade Agreement —
68
Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, red.) Bagaikan kisah dongeng, ribuan gerilyawan tentara EZLN, di bawah pimpinan seorang laki-laki dengan topeng ski dan pipa cangklong terselip di bibir, menguasai kota San Cristobal de las Casas dan kota-kota kecil sekitarnya. Pesan politik dari aksi tersebut cukup jelas, yaitu mengingatkan pemerintah Meksiko dan dunia tentang nasib masyarakat adat yang disengsarakan, ditindas, terusir, dan dilupakan. Namun yang lebih penting lagi, hari itu adalah sebuah pembaptisan, sebuah permulaan ‘perang global’, menentang neo-liberalisme. Dan gerakan tersebut dipimpin oleh seorang tokoh misterius dengan mata hijau yang bersinar dari balik topeng skinya. Ketika para jurnalis bertanya “Siapakah Anda ?”, laki-laki bertopeng itu menjawab, “Saya adalah Subcomandante Marcos”. Penampilannya yang misterius menimbulkan berbagai spekulasi tentang siapa sebenarnya pria karismatik ini? Sesuatu yang serba misterius memang mengundang keingintahuan orang, apalagi para jurnalis. Tidak heran, nama Subcomandante Marcos menjadi suatu daya tarik, semacam teka-teki, di mana semua orang ikut bermain, dan dengan bersahaja mencoba menebak-nebak wajahnya, atau sekedar membagi kerinduan dan impian. Pokoknya, tidak ada suatu penafsiran tunggal tentang sosok misterius di balik topeng tersebut. Setiap orang bebas membangun impiannya sendiri, bahkan setiap orang juga bebas menjadi Subcomandante Marcos itu sendiri. EZLN berbeda dengan berbagai perjuangan revolusioner lainnya dengan wajah para pimpinannya yang sangat dikenal publik. Subcomandante Marcos berhasil membangun semacam tradisi baru, di mana identitas pimpinan adalah sesuatu yang anonim; sosok yang ada, tapi seperti tidak ada; hadir, tapi seperti tidak hadir; dikenal, tapi orang tidak mengenalnya; bersembunyi, tapi semua orang dapat melihatnya. Identitas anonim Marcos mungkin ingin menjelaskan suatu prinsip, bahwa rakyat yang utama, rakyat yang nyata, rakyat tidak anonim, rakyat yang punya sejarah, rakyat yang memiliki penderitaan, dan rakyat pula yang memiliki perjuangan, bukan para pimpinannya. Karena itu biarlah para pimpinan dikenal sebagai sesuatu yang anonim, sebab mereka bukanlah hal yang paling penting dalam perubahan atau sebuah perjuangan. Nama sebagai sesuatu identitas pribadi atau individu baginya adalah omong kosong, sebab”sekarang kita mempunyai nama kolektif”. Pada musim panas 1994, para pejuang Zapatista mengundang pers nasional dan internasional, para aktivis dan orang-orang yang sekedar ingin tahu, untuk menghadiri pertemuan di hutan Chiapas. Sekitar 600 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Kebanyakan yang datang ingin tahu “Mengapa ia bersembunyi di balik topeng? Mengapa ia takut menunjukkan wajahnya?” Merespon keingintahuan tersebut, Marcos melakukan gerakan seperti hendak membuka topengnya. Kesunyian terasa di tengah hutan. Semua orang seperti menahan nafas, penasaran siapa di balik topeng tersebut. Tiba-tiba kesunyian terpecah dengan teriakan “Jangan.. jangan.. jangan!”. Dan topeng tersebut tidak jadi dibuka. Topeng tersebut, bukan hanya penting untuk menghapuskan identitas dirinya sebagai individu, tapi sebagai identitas komunal dari penduduk asli Chiapas yang telah dilupakan, menderita, tapi tidak kehilangan harga diri; sebagai identitas komunal yang baru— komune perjuangan. Sejak itu, Marcos, melalui internet, mengeluarkan berbagai pernyataan, surat seruan, puisi, dongeng, solidaritas kepada dunia. Tulisan-tulisannya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menyebar dengan cepat melalui jaringan internet. Dari cara Subcomandante Marcos bermain dengan kata-kata, perjuangan revolusioner menjadi suatu medium estetik, proses kreatif, yang mungkin tidak lazim dari perspektif teori seni arus
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
TOKOH
sumber foto: www.ezln.org
utama. Yang paling menarik adalah kisah-kisah dongengnya. Dongeng-dongeng tersebut adalah bentuk foklore yang terus hidup dari satu generasi ke generasi. Karena itu dongeng dapat diartikan sebagai suatu penelusuran ke masa lalu guna memberikan ‘identitas historis’ kepada masyarakat “bahwa mereka sudah ada, sebelum para penindas ada. Dan akan terus ada, ketika para penindas menjadi tidak ada”. Marcos sudah menggunakan cara bertutur seperti mendongeng sejak awal terlibat dalam perjuangan bersenjata, sekitar 1984. Dongeng pertama ia kisahkan pada suatu senja di Agustus 1984 berjudul “Menanam Pohon Masa Depan”. Dengan dongeng itu menyampaikan “apa yang ingin dilakukan oleh Zapatista”: “Untuk menanam pohon masa depan, itulah yang kita akan lakukan… Pohon masa depan adalah ruang bagi semua orang, tempat setiap orang saling menghormati yang lain… Jika anda memaksa saya untuk mengatakannya dengan lebih persis, Saya akan katakan pada kalian itu adalah sebuah tempat dengan demokrasi, kebebasan dan keadilan; itulah yang dimaksud dengan pohon masa depan. “ Marcos selalu berpesan ‘rakyat yang tidak mempunyai masa lalu tidak akan mempunyai masa depan.” Kalimat ini keluar untuk
TOKOH
merespon politik penguasa yang menganggap ‘penduduk asli’ (baca: kaum tertindas) tidak pernah ada, baik di masa kini, di masa lalu dan masa depan. Karena itu mereka selalu diabaikan, tidak pernah diajak bicara, berembug, atau menentukan nasib mereka sendiri. Pokoknya dianggap tidak pernah ada. Dengan dongeng, Marcos seperti membuktikan bahwa “kami ada”; “kami mempunyai sejarah kami sendiri”; sejarah yang telah dikisahkan selama ratusan tahun oleh para nenek moyang. Dan keberadaan itu sekarang juga hadir dalam bentuk perjuangan. Perjuangan yang membuat penduduk asli mempunyai masa lalu, masa kini, dan tentu saja masa depan. Masa lalu adalah suatu yang hidup dalam masa kini, hadir dalam berbagai dongeng yang kreatif, penuh dengan ajaran moral, didaktis, nilai-nilai pengorbanan, harapan, dan perjuangan. Uniknya, masa lalu itu sebetulnya sudah dikenal baik oleh semua orang, karena sudah dikisahkan sejak kecil. Dan ketika si kecil sudah dewasa, dia mengisahkan kembali kepada anak-anaknya. Demikianlah ‘sebuah rantai sejarah’ direkam dalam kepala setiap orang. Inilah salah satu kekuatan bahasa tutur, sebuah dongeng, ketimbang teks sejarah akademis. “Sejarah dunia yang menciptakan dunia ini datang dari tempat yang sangat jauh sekali. Kalian tidak bisa menemukannya tertera di dalam buku atau terlukis di atas pohon. Juga tidak ada dalam aliran sungai
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
69
atau awan-awan yang beterbangan. Kalian tidak akan dapat membaca sejarah tentang dunia di dalam kalender. Sejarah tentang bagaimana kita lahir dan bagaimana kita diciptakan tidak tersembunyi di balik tulisan atau di dalamnya.” (21 Oktober 1999)
Dalam Catatan editor buku kumpulan tulisan Marcos Our Word is Our Weapon, Juana Ponce de Leon mengatakan bahwa “Buku tersebut adalah sebuah kesaksian tentang kekuatan bahasa.” Dengan tulisan-tulisannya, Subcomandante Marcos telah menjadikan Chiapas sebagai jendela bagi semua orang. Bahkan menurut Juana Ponce, “Kata-kata berbicara lebih banyak daripada revolusi”. Apa yang dilakukan Marcos persis seperti yang dilakukan para penulis besar Amerika Latin, seperti Pablo Neruda, Miguel Angel Asturias, atau Gabriel Garcia Marquez. Marcos mungkin agak mirip seperti sastrawan, “Ia memadukan keyakinan politik dan keindahan sastra untuk menciptakan keindahan bagi pandangan-pandangannya.” Salah satu hal yang menarik perhatian saya dari dongeng Marcos adalah penggunaan ‘kata kecil” dengan makna yang ‘besar’. Terdapat lima dongeng dengan protagonis utama adalah ‘si Kecil”. Intisarinya mungkin bahwa yang kecil belum tentu kalah; bahwa yang kecil belum tentu tidak berarti; bahwa yang kecil justru menjadi awal dari suatu yang besar; bahwa kecil itu juga sebuah kekuatan. Pemaknaan baru atas hal-hal yang dianggap kecil, merupakan suatu dekonstruksi terhadap kesalahpahaman dominan, atau kealpaan banyak orang, yang selalu mengidentikkan, menafsirkan sesuatu yang kecil dengan kelemahan, ketakberdayaan, kekalahan, marjinal, dan sesuatu yang tidak berarti. Sebuah dongeng tentang “Seonggok Awan Kecil” menjadi contoh bagaimana Marcos memberi makna yang dalam pada sesuatu yang kecil. Mahluk yang tadinya rendah diri, merasa tidak berguna, dan dilecehkan oleh awan-awan yang lebih besar, menemukan jati dirinya, kebanggaan diri, ketika ia menjadi pelopor menyirami sebuah padang pasir dengan hujan rintik-rintik. Ketika dia menjadi berguna bagi yang lain, maka si Awan Kecil sesungguhnya sudah melakukan sesuatu yang besar.
Salemba, 24 April 2003 Wilson, peneliti di Praxis Institute, Jakarta
sumber foto: www.ezln.org
Pada suatu masa, terdapat sebongkah awan yang sangat kurus, sendirian, dan selalu menjauh dari awan yang besar. Dia sangat kecil, hanya seonggok awan. Ketika awan-awan yang besar mengubah dirinya menjadi hujan yang melumuri gunung-gunung yang hijau, si Awan Kecil hanya dapat melayang-layang di atasnya. Tapi mereka mengejeknya karena dia begitu kecil. “Kau tidak memberikan apapun,” begitulah yang selalu diucapkan awan besar kepadanya.”Kamu terlalu kecil.” Awan-awan yang lebih besar selalu membuat gurauan lucu tentang dirinya. Lalu, karena begitu sedihnya, si Awan Kecil mencoba pergi ke tempat lain untuk mengubah dirinya menjadi hujan, tapi ke mana pun ia pergi, para awan besar selalu mendorongya keluar. Sehingga si Awan Kecil tidak pernah berubah. Hingga suatu hari, dia datang ke sebuah tempat yang sangat kering, begitu keringnya sehingga tidak ada satu
tokoh
pun yang dapat tumbuh. Dan si Awan Kecil berkata kepada cerminnya. (Aku lupa mengatakan kepada kalian bahwa si Awan Kecil ini membawa sebuah cermin, jadi dia dapat berkata kepada dirinya sendiri ketika sedang sendirian): “Ini tempat yang pas untuk mengubah diriku menjadi hujan sebab tak ada seorang pun yang pernah datang kemari.” Si Awan Kecil melakukan berbagai upaya agar dirinya menjadi hujan, dan akhirnya rintik-rintik kecil berjatuhan. Si Awan Kecil pun lenyap dan mengubah dirinya menjadi hujan rintik-rintik. Sedikit demi sedikit, si Awan Kecil yang sekarang menjadi hujan rintik-rintik mulai berjatuhan. Sepenuhnya dalam kesendirian, dia merasakan dan merasakannya, tapi tidak ada satu pun yang menantinya di bawah sana. Akhirnya, rintik hujan memecah seluruh dirinya. Saat itu, padang pasir masih sangat sunyi, hujan rintik-rintik membuat sedikit kegaduhan ketika dia jatuh tepat di atas bebatuan. Kegaduhan Itu telah membangunkan Bumi yang berujar: “Suara ribut apa ini?” “Wah turun hujan? Ini berarti akan turun hujan! Hayo, semuanya bangun! Hari akan hujan!” dia berteriak pada tetumbuhan yang bersembunyi di bawah batu, menghindar dari sinar mentari. Sang tetumbuhan segera bangun dan menggeliat. Dalam sekejap seluruh guruh menjadi kehijauan, dan Awan-awan besar melihat seluruh kehijauan tersebut dari jauh dan berujar: “Lihatlah! Di sana tampak banyak warna hijau. Mari mengubah diri kita menjadi hujan di sana. Kok kita tidak pernah tahu di sana ada yang begitu hijau.” Mereka pun mengubah dirinya menjadi hujan di sebuah tempat yang dulunya padang pasir. Mereka terus menurunkan hujan tanpa henti dan pepohonan mulai tumbuh membuat semuanya tampak hijau. “Sangat mujur sekali bahwa kita ada di sekitar sini,” kata si awan besar. “Tanpa kita, pastilah tidak mungkin akan sehijau ini”. Tampaknya tidak seorang pun mengingat bahwa seonggok Awan Kecil yang berubah menjadi rintik-rintik hujan telah membangunkan semuanya. Boleh saja tak seorang pun pernah mengingat, tapi bebatuan tetap menjaga rahasia hujan rintik-rintik itu. Waktu pun terus berlalu, awan besar pertama sudah menghilang dan pohon-pohon pertama sudah beranjak mati. Tinggallah bebatuan yang tidak pernah mati, selalu menceritakan kisah tentang seonggok Awan Kecil yang berubah menjadi hujan rintik-rintik pada tumbuh-tumbuhan yang baru muncul dan pada awan-awan yang baru tiba. (“ Dongeng Tentang Seonggok Awan Kecil”7 November 1997) 0
70
media kerjabudaya. edisi 11 tahun 2003
TOKOH
Lébur! Seni Musik dan Pertunjukan Dalam Masyarakat Madura Penulis: Helene Bouvier Kata Pengantar: Georges Condominas Penerjemah: Rahayu S. Hidayat dan Jean Couteau Penyunting terjemahan: Daniel Perret dan Rahayu S. Hidayat Penerbit: Forum Jakarta Paris, Ecole Francais d’Extreme-Orient, Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan dan Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2002
Buku ini menyoroti suatu aspek masyarakat Madura yang kurang dikenal, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu kegiatan keseniannya. Metode penelitian etnografis yang dipergunakan penulis memungkinkan ia mengamati kesenian dari segi estetika maupun segi sosial. Ia juga menyoroti proses penciptaan yang nyata sampai ke sumber materialnya, sehingga ia bisa mengungkapkan kaitan struktural bentuk kesenian di bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Dari pengamatannya, karena setiap kegiatan kesenian melibatkan satu segmen masyarakat pada berbagai macam tingkatan, konsep kesenian tradisional dan identitas budaya meliputi keadaan yang sangat bervariasi di Madura. Muncullah pertanyaan, “Apa yang akan terjadi dengan stereotip tentang “Kebudayaan Madura”? Buku ini meraih penghargaan Jeanne Cuisinier (buku Prancis terbaik tentang Indonesia) pada 1992 dan Penghargaan Georges Jamati (buku Prancis terbaik tentang estetika seni pentas) pada 1994. 0
Transcending Borders: Arabs, Politics, Trade and Islam in Southeast Asia Editor: Huub De Jonge and Nico Kaptein Penerbit: KITLV Press, Leiden 2002
Imigran Arab ke Asia Tenggara dan anak cucu mereka tidak banyak menerima perhatian peneliti jika dibandingkan dengan imigran-imigran dari belahan dunia lain, seperti Cina, India, dan Eropa. Secara jumlah, orang-orang Arab sering dianggap tidak penting di sisi minoritas asing lainnya, tapi mereka mempunyai pengaruh besar di bidang ekonomi, politik, sosial, dan perkembangan agama di wilayah berpulau-pulau ini selama berabad-abad. Buku ini memuat 10 artikel dari berbagai perspektif disiplin: sejarah, sosiologi, antropologi, dan Islamologi. Esaiesai ini membahas hubungan di dalam berbagai komunitas Arab, dan antara kalangan masyarakat Arab dengan masyarakat yang lebih luas; dalam bidang politik, perdagangan dan Islam. Huub de Jonge adalah dosen senior dalam ekonomi antropologi di University of Nijmegen, Belanda, sedangkan Nico J.G. Kaptein adalah koordinator dan dosen dalam kerjasama Indonesia-Belanda untuk Studi Islam di Leiden University. 0
The Thugs, The Curtain Thief, And The Sugar Lord: Power, Politics, and Culture in Colonial Java Penulis: Onghokham Penerbit: Metafor Publishing, Jakarta 2003
Kehidupan di Jawa pada zaman Hindia Belanda tidak pernah tampak sesederhana lukisan kuno. Dalam kumpulan tulisan ini, Onghokham, sejarawan terkemuka Indonesia, membeberkan kompleksitas kehidupan Jawa pada masa kolonial. Terperinci dalam penjelasan, penuh simpati, dan melemparkan kemeriahan anekdot, kumpulan esai ini memperlihatkan kelincahan interaksi antara penguasa kolonial dengan pribumi yang cerdik, dan bagaimana interaksi ini secara bertahap menciptakan sistem politik dan kebudayaan baru. Dalam satu esainya, Ong menggambarkan bagaimana usaha menyingkap sebuah pencurian sudah mendesak pemerintah Hindia Belanda ke dalam sebuah kesulitan. Di bagian lain, Ong menggambarkan bagaimana canggihnya lapisan kriminal tumbuh di luar sistem kepemimpinan tradisional Jawa. Membaca kumpulan karangan ini membantu kita melihat bagaimana Indonesia masa kini sebagai sebuah produk sejarah yang panjang. 0
http://tkkorba.kerjabudaya.org KAMPANYE INI DIPERSEMBAHKAN OLEH X-Y BEKERJA SAMA DENGAN MKB
Related Documents

Media Kerjabudaya Edisi 112003
February 2021 1
Web Media Kerjabudaya Edisi 072001
February 2021 0
( Edisi Revisi )
January 2021 1
Media
January 2021 4
Edisi 1
January 2021 3
Youthmarketers Edisi 11 2013
January 2021 0More Documents from "Yanto Ciu"

Web Media Kerjabudaya Edisi 072001
February 2021 0
Buku Kumpulan Diskusi 2000 Dbp
February 2021 1
Media Kerjabudaya Edisi 112003
February 2021 1
Perkembangan Cybercrime Di Indonesia
February 2021 1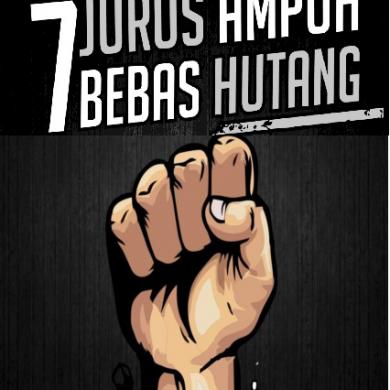
Jurus Ampuh Bebas Hutang
January 2021 1